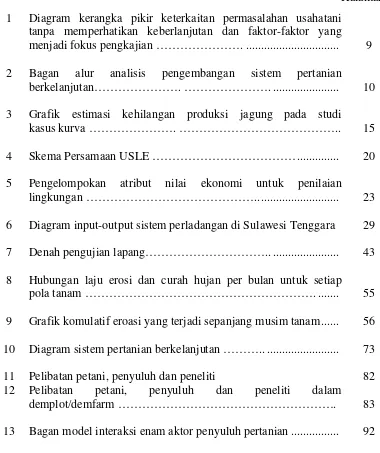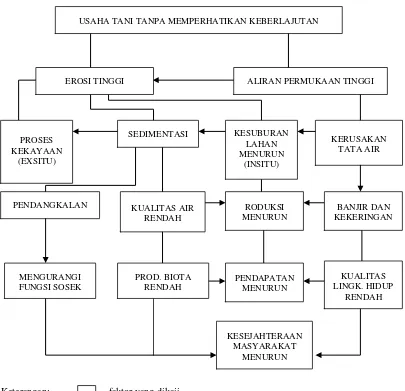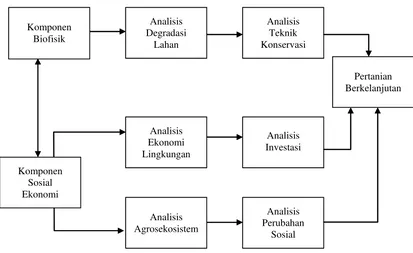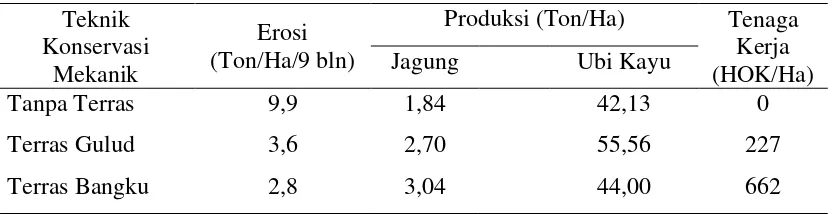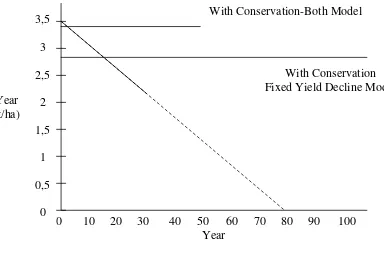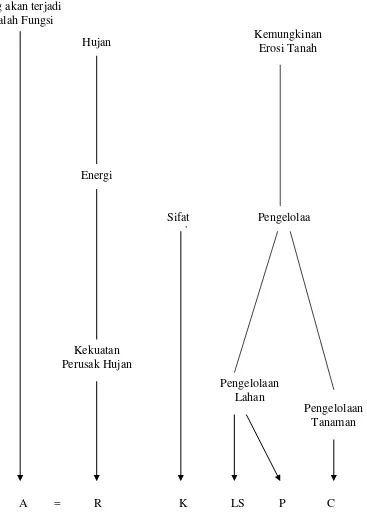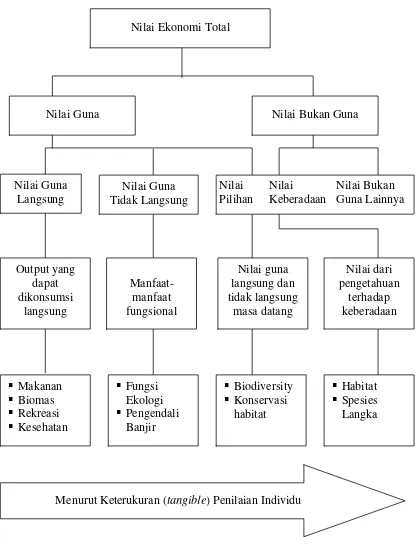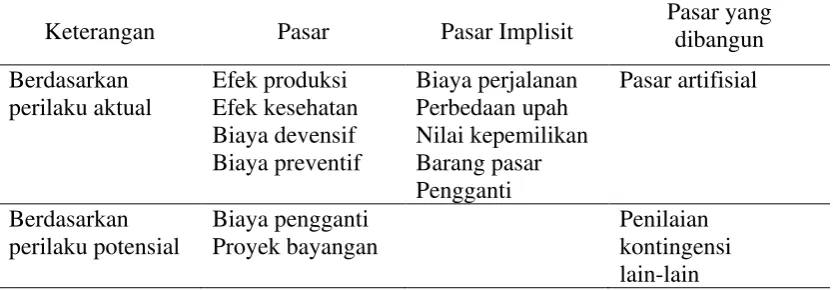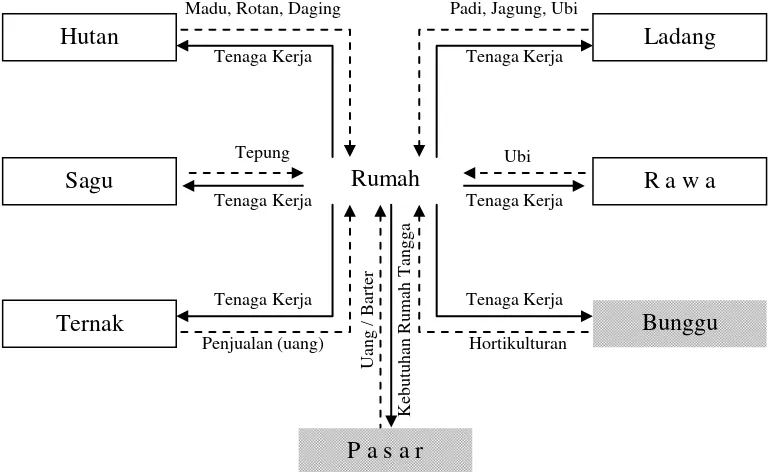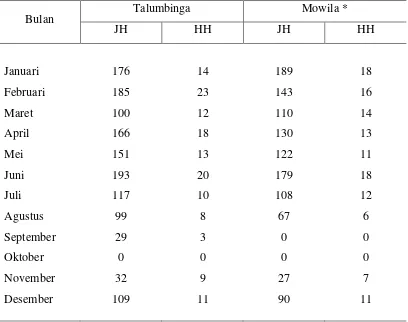ILAH LADAMAY
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam disertasi saya yang berjudul: Pengelolaan Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir disertasi ini.
Bogor, Februari 2010
under direction of SOLEH SOLAHUDDIN, Alm. F. GUNARWAN SOERATMO SEDIONO, SMP TJONDRONEGORO, NAIK SINUKABAN and SJAFRI MANGKUPRAWIRO.
The aims of this research are to analysize the biophysics and socio-economic technique management to encourage the creation of tie sustainable agricultural system. Beside that, the usage of this study could show the alternative’s way of biophysics (conservation) and socio-economic management, so it can create the sustainable agricultural system. This research was done in Southeast Sulawesi, Talumbinga village, Landono Kendari district. Generally most of agriculture’s form in this area is dry land agricultural or known as arable farming and there still done shifting cultivation. The approach of this research was done two ways, thre are the approach to the ecology or biophysics and the approach to the socio-economic.
The results indicated that biophysically the local farm-hand of shifting cultivation has made the increase of land erotion, which could reach 130,9 ton per year or 10,91 mm. whereas the conservation technique biophysically and socio-economic are by the multiple cropping farm's pattern between beans and corn (maise). This pattern could decrease the accelerate of erotion until 75% or become round 23 ton per hectare per year or 1.97 mm per year.
To research the prosperity grade of farmers based on UMR standard, so the pattern of multiple cropping between beans and corn (maise) have to be applied in mixed farm enterprises, that is the farmer have to take care of livestock, such as cows, and fruits plant like rambutan and durian. To achieve the income over the UMR standard, so farmer need to be undersurveilance for 3-5 years intensively. This is now the reason why farmer should move from dry- land farming to the new pattern mentioned above.
The erosion level analysis is used to know growing pattern that gives erosion level under ETOL, while financial analysis which uses net present value, net B/C and IRR, is also used to know business feasibility of each growing pattern.
The results of the research imply that the rate of erosion occur in advance of growing season for all growing pattern, but two to three weeks after growing, each pattern give different response. In many cases, growing pattern proceeded by intercropping of paddy and corn resulting in higher erosion rate in comparison with pattern which is proceeded by intercropping of cont and legumes. The total erosion occurred on pattern with intercropping of paddy and corn range between 88.521 ton to 130.926 ton/year, or between 6,88 mm/year to 10,91 mm/year. All is over tolerated erosion namely 5,2 mm/year.
bimbingan oleh SOLEH SOLAHUDDIN, Alm. F. GUNARWAN SOERATMO SEDIONO, SMP. TJONDRONEGORO, NAIK SINUKABAN dan SJAFRI MANGKUPRAWIRA.
Sistem pertanian lahan kering adalah suatu bentuk bercocok tanam, yang kebutuhan air sangat bergantung pada curah hujan. Bentuk pertanian seperti ini diidentifikasi sebagai bentuk pertanian yang sangat rentan terhadap faktor-faktor pembatas seperti kesuburan tanah yang rendah, curah hujan terbatas dan peka terhadap bahaya erosi. Kondisi seperti ini mengakibatkan petaninya dikategorikan sebagai kelompok yang marginal secara sosial ekonomi. Pembatas sosial ekonomi inilah yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan mereka sangat lamban. Bukan karena keterbatasan teknologi, tetapi karena penerapan teknologi secara komprehensif dan aplikatif sangat terbatas.
Penerapan teknik konservasi bagi sebagian besar petani terutama petani miskin dan marginal masih sangat terbatas. Keterbatasan ini karena masih kuat anggapan mereka bahwa penerapan teknik konservasl hanya memberikan tambahan kerja, tetapi tidak memberikan tambahan pendapatan. Anggapan ini juga diperkuat dengan terbatasnya program diseminasi teknologi konservasi yang benar-benar dapat merubah sikap dan perilaku petani, tetapi lebih cenderung kepada progam yang berorientasi pada penyelesaian proyek.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis faktor-faktor pengelolaan biofisik pertanian lahan kering berdasarkan analisis degradasi lahan dan analisis teknik konservasi dalam rangka mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan, (2) Menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi ekonomi lingkungan berdasarkan pendekatan nilai ekonomi total (NET) dan dilanjutkan dengan analisis investasi untuk mendapatkan kelayakan secara finansial dan ekonomi lingkungan berdasarkan alternative pengelolaan, untuk mendukung terwujudnya sistem pertanian yang berkelanjutan,
Penelitian terhadap erosi dilakukan melalui pengukuran langsung di lapangan dengan mengunakan petak standar dan bak erosi (soil collector). Tanah yang terkumpul pada bak erosi dikeringkan dan ditimbang. Contoh tanah dari bak erosi diambil dan dianalisis untuk mengetahui kandungan hara utama yaitu nitrogran, phosphor dan kalium yang terkandung di dalamnya. Manfaat dan biaya untuk setiap pola tanam dianalisis dan diperbandingkan dengan tingkat erosi yang terjadi.
Analisis tingkat erosi digunakan untuk mengetahui pola tanam yang memberikan tingkat erosi dibawah Etol, sedangan alisis finansil yang menggunakan Net Present value, Net B/C, dan IRR, untuk mengetahui kelayakan usaha dari masing-masing pola tanam.
yaitu 5,2 m m/tahun.
Total erosi yang terjadi pada pola tanam yang diawali dengan tumpangsari jagung dan kacang-kacangan lebih rendah dibanding pola tumpangsari jagung dan padi ladang yaitu antara 16,931 ton/ha hingga 29,345 ton/ha atau antara 1,41mm/tahun hingga 2,45 mm/tahun, lebih kecil dari Etol. Kondisi ini disebabkan oleh penutupan lahan yang baik oleh tanaman kacang-kacangan terutama kacang-tanah. Erosi terendah pada pola tanam tumpangsari jagung dan kacang tanah, dilanjutkan dengan kedele dan Mucuna sp, tetapi tidak sampai panen ( tp).
Total manfaat masing-masing pola tanam dibedakan atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung terbesar diperoleh dari pola tanam tumpangsari jagung dan kacang tanah yang dilanjutkan dengan kedele dan Mucuna sp tidak panen (tp). Manfaat tidak langsung berasal dari sumbangan unsur hara (N, P, K) dari biomas tanaman konservasi Flemengia congesto dan Mucuna sp, yang dikonversikan ke nilai pupuk urea, TSP dan KCl. Total nilai sumbangan tanaman konservasi dalam satu musim tanam adalah Rp. 2.802.300,-Manfaat tidak langsung lainnya berasal dari nilai manfaat penurunan erosi dan nilai keberadaan kehilangan produksi yang dapat dicegah.
Analisis terhadap biaya usahatani terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Total biaya langsung untuk pola tanam yang dicoba berkisar antara Rp. 2.2.0.500, - hingga Rp. 3.426.000,- yang terdiri dari biaya pengolahan lahan dan tanam, bibit, pupuk, obat-obatan, penyiangan serta panen. sedang biaya tidak langsung dihitung atas dasar kehilangan unsur hara akibat erosi dari berbagai pola tanam yang diterapkan. Total kehilangan unsur hara termasuk kehilangan bahan organic berkisar antara Rp. 971.605,-/ha hingga Rp. 1.023.560,-/ha untuk pola tanam yang diawali dengan tumpang sari padi lading dan jagung serta Rp. 140.955,-/ha Rp. 248.215,-/ha untuk pola tanam yang diawali dengan tumpangsari jangung dan kacang-kacangan.
Analisis financial dilakukan dengan menghitung rasio biaya manfaat secara langsung dan tidak langsung. Hal ini ditujukan untuk memberikan gambaran terhadap besarnya manfaat yang secara langsung diterima oleh petani, Sedang rasio manfaat biaya secara tidak langsung menggambarkan tentang manfaat-manfaat lingkungan yang diperoleh. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola tanam yang diawali dengan tumpangsari padi ladang dan jagung kemudian dilanjutkan dengan penanaman Mucuna sp. hingga panen memberikan Net B/C langsung terbaik yaitu 2,59. Sedang pola tanam yang diawari dengan tumpangsari jagung dan kacang tanah kemudian dilanjutkan dengan Kedele dan Mucuna sp. (tp), memberikan Net B/C tidak langsung terbaik yaitu 3,75.
pendapatan petani per tahun minimal Rp. 27.500.000,- atau Rp. 1.833.000,- per bulan. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan mix farmning dengan mengusahankan ternak sapi, ayam dan buah-buahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah tiga tahun pelaksanaan mix farming pendapatan petani dapat mencapai Rp. 31.250.000,- pertahun atau rata-rata Rp. 2.604.000 per bulan.
Untuk mencapai tingkat pendapatan petani diatas nilai KHL tidaklah mudah karena masih ada sejumlah permasalahan social budaya seperti masih perlu adanya perubahan sikap dari peladang ke petani menetap juga perubahan orientasi usaha dari untuk memenuhi kebutuhan sendiri mejadi usaha yang komersil, termasuk di dalamnya bagaimana mempertahankan kelangsung produksi agar tetap tinggi dan berkelanjutan. Untuk mencapai perubahan sebagaimana diharapkan maka perlu dilakukan pola pendekatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dengan pendekatan enam aktor pembangunan dan pendekatan yang partisipatif dalam membangun program pembangunan berkelanjutan.
©Hak cipta milik IPB, tahun 2010 Hak cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
ILAH LADAMAY
Disertasi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada
Program Sudi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nama : Ilah Ladamay
NIM : 94538
Disetujui : Komisi Pembimbing
Ketua
Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, M.Sc
Anggota
Prof. Dr. Ir. F. G. Soeratmo, MF
Anggota
Prof. Dr. SMP. Tjondronegoro
Anggota
Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban
Anggota
Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira
Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, M.S. Prof.Dr.Ir. Khairil Anwar. Notodiputro, M.S.
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmatNya penelitian dengan judul Pengelolaan Lingkungan Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan ini dapat kami selesaikan dan disajikan dalam disertasi. Kesemuanya ini berkat dorongan komisi pembimbing, keluarga dan teman sejawat. Berkenan dengan itu, kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada .
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Alm. Prof. Dr. Ir. F.G. Soeratmo, Bapak Prof.Dr. SMP Tjondronegoro, Bapak Prof.Dr.lr. Naik Sinukaban, Bapak Prof. Dr.Ir. Sjafri Mangkuprawira, sebagai Anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan dorongan, saran, arahan serta petunjuk sejak penyusunan rencana penelitian hingga penulisan disertasi ini.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada kami mengikuti program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
3. Bapak Rektor Universitas Haluoleo dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 4. Ibu Mette Jansen, Program Coordinator Government UNDP, Bapak Ir. Jusuf
Widodo (National Program Director) BUILD-UNDP, Bapak Paul Sutmuller (Chief Technical Assistant) BUILD-UNDP, Bapak Kismet Kosasih (National Program Manager) BUILD-UNDP, Bapak H. Masyhur Masie Abunawas (Walikota Kendari), yang telah memberikan waktu, kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan pendidikan, selama kontrak kami dengan program BUILD-UNDP.
5. Bapak Dr. Suwardjo dan Bapak Drs. Suleman, yang telah memberikan rekomendasi dan bantuan serta dorongan moril sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
6. Bapak Sekarmika yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengujian pada lahan usahataninya serta membantu kami dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan penelitian kami di Desa Talumbinga Kecamatan Landono Kabupaten Kendari.
7. Rekan-rekan Ir. Marzuki Iswandi, M.Si., Ir. Lukman Yunus. M.Si., Ir. La Ode Sabaruddin,M.si., M. Ilyas, SE., Drs. Awaluddin, Ir. Benny M. Chalik, M.Si., yang telah memberikan bantuan teknis, saran dan nasehat selama penelitian dan penulisan disertasi ini.
Faradibah. Mariana Filda Fadilah, Maisun Fatin Fatimah dan Muh. Fikran, atas semua pengorbanan, pengertian, perhatian dan dorongan, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan ini.
Akhirnya semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan dan berguna dalam pembangunan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Amin.
Bogor, Februari 2010
Penulis dilahirkan di Tanah Merah (Boven Digul) Papua, pada tanggal 18 November 1958. Ayah bernama OMN. Ali Ladamay (wafat 25 Juni 1978) dan Ibu bernama Rapijah Laduani (wafat 24 Februari 1984).
Menyelesaikan Sekolah Dasar pada tahun l97l di Merauke dan menyelesaikan Sekolah Teknik Jurusan Mesin pada tahun 1974 juga di Merauke. Pada tahun 1979 lulus STM Pembangunan di Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1980 lulus SMA Muhammadyah di Kendari. Pada tahun 1986 menyelesaikan pendidikan Sl pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada tahun 1994 mengikuti pendidikan program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.
xii
DAFTAR TABEL ... xiv
DAFTAR GAMBAR ... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ... xvii
PENDAHULUAN ... 1
Latar Belakang ... 1
Permasalahan ... 5
Kerangka Pemikiran ... 5
Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 10
Hipotesis ………. 10
TINJAUAN PUSTAKA ... 11
Konservasi Lahan Kering ... 11
Prediksi Erosi ... 15
Penilaian Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan ... 22
Analisis Pendapatan ... 25
Analisis Investasi ... 26
Analisis Agrosistem Rumah Tangga Petani ... 28
GAMBARAN UMUM WILAYAH ... 32
Wilayah Sulawesi Tenggara ... 32
Letak dan Administrasi Wialayah ... 32
Keadaan Geografis ... 32
Keadaan lklim ... 32
Demografi ... 33
Penggunaan Lahan ... 33
Produksi Pertanian dan Kehutanan ... 33
Gambaran Lokasi Penelitian ... 36
Tanah ... 36
Iklim... 36
Penggunaan Lahan ... 37
Mata Pencaharian ... 37
Pendapatan ... 38
Kondisi Sosial Budaya... 38
METODE PENELITIAN ... 39
Unit Penelitian ... 39
Waktu Penelitian ... 39
Alat dan Bahan ... 39
Metode Pendekatan Penelitian ... 40
xiii
HASIL DAN PEMBAHASAN ... 52
Analisis Biofisik Lahan ... 52
Analisis Degradasi Lahan ... 52
Analisis Penerapan Teknik Konservasi ... 54
Analisis Ekonomi ... 59
Analisis Manfaat Langsung ... 59
Analisis Manfaat Tidak Langsung ... 60
Analisis Biaya ... 63
Analisis Investasi ... 65
Analisis Rasio Manfaat Biaya ... 66
Analisis Nilai Sekarang Bersih ... 68
Analisis Agrosistem Rumah Tangga Petani dalam Pertanian Berkelanjutan ... 68
Analisis Kelayakan Kehidupan Rumah Tangga Tani Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak ... 70
Analisis Perubahan Sosial Petani Lahan Kering ... 74
Pemberdayaan Petani ... 75
Penyuluhan ... 78
Pendekatan Pembangunan ... 84
KESIMPULAN DAN SARAN ... 86
Kesimpulan ... 86
Saran ... 87
DAFTAR PUSTAKA ... 88
xiv
1 Data penerapan teknik konservasi, produksi dan tenaga kerja yang dipergunakan dalam penerapan konservasi di DAS Brantas... 14 2 Taksonomi teknik penilaian yang relevan ……… ... 24 3 Curah hujan dilokasi penelitian desa Talumbinea dan penakar hujan
terdekat desa Mowila ……… ... 41 4 Pengaruh berbagai pola tanam terhadap erosi ... 53 5 Jumlah hasil kandungan unsur hara (N, P, K) dalam biomas
Mucuna sp dan Flemengia Congesta (kg) ………….. ... 58 6 Produksi jenis tanaman berdasarkan pola tanam ... 59 7 Manfaat langsung tanaman berdasarkan pola tanam ... 60 8 Nilai kesetaraan sumbangan unsur hara dari masing-masing
tanaman ……… ... 61 9 Nilai manfaat tidak langsung pengurangan erosi akibat penerapan
teknik konservasi terhadap pola lokal ……… ... 62 10 Nilai manfaat tidak langsung untuk nilai keberadaan berdasarkan
penurunan produksi pola tanam yang di rancang terhadap pola lokal ………. ... 63 11 Uraian biaya penerapan konservasi melalui pengaturan pola tanam
dalam satu tahun ……… ... 64 12 Analisis kehilangan unsur hara pada berbagai pola tanam ... 65 13 Manfaat langsung bersih dan manfaat tidak langsung
bersih penerapan teknik konservasi ……….. ... 66 14 Analisis ratio manfaat dan biaya langsung serta manfaat dan
biaya total ……….. ... 67 15 Hasil bersih pendapatan usahatani sesudah biaya rumah tangga ... 69 16 Kondisi ekonomi dan ekologi analisis pengelolaan pertanian lahan
xv
18 Perbandingan aktivitas antara sistem perladangan dan sistem pertanian berkelanjutan ……… ... 79 19 Obyek dan pesebaran lokasi penelitian pengembangan pertanian
xvi
Halaman 1 Diagram kerangka pikir keterkaitan permasalahan usahatani
tanpa memperhatikan keberlanjutan dan faktor-faktor yang menjadi fokus pengkajian ………. ... 9 2 Bagan alur analisis pengembangan sistem pertanian
berkelanjutan………. ………. ... 10 3 Grafik estimasi kehilangan produksi jagung pada studi
kasus kurva ………. ……….. 15
4 Skema Persamaan USLE ……… ... 20 5 Pengelompokan atribut nilai ekonomi untuk penilaian
lingkungan ……….. ... 23 6 Diagram input-output sistem perladangan di Sulawesi Tenggara 29 7 Denah pengujian lapang……….. ... 43 8 Hubungan laju erosi dan curah hujan per bulan untuk setiap
pola tanam ………. ... 55
9 Grafik komulatif eroasi yang terjadi sepanjang musim tanam ... 56 10 Diagram sistem pertanian berkelanjutan ……….. ... 73
11 Pelibatan petani, penyuluh dan peneliti 82
12 Pelibatan petani, penyuluh dan peneliti dalam
demplot/demfarm ………. 83
xvii
Halaman 1 Nilai faktor C dari berbagai tanaman dan pengelolaan atau tipe
penggunaan lahan ……….……… 101
2 Nilai faktor C beberapa macam tanaman di afrika barat …………. 103
3 Faktor penggunaan teknik konservasi tanah ………… ... 104
4 Faktor kedalaman tanah dari berbagai jenistanah ... 106
5 Kedalaman tanah minimum yang dapat diterima dan nilai faktor penggunaan lahan dari berbagai jenis tanaman penggunaan lahan ………. ... 107
6 Analisis kehilangan unsur hara pada berbagai pola tanam ... 109
7 Produksi jenis tanaman berdasarkan pola tanam ... 109
8 Nilai manfaat langsung dari masing-masing pola tanam ... 110
9 Nilai manfaat tidak langsung pengurangan erosi akibat penerapan teknik konservasi terhadap pola lokal……… ... 110
10 Nilai manfaat tidak langsung untuk nilai keberadaan penurunan produksi ……… ... 111
11 Uraian biaya penerapan teknik konservasi berdasarkan pola tanam ……….. ... 111
12 Analisis nilai kehilangan unsur hara pada berbagai pola tanam ... 112
13 Nilai manfaat langsung bersih dan manfaat tidak langsung bersih penerapan teknik konservasi ……….. ... 112
14 Analisis rasio manfaat dan biaya langsung serta manfaat dan biaya total pada berbagai pola tanam ……….. ... 113
15 Hasil bersih pendapatan pada berbagai pola tanam ... 113
xviii
18 Analisis finansial pola tanam 2 ………. ... 116
19 Analisis finansial pola tanam 3 ……….………. 117
20 Analisis finansial pola tanam 4 ……… ... 118
21 Analisis finansial pola tanam 5 ………. ... 119
Latar Belakang
Sistem pertanian lahan kering adalah merupakan suatu bentuk bercocok
tanam diatas lahan tanpa irigasi, yang kebutuhan air sangat bergantung pada curah
hujan. Bentuk pertanian seperti ini disebut tegalan, ladang dan huma, umumnya
tersebar di kawasan hutan hujan tropika. Ciri penting dari sistem pertanian ini
adalah ketergantungannya yang tinggi pada kondisi iklim terutama curah hujan
dan dalam pengelolaannya kondisi lahan relatif terbuka sepanjang tahun.
Kondisi lahan seperti ini ditambah dengan curah hujan yang tinggi,
menyebabkan lahan-lahan pada sistem pertanian ini sangat peka terhadap erosi
dan pencucian hara. Disamping itu pengangkutan sisa-sisa tanaman keluar
usahatani dan cara pembersihan dengan pembakaran semakin mempercepat laju
penurunan kualitas lahan. Cara pengelolaan seperti ini sangat merusak, sehingga
mempercepat meluasnya lahan kritis.
Umumnya kerusakan lahan di Indonesia terjadi akibat penggunaan lahan
secara intensip tanpa tindakan konservasi yang memadai. Belum diterapkannya
teknik konservasi pada lahan pertanian cenderung disebabkan oleh faktor sosial
ekonomi dan budaya serta kesadaran petani yang rendah. Penerapan teknik
konservasi bagi petani marginal dianggap sebagai suatu tambahan kerja dan tidak
memberikan tambahan pendapatan secara langsung. Hal ini sebenarnya suatu
persepsi yang keliru.
Kekeliruan persepsi ini terutama disebabkan karena pengetahuan tentang
penerapan teknik konservasi masih rendah, termasuk pengetahuan terhadap
kondisi biofisik lahan. Diketahui bahwa sebagian besar tanah di kawasan hutan
hujan tropika terdiri dari jenis podsolik merah kuning yang peka tehadap erosi dan
tingkat kesuburan tanah rendah (Foth 1991).
Sinukaban (1994) mengemukakan bahwa petani miskin di lahan yang
miskin akan terus saling memiskinkan kalau faktor-faktor penyebabnya tidak
dibenahi. Situasi pertanian di daerah yang demikian biasanya terkesan gerah, tidak
teratur dan tidak produktif. Keadaan seperti ini hampir dapat dijumpai di seluruh
Kondisi pengelolaan lahan yang demikian akan semakin memperluas terjadinya
lahan kritis dan kesenjangan sosial masyarakat.
Data statistik Indonesia (1990) menunjukkan bahwa pada tahun 1985
lahan kritis di Indonesia seluas 5.294.051 hektar, meningkat menjadi 12.905.600
hektar pada tahun 1989 atau meningkat sebesar 143 persen, dengan penyebab
utama adalah lahan-lahan bekas tegalan, ladang dan huma. Jumlah ini belum
termasuk lahan yang tidak dimanfaatkan seluas 111.000 hektar dan lahan-lahan
pertanian tanpa irigasi lainnya seluas 13.110.503 hektar, yang potensil menjadi
kritis karena dikelola tanpa konservasi. Pertambahan luas lahan kritis paling
banyak terjadi di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Baharsjah
(1994) luas lahan tidak produktif di Indonesia 38 juta hektar atau 20 persen dari
luas daratan Indonesia.
Sedang pada tahun 2007, luas lahan kritis bertambah menjadi 77,8 juta ha,
(Dirjen RPLS) meningkat sangat tajam dibanding 1989. Pertambahan lahan kritis
ini terjadi akibat pengelolaan pertanian dan penggundulan hutan. Motif
pertambahan luas lahan kritis dalam satu decade terakhir ini telah bergeser dari
penggunaan lahan untuk pertanian tanpa konservasi ke penebangan hutan untuk
produksi kayu, usaha-saha kehutanan seperti Hutan Tanaman Industri dan
pertambangan. Aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar tanpa diikuti dengan
rehabilitasi lahan memberikan ancaman yang lebih serius terhadap konservasi
tanah dan air di Indonesia.
Pengelolaan usaha tani yang baik harus dapat memberikan produksi yang
cukup tinggi bagi petani secara terus-menerus. Hal ini dapat dicapai bila erosi
yang terjadi pada lahan usahatani masih berada dibawah besarnya erosi yang
dapat ditoleransikan Etol (Sinukaban 1994). Dikemukakan pula bahwa
pengelolaan usahatani dengan erosi yang lebih kecil dari Etol dapat dicapai
dengan beberapa cara antara lain melalui pemilihan dan rotasi komoditas
pertanian secara tepat, penggunaan mulsa, pembuatan teras dan lain-lain.
Pemilihan dan rotasi tanaman secara tepat merupakan salah satu alternatif yang
menguntungkan karena dapat meningkatkan produktivitas lahan, permukaan tanah
tertutup sepanjang tahun, dan tanah terhindar dari energi kinetik air hujan yang
Arsyad (1989) mengemukakan bahwa penentuan erosi yang dapat
ditoleransikan perlu karena tidaklah mungkin menekan laju erosi menjadi nol dari
tanah-tanah yang diusahakan untuk pertanian terutama pada tanah-tanah yang
berlereng. Akan tetapi suatu kedalaman tanah tertentu harus dipelihara agar
terdapat suatu volume tanah yang cukup dan baik bagi tempat berjangkarnya akar
tanaman dan untuk tempat penyimpanan air serta unsur hara yang diperlukan bagi
tanaman. Oleh karena itu suatu lahan yang dimanfaatkan harus dapat diprediksi
besarnya erosi yang terjadi, agar dapat dilakukan berbagai tindakan konservasi.
Salah satu metoda prediksi erosi adalah model kotak kelabu untuk bidang
tanah dengan ukuran standar yang dikembangkan oleh Wischmeimer dan Smith
(1978) dikenal dengan the Universal Soil Loss Equation atau USLE. Persamaan ini adalah A = R K L S C P, dimana A = besarnya tanah tererosi, R = faktor
erosivitas hujan, K = erodibilitas tanah, L = panjang lereng, S = kecuraman
lereng, C = faktor pengelolaan tanaman, dan P = faktor pengelolaan tanah.
Faktor- faktor RKLS merupakan faktor-faktor yang bersifat tetap, sedang faktor C
dan P merupakan faktor pengelolaan yang dapat dimanipulasi.
Berdasarkan persamaan diatas, maka nilai faktor C dan P merupakan nilai
faktor yang berhubungan erat dengan tindakan konservasi yang dilakukan. Karena
RKLS adalah faktor-faktor yang bersifat tetap yang mempengaruhi besarnya
erosi. Semakin kecil nilai faktor C dan P, erosi yang terjadi akan semakin rendah,
berarti penerapan konservasi semakin baik. Atau dengan kata lain penerapan
konservasi yang baik harus dapat menekan erosi sekecil mungkin sekaligus
memberikan produksi pertanian yang tinggi secara terus-menerus.
Saat ini teknologi konservasi yang sesuai untuk sistem pertanian lahan
kering di Indonesia telah cukup berkembang. Metoda pendekatan secara rnekanik,
kimia dan vegetatif telah banyak diternukan, tetapi masih terbatas pada pengujian
demplot. Ditingkat petani belum banyak berkembang, kalaupun ada umumnya
dalam bentuk proyek pemerintah. Hambatan ditingkat petani bukan saja
disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang rendah, tetapi petani tidak
merasakan manfaat langsung dari penerapan teknik konservasi. Bahkan ada
sebaliknya memberikan tambahan kerja dan biaya. Anggapan seperti ini karena
terbatasnya modal dan tenaga kerja dikalangan petani lahan kering.
Dengan ketersediaan tenaga kerja rata-rata 2,8 HKP (hari kerja pria), per
hari per keluarga (di Sulawesi Tenggara) (Djuhumria l988), maka luas lahan yang
dapat diolah untuk satu musim tanam rata-rata 0,7 hektar dari luas pemilikan 2-3
hektar.
Di Sulawesi Tenggara ketersediaan tenaga kerja bagi sebagian besar
peladang adalah 2,8 HKP (hari kerja pria) perhari per keluarga, dengan
kemampuan olah lahan 0,7 hektar dari luas pemilikan lahan 2 – 3 hektar.
(Dujuhumria 1988). Sedang di Lampung satu keluarga transmigrasi memiliki
tenaga kerja per hari per keluarga 1,75 HOK (hari orang kerja), kemampuan olah
lahan antara 0,5 - 0,75 hektar dari luas pemilikan lahan pertanian 1,75 hektar,
Nasendi dan Anwar (1985). Sedang menurut Juwanti et al. (1992) dan Sinukaban (1994) mengemukakan bahwa luas usahatani petani di DAS Jratunseluna dan
Brantas memiliki lahan bervariasi dari 0,30 - 1,1 hektar, dengan luas pengusahaan
rata-rata oleh setiap petani berkisar dari 0,358 - 0,770 hektar. Kemampuan
pengelolaan lahan yang terbatas juga disebabkan karena faktor penguasaan
teknologi, modal dan lain-lain.
Harijaya (1995) mengemukakan adanya anggapan klasik sebagian besar
petani di Indonesia bahwa tanah-tanah disini cukup subur dan dapat dipergunakan
sepanjang masa tanpa memerlukan perlakuan yang teratur. Anggapan seperti ini
juga merupakan kendala dalam menerapkan teknik konservasi di tingkat petani,
Persepsi yang keliru inilah juga merupakan penyebab tidak berkembangnya teknik
konservasi di kalangan petani.
Dalam memberikan arahan tepat dalam pembenahan faktor-faktor fisik
lahan melalui penerapan teknik konservasi, perlu diikuti dengan analisis sosial
ekonomi. Kendala-kendala seperti biaya, tenaga kerja dan pola tanam perlu
diperhitungkan. Dalam konteks ini sistem pengelolaan usahatani dapat di dekati
dengan melakukan analisis investasi atau analisis proyek (Gittinger 1982). Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara holistic terhadap pengelolaan
Dengan Demikian pertimbangan-pertimbangan biofisik dan sosial
ekonomi harus dianalisis secara bersamaan dan simultan. Disinilah diperlukan
pendekatan yang konprehensif dalam pengembangan suatu analisis cara bertani di
lahan kering secara berkelanjutan.
Permasalahan
Permasalahan pokok dalam pengembangan pertanian lahan kering saat ini
adalah belum optimalnya.penggunaan lahan baik secara biofisik maupun sosial
ekonomi dalam rangka penyelenggaraan sistem pertanian yang berkelanjutan.
Secara rinci pernyataan permasalahan dalam mengoptimalkan penggunaan lahan
kering baik secara biofisik dan sosial ekonomi adalah:
1. Bagaimana mengembangkan suatu sistem pengelolaan tanah dan tanaman
melalui penerapan prinsip-prinsip konservasi secara optimal untuk
mendapatkan tingkat pengelolaan biofisik lahan terbaik dalam rangka
pelaksanaan sistem pertanian lahan kering berkelanjutan,
2. Bagaimana kombinasi pengelolaan tanah dan tanaman dengan prinsip –
prinsip konservasi berdasarkan kriteria sosial ekonomi, agar dapat
memberikan hasil yang optimal.
3. Bagaimana mengelola pola pertanaman (diversifikasi usahatani) secara layak
agar dapat memberikan manfaat terhadap perbaikan biofisik lahan dan
pendapatan petani.
4. Bagaimana mengembangkan konsep keterpaduan secara biofisik dan sosial
ekonomi untuk mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan.
Kerangka Pemikiran
Sistem pertanian berkelanjutan dapat dicapai apabila kondisi biofisik lahan
terpelihara dengan baik sehingga memungkinkan produktivitas lahan tetap tinggi
dan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi petani. Hubungan antara
terpeliharanya biofisik lahan dan peningkatan pendapatan harus berjalan secara
paralel, karena produksi pertanian dapat meningkat bila tanaman mendapatkan
dengan baik jika petani memiliki kesadaran dan kemampuan untuk
memperbaikinya serta adanya insentif untuk memelihara kondisi biofisik lahan,
berdasarkan metode yang benar yang mereka anut.
Metode untuk mempertahankan kondisi biofisik lahan terutama pada
pertanian lahan kering mutlak diperlukan. Derajat kebutuhannya bukan hanya
berkaitan dengan pengetahuan teknik konservasi tetapi juga kesadaran ancaman
degradasi lahan akibat salah kelola. Artinya mereka harus paham bahwa lahan
yang dikelola perlu terus dijaga karena dengan demikian akan menjamin
kelangsungan usahanya. Sebaliknya akibat salah kelola akan merugikan mereka
secara langsung, termasuk masyarakat di luar sistem pertanian yang terkena
dampak secara langsung misalnya akibat erosi, maupun yang bergantung pada
produksi pertanian.
Kerusakan lahan juga tidak hanya bersifat in-situ, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar lahan yang tererosi bahkan sampai
pada radius yang sangat luas (ex-situ). Kondisi seperti ini dapat terjadi sesuai bentuk kawasan daerah aliran sungai. Kerusakan yang terjadi secara in-situ
maupun ex-situ kedua-duanya berakibat kerugian baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Oleh sebab itu petani merupakan aktor kunci yang perlu diberdayakan
dan ditingkatkan pengetahuan, keterampilan, pendapatan serta memberikan
insentif lainnya, sehingga mereka mau menerapkan teknik-teknik konservasi dan
menjadi bagian dari kebiasaannya.
Program konservasi seperti Upland Agriculture and Conservation Project (UACP), di DAS Jratunseluna dan Brantas, dan beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor, di Jawa,
Sumatera, Kalimantan dan tiga lokasi di Sulawesi yaitu di Gorontalo (Sulut), di
Maros (Sulsel) dan di Kendari (Sultra), merupakan refensi yang baik untuk dasar
pengembangan pertanian berkelanjutan dilahan kering.
Hasil evaluasi tahun l99l/l992 menunjukkan bahwa laju erosi di DAS
Jratunseluna dan DAS Brantas telah dapat diturunkan hingga 60 persen, tetapi
masih tetap berada diatas erosi yang ditoleransikan. Sinukaban (1994)
mengemukakan bahwasalah satu penyebab adalah tidak terpeliharanya komponen
yang diterapkan. Selanjutnya dikemukakan bahwa hal itu disebabkan; (1)
kurangnya pemahaman petani tentang fungsi komponen teknik konservasi tanah
yang telah dibangun, (2) kurangnyapenyuluhan tentang pentingnya pemeliharaan
komponen-komponen pengendalian erosi untuk meningkatkan dan
mempertahankan produktivitas secara lestari, (3) mahalnya biaya pemeliharaan
yang dapat mencapai Rp. 148.000,-/ha/tahun, dan (4) rendahnya pendapatan
keluarga.
Kenyataan ini menunjukkan untuk mempertahankan kelestarian komponen
biofisik, petani dituntut untuk terampil dan mempunyai kesadaran, serta
memerlukan kemampuan ekonomi yang stabil. Arsyad (1989) mengemukakan
bahwa keseimbangan antara sub sistem sosial ekonomi dan sub sistem biofisik
sangat penting, karena sub sistem biofisik merupakan dasar yang akan
menentukan struktur dan bentuk dari sub sistem sosial ekonomi. Sub sistem
biofisik yang dibangun oleh komponen tanah, topografi dan penggunaan lahan,
sangat penting dan menentukan keberlanjutan dari usaha tani. Sedang
keberlanjutan dari suatu usaha tani selain didukung oleh faktor-faktor biofisik
yang lestari juga memerlukan manajemenusahatani yang baik.
Untuk menjaga kelestarian kondisi biofisik, maka selain diterapkan
teknik-teknik konservasi, juga diperlukan tindakan-tindakan pemeliharaan seperti
penyiangan, pemupukan, penambahan bahan organik, dan lain-lain. Hal ini
digambarkan oleh Sumarwoto (1974) sebagai usaha pemberian energi untuk
mempertahankan suatu kemantapan ekosistem pertanian. SedangClapham (1976)
menggambarkan tindakan-tindakan tersebut sebagai tekanan balik dari suatu
ekosistem yang dimanfaatkan.
Oleh karena luasnya permasalahan lingkungan dalam kaitannnya dengan
pengelolaan pertanian lahan kering, maka kajian dalam penelitian ini dibatasi
pada analisis hubungan antara faktor biofisik yang berkaitan dengan degradasi
lahan (erosi), faktor ekonomi yaitu produksi dan pendapatan serta faktor sosial
budaya seperti perilaku petani peladang, perubahan sikap terhadap inovasi dan
tata cara bertani. Diagram kerangka pikir dan faktor-faktor yang dikaji dalam
```
Keterangan: faktor yang dikaji
Gambar l Diagram kerangka pikir keterkaitan permasalahan usahatani tanpa memperhatikan keberlanjutan dan faktor-faktor yang menjadi fokus pengkajian.
Dengan demikian utnuk mengembangkan suatu sistem pertanian secara
berkelanjutan maka diperlukan pendekatan komprehensif dengan memperhatikan
komponen biofisik dan sosial melalui analisis tingkat degradasi lahan dan analisis
teknologi konservasi, analisis nilai ekonomi total dan analisis manfaat lingkungan
serta analisis kondisi sosial dan budaya. Hubungan proses analisis biofisik dan
sosial ekonomi untuk mencapai sistem pertanian berkelanjutan disajikan pada
Gambar 2.
USAHA TANI TANPA MEMPERHATIKAN KEBERLAJUTAN
EROSI TINGGI ALIRAN PERMUKAAN TINGGI
PROSES KEKAYAAN
(EXSITU)
SEDIMENTASI
PENDANGKALAN KUALITAS AIR RENDAH
MENGURANGI FUNGSI SOSEK
PROD. BIOTA RENDAH
KESUBURAN LAHAN MENURUN
(INSITU)
KERUSAKAN TATA AIR
RODUKSI MENURUN
BANJIR DAN KEKERINGAN
PENDAPATAN MENURUN
KUALITAS LINGK. HIDUP
RENDAH
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Gambar 2 Bagan alur analisis pengembangan sistem pertanian berkelanjutan.
Tujuan, Kegunaan Penelitian dan Hipotesis Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan
sistem pertanian lahan kering secara berkelanjutan yang meliputi :
1. Analisis faktor-faktor pengelolaan biofisik pertanian lahan kering berdasarkan
analisis degradasi lahan dan analisis teknik konservasi dalam rangka
mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan,
2. Analisis faktor-faktor sosial ekonomi ekonomi lingkungan berdasarkan
pendekatan nilai ekonomi total (NET) dan dilanjutkan dengan analisis
investasi untuk mendapatkan kelayakan secara finansial dan ekonomi
lingkungan berdasarkan alternative pengelolaan, untuk mendukung
terwujudnya sistem pertanian yang berkelanjutan,
3. Mengembangkan model pertanian lahan kering berkelanjutan yang
memungkinkan dalam jangka waktu 3 – 5 tahun petani lahan kering dapat
Kegunaan Penelitian
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif tentang cara-cara
perlakukan teknik konservasi pertanian lahan kering guna mendapatkan model
pengembangan yang sesuai dengan biofisik, sosial ekonomi dan budaya
masyarakat.
2. Merupakan masukan para pengambil kebijakan dalam mengembangkan
pertanian lahan kering secara berkelanjutan.
3. Mengembangkan model system pertanian lahan kering berkelanjutan untuk
meningkatkan kesejahteraan petani dengan ukuran kebutuhan hidup layak.
Hipotesis
Hipotesis utama adalah bahwa melalui penerapan teknik konservasi pada
pertanian lahan kering, dapat menjaga kondisi biofisik lahan serta meningkatkan
pendapatan pateni dan memperbaiki kondisi sosial petani lahan kering.
1. Secara biofisik hipotesis diterima bila erosi yang ditimbulkan berdasarkan
penerapan teknik konservasi lebih kecil dari erosi yang ditoleransi (Etol)
2. B/C ratio total manfaat lebih besar dari B/C ratio manfaat langsung ; NPV pola taman dengan kondisi biofisik terbaik posif.
3. Pendapatan petani setelah 3 – 5 tahun lebih besar atau sama dengan standar
Konservasi Lahan Kering
Pertanian lahan kering adalah sebidang tanah yang dipergunakan untuk
usahatani dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya kebutuhan air
hanya mengharapkan dari curah hujan (Hanjaya 1995). Sedang menurut
Suwardjo (1981) sistem pertanian lahan kering adalah pertanian yang
dilaksanakan diatas tanah tanpa irigasi dalam bentuk tegalan atau ladang. Kondisi
permukaan tanah yang relatif terbuka sepanjang tahun dan curah hujan yang
tinggi, merupakan penyebab kerusakan lahan, oleh karena itu penerapan teknik
konservasi pada pertanian lahan kering merupakan suatu persyaratan mutlak untuk
menjaga kelangsungan penggunaan lahan.
Prinsip-prinsip dalam konservasi lahan kering tidak terlepas dari pengertian
konservasi mengenai tanah dan air. Kondisi tanah yang marginal pada lahan
kering dengan ciri solum tanah dangkal, kandungan bahan organic rendah,
kesuburan tanah rendah dan tingkat kemasaman tinggi atau pH rendah, merupakan
kendala dalam penggunaan lahan untuk pengembangan usahatani.
Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada
penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan
memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi
kerusakan tanah. Sedang konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air
yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin, melalui pengaturan waktu
aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak dan cukup air pada musim
kemarau (Arsyad l989).
Pertanian lahan kering umumnya berada pada daerah hulu (up land) hingga daerah-daerah pertengahan dengan keadaan lahan yang berlereng (Harijaya 1995).
Keadaan lahan seperti ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya erosi
dan aliran permukaan yang berlebihan Disamping faktor lereng, sifat tanah, curah
hujan, vegetasi penutup dan aktivitas manusia juga mempengaruhi terjadinya
erosi. Hayward dalam Klootwijk (1975) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi erosi adalah; (1) tanaman penutup, (2) cara bercocok tanam, (3)
tanah, dan (6) faktor tanah. Pertanian lahan kering tanpa konservasi di daerah hulu
juga berperanan sangat besar pada berbagai fenomena alam seperti banjir,
kekeringan dan sedimentasi di daerah hilir.
Arsyad (1989) mengemukakan bahwa pada dasarnya faktor-faktor
penyebab erosi dibedakan atas; (l) faktor-faktor yang dapat dirobah oleh manusia
seperti tumbuhan yang tumbuh diatas tanah, sebagai sifat-sifat tanah seperti
kesuburan, ketahanan agregat, kapasitas infiltrasi dan panjang lereng, serta (2)
faktor-faktor yang tidak dapat dirobah yaitu seperti iklim, tipe tanah dan
kecuraman lereng. Penerapan teknik konservasi pada prinsipnya cenderung
kepada intervensi terhadap faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manusia.
Secara garis besar metoda konservasi dapat dibedakan atas tiga metoda yaitu
metoda vegetatif, mekanik dan kimia. Yang sering digunakan adalah metoda
vegetatif dan metoda mekanik, sedang metoda kimia jarang digunakan karena
memerlukan biaya mahal. Termasuk metoda vegetatif adalah; (l) penanaman
tumbuhan atau tanaman yang menutup tanah secara terus-menerus sepanjang
tahun, (2) penanaman dalam strip, (3) pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk
hijau atau tanaman penutup tanah, (4) sistem pertanian hutan, (5) Pemanfaatan
sisa-sisa tanaman atau tumbuhan sebagai mulsa, dan (6) penanaman
saluran-saluran air dengan rumput. Sedang yang tergolong dalam metoda mekanik adalah;
(1) pengolahan tanah, (2) pengolahan tanah menurut kontur, (3) guludan dan
guludan bersaluran menurut kontur, (4) terras, (5) penghambat, waduk, rorak,
tanggul dan (6) perbaikan drainase dan irigasi (Arsyad 1989).
Suwardjo (1993) mengemukakan karena adanya berbagai kendala fisik dan
sosial ekonomi, maka metoda yang mudah dan murah serta sangat efektif untuk
konservasi di lahan kering adalah metoda vegetatif. Penggunaan tanaman legum
seperti Flamengia congesta, Mucuna sp., dan Komak, dapat meningkatkan produktivitas lahan pada beberapa lokasi pengujian baik di Pulau Jawa maupun di
beberapa tempat seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu
diperlukan masukan pupuk yang tinggi, agar produktivitas pertanian lahan kering
dapat dipertahankan.
Hasil pengujian metoda konservasi vegetatif melalui pertanaman lorong di
kimia tanah setelah perlakuan selama tiga musim tanam (Sudharto 1993).
Ketahanan penetrasi tanah menujukan penurunan dari rata-rata 15 kgF/cm2
menjadi rata-rata 10,5 kgF/cm2. Kondisi penetrasi ketahanan tanah seperti ini
merupakan suatu kondisi yang baik bagi perakaran tanaman. Perkembangan
perakaran sebagian besar tanaman akan terganggu pada ketanahan penetrasi 13
kgF/cm2
Metoda mekanik seperti pembuatan terras juga efektif untuk konservasi
tanah dan air. Tetapi dalam pembuatan terras harus memperhatikan beberapa
persyaratan seperti solum tanah harus cukup dalam, tanah tidak peka terhadap
erosi dan tidak terdapat bidang luncur untuk lahan-lahan dengan kemiringan yang
cukup terjal (Harijaya, 1995). Menurut Suwardjo dan Dariah (1994) penggunaan
terras gulud cukup baik dan murah serta dapat dibuat pada hampir semua jenis
tanah dan lereng yang bervariasi dari 3-50 persen. Sebagai perbandingan
pembuatan terras bangku memerlukan tenaga kerja 500-1.000 HOK /hektar,
sedang untuk pembuatan terras gulud hanya memerlukan 50-100 HOK/hektar. . Penurunan ketahanan penetrasi merupakan salah satu indikator semakin
baiknya sifat-sifat fisik tanah. Suwardjo (1981) mengemukakan bahwa
penggunaan sisa-sisa tanaman sebagai mulsa dapat menekan laju erosi hingga
dibawah tingkat erosi yang dapat dibiarkan, menekan laju aliran permukaan,
memperbaiki sifat fisik tanah dan kimia tanah serta aktivitas biologi dan
meningkatkan pertumbuhan dan produksi.
Penerapan metoda konservasi mekanik yang dilakukan di DAS Brantas
menunjukan bahwa pembuatan terras bangku sangat efektif untuk menekan erosi,
dan dapat meningkatkan produksi jagung dan ubikayu, tetapi sejalan dengan itu
memerlukan korbanan tenaga kerja yang cukup besar (Sembiring 1990 dalam
Harijaya 1995). Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa data penerapan
teknik konservasi, data erosi yang terjadi, data produksi dan data tenaga kerja
Tabel 1 Data penerapan teknik konservasi, produksi dan tenaga kerja yang dipergunakan dalam penerapan konservasi di DAS Brantas.
Teknik Konservasi
Mekanik
Erosi (Ton/Ha/9 bln)
Produksi (Ton/Ha) Tenaga
Kerja
Sumber: Sembiring (1990) dalam Harijaya (1995).
Sebagai perbandingan data penggunaan tenaga kerja untuk penerapan
metoda konservasi vegetatif dengan teknik pertanaman lorong adalah 116
HOK/hektar. Nissen-Petersen, E. 2000. melaporkan tentang metoda konservasi yang
dilakukan oleh masyarakat di dataran tinggi Ekuador yang disebut Sulaman
Metoda ini dilaksanakan pada areal dengan ketinggian 7.500 feet dan kecuraman
lereng 50-70 persen, berada pada iklim tropika dingin (cool tropical) atau mesothermal. Metoda ini merupakan gabungan antara metoda mekanik dengan
vegetatif, yaitu dengan menerapkan pengolahan tanah menurut garis kontur dan
penanaman strip tanaman. Dengan menggunakan biaya yang rendah, metoda ini
mampu mempertahankan produksi pangan dan buah-buahan, dimana keberhasilan
metoda ini oleh Bank Dunia disamakan dengan fungsi pelayanan penyuluhan
yang dilakukan oleh Soil Conservation Service di Amerika Serikat.
Beberapa metoda konservasi yang bersifat tradisional yang telah berhasil
dinegara-negara Afrika seperti dilaporkan oleh Journal Of Soil and Water Conservation, adalah Zays system, dikembangkan di Mali, yang menggunakan striptanaman dari jenis rumput vertiver, Milpa system di kembangkan di Meksiko Tengah, dilaporkan oleh Bacco (1991), Sistem Hunano'o dikembangkan di
Philipina, dilaporkan oleh Conklin (1997), dan Sistem Produksi Modular,
dikembangkan di Tabasco, Meksiko, dilaporkan oleh Gliessman (1981) Suatu
studi kasus yang dilaporkan oleh Pagiola (2006) di Kenya menunjukan bahwa
pengelolaan pertanianlahan kering pada lahan dengan kemiringan 15 persen tanpa
diikuti dengan tindakan konservasi yang intensip, mengakibatkan penurunan
Dalam sepuluh tahun pertama terjadi penurunan produksi sebesar 20 persen,
sedang pada 20 tahun berikutnya terjadi penurunan produksi sebesar 40 persen.
Suatu kondisi dimana secara ekonomi sudah tidak menguntungkan lagi. Model
estimasi dalam studi kasus tersebut disajikan padagambar 3.
Gambar 3 Grafik estimasi kehilangan produksi jagung pada studi kasus di Kenya.
Berdasarkan uraian tentang konservasi lahan kering diatas, maka pada
prinsipnya penerapan teknik-teknik konservasi menunjukkan mampu menekan
laju erosi dan meningkatkan serta mempertahankan produksi pada pertanian lahan
kering, tetapi sampai sejauh mana usaha-usaha itu telah memberikan dampak
kepada peningkatan pendapatan keluarga petani dan mengoptimalkan
faktor-faktor biofisik dan sosial ekonomi belumlah dianalisis.
Prediksi Erosi
Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau
bagian-bagian tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh media alami (Arsyad 1989).
Media alami yang dimaksud disini adalah air dan angin. Di Indonesia dan di
daerah tropis umumnya yang paling berperan adalah air.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Year 3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0 Year (t/ha)
Berdasarkan kejadiannya erosi dapat dibedakan atas; (1) erosi normal atau
erosi geologi atau erosi alami yaitu proses pengangkutan tanah yang terjadi
dibawah keadaan vegetasi alami, dan (2) erosi dipercepat yaitu pengangkutan
tanah yang menimbulkan kerusakan tanah sebagai akibat perbuatan manusia, yang
menggangu keseimbangan antara proses pembentukan dan pengangkutan tanah.
Erosi dipercepati inilah yang menjadi perhatian konservasi tanah.
Masalah erosi menjadi begitu penting karena akibat yang ditimbulkan tidak
saja merugikan tempat dimana erosi itu terjadi, tetapi juga memberi dampak
negatif terhadap tempat-tempat diluar lokasi dimana erosi itu terjadi. Kerusakan
yang terjadi pada tempat erosi adalah kemunduran sifat fisik dan kimia tanah.
Kemunduran yang terjadi pada sifat fisik tanah antara lain menurunnya kapasitas
infiltrasi dan kemampuan menahan air, meningkatnya kepadatan dan ketahanan
penetrasi tanah serta berkurangnya kemantapan struktur tanah. Sedang
kemunduran sifat kimia tanah dapat terjadi karena terangkutnya unsur hara
bersama tanah yang tererosi.
Suwardjo (1981) mengemukakan bahwa suatu tanah Latosol Merah di
Citayam yang mengandung 0,074% nitrogen, 3,450 bahan organik, 0,042% P2O5,
0,008% K2O dan 0,074% Ca dengan erosi sebesar 121,1 ton/ha, dalam satu
musim tanam jagung, mengalami kehilangan unsur hara sebanyak 206 kg
nitrogen, 4.190 kg bahan organik, 52 kg P2O5, 10 kg K2
Dampak erosi terhadap tempat di luar kejadian erosi adalah pelumpuran dan
pendangkalan waduk, sungai, saluran dan badan air lainnya. Dampak lainnya
adalah tertimbunnya lahan pertanian di daerah bawah, kerusakan kualitas air dan
menghilangnya mata air serta berkurangnya umur guna waduk dan berbagai
kerugian material lainnya, Arsyad (1989). Dampak erosi terhadap tempat diluar
kejadian digambarkan sebagai suatu usaha yang bukan hanya merugikan diri
sendiri, tetapi juga merugikan orang lain.
O dan 90 kg CaO per
hektar. Jumlah unsur hara yang hilang tersebut setara dengan 4,3 kuintal urea,
1,15 kuintal TSP, 0,20 kuintal KCl dan 2,0 kuintal kapur.
Akibat erosi yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan tanah akan
menjadi rusak atau yang diistilahkan dengan lahan kritis. Menurut Sadikin (1997)
penggunaan dengan kemampuannya, telah mengalami atau dalam kerusakan fisik,
kimia dan biologi, yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi dan
produksi pertanian, pemukiman serta kehidupan sosial. Hal ini mengakibatkan
perkembangan lahan kritis dengan cepat dari tahun ke tahun.
Erosi di daerah tropika disebabkan oleh tingginya curah hujan. Oleh karena
itu daerah-daerah di kawasan tropika merupakan daerah-daerah dengan tingkat
erosi tertinggi di dunia. El-Swaify (Arsyad dan Krisnarajah 1983). Secara
keseluruhan Asia merupakan benua dengan tingkat erosi tertinggi yaitu rata-rata
166 ton/km2/tahun dan Australia merupakan benua dengan tingkat erosi terendah
yaitu 32 ton/km2
Erosi pada dasarnya tidak dapat ditekan hingga nol, oleh karena itu maka
ditetapkan suatu batas erosi yang diperbolehkan, yang disebut sebagai nilai T,
(Arsyad 1989) atau oleh Sinukaban (1994) disebut E
/tahun. Besarnya erosi yang terjadi di benua Asia tidak terlepas
dari sumbangan yang diberikan oleh sektor pertanian lahan kering dan
perambahan hutan.
tol
Produktivitas tanah berdasarkan konsep Hammer (1981) adalah sebagai
akibat menurunnya kandungan unsur hara tanah dan/atau merosotnya sifat-sifat
fisik tanah. Untuk itu dilakukan pengelompokkan kedalam kategori rendah (R),
sedang (S) dan tinggi (T). Kombinasi penurunan faktor fisik dan kimia tanah
dengan tiga kategori tersebut diperoleh sembilan stratifikasi nilai faktor
kedalaman tanah. Nilai faktor kedalaman tanah dikalikan dengan kedalaman
efektif tanah (effective soil depth) diperoleh kedalaman eqivalen.
. Ada dua cara penetapan
nilai T yaitu; pertama dengan menggunakan kedalam tanah, permeabilitas lapisan
bawah dan kondisi stratum. Untuk itu ditetapkan enam sifat tanah dan stratum
Kedua Hammer (1981) menggunakan konsep kedalaman ekivalen (equivalent depth) dan umur guna (resource life). Kedalaman eqivalen adalah kedalaman tanah yang setelah mengalami erosi produktivitasnya berkurang dengan 60% dari
produktivitas tanah yang tidak tererosi.
Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman tanah sampai suatu lapisan yang
bisa ditembus akar. Nilai faktor kedalaman tanah untuk 30 sub-order tanah telah
disusun oleh Hammer (1981). Deskripsi ini adalah untuk tanah-tanah di Indonesia
Pendekatan yang dilakukan oleh Hammer (1981) sebagaimana diuraikan di
atas, tidak memperhitungkan faktor pembentukan tanah. Bila diperhitungkan
faktor pembentukan tanah maka rumus dengan menggunakan kedalaman
eqivalen sebagai berikut:
) / (
min PT mm tahun
MPT D D
Etol = e − + (Sinukaban 1995)
Dimana: De
D
= kedalaman tanah efektif x faktor kedalaman
min
MPT = masa pakai tanah
= kedalaman tanah minimum
PT = laju pembentukan tanah.
Tingkat pengelolaan tanaman dan tanah yang baik adalah apabila besarnya
erosi yang terjadi (erosi aktual), lebih kecil dari erosi yang ditoleransikan (Etol). Untuk itu maka perlu dilakukan prediksi erosi aktual. Prediksi erosi dilakukan
dengan menggunakan persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation) yaitu:
A = R K L S C P
A = besarnya erosi yang terjadi (ton hektar-1tahun-1
R = erosivitas hujan tahunan yaitu satuan indeks erosi hujan yang
menyatakan hubungan antara energi hujan total (E) dengan intensitas
hujan maksimum 30 menit (EI
)
30). Nilai R adalah penjumlahan dari
EI30
R = EI
selama satu tahun.
Nilai R juga dapat diperoleh dengan menggunakan peta isoeroden
30
K = erodibilitas tanah yaitu laju erosi per indeks erosi hujan untuk suatu
tanah yang didapat dari petak percobaan standar dengan panjang 22,1
meter, terletak pada lereng sembilan persen tanpa tanaman. Bila
diketahui kandungan bahan organik tanah, tekstur, struktur dan
permiabilitas, maka nilai K dapat dihitung dengan menggunakan
rumus yang dikemukakan oleh Wischmeier (1978).
M = (% pasir halus + debu)(100 - %liat)
a = % bahan organic
b = Kode struktur tanah
c = Kelas permiabilitas profil tanah.
Penetapan nilai erodibilitas (K) dapat juga ditentukan dengan
menggunakan nomograf erodibilitas tanah.
L = panjang lereng yang diukur mulai dari tempat terjadinya aliran air
diatas permukaan tanah sampai ke tempat mulai terjadinya
pengendapan, yang disebabkan karena berkurangnya kecuraman
lereng. Faktor panjang lereng merupakan nisbah antara erosi dari tanah
dengan suatu panjang lereng tertentu terhadap erosi dari tanah dengan
paryang 22,1 meter di bawah keadaan identik.
Faktor panjang lereng ditentukan dengan rumus :
L = (X 22-1)
Dimana: X = panjang lereng sebenarnya
m
m = konstanta, 0,3 untuk kecuraman lereng < 5%
0,5 untuk kecuraman lereng > 5%
S = kecuraman lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi pada suatu tanah
dengan kecuraman lereng tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah
dengan lereng sembilan persen dibawah keadaan identik. Nilai faktor S
dihitung dengan rumus :
613 , 6
043 , 0 3 , 0 43 ,
0 s s2
S = + +
dimana: S = kecuraman lereng (%)
C = faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman, yaitu nisbah
antara besarnya erosi dari suatu areal dengan vegetasi penutup dan
pengelolaan tanaman tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang
identik tanpa tanaman.
P = faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah, yaitu nisbah antara
besarnya erosi dari tanah yang diberikan perlakuan tindakan
dalam strip atau terras, terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah
searah lereng dalam keadaan identik. Skema persamaan erosi
berdasarkan pendekatan Universal Soil Loss Equation (USLE) pada Gambar 4.
A = R K LS P C
Gambar 4 Skema persamaan USLE (Arsyad 1989) Hujan
Energi
Kekuatan Perusak Hujan
Pengelolaan Lahan Sifat
t h
Pengelolaan Tanaman Pengelolaa
Kemungkinan Erosi Tanah Besarnya Erosi
Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi erosi dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu faktor-faktor yang
dapat dimanipulasi oleh manusia dan yang tidak dapat dimanipulasi. Bila
dikaitkan dengan persamaan USLE, maka faktor C dan P merupakan faktor yang
dapat dimanipulasi, tetapi bersifat spesifik lokasi. Oleh karena itu nilai yang
diberikan dari kombinasi tanaman dan tanah juga bersifat spesifik lokasi. Artinya
nilai-nilai tersebut hanya dapat dipergunakan secara akurat untuk suatu kondisi
dengan keadaan biofisik (tanah dan iklim) yang identik. Beberapa nilai C dan P di
Indonesia dan Afrika disajikan pada lampiran.
Perbandingan nilai erosi aktual dari petak standar tanpa perlakuan (C dan
P = 1), dengan nilai erosi petak standar dengan perlakuan kombinasi tanaman,
akan diperoleh nilai faktor pengelolaan tanaman dan tanah. Semakin kecil faktor
C dan P, memberikan gambaran semakin baiknya pengelolaan. Kondisi seperti itu
digambarkan oleh Sinukaban (1994) sebagai upaya pengembangan sistem
pertanian konservasi (SPK), dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Produksi pertanian cukup tinggi sehingga petani tetapi tetap bergairah
melanjutkan usahanya.
2. Pendapatan petani cukup tinggi, sehingga petani dapat mendesain masa depan
keluarganya dari pendapatan usahataninya.
3. Teknologi yang diterapkan baik teknologi produksi maupun teknologi
konservasi adalah teknologi yang dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan
petani dan diterima oleh petani dengan senang hati sehingga sistem pertanian
tersebut dapat dan akan diteruskan oleh petani dengan kemampuannya secara
terus menerus tanpa bantuan dari luar.
4. Laju erosi kecil (minimal), lebih kecil dari erosi yang ditoleransikan,
sehingga produktivitas yang cukup tinggi tetap dapat
dipertahankan/ditingkatkan secara lestari dan fungsi hidrologis daerah
terpelihara dengan baik sehingga tidak terjadi banjir dimusim hujan dan
kekeringan dimusim kemarau, dan
5. Sistem penguasaan/pemilikan lahan dapat menjamin keamanan investasi
Penilaian Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Suatu kekeliruan yang menganggap bahwa tanah merupakan suatu faktor
produksi yang sifatnya tetap, karena tanah secara kualitas (tingkat kesuburan)
maupun kuantitas (kedalaman lapisan olah bahkan luasnya) selalu mengalami
degradasi. Kondisi seperti ini perlu dicermati, karena berpengaruh terhadap upaya
pengelolaan lahan untuk menjaga kesinambungan produksi atau menjaga
produktivitas lahan.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan, degradasi lahan yang
umumnya disebabkan oleh erosi memberikan dampak negatif yang nyata baik
pada lahan yang diolah (on site impact) maupun diluar lahan yang diolah (off site impact). Dampak yang terjadi baik yang bersifat in site maupun off site, memiliki konsekuensi biaya pengelolaan langsung maupun tidak langsung. Biaya-biaya
seperti ini biasanya tidak diperhitungkan, karena untuk menghitungnya
memerlukan pengetahuan teknis yang baik, terutama cara pengukurannya.
Munasinghe (1993) mengemukakan konsep dasar untuk penilaian
ekonomi lingkungan tentang nilai ekonomi total (total economic value). Konsep ini membagi nilai ekonomi total atas; (l) nilai guna (use value), dan (2) nilai bukan guna (non use value), nilai guna dibedakan lagi atas nilai guna langsung (direct use value), nilai guna tak langsung (indirect use value) dan nilai pilihan (option value). Penilaian ini dilakukan atas dasar keterukuran atau sesuatu yang nyata (tangible) secara individu.
Gambar 5 Pengelompokan atribut nilai ekonomi untuk penilaian lingkungan (Diadopsi dari Pearce 1992 dalam Munasinghe 1993)
Nilai Ekonomi Total
Nilai Guna Nilai Bukan Guna
Nilai Guna Langsung
Nilai Guna Tidak Langsung
Nilai Nilai Nilai Bukan
Pilihan Keberadaan Guna Lainnya
Output yang dapat dikonsumsi
langsung
Manfaat-manfaat fungsional
Nilai guna langsung dan tidak langsung
masa datang
Nilai dari pengetahuan
terhadap keberadaan
Makanan
Biomas
Rekreasi
Kesehatan
Fungsi Ekologi
Pengendali Banjir
Biodiversity
Konservasi habitat
Habitat
Spesies Langka
Secara matematik persamaan nilai ekonomi total (NET) adalah
NET = NG + NBG
NET = (NGL + NGTL + NP) + NBG
Dimana:
NET = Nilai Ekonomi Total
NG = Nilai Guna
NBG = Nilai Bukan Guna
NGL = Nilai Guna Langsung
NGTL = Nilai Guna Tidak Langsung
NP = Nilai Pilihan
Teknik penilaian ekonomi lingkungan walaupun baru, tetapi cukup
berkembang. Prinsip yang perlu dipahami adalah kesediaan membayar
(willingnessto pay) dari individu dalam memberikan penilaian. Hufschmidt (1987), mengelompokkan dalam tiga kategori yaitu (1) teknik yang langsung
didasarkan pada nilai pasar atau produktivitas, (2) teknik yang menggunakan nilai
pasar atau barang subtitusi, dan (3) pendekatan yang menggunakan teknik survey.
Dalam memberikan penilaian maka dianjurkan untuk pertama-tama harus
menggunaka nilai pasar. Bila tidak tersedian nilai pasar baru digunakan nilai pasar
barang subtitusi dan selanjutnya bila tidak nilai barang subtitusi baru
menggunakan nilai berdasarkan teknik survey. Dalam memberikan penilaian nilai
ekonomi, Munasinghe (1993) membuat taksonomi seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Taksonomi teknik penilaian yang relevan
Keterangan Pasar Pasar Implisit Pasar yang dibangun
Berdasarkan perilaku aktual
Efek produksi Efek kesehatan Biaya devensif Biaya preventif
Biaya perjalanan Perbedaan upah Nilai kepemilikan Barang pasar Pengganti
Pasar artifisial
Berdasarkan perilaku potensial
Biaya pengganti Proyek bayangan
Penilaian kontingensi lain-lain
Penggunaan teknik penilaian seperti dikemukakan dalam Tabel 2
disesuaikan dengan kebutuhan penilaian terhadap jasa lingkungan dan
sumberdaya alam yang ada. Penilaian ekonomi terhadap pengelolaan lahan yang
rusak akibat erosi dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian biaya
pengganti (Dixon dkk. 1993). Teknik ini digunakan bila manfaat sosial bersih
pemanfaatan tertentu tidak dapat diperkirakan secara langsung. Berdasarkan
penilaian teknik ini nilai barang atauj asa lingkungan adalah sebesar biaya yang
harus dikeluarkan untuk mengganti atau membuat barang atau jasa lingkungan
yang dapat memberikan manfaat setara dengan sebelumnya.
Analisis Pendapatan
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa walaupun
penerapan konservasi dapat dikatakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pertanian
berkelanjutan tetapi oleh petani hal itu dilihat sebagai suatu tambahan kerja yang
tidak memberikan tambahan pendapatan. Kondisi seperti ini dapat dipahami
karena selama ini petani selalu berada pada kondisi kesejahteraan yang kurang
menguntungkan. Pendapatan yang diperoleh dari usahatani hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan dasar, bahkan pada waktu-waktu tertentu mereka masih
dihadang oleh masa paceklik.
Kadariah dan Clive (1978) menyatakan bahwa analisis finansial penting
dalam memperhitungkan insentif, karena tidak ada gunanya melaksanakan suatu
kegiatan bila keuntungan hanya dilihat dari sudut perekonomian secara
keseluruhan tetapi petani yang menjalankan aktivitas produksi tidak bertambah
baik keadaannya. Kondisi marginalitas dan subsisten minded, merupakan suatu kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan petani masih memprihatinkan karena
aktivitasnya pada usahatani belum dapat memberikan kehidupan yang layak.
Sajogyo dalam Singarimbun (1978) membedakan tingkat pengeluaran penduduk atas miskin sekali dan miskin. Kategori miskin sekali bila pengeluaran
setara 180 kg/kapita bagi penduduk pedesaaan dan 270 kg/kapita bagi penduduk
perkotaan. Sedang yang tergolong miskin adalah bila tingkat pengeluaran rata-rata
320 kg/kapita bagi penduduk pedesaaan dan 480 kg/kapita bagi penduduk
berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori yaitu 2.100 kalori/kapita. Suatu
keluarga dianggap sangat miskin bila pendapatannya hanya mampu memenuhi
kebutuhan minimum kalori yang ditetapkan. Sedang bila pendapatan keluarga
selain bisa mencukupi kebutuhan minimum kalori dapat juga memenuhi
kebutuhan pokok seperti perumahan, air bersih, sandang dan pendidikan
dikategorikan sebagai keluarga miskin.
Dewasa ini Pemerintah menetapkan sistim upah minimum yang
didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tetap. Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1999
menyebutkan bahwa penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan
kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, perkembangan dan
kelangsungan perusahaan, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian
dan pendapatan perkapita. Sedang secara teknis penetapan masing-masing daerah
ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka melalui Keputusan
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 512 Tahun 2000, ditetapkan Upah
Minimum Propinsi sebesar Rp. 275.000,-/bulan atau Rp 3.300.000,-/tahun.
Jumlah pendapatan berdasarkan ukuran upah minimum ini nampak lebih
menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik disbanding dengan ukuran-ukuran
lainnya seperti disebutkan terdahulu. Dengan demikian bila kesejahteraan petani
akan ditingkatkan maka ukuran upah minimum sebaiknya yang dipergunakan
sebagai patokan dalam mendorong produksinya dalam konteks pertanian
berkelanjutan.
Analisis Investasi
Dalam pengelolaan lingkungan pertanian lahan kering, kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan pola tanam, penerapan teknik konservasi dan
penggunaan tenaga kerja perlu direncanakan secara matang untuk mendapatkan
pola penggunaan lahan dan produksi yang optimum. Ruslan, dkk (2002)
mengemukakan bahwa penggunaan lahan optimal baik secara fisik rnaupun sosial
ekonomi pada suatu wilayah seyogyanya diwujudkan secara dini, sebelum