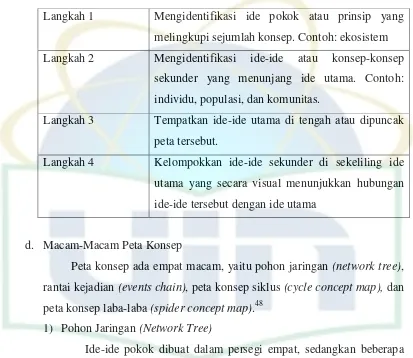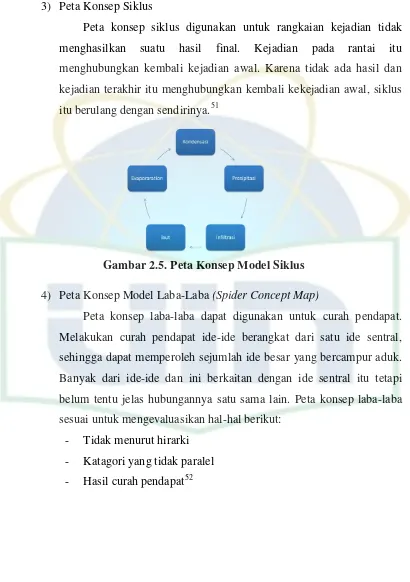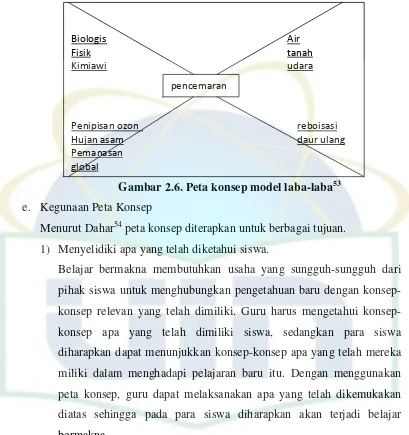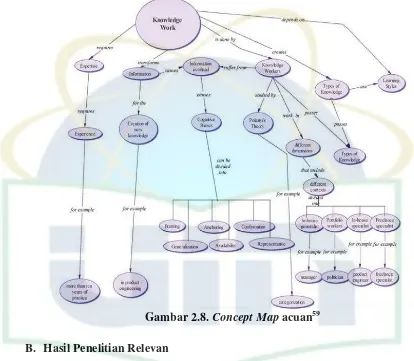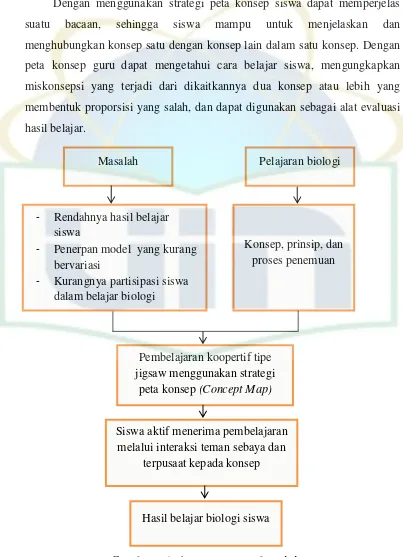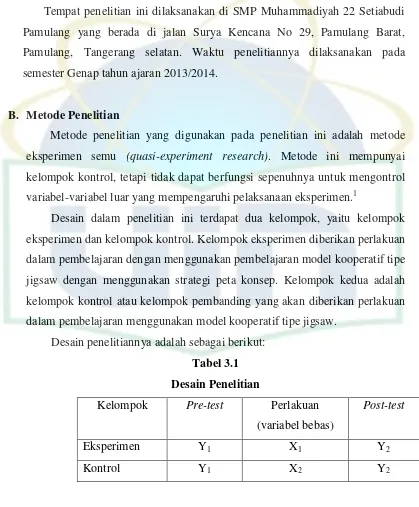PENGARUH PENGGUNAAN MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW MENGGUNAKAN STRATEGI PETA KONSEP (CONCEPT
MAP) TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Oleh Syifa Fauziah
NIM. 109016100073
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
ii
ABSTRAK
SYIFA FAUZIAH. Pengaruh Penggunaan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Menggunakan Strategi Peta Konsep (Concept Map) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Model Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw Menggunakan Strategi Peta Konsep (Koncept Map) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Februari -16 April 2014 di SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang. Metode penelitan yang digunakan adalah quasi eksperimen. Sampel terdiri dari 60 siswa kelas VIII yang diambil dari 2 kelas yang berbeda. Kelas pertama menjadi kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menggunakan strategi peta konsep (concept map) dan kelas kedua menjadi kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada konsep struktur dan fungsi tumbuhan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah istrumen tes pilihan ganda 4 alternatif jawaban sebanyak 20 soal. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara rata-rata kelas eksperimen 82,67 dan kelas kontrol 75. Dari hasil perhitungan uji “t”
(α = 0,05) didapatkan nilai thitung (2,51) > ttabel (1,6716) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa.
iii
Strategy Concept Map (Concept Map) to the result of student biology study This reseach aimed to know influence model cooperative learning type Jigsaw Using Concept Maps Strategy to the result of student biology study. This research has done on February 25th-April 16th 2014 in Junior high school Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang, on quasi experimental research methods with 60 student on 8th levels from two different class as the sample. The first class being an experimental wich has learn with cooperative learning type jigsaw using a strategy map concept (concept map) and the second class being on control wich has learn with cooperative learning jigsaw counsept structure and fungtion of plant. The instrument is use are multiple choice test with 4 alternative choices, with 20 questions. The results show there are the difference mean experimental class 82.67 and control class 75. The results from the calculations of "t" test (α = 0.05) obtained the score (2.51) > ttable (1.6716)
finally, it can be concluded that cooperative learning type jigsaw using strategy concept map can give a significant effect about result study of biologi
iv
KATA PENGANTAR bismillahirrahmannirrahim
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, karunia dan
Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Model Kooperatif Tipe Jigsaw
Menggunakan Strategi Peta Konsep (Concept Map) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S,Pd) pada jenjang Strata 1 (S1) di Program Studi
Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah
membantu sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini selesai.
1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Baiq Hana Susanti, M.Sc, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Yanti Herlanti M.Pd, selaku Ketua Program Studi pendidikan Biologi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak Dr. Sujiyo Miranto, M.Pd dan Ibu Nengsih Juanengsih M.Pd, selaku
pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan,
motivasi, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Bapak. Drs. Hudaefi, dan
Bapak Suswanto, S.Pd selaku guru Biologi kelas VIII, beserta dewan guru
dan staf yang telah bersedia bekerja sama dan memberi kesempatan penulis
untuk melaksanakan penelitian ini.
v
memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil dalam
penyusunan skripsi ini.
7. Sahabatku tersayang Reni Desriyani, Ria Mahardika, Eva Sofwatun Nida, dan
Nurul Husna yang memberikan semangat dan doa.
8. Adikku tersayang Ahmad Fauzi, yang memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang telah membantu yang tak dapat penulis sebutkan satu
persatu.
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca,
khususnya mahasiswa Program Studi pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 30 Mei 2016
vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ... i
ABSTRAK ... ii
KATA PENGANTAR ... iv
DAFTAR ISI ... ix
DAFTAR TABEL ... viii
DAFTAR GAMBAR ... x
DAFTAR LAMPIRAN ... xi
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Identifikasi Masalah ... 5
C. Pembatasan Masalah ... 5
D. Perumusan Masalah ... 5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 5
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS ... 7
A. Deskrisi Teoritik... 7
1. Hasil Belajar Dan Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar... 7
a. Hasil Belajar ... 7
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Dan Hasil Belajar 8 2. Hasil Belajar Sebagai Objek Penilaian ... 10
3. Model Pembelajaran Kooperatif ... 11
a. Pengertian, Karakteristik dan Prinsip Pembelajaran Kooperatif.11 4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw ... 15
a. Pengertian Jigsaw ... 15
b. Jenis Jigsaw dan Langkah-Langkah Pelaksanaanya ... 18
c. Kelebihan Model Jigsaw ... 21
5. Strategi Pembelajaran... 22
a. Pengertian Strategi... 22
b. Macam-Macam Strategi ... 23
6. Peta Konsep ... 23
a. Pengertian Peta Konsep (Concept Mapping) ... 23
vii
c. Menyusun Peta Konsep ... 26
d. Macam-Macam Peta Konsep ... 27
e. Kegunaan Peta Konsep ... 30
f. Peta Konsep Sebagai Alat Evaluasi ... 31
g. Rubrik Penilaian Peta Konsep ... 32
B. Hasil Penelitian Relevan ... 34
C. Kerangka Berpikir ... 37
D. Hipotesis Penelitian ... 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 40
A. Waktu dan Tempat ... 40
B. Metode Penelitian... 40
C. Populasi dan Sampel Penelitian ... 41
D. Variabel Penelitian ... 42
E. Teknik Pengumpulan Data ... 42
F. Instrumen Penelitian... 42
G. Kalibrasi Instrumen Penelitian ... 44
1. Validitas ... 44
2. Reliabilitas ... 45
3. Taraf kesukaran ... 45
4. Daya beda ... 46
H. Teknik Analisis Data ... 46
1. Pengujian prasyarat analisis ... 46
2. Uji Hipotesis ... 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 49
A. Hasil Penelitian ... 49
1. Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol... 49
2. Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 50
3. Deskripsi Data Hasil Observasi ... 50
4. Nilai Normal Gain (N-Gain) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.52 5. Nilai Hasil Peta Konsep dan Rangkuman ... 53
B. Pengujian Prasyarat Analisis ... 55
1. Uji Normalitas ... 55
2. Uji Homogenitas ... 56
3. Uji Hipotesis ... 57
C. Pembahasan ... 58
viii
A. Kesimpulan ... 63
B. Saran ... 63
DAFTAR PUSTAKA ... 64
ix
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Langkah-Langkah Dalam Membuat Peta Konsep ... 27
TABEL 3.1 Desain Penelitian ... 40
TABEL 3.2 Kisi-Kisi Instrumen ... 43
TABEL 4.1 Data Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan kontrol ... 49
TABEL 4.2 Data Hasil Postest Kelas Eksperimen dan Kontrol ... 50
TABEL 4.3 Rekapitulasi N-gain kelas Eksperimen dan Kelas kontrol ... 52
TABEL 4.4 Nilai Peta Konsep Pembahasan Jaringan Pada Tumbuhan ... 53
TABEL 4.5 Nilai Peta Konsep Pembahasan Organ Tumbuhan ... 53
TABEL 4.6 Nilai Peta Konsep Pembahasan Transportasi dan Adaptasi Pada Tumbuhan ... 54
TABEL 4.7 Nilai Rangkuman Pembahasan Jaringan Tumbuhan ... 54
TABEL 4.8 Nilai Rangkuman Pembahasan Organ Tumbuhan... 55
TABEL 4.9 Nilai Rangkuman Pembahasan Transportasi dan Adaptasi Tumbuhan. ... 55
TABEL 4.10 Hasil Uji Normalitas Pretest dan Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 56
TABEL 4.11 Hasil Uji Homogenistas Pretest dan Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol... 54
x
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1 Ilustrasi Kelompok Jigsaw ... 18
GAMBAR 2.2 Peta Konsep yang Memperlihatkan Konsep yang Berkaitan .. 25
GAMBAR 2.3 Peta Konsep Model Pohon Jaringan (Network Tree) ... 28
GAMBAR 2.4 Peta Konsep Model Rantai Kejadian ... 28
GAMBAR 2.5 Peta Konsep Model Siklus ... 29
GAMBAR 2.6 Peta Konsep Model Laba-Laba ... 30
GAMBAR 2.7 Penskoran Peta Konsep Menurut Novak dan Gowin ... 33
GAMBAR 2.8 Peta Konsep Acuan ... 34
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Protokol Wawancara Observasi ... 68
Lampiran 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian... 70
Lampiran 3 Rekap Analasis Butir ... 86
Lampiran 4 Instrumen Penelitian ... 88
Lampiran 5 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen . 91 Lampiran 6 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol ... 116
Lampiran 7 Data Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen ... 147
Lampiran 8 Data Pretest dan Posttest Kelas Kontrol ... 148
Lampiran 9 Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 149
Lampiran 10 Uji Homogenitas Pretest ... 153
Lampiran 11 Uji Hipotesis Pretest ... 154
Lampiran 12 Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 156
Lampiran 13 Uji Homogenitas Posttest ... 160
Lampiran 14 Uji Hipotesis Posttest ... 161
Lampiran 15 Nilai N-Gain Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen ... 163
Lampiran 16 Rekapitulasi Nilai Peta Konsep ... 166
Lampiran 17 Rekapitulasi Nilai Rangkuman ... 167
Lampiran 18 Lembar Observasi Kelas Eksperimen dan Kontrol ... 168
Lampiran 19 Lembar Ahli Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 192
Lampiran 20 Peta Konsep Siswa ... 232
Lampiran 21 Rangkuman Siswa ... 239
Lampiran 22 Rubrik Penilaian Rangkuman ... 250
Lampiran 23 Dokumentasi Foto Penelitian ... 272
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan seseorang.
Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat
yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Pendidikan dari segi kehidupan
dirasakan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Pendidikan
sudah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu.
Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1
Pendidikan melibatkan kemampuan pembelajaran untuk membentuk
hubungan-hubungan diantara berbagai gagasan, makna, dan peristiwa.
Pembelajaran secara eksperimental didasarkan pada hakikatnya merupakan
proses membangun relasi antara lingkungan (pengalaman) dan pikiran serta
tindakannya. Semua pengetahuan, pemikiran, dan pembelajaran dapat muncul
melalui pengalaman.2
Pendidikan, khususnya sekolah, harus memiliki sistem pembelajaran yang
menekankan pada proses dinamis yang didasarkan pada upaya meningkatkan
keingintahuan (curiosity) siswa tentang dunia. Pendidikan harus mendesain
pembelajaran yang responsif dan berpusat pada siswa agar minat dan aktivitas
sosial mereka terus meningkat.
Masalah utama dalam pendidikan formal dewasa ini adalah masih
rendahnya daya serap dan daya respon peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil
belajar peserta didik yang rendah. Proses pembelajaran di sekolah pada
1
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2
umumnya belum memperlihatkan sistem belajar mengajar yang mengajak
siswa untuk aktif dan bertindak melakukan penggalian potensi yang siswa
punya. Sikap yang demikian disebabkan karena model pembelajaran yang
kurang bervariasi, serta materi pelajaran yang relatif sukar. Hal ini secara
tidak langsung mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Keadaan ini
merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan
tidak mengajak siswa untuk bersikap lebih aktif dalam pembelajaran.
Pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada umumnya dengan cara
menceramahkan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan hukum-hukum dalam
bentuk yang sudah jadi kepada siswa. Guru menganggap pembelajaran
dengan cara ini sudah berhasil, tetapi sesungguhnya siswa belum belajar
secara aktif karena dalam pikiran siswa tidak terjadi perkembangan struktur
kognitif. Sehingga ada kecendrungan siswa kurang tertarik dengan mata
pelajaran tersebut.
Hasil observasi yang didapat di SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi
Pamulang. Terdapat 4 kelas VIII yang tediri dari kelas VIII-1, VIII-2, VIII-3
dan VIII-4. Diantara empat kelas tesebut ditemukan beberapa masalah seperti
hasil ulangan bilogi siswa rendah, kurangnya model yang variatif dalam
pembelajaran yang menyebabkan siswa menjadi bosan bahkan mengantuk
pada saat proses pembelajaran berlangsung. Metode yang digunakan oleh
guru masih berupa metode ceramah umum dan berkeliling sekolah tanpa
terarah, serta daya respon siswa kurang yang menyebabkan tingkat partisipasi
siswa dalam proses belajar mengajar pasif karena siswa hanya mendengarkan
pelajaran dari guru, dan siswa malas untuk membaca buku atau bahan lain
yang mendukung proses belajar mengajar. Konsep struktur dan fungsi
tumbuhan dianggap sulit pada subkonsep anatomi (struktur dalam) tumbuhan
dan proses transportasi tumbuhan. Karena itu, peneliti menggunakan konsep
struktur dan fungsi tumbuhan sebagai bahan penelitian.
Siswa banyak mengalami kesulitan dalam belajar dan memahami
konsep, mengingat struktur anatomi tumbuhan, fungsi-fungsinya, contoh, dan
3
materi yang perlu dihafal sehingga pembelajaran biologi kurang bermakna
bagi siswa.
Diperlukan model baru untuk meminimalisasi masalah-masalah
tersebut. Salah satunya adalah menggunakan model kooperatif tipe jigsaw.
Menurut Tiwan MT, Jigsaw adalah model kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling berketergantungan positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut pada anggota kelompok lain.3
Model kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa, dan
dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial siswa.
Siswa terlatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya, karena
dalam model jigsaw masing-masing siswa menjadi ahli dalam sub materi
yang telah diberikan oleh guru. Siswa terlatih untuk berinteraksi, dan mampu
menemukan gagasan atau ide baru. Siswa dapat membandingkan idenya
dengan orang lain. Efektifitas pembelajaran yang ditargetkan dalam satu
semester dapat cepat selesai karena dengan jigsaw materi dapat dibagi-bagi
perkelompok.
Hanya saja keaktifan siswa belum cukup, memperbaiki hasil belajar
biologi. Harus disertai peta konsep. Peta konsep menurut beberapa penelitian
Ahmad Ridwan,4 dan Ayu Arsyi Rahayu5 dapat memperbaiki hasil belajar.
Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana
sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada katagori
3 Tiwan MT, “
Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Pembelajaran Bahan Teknik Melalui Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw” Edukasi, 2008, h. 5
4
Ahmad Ridwan, “Pengaruh Pembelajaran Dengan Menggunakan Peta Konsep (Concept Map) Terhadap Hasil Belajar Biologi (Eksperimen Di Mts Tarbiyatusshibyan), Skripsi, Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2005, h. 26
5
yang sama.6 Peta konsep merupakan hubungan yang bermakna antara
konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi.7
Peta konsep dikembangkan untuk menggali struktur kognitif siswa dan
melihat apa yang telah diketahui oleh siswa. Peta konsep merupakan suatu
strategi yang dapat dilaksanakan dan dapat dikembangkan baik oleh siswa
secara bebas. Susuai dengan teori belajar Ausubel yang mendasari
pembentukan peta konsep yaitu, (a) struktur kognitif tersusun secara hirarki
dengan konsep dan proposisi yang lebih insklusif dan lebih khusus, (b)
konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif,
yaitu belajar bermakna merupakan proses yang kontinu dimana
konsep-konsep baru meningkat atau konsep-konsep-konsep-konsep baru dapat diperoleh dari
hubungan-hubungan baru. (c) penyesuaian integratif merupakan salah satu
prinsip belajar yang mengemukakan bahwa belajar bermakna meningkat bila
pelajar mengenal hubungan-hubungan baru antara konsep satu dengan yang
lainnya.8
Dengan menggunakan model kooperatif tipe jigsaw siswa akan lebih
aktif dalam proses pembelajaran dan dapat melatih tanggung jawab siswa
terhadap kelompoknya. Model kooperatif tipe jigsaw mempunyai kelemahan,
salah satunya adalah jika saat berdiskusi siswa tidak diarahkan dengan baik
maka diskusi itu akan melebar ke topik yang lain. Sehingga siswa tidak dapat
membuat pemahaman terhadap konsep-konsp yang didiskusikan. Siswa tidak
menemukan titik kesimpulan. Oleh karena itu untuk menutupi kelemahan
model jigsaw dibutuhkan strategi peta konsep yang berperan untuk
membangun pemahaman konsptual siswa sehingga mencapai hasil kognitif
yang tinggi dalam pembelajaran bermakna.
6
Trianto, Mendesain Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 158
7
Zulfiani, Strategi Pembelajaran Sains, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 29
8
5
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat
“Pengaruh Penggunaan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Menggunakan Strategi Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Bidang Studi Biologi Siswa SMP Muhammadiyah 22”
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam peneitian ini, antara lain:
1. Rendahnya hasil belajar biologi siswa di sekolah.
2. Penerapan model pembelajaran kurang bervariasi.
3. Kurangnya partisipasi dan respon siswa dalam pelajaran biologi.
C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Hasil belajar yang dilihat adalah aspek kognitif. Karena aspek kognitif
berkaitan erat dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan
pengajaran.
2. Penggunaan model yang digunakan adalah model kooperatif tipe jigsaw.
Karena model kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan jumlah
partisipasi siswa.
3. Penggunaan strategi penelitian adalah strategi peta konsep. Karena
strategi peta konsep dapat membantu pembelajaran lebih terfokus dan
terarah.
D. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: “Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menggunakan
strategi peta konsep terhadap hasil belajar biologi siswa?”
E. Tujuan dan Manfaat
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menggunakan strategi peta konsep
(concept map) terhadap hasil belajar biologi siswa.
1. Bagi pihak guru dapat dijadikan bahan masukan bagi tenaga pengajar
khusunya dalam meningkatkan proses pembelajaran biologi.
2. Bagi kepala sekolah Dapat dijadikan landasan kebijaksanaan untuk
menganjurkan media dan model ini kepada guru-guru sekolahnya,
7
BAB II
KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS A. Deskripsi Teoritik
1. Hasil Belajar dan Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
a. Hasil Belajar
Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product)
menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya sebuah aktivitas atau
proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil
produksi merupakan perolehan karena adanya proses perubahan bahan
(raw material) menjadi barang jadi (finished goods)1.
Hasil belajar menurut Sulihin merupakan kemampuan yang
diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat
memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman,
sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari
sebelumnya.2
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai pengertian,
sikap-sikap, apresiasi keterampilan. Hasil belajar berupa:
1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam
bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan.
2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep
dan lambang.
3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan
aktivitas kognitifnya sendiri.
4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian
gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud
otomatisme gerak jasmani.
1
Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. 3, h. 44
2
5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian terhadap objek tersebut.3
Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk
mengetahui seberapa jauh seorang menguasai bahan yang sudah
diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan
serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan
memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena
pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada
berbagai bidang termasuk pendidikan.
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar
Berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:4
1) Faktor lingkungan
Lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu:
Lingkungan alami, adalah lingkungan tempat peserta didik hidup
dan berusaha didalamnya.
Lingkungan sosial budaya, sebagai anggota masyarakat, anak
didik tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial
yang terbentuk mengikat perilaku anak didik.
2) Faktor instrumental
Instrumental-instrumental sekolah antara lain adalah:
Kurikulum, kurikulum adalah a plan of learning yang merupakan
unsur substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan
belajar mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi apa yang
harus guru sampaikan dalam suatu pertemuan kelas, belum guru
programkan sebelumnya.
Program, setiap sekolah mempunyai program pendidikan.
Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi kemajuan
3
Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5
4
9
pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari
baik tidaknya program pendidikan yang dirancang. Program
pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia,
baik tenaga, finansial, dan sarana prasarana
Sarana dan fasilitas, sarana mempunyai arti penting dalam
pendidikan. Gedung sekolah misalnya sebagai tempat yang
strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar
disekolah.
Guru, guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan.
Kehadiran guru mutlak diperlukan didalamnya. Kalau hanya ada
anak didik, tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan
belajar mengajar di sekolah.
3) Kondisi fisiologi
Kondisi fisiologi pada umunya sangat berpengaruh terhadap
kemampuan belajar seseorang. Hal yang tidak kalah pentingnya
adalah kondisi panca indra, terutama mata sebagai alat untuk melihat
dan telinga sebagai alat mendengar.5
4) Kondisi psikologis
Faktor-faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan
hasil belajar anak didik adalah:6
Minat, suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan
yang menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal
dari pada hal lainnya.
Kecerdasan, pendidikan yang berhasil karena menyelami jiwa anak didiknya.
Bakat, bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap
proses dan hasil belajar seseorang. Belajar pada bidang yang
sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan berhasilnya
5
Ibid, h. 189 6
usaha itu. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal yang menghalangi
untuk terciptanya kondisi yang sangat diinginkan oleh setiap
orang.
Motivasi, adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang
untuk melakukan sesuatu.
Kemampuan kognitif, merupakan kemampuan yang selalu
dituntut kepada anak didik untuk dikuasai. Karena penguasaan
kemampuan pada tingkatan ini menjadi dasar bagi penguasaan
ilmu pengetahuan.
2. Hasil Belajar Sebagai Objek Penilaian
Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh
mana tujuan yang ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain,
penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses
dan hasil belajar siswa.7
Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan pendidikan, baik
tujuan kulikuler maupun tujuan instruksional. Hasil belajar yang secara
garis besar terbagi menjadi tiga ranah, yaitu8:
a. Ranah kongnitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan,
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek
pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek
berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.
b. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,
yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan
internalisasi.
c. Ranah psikomotoris, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan
dan kempuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni
7
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 22
11
(a) gerakan reflex, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan
perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan
keterampilan kompleks, (f) gerakan ekspresif dan interpretatif.
Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar.
Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai
oleh para guru disekolah karena berkaitan dengan kempuan siswa dalam
menguasai isi bahan pengajaran.
3. Model Pembelajaran Kooperatif
a. Pengertian, Karakteristik dan Prinsip Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk
pembelajaran dengan cara belajar dan bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotannya terdiri dari empat
sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.9
Pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing proses antara
peserta belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama
diantara peserta belajar itu sendiri.10 Dalam pembelajaran ini akan
tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi
yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa
dengan guru. Miftahul Huda11 menyatakan:
pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang ada didalamnya, setiap pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.
Cooperative learning menurut merupakan model pembelajaran
yang sistematis dengan mengelompokkan siswa untuk tujuan
9
Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 202
10
Ibid., h. 203 11
menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif yang
mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademis.12
Pembelajaran kooperatif adalah cara belajar yang menggunakan
kelompok kecil sehingga siswa bekerja dan belajar satu sama lain. Untuk
mencapai tujuan kelompok didalam belajar kooperatif siswa berdiskusi
dan saling membantu serta mengajak satu sama lain untuk memahami isi
materi pelajaran.13
Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang
melibatkan siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang
heterogen dan bekerjasama dalam tugas akademik untuk mencapai tujuan
bersama.14 Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang
melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling
berinteraksi.15
Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang
mengelompokkan siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk saling
bekerja sama dalam mencapai pemahaman dalam suatu pembelajaran.
Dengan demikian, pembelajaran kooperatif bergantung pada efektivitas
kelompok-kelompok siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru
diharapkan mampu membentuk kelompok-kelompok kooperatif dengan
berhati-hati agar semua anggotanya dapat bekerja bersama-sama untuk
memaksimalkan pembelajarannya sendiri dan pembelajaran teman-teman
satu kelompoknya.
12
Zulfiani, Strategi Pembelajaran Sains, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 130
13
Ibid. 14
Ritawati Mahyuddin, Penggunaan Pendekatan Kooperatif Model Cooperative
Integrated Reading And Composition (CIRC) Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis
Ringkasan Mahasiswa PGSD FIP UNP, Edukasi, 2013, h. 76
15
13
Belajar secara kooperatif dalam kelompok kecil membantu siswa
dan anggota dalam tim untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama.
Secara umum pembelajaran kooperatif terdiri dari lima karakteristik,
yaitu:16
a) Siswa belajar bersama pada tugas-tugas umum atau aktivitas untuk
menyelesaikan tugas atau aktivitas pembelajaran.
b) Siswa saling bergantung secara positif. Aktivitas diatur sehingga
siswa membutuhkan siswa lain untuk mencapai hasil bersama.
Pembelajaran yang paling baik ditangani jika melalui kerja kelompok.
c) Siswa belajar bersama dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2
sampai 5 orang siswa.
d) Siswa menggunakan prilaku kooperatif, pro-sosial
e) Setiap siswa secara mandiri bertanggungjawab untuk pekerjaan
mereka.
Tidak semua kerja kelompok bisa dianggap Cooperative
Learning.17 Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur atau prinsip
model pembelajaran kooperatif harus diterapkan, yaitu:
a) Prinsip ketergantungan positif (Positive Interdependence), yaitu
keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat bergantung kepada
usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya, keberhasilan
tugas kelompok akan ditentukan oleh masing-masing anggota.
b) Tanggungjawab perseorangan (Individual Accountability), yaitu
keberhasilan kelompok tergantung anggota kelompoknya, maka setiap
anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan
tugasnya.
c) Interaksi tatap muka (Face To Face Promotion Interaction), yaitu
memberikan ruang dan kesempatan luas kepada setiap anggota untuk
16
Zulfiani, op. cit., h. 131 17
bertatap muka saling memberikan informasi dan saling
membelajarkan.
d) Partisipasi dan komunikasi antar anggota (Participation
Communication), yaitu pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk
dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi.
e) Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwal waktu khusus bagi
kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil
kerjasama siswa agar selanjutnya dapat bekerjasama dengan lebih
efektif.
Pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya mempelajari materi
pembelajaran. Siswa juga harus mempelajari keterampilan interpersonal
agar dapat bekerja sama secara produktif. Lundgren membagi
keterampilan kooperatif kooperatif menjadi tiga tingkatan, yaitu18:
a) Keterampilan kooperatif tingkat awal, meliputi berbagai tugas,
mendorong partisipasi dan mengundang orang lain untuk berbicara.
b) Keterampilan kooperatif tingkat menengah, meliputi mendengarkan
dengan aktif, bertanya, membuat ringkasan dan menerima tanggung
jawab.
c) Keterampilan kooperatif tingkat mahir, meliputi mengelaborasi,
memeriksa ketepatan dan menetapkan tujuan.
Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan
kerja dan tugas. Peran kerja dapat dibangun dengan mengembangkan
komunikasi antar anggota kelompok sedangkan peranan tugas dilakukan
dengan membagi tugas antar kelompok selama kegiatan.
Pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidaklah berjalan dengan
mulus meskipun rencana telah dirancang sedemikian rupa.
18
15
Hal-hal yang dapat menghambat proses pembelajaran terutama
Cooperative Learning diantaranya adalah sebagai berikut:19
a) Kurangnya pemahaman pembelajaran mengenai pembelajaran
kooperatif.
b) Jumlah peseta didik yang terlalu banyak yang mengakibatkan
perhatian pembelajar terhadap proses pembelajaran relatif kecil
sehingga yang hanya segelintir orang yang menguasai arena kelas,
yang lain hanya sebagai penonton.
c) Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang teknik pembelajaran
kooperatif.
d) Kurangnya buku sumber sebagai media pembelajaran.
e) Terbatasnya pengetahuan peserta didik akan system teknologi dan
informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran.
4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
a. Pengertian Jigsaw
Model ini pertama kali dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot
Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas.20 Metode ini
memiliki dua versi tambahan, jigsaw II yang dikembangkan oleh Slavin
dan jigsaw III yang dikembangkan oleh Kagan. Arti jigsaw dalam bahasa
inggris adalah gregaji ukir dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah
puzzle yaitu sebuah teka teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw ini mengambil pola cara kerja sebuah gregaji, yaitu
siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan
siswa lain untuk mencapai tujuan bersama.
Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta
didik terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain.
19
Martinis Yamin, Strategi & Metode Dalam Model Pembelajaran, (Jakarta: Referensi GP Press Grup), 2013, h. 95
20
Martinis Yamin mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif model
jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan cara peserta didik
saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara
kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan.21
Jigsaw adalah upaya siswa membentuk kelompok-kelompok kecil
untuk mencapai tujuan umum pembelajaran dengan cara memecahkan
masalah atau melakukan tugas dengan cara kerja kolektif.22
Tujuan jigsaw adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan
belajar kooperatif dan penguasaan pengetahuan secara mendalam yang
tidak mungkin diperoleh siswa apabila siswa mempelajari materi secara
individual.23 Jigsaw dikatakan dapat meningkatkan jumlah partisipasi
siswa karena a) siswa tidak tertekan karena belajar, b) meningkatkan
jumlah partisipasi siswa dalam kelas, c) mengurangi dominasi guru dalam
kelas.24
Pelajar dalam kelompok jigsaw dianggap sebagai ahli dalam aspek
tertentu dari topik-topik yang diteliti, dan diharapkan untuk berkontribusi
dalam memberikan pengetahuan yang tidak dimengerti anggota kelompok
lainnya.25 Pembelajaran model jigsaw ini dikenal juga dengan kooperatif
para ahli. Karena nggota setiap kelompok dihadapkan pada permasalahan
yang berbeda. Tetapi permasalahan yang dihadapi setiap kelompok sama,
setiap utusan dalam kelompok yang berbeda membahas materi yang
sama, disebut sebagai tim ahli yang bertugas membahas permasalahan
21
Yamin Op.Cit H. 92 22
Ali Gocer, A Comparative Research On The Effectivity Of Cooperative Learning Method and Jigsaw Technique On Teaching Literary Genres Jigsaw, Educational Research and Reviews Vol. 5, 2010, Pp. 441
23
Arya Widi Kristiani, Efektifitas Metode Jigsaw Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Pembelajaran Geografi, Jurnal Pendidikan Penabur. No 6, 2011, h. 57
24
Qiao Mengguo and Jin Xiaoling, Jigsaw Strategy As A Cooperative Learning Technique: Focusing On The Language Learners, Chines Journal Of Applied Linguistics (Bimonthly), Vol 33, No 4, 2010, Pp. 114
25
17
yang dihadapi, selanjutnya hasil pembahasan itu dibawa kekelompok asal
dan disampaikan kepada anggota kelompoknya.
Lie mengungkapkan dalam teknik jigsaw ini, guru memperhatikan
sekemata atau latar belakang pengalaman siswa agar bahan pelajaran
menjadi lebih bermakna.26
Metode jigsaw menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok
kecil yang terdiri dari 5 anggota. Setiap kelompok diberi informasi yang
membahas salah satu topik dari materi pelajaran siswa saat itu. Dari
informasi yang diberikan pada setiap kelompok ini, masing-masing
anggota harus mempelajari bagian-bagian yang berbeda dari informasi
tersebut. Misalnya jika kelompok A diminta mempelajari informasi
tentang novel, maka lima anggota kelompok didalamnya harus
mempelajari bagian-bagian yang lebih kecil dari novel, seperti tema, alur,
tokoh, konflik, dan latar.
Siswa mempelajari informasi tersebut dalam kelompoknya
masing-masing, kemudian setiap anggota yang mempelajari bagian-bagian ini
berkumpul dengan anggota-anggota dari kelompok-kelompok lain yang
juga menerima bagian-bagian materi yang sama. Jika anggota dalam
kelompok A mendapatkan tugas mempelajari alur, maka ia harus
berkumpul dengan siswa dalam kelompok B dan C yang membahas
bagian yang sama. Perkumpulan siswa yang memiliki bagian informasi yang sama dikenal dengan istilah “kelompok ahli (expert group)”. Dalam “kelompok ahli” ini, masing-masing siswa saling berdiskusi dan mencari cara terbaik bagaimana cara menjelaskan informasi itu kepada
teman-teman satu kelompoknya yang semula, dan masing-masing dari mereka
mulai menjelaskan bagian informasi tersebut kepada teman-teman satu
kelompoknya.27
26
Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), h. 69
27
Hubungan antara kelompok asli dan asal lihat gambar berikut:
Gambar 2.1. Ilustrasi Kelompok Jigsaw28
(tiap kelompok ahli memiliki satu anggota dari tim asal)
b. Jenis Jigsaw dan Langkah-Langkah Pelaksanaannya
1) Jigsaw I
Metode jigsaw ini mirip dengan jigsaw II dalam sebagian besar
aspeknya, tetapi juga mempunyai perbedaan penting. Dalam jigsaw I,
para siswa membaca bagian-bagian yang berbeda dengan yang dibaca
oleh teman satu timnya. Ini memang berguna untuk membantu para
ahli menguasai informasi yang unik, sehingga membuat tim sangat
menghargai kontribusi tiap anggotanya. Misalnya, dalam unit tentang
chile, satu siswa mungkin saja memiliki informasi tentang ekonomi
chile, satu siswa yang lain tentang geografinya, yang ketiga tentang
sejarahnya, dan seterusnya. Untuk mengetahui segala sesuatu tentang
chile, siswa harus bergantung kepada teman satu timnya. Jigsaw I juga
membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan jigsaw
II. Bacaannya singkat, hanya satu bagian dari seluruh unit yang harus
28
19
dipelajari. Bagian yang paling sulit dari jigsaw orisinil ini adalah tiap
bagain harus ditulis supaya dengan sendirinya dapat dipahami.29
Model jigsaw, siswa bekerja kelompok selama dua kali. Yakni
dalam kelompok sendiriasal siswa dan dalam “kelompok ahli”.
Setelah anggota menjelaskan bagiannya masing-masing kepada
teman-teman satu kelompoknya, mereka mulai bersiap untuk diuji
secara individu (biasanya dengan kuis). Guru memberikan kuis
kepada setiap anggota kelompok untuk dikerjakan sendiri-sendiri,
tanpa bantuan siapapun. Skor yang diperoleh setiap anggota dari hasil
ujian atau kuis inidividu ini akan menentukan skor yang diperoleh
kelompok masing-masing.30
Kegiatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini diatur secara
intruksional sebagai berikut:31
Membaca
Para siswa menerima topik ahli dan membaca meteri yang
diminta untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan
topik mereka.
Diskusi kelompok ahli
Para siswa dengan keahlian yang sama bertemu untuk
mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli.
Laporan tim
Para ahli kembali mereka masing-masing (kelompok asal) untuk
mengajari topik-topik mereka kepada teman satu timnya.
29
Slavin, Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik, Terj. Dari Cooperative Learning: Theory, Reserch And Practice Oleh Nurulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 245
30
Huda, Op. Cit, h. 121 31
Indah Budi Lestari, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Biologi Di MAN Babakan Lebaksiu Tegal,”
Tes
Setelah selesai menjelaskan pembelajaran, siswa harus
menunjukkan apa yang dipelajari selama bekerja kelompok
dengan menggunakan tes secara individual.
2) Jigsaw II
Metode jigsaw dikembangkan pertama kalinya oleh Aronson,
lalu Slavin mengadopsi dan memodifikasinya kembali. Hasil
modifikasi dikenal dengan metode jigsaw versi II. Jigsaw II dapat
digunakan apabila materi yang akan dipelajari adalah yang berbentuk
narasi tertulis. Metode ini paling sesuai untuk subjek-subjek seperti
pelajaran ilmu sosial, literatur, sebagian pelajaran ilmu pengetahuan
ilmiah, dan bidang-bidang lain yang tujuan pembelajaran lebih kepada
penguasaan konsep dari pada penguasaan kemampuan.32 Dalam metode ini, setiap kelompok “berkompetisi” untuk memperoleh penghargaan kelompok (group reward). Penghargaan ini diperoleh
berdasarkan performa individu masing-masing anggota. Setiap
kelompok akan memperoleh poin tambahan jika masing-masing
anggotanya mampu menunjukkan peningkatan performa
(dibandingkan sebelumnya) saat ditugaskan mengerjakan kuis.33
Teknis pelaksanaanaya hampir sama dengan jigsaw I, dalam
jigsaw II ini, para siswa bekerja dalam tim yang heterogen, seperti
dalam STAD dan TGT. Para siswa tersebut diberikan tugas untuk
membaca beberapa bab atau unit, dan diberikan “lembar ahli” yang
terdiri atas topik yang berbeda-beda yang harus menjadi fokus
perhatian masing-masing anggota tim saat membaca. Setelah semua
anak selesai membaca, siswa-siswa dari tim yang berbeda yang mempunyai fokus topik yang sama bertemu dalam “kelompok ahli” untuk mendiskusikan topik yang didapatkan siswa sekitar tiga puluh
menit. Para ahli tersebut kemudian kembali ke tim asal secara
32
Robert E Slavin, Student Team Learning: A Practical Guide To Cooperative Learning, (Washington DC: National Education Association Of The Unites States), 1991, Pp. 47
33
21
bergantian mengajari teman satu timnya mengenai topik yang
didiskusikan. Yang terakhir adalah para siswa menerima penilaian
yang mencakup seluruh topik, dan skor kuis yang menjadi skor tim,
skor-skor dikontribusikan para siswa kepada timnya didasarkan
kepada skor perkembangan individual, dan para siswa yang timnya
meraih skor tertinggi akan menerima sertifikat atau bentuk-bentuk
rekognisi tim lainnya. Sehingga, para siswa termotivasi mempelajari
materi dengan baik dan untuk bekerja kerasa dalam kelompok ahli
supaya dapat membantu timnya melakukan tugas dengan baik.34
3) Jigsaw III
Metode jigsaw yang ketiga ini dikembangkan oleh Kagan. Tidak
ada perbedaan yang menonjol antara JIG I, JIG II, dan JIG III dalam
tata laksana dan prosedurnya masing-masing. Hanya saja, dalam JIG
III, kagan lebih fokus pada penerapannya di kelas-kelas bilingual.
Kelas bilingual dapat dipahami sebagai kelas yang didalamnya
terdapat para pembelajar bahasa Inggris dari berbagai daerah dengan
level profiency yang berbeda-beda. Dalam kelas bilingual biasanya
terdapat 1) siswa-siswa yang mempelajari bahasa inggris sebagai
bahasa nasional, 2) siswa-siswa yang bahasa nasionalnya bukan
bahasa inggris, 3) siswa-siswa yang bahasa nasionalnya bukan bahasa
inggris namun mereka mahir berbahasa inggris. Karena diterapkan
dalam kelas bilingual, maka JIG III pada umumnya menggunakan
bahasa inggris untuk materi, bahan, lembar kerja, dan kuisnya.35
c. Kelebihan Model Jigsaw
Jhonson and jhonson melakukan penelitian tentang pembelajaran
kooperatif model jigsaw yang hasilnya menunjukkan bahwa interaksi
34
Slavin, op. cit., h. 237 35
kooperatif memiliki berbagai pengaruh positif terhadap perkembangan
anak.36 Pengaruh positif tersebut adalah:
1) Meningkatkan hasil belajar
2) Meningkatkan daya ingat
3) Dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi
4) Mendorong tumbuhnya motivasi instrinsik (kesadaran individu)
5) Meningkatkan hubungan antarmanusia yang heterogen
6) Meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah
7) Meningkatkan sikap positif terhadap guru
8) Meningkatkan harga diri anak
9) Meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif, dan
10) Meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong.
5. Strategi Pembelajaran
a. Pengertian Strategi
Strategi diartikan sebagai sebagai perencanaan yang berisi tentang
rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.37
Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan
guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan
efisien.38 Jadi strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam
proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan
guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar,
pengelolaan sumber belajar dan penilaian (asesmen) agar pembelajaran
36
Davi Sulaiman Putra, dan Sasmita Kristina Yuli Hartati, Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Chest Pass Pada Permainan Bola Basket, Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Volume 02, 2014, h. 528
37
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasikan Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana Media Grup), 2008, h. 126
38
Akhmad Sudrajat , Pengertian Pendekatan Strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model Pembelajaran, h. 2
23
lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan.39
b. Macam-Macam Strategi
Strategi belajar yang dapat digunakan dan diajarkan, yaitu:40
1) Strategi mengulang, yaitu mengulang pelajaran dan menghubungkan
informasi baru dengan pengetahuan awal.
2) Strategi Elaborasi (Elaboration Strategies), yaitu proses penambahan
rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna.
Strategi elaborasi membantu pemindahan informasi baru dari memori
jangka pendek ke memori jangka panjang dengan menggunakan
gabungan dan hubungan antara informasi baru dengan apa yang telah
diketahui. Dapat dilakukan dengan cara dengan pembuatan catatan,
analogi, dan PQ4R.
3) Strategi Organisasi (Organization Strategies), yaitu strategi yang
bertujuan untuk membantu pelajar meningkatkan kebermaknaan
bahan-bahan baru, terutama dilakukan dengan struktur-struktur
pengorganisasian baru pada bahan-bahan tersebut. Strategi organisasi
dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah
menjadi sub set yang lebih kecil seperti Outlining, mapping,
mnemonics yang meliputi pemotongan, akronim dan kata terkait.
6. Peta Konsep
a. Pengertian Peta Konsep (Concept Maping)
Peta konsep dikembangkan oleh guru besar Joseph D. Novack dari
Cornell universitas. Peta konsep adalah teknik yang secara visual
mewakili struktur informasi bagaimana konsep di dalam suatu daerah
saling berhubungan. Peta konsep ini didasarkan pada teori Ausubel yaitu
39
Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2011, h. 20
40
tentang pelajaran penuh makna yang menekankan bahwa belajar
pengetahuan baru adalah bergantung pada apa yang telah dikenal.41
Peta konsep adalah istilah yang dikenal dengan sebutan “consep mapping” atau “Pattern Noting” Pannen mengartikan peta konsep sebagai peta kognitif yang dapat memperlihatkan arti suatu konsep berdasarkan
proposisi konsep tersebut dengan konsep-konsep lain.42 Peta konsep
merupakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk
proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi merupakan dua atau lebih konsep
yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit semantik.43 Secara
sederhana peta konsep hanya terdiri atas dua konsep yang dihubungkan
oleh suatu kata penghubung untuk membentuk suatu proposisi. Misalnya “air diperlukan untuk makhluk hidup” akan merupakan suatu peta konsep yang sederhana sekali, terdiri atas dua konsep, yaitu air dan makhluk
hidup dihubungkan oleh kata diperlukan. Proposisi yang menyangkut konsep “makhluk hidup” dapat diperluas kembali arti ketelitiannya. Proposisi-proposisi itu antara lain adalah: makhluk hidup seperti
tumbuhan, makhluk hidup seperti hewan, makhluk hidup itu bernafas.
Maka, belajar bermakna lebih mudah jika konsep-konsep baru dikaitkan
pada konsep yang lebih inklusif, maka peta konsep harus disusun secara
hirarki. Konsep yang lebih inklusif ada di puncak. Makin kebawah
konsep-konsep diurutkan makin menjadi lebih khusus.
41
Eric Plotnick, Concept Mapping: A Graphical System For Understanding The Relationship Between, Eric Digests, 1997, h. 2
42
C.I. Yogihati, Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Fisika Umum Melalui Pembelajaran Bermakna Dengan Menggunakan Peta Konsep, Edukasi, 6, 2010, h. 105
43
25
Gambar 2.2 Peta konsep yang memperlihatkan konsep yang berkaitan44
b. Ciri-Ciri Peta Konsep
Pemahaman terhadap peta konsep dapat lebih jelas, maka Tianto,45
mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut:
1) Peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk
memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu studi,
apakah itu bidang fisika, kimia, biologi, matematika. Dengan
menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat bidang studi itu lebih
jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna.
2) Suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang
studi, atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat
memperlihatkan hubungan-hubungan proporsional antara
konsep-konsep.
3) Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada
konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep yang lain.
4) Bila dua atau lebih konsep digambarkan dibawah suatu konsep yang
lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep tersebut.
44
Zulfiani, Op. Cit, h. 30 45
Trianto, Op.Cit, h. 159
Makhluk hidup
tumbuhan hewan
air
molekul
gerak
panas
padat
hewan
gas cair
dapat dapat
mengandung mengandung
Dalam keadaan
Meningkat karena
beruba
dapat dapat
Ciri-ciri tersebut di atas menunjukkan sebaiknya peta konsep disusun
secara hirarki, artinya konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak
peta, makin ke bawah konsep-konsep diurutkan menjadi konsep yang
kurang inklusif. Dalam IPA peta konsep membuat informasi abstrak
menjadi konkret dan sangat bermanfaat meningkatkan ingatan suatu
konsep pembelajaran, dan menunjukkan pada siswa bahwa pemikiran itu
mempunyai bentuk.
c. Menyusun Peta Konsep
Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu sajian
visual atau suatu diagram tentang ide-ide penting atau suatu topik tertentu
dihubungkan satu sama lain. Peta konsep mirip peta jalan, namun peta
konsep menaruh perhatian pada hubungan antara ide-ide, bukan hubungan
antar tempat.
Terdapat beberapa langkah penyusunan peta konsep, yaitu:46
1) Pilihlah satu bacaan dari buku pelajaran
2) Tentukan konsep-konsep yang relevan
3) Urutkan konsep-konsep itu dari yang paling tidak inklusif atau
contoh-contoh.
4) Susunlah konsep-konsep itu di atas kertas, mulai dengan konsep yang
paling inklusif di puncak ke konsep yang paling tidak inklusif.
5) Hubungkanlah konsep-konsep itu dengan kata atau kata-kata
penghubung.
46
27
Trianto memberikan langkah-langkah dalam pembuatan peta konsep
sebagai berikut:
Tabel 2.1 . Langkah-langkah dalam membuat peta konsep47
Langkah 1 Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang
melingkupi sejumlah konsep. Contoh: ekosistem
Langkah 2 Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep
sekunder yang menunjang ide utama. Contoh:
individu, populasi, dan komunitas.
Langkah 3 Tempatkan ide-ide utama di tengah atau dipuncak
peta tersebut.
Langkah 4 Kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide
utama yang secara visual menunjukkan hubungan
ide-ide tersebut dengan ide utama
d. Macam-Macam Peta Konsep
Peta konsep ada empat macam, yaitu pohon jaringan (network tree),
rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept map), dan
peta konsep laba-laba (spider concept map).48
1) Pohon Jaringan (Network Tree)
Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa
kata yang lain ditulis pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada
peta konsep menunjukkan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang
ditulis pada garis memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pohon
jaringan sesuai digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:
- Menunjukkan sebab akibat
- Suatu hirarki
- Prosedur yang bercabang
47
Trianto, Op. Cit, h. 160
48
- Istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk
menjelaskan hubungan-hubungan49
G
ambar 2.3. Peta konsep model pohon jaringan (network tree) 2) Rantai Kejadian (Event Chain)
Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan
suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau
tahap-tahap dalam suatu proses. Rantai kejadian sesuai digunakan
untuk memvisualisasikan hal-hal:
- Memberikan tahapan-tahapan suatu proses,
- Langkah-langkah dalam suatu prosedur,
- Suatu urutan kejadian50.
Gambar 2.4. Peta konsep model rantai kejadian (events chain)
49
Ibid 50
29
3) Peta Konsep Siklus
Peta konsep siklus digunakan untuk rangkaian kejadian tidak
menghasilkan suatu hasil final. Kejadian pada rantai itu
menghubungkan kembali kejadian awal. Karena tidak ada hasil dan
kejadian terakhir itu menghubungkan kembali kekejadian awal, siklus
itu berulang dengan sendirinya.51
Gambar 2.5. Peta Konsep Model Siklus
4) Peta Konsep Model Laba-Laba (Spider Concept Map)
Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat.
Melakukan curah pendapat ide-ide berangkat dari satu ide sentral,
sehingga dapat memperoleh sejumlah ide besar yang bercampur aduk.
Banyak dari ide-ide dan ini berkaitan dengan ide sentral itu tetapi
belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. Peta konsep laba-laba
sesuai untuk mengevaluasikan hal-hal berikut:
- Tidak menurut hirarki
- Katagori yang tidak paralel
- Hasil curah pendapat52
51
Trianto Op. Cit, h. 163
Gambar 2.6. Peta konsep model laba-laba53
e. Kegunaan Peta Konsep
Menurut Dahar54 peta konsep diterapkan untuk berbagai tujuan.
1) Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa.
Belajar bermakna membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari
pihak siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan
konsep relevan yang telah dimiliki. Guru harus mengetahui
konsep-konsep apa yang telah dimiliki siswa, sedangkan para siswa
diharapkan dapat menunjukkan konsep-konsep apa yang telah mereka
miliki dalam menghadapi pelajaran baru itu. Dengan menggunakan
peta konsep, guru dapat melaksanakan apa yang telah dikemukakan
diatas sehingga pada para siswa diharapkan akan terjadi belajar
bermakna.
2) Mempelajari Cara Belajar
Dengan membuat peta konsep untuk mengambil sari dari apa yang
mereka baca, baik buku teks maupun bacaan-bacaan lain, berarti
meminta mereka membaca buku dengan seksama. Mereka tidak dapat
dikatakan tidak berpikir. Untuk mengeluarkan konsep-konsep,
kemudian menghubungkan konsep-konsep itu dengan kata
53
Ibid, h. 164 54
Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 110
Biologis Air
Fisik tanah
Kimiawi udara
Penipisan ozon reboisasi
Hujan asam daur ulang
Pemanasan global
31
penghubung menjadi proporsi-proporsi yang bermakna, bukanlah
tugas yang sambil lalu dapat dilakukan.
3) Mengungkapkan Miskonsepsi
Dari peta konsep yang dibuat, ada kalanya ditemukan miskonsepsi
yang terjadi dari dikaitkannya dua konsep atau lebih yang membentuk
proporsi yang salah.
f. Peta Konsep Sebagai Alat Evaluasi
Peta konsep digunakan untuk menilai hubungan antara pemahaman
konseptual dan penggunaan strategi untuk siswa biologi.55 Peta konsep
dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum guru
mengajarkan topik, menolong siswa bagaimana belajar, untuk
mengungkapkan konsepsi salah (miskonsepsi) yang ada pada anak, dan
sebagai alat evaluasi. Menurut Trianto,56 peta konsep sebagai alat evaluasi
didasarkan atas tiga prinsip dalam teori Ausubel, yaitu:
1) Struktur kognitif diatur secara hirarki dengan konsep-konsep dan
proposisi-proposisi yang lebih inklusif, lebih umum, super koordinat
terhadap konsep-konsep, dan proposisi-proposisi yang kurang inklusif
dan lebih khusus.
2) Konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi
progresif. Prinsip ini menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan
proses yang kontinu, dimana konsep-konsep baru memperoleh lebih
banyak arti dengan dibentuk lebih banyak kaitan-kaitan proporsional.
Jadi konsep-konsep tidak pernah tuntas dipelajari, tetapi selalu
dipelajari, dimodifikasi, dan dibuat lebih inklusif.
3) Prinsip penyesuaian integratif menyatakan bahwa belajar bermakna
akan meningkat bila siswa menyadari akan perlunya kaitan-kaitan baru
antara segmen-segmen konsep atau proposisi. Dalam peta konsep
55
John R Mcclure, Brian Sonak, Hoi K. Suen, Concept Map Assasement Of Classroom Learning: Reliability, Validity, and Logistical Practicality, Journal Of Research In Science Teaching Vol 36, 1999, h. 2
56
penyesuaian integratif ini diperlihatkan dengan kaitan-kaitan silang
antara segmen-segmen konsep.
Peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman suatu bacaan,
sehingga dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa
untuk membaca peta konsep dan menjelaskan hubungan antara konsep
satu dengan konsep lain dalam satu konsep.
g. Rubrik Penilaian Peta Konsep
Rubrik adalah alat yang digunakan untuk menilai keriteria yang
kompleks dan subjektif, yang diartikulasikan dengan kriteria dan standar
yang akan digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan siswa. Rubrik dapat
membantu membuat kriteria penilaian yang transparan. Kriteria penilaian
peta konsep adalah:
1) Proposisi adalah hubungan dua konsep yang dihubungkan oleh kata
penghubung. Proposisi dikatakan sahih jika menggunakan kata
penghubung yang tepat. Untuk setiap proporsisi yang sahih diberi skor
1.
2) Hirarki adalah tingkatan dari konsep yang paling umum sampai
konsep yang lebih umum dituliskan di atas dan konsep yang lebih
khusus dituliskan di bawahnya. Hirarki dikatakan sahih jika urutan
penempatan konsepnya benar. Untuk setiap hirarki yang yang sahih
diberi skor 5.
3) Kaitan silang adalah hubungan yang bermakna antara suatu konsep
pada suatu hirarki dengan konsep lain pada hirarki yang lainnya.
Kaitan silang dikatakan sahih jika menggunakan kata penghubung
yang tepat dalam menghubungkan dua konsep pada hirarki yang
berbeda. Sementara itu, kaitan silang dikatakan kurang sahih jika tidak
menggunakan kata penghubung yang tepat dalam menghubungkan
kedua konsep sehingga antara kedua konsep tersebut menjadi kurang
jelas. Untuk setiap kaitan silang yang sahih diberi skor 10. Sedangkan
33
4) Contoh adalah kejadian atau objek yang spesifik yang sesuai dengan
atribut konsep. Contoh dikatakan sahih jika contoh tersebut tidak
dituliskan di dalam kotak. Contoh bukanlah konsep untuk setiap
contoh yang sahih diberi skor 1.57
G
G
Gambar 2.7 penskoran peta konsep menurut novak dan gowin58
57
Zahrotul Hayati, “Perbandingan Hasil Belajar Antara Siswa Yang Diajar Dengan
Pembelajaran Konstruktivisme Teknik Mind Map dan Concept Map,”Skripsi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2012, h, 24, tidak dipublikasikan
58
Concept map yang dijadikan acuan pembelajaran dikelas
adalah sebagai berikut.
G
G a
Gambar 2.8. Concept Map acuan59 B. Hasil Penelitian Relevan
1. Mareta Dwi Satuti, yang berjudul pengaruh pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw terhadap hasil belajar kimia siswa. Penelitian tersebut bertujuan
untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar kimia siswa. Metode
penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan sampel
diambil dari 2 kelas berbeda. Instrumen penelitian tersebut berupa tes
objektif. Analisis penelitian menggunakan uji-t, didapatkan nilai t hitung
= 4,47 dan nilai t tabel = 1,999. Dapat disimpulkan bahwa model
59