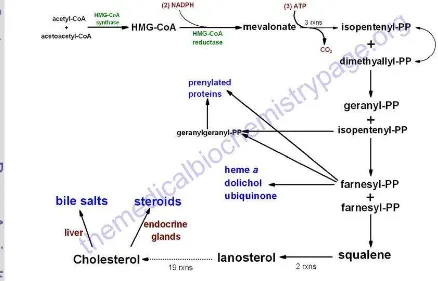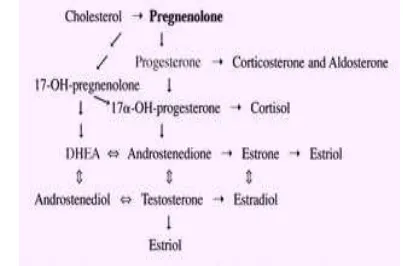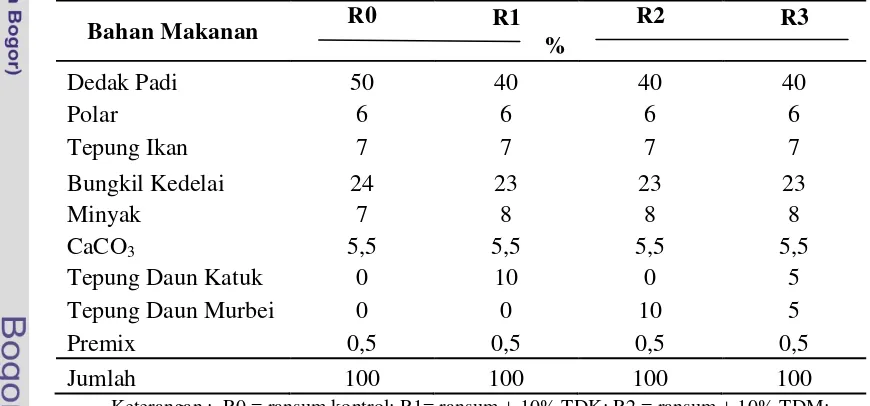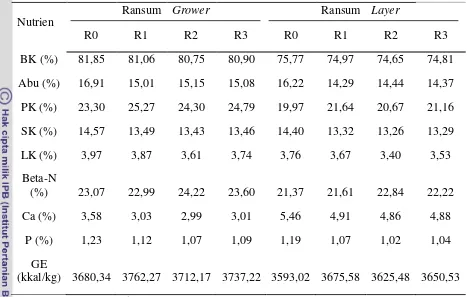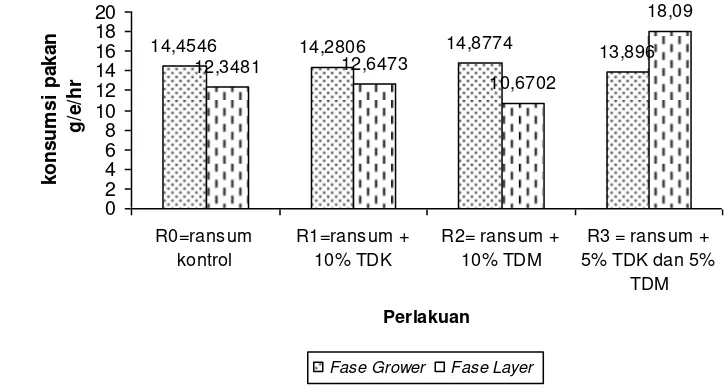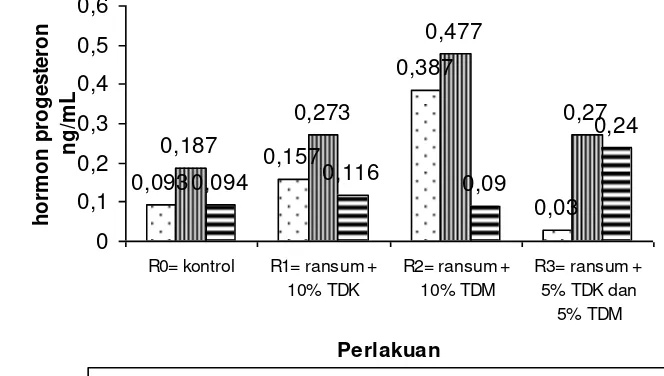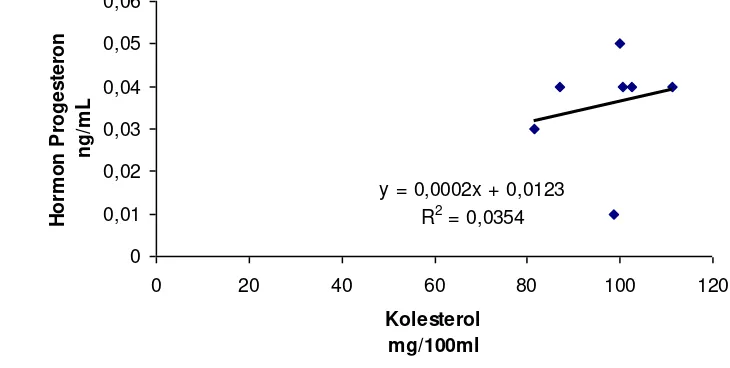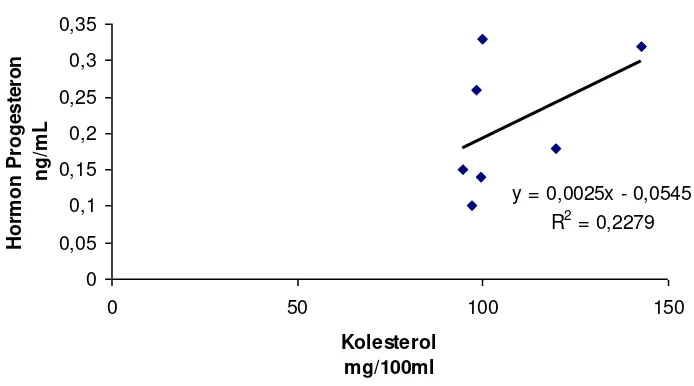PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN KATUK (Sauropus
androgynus) DAN MURBEI (Morus sp.) TERHADAP SERUM
KOLESTEROL DAN HORMON PROGESTERON
PADA PUYUH
SKRIPSI AAN
DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN
RINGKASAN
AAN. D24070188. 2011. Pengaruh Pemberian Tepung Daun Katuk (Sauropus androgynus) dan Murbei (Morus sp.) terhadap Serum Kolesterol dan Hormon Progesteron Pada Puyuh. Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
Pembimbing Utama : Ir. Widya Hermana, M.Si.
Pembimbing Anggota : Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS.
Pakan sangat dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan hidup ternak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian berbagai sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi sumber bahan pakan, antara lain yang berasal dari tanaman. Sumber bahan pakan alternatif yang mengandung nilai gizi tinggi dan keberadaannya sudah sejak lama dikenal masyarakat luas adalah daun katuk dan daun murbei. Daun katuk dan daun murbei dalam bentuk tepung dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang mengandung tepung daun katuk dan murbei terhadap konsentrasi kolesterol dan hormon progesteron pada burung puyuh yang dapat meningkatkan fungsi hormon reproduksi.
Penelitian ini menggunakan 36 ekor puyuh betina fase grower umur 7 minggu dan dilanjutkan hingga fase layer umur 11 minggu (Cortunix cortunix japonica) yang dialokasikan ke dalam 4 perlakuan dengan 3 ulangan dan setiap ulangan terdiri atas 3 ekor puyuh. Perlakuannya adalah ransum R0 : ransum kontrol, tanpa tepung daun katuk dan tepung daun murbei, ransum R1 : ransum yang mengandung 10% tepung daun katuk (TDK), ransum R2 : ransum yang mengandung 10% tepung daun murbei (TDM), ransum R3 : ransum yang mengandung 5% tepung daun katuk (TDK) dan 5% tepung daun murbei (TDM). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan sidik ragam ANOVA dan jika berbeda nyata maka, diuji lanjut dengan uji jarak Duncan.
Berdasarkan hasil sidik ragam, pemberian tepung daun katuk dan tepung daun murbei pada ransum sampai dengan dosis 10% tidak nyata mempengaruhi kadar kolesterol dan hormon progesteron serum pada seluruh perlakuan. Korelasi kolesterol dan hormon progesteron pada fase grower memiliki hubungan y = 0.0002x + 0.0123 dan R2 = 0.0354. Korelasi kolesterol dan hormon progesteron pada fase layer memiliki hubungan y = 0.0025x - 0.0545 dan R2 = 0.2279 yang berarti ada hubungan antara kolesterol dan hormon progesteron. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian tepung daun katuk dan tepung daun murbei pada ransum tidak berpengaruh terhadap kadar kolesterol dan konsentrasi hormon progesteron pada burung puyuh. Pemberian campuran tepung daun katuk dan tepung daun murbei cenderung lebih baik dibandingkan pemberian secara tunggal.
ABSTRACT
The Effect of Using Katuk Leaves Meal (Sauropus androgynus) and Mulberry Leaves Meal (Morus sp.) on Cholesterol and Progesterone Serum in Japanese Quails
Aan, W. Hermana, and D. A. Astuti
Sauropus androgynus leaves meal and mulberry leaves meal are considered as herbal medicine. Sauropus androgynus could improve the milk production in human as well as in animals. It could increase the egg production as well as poultry performances. It had been proved to increase vitamin A content in chicken liver and in the egg yolk. Some previous studies reported that mulberry leaves, from some different species, contain 15.7-22.6% crude protein and some pro-vitamin A. This research was focused on comparing the benefit of two herbal leaves and its combination on Japanese quails including the status of serum cholesterol and progesteron hormone. Thirty six of Japanese quails before and until laying periods were divided into 4 treatments with 3 replications and 3 quails in each replicate. Four treatment diets were formulated, i.e. : control diet without leaves (R0), diet with 10% katuk leaves meal (R1), diet with 10% mulberry leaves meal (R2), and diet with 5% katuk leaves and 5% mulberry leaves meal (R3). The treatments were given from 3 weeks up to 12 weeks old of japanese quails. The parameter observed were the cholesterol and progesterone hormone content in serum. All data were collected and analyzed statistically using a completely randomized design by ANOVA. Result showed that combination katuk leaves meal and mulberry leaves meal in the ration were not significantly effected on cholesterol and progesterone serum in japanese quails.
PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN KATUK (Sauropus
androgynus) DAN MURBEI (Morus sp.) TERHADAP SERUM
KOLESTEROL DAN HORMON PROGESTERON
PADA PUYUH
AAN D24070188
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN
Judul : Pengaruh Pemberian Tepung Daun Katuk (Sauropus androgynus) dan Murbei (Morus sp.) terhadap Serum Kolesterol dan Hormon Progesteron Pada Puyuh
Nama : Aan
NIM : D24070188
Menyetujui,
Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,
(Ir. Widya Hermana, M.Si) (Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS) NIP. 19680110 199203 2 001 NIP. 19611005 198503 2 001
Mengetahui, Ketua Departemen
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan,
(Dr. Ir. Idat Galih Permana, MSc.Agr.) NIP. 19670506 199103 1 001
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1989 di Tangerang, Banten sebagai anak
kedua, dari pasangan Bapak Isupardi dan Ibu Lian Wha.
Pendidikan formal pertama dimulai pada tahun 1995 di Sekolah Dasar Yunike
Andreas Kota Tangerang, lulus pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis
melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Strada Santa Maria 2 Kota Tangerang, dan
lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 7 Kota Tangerang, lulus pada tahun 2007. Penulis diterima sebagai mahasiswa
IPB pada tahun 2007 melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) dan pada tahun
2008 diterima di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan,
Institut Pertanian Bogor.
Selama masa perkuliahan, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa PMK
(Persekutuan Mahasiswa Kristen) IPB, Keluarga Mahasiswa Banten sebagai anggota,
sebagai asisten dosen mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan Tingkat
Persiapan Bersama tahun 2009 dan 2010, serta asisten praktikum mata kuliah Integrasi
Proses Nutrisi tahun 2011. Penulis pernah melaksanakan kegiatan magang selama satu
bulan di PT. Charoen Pokphand, Balaraja, Tangerang, Banten di bagian quality control
pada bulan Juni 2009. Penulis berkesempatan menjadi penerima beasiswa Eka Tjipta
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkat-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah, penelitian, dan penyusunan tugas akhir
dengan lancar.
Skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Tepung Daun Katuk (Sauropus androgynus) dan Murbei (Morus sp.) terhadap Serum Kolesterol dan Hormon Progesteron Pada Puyuh ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bulan Desember 2010 hingga Januari 2011 di Laboratorium Terpadu, Fakultas
Peternakan, Institut Pertanian Bogor dan Laboratorium Mandapa di Bogor. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang mengandung tepung daun
katuk dan murbei terhadap konsentrasi kolesterol dan hormon progesteron pada burung
puyuh yang dapat meningkatkan fungsi hormon reproduksi.
Pakan sangat dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan hidup ternak. Oleh karena
itu, perlu dilakukan kajian sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi sumber
bahan pakan, antara lain yang berasal dari tanaman. Sumber bahan pakan alternatif yang
mengandung nilai gizi tinggi dan keberadaannya sudah sejak lama dikenal masyarakat
luas adalah daun katuk dan daun murbei. Daun katuk dikenal sebagai sumber provitamin
A dalam bentuk karoten. Daun murbei merupakan tanaman lokal yang memiliki potensi
tinggi jika digunakan sebagai pakan ternak karena dapat tumbuh pada lokasi dengan
variasi suhu, pH tanah, dan ketinggian. Penggunaan tepung daun katuk dan murbei serta
kombinasinya dalam ransum puyuh digunakan karena adanya senyawa yang berperan
penting dalam biosintesis hormon steroid. Senyawa tersebut dapat meningkatkan fungsi
hormon reproduksi pada burung puyuh.
Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, kesalahan berasal dari penulis.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.
Bogor, April 2011
Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan Kolesterol... 19
Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsentrasi Hormon Progesteron... 22
KESIMPULAN DAN SARAN... 26
Kesimpulan... 26
Saran... 26
UCAPAN TERIMAKASIH... 27
DAFTAR PUSTAKA... 28
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1. Susunan Ransum Puyuh Grower... 15
2. Susunan Ransum Puyuh Layer... 15
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1. Tanaman Katuk... 3
2. Tanaman Murbei... 6
3. Mekanisme Sintesis Kolesterol... 9
4. Mekanisme Sintesis Hormon Progesteron ... 11
5. Rataan Konsumsi Pakan Puyuh... 19
6. Hasil Rata-Rata Pengukuran Kolesterol Serum Darah Puyuh... 20
7. Hasil Rata-Rata Pengukuran Hormon Progesteron Serum Darah Puyuh 22
8. Korelasi Kolesterol dan Hormon Progesteron Fase Grower... 23
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. ANOVA ( Analysis of Variance ) Rataan Kadar Kolesterol Fase 32 Grower...
2. ANOVA ( Analysis of Variance ) Rataan Kadar Kolesterol Fase 32 Layer...
3. ANOVA ( Analysis of Variance ) Selisih Kadar Kolesterol Fase 32 Grower dan Fase Layer...
4. ANOVA ( Analysis of Variance ) Rataan Konsentrasi Hormon 33 Progesteron Fase Grower...
5. ANOVA ( Analysis of Variance ) Rataan Konsentrasi Hormon 33 Progesteron Fase Layer...
PENDAHULUAN Latar Belakang
Pakan sangat dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan hidup ternak. Oleh karena
itu, perlu dilakukan kajian sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi sumber
bahan pakan, antara lain yang berasal dari tanaman. Sumber bahan pakan alternatif yang
memiliki nilai gizi tinggi dan keberadaannya sudah sejak lama dikenal masyarakat luas
adalah daun katuk dan daun murbei.
Daun katuk memiliki kandungan protein 6,4 g, lemak 1,0 g, kalsium 233 mg, fosfor
98 mg, besi 3,5 mg, vitamin A, B, dan C 164 mg, steroid, flavonoid, dan polifenol. Daun
katuk memiliki senyawa aktif androstan – 17 – one, 3 – ethyl – 3 – hydroxy – 5 alpha
yang dapat meningkatkan hormon progesteron di dalam darah, sehingga dapat
meningkatkan produksi telur pada puyuh.
Daun murbei mengandung protein15,71 – 22,59 %, lemak 3,70 – 6,15 %, dan serat
kasar 8 – 16,8 %. Daun murbei merupakan tanaman lokal yang memiliki potensi tinggi
jika digunakan sebagai pakan ternak karena dapat tumbuh pada lokasi dengan variasi
suhu, pH tanah, dan ketinggian. Pohon murbei dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis
sehingga cocok untuk dibudidayakan di seluruh Indonesia. Daun murbei juga memiliki
senyawa steroid yang dapat meningkatkan fungsi hormon reproduksi.
Puyuh merupakan salah satu unggas yang berpotensi untuk dibudidayakan di
kalangan masyarakat Indonesia. Puyuh memiliki dua manfaat, yaitu daging dan telurnya
dapat dimanfaatkan. Selain itu, di dalam pemeliharaan puyuh tidak membutuhkan
kandang yang luas dan biaya pemeliharaanya relatif kecil. Puyuh mulai bertelur pada
umur 5 sampai 6 minggu, oleh karena itu perlunya senyawa steroid yang dapat
meningkatkan sintesis kolesterol untuk menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah
yang banyak sehingga, produksi telur dapat meningkat.
Permasalahannya, belum banyak penelitian mengenai kombinasi pemberian herbal
yang ditentukan untuk mengevaluasi status hormonal yang dihubungkan dengan hormon
progesteron yang mencerminkan kesiapan produksi telur. Hal tersebut mendorong untuk
mengkaji mengenai pengaruh tepung daun katuk dan daun murbei terhadap fungsi
memiliki senyawa steroid yang dapat memacu ovulasi, sehingga dapat meningkatkan
produksi telur pada puyuh.
Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang
mengandung tepung daun katuk dan murbei terhadap konsentrasi kolesterol dan hormon
progesteron pada burung puyuh yang dapat meningkatkan fungsi hormon reproduksi.
TINJAUAN PUSTAKA
Katuk (Sauropus androgynus L. Merr)
Bahasa lokal tanaman katuk (Sauropus androgynus L. Merr) dikenal dengan nama
katuk (Sunda, Melayu), babing atau katukan (Jawa), simanis (Minangkabau), kerakur
(Madura) (Subekti, 2007).
Gambar 1. Tanaman Katuk
Menurut Yuliani dan Marwati (1997), daun katuk dikenal sebagai sumber vitamin
A dalam bentuk karoten (provitamin A). Karoten yang telah banyak diketahui adalah alfa,
beta, dan gama karoten. Karoten yang paling penting untuk manusia adalah beta karoten
karena memiliki aktivitas provitamin A yang terbesar. Azis dan Muktiningsih (2006),
menyatakan bahwa kandungan zat makanan katuk per 100 gram mengandung kalori 59
kal, protein 6,4 g, lemak 1 g, hidrat arang 9,9 g, serat 1,5 g, abu 1,7 g, kalsium 233 mg,
phosphor 98 mg, besi 3,5 mg, karoten 10.020 µg, vitamin B dan C 164 mg, air 81 g.
Daun katuk mengandung zat-zat antinutrisi seperti tanin, saponin, alkaloid, dan
flavonoid. Level tanin yang optimum perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya
respon pertumbuhan yang buruk. Saponin dalam katuk dapat menurunkan permeabilitas
membran sel mukosa sehingga mempengaruhi transpor aktif nutrien. Saponin
mengakibatkan enzim-enzim yang terdapat dalam membran sel mukosa usus kehilangan
aktivitasnya dalam membantu uptake komponen nutrien ke dalam usus. Pada kondisi
tertentu flavonoid bersama dengan asam askorbat dapat memiliki aktivitas fungsional
yang mendukung pertumbuhan, namun keracunan flavonoid secara farmakologis pada
sisi yang lain juga dapat menurunkan penampilan ternak (Suprayogi, 1995).
Menurut Prayogo dan Santa (1997), taksonomi daun katuk adalah sebagai berikut:
Spesies : Sauropus androgynus (L.) Merr
Ciri makroskopis morfologi daun katuk yang dapat membedakan dengan jenis
katuk lainnya adalah (a) daun tunggal menyerupai majemuk dengan filotaksis tersebar,
(b) stipule persisten, (c) berbau aromatik lemah, (d) helai daunnya bulat telur sampai
lonjong, (e) bagian atas berwarna hijau tua bercak putih, (f) bagian bawah hijau muda, (g)
ujung dan pangkal daun meruncing serta (h) tulang daun menyirip (Prayogo dan Santa,
1997).
Menurut Sudiarto et al. (1997), budidaya tanaman katuk untuk komoditas komersial
telah dilakukan oleh petani di desa Cilebut, Cibadak, dan Kecana, Kecamatan Semplak,
Kabupaten Bogor. Budidaya tersebut dilakukan dengan bahan tanam stek berukuran
15-20 cm pada bedengan selebar 2 m. Jarak tanam yang digunakan adalah 4-5 cm x 15-20 cm.
Pemanenan pertama dapat dilakukan 2,5-3 bulan setelah penanaman dan panen
selanjutnya berselang 40-50 hari sekali. Hal tersebut dilakukan dengan pemangkasan
bagian tanaman menggunakan ketam mulai pada ketinggian 30-80 cm dari tanah. Pada
panen pertama biasanya diperoleh hasil sebesar 4 juta ton/ha dan selanjutnya pada tahun
pertama, yaitu setelah 6-7 kali panen dapat mencapai 21-30 ton/ha. Umur produktif
tanaman katuk umumnya 5-7 tahun dan maksimal 11-12 tahun.
Suprayogi (2000) melaporkan bahwa dengan menggunakan alat GCMS daun katuk
diperkirakan mengandung 7 senyawa aktif utama yang berperan penting dalam
memunculkan daya khasiatnya. Ketujuh senyawa tersebut adalah (a) octadecanoic-acid,
(b) 9-eicosine, (c) 5,8,11-heptadecatrienoic acid methyl ester, (d)
9,12,15-octadecatrienoic acid ethyl ester, (e) 11,14,17-eicosatrienoic acid methyl ester, (f)
androstan-17-one, 3-ethyl-3hydroxy-5-alpha, dan (g) 3,4-dimethyl-2-oxocyclopent-3-
enylacetatic acid, monomethyl succinate, phenylmalonic acid, cyclopentanol,
2-methyl-acetate, dan methylpyroglutamate terdapat di dalam saluran pencernaan ternak
ruminansia maupun monogastrik, dari ketujuh senyawa tersebut yang dapat
meningkatkan fungsi hormon reproduksi adalah senyawa androstan-17-one,
3-ethyl-3hydroxy-5-alpha. Piliang (2002) melaporkan bahwa kandungan tepung daun katuk
berbeda dengan serbuk ekstraksi daun katuk. Tepung daun katuk memiliki kandungan
gizi yang lebih baik dibandingkan dengan serbuk ekstrak daun katuk kering. Daun katuk
memiliki kandungan karotenoid dan provitamin A yang paling tinggi dibandingkan
sayuran lain di Indonesia.
Murbei (Morus sp.)
Daun murbei merupakan produk dari tanaman murbei yang banyak dimanfaatkan
dalam proses pengembangbiakan ulat sutera. Tanaman murbei dapat tumbuh mulai dari
daerah dingin hingga daerah yang panas. Tanaman murbei sangat cocok ditanam pada
lahan terbuka karena membutuhkan banyak cahaya untuk dapat tumbuh dengan baik di
dataran rendah maupun di dataran tinggi. Murbei mempunyai banyak nama lokal yaitu
kerta, kitau (Sumatera), murbai, besaran (Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali), gertu
(Sulawesi), kitaoc (Sumatera Selatan).
Tanaman murbei diklasifikasikan sebagai berikut (Samsijah, 1992) :
Divisi : Spermathophyta
Tanaman murbei termasuk semak atau pohon berukuran kecil sampai sedang
dengan tinggi tanaman mencapai 15 m dan diameter batang mencapai 60 cm. Tanaman
murbei dapat tumbuh di daerah temperit sampai ke daerah tropik yang kering. Tanaman
ini toleran tumbuh pada suhu lingkungan 5,9 sampai 27,50 C dan pH tanah dari 4,9
sampai 8,0. Di India dilaporkan bahwa tanaman murbei dapat tumbuh pada daerah pantai
sampai daerah dengan ketinggian 3300 m dpl. Tanaman murbei dapat diperbanyak
dengan biji, stek atau okulasi. Perbanyakan dengan biji relatif lebih mahal, tetapi
menghasilkan tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan perbanyakan melalui stek.
Perbanyakan tanaman dengan stek membutuhkan 75000 sampai 120000 stek/ha,
sedangkan perbanyakan dengan okulasi membutuhkan 4000 tanaman/ha. Teknik
perbanyakan tanaman dengan okulasi secara eksklusif dilakukan di Jepang (Machii et
al., 2002).
Gambar 2. Tanaman Murbei
Tanaman murbei mencapai ketinggian 1,3 m pada umur 10 minggu. Pemanenan
pertama daun dilakukan pada umur 12 minggu setelah penanaman. Pemanenan dapat
dilakukan sebanyak 10 kali/tahun untuk daerah yang beririgasi, sedangkan pada daerah
tadah hujan dapat dilakukan pemanenan sebanyak 6 sampai 7 kali. Tanaman murbei
dapat berproduksi dengan baik sampai berumur 15 tahun. Setelah itu, tanaman harus
diremajakan. Tanaman murbei mempunyai potensi sebagai bahan pakan yang berkualitas
karena potensi produksi, kandungan nutrien dan daya adaptasi tumbuhnya yang baik
(Singh dan Makkar, 2002). Produksi daun murbei sangat bervariasi, tergantung pada
varietas, lahan, ketersediaan air dan pemupukan. Martin et al. (2002) melaporkan
produksi biomassa murbei dengan interval defoliasi 90 hari akan mencapai 25 ton
BK/ha/thn dan produksi daun murbei sebesar 16 ton BK/ha/thn, sedangkan Boschini
(2002) melaporkan bahwa produksi daun murbei sebesar 19 ton BK/ha/tahun.
Daun murbei kaya akan sulfur (Saddul et al., 2005). Daun murbei mengandung
protein15,71 – 22,59 %, lemak 3,70 – 6,15 %, dan serat kasar 8 – 16,8 % (Ekastuti et al.,
1996). Daun murbei mengandung ekdisteron, inkosteron, lupeol, β-sitosterol, ritin,
morakatein, isoquersetin, skopoletin, skopolin, α-heksenal, β-heksenal, cis-β-heksenol,
cis-heksanol, benzaldehid, eugenol, linanol, benzil alkohol, butilamin, trigonelin, cholin,
adenin, asam amino, vitamin A, vitamin B, vitamin C, karoten, asam fumarat, asam folat,
asam formiltetrahidrofili, mionositol, logam, seng, dan tembaga (LIPI, 2009).
Karakteristik Puyuh Jepang
Semua jenis puyuh berasal dari jenis yang sama yaitu Coturnix coturnix, unggas liar
yang berpindah-pindah yang berasal dari Eropa, Asia, dan Afrika (Thear, 2005). Coturnix
Japonica berasal dari daerah Rusia, Asia Timur, dan India yang telah didomestikasi sejak
abad ke-13 (Pappas, 2002).
Puyuh (Cortunix cortunix japonica) atau japanese quail telah tersebar luas di Eropa
dan Asia. Puyuh dapat dibedakan jenis kelaminnya pada umur 3 minggu berdasarkan
warna kulitnya. Puyuh jantan memiliki warna bulu coklat pada bagian leher dan dada
serta mencapai dewasa kelamin pada umur 5-6 minggu dengan bobot badan 100-140
gram. Puyuh betina dapat diidentifikasi dengan melihat bulu pada bagian leher dan dada
yang warnanya lebih cerah. Puyuh betina mulai bertelur pada umur 35 hari pada kondisi
yang baik dan memproduksi sekitar 200-300 telur per tahun (Varghese, 2007).
Puyuh memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.
Sifat reproduksinya cepat, dalam satu tahun mampu menghasilkan 3-4 generasi. Bobot
badan puyuh betina dewasa mencapai 143 g/ekor. Bobot telur yang dihasilkan puyuh 10
gram per butir (Randall dan Bolla, 2008).
Puyuh merupakan hewan yang memiliki saluran pencernaan yang dapat
menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Gizzard dan usus halus puyuh
memberikan respons yang fleksibel terhadap ransum dengan kandungan serat kasar yang
tinggi (Starck dan Rahmaan, 2003).
Burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang, ukuran tubuh
relatif kecil, berkaki pendek, dan dapat diadu. Adapun klasifikasi zoologi burung puyuh
menurut Pappas (2002) adalah sebagai berikut :
Kingdom : Animalia
Beberapa keunggulan burung puyuh diantaranya produksi telur dan dagingnya
yang mempunyai nilai gizi serta rasanya yang lezat, bulunya dapat dimanfaatkan sebagai
bahan aneka kerajinan atau perabot rumah tangga lainnya, termasuk kotorannya yang
dapat digunakan sebagai pupuk kandang atau kompos untuk pupuk tanaman (Helsing,
2000). Puyuh akan menghasilkan telur jika kandungan kolesterol di dalam darah tinggi
yang kemudian akan diubah dengan bantuan enzim spesifik menjadi hormon progesteron
untuk pembentukan telur dalam jumlah yang banyak.
Kolesterol
Kolesterol berasal dari kata cholesterine yang berasal dari bahasa Yunani, chole
berarti empedu dan stereos berarti padat. Hal ini disebabkan pada saat pertama kali
ditemukan dengan mengisolasinya dari batu empedu. Kolesterol merupakan kelompok
sterol yang khas pada hewan. Kolesterol disintesis seperti umumnya asam lemak, yaitu
dari asetil-KoA yang mengandung dua buah karbon dan terkondensasi melalui beberapa
jalur yang sedikit berbeda. Asetil-KoA merupakan prekursor kecil bagi umumnya asam
lemak dalam tubuh (Gurr et al., 2001). Selain sebagai bagian dari membran sel,
kolesterol juga merupakan perantara metabolis yang penting sebagai (a) Substrat bagi
proses pembentukan empedu (asam dan garamnya), (b) Prekursor hormon-hormon
steroid seperti glukokortikoid, aldosteron, estrogen, progesteron, dan androgen dan (c)
Bentuk teresterifikasi lanjutan seperti vitamin D3 (Gurr et al., 2001). Sebagai bagian dari
membran sel, kolesterol tidak dibutuhkan secara kontinyu dan terjadinya siklus
pergantian membran, tetapi dibutuhkan dalam jumlah yang mencukupi untuk
menghasilkan empedu di hati. Keseimbangan kolesterol dalam sel dipengaruhi oleh (a)
Uptake lipoprotein langsung melalui reseptor, (b) Uptake kolesterol bebas dari
lipoprotein melalui transfer lemak, (c) Sintesis kolesterol, (d) Metabolisme kolesterol, (e)
Siklus perubahan kontinyu kolesterol, (f) esterifikasi kolesterol enzim asil-CoA :
kolesterol asiltransferase, dan (g) pemecahan ester kolesterol oleh enzim neutral-chole
esterase (Gurr et al., 2001).
Kolesterol adalah zat menyerupai lemak yang secara alami terdapat di seluruh
tubuh. Kolesterol terdapat pada dinding dan membran setiap sel, termasuk otak, saraf,
otot, kulit, hati, usus, dan jantung. Tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa
kolesterol (Laurencio, 2002). Kolesterol merupakan sterol utama dalam lipida hewan dan
dapat menghasilkan sejumlah produk oksidasi dibawah kondisi tertentu. Sejumlah kecil
produk oksidasi tersebut terdapat pada daging mentah dan yang telah mengalami
pemasakan.
Gambar 3. Mekanisme Sintesis Kolesterol(King, 2008)
Kolesterol merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah senyawa
penting, seperti vitamin D (untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat),
hormon seks (contohnya estrogen dan testosteron), dan asam empedu untuk fungsi
pencernaan (Smaolin dan Grosvenor, 1997). Selain untuk proses metabolisme, kolesterol
berguna untuk membungkus jaringan saraf (mielin), melapisi selaput sel, dan sebagai
pelarut vitamin (Dalimartha, 2005).
Menurut Frandson (1993), jumlah kolesterol dalam darah tergantung pada sebagian
besar makanan, umur, dan jenis kelamin. Selain itu, juga dipengaruhi oleh konsumsi
asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lemak jenuh dalam makanan
meningkatkan terbentuknya kolesterol dalam hati sedangkan lemak tidak jenuh menekan
tingkat kolesterol darah dalam mekanisme yang belum diketahui.
Semua jaringan tubuh mempunyai kemampuan untuk mensintesis kolesterol, namun
yang paling aktif adalah hati. Kolesterol dalam makanan akan mempengaruhi biosintesis
kolesterol dalam tubuh. Jika jumlah kolesterol dalam makanan kurang, sintesis kolesterol
dalam hati dan usus meningkat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan organ lain.
Sebaliknya jika jumlah kolesterol dalam makanan meningkat, sintesis kolesterol dalam
hati dan usus akan menurun (Piliang dan Djojosoebagio, 2000).
Hormon Progesteron
Progesteron merupakan hormon steroid yang memiliki struktur kimia yang mirip
dengan kolesterol dan sebagian besar tipe ini berasal dari kolesterol. Progestogen adalah
nama umum untuk sekelompok steroid yang terdiri atas 21 rantai atom karbon (Guyton
dan Hall, 1997). Progesteron merupakan hormon steroid (tidak bisa disimpan dalam
tubuh) yang berasal dari kolesterol. Progesteron merupakan zat penting dalam biosintesis
steroid pada semua jaringan yang mensekresi hormon steroid (Ganong, 2001).
Biosintesis progesteron dimulai dengan asetat dari kolesterol dan produk akhir yang
utama dari degradasi progesteron adalah pregnanediol (Guyton dan Hall, 1997).
Progesteron tidak disimpan di dalam tubuh, progesteron dipakai secara cepat atau
diekskresikan, sehingga di dalam jaringan tubuh hanya terdapat dalam kadar yang
rendah. Progesteron dibawa dalam darah dalam wujud berikatan dengan albumin plasma,
walaupun ada sejumlah kecil yang juga berikatan dengan globulin khusus yang mengikat
progesteron (Guyton dan Hall, 1997). Progesteron dimetabolisme menjadi pregnanediol,
terutama pada hati dengan cara dioksidasi, reduksi, dan hidroksilasi.
Gambar 4. Mekanisme Sintesis Hormon Progesteron(Baulieu, 1997)
Menurut Reeves (1987), fungsi progesteron adalah mempersiapkan lingkungan
estrus untuk implantasi dan memelihara kebuntingan melalui peningkatan sekresi dari
glandula endometrium serta menghambat motilitas miometrium uterus. Progesteron
bekerja secara sinergis dengan estrogen untuk menginduksi tingkah laku birahi,
merangsang sekresi kelenjar alveoli dan pertumbuhan glandula mamae. Progesteron
dalam tingkat tinggi akan menghambat birahi dan ovulasi karena progesteron dapat
menekan pelepasan FSH dan LH karena mempengaruhi daya kerja umpan balik negatif
terhadap FSH dan LH. Konsentrasi progesteron diperkirakan tergantung pada
kematangan seksual yang bisa menimbulkan peningkatan hormon gonadotropin dari
kelenjar hipofisa kemudian hormon gonadotropin bisa menstimulasi sintesis progesteron
dari folikel ovarium terbesar yang memiliki feedback positif terhadap hipothalamus.
Konsentrasi hormon progesteron meningkat sejalan dengan pertumbuhan folikel. Pada
sistem reproduksi, progesteron memacu LH praovulasi sehingga proses ovulasi bisa
terjadi, selain itu progesteron bersama estrogen diperlukan juga dalam pembentukan
albumin pada saluran reproduksi (Baskt dan Bahr, 1993).
Progesteron sendiri dibentuk dalam ovarium melalui mekanisme kerja : cholesterol
–pregnolone– progesterone dan proses metabolisme progesteron terjadi di hati (Guyton dan Hall, 1997). Konsentrasi progesteron dalam plasma darah turun naik selama siklus
ovulasi, apabila distimulasi progesteron yang melepaskan LH dari lobus anterior pituitary
maka, akan menyebabkan ovulasi oleh aktivitas saraf pusat yang melibatkan susunan
saraf pusat hipothalamus. Konsentrasi hormon progesteron meningkat 4-7 jam sebelum
ovulasi (Cunningham dan Senior, 1973).
Fitosterol
Dewanti (2006), fitosterol merupakan sterol yang secara alami didapatkan dari
tanaman. Secara kimiawi, fitosterol mirip dengan kolesterol yang didapat dari hewan.
Sterol terdiri dari tiga gabungan cincin sikloheksan dengan berbagai macam sterol (lebih
dari 40 fitosterol). Fitosterol tanaman merupakan komponen alami dari minyak tumbuhan
seperti minyak biji bunga matahari dan beberapa konstituen alami dalam makanan
manusia.
Menurut Silalahi (2006), fitosterol adalah steroida (sterol) yang terdapat di dalam
tanaman. Kedua senyawa ini mempunyai struktur yang mirip dengan kolesterol, tetapi
fitosterol mengandung gugus etil (-CH2-CH3) pada rantai cabang. Sebagaimana
pentingnya fungsi kolesterol dalam membran sel tubuh manusia dan hewan, demikian
juga fitosterol di dalam tanaman. Pada tanaman terdapat lebih dari 40 senyawa sterol
yang didominasi oleh beberapa senyawa dari kelompok fitosterol. Fitosterol terdapat
dalam bahan makanan nabati, seperti minyak, serealia, buah-buahan, dan sayur-sayuran
dalam jumlah yang hanya sedikit. Oleh kerena itu senyawa fitosterol harus diisolasi
dengan jumlah yang efektif untuk menurunkan kolesterol darah.
Sterol utama dalam hewani adalah kolesterol, yang jika banyak dikonsumsi dapat
menaikkan kolesterol darah. Sebaliknya, sterol nabati (fitosterol) hanya sedikit diabsorpsi
(5%) dan akan menurunkan kadar kolesterol darah. Konsumsi fitosterol per hari adalah
150-140 mg. Fitosterol utama dalam diet adalah Beta-sitosterol, kampesterol, dan
stigmasterol. Fitosterol menghambat absorpsi kolesterol dari usus, meningkatkan ekskresi
garam-garam empedu, atau menghindarkan esterifikasi kolesterol dalam mukosa
intestinal. Fitosterol dapat menghambat sintesis kolesterol dengan memodifikasi aktivitas
enzim hepatic acetyl-coa carboxylase dan cholesterol 7 – hydroxylase (Silalahi, 2006).
MATERI DAN METODE Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai bulan Januari 2011.
Analisis laboratorium kolesterol dilakukan di Laboratorium Terpadu, Fakultas
Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Darmaga dan analisis hormon progesteron
dilakukan di Laboratorium Mandapa di Bogor.
Materi Ternak
Penelitian ini menggunakan 36 ekor puyuh betina fase grower umur 7 minggu dan
dilanjutkan hingga fase layer umur 11 minggu (Cortunix cortunix japonica) yang
dialokasikan ke dalam 4 perlakuan dengan 3 ulangan dan setiap ulangan terdiri atas 3
ekor puyuh. Fase grower adalah puyuh umur 3 sampai dengan 7 minggu dan fase layer
adalah puyuh umur 8 sampai dengan 11 minggu. Setiap serum dari 3 ekor puyuh pada
setiap ulangan yang dikomposit, sehingga diperoleh 1 sampel yang dianalisis. Jumlah 12
serum darah puyuh fase grower dan 12 serum darah fase layer siap untuk dianalisis.
Perlakuan
Perlakuan pemberian pakan puyuh yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Ransum R0 : Ransum kontrol, tanpa tepung daun katuk dan tepung daun murbei
Ransum R1 : Ransum yang mengandung 10% tepung daun katuk (TDK)
Ransum R2 : Ransum yang mengandung 10% tepung daun murbei (TDM)
Ransum R3 : Ransum yang mengandung 5% tepung daun katuk (TDK) dan 5% tepung
daun murbei (TDM)
Susunan ransum puyuh perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat
pada Tabel 1 dan 2 serta kandungan nutrien ransum perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kandungan Nutrien Ransum Perlakuan
Pembuatan Tepung Daun Katuk dan Tepung Daun Murbei
Setelah katuk dan murbei didapatkan, dilakukan pemisahan antara daun dan batang.
Kemudian, daun katuk dan daun murbei dilayukan selama 24 jam. Setelah itu, daun katuk
dan daun murbei dimasukkan ke dalam oven bersuhu 600 selama 24 jam, lalu setelah
Sampel darah diambil dari vena jugularis sebanyak 1 ml dengan menggunakan syringe 3
ml. Sampel darah dimasukkan ke dalam tabung tidak berheparin, kemudian
disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm lalu serum dipisahkan dari total darah untuk
dianalisis. Serum yang didapat dimasukkan ke dalam tabung eppendorf. Setiap serum
dari 3 ekor puyuh pada setiap ulangan yang dikomposit sehingga, diperoleh 1 sampel
yang dianalisis. Jumlah 12 serum darah puyuh fase grower umur 7 minggu dan 12 serum
darah fase layer umur 11 minggu siap untuk dianalisis.
Peubah yang Diukur
Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah :
1. Konsumsi Ransum
2. Kolesterol Serum Darah
Pengukuran kolesterol menggunakan KIT dengan merek Human. Disiapkan
tabung blanko berisi 10µl aquades dan 1000µl reagen kit, tabung sampel berisi 10µl
serum darah dan 1000µl reagen kit. Campuran kemudian dihomogenkan selama 10
detik lalu diinkubasi selama 10 menit. Absorbansi dibaca pada
spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nm.
3. Hormon Progesteron Serum Darah
Konsentrasi progesteron dalam serum diukur dengan radioimmunoassay (RIA)
teknik fase padat, tiap sampel diambil 10µl dengan mikropipet dimasukkan ke dalam
tabung yang telah dilapisi antibodi progesteron spesifik, kemudian ditambahkan
1000µl radio isotop I-125 dan diinkubasi. Setelah itu larutan dibuang dengan
membalikkan tabung dan biarkan selama 3 jam dalam suhu ruang. Radioaktifitas
progesteron yang terikat dalam tabung dihitung dengan “Multi Well Gamma Counter SD 12/16”.
Rancangan Percobaan
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
(Steel dan Torrie, 1993). Metode matematiknya adalah :
Yij = µ + Pi + єij
Keterangan:
Yij : Pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
µ : Rataan umum
Pi : Pengaruh perlakuan ke-i
Єij : Galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan sidik ragam analysis of variance
(ANOVA) (Steel dan Torrie, 1993). Jika data yang diperoleh berbeda nyata maka, diuji
lanjut dengan uji jarak Duncan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsumsi Pakan
Rataan konsumsi pakan pada fase grower lebih tinggi dibandingkan dengan fase
layer kecuali, pada perlakuan R3 yaitu ransum yang ditambahkan 5 % tepung daun katuk
dan 5 % tepung daun murbei. Hal ini disebabkan pada fase grower lebih banyak
membutuhkan asupan makanan untuk proses pertumbuhan dan pembentukan telur,
sedangkan pada fase layer puyuh tidak membutuhkan untuk pertumbuhan tetapi hanya
untuk memproduksi telur.
Pada perlakuan R3, tingginya konsumsi pakan pada fase layer dibandingkan dengan
fase grower disebabkan karena puyuh mengalami keterlambatan dalam bertelur
dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Pada fase layer puyuh masih mengalami
pertumbuhan dan pembentukan telur.
Berdasarkan hasil sidik ragam, pemberian tepung daun katuk dan tepung daun
murbei pada ransum tidak nyata mempengaruhi kadar kolesterol serum pada seluruh
perlakuan. Hasil rata-rata pengukuran kadar kolesterol serum darah burung puyuh
disajikan pada Gambar 6.
Fase Grower Fase Layer Selisih Fase Grower dan Fase Layer
Gambar 6. Hasil Rata-Rata Pengukuran Kolesterol Serum Darah Puyuh
Selisih kadar kolesterol serum darah puyuh fase grower dan fase layer pada
perlakuan kontrol (R0) lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Puyuh
yang mendapat perlakuan ransum + 10% tepung daun katuk (R1) meningkat 2,4 kali
dibandingkan dengan ransum yang tidak diberi tepung daun katuk dan murbei (R0).
Puyuh yang mendapat perlakuan ransum + 10% tepung daun murbei (R2) meningkat 0,7
kali dibandingkan dengan R0. Puyuh yang mendapat perlakuan ransum + 5% tepung
daun katuk dan 5% tepung daun murbei (R3) meningkat 9 kali dibandingkan dengan R0.
Hal ini membuktikan bahwa kombinasi tepung daun katuk dan tepung daun murbei
meningkatkan kolesterol serum darah puyuh.
Kolesterol merupakan prekursor hormon progesteron. Kolesterol dibentuk melalui
tiga tahapan, yaitu pembentukan mevalonat yang merupakan kondensasi dari dua asetil
ko-enzim A, setelah itu síntesis squalen dari mevalonat, kemudian síntesis squalen
menjadi lanosterol dan kemudian akan diubah menjadi kolesterol. Suprayogi (2000)
menemukan senyawa aktif yang dapat meningkatkan konsentrasi hormon progesteron
pada daun katuk, yaitu senyawa androstan – 17 – one, 3 – ethyl – 3 – hydroxy – 5 alpha
sebagai prekursor dalam biosintesis hormon steroid.
Menurut Swenson (1984), kadar normal kolesterol darah unggas berkisar antara
125-200 mg/100 ml. Pemberian tepung daun katuk dan murbei pada ransum
menghasilkan kadar kolesterol serum darah puyuh berkisar antara 100 - 117,695 mg/100
ml artinya lebih rendah dibandingkan dengan pernyataan Swenson.
Rendahnya kandungan kolesterol serum darah puyuh fase grower disebabkan
karena pada saat fase grower belum optimalnya pembentukan hormon steroid. Hal ini,
menyebabkan kandungan kolesterol di dalam serum darah puyuh lebih rendah jika
dibandingkan dengan kandungan kolesterol fase layer.
Rendahnya kadar kolesterol serum darah puyuh disebabkan oleh kadar serat kasar
yang tinggi dalam ransum yaitu mencapai 14%. Tingginya serat kasar pada ransum dapat
menurunkan kolesterol karena serat kasar akan mengikat asam empedu dan akan
langsung dibuang ke dalam ekskreta.
Adanya zat antinutrisi pada daun katuk dan daun murbei yang akan mengurangi
kecernaan lemak kasar. Menurunnya kecernaan lemak dan absorpsi lemak akan
menurunkan kolesterol di dalam serum.
Penyerapan sejumlah komponen di dalam suatu jaringan dipengaruhi oleh
kandungan nutrien pada ransum. Konsumsi kolesterol dari ransum akan mempengaruhi
produksi kolesterol secara endogen. Kolesterol eksogen yang berasal dari makanan
dibutuhkan dalam tubuh hanya 25%, sedangkan kolesterol endogen yang dibentuk oleh
sel-sel tubuh dibutuhkan sebesar 75% (Frandson, 1993).
Asupan kolesterol pada burung puyuh dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam
darah. Apabila produksi kolesterol berlebih, maka akan mengurangi produksi kolesterol
secara eksogen ataupun sebaliknya. Kolesterol yang tidak mencukupi dari ransum maka,
hati akan memproduksi kolesterol. Kecepatan sintesis kolesterol oleh hati sangat
dipengaruhi oleh kandungan kolesterol makanan (Martin et al., 1983).
Adanya dedak padi di dalam ransum yang mencapai 50% dapat menurunkan
kolesterol karena dedak padi memiliki serat kasar yang tinggi sehingga, kolesterol
eksogen yaitu kolesterol yang berasal dari makanan tidak mencukupi kolesterol yang
dibutuhkan oleh puyuh sehingga, puyuh harus meningkatkan kolesterol endogenusnya
untuk pembentukan hormon progesteron.
Selain itu, adanya senyawa fitosterol yang berasal dari daun katuk dan daun murbei
yang dapat menghambat pembentukan kolesterol di dalam tubuh puyuh karena senyawa
fitosterol akan menggantikan kolesterol yang ada di dalam tubuh puyuh.
Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsentrasi Hormon Progesteron Serum
Berdasarkan hasil sidik ragam, pemberian tepung daun katuk dan tepung daun
murbei pada ransum tidak nyata mempengaruhi konsentrasi hormon progesteron serum
pada seluruh perlakuan. Hasil rata-rata pengukuran konsentrasi hormon progesteron
serum darah burung puyuh disajikan pada Gambar 7.
0,093
Fase Grower Fase Layer Selisih Fase Grower dan Layer
Gambar 7. Hasil Rata-Rata Pengukuran Hormon Progesteron Serum Darah Puyuh
Selisih konsentrasi hormon progesteron serum darah puyuh fase grower dan fase
layer, pada puyuh yang mendapat perlakuan ransum + 10% tepung daun katuk (R1)
meningkat 0,2 kali dibandingkan dengan ransum yang tidak diberi tepung daun
katuk dan murbei (R0). Puyuh yang mendapat perlakuan ransum + 10% tepung daun
murbei (R2) tidak mengalami peningkatan hormon progesteron. Puyuh yang mendapat
perlakuan ransum + 5% tepung daun katuk dan 5% tepung daun murbei (R3) meningkat
1,5 kali dibandingkan dengan R0.
Proses metabolisme hormon progesteron terjadi di hati (Guyton dan Hall, 1997).
Biosintesis hormon progesteron dimulai dengan pembentukan kolesterol. Kemudian,
kolesterol dibawa ke pregnenolon yaitu prekursor hormon steroid untuk diubah menjadi
hormon progesteron dengan bantuan enzim P450c17,17-hidroksilase.
Adanya senyawa steroid pada daun katuk dan daun murbei dapat meningkatkan
konsentrasi hormon progesteron di dalam serum darah puyuh. Pada sistem reproduksi,
progesteron memacu Luteinizing Hormone (LH) praovulasi sehingga proses ovulasi bisa
terjadi (Baskt dan Bahr, 1993). Hormon progesteron tidak disimpan di dalam tubuh,
hormon progesteron dipakai secara cepat atau diekskresikan, sehingga di dalam jaringan
tubuh hanya terdapat dalam kadar yang rendah. Konsentrasi hormon progesteron
meningkat pada saat 4-7 jam sebelum ovulasi (Cunningham & Senior, 1973).
Kandungan hormon progesteron pada unggas 4-7 jam fase grower 6,47 ng/ml.
Gambar 8. Korelasi Kolesterol dan Hormon Progesteron Fase Grower
y = 0,0025x - 0,0545
Gambar 9. Korelasi Kolesterol dan Hormon Progesteron Fase Layer
Rendahnya rataan nilai hormon progesteron pada fase grower karena umur bertelur
pada puyuh yang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kandungan fitosterol
pada daun katuk dan daun murbei dan serat kasar yang tinggi pada ransum.
Produksi telur dari 4 minggu menjelang akhir pemeliharaan menunjukkan data yang
fluktuatif dengan kisaran 20-99% (Piliang et al., 2009).
Korelasi antara kolesterol dan hormon progesteron pada fase grower memiliki
korelasi yang meningkat. Korelasi kolesterol dan hormon progesteron memiliki hubungan
y = 0.0002x + 0.0123 dan R2 = 0.0354 yang berarti ada hubungan antara kolesterol dan hormon progesteron.
Korelasi antara kolesterol dan hormon progesteron pada fase layer memiliki
korelasi yang meningkat juga. Korelasi kolesterol dan hormon progesteron memiliki
hubungan y = 0.0025x – 0.0545 dan R2 = 0.2279 yang berarti ada hubungan antara
kolesterol dan hormon progesteron.
Kolesterol mempengaruhi konsentrasi hormon progesteron di dalam darah.
Konsentrasi hormon progesteron di dalam darah dipengaruhi oleh tingkat kematangan
seksual (Magdi et al., 1982). Rendahnya korelasi kolesterol dan hormon progesteron
disebabkan oleh kadar kolesterol yang rendah di dalam darah karena tingginya serat kasar
di dalam ransum sehingga, menigkatkan ekskresi lemak ke dalam ekskreta.
Umur bertelur puyuh yang terlambat juga mempengaruhi korelasi antara kolesterol
dan hormon progesteron. Puyuh bertelur mulai umur 5-6 minggu, tetapi pada penelitian
ini puyuh mulai bertelur pada umur 7-8 minggu. Pada penelitian ini juga tingkat variasi
pada puyuh tinggi sehingga, mempengaruhi di dalam proses ovulasi.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pemberian tepung daun katuk, tepung daun murbei, dan kombinasinya hingga 10%
pada ransum belum berpengaruh terhadap kadar kolesterol dan konsentrasi hormon
progesteron pada burung puyuh. Pemberian campuran tepung daun katuk dan tepung
daun murbei cenderung lebih baik dibandingkan pemberian secara tunggal.
Saran
Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang penentuan dosis dan ulangan yang lebih
banyak dalam menguatkan hipotesa manfaat campuran tepung daun katuk dan tepung
daun murbei terhadap produksi burung puyuh.
UCAPAN TERIMAKASIH
Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya yang
telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini
penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Lian Wha
dan Ayahanda Isupardi yang telah memberikan semangat dan doa hingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir ini. Dukungan yang telah mereka berikan baik secara moril
maupun materil tidak akan pernah dapat penulis lupakan sepanjang hidup ini.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Eka Tjipta Foundation yang telah
membiayai penulis selama kuliah di IPB. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak
kepada Ir. Widya Hermana, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang juga sebagai
dosen pembimbing akademik dan Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS selaku dosen
pembimbing anggota yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi saran selama
penelitian dan penyusunan skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ir. Rita
Mutia, M.Agr selaku dosen penyaji seminar yang telah memberikan saran dalam
perbaikan makalah seminar. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ir. Dwi
Margi Suci, MS dan Dr. Ir. Rukmiasih, MS yang telah memberikan saran dalam
perbaikan skripsi.
Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Wiranda G.
Pilliang, M.Sc sebagai ketua penelitian hibah kompetitif yang telah memberikan dana
untuk penelitian penulis, kemudian kepada Ibu Lanjarsih yang telah banyak membantu
penulis melaksanakan penelitian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkatNya
untuk kita semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya dan pembaca pada umumnya.
Bogor, April 2011
Penulis
DAFTAR PUSTAKA
Azis, S. & S. R. Muktiningsih. 2006. Studi manfaat daun katuk (Sauropus androgynus). Cermin Dunia Kedokteran. 151: 48-50. http://www.kalbe.co.id [29 Juli 2010].
Bakst, M. R. & J. M. Bahr. 1993. Poultry Reproduction in Farm Animal. E. S. E. Hafez, (Ed) 6th Ed. Lea and Febiger, USA.
Baulieu, E. E. 1997. Neurosteroids: of the nervous system, by the nervous system, for the nervous system. Recent Prog Horm Res. 52 : 1-32.
Boschini, C. F. 2002. Nutritional quality of mulberry cultivation for ruminant feeding. FAO Animal Production and Health Paper, Roma. 147 : 173-182.
Cunningham, F. J. & B. E. Senior. 1973. Oestradiol and LH during the ovulatory cycles of the hen. J. Endoc. 60 : 201 – 202.
Dalimartha, S. 2005. Turunkan kolesterol dangan terapi herbal. http://www. suarakarya_online.com/news.html [29 Juli 2010].
Dewanti W, Tri. 2006. Pangan fungsional makanan untuk kesehatan. Universitas Brawijaya. Malang.
Ekastuti, D. R., D. A. Astuti, R. Widjajakusuma & D. Sastradipradja. 1996. Rearing silkworm (Bombyx Mori) with artificial diets as an effort to promote the quantity and quality of national rawsilk production. Research Report, Research Institute of IPB, Bogor, Indonesia.
Frandson R. D. 1993. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Ed ke-4. Terjemahan. B. Srigandono & K. Praseno. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Ganong, W. F. 2001. Fisiologi Kedokteran edisi ke-20. Terjemahan: H. M. D Widjajakusumah. Penerbit buku kedokteran EGC. Jakarta.
Gurr, M. I., J. L. Harword & K. N. Frayn. 2001. Lipid Biochemistry. 5th Edition. Blackwell Science, Ltd., United Kingdom.
Guyton, A. C. & J. E. Hall. 1997. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Ed ke-9. Terjemahan: Irawati Setiawan. EGC. Jakarta.
Helsing, E. V. 2000. Budidaya burung puyuh coturnix-coturnix. Bappenas web. http://www.ristek.go.id. [ 29 Juli 2010].
King, M. W. 2008. Steroid hormone. www.miking.at.iupui.edu [1 Juni 2011].
Laurencio, B. A. 2002. Cholesterol, part one: a patient guide. http://www. heartinfo.org
[29 Juli 2010].
LIPI. 2009. Pengobatan alternatif dengan tanaman obat. www.bit.lipi.go.id [1 juni 2011].
Machii, H., A. Koyama, & H. Yamanouchi. 2002. Mulberry breeding, cultivation and utilization in Japan. FAO Animal Production and Health Paper, Roma. 147 : 63-72.
Magdi, M., Mashaly, & L. Maria. 1982. Relationship between progesteron and egg production in pheasant. Poultry. Sci. 61: 982-987.
Martin, D. W., P. A. Mayes, & V. W. Rodwell. 1983. Harper’s Review of Biochemistry.19th Ed. Lange Medical Publication. Los Altos, California.
Martin, G., F. Reyes, I. Hernandez, & M. Milera. 2002. Agronomic studies with mulberry in Cuba. FAO Animal Production and Health Paper, Roma. 147 : 103-114.
Pappas, J. 2002. Coturnix japonica. Animal diversity web. http: //animaldiversity.ummz.edu/site/accounts/information/Coturnix-japonica.html. [4 Agustus 2010].
Piliang, W. G. 2002. Nutrisi Vitamin. Volume I. Edisi ke-5. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.
Piliang, W. G. & S. Djojosoebagio. 2000. Fisiologi Nutrisi. Volume I. Ed ke-2. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.
Piliang, W. G., D. A. Astuti, & W. Hermana. 2009. Pengkayaan Produk Puyuh Melalui Pemanfaatan Pakan Lokal Yang Mengandung Antioksidan Dan Mineral Sebagai Alternatif Penyediaan Protein Hewani Bergizi Tinggi. Laporan Penelitian. Institut Pertanian Bogor.
Prayogo, B. E. W. & I. G. P. Santa 1997. Studi taksonomi Sauropus androgynus (L.) Merr. Warta Tumbuhan Obat Indonesia 3(3) : 53-55.
Randall, M & Bolla, G. 2008. Raising Japanese quail. Ed ke-2. New South Wales: Primefact Home. http://www.publish.csiro.au.html. [20 Maret 2011].
Reeves, J. J. 1987. Endicrinology of reproduction. In E. S. E. Hafez (Editor). Reproduction in Farm Animals. Lea and Febiger. Philadelphia.
Saddul, D. Z., Z. A. Jelan, J. B. Liang, & R. A. Halim. 2005. Evaluation of mulberry (Morus Alba) as potential feed supplement for ruminants : the effect of plant maturity on in situ disapperarance and in vitro intestinal digestibility of plant fraction. Asian – Aust. J. Anim. Sci. 18 : 1569 – 1574.
Samsijah. 1992. Pemilihan tanaman murbei (morus sp.) yang sesuai dengan daerah sindang resmi Sukabumi, Jawa Barat. Buletin Penelitian Hutan. 547 : 45-59.
Silalahi, J. 2006. Fitosterol dalam margarine cara efektif menurunkan kolesterol. www.tempointeraktif.com. [31 Maret 2011].
Singh, B. & H. P. S. Makkar. 2002. The potential of mulberry foliage as a feed supplement in India. FAO Animal Production and Health Paper, Roma 147 : 139-156.
Smaolin, L. A. & M. B. Grosvenor. 1997. Nutrition: Science and Application, 2nd Edition. Saunders College Publishing. http://www.mediastore.com [29 Juli 2010].
Starck, M. J. & G. H. A. Rahmaan. 2003. Phenotypic flexibility of structure and function of the digestive system of japanese quail. The Journal of Experimental Biology 206: 1887 – 1897.
Steel, R. G. D. & J. H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika Suatu Pendekatan Biometrik. Terjemahan. B. Sumantri. Gramedia Pustaka. Jakarta.
Subekti S. 2007. Komponen sterol dalam ekstrak daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) dan hubungannya dengan system reproduksi puyuh. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Sudiarto, D. E. Effendi & Suprapto. 1997. Studi aspek teknis budidaya katuk di lahan petani kecamatan Semplak, Bogor. J. Ind. Med. Plants. 3 (3) : 8-10.
Suprayogi, A. 1995. The effect of Sauropus androgynus leaves on the feed digestibility, glucose absorption and glucose metabolism in the liver (a study on tropical medicinal plant). Master Thesis of Gottingen University, Germany.
Suprayogi, A. 2000. Studies on the biological effect of Sauropus androgynus (L. Merr.): Effect on milk production and the possibilities of induced pulmonary disorder lactating sheep. Universitat Gottingen Institut fur Tierphysiology und Tieremahrung. Gottingen: George-August.
Swenson, M. J. 1984. Duke’s Phsiology of Domestic Animals. 10th Edition. Publishing Assocattes a Division of Cornell University. Ithaca and London.
Thear, K. 2005. Keeping Quail. Broad Leys Publishing Ltd., United Kingdom.
Varghese, S.K. 2007. The Japanese Quail. Feather Francier Newspaper, Canada.
Yuliani, S. & T. Marwati. 1997. Tinjauan katuk sebagai bahan makanan tambahan yang bergizi. Warta Tumbuhan Obat Indonesia. 3 (3):55-56.
Lampiran 1. ANOVA (Analysis of Variance) Rataan Kadar Kolesterol Fase Grower
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 800,055 266,685 0,914 4,07 7,59
Error 8 2333,254 291,657
Total 11 3133,309 284,846
Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata
Lampiran 2. ANOVA (Analysis of Variance) Rataan Kadar Kolesterol Fase Layer
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 829,477 276,492 0,539 4,07 7,59
Error 8 4101,533 512,692
Total 11 4931,01 448,274
Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata
Lampiran 3. ANOVA (Analysis of Variance) Selisih Kadar Fase Grower dan Fase Layer
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 745,949 248,65 0,483 4,07 7,59
Error 8 4116,52 514,565
Total 11 4862,469 442,043
Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata
Lampiran 4. ANOVA (Analysis of Variance) Rataan Konsentrasi Hormon Progesteron Fase Grower
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 0,219 0,073 0,785 4,07 7,59
Error 8 0,746 0,093
Total 11 0,965 0,088
Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata
Lampiran 5. ANOVA (Analysis of Variance) Rataan Konsentrasi Hormon Progesteron Fase Layer
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 0,138 0,046 1,122 4,07 7,59
Error 8 0,331 0,041
Total 11 0,469 0,043
Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata
Lampiran 6. ANOVA (Analysis of Variance) Selisih Konsentrasi Hormon Progesteron Fase Grower dan Fase Layer
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01
Perlakuan 3 0,045 0,015 1,875 4,07 7,59
Error 8 0,068 0,008
Total 11 0,113 0,010
Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata