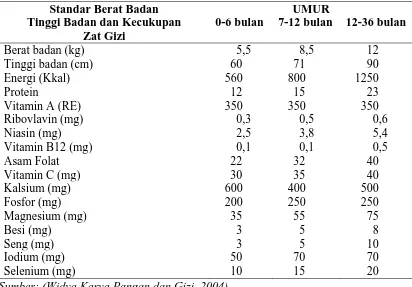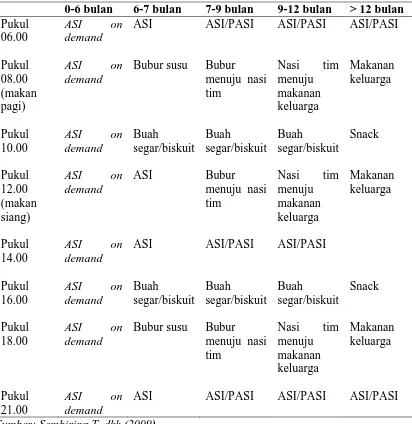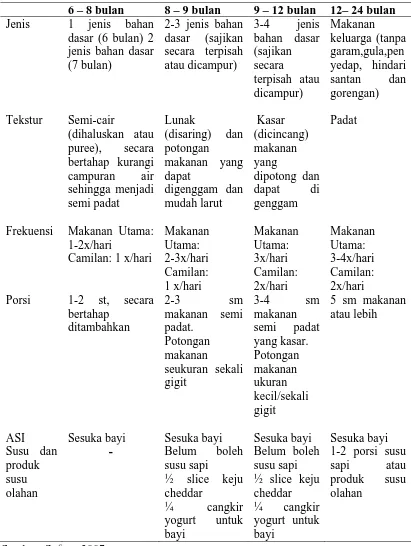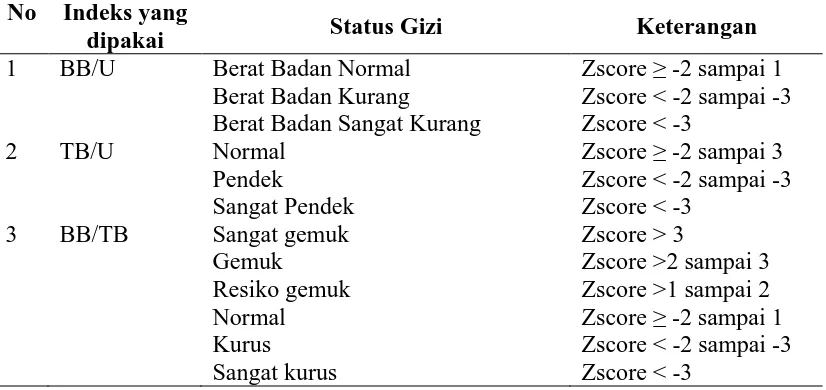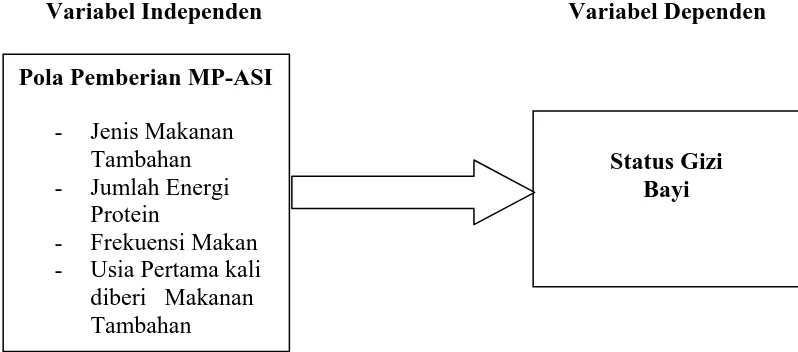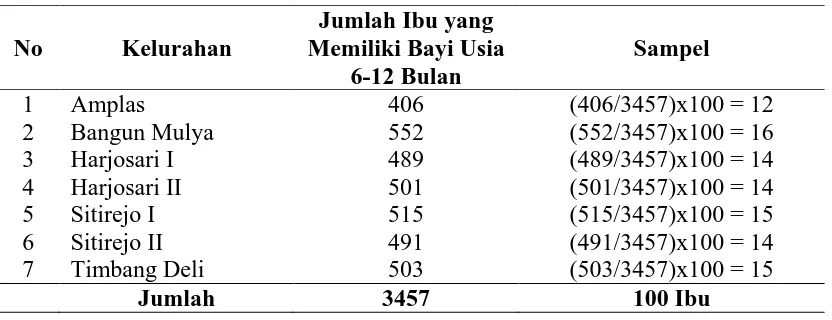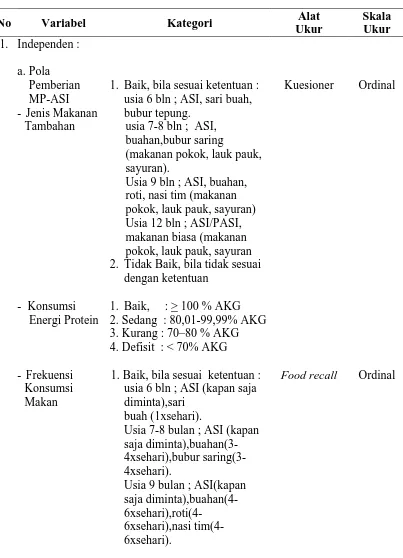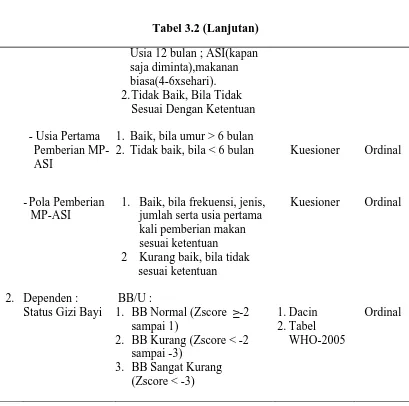PENGARUH POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) TERHADAP STATUS GIZI PADA BAYI 6-12 BULAN
DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS
TESIS
Oleh :
SUMARTINI 097032039/IKM
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
THE INFLUENCE OF COMPLEMENTARY FEEDING PATTERN ON THE NUTRITIONAL STATUS OF INFANT 6-12 MONTHS
IN MEDAN AMPLAS SUBDISTRICT
THESIS
By
SUMARTINI 097032039/IKM
MAGISTER OF PUBLIC HEALTH STUDY PROGRAM FACULTY OF PUBLIC HEALTH
UNIVERSITY OF NORTH SUMATERA MEDAN
PENGARUH POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) TERHADAP STATUS GIZI PADA BAYI 6-12 BULAN
DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Gizi Masyarakat
pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
OLEH
SUMARTINI 097032039/IKM
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
Judul Tesis : PENGARUH POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) TERHADAP STATUS GIZI PADA BAYI 6-12 BULAN DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS
Nama Mahasiswa : Sumartini Nomor Induk Mahasiswa : 097032039
Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Minat Studi : Administrasi dan Kebijakan Gizi Masyarakat
Menyetujui Komisi Pembimbing :
(Dr. Ir. Evawany Aritonang, M.Si Ketua
)
Anggota
(Dra. Jumirah, Apt, M.Kes)
Ketua Program Studi
(Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si)
Dekan
(Dr. Drs. Surya Utama, M.S)
PERNYATAAN
PENGARUH POLA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) TERHADAP STATUS GIZI PADA BAYI 6-12 BULAN
DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.
Medan, Desember 2011
Telah diuji pada
Tanggal : 12 Oktober 2011
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Dr. Ir. Evawany Aritonang, M.Si Anggota : 1. Dra. Jumirah, Apt, M.Kes
ABSTRAK
Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk di Puskesmas Amplas periode tahun 2008, 2009 dan 2010 mengalami mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 ditemukan balita gizi buruk sebanyak 17 balita (0,3%) dan gizi kurang 69 balita (1,3%). Pada tahun 2009 ditemukan balita gizi buruk 22 balita (0,4%) dan gizi kurang 96 balita (1,9%) dan pada tahun 2010 balita gizi buruk 27 balita (0,5%) dan gizi kurang sebanyak 116 balita (2,1%).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pola pemberian makanan pendamping ASI (jenis makanan, frekuensi makan, jumlah makanan, dan waktu pertama kali pemberian MP-ASI)) terhadap status gizi bayi 6-12 bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. J
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberian MP-ASI meliputi jenis makanan tambahan, konsumsi energi dan protein serta frekuensi konsumsi makan berpengaruh terhadap status gizi bayi 6-12 bulan (p<0,05). Usia pertama kali pemberian MP-ASI tidak berpengaruh terhadap status gizi bayi 6-12 bulan (p>0,05) di Kecamatan Amplas Medan Kota.
enis penelitian adalah survey explanatory
research dengan desain cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei
sampai dengan Juli 2011. Populasi sebanyak 3.457 ibu yang memiliki bayi berumur 6-12 bulan dan jumlah sampel diperoleh 100 ibu. Data pola pemberian MP-ASI diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner dan food recall 24 jam. Status gizi bayi diukur berdasarkan indeks BB/U menurut rujukan WHO-2005. Data dianalisis menggunakan uji Regresi Logistik.
Kepada Dinas Kesehatan dan instansi terkait disarankan menggalakkan kembali program ASI Ekslusif dan melaksanakan penyuluhan secara kontinu tentang bahan atau jenis makanan yang bergizi, murah dan mudah diperoleh di lingkungan sekitarnya serta kegiatan praktek pengelolaan keanekaragaman makanan di posyandu sehingga masyarakat mengetahui gizi makanan yang baik untuk diterapkan dalam keluarga dan masyarakat dalam memenuhi status gizi bayi.
ABSTRACT
The prevalence of bad and worst malnutrition of children under five in Amplas Health Centre Medan city was increased respectively in 2008, 2009 and 2010 period. In 2008, it was found worst malnutrition for 17 (0,3%) children under five, and less malnutrition for 69 (1,3%). In 2009, it was found bad malnutrition for 22 (0,45) children under five and 96 (1,95) children under five and in 2010, it was found bad malnutrition for 27 (0,5%) children under five and less malnutrition for 116 (2,1%) children under five.
The objective of this research was to analyze the influence of complementary mother’s milk feeding pattern (type of food, eating frequency, amount of energy and protein consumption at the first time of mother’s milk feeding) on the nutrient status of children under five aged 6-12 old months in Medan Amplas District, Medan City. This research was survey explanatory, conducted on May through July 2011.
The results of research showed that the pattern of complementary feeds action include additional types of food, the consumption of energy and protein intake and meal frequency influence on the nutritional status of infants 6-12 months (p <0.05). The age for the first time of mother’s milk feeding did not have influence on nutrient status for the children under five aged 6-12 old months (p>0,05) in Medan Amplas District, Medan City.
The population were all mothers with children aged 6-12 old months for 3,457 persons and the sample was taken for 100 mothers. Data the influence of companion mother’s milk feeding pattern collection were collected through interview referring to the questionnaire and 24-hour food recall. The nutritional status of infants measured by the index weight / age according to reference who-2005. The data were analyzed using Logistics Regression test.
It is suggested to Medan District Health Office and related institution to encourage and maintain exclusive mother’s milk feeding as well as to give counselling continuously regarding the type of food with good nutrient, inexpensive and easy to get in their surrounding. Various food management practice should be carried out in Integrated Health Service Centre for the socialization of good food nutrient to be applied in family to fulfill the status of nutrient of children under five.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
memberi rahmat dan hidayat-Nya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat
menyelesaikan tesis yang berjudul ”Pengaruh Pola Pemberian Makanan Pendamping
ASI (MP-ASI) terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan
Amplas”.
Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan
pendidikan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi
dan Kebijakan Gizi Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Sumatera Utara Medan.
Dalam menyusun tesis ini, penulis mendapat bantuan, dorongan dan
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, D.T.M&H.,
M.Sc (CTM)., Sp.A, (K).
2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Dr. Drs. Surya
Utama, M.S atas kesempatan penulis menjadi mahasiswa Program Studi S2 Ilmu
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera
Utara.
3. Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si dan
Pembimbing dan Anggota Komisi Pembimbing Dra. Jumirah, Apt, M.Kes yang
telah membimbing kami dan memberikan masukan serta saran dalam
penyelesaian tesis ini .
4. Tim Komisi Penguji Dr. Ir. Zulhaida Lubis, M.Kes dan Anggota Komisi Penguji
Ernawati Nasution, S.K.M, M.Kes yang telah banyak memberikan saran,
bimbingan dan perhatian selama penulisan tesis.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Kabid PMK dan Kapus Medan Amplas
yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam
rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan
Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.
7. Para dosen, staf dan semua pihak yang terkait di lingkungan Program Studi S2
Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Gizi
Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
8. Ucapan terima kasih yang tulus saya tujukan kepada ayahanda H. Samidjo dan
Ibunda Hj. Suziah serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril
serta doa dan motivasi selama penulis menjalani pendidikan.
9. Teristimewa buat suami Edy Sofyan, S.E, M.M dan ananda Amanda Chayara
Alima dan Dinda Rameyza Alia berkat merekalah saya termotivasi untuk
menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat,
khususnya teman-teman Gizi, Diana, Nita, Iwan, Buk Mariani dan Kak Yus atas
Akhirnya saya menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu, saran dan
kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, dengan
harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di bidang kesehatan
dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Medan, Desember 2011
Penulis
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Sumartini dilahirkan di Seruway tanggal 13 Januari 1972.
Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan H. Samidjo dan Hj.
Suziah, sudah menikah dan dikaruniai putri kembar.
Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Pertamina Rantau
pada tahun 1984, menamatkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Pertamina Rantau
pada tahun 1987, menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMA Jaya Langsa pada
tahun 1990, menamatkan sekolah di Akademi Gizi (AKZI) Sutan Oloan Medan pada
tahun 1994, menamatkan Sarjana S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Helvetia pada
tahun 2006.
Penulis memulai karir pada tahun 1994 di PT Nestle Indonesia Jakarta sampai
tahun 1995. Bekerja pada PT. Servier Indonesia dari tahun 1995-1996. Pada tahun
1996 sampai dengan 2004 sebagai PNS di Puskesmas Perbaungan Kabupaten
Serdang Bedagai, dan pada tahun 2004 sampai sekarang bertugas pada Dinas
DAFTAR ISI
2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI .. 19
BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 45
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian ... 45
4.2. Hasil Penelitian ... 47
4.2.1. Karakteristik Ibu ... 47
4.2.2. Karakteristik Bayi ... 49
4.2.3. Status Gizi Bayi ... 49
4.2.4. Pola Pemberian MP-ASI Bayi Berdasarkan Jenis Makanan Tambahan pada Kelompok Umur Bayi ... 50
4.2.5. Pola Pemberian MP-ASI Bayi Berdasarkan Konsumsi Energi Protein pada Kelompok Umur Bayi ... 50
4.2.6. Pola Pemberian MP-ASI Bayi Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Makan pada Kelompok Umur Bayi ... 51
4.2.7. Pola Pemberian MP-ASI Bayi berdasarkan Usia Pertama Kali diberi Makan pada Kelompok Umur Bayi ... 52
4.2.8. Hubungan Jenis Makanan dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 53
4.2.9. Hubungan Konsumsi Energi dan Protein dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 53
4.2.10. Hubungan Frekuensi Konsumsi Makan dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 55
4.2.11. Hubungan Usia Pertama Kali diberi Makan dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 55
4.2.12. Pengaruh Pola Pemberian Makanan Pendamping ASI (Jenis Makanan, Frekuensi Konsumsi Makan, dan Jumlah Energi Protein) terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ... 56
BAB 5. PEMBAHASAN ... 59
5.1. Pengaruh Jenis Makanan dengan Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas... 59
5.2. Pengaruh Konsumsi Energi Protein terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 61
5.3. Pengaruh Frekuensi Makanan terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 62
5.4. Pengaruh Frekuensi Makanan terhadap Status Gizi pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 63
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 65
6.1. Kesimpulan ... 65
6.2. Saran ... 66
DAFTAR PUSTAKA ... 67
DAFTAR TABEL
No. Judul Halaman
2.1. Estimasi Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Anak
Indonesia ... 17
2.2. Jadwal Pemberian Makanan Tambahan Menurut umur Bayi,
Jenis Makanan, dan Frekuensi Pemberian Makanan ... 23
2.3. Jadwal Pemberian Makanan Tambahan pada Bayi
(Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia /IDAI) ... 24
2.4. Makanan Tambahan Anak Usia 6 – 24 bulan ... 26
2.5. Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB
Standar Baku Antropometri Menurut WHO 2005 ... 31
3.1 Jumlah Ibu yang memiliki Bayi Usia 6-12 Bulan sebagai Sampel Penelitian di Setiap Kelurahan di Kecamatan Medan Amplas
Kota Medan ... 39
3.2 Skala Pengukuran Variabel Independen dan Variabel Dependen . 42
4.1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ... 46
4.2 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan ... 46
4.3. Distribusi Sarana Kesehatan ... 47
4.4. Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Berdasarkan Umur, Agama, Jumlah Anak, Pendidikan, Pekerjaan Orangtua, dan
Penghasilan per Bulan ... 48
4.5. Distribusi Frekuensi Karakteristik Bayi Berdasarkan Umur,
Berat Badan ... 49
4.6. Distribusi Status Gizi Bayi Berdasarkan BB/U ... 49
4.7. Tabulasi Silang Jenis Makanan Tambahan Berdasarkan
4.8. Tabulasi Silang Konsumsi Energi Berdasarkan Kelompok Umur
Bayi ... 51
4.9. Tabulasi Silang Konsumsi Protein Berdasarkan Kelompok
Umur Bayi ... 51
4.10. Tabulasi Silang Frekuensi Konsumsi Makanan Berdasarkan
Kelompok Umur Bayi ... 52
4.11. Distribusi Frekuensi Pola Pemberian MP-ASI Bayi Berdasarkan
Usia Pertama Kali diberi Makan ... 52
4.12. Hubungan Jenis Makanan Tambahan dengan Status Gizi pada
Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 53
4.13. Hubungan Konsumsi Energi dengan Status Gizi pada Bayi 6-12
Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 54
4.14. Hubungan Konsumsi Protein dengan Status Gizi pada Bayi 6-12
Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 54
4.15. Hubungan Frekuensi Konsumsi Makan dengan Status Gizi pada
Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 55
4.16. Hubungan Usia Pertama Kali diberi Makan dengan Status Gizi
pada Bayi 6-12 Bulan di Kecamatan Medan Amplas ... 56
4.17. Hasil Uji Regresi Logistik Pola Pemberian Makanan Pendamping ASI (Jenis Makanan, Konsumsi Energi dan Protein serta Frekuensi Konsumsi Makan) terhadap Status Gizi pada
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Halaman
2.1. Penyebab Kurang Gizi Pada Anak (Unicef, 1998) ... 35
DAFTAR LAMPIRAN
No. Judul Halaman
1. Surat Izin Penelitian dari Program Studi S2 Ilmu Kesehatan
Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU 69
2 Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Medan ... 70
3 Surat Telah Selesai Meneliti dari Dinas Kesehatan Kota Medan ... 71
4. Kuesioner Penelitian ... 72
5. Pengolahan Data ... 75
ABSTRAK
Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk di Puskesmas Amplas periode tahun 2008, 2009 dan 2010 mengalami mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 ditemukan balita gizi buruk sebanyak 17 balita (0,3%) dan gizi kurang 69 balita (1,3%). Pada tahun 2009 ditemukan balita gizi buruk 22 balita (0,4%) dan gizi kurang 96 balita (1,9%) dan pada tahun 2010 balita gizi buruk 27 balita (0,5%) dan gizi kurang sebanyak 116 balita (2,1%).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pola pemberian makanan pendamping ASI (jenis makanan, frekuensi makan, jumlah makanan, dan waktu pertama kali pemberian MP-ASI)) terhadap status gizi bayi 6-12 bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. J
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberian MP-ASI meliputi jenis makanan tambahan, konsumsi energi dan protein serta frekuensi konsumsi makan berpengaruh terhadap status gizi bayi 6-12 bulan (p<0,05). Usia pertama kali pemberian MP-ASI tidak berpengaruh terhadap status gizi bayi 6-12 bulan (p>0,05) di Kecamatan Amplas Medan Kota.
enis penelitian adalah survey explanatory
research dengan desain cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei
sampai dengan Juli 2011. Populasi sebanyak 3.457 ibu yang memiliki bayi berumur 6-12 bulan dan jumlah sampel diperoleh 100 ibu. Data pola pemberian MP-ASI diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner dan food recall 24 jam. Status gizi bayi diukur berdasarkan indeks BB/U menurut rujukan WHO-2005. Data dianalisis menggunakan uji Regresi Logistik.
Kepada Dinas Kesehatan dan instansi terkait disarankan menggalakkan kembali program ASI Ekslusif dan melaksanakan penyuluhan secara kontinu tentang bahan atau jenis makanan yang bergizi, murah dan mudah diperoleh di lingkungan sekitarnya serta kegiatan praktek pengelolaan keanekaragaman makanan di posyandu sehingga masyarakat mengetahui gizi makanan yang baik untuk diterapkan dalam keluarga dan masyarakat dalam memenuhi status gizi bayi.
ABSTRACT
The prevalence of bad and worst malnutrition of children under five in Amplas Health Centre Medan city was increased respectively in 2008, 2009 and 2010 period. In 2008, it was found worst malnutrition for 17 (0,3%) children under five, and less malnutrition for 69 (1,3%). In 2009, it was found bad malnutrition for 22 (0,45) children under five and 96 (1,95) children under five and in 2010, it was found bad malnutrition for 27 (0,5%) children under five and less malnutrition for 116 (2,1%) children under five.
The objective of this research was to analyze the influence of complementary mother’s milk feeding pattern (type of food, eating frequency, amount of energy and protein consumption at the first time of mother’s milk feeding) on the nutrient status of children under five aged 6-12 old months in Medan Amplas District, Medan City. This research was survey explanatory, conducted on May through July 2011.
The results of research showed that the pattern of complementary feeds action include additional types of food, the consumption of energy and protein intake and meal frequency influence on the nutritional status of infants 6-12 months (p <0.05). The age for the first time of mother’s milk feeding did not have influence on nutrient status for the children under five aged 6-12 old months (p>0,05) in Medan Amplas District, Medan City.
The population were all mothers with children aged 6-12 old months for 3,457 persons and the sample was taken for 100 mothers. Data the influence of companion mother’s milk feeding pattern collection were collected through interview referring to the questionnaire and 24-hour food recall. The nutritional status of infants measured by the index weight / age according to reference who-2005. The data were analyzed using Logistics Regression test.
It is suggested to Medan District Health Office and related institution to encourage and maintain exclusive mother’s milk feeding as well as to give counselling continuously regarding the type of food with good nutrient, inexpensive and easy to get in their surrounding. Various food management practice should be carried out in Integrated Health Service Centre for the socialization of good food nutrient to be applied in family to fulfill the status of nutrient of children under five.
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Peningkatan kualitas hidup manusia dimulai sedini mungkin sejak masih bayi.
Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas
manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI semaksimal mungkin
merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan anak dan persiapan generasi
penerus di masa depan (Depkes RI, 2004)
Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang
pesat, sehingga kerap diistilahkan sebagai ”periode emas” sekaligus ”periode kritis”.
Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh
asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Sebaliknya apabila bayi dan
anak pada masa ini tidak memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizinya, maka
periode emas akan berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu tumbuh
kembang bayi dan anak, baik pada saat ini maupun masa selanjutnya (Depkes, 2006).
Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, di dalam Global Strategi For
Infant and Young Child Feeding, WHO/UNICEF merekomendasikan empat hal
penting yang harus dilakukan yaitu pertama memberikan Air Susu Ibu kepada bayi
segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, kedua memberikan hanya Air Susu
Ibu (ASI) saja atau pemberian ASI secara Eksklusif sejak lahir sampai bayi
sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan. Dan keempat meneruskan pemberian ASI
sampai anak berusia 24 bulan atau lebih (Depkes RI, 2006).
Masa pertumbuhan bayi berumur 6-12 bulan membutuhkan asupan gizi tidak
hanya cukup dengan ASI saja, karena produksi ASI pada saat itu semakin berkurang
sedangkan kebutuhan bayi semakin meningkat seiring bertambahnya umur dan berat
badan, oleh karena itu bayi harus mendapat makanan pendamping selain
ASI (MP-ASI) untuk menutupi kekurangan zat-zat gizi yang terkandung di dalam
ASI. Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang jenis dan cara mengolah makanan
bayi dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan gizi pada bayi (Krisnatuti, 2006).
ASI memiliki manfaat yang sangat besar, maka sangat disayangkan bahwa
pada kenyataan penggunaan ASI Eksklusif belum seperti yang diharapkan. Hal ini
disebabkan karena ibu sibuk bekerja dan hanya diberi cuti melahirkan selama tiga
bulan. Selain itu masih banyak ibu yang beranggapan salah sehingga tidak menyusui
secara Eksklusif, karena ibu takut dengan menyusui akan merubah bentuk payudara
menjadi jelek, dan takut badan akan menjadi gemuk. Dengan alasan inilah ibu
memberikan makanan pendamping ASI, karena ibu merasa ASI nya tidak mencukupi
kebutuhan gizi bayinya sehingga ibu memilih susu formula karena lebih praktis
(Roesli, 2002).
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Departemen Kesehatan sudah lama
mencanangkan anjuran bagi para ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada
bayinya, tapi pelaksanaan anjuran tersebut masih jauh dari harapan. Masih banyak ibu
Indonesia sudah mendapat MP-ASI secara dini pada umur kurang dari satu bulan.
Bahkan pada umur 2-3 bulan bayi ada yang sudah mendapat makanan padat (Irawati,
2005).
Jenis makanan prelakteal yang diberikan cukup beragam antar daerah
tergantung kebiasaan di daerah tersebut. Pada riskesdas 2010 jenis makanan
prelakteal yang paling banyak diberikan kepada bayi baru lahir yaitu susu formula
sebesar (71,3%), Madu (19,8%) dan air putih (14,6%). Jenis yang termasuk kategori
lainnya meliputi kopi, santan, biscuit, kelapa muda dan kurma (Riskesdas, 2010).
Berdasarkan Riskesdas 2010, persentase bayi yang menyusui Eksklusif
sampai dengan 6 bulan adalah 15,3%. Inisiasi menyusu dini kurang dari satu jam
setelah bayi lahir adalah 29,3%, tertinggi di Nusa Tenggara Timur 56,2% dan
terendah di Maluku 13,0% sedangkan di Sumatera Utara 20,2%. Sebagian besar
proses mulai menyusui dilakukan pada kisaran waktu 1-6 jam setelah bayi lahir tetapi
masih ada 11,1% proses mulai disusui dilakukan setelah 48 jam. Cakupan ASI
eksklusif di Indonesia masih rendah jauh dari rata-rata dunia yaitu sebesar 38%.
Pencapaian program pemberian ASI eksklusif di propinsi Sumatera Utara
pada tahun 2008 sebesar 36,72%. Hasil ini masih dibawah target nasional yaitu
sebesar 80% (Dinkes Propinsi Sumatera Utara, 2009)
Sedangkan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif kota Medan pada
tahun 2009 adalah sebesar 1,32%, masih sangat rendah dibandingkan pencapaian
Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara dini sangatlah
berbahaya, apalagi jika disajikan tidak secara higienis karena menyebabkan
masuknya berbagai jenis kuman,. Bayi yang mendapatkan MP-ASI sebelum berumur
enam bulan lebih banyak terserang diare, sembelit, batuk pilek, dan panas
dibandingkan bayi yang hanya mendapatkan ASI eksklusif. Selain itu pemberian
makanan padat secara dini akan menyebabkan kerusakan saluran pencernaan dan
menimbulkan penyumbatan saluran pencernaan (Lily L, 2005).
Menurut WHO pemberian MP-ASI harus sesuai dengan waktu pemberian
yang tepat, memadai, aman untuk dikonsumsi. Bayi yang diberi MP-ASI dalam
waktu yang semakin awal memiliki kecenderungan mempunyai status gizi yang
kurang dibandingkan dengan bayi yang diberikan MP-ASI tepat pada waktunya yaitu
mulai usia enam bulan (Depkes RI, 2000).
Beberapa penelitian menyatakan bahwa keadaan kurang gizi pada bayi dan
anak disebabkan karena kebiasaan memberikan MP-ASI yang tidak tepat. Keadaan
ini memerlukan penanganan tidak hanya penyediaan pangan, tetapi dengan
pendekatan yang lebih komunikatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan
kemampuan masyarakat. Selain itu ibu-ibu kurang menyadari bahwa setelah bayi
berumur 6 bulan memerlukan MP-ASI dalam jumlah dan mutu yang semakin
bertambah, sesuai dengan pertambahan umur bayi dan kemampuan alat cerna nya.
Pemberian makanan tambahan pada bayi sebaiknya diberikan setelah usia
bayi lebih dari enam bulan atau setelah pemberian ASI eksklusif karena pada usia
mendapatkan makanan tambahan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi seperti
infeksi telinga dan pernapasan, diare, resiko alergi, gangguan pertumbuhan dan
perkembangan bayi (Arisman, 2004).
Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa ibu-ibu tidak memberikan ASI
secara Eksklusif tetapi lebih memilih memberikan susu formula atau makanan
tambahan pada bayi kurang dari enam bulan. Karena masih banyak ibu-ibu yang
belum mengetahui manfaat pemberian ASI secara Eksklusif. Sebagian ibu
menganggap bahwa dengan memberikan makanan tambahan akan memenuhi
kebutuhan gizi bayi dan bayi tidak akan merasa kelaparan. Hal ini berbahaya dilihat
dari sistem pencernaan bayi belum sanggup mencerna atau menghancurkan makanan
secara sempurna (Boedihardjo, 1994).
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2002) menyatakan bahwa
persentase ibu yang memberikan makanan tambahan terlalu dini kepada bayi usia 2-3
bulan sebanyak (32%) dan bayi 4-5 bulan sebanyak (69%) di Indonesia. Sejalan
dengan hal ini, hasil penelitian padang (2007) menyatakan bahwa sebesar 52,15%
bayi sudah mendapat makanan tambahan di bawah usia enam bulan di Kecamatan
Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baso (2007) dalam Pardosi (2009)
mengenai studi pertumbuhan bayi yang diberi makanan pendamping ASI Pabrik dan
Non Pabrik di Kabupaten Gowa. Di dapatkan bahwa makanan pendamping ASI
Pabrik telah diberikan sejak bayi berusia kurang dari empat bulan (54,4%) dan
pendamping ASI non pabrik yang diberikan adalah buah (0,5%) dan bubur (0,6%).
Sedangkan jenis makanan pabrik adalah susu. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa makanan pendamping ASI pabrik lebih banyak digunakan.
Menurut Manalu (2008) menyatakan bahwa sebagian besar anak sudah
diberikan makanan tambahan sebelum umur 5 bulan yaitu sebesar 80,49% dan yang
paling rendah adalah pada umur 5-7 bulan yaitu sebesar 19,51%. Adapun MP-ASI
yang diberikan adalah nasi bubur dengan tambahan garam,atau nasi bubur dengan
lauk, atau nasi keras dengan sayur saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
frekuensi makan anak yang terbanyak adalah 2x sehari yaitu sebesar 63,41% dan
yang terendah adalah 1x sehari sebesar 9,76%. Dari hasil penelitian didapat bahwa
anak yang frekuensi makannya sedikit memiliki status gizi yang tidak baik.
Survei pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan November 2010
dengan beberapa ibu –ibu yang tinggal di kecamatan Medan Amplas adalah bahwa
rata-rata mereka sudah memberikan MP-ASI pada bayinya pada saat umur satu atau
dua bulan dengan pisang, bubur nasi atau MP-ASI pabrikan, susu formula, alasan
nya mereka takut bayinya kurang kenyang dan kurang gizi bila hanya diberikan ASI
saja. Data yang diperoleh dari Puskesmas Amplas tahun 2008 berdasarkan indeks
BB/U gizi buruk sebanyak 17 balita (0,3%) dan gizi kurang 69 Balita (1,3%), pada
tahun 2009 gizi buruk 22 balita (0,4%) dan gizi kurang 96 balita (1,9%) dan pada
tahun 2010 gizi buruk 27 balita (0,5%) dan gizi kurang sebanyak 116 orang (2,1%).
Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh
pola pemberian MP-ASI (jenis makanan, konsumsi energi protein, frekuensi makan,
usia pertama kali pemberian MP-ASI) terhadap status gizi pada bayi 6-12 bulan di
1.2. Permasalahan
Adanya pemberian MP-ASI yang terlalu dini pada bayi dengan pisang, bubur
nasi atau MP-ASI pabrikan, rendah nya cakupan ASI Eksklusif serta tinggi nya status
gizi kurang pada bayi di Kecamatan Medan Amplas, sehingga ingin diteliti
bagaimana pengaruh pola pemberian MP-ASI terhadap status gizi pada bayi 6-12
bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tahun 2011.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisa pengaruh pola pemberian Makanan Pendamping ASI (jenis makanan,
jumlah energi protein, frekuensi makan, dan waktu pertama kali pemberian MP-ASI)
terhadap status gizi bayi 6-12 bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tahun
2011.
1.4. Hipotesis
Ada pengaruh pola pemberian Makanan Pendamping ASI (jenis makanan,
konsumsi energi protein, frekuensi makan, dan umur pertama kali pemberian
MP-ASI) terhadap status gizi pada bayi 6-12 bulan di Kecamatan Medan Amplas Kota
Medan
1.5. Manfaat Penelitian
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara yang benar dalam
2. Memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota
Medan, dalam membuat perencanaan program Makanan Pendamping ASI
dalam perbaikan gizi, dan bagi petugas kesehatan untuk memberikan bantuan
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
Makanan Pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung
zat gizi, diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan
gizi selain dari Air Susu Ibu (Depkes RI, 2006). Makanan pendamping ASI ini
diberikan pada bayi karena pada masa itu produksi ASI semakin menurun sehingga
suplai zat gizi dari ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi anak yang semakin
meningkat sehingga pemberian dalam bentuk makanan pelengkap sangat dianjurkan
(WHO, 2000).
Makanan tambahan berarti memberi makanan lain selain ASI dimana selama
periode pemberian makanan tambahan seorang bayi terbiasa memakan makanan
keluarga. Pemberian makanan tambahan merupakan proses transisi dari asupan yang
semata berbasis susu menuju ke makanan yang semi padat. Untuk proses ini juga
dibutuhkan keterampilan motorik oral. Keterampilan motorik oral berkembang dari
refleks menghisap menjadi menelan makanan yang berbentuk bukan cairan dengan
memindahkan makanan dari lidah bagian depan ke lidah bagian belakang
(Depkes, 2000).
Istilah untuk makanan pendamping ASI bermacam-macam yakni makanan
pelengkap, makanan tambahan, makanan padat, makanan sapihan, weaning food,
makanan peralihan, beiskot (istilah dalam bahasa jerman yang berarti makanan selain
pengertian bahwa ASI maupun pengganti ASI (PASI) untuk berangsur berubah ke
makanan keluarga atau orang dewasa (Depkes RI, 2004).
2.1.1 Jenis Makanan Tambahan
a. Makanan tambahan lokal
Makanan tambahan lokal adalah makanan tambahan yang diolah di rumah
tangga atau di Posyandu, terbuat dari bahan makanan yang tersedia setempat, mudah
diperoleh dengan harga terjangkau oleh masyarakat, dan memerlukan pengolahan
sebelum dikonsumsi oleh bayi. Makanan tambahan lokal ini disebut juga dengan
makanan pendamping ASI lokal (MP-ASI Lokal) (Depkes RI, 2006).
Pemberian makanan tambahan lokal memiliki beberapa dampak positif, antara
lain ibu lebih memahami dan terampil dalam membuat makanan tambahan dari
pangan lokal sesuai dengan kebiasaan dan sosial budaya setempat, sehingga ibu dapat
melanjutkan pemberian makanan tambahan secara mandiri, meningkatkan partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kelembagaan seperti posyandu,
memiliki potensi meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil
pertanian, dan sebagai sarana dalam pendidikan atau penyuluhan gizi
(Depkes RI, 2006).
b. Makanan tambahan olahan pabrik
Makanan tambahan hasil olahan pabrik adalah makanan yang disediakan
dengan olahan dan bersifat instan dan beredar dipasaran untuk menambah energi dan
Makanan tambahan pabrikan disebut juga makanan pendamping ASI pabrikan
(MP-ASI pabrikan) atau makanan komersial. Secara komersial, makanan bayi
tersedia dalam bentuk tepung campuran instan atau biskuit yang dapat dimakan
secara langsung atau dapat dijadikan bubur (Krisnatuti, 2000).
Sunaryo (1998) dalam Krisnatuti (2000) menyatakan bahwa untuk membuat
makanan bayi harus memenuhi petunjuk dan mempertimbangkan hal-hal berikut:
1) Formula
Formula harus dibuat berdasarkan angka kecukupan gizi bayi dan balita, bahan baku
yang diizinkan, criteria zat gizi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.
2) Proses Teknologi
Pemilihan proses teknologi berkaitan dengan spesifikasi produk yang
diinginkan, tingkat sanitasi dan higienitas yang dikehendaki, faktor keamanan
pangan, serta mutu akhir produk.
3) Higiene
Produk jadi makanan tambahan harus memenuhi syarat-syarat seperti bebas
dari mikroorganisme pathogen, bebas dari kontaminan hasil pencemaran mikroba
penghasil racun atau alergi, bebas racun, harus dikemas tertutup sehingga terjamin
sanitasinya dan disimpan di tempat yang terlindung.
4) Pengemasan
Kemasan yang dipakai harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak beracun,
tidak mempengaruhi mutu inderawi produk (dari segi penampakan, aroma, rasa dan
5) Label
Persyaratan label makanan bayi harus mengikuti codex standard 146-1985,
dengan informasi yang jelas, tidak menyesatkan konsumen, komposisi bahan-bahan
tercantum dalam kemasan, nilai gizi produk dan petunjuk penyajian.
Makanan tambahan pabrikan seperti bubur susu diperdagangkan dalam
keadaan kering dan pre-cooked, sehingga tidak perlu dimasak lagi dan dapat
diberikan pada bayi setelah ditambah air matang seperlunya.
Bubur susu terdiri dari tepung serealia seperti beras, maizena, terigu ditambah
susu dan gula, dan bahan perasa lainnya. Makanan tambahan pabikan yang lain
seperti nasi tim yakni bubur beras dengan tambahan daging, ikan atau hati serta
sayuran wortel dan bayam, dimana untuk bayi kurang dari 10 bulan nasi tim harus
disaring atau di blender terlebih dahulu. Selain makanan bayi lengkap (bubur susu
dan nasi tim) beredar pula berbagai macam tepung baik tepung mentah maupun yang
sudah matang (pre-cooked) (Pudjiadi, 2000).
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Pemberian Makanan Tambahan
Tujuan pemberian makanan pendamping ASI adalah untuk menambah energi
dan zat-zat gizi yang diperlukan bayi karena ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan
bayi secara terus menerus, untuk mencapai pertumbuhan perkembangan yang
optimal, menghindari terjadinya kekurangan gizi, mencegah resiko masalah
gizi, defesiensi zat gizi mikro (zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C dan
folat), menyediakan makanan ekstra yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan
sakit, membantu perkembangan jasmani, rohani, psikomotor, mendidik kebiasaan
yang baik tentang makanan dan memperkenalkan bermacam-macam bahan makanan
yang sesuai dengan keadaan fisiologis bayi (Husaini, 2001).
Pemberian makanan tambahan pada bayi juga bertujuan untuk melengkapi
ASI (mixed feeding) dan diperlukan setelah kebutuhan energy dan zat-zat gizi tidak
mampu dipenuhi dengan pemberian ASI saja. Pemberian makanan tambahan
tergantung jumlah ASI yang dihasilkan oleh ibu dan keperluan bayi yang bervariasi
dalam memenuhi kebutuhan dasarnya diantaranya untuk mempertahankan kesehatan
serta pemulihan kesehatan setelah sakit, untuk mendidik kebiasaan makan yang baik
mencakup penjadwalan waktu makan, belajar menyukai makanan (Sembiring, 2009).
Menurut Suharjo (1999) dalam Pardosi (2009) Pemberian MP-ASI
bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan zat gizi anak, menyesuaikan kemampuan alat
cerna dalam menerima makanan tambahan dan merupakan masa peralihan dari ASI
ke makanan keluarga. Selain untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi,
pemberian makanan tambahan merupakan salah satu proses pendidikan dimana bayi
diajar untuk mengunyah dan menelan makanan padat, serta membiasakan
selera-selera baru.
2.1.3 Komposisi Makanan Tambahan
Makanan tambahan yang baik adalah makanan yang kaya energy, protein dan
mikronutrien (terutama zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C dan
fosfat), bersih dan aman, tidak ada bahan kimia yang berbahaya atau toksin, tidak ada
panas atau asin, mudah dimakan bayi, disukai bayi, mudah disiapkan dan harga
terjangkau (Rosidah, 2004).
Bahan makanan tambahan pada bayi dibedakan atas 2 golongan yaitu hewani
dan nabati. Golongan hewani terdiri dari ikan, telur, daging. Golongan nabati terdiri
dari buah-buahan, sayur-sayuran, padi-padian (Baso, 2007).
Makanan tambahan yang baik adalah makanan yang mengandung sejumlah
kalori atau energi (karbohidrat, protein dan lemak), vitamin, mineral dan serat untuk
pertumbuhan dan energi bayi, disukai oleh bayi, mudah disiapkan dan harga yang
terjangkau. Makanan harus bersih dan aman, terhindar dari pencemaran
mikroorganisme dan logam, serta tidak kadaluarsa (Kepmenkes RI, 2007).
Karbohidrat diperlukan sebagai sumber energi yang paling murah, untuk
mencukupi kebutuhan energi dianjurkan sekitar 60-70% energi total berasal dari
karbohidrat. Pada ASI dan sebagian besar susu formula bayi, 40-50% kandungan
kalorinya berasal dari karbohidrat terutama laktosa (Krisnatuti, 2000).
Protein ASI rata-rata 1,15g/100ml sehingga apabila bayi mengkonsumsi ASI
selama 4 bulan pertama (sekitar 600-900ml/hari). Pertambahan Protein pada bayi
yang diberi MP-ASI pertama kali ( usia 6-12 bulan) pertambahan Protein nya tidak
terlalu besar. Semakin bertambah usia bayi maka protein yang dibutuhkan semakin
meningkat. Setelah menginjak usia satu tahun bayi membutuhkan protein sekitar dua
kali lipat pada masa sebelum nya (Krisnatuti, 2000). Kacang-kacangan merupakan
sumber protein nabati yang baik untuk bayi dan sebagai bahan campurannya
Lemak merupakan sumber energi dengan konsentrasi tinggi. Lemak berfungsi
sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta member
rasa gurih dan sedap pada makanan. Apabila energi dan protein sudah terpenuhi maka
kecukupan gizi lemak yang dianjurkan tidak dicantumkan karena secara langsung
kecukupan lemak sudah terpenuhi (Krisnastuti, 2000).
Vitamin yang dibutuhkan terdiri dari vitamin yang larut dalam lemak dan
vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D,
E, dan K, sedangkan yang larut dalam air adalah vitamin vitamin C, B1, Riboflavin,
Niasin, B6, B12, asam folat, dan vitamin lain yang tergolong vitamin B kompleks
(Krisnastuti, 2000). ASI tidak mengandung vitamin D dalam konsentrasi yang
dibutuhkan bayi. Vitamin ini secara alami dihasilkan oleh kulit ketika terpapar sinar
matahari, dan bila bayi sering berjemur di daerah panas atau matahari beberapa kali
seminggu maka kulitnya akan menghasilkan semua vitamin D yang dibutuhkan bayi
(Satyanegara, 2004).
Mineral dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Unsur Fe (besi) dan
I (iodium) merupakan 2 jenis mineral bayi yang jarang terpenuhi yang mengakibatkan
anemia dan gondok. Bayi tidak dilahirkan dengan cadangan zat besi yang memadai
yang akan melindungi bayi dari anemia. Jika bayi diberi ASI maka kebutuhan zat
besinya dapat terpenuhi sehingga tidak dibutuhkan tambahan. Setelah bayi berumur 6
bulan, bayi harus mulai diberikan makanan yang mengandung zat besi (sereal,
pertumbuhan yang sehat (Satyanegara, 2004). Jenis mineral lainnya yang dibutuhkan
bayi seperti kalsium, fosfor dan seng (Krisnastuti, 2000).
2.2. Pola Pemberian Makanan Tambahan
Air Susu Ibu (ASI) memenuhi seluruh kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi
yaitu untuk pertumbuhan dan kesehatan sampai berumur enam bulan, sesudah itu ASI
tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan bayi. Makanan tambahan mulai diberikan umur
enam bulan satu hari. Pada usia ini otot dan saraf di dalam mulut bayi cukup
berkembang dan mengunyah, menggigit, menelan makanan dengan baik, mulai
tumbuh gigi, suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut nya dan berminat terhadap
rasa yang baru (Rosidah,2004).
Makanan tambahan yang baik adalah kaya energi, protein, dan mikronutrien
(terutama zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat), bersih dan aman,
tersedia didaerah anda dan harga terjangkau serta mudah disiapkan (Depkes, 2006).
Jumlah zat gizi yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh bayi dapat dilihat pada
setiap Recommended Dietary Allowance (RDA) yang telah diestimasikan berdasarkan
Tabel 2.1 Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Anak Indonesia
Standar Berat Badan UMUR
Tinggi Badan dan Kecukupan Zat Gizi
Sumber: (Widya Karya Pangan dan Gizi, 2004)
Angka kebutuhan diatas bukanlah suatu kebutuhan minimum dan maksimum,
akan tetapi dapat dipakai untuk mengetahui tingkat konsumsi dari suatu populasi.
2.2.1 Risiko /Dampak Pemberian MP-ASI Dini
Risiko pemberian makanan tambahan pada bayi usia kurang dari enam bulan
berbahaya karena pemberian makanan yang terlalu dini dapat menimbulkan solute
load hingga dapat menimbulkan hyperosmolality, kenaikkan berat badan yang terlalu
cepat dapat menyebabkan obesitas, alergi terhadap salah satu zat gizi yang terdapat
dalam makanan yang diberikan pada bayi. Bayi yang mendapat zat-zat tambahan
dalam makanan padat yang dipasarkan terdapat zat pewarna atau zat pengawet yang
membahayakan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan (Pudjiadi, 2000).
Pemberian makanan tambahan pada bayi sebelum umur tersebut akan
menimbulkan risiko sebagai berikut (Ariani, 2008):
a) Seorang anak belum memerlukan makanan tambahan saat ini, makanan tersebut
dapat menggantikan ASI, jika makanan diberikan maka anak akan minum ASI
lebih sedikit dan produksi ASI ibu akan lebih sedikit sehingga akan lebih sulit
untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak.
b) Anak mendapat faktor perlindungan dari ASI lebih sedikit sehingga resiko infeksi
meningkat.
c) Risiko diare meningkat karena makanan tambahan tidak sebersih ASI.
d) Makanan yang diberikan sebagai pengganti ASI sering encer, bubur nya berkuah
dan sup karena mudah dimakan bayi, makanan ini memang membuat lambung
penuh tetapi memberikan nutrient sedikit.
e) Ibu mempunyai risiko lebih tinggi untuk hamil lagi.
Pemberian makanan padat terlalu dini sering dihubungkan dengan
meningkatnya kandungan lemak dan berat badan pada anak-anak. Makanan tambahan
yang diberikan pada bayi cenderung mengandung protein dan lemak tinggi sehingga
pada akhirnya akan berdampak pada konsumsi kalori yang tinggi dan mengakibatkan
2.2.2 Faktor –faktor yang Memengaruhi Pemberian MP-ASI
Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian makanan pendamping ASI
yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan penduduk, sosial ekonomi, begitu pula
faktor kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang turun temurun
mengenai pemberian MP-ASI pada bayi.
1. Tingkat Pengetahuan
Menurut Notoatmojo (2000), pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi
setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap subyek tertentu. Pengetahuan ibu
adalah faktor yang penting dalam pemberian makanan tambahan pada bayi karena
dengan pengetahuan yang baik, ibu tahu kapan waktu pemberian makanan yang tepat.
Pengetahuan dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan orang lain, media
cetak media elektronik, atau penyuluhan-penyuluhan. Pengetahuan didukung oleh
pendidikan karena pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan semua
aspek kepribadian manusia meliputi pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan
sehingga terjadi perubahan perilaku yang positif.
Ketidaktahuan tentang akibat pemberian makanan pendamping ASI dini dan
cara pemberian nya serta kebiasaan yang merugikan kesehatan, secara langsung
maupun tidak langsung menjadi penyebab masalah gizi kurang pada anak, khususnya
pada anak dibawah 2 tahun (DepKes, 2000).
2. Tingkat pendidikan
Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian, mengembangkan
Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi dan keterampilan tetapi
diperluas ruang lingkup nya sehingga mencakup usaha mewujudkan kehidupan
pribadi sosial yang memuaskan. Makin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan
keterampilan maka terdapat kemungkinan makin baik tingkat ketahanan pangan
keluarga, makin baik pola pengasuhan anak, makin mengerti waktu yang tepat
memberikan makanan tambahan bagi bayi serta mengerti dampak yang ditimbulkan
jika makanan tersebut diberikan terlalu dini. Ibu yang berpendidikan akan memahami
informasi dengan baik penjelasan yang diberikan oleh petugas kesehatan, selain itu
tidak akan terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas.
3. Sosial Ekonomi
Status sosial ekonomi berhubungan erat dengan pekerjaan dan pendapatan
orang tua yang nanti nya bepengaruh terhadap konsumsi energi. Ibu yang bekerja
akan berpengaruh terhadap pola asuh anak, ibu menjadi kurang perhatian dan kurang
dekat dengan anak karena sebagian besar waktu siang digunakan untuk bekerja diluar
rumah. Selain itu pemberian ASI untuk bayipun semakin berkurang.
Orang tua yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai daya beli
yang lebih tinggi pula, sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk memilih
berbagai jenis makanan. Adanya peluang tersebut mengakibatkan pemilihan jenis
makanan dan jumlah makanan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan dan
pertimbangan kesehatan, termasuk pada pemberian makanan pendamping ASI bagi
Pemberian makanan pendamping ASI terlalu dini bisa terjadi karena orang tua
terlalu sibuk dengan pekerjaan diluar rumah dan pengasuhan anak diserahkan kepada
orang lain. Banyak sekali orang tua yang memberikan makanan pendamping sebelum
usia 6 bulan. Umumnya banyak ibu yang beranggapan bahwa jika anak nya kelaparan
diberi makanan akan tidur nyenyak belum lagi anggapan masyarakat seperti orang tua
terdahulu bahwa anak mereka dulu yang diberi makanan pada umur 2 bulan sampai
sekarang dapat hidup sehat, alasan lain bahwa saat ini gencarnya promosi makanan
bayi yang belum mengindahkan ASI eksklusif sampai 6 bulan (Lily, 2005).
2.3. Pola Pemberian Makanan Pada Bayi
Pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang/sekelompok orang untuk
memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis,
psikologis, budaya dan sosial (Suhardjo, 1986).
Menurut Kartini (2006), yang mengutip pendapat Lie goan hong menyatakan
pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam
dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan merupakan
cirri khas untuk satu kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan menurut baliwati
(2004) pola konsumsi makan adalah susunan jenis dan jumlah makanan yang
dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu.
2.3.1 Pola Makan pada Bayi Usia 0-6 Bulan
Tahun pertama khususnya enam bulan pertama, adalah masa yang sangat
dengan cepat, tetapi juga pembentukan psikomotor dan akulturasi terjadi dengan
cepat. ASI harus merupakan makanan utama pada masa ini. Biasanya makanan
tambahan ASI diperlukan pada trimerter ke dua yaitu pada anak setelah berumur
enam bulan.
ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi, berikanlah ASI saja sampai bayi
berumur 6 bulan (ASI Eksklusif). Kontak fisik dan hisapan bayi akan merangsang
produksi ASI terutama 30 menit pertama setelah lahir. Pada periode ini ASI saja
sudah dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi (Depkes, 2000).
Kolustrum harus segera diberikan kepada bayi ,walaupun jumlah nya sedikit
namun sudah memenuhi kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama. Sebaiknya
jangan memberikan makanan atau minuman seperti air kelapa, air tajin, air the, madu,
pisang, dan lain-lain) pada bayi sebelum diberikan ASI karena sangat membahayakan
kesehatan bayi dan mengganggu keberhasilan menyusui.
Pada umumnya bayi yang baru lahir mempunyai jadwal makan yang tidak
teratur, bayi bisa makan sebanyak 6-12 kali atau lebih dalam 24 jam tanpa jadwal
yang teratur. Menyusui bayi dapat dilakukan setiap 3 jam alasannya karena lambung
bayi akan kosong dalam waktu 3 jam sehabis menyusui. Sejalan dengan
bertambahnya usia jarak antara waktu menyusui menjadi lebih lama, karena kapasitas
Beberapa contoh menu sehat makanan untuk bayi sesuai dengan kebutuhan
gizi seperti berikut:
Tabel 2.2 Jadwal Pemberian Makanan Tambahan Menurut Umur Bayi, Jenis Makanan, dan Frekuensi Pemberian Makanan
Usia Bayi Jenis Makanan Berapa Kali Sehari
0-6 bulan ASI 10-12 kali sehari
6-7 bulan ASI Saat dibutuhkan
Buah lunak/sari buah
Bubur: bubur havermout/bubur tepung beras merah
1-2 kali
7-9 bulan ASI Saat dibutuhkan
Buah-buahan
Hati ayam atau kacang-kacangan Beras merah atau ubi
Sayuran (wortel, bayam) Minyak/santan/advokad Air tajin
3-4 kali
9-12 bulan ASI Saat dibutuhkan
Buah-buahan Sari buah tanpa gula
4-6 kali
12-24 bulan ASI Saat dibutuhkan
Makanan pada umumnya, termasuk telur dengan kuning telurnya dan jeruk
4-6 kali
Tabel 2.3 Jadwal Pemberian Makanan Tambahan pada Bayi (Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia /IDAI)
0-6 bulan 6-7 bulan 7-9 bulan 9-12 bulan > 12 bulan
Pukul 06.00
ASI on demand
ASI ASI/PASI ASI/PASI ASI/PASI
Pukul
ASI ASI/PASI ASI/PASI ASI/PASI
Sumber: Sembiring T, dkk (2009)
2.3.2 Pola Makan pada Bayi Usia 6-12 Bulan (ASI dan MP-ASI)
Seorang bayi untuk tumbuh dan menjadi lebih aktif, gizi nya tidak cukup
sampai umur 6 bulan. Setelah itu produksi ASI semakin berkurang sedangkan
kebutuhan bayi semakin meningkat seiring bertambah umur dan berat badannya.
Makanan tambahan yang baik adalah kaya energi, protein, dan mikronutrien
(terutama zat besi, zink, kalsium, vitamin A, vitamin C dan folat), bersih dan aman,
tidak terlalu pedas atau asin, mudah dimakan oleh anak, disukai anak, harga
terjangkau dan mudah disiapkan (Depkes RI, 2006).
Walaupun bayi telah diperkenalkan dengan makanan tambahan sebagai tahap
awal, perkenalkan dengan bubur dan sari buah dua kali sehari sebanyak 1-2 sendok
makan penuh. Frekuensi pemberian bubur ini, lambat laun harus ditingkatkan.
Menginjak umur 7-9 bulan porsi kebutuhannya dapat ditingkatkan yaitu sebanyak 3-6
sendok penuh tiap kali makan, paling tidak empat kali sehari keadaan bubur harus
tetap disaring, apabila bayi masih tampak lapar dapat diberi makanan kecil misalnya
roti kering, pisang. Pada umur 9 bulan berikan bubur yang tidak disaring atau nasi tim
yang dibuat dari bahan makanan bergizi tinggi (WHO, 2004).
Menginjak usia 10-12 bulan bayi sudah dapat diberi bubur yang dicacah untuk
mempermudah proses penelanan. Setelah berumur satu tahun bayi mulai mengenal
makanan yang dimakan oleh seluruh anggota keluarga. Seorang bayi harus makan 4-5
kali sehari. Makanan anak harus terdiri dari makanan pokok, kacang-kacangan,
Tabel 2.4 Makanan Tambahan Anak Usia 6 – 24 bulan
Tekstur Semi-cair
(dihaluskan atau
Frekuensi Makanan Utama: 1-2x/hari
2.4. Status Gizi Bayi
Keadaan gizi adalah keadaan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan
penyerapan zat gizi dan penggunaan zat-zat gizi tersebut atau keadaan fisiologis
akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh. Sehingga status gizi dapat
diartikan sebagai ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel
tertentu, atau perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tertentu
(Supariasa dkk, 2002).
Status gizi merupakan suatu keadaan tubuh yang disebabkan konsumsi
makanan dan penggunaan zat gizi. Status gizi seseorang dipengaruhi oleh jumlah dan
jenis yang dikonsumsi dan penggunaan nya dalam tubuh. Apabila konsumsi makanan
dalam tubuh terganggu dapat mengakibatkan status gizi jelek dan biasanya disebut
kurang gizi (Almatsier, 2004).
2.4.1 Penilaian Status Gizi pada Anak
Penilaian status gizi pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan
gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat objektif
maupun subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku yang telah tersedia
(Arisman, 2006)
Menurut Supariasa dkk (2001), penilaian status gizi dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu: penilaian status gizi secara langsung dan penilaian status gizi secara
1. Penilaian status gizi secara langsung
Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi empat penilaian yaitu :
1. Secara antropometri : dengan mengukur berat badan, tinggi badan, atau mengukur
bagian tubuh seperti lingkar atas, lingkar kepala, tebal lapisan lemak dan lain-lain.
2. Secara klinis : dengan pemeriksaan keadaan jasmani oleh dokter atau orang yang
sudah terlatih. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang
dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal tersebut dapat dilihat pada
jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau organ-organ yang
dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.
3. Secara biokimia : dengan pemeriksaan specimen yang diuji secara laboratoris
yang dilakukan pada berbagai jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan
antara lain: urine, tinja, darah, beberapa jaringan tubuh lain seperti hati dan otot.
4. Secara biofisik : dengan melihat kemampuan fungsi (khusus nya jaringan) dan
melihat perubahan struktur dari jaringan.
2. Penilaian status gizi secara tidak langsung
Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi 3 penilaian yaitu :
1. Survei konsumsi makanan: Adalah suatu metode penentuan status gizi secara
tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.
Kesalahan dalam survei makanan bisa disebabkan oleh perkiraan yang tidak tepat
dalam menentukan jumlah makanan yang dikonsumsi balita, kecenderungan
yang bernilai sosial tinggi, keinginan melaporkan konsumsi vitamin dan mineral
tambahan kesalahan dalam mencatat (food record).
2. Statistik vital: Adalah dengan cara menganalisa data beberapa statistik kesehatan
seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat
penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.
3. Faktor Ekologi: malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi
beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang
tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dll.
2.4.2. Penilaian Status Gizi Secara Antropometri
Di masyarakat, cara pengukuran status gizi yang paling sering digunakan
adalah antropometri gizi. Antropometri telah lama dikenal sebagai indikator untuk
penilaian status gizi perseorangan maupun masyarakat. Pengukuran antropometri
dapat dilakukan oleh siapa saja dengan hanya memerlukan latihan yang sederhana
(Depkes, 2000).
Selain itu pengukuran antropometri memiliki metode yang tepat, akurat
karena mempunyai ambang batas dan rujukan yang pasti, pengukuran antropometri
juga mempunyai prsedur yang sederhana dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel
yang besar (Supariasa, 2002)
Indeks yang umum digunakan dalam menilai status gizi adalah berat badan
menurut umur (BB/U), Tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut
1. Berat badan menurut umur (BB/U)
Berat badan adalah satu parameter yang sangat sensitif terhadap
perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya
nafsu makan, atau menurunnya makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah
parameter antropometri yang sangat labil, oleh sebab itu indeks BB/U lebih
menggambarkan status gizi seseorang saat ini.
2. Tinggi badan menurut umur (TB/U)
Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan
pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan
pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif
kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek.
Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang
relatif lama. Indeks TB/U disamping menggambarkan status gizi masa lalu, juga erat
kaitannya dengan status sosial ekonomi.
3. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)
Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam
keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi
badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik
untuk menilai status gizi saat ini. Indeks BB/TB adalah indeks yang independen
terhadap umur.
Penggunaan berat badan dan tinggi badan akan lebih jelas dan sensitif/peka
BB/TB, menurut standar WHO bila prevalensi kurus/wasting < -2SD diatas 10%
menunjukkan suatu daerah tersebut mempunyai masalah gizi yang sangat serius dan
berhubungan langsung dengan angka kesakitan.
Tabel 2.5 Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standar Baku Antropometri Menurut WHO 2005
No Indeks yang
dipakai Status Gizi Keterangan
1 BB/U Berat Badan Normal
Berat Badan Kurang
Berat Badan Sangat Kurang
Zscore ≥ -2 sampai 1
Zscore >2 sampai 3 Zscore >1 sampai 2 Zscore ≥ -2 sampai 1 Zscore < -2 sampai -3 Zscore < -3
Sumber : Interpretasi Indikator Pertumbuhan Depkes 2008
2.4.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Gizi Pada Bayi
Status gizi dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi
di dalam tubuh. Bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara
efisien akan tercapai status gizi optimal yang memungkinkan pertumbuhan
fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat
setinggi mungkin (Almatsier, 2001).
Ada dua faktor yang berperan dalam menentukan stautus gizi seseorang yaitu
1. Faktor Gizi Internal
Faktor gizi internal adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pemenuhan
tingkat kebutuhan gizi seseorang, yaitu nilai cerna makanan, status kesehatan, status
fisiologis, kegiatan, umur, jenis kelamin dan ukuran tubuh. Secara langsung status
gizi dipengaruhi oleh asupan gizi dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak.
Kedua penyebab langsung ini sangat terkait dengan pola asuh anak yang diberikan
oleh ibu/pengasuh nya. Dan penyebab tidak langsung adalah ketahanan pangan di
keluarga, Pola pengasuhan anak serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan.
Ketiga faktor ini saling terkait dengan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan
keluarga (Dinkes Sumatera Utara, 2010)
2. Faktor Gizi Eksternal
Faktor gizi eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh diluar diri
seseorang, yaitu daya beli keluarga, latar belakang sosial budaya, tingkat pendidikan
dan pengetahuan gizi, jumlah anggota keluarga dan kebersihan lingkungan.
2.5. Pola Makan dan Status Gizi
Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Kondisi
status gizi baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang akan
digunakan secara efesien, sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan fisik,
perkembangan otak, kemampuan kerja untuk mencapai tingkat kesehatan optimal
(Roesli, 2005). Hal ini sesuai dengan penelitian Munawaroh (2006) di Kabupaten
Pekalongan yang menyatakan bahwa Balita dengan pola makan yang tidak baik
mempunyai resiko untuk mengalami status gizi kurang 8,1 kali lebih besar dari pada
Menurut Manalu (2008) penelitian di Desa Palip Kecamatan Silima
Pungga-pungga Kabupaten Dairi. pada pengelompokan anak menurut pola makan diketahui
bahwa anak yang memiliki pola makan yang baik maka status gizi nya baik sebanyak
(86%), dan anak yang memiliki pola makan tidak baik tetapi ststus gizi nya baik
sebanyak (13,6%), sedangkan anak yang memiliki pola pola makan baik tetapi status
gizi nya tidak baik ada sebanyak (42,1%) dan anak yang memiliki pola makan tidak
baik dan status gizinya juga tidak baik ada sebesar (57,9%). Analisa statistik
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pola makan dengan status gizi
anak (p<0,05).
Berdasarkan hasil penelitian Mahlia Y (2009) di Kecamatan Pangkalan Susu
Langkat terlihat bahwa pola asuh makan menurut waktu pertama kali pemberian
MP-ASI ternyata pertumbuhan bayi yang tergolong tidak normal lebih banyak pada bayi
yang di beri MP-ASI kurang dari 6 bulan (85,5%). Dari hasil uji chi square
menunjukkan bahwa ada hubungan antara waktu pertama kali pemberian MP-ASI
terhadap pertumbuhan bayi.
2.6. Landasan Teori
Menurut WHO, terjadinya kekurangan gizi dalam hal ini gizi kurang dan gizi
buruk lebih di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni, penyakit infeksi dan asupan
makanan yang secara langsung berpengaruh terhadap kejadian kekurangan gizi, pola
asuh serta pengetahuan ibu juga merupakan salah satu faktor yang secara tidak
Faktor yang menyebabkan kurang gizi telah di perkenalkan UNICEF dan
telah digunakan secara international, yang meliputi beberapa tahapan penyebab
timbulnya kurang gizi pada anak balita, baik penyebab langsung dan tidak
langsung, akar masalah dan pokok masalah. Berdasarkan Soekirman dalam materi
Aksi Pangan dan Gizi nasional (Depkes RI, 2000), penyebab kurang gizi dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Pertama, penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang
mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan yang
kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi
karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi. Demikian pula
anak yang makannya tidak cukup cukup baik maka daya tahan tubuh akan melemah
dan mudah terserang penyakit. Kenyataan nya baik makanan maupun penyakit secara
bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi.
Kedua, penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola
asuh, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Ketahanan pangan adalah
kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga
dalam jumlah yang cukup dan baik mutu nya. Pola pengasuhan adalah kemampuan
keluarga untuk menyediakan waktunya, perhatian dan dukungan terhadap anak agar
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial.
Pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan adalah tersedianya air bersih dan sarana
Status gizi anak balita dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Unicef (1998),
penyebab kurang gizi pada anak balita sebagaimana terlihat pada gambar 2.1.
Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan
Gambar 2.1. Penyebab Kurang Gizi pada Anak (Unicef, 1998)
Makanan tidak seimbang Infeksi wanita dan keluarga, kurang
2.7. Kerangka Konsep
Berdasarkan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka di atas, maka dapat
disusun kerangka konsep penelitian ini sebagai berikut :
Variabel Independen Variabel Dependen
Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian Pola Pemberian MP-ASI
- Jenis Makanan Tambahan - Jumlah Energi
Protein
- Frekuensi Makan - Usia Pertama kali
diberi Makanan Tambahan
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei explanatory research dengan
desain cross sectional yang bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel
penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya (Singarimbun, 1989).
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dengan
pertimbangan bahwa di Kecamatan Medan Amplas pencapaian program ASI
eksklusif nya 1,7% apabila dibandingkan dengan target pencapaian sebesar 80%
maka persentase pencapaian ASI Eksklusif di kecamatan Medan Amplas masih
sangat rendah, disamping itu juga tinggi nya praktek pemberian MP-ASI dini pada
bayi kurang dari 6 bulan. Untuk kasus gizi kurang di Kecamatan Medan Amplas ada
116 kasus gizi kurang (5,4%) apabila tidak ditangani secara serius akan menjadi gizi
buruk (Dinkes Medan, 2010).
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2011.
3.3. Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi
berusia 6-12 bulan yang berdomisili di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tahun