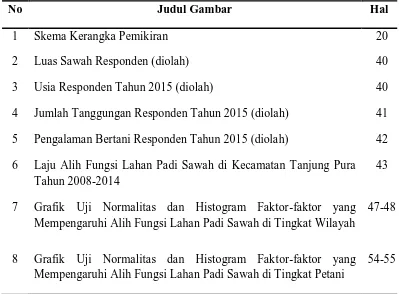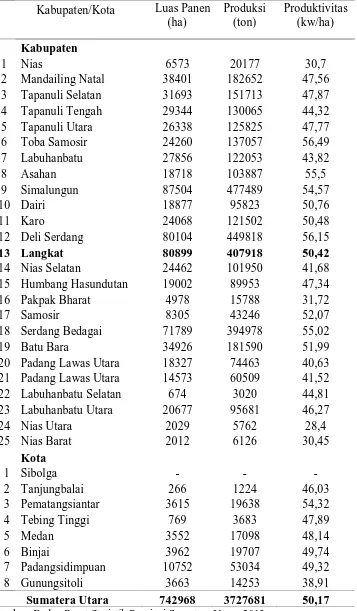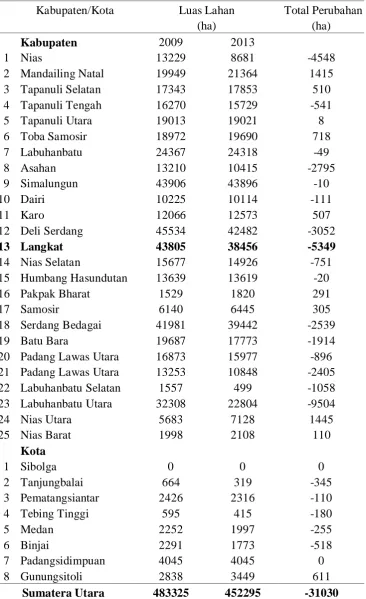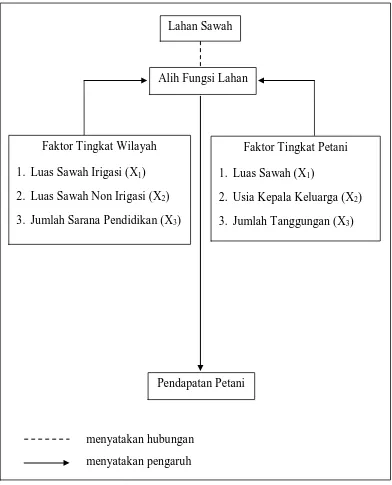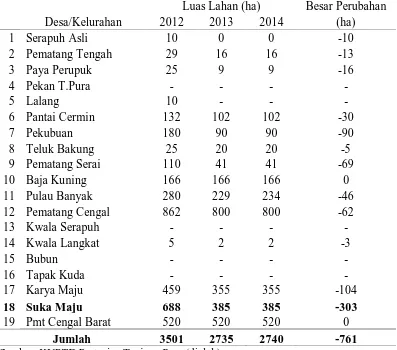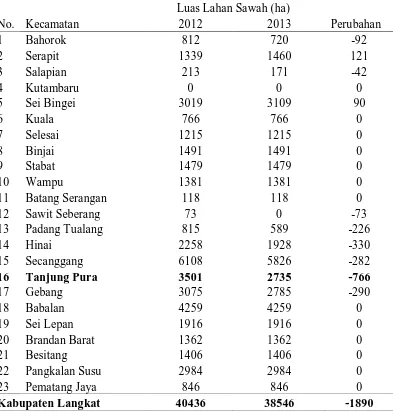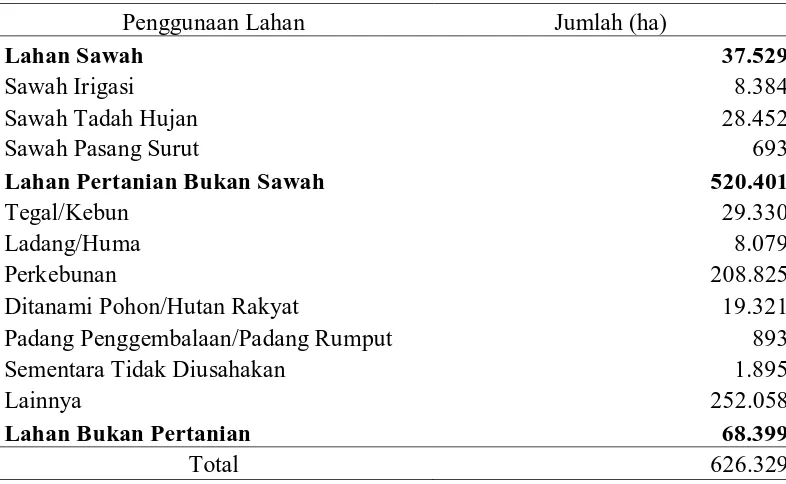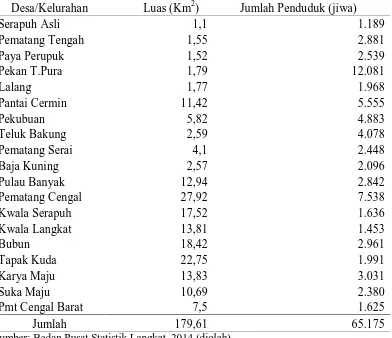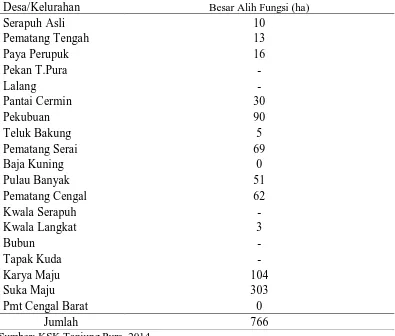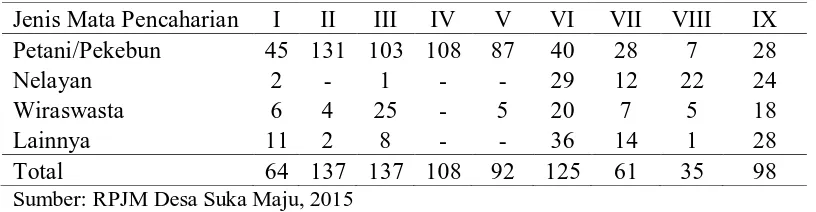TERHADAP PENDAPATAN PETANI
(Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)
___ __ SKRIPSI
OLEH :
ADE REZKIKA NASUTION
110304074
AGRIBISNIS
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
TERHADAP PENDAPATAN PETANI
(Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)
________ SKRIPSI
OLEH :
ADE REZKIKA NASUTION 110304074
AGRIBISNIS
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat melakukan Penelitian Di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian,
Universitas Sumatera Utara, Medan
Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing
Ketua Anggota
Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA NIP. 194608021973011001 NIP. 197008272008122001
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
ADE REZKIKA NASUTION (110304074) dengan judul skripsi “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani” Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS dan Ibu Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan menganalisis pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap pendapatan petani di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penentuan daerah penelitian secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder dengan jumlah sampel 30 orang petani padi sawah yang pernah melakukan alih fungsi lahan padi sawah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan uji beda rata-rata menggunakan alat bantu SPSS 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan padi sawah memiliki rata-rata sebesar 7,58% pada tahun 2008-2014. Berdasarkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat wilayah diperoleh nilai Koefisien Determinasi (Rsquared) sebesar 80,80% yang menunjukkan bahwa variabel luas sawah irigasi, jumlah sarana pendidikan, luas sawah dan laju pertumbuhan penduduk dapat menerangkan keragaman variabel penurunan luas lahan padi sawah sebesar 80,80%. Nilai signifikansi F-hitung 0,049 < 0,05, artinya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Secara parsial hanya variabel sarana pendidikan dan luas sawah yang berpengaruh nyata. Sedangkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat petani diperoleh nilai Koefisien Determinasi (Rsquared) sebesar 74,70% yang menunjukkan bahwa variabel luas sawah, usia kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, hama dan proporsi pendapatan padi sawah terhadap total pendapatan rumah tangga dapat menerangkan keragaman variabel alih fungsi lahan padi sawah sebesar 74,70%. sedangkan sisanya yaitu 26,30% diterangkan oleh variabel lainnya diluar model. Nilai signifikansi F-hitung 0,000 < 0,05, artinya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Secara parsial hanya variabel luas sawah yang berpengaruh nyata. Tidak terjadi multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas serta asumsi normalitas terpenuhi.
Penulis lahir di Kota Binjai pada tanggal 31 Agustus 1993 dari ayah H.
Darmansyah Nasution dan ibu Hj. Wardah Sagala, SE. Penulis merupakan anak
bungsu dari dua bersaudara.
Penulis mengikuti pendidikan sebagai berikut:
1. Sekolah Dasar di Yayasan Pendidikan Ahmad Yani Binjai tahun 1999-2005.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Binjai tahun 2005-2008.
3. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Binjai tahun 2008-2011.
4. Tahun 2011 masuk di Departemen Agribisnis FP USU melelui jalur ujian
tertulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
5. Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli 2014 di Desa
Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
6. Melaksanakan Penelitian pada bulan Mei 2015 sampai dengan Juni 2015 di
Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah
serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH
FUNGSI LAHAN PADI SAWAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENDAPATAN PETANI” Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung
Pura Kabupaten Langkat.
Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi sebagian dari
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pertanian di Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan
bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:
1. Ayahanda tercinta H. Darmansyah Nasution dan Ibunda tercinta Hj. Wardah
Sagala, SE, saudara tersayang Agung Wardhana Nasution, AMd yang telah
memberikan doa dan begitu banyak perhatian, cinta, kasih sayang, serta
dukungan baik moril maupun materil bagi penulis dalam menyelesaikan
pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Sekali lagi teruntuk Ayahanda dan
Ibunda, tiada kata yang mampu mewakilkan ucapan terima kasih Ananda atas
doa, perjuangan dan pengorbanan yang tiada henti-hentinya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing
dan Ibu Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA sebagai Anggota Komisi Pembimbing
yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan
4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis
serta kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Departemen Agribisnis FP
USU.
5. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat
kepada saya selama penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat penulis Dila Armaya SH, Ipak Purnama Sari AMd, Mahdalin Husna
AMd, Nur Aisyah Ridha Pulungan AMd dan Faizil Hasanah.
7. Teman-teman seperjuangan penulis di Departemen Agribisnis Fakultas
Pertanian Universitas Sumatera Utara angkatan 2011 khususnya Sri Ayu
Wulandari Saragih, Mutiara Sani SP, Syari Syafrina SP, Annisa Azzahra SP,
Yuli Hariani Siregar SP, Dwi Utari, Maya Anggraini, Denti Juli Irawati, Risa
Januarti, Ade Silvana Sari, Sri Wahyuni SP, Novita S. Sinaga SP, M. Fadli
Nasution SP, Budi Ginting SP, M. Sidik Pramono, Daniel Siahaan, dan teman
semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas
dukungan, semangat dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua
pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima
kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Medan, Juni 2015
ABSTRAK ... i
2.3 Penelitian Terdahulu... 17
2.5 Kerangka Pemikiran ... 19
2.6 Hipotesis Penelitian ... 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian... 22
3.2 Metode Penentuan Sampel ... 23
3.3 Metode Pengumpulan Data ... 24
3.4 Metode Analisis Data ... 24
3.5 Definisi dan Batasan Operasional... 32
4.4 Karakteristik Umum Responden... 39
4.4.1 Luas Sawah... 39
4.4.2 Usia ... 40
4.4.3 Jumlah Tanggungan ... 41
4.4.4 Pengalaman Bertani ... 42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Laju Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Pura ... 43
5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah ... 44
5.2.1 Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Wilayah ... 44
5.2.2 Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Petani ... 50
5.3 Pengaruh Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Pendapatan Petani ... 59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 63
6.2 Saran ... 64
DAFTAR PUSTAKA
No Judul Tabel Hal
3 Luas Lahan Padi Sawah dan Perubahannya Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2012-2014 Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama (Agustus 2011)
35
6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Langkat Tahun 2014 35
7 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2013
37
8 Banyaknya Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Desa/Kelurahan Tahun 2013
37
9 Besarnya Alih Fungsi Lahan Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2013 38 10 Mata Pencaharian Penduduk Desa Suka Maju Tahun 2015 39 11 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alih Fungsi Lahan
Padi Sawah di Tingkat Wilayah
45
12 Proses Alih Fungsi Lahan Oleh Petani di Desa Suka Maju 51 13 Luas Sawah yang Mengalami Alih Fungsi di Desa Suka Maju 51 14
15
Luas Sawah yang dimiliki Petani Sebelum Melakukan Alih Fungsi Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Tingkat Wilayah
52 52
16 Perbandingan Rata-rata Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Sawah (Per Tahun)
No Judul Gambar Hal
1 Skema Kerangka Pemikiran 20
2 Luas Sawah Responden (diolah) 40
3 Usia Responden Tahun 2015 (diolah) 40
4 Jumlah Tanggungan Responden Tahun 2015 (diolah) 41
5 Pengalaman Bertani Responden Tahun 2015 (diolah) 42
6 Laju Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2008-2014
43
7 Grafik Uji Normalitas dan Histogram Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Tingkat Wilayah
47-48
8 Grafik Uji Normalitas dan Histogram Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Tingkat Petani
No Judul Lampiran
1 Laju Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Tanjung Pura
2 Proporsi Luas Sawah terhadap Luas Kecamatan Tanjung Pura
3 Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2008-2014
4 Perubahan Luas Lahan Padi Sawah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2013
5 Hasil Kuesioner Kepada Petani Desa Suka Maju yang Pernah Melakukan Alih Fungsi Sawah
6 Data Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Wilayah Kabupaten Langkat
7 Data Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Petani Desa Suka Maju
8 Hasil Analisis Data Sekunder Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Wilayah
9 Hasil Pengujian Normalitas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Wilayah
10 Grafik Scatterplot dalam menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas
11 Hasil Analisis Data Sekunder Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Petani
12 Hasil Pengujian Normalitas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Petani
13 Grafik Scatterplot dalam menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas
14 Pendapatan Petani Desa Suka Maju Sebelum dan Sesudah Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah
ADE REZKIKA NASUTION (110304074) dengan judul skripsi “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani” Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS dan Ibu Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan menganalisis pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap pendapatan petani di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penentuan daerah penelitian secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder dengan jumlah sampel 30 orang petani padi sawah yang pernah melakukan alih fungsi lahan padi sawah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan uji beda rata-rata menggunakan alat bantu SPSS 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan padi sawah memiliki rata-rata sebesar 7,58% pada tahun 2008-2014. Berdasarkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat wilayah diperoleh nilai Koefisien Determinasi (Rsquared) sebesar 80,80% yang menunjukkan bahwa variabel luas sawah irigasi, jumlah sarana pendidikan, luas sawah dan laju pertumbuhan penduduk dapat menerangkan keragaman variabel penurunan luas lahan padi sawah sebesar 80,80%. Nilai signifikansi F-hitung 0,049 < 0,05, artinya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Secara parsial hanya variabel sarana pendidikan dan luas sawah yang berpengaruh nyata. Sedangkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat petani diperoleh nilai Koefisien Determinasi (Rsquared) sebesar 74,70% yang menunjukkan bahwa variabel luas sawah, usia kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, hama dan proporsi pendapatan padi sawah terhadap total pendapatan rumah tangga dapat menerangkan keragaman variabel alih fungsi lahan padi sawah sebesar 74,70%. sedangkan sisanya yaitu 26,30% diterangkan oleh variabel lainnya diluar model. Nilai signifikansi F-hitung 0,000 < 0,05, artinya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Secara parsial hanya variabel luas sawah yang berpengaruh nyata. Tidak terjadi multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas serta asumsi normalitas terpenuhi.
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama
perekonomian nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil Sensus
Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebanyak
26,14 juta rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan
hukum sebanyak 4.209 perusahaan dan usaha pertanian lainnya sebanyak 5.982
unit. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, jumlah rumah tangga usaha
pertanian sebanyak 1,33 juta rumah tangga (5,09% dari total rumah tangga
pertanian di Indonesia). Subsektor tanaman pangan mendominasi rumah tangga
usaha pertanian (0,74 juta rumah tangga) di Sumatera Utara.
Pada 2014, pihak Dinas Pertanian Sumatera Utara menargetkan total produksi
padi mencapai sebanyak 3,9 juta ton. Angka itu lebih tinggi dari target tahun
sebelumnya yang hanya 3,7 juta ton per tahun. Sepanjang tahun 2014, total
produksi padi hingga bulan April mencapai 1.593.315 ton. Angka tersebut
merupakan hasil dari produksi sebanyak 31 kabupaten/kota yang ada dari total 33
Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi (Sawah dan Ladang)
15 Humbang Hasundutan 19002 89953 47,34
16 Pakpak Bharat 4978 15788 31,72
7 Padangsidimpuan 10752 53034 49,32
8 Gunungsitoli 3663 14253 38,91
Sumatera Utara 742968 3727681 50,17
Pada Tabel 1. tertulis bahwa pada tahun 2013 luas panen tertinggi dimiliki oleh
Kabupaten Simalungun seluas 87.504 ha, Langkat seluas 80.899 ha dan Deli
Serdang seluas 80.104 ha. Namun luas panen tertinggi kedua hanya menjadikan
Kabupaten Langkat sebagai produsen padi terbesar ketiga di Sumatera Utara
dengan produktivitas sebesar 50,42 kw/ha.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, produksi
padi pada tahun 2013 hanya meningkat sebesar 0,33% dari tahun 2012. Hal ini
meningkatkan produktivitas sebesar 3,32% dikarenakan penurunan luas panen
sebesar 2,89%.
Lahan merupakan salah satu fungsi produksi yang jumlahnya terbatas. Apabila
banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi non pertanian, hal ini
tentunya akan menyebabkan penurunan produksi pertanian. Ini dapat terjadi
karena input yang digunakan untuk proses produksi tersebut berkurang, sehingga
hasil yang akan didapatkan juga menurun.
Dengan adanya peran teknologi diharapkan dapat mengatasi penurunan produksi
pertanian, misalnya pengembangan sawah modern untuk meningkatkan produksi
padi. Lili Sunardi (2015) dalam artikelnya tertulis bahwa sawah modern yang
keseluruhan prosesnya menggunakan mesin dapat menghasilkan 8 ton gabah
kering per hektar. Sementara sawah yang digarap secara manual hanya
memproduksi 6,9 ton gabah per ha. Namun pengembangan sawah modern
membutuhkan investasi yang lebih tinggi, serta mengurangi penggunaan tenaga
Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan
fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang
direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah)
terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat
diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor
yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk
yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu
kehidupan yang lebih baik (Lestari, 2009).
Luas lahan sawah di Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar 452.295 ha. Dari
total lahan sawah tersebut, hanya 96,92% yang ditanami padi sedangkan sisanya
tidak diusahakan. Luas lahan sawah turun sebesar 2,70% atau sebesar 12.532 ha
dibandingkan luas lahan sawah pada tahun 2012. Dilihat perkembangan selama
lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan luas lahan sawah per tahun dari tahun
2008 sampai tahun 2013 sebesar -1,74% per tahun. Kondisi ini semakin
mencerminkan tingginya tingkat konversi lahan selama lima tahun terakhit ini di
Sumatera Utara (Bangun, 2013).
Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten
yang mengalami penurunan luas lahan pertanian khususnya lahan sawah.
Berdasarkan data Statistik Luas Lahan Sawah Provinsi Sumatera Utara, total
penurunan luas lahan sawah tertinggi (2009-2013) adalah Kabupaten Labuhanbatu
Utara seluas 9.504 ha. Sedangkan Kabupaten Langkat merupakan yang tertinggi
Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan Sawah Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2009-2013
Kabupaten/Kota Luas Lahan Total Perubahan
(ha) (ha)
Sumatera Utara 483325 452295 -31030
Berdasarkan hasil sensus Pertanian 2013, dari 18 sumber usaha di sektor
pertanian, tanaman padi merupakan salah satu sumber usaha dengan rata-rata
pendapatan rumah tangga yang rendah di Kabupaten Langkat (pada tahun 2012),
yaitu sebesar Rp 12.368.640 per tahun (sama dengan rata-rata pendapatan per
tahun dari pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar) dan hanya 6,76% dari
keseluruhan sumber usaha. Dengan peningkatan alih fungsi lahan di bidang
pertanian khususnya lahan sawah, maka kemungkinan akan memberikan dampak
terhadap pendapatan rumah tangga petani tersebut.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dirumuskan adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura
Kabupaten Langkat Tahun 2008-2014?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Desa
Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap pendapatan petani
di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan
sawah di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
3. Untuk menganalisis pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap
pendapatan petani di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura
Kabupaten Langkat.
3.4 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Sebagai bahan referensi atau sumber informasi ilmiah bagi pihak-pihak
yang membutuhkan.
2. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh pemda setempat
2.1 Tinjauan Pustaka
Alih fungsi atau konversi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam
pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya.
Alih fungsi lahan umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan
untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa
(Kustiawan (1997) dalam Puspasari (2012)).
Konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan
lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan
membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat
yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk
menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan
yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran
kesempatan kerja ke sektor non pertanian (Furi, 2007).
Menurut Barlowe (1978), faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan
adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi dan faktor
kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan
adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi,
pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan pengeluaran, selera dan tujuan, serta
Winoto (2005) mengungkapkan bahwa lahan pertanian yang paling rentan
terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh:
1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan
sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan
kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi,
2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah
perkotaan,
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah
persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering,
4. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, kawasan industri, dan
sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar.
Konversi lahan sawah adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia, bukan
suatu proses alami. Kita ketahui bahwa percetakan sawah dilakukan dengan biaya
tinggi, namun ironisnya konversi lahan tersebut sulit dihindari dan terjadi setelah
sistem produksi pada lahan sawah tersebut berjalan dengan baik. Konversi lahan
merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk
serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal
yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah
karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif (Anwar, 1993).
Menurut Yanis (2014), pada umumnya laju konversi lahan sawah yang tertinggi
terjadi pada hamparan sawah di sekitar perkotaan. Oleh karena berbagai aturan
dan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengendalikan konversi lahan
menimpa lahan-lahan sawah produktif dengan fasilitas irigasi yang baik.
Mengingat bahwa dimasa mendatang peluang untuk memperluas areal panen
semakin terbatas, maka konversi lahan sawah untuk jangka panjang sangat
berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional baik secara langsung maupun
tidak langsung. Secara langsung hal itu bersumber dari degradasi luas panen,
secara tidak langsung disebabkan menurunnya produktivitas hamparan lahan
sawah disekitarnya.
Ditinjau menurut prosesnya, konversi lahan sawah dapat pula terjadi: (1) secara
gradual; (2) seketika (instan). Alih fungsi secara gradual lazimnya disebabkan
fungsi sawah tidak optimal. Umumnya hal seperti ini terjadi akibat degradasi
mutu irigasi atau usaha tani padi di lokasi tersebut tidak dapat berkembang karena
kurang menguntungkan. Alih fungsi secara instan pada umumnya berlangsung di
wilayah sekitar urban, yakni berubah menjadi lokasi pemukiman atau kawasan
industri (Sumaryanto dkk, 1995).
Pola konversi lahan sawah dapat dipilah menjadi dua, yaitu sistematis dan
sporadis. Konversi lahan sawah untuk pembangunan kawasan industri, perkotaan,
kawasan pemukiman (real estate), jalan raya, kompleks perkantoran, dan
sebagainya mengakibatkan terbentuknya pola konversi yang sistematis. Lahan
sawah yang dikonversi pada umumnya mencakup suatu hamparan yang cukup
luas dan terkonsolidasi. Konversi lahan sawah yang dilakukan sendiri oleh
pemilik lahan sawah umumnya bersifat sporadis, luas lahan sawah yang
terkonversi kecil-kecil dan terpencar. Proses konversi lahan sawah bersifat
waktu yang relatif pendek cenderung berkonversi pula dengan luas yang
cenderung meningkat. Secara empiris progresifitas konversi lahan dengan pola
sistematis cenderung lebih tinggi daripada pola yang sporadis
(Direktorat Pangan dan Pertanian, 2006).
Sumaryanto dan Tahlim (2005) dalam Puspasari (2012) mengungkapkan bahwa
dampak negatif dari konversi lahan sawah adalah degradasi daya dukung
ketahanan pangan nasional, pendapatan pertanian menurun, dan meningkatnya
kemiskinan masyarakat lokal. Selain itu dampak lainnya adalah rusaknya
ekosistem sawah, serta adanya perubahan budaya dari agraris ke budaya urban
sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas.
Kini ancaman penurunan produksi padi di Indonesia semakin serius karena petani
mulai meninggalkan tanaman kebutuhan pokok itu. Mereka beralih ke tanaman
perkebunan, kelapa, dan kelapa sawit. Keinginan petani mengkonversi lahannya
dari sawah menjadi lahan perkebunan, khususnya kelapa dan kelapa sawit, sulit
dibendung karena lebih menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi (Hadi, 2004).
2.2 Landasan Teori
Alih Fungsi Lahan
Manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, use values
atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai personal use values. Manfaat ini
dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usahatani yang dilakukan pada
sumber daya lahan pertanian. Kedua, non use values dapat pula disebut sebagai
sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari
pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini
(Sumaryanto dan Tahlim (2005) dalam Puspasari (2012)).
Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata
pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan
keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk
mengakumulasikan modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu
negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang
saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang
tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam
memanfaatkan lahan (Puspasari, 2012).
Banyaknya sawah yang dikonversi menjadi pabrik atau perumahan dan prasarana
jalan menyebabkan kesempatan kerja di sawah berkurang. Ditambah lagi dengan
digunakannya alat-alat pertanian yang efektif menyebabkan pengangguran di desa
meningkat. Fenomena tersebut telah menciptakan pengurangan kebutuhan jumlah
tenaga kerja di sektor pertanian. Apalagi menyusutnya luas baku sawah telah
berdampak menurunnya kebutuhan tenaga kerja di sawah. Akan tetapi, dengan
mengecilnya satuan luas usaha tani, para petani justru mengurangi produktivitas
kerja mereka (Adiratma, 2004).
Adiratma (2004) menambahkan aspek sosial lainnya yang diakibatkan pleh
tingginya konversi lahan sawah adalah beralihnya kepemilikan sawah. Meskipun
di desa ke orang-orang kaya di kota. Akibat lainnya terhadap petani adalah
beralihnya status. Bila tetap ingin menjadi petani, mereka beralih status dari petani
pemilik penggarap menjadi petani penyakap. Luas garapannya pun menyusut.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah
Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi atau konversi lahan sawah ke
penggunaan non pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang
mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat wilayah yaitu faktor yang tidak
langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan konversi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani yaitu faktor-faktor
yang langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan alih fungsi
(Pakpahan (1993) dalam (Puspasari (2012)).
Selanjutnya Pakpahan (1993) membagi faktor yang mempengaruhi konversi lahan
sawah di tingkat wilayah yakni:
1. Faktor tidak langsung antara lain perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan
penduduk, arus urbanisasi dan konsistensi implementasi rencana tata ruang.
2. Secara langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana
transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan
sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.
Faktor langsung dipengaruhi oleh faktor tidak langsung, seperti pertumbuhan
penduduk akan menyebabkan pertumbuhan pemukiman, perubahan struktur
ekonomi ke arah industri dan jasa akan meningkatkan kebutuhan pembangunan
sarana transportasi dan lahan untuk industri, serta peningkatan arus urbanisasi
Sumaryanto dan Tahlim (2005) dalam Puspasari (2012) mengungkapkan bahwa
pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek:
1. Alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya
motif tindakan ada 3: (a) untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal,
(b) dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha, (c) kombinasi
dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha.
Pola alih fungsi lahan ini terjadi disembarang tempat, kecil-kecil, dan
tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan
sawah sekitarnya baru significant untuk jangka waktu lama.
2. Alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik menjual
kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonpertanian
atau kepada makelar. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi
dalam hamparan yang luas, terkonsentrasi, dan umumnya berkorelasi positif
dengan proses urbanisasi (pengotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap
eksistensi lahan sawah sekitarnya berlangsung cepat dan nyata.
Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat sementara. Jika
lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri,
maka alih fungsi lahan bersifat permanen. Akan tetapi, jika sawah tersebut
berubah menjadi perkebunan tebu, maka alih fungsi lahan tersebut bersifat
sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali.
Alih fungsi lahan permanen biasanya lebih besar dampaknya dari pada alih fungsi
Faktor yang berpengaruh terhadap proses alih fungsi lahan pertanian sawah, yaitu
(1) Faktor eksternal adalah faktor-faktor dinamika pertumbuhan perkotaan,
demografi maupun ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan sawah ke
penggunaan non pertanian, (2) Faktor-faktor Internal adalah kondisi sosial
ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan yang mendorong lepaskan
kepemilikan lahan, dan (3) Faktor Kebijaksanaan Pemerintah
(Kustiawan (1997) dalam Puspasari (2012)).
Menurut Widjanarko (2006) dalam Puspasari (2012) ada tiga kebijakan nasional
yang berpengaruh langsung terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian:
1. Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri sesuai Keputusan
presiden Nomor 53 Tahun 1989 yang telah memberikan keleluasaan kepada
pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan kawasan
industri dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar. Dampak
kebijakan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kebutuhan lahan sejak
tahun 1989, yang telah berorientasi pada lokasi subur dan menguntungkan
dari ketersediaan infrastruktur ekonomi.
2. Kebijakan pembangunan pemukiman skala besar dan kota baru. Akibat
penerapan kebijakan ini ialah munculnya spekulan yang mendorong minat
petani menjual lahannya.
3. Kebijakan deregulasi dalam hal penanaman modal dan perizinan sesuai Paket
Kebijaksanaan Oktober Nomor 23 Tahun 1993 memberikan kemudahan dan
penyederhanaan dalam pemrosesan perizinan lokasi. Akibat kebijakan ini
ialah terjadi peningkatan sangat nyata dalam hal permohonan izin lokasi baik
Pendapatan
Penerimaan adalah hasil penjualan dari sejumlah barang tertentu yang diterima
atas penyerahan sejumlah barang kepada pihak lain. Jumlah penerimaan di
defenisikan sebagai penerimaan dari penjualan barang tertentu yang diperoleh dari
jumlah barang yang terjual dikalikan dengan harga penjualan setiap satuan
(Soedarsono, 1995).
Menurut Soekartawi dkk (1994), pendapatan keluarga mencerminkan tingkat
kekayaan dan besarnya modal yang dimiliki petani. Pendapatan yang besar
mencerminkan dana yang besar dalam usahatani, sedangkan pendapatan yang
rendah dapat menyebabkan menurunnya infestasi dan upaya pemupukan modal,
pendapatan bersih petani adalah hasil kotor dari produksi yang dinilai dengan
uang kemudian hasil kotor tersebut dikurangi dengan biaya produksi dan biaya
pemasaran.
Rendahnya pendapatan petani disebabkan sempitnya luas lahan yang dimiliki dan
diolah. Di Provinsi sumatera Utara terdapat 58% adalah petani gurem yakni petani
yang memiliki luas lahan < 0,5 ha dan 66% petani mengerjakan lahannya sendiri
(Tafbu dkk, 2009).
Mardikanto (1990) menyatakan, bahwa rendahnya pendapatan petani selain
disebabkan oleh (1) sempitnya luas lahan usahatani yang dimiliki, (2) rendahnya
produktivitas usahatani karena keterbatasan peralatan dan teknologi yang
diterapkan serta keterbatasan petani kecil untuk menggunakan input-input modern
(seperti: benih, pupuk buatan dan pestisida), (3) sistem pemasaran yang seringkali
lain (di luar usahataninya) karena rendahnya pendidikan dan keterampilan yang
dimilikinya.
2.3 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang berjudul ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Padi Sawah Melakukan Alih Fungsi Lahan ke Komoditi Perkebunan (Studi Kasus:
Daerah Irigasi Namu Sira-Sira, Kabupaten Langkat)” oleh Matondang (2011) memilih 4 (empat) desa yaitu Desa Namu Ukur Utara, Desa Psr II
Purwobinganun, Desa Psr. VI Kwala Mencirim, Desa Emplasmen Kwala
Mencirim, dengan pertimbangan Daerah Irigasi Namu Sira-Sira merupakan
daerah irigasi akan tetapi di daerah ini mengalami alih fungsi lahan ke komoditi
perkebunan. Sampel petani dipilih dengan metode Simple Random Sampling yang
selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh
kesimpulan faktor yang paling mempengaruhi petani melakukan alih fungsi lahan
adalah perbedaan penerimaan usaha tani (padi, kakao dan sawit) dan
kecenderungan perkembangan harga padi sawah, kakao, dan sawit. Di samping itu
kecukupan air serta luas lahan yang dimiliki petani juga ikut mempengaruhi
keputusan petani untuk alih fungsi lahan.
Barokah et al (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Konversi
Lahan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Karanganyar”
menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan fungsi lahan sawah 0,120 hektar per
rumah tangga petani dari tahun 1998-2010, proporsi pendapatan usahatani
berkurang (8,30%) dari 42% menjadi 33,7% dan proporsi pendapatan luar
analisis uji t dengan α 5% menunjukkan pendapatan rumah tangga petani sebelum
konversi tidak sama dengan sesudah konversi lahan pertanian (pendapatan
bertambah Rp 1.482.000 per tahun). Metode yang digunakan dalam penelitian ini
untuk melihat perubahan pendapatan digunakan uji beda rata-rata.
Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani” oleh Puspasari (2010), alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang pada tahun 2001-2010
dipengaruhi faktor ditingkat wilayah dan faktor ditingkat petani. Faktor-faktor
ditingkat wilayah yang diduga mempengaruhi penurunan lahan sawah di
Kabupaten Karanganyar adalah laju pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah
industri, produktivitas padi sawah, proporsi luas lahan sawah terhadap luas
wilayah, dan kebijakan tata ruang wilayah. Variabel yang berpengaruh nyata
secara signifikan pada taraf 10% adalah jumlah industri dan proporsi luas lahan
sawah terhadap luas wilayah. Sedangkan faktor-faktor ditingkat petani yang
diduga mempengaruhi alih fungsi lahan adalah tingkat usia, lama pendidikan, luas
lahan, proporsi pendapatan sektor pertanian, tanggungan keluarga, pengalaman
bertani, dan produktivitas. Faktor yang berpengaruh nyata secara signifikan pada
taraf 5% adalah luas lahan, pada taraf 15% adalah tingkat usia, lama pendidikan,
dan pengalaman bertani. Pengaruh alih fungsi lahan terhadap pendapatan petani
tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf 5%. Namun tetap terjadi penurunan
total pendapatan (usahatani dan non usahatani) dari Rp 1.421.514,03 (sebelum
melakukan alih fungsi lahan) menjadi Rp 1.299.796,30 (setelah melakukan alih
2.4 Kerangka Pemikiran
Lahan merupakan input penting dalam proses produksi pertanian, khususnya
pertanian padi sawah. Semakin luas lahan, produksi yang dihasilkan juga akan
meningkat. Tidak hanya sebatas sektor pertanian, lahan juga merupakan modal
yang harus dimiliki untuk sektor lainnya. Misalnya sektor industri yang
membutuhkan lahan untuk membangun pabrik dan bangunan lainnya yang
diperlukan untuk kegiatan industri. Namun alangkah sayangnya jika lahan yang
digunakan adalah lahan yang dahulunya merupakan lahan sawah. Hal ini
kemungkinan dikarenakan terbatasnya lahan kosong, serta lokasi dan harga dari
lahan sawah yang dialihfungsikan tadi.
Adanya alih fungsi lahan sawah dapat mengubah pendapatan petani dikarenakan
adanya perubahan penggunaan lahan yang semula sawah menjadi lahan pertanian
lainnya maupun lahan pembangunan. Misalnya pendapatan seorang petani yang
awalnya memiliki lahan sawah seluas 2 ha akan berbeda dengan pendapatan
petani yang kemudian mengalihfungsikan 1 ha sawahnya menjadi lahan
perkebunan. Begitu pula dengan petani yang kemudian juga menggarap sawah
lain seluas 1 ha akan mengubah pendapatan dan status kepemilikannya.
Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah dibagi menjadi dua faktor,
yaitu faktor tingkat wilayah yang secara tidak langsung mempengaruhi keputusan
petani dalam melakukan alih fungsi lahan sawah dan faktor tingkat petani yang
secara langsung mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan alih fungsi
lahan sawah.
Skema faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah dan pengaruhnya
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran menyatakan pengaruh
Lahan Sawah
menyatakan hubungan Faktor Tingkat Wilayah
1. Luas Sawah Irigasi (X1)
2. Luas Sawah Non Irigasi (X2)
3. Jumlah Sarana Pendidikan (X3)
Alih Fungsi Lahan
Faktor Tingkat Petani
1. Luas Sawah (X1)
2. Usia Kepala Keluarga (X2)
3. Jumlah Tanggungan (X3)
2.5 Hipotesis Penelitian
Sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut:
1. Laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
meningkat setiap tahunnya,
2. Faktor tingkat wilayah (luas sawah irigasi, luas sawah non irigasi, jumlah
sarana pendidikan) dan faktor tingkat petani (luas sawah, usia kepala
keluarga, jumlah tanggungan keluarga) berpengaruh nyata terhadap alih
fungsi lahan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten
Langkat,
3. Terjadi perbedaan pendapatan petani padi sawah di Desa Suka Maju
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat akibat alih fungsi padi sawah
3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian
Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive memilih Kabupaten
Langkat dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten ini merupakan produsen
padi terbesar ketiga (2013) yang mengalami penurunan lahan sawah terbesar
kedua di Sumatera Utara (2009-2013). Kecamatan Tanjung Pura dan Desa Suka
Maju dipilih dengan alasan besarnya penurunan lahan sawah (2012-2014).
Tabel 3. Luas Lahan Padi Sawah dan Perubahannya Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2012-2014
Desa/Kelurahan
Luas Lahan (ha) Besar Perubahan
2012 2013 2014 (ha)
Tabel 4. Luas Lahan Sawah dan Perubahannya Menurut Kecamatan Tahun
Kabupaten Langkat 40436 38546 -1890
Sumber: Statistik Luas Lahan Sawah Provinsi Sumatera Utara (diolah)
3.2 Metode Penentuan Sampel
Metode penentuan sampel penelitian dengan Metode Accidental (penelusuran).
Dengan metode accidental sample ini, sampel yang diambil dari siapa saja yang
kebetulan ada. Pengambilan sampel penelitian melalui metode ini adalah dari
petani padi sawah yang lahannya pernah mengalami alih fungsi. Adapun jumlah
petani yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 30 petani yang berada di
3.3 Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden di
daerah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi
terkait, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat
Statistik Kabupaten Langkat, Dinas Pertanian dan instansi lain yang terkait di
daerah penelitian ini.
3.4 Metode Analisis Data
Masalah (1) dianalisis dengan cara menghitung laju alih fungsi lahan pada
periode 2008-2014 di Kecamatan tanjung Pura Kabupaten Langkat. Cara ini
dengan menggunakan persamaan yang digunakan oleh Astuti (2011) dalam
Puspasari (2012):
V = Laju alih fungsi lahan (%)
Lt = Luas lahan tahun ke-t (ha)
Lt-1 = Luas lahan sebelumnya (ha)
Masalah (2) atau hipotesis (1) dianalisis dengan menggunakan Analisis Regresi
Linier Berganda, yaitu dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi alih
fungsi lahan sawah di daerah penelitian, mencakup faktor tingkat wilayah dan
faktor tingkat petani.
Persamaan model regresi linear berganda untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi alih fungsi lahan sawah pada tingkat wilayah adalah sebagai
Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3 + ε
Dimana:
Y = Penurunan luas lahan padi sawah (ha)
α = Intersep
X1 = Luas Sawah Irigasi (ha)
X2 = Luas Sawah Non Irigasi (ha)
X3 = Jumlah sarana pendidikan (unit)
βi = Koefisien Regresi
ε = Eror Term
Sedangkan persamaan model regresi berganda untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi alih fungsi lahan sawah pada tingkat petani adalah sebagai berikut:
Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3 + ε
Dimana:
Y = Penurunan lahan sawah akibat alih fungsi lahan sawah (ha)
Α = Intersep
X1 = Luas sawah sebelum melakukan alih fungsi (ha)
X2 = Usia kepala keluarga saat melakukan alih fungsi (tahun)
X3 = Jumlah tanggungan saat melakukan alih fungsi (jiwa)
βi = Koefisien Regresi
ε = Eror Term
Model analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis yang
didasarkan pada metode Ordinary Least Square (OLS). Konsep dari metode least
(error). Ordinary least square (OLS) dapat menduga koefisien regresi dengan
baik karena: (1) memiliki sifat tidak bias dengan varians yang minimum (efisien)
baik linear maupun bukan, (2) konsisten, dangan meningkatknya ukuran sampel
maka koefisien regresi mengarah pada nilai populasi yang sebenarnya, serta (3) β0
dan β1 terdistribusi secara normal (Gujarati 2002).
Sebagai langkah awal pengujian dilakukan pengujian ketelitian dan kemampuan
model regresi. Pengujian model regresi diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari
tiga pengujian, yaitu uji koefisien determinasi (R-squared), Uji F, dan Uji t.
1. Uji Koefisien Determinasi (R-squared)
Nilai R-squared mencerminkan seberapa besar keragaman dari variabel dependent
yang dapat diterangkan oleh variabel independent. Nilai R-squared memiliki
besaran yang positif dan besarannya adalah 0 < squared < 1. Jika nilai
R-squa red bernilai nol maka artinya keragaman variabel dependent tidak dapat
dijelaskan oleh variabel independent-nya. Sebaliknya, jika nilai R-squared
bernilai satu maka keragaman dari variabel dependent secara keseluruhan dapat
diterangkan oleh variabel independent-nya secara sempurna (Gujarati, 2002).
Rsquared dapat dirumuskan sebagai berikut:
ESS = Explained of Sum Squared
TSS = Total Sum of Squared
2. Uji t
Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi masing-masing variabel
terhadap variabel dependent-nya. Adapun prosedur pengujiannya yang diungkap
Gujarati (2002):
H0: β1 = 0
H1: β1≠ 0
b = Parameter dugaan
βt = Parameter Hipotesis
Seβ = Standar error parameter β
Jika t hitung (n-k) < t tabel α/2, maka H0 diterima, artinya variabel berarti variabel
(Xi) tidak berpengaruh nyata terhadap (Y). Namun, jika t hitung (n-k) > t tabel
α/2, maka H0 ditolak, artinya variabel (Xi) berpengaruh nyata terhadap (Y).
3. Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent atau bebas (Xi)
secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau terikat (Y).
Adapun prosedur yang digunakan dalam uji F (Gujarati, 2002):
H0= β1= β2= β3= .... = βi = 0
H1= minimal ada satu βi≠ 0
JKR = Jumlah Kuadrat Regresi
JKG = Jumlah Kuadrat Galat
k = jumlah variabel terhadap intersep
Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa
variabel bebas (Xi) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y).
Sedangkan apabila F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima yang
berarti bahwa variabel (Xi) berpengaruh nyata terhadap variabel (Y). Model yang
dihasilkan dari regresi linear berganda haruslah baik. Jika tidak baik maka akan
mempengaruhi interpretasinya. Interpretasi ini menjadi tidak benar apabila
terdapat hubungan linear antara variabel bebas
(Nachrowi et a l., 2002).
Namun, agar diperoleh model regresi linear berganda yang baik, maka model
harus memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). BLUE dapat
dicapai bila memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan pengujian
pada model yang telah berbentuk linear untuk mendapatkan model yang baik.
Setelah model diregresikan kemudian dilakukan uji penyimpangan asumsi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah model tersebut baik atau tidak.
Model dikatakan baik jika mempunyai distribusi normal atau hampir normal. Uji
yang dapat digunakan adalah Uji Kolmogorov-Smirnov.
Hipotesis pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:
H0 : Error term terdistribusi normal.
H1 : Error term tidak terdistribusi normal.
Dengan kriteria uji :
Jika P-value < α maka tolak H0
Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan
persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat lain. Penerapan pada uji
Kolmogorov-Smirnov adalah jika signifikansi di atas 5 persen berarti tidak
terdapat pebedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal
baku, artinya data tersebut normal.
b. Uji Autokorelasi
Menurut Nachrowi et al. (2002), autokorelasi adalah adanya korelasi antara
variabel itu sendiri, pada pengamatan berbeda waktu dan individu. Umumnya,
kasus autokorelasi terjadi pada data time series. Ada beberapa cara yang dapat
digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Salah satu cara yang
digunakan adalah Uji Durbin Watson (DW-test). Uji ini hanya digunakan untuk
autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya
intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel
penjelas. Jika pengujian autokorelasi diabaikan, maka akan berdampak terhadap
pengujian hipotesis dan proses peramalan. Besarnya nilai statistik DW dapat
diperoleh dengan rumus (Nachrowi et al., 2002):
d = statistik Durbin-Watson
ut dan ut-1 = Gangguan estimasi
Pengambilan keputusannya:
− Jika nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.
− Jika DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.
− Jika nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
− Jika nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
c. Uji Multikolinearitas
Jika suatu model regresi berganda terdapat hubungan linear sempurna antar
peubah bebas dalam model tersebut, maka dapat dikatakan model tersebut
mengalami multikolinearitas. Terjadinya multikolinearitas menyebabkan
Rsquared tinggi namun tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t. Ada
berbagai cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala
multikolinearitas. Salah satu cara yang digunakan adalah uji Varian Infiaction
Fa ctor (VIF). Cara ini sangat mudah, hanya melihat apakah nilai VIF untuk
masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai VIF lebih besar
dari 10 maka diindikasikan model tersebut mengalami multikolinearitas.
Sebaliknya, jika VIF lebih kecil dari 10 maka diindikasikan bahwa model tersebut
tidak mengalami multikolinearitas yang serius.
d. Uji Heteroskedastisitas
Asumsi penting dari regresi linear klasik adalah bahwa gangguan yang muncul
heteroskedastisitas terjadi jika ragam sisaan tidak sama untuk tiap pengamatan kei
dari peubah-peubah bebas dalam model regresi. Masalah heteroskedastisitas
biasanya sering terjadi dalam data cross section. Salah satu cara dalam mendeteksi
heteroskedastisitas adalah dengan transformasi terhadap peubah respon dilakukan
dengan tujuan untuk menjadikan ragam menjadi homogen pada peubah respon
hasil transformasi tersebut. Namun, dalam mendeteksi terjadinya
heteroskedastisitas dalam model dapat digunakan juga metode grafik.
Masalah (3) atau hipotesis (2) dianalisis dengan menggunakan uji beda rata-rata.
Perubahan pendapatan dilihat dari perubahan pendapatan rumah tangga petani
sebelum dan sesudah melakukan alih fungsi lahan.
Persamaan uji T adalah sebagai berikut:
X1 = Rata-rata pendapatan petani sebelum terjadinya alih fungsi lahan sawah
X2 = Rata-rata pendapatan petani setelah terjadinya alih fungsi lahan sawah
n1 = Jumlah petani sebelum terjadinya alih fungsi lahan sawah
n2 = Jumlah petani setelah terjadinya alih fungsi lahan sawah
s1 = Standar deviasi sebelum terjadinya alih fungsi lahan sawah
s2 = Standar deviasi setelah terjadinya alih fungsi lahan sawah
Hipotesis:
H0 = X1 = X2
Apabila thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak ada
perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan.
Sedangkan apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti ada
perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan.
3.5 Defenisi dan Batas Operasional
Defenisi
1. Pertanian adalah seluruh kegiatan manusia dalam mengelola sumberdaya
alam hayati. Pada penelitian ini, lahan pertanian yang diteliti adalah lahan
sawah.
2. Alih fungsi lahan adalah peralihan fungsi lahan padi sawah menjadi komoditi
lainnya atau menjadi non pertanian.
3. Produksi padi adalah total produksi padi di Kabupaten Langkat/Kecamatan
Tanjung Pura/Desa Suka Maju yang dihitung dalam ton.
4. Luas lahan adalah luas lahan sawah yang dipakai untuk komoditi padi dimana
termasuk lahan sawah irigasi teknis dan non teknis yang dihitung dalam
satuan ha.
5. Pendapatan rumah tangga petani adalah pendapatan yang diperoleh dari
kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan
diluar usahatani.
6. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan
7. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat
melakukan kegiatan diluar usahatani seperti berdagang, menarik becak,
merantau dan lain-lain.
Batasan Operasional
1. Daerah penelitian adalah Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
2. Waktu penelitian adalah tahun 2015.
3. Data luas lahan sawah menggunakan data sekunder dari tahun 2004-2014
Kabupaten Langkat.
4. Luas lahan pertanian dibatasi hanya pada lahan padi sawah saja.
5. Pendapatan yang diperhitungkan dilihat dari perubahan pendapatan rumah
4.1 Kabupaten Langkat
Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
Secara geografis, wilayah Kabupaten langkat berada pada 3014’ 00” – 4013’ 00” Lintang Utara dan 970 52’ 00” – 980 45’ 00” Bujur Timur. Wilayah ini mempunyai ketinggian 4–105 m dari permukaan laut.
Luas wilayah Kabupaten Langkat ±6.263,29 km2 atau 626.329 ha. Luas wilayah
tersebut merupakan 8,74% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data
dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada tahun 2014, sebagian besar lahan di
Kabupaten Langkat merupakan lahan pertanian bukan sawah yaitu sebesar
83,09% atau 520.401 ha. Sedangkan lahan sawah hanya sebesar 6% atau 37.529
ha yang terdiri dari lahan sawah irigasi (22%), tadah hujan (76%) dan pasang
surut (2%) dan sisanya adalah lahan bukan pertanian.
Pada tahun 2013 Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan jumlah
desa seluruhnya 240 desa serta 37 kelurahan definitif. Batas-batas wilayah
Kabupaten Langkat secara geografis sebagai berikut:
• Sebelah Utara : Provinsi Aceh dan Selat Malaka
• Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai
• Sebelah Selatan : Kabupaten Karo
Jumlah penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2013 sebanyak 978.734 jiwa
(menurut hasil proyeksi penduduk 2010) dengan kepadatan penduduk 156,27 jiwa
per km2.
Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama (Agustus 2011)
Berusaha Sendiri 81.742 17,42
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar 76.977 16,40
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar 16.750 3,57
Buruh/Karyawan/Pegawai 150.100 31,98
Pekerja Bebas Di Pertanian 21.397 4,56
Pekerja Bebas Di Nonpertanian 23.659 5,04
Pekerja Tak Dibayar 98.670 21,03
Jumlah 469.295 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2014 (diolah)
Tabel 6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Langkat Tahun 2014
Penggunaan Lahan Jumlah (ha)
Lahan Sawah 37.529
Sawah Irigasi 8.384
Sawah Tadah Hujan 28.452
Sawah Pasang Surut 693
Lahan Pertanian Bukan Sawah 520.401
Tegal/Kebun 29.330
Lahan Bukan Pertanian 68.399
Total 626.329
4.2 Kecamatan Tanjung Pura
Kecamatan tanjung pura adalah salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada
di wilayah Kabupaten Langkat. Secara geografis, batas-batas wilayah Kecamatan
Tanjung Pura sebagai berikut:
• Sebelah Utara : Selat Malaka
• Sebelah Selatan : Kecamatan Hinai dan Kecamatan Padang Tualang
• Sebelah Barat : Kecamatan Gebang
• Sebelah Timur : Selat Malaka dan Kecamatan Secanggang
Luas wilayah Kecamatan Tanjung Pura adalah 17.961 ha, terdiri dari lahan sawah
seluas 3.051 ha, lahan bukan sawah seluas 9.308 ha dan lahan non pertanian
seluas 5.152 ha. Permukaan tanah Tanjung Pura memiliki ketinggian 4 m diatas
permukaan laut.
Jarak Kecamatan Tanjung Pura ke ibu kota kabupaten lebih kurang 18 km. Secara
administratif, Kecamatan Tanjung Pura membawahi 19 Desa/Kelurahan yang
terdiri dari Desa Serapuh Asli, Pematang Tengah, Paya Perupuk, Pekan Tanjung
Pura, Lalang, Pantai Cermin, Pekubuan, Teluk Bakung, Pematang Serai, Baja
Kuning, Pulau Banyak, Pematang Cengal, Kwala Serapuh, Kwala Langkat,
Bubun, Tapak Kuda, Karya Maju, Suka Maju, dan Pematang Cengal Barat.
Kecamatan Tanjung Pura memiliki kepadatan penduduk tertinggi keenam dari
seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, yaitu sebesar 362,87 per km2. Jumlah
penduduk di wilayah ini sebesar 65.175 jiwa yang terdiri atas 32.873 laki-laki dan
Tabel 7. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2013
Desa/Kelurahan Luas (Km2) Jumlah Penduduk (jiwa)
Serapuh Asli 1,1 1.189
Pematang Tengah 1,55 2.881
Paya Perupuk 1,52 2.539
Pematang Cengal 27,92 7.538
Kwala Serapuh 17,52 1.636
Sumber: Badan Pusat Statistik Langkat, 2014 (diolah)
Tabel 8. Banyaknya Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Desa/Kelurahan Tahun 2013
Jenis Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) Jumlah (%)
Kecamatan Tanjung Pura merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat
yang mengalami penurunan luas lahan sawah. Berdasarkan data dari Badan
Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanjung Pura, besarnya alih fungsi lahan pada
tahun 2013 sebesar 766 ha. Penurunan luas lahan dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Besarnya Alih Fungsi Lahan Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2013
Desa/Kelurahan Besar Alih Fungsi (ha)
Serapuh Asli 10
Desa Suka Maju merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung
Pura, Kabupaten Langkat. Luas wilayahnya sebesar 10,69 ha yang terdiri dari
penduduk Desa Suka Maju mencapai 2380 orang dengan jumlah laki-laki 1183
orang dan perempuan 1197 orang. Kepadatan penduduk sebesar 219 jiwa per km2.
Mata pencaharian penduduk Desa Suka Maju cukup bervariasi. Sebagian besar
penduduk bekerja dibidang pertanian namun saat ini akibat jumlah lahan pertanian
terus berkurang sehingga banyak penduduk yang beralih profesi. Mata
Pencaharian penduduk Desa Suka Maju dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Mata Pencaharian Penduduk Desa Suka Maju Tahun 2015
Sumber: RPJM Desa Suka Maju, 2015
4.4 Karakteristik Umum Responden
Karakteristik responden di daerah penelitian ini diperoleh berdasarkan survei yang
dilakukan kepada 30 responden yang termasuk dalam petani yang melakukan alih
fungsi lahan padi sawah. Karakteristik umum tersebut terdiri dari luas sawah, usia,
jumlah tanggungan dan pengalaman bertani.
4.4.1 Luas Sawah
Luas sawah yang menjadi karakteristik responden adalah luas sawah yang dimiliki
petani sebelum melakukan alih fungsi. Kisaran luas sawah yang dimiliki
responden dimulai dari 0,04 ha sampai dengan 5,98 ha dengan rata-rata 1,55 ha.
Sedangkan luas sawah yang dialihfungsikan memiliki rata-rata sebesar 50 persen. Jenis Mata Pencaharian I II III IV V VI VII VIII IX
Petani/Pekebun 45 131 103 108 87 40 28 7 28
Nelayan 2 - 1 - - 29 12 22 24
Wiraswasta 6 4 25 - 5 20 7 5 18
Lainnya 11 2 8 - - 36 14 1 28
Gambar 2. Luas Sawah Responden (diolah)
Berdasarkan Gambar 2. luas sawah yang dimiliki petani sebelum alih fungsi lahan
tergolong sedang. Sebanyak 40% responden memiliki sawah seluas kurang dari 1
ha, 33% responden memiliki sawah seluas 1-2 ha dan 27% sisanya memiliki
sawah seluas lebih dari 2 ha.
4.4.2 Usia
Usia menjelaskan kemampuan seseorang dalam bekerja. Semakin tua seseorang,
maka keadaan tubuh semakin lemah sehingga kemampuan bekerja menurun. Usia
petani yang menjadi responden memiliki kisaran dari 25 tahun sampai dengan 97
tahun.
Gambar 3. Usia Responden Tahun 2015 (diolah)
Berdasarkan Gambar 3. diperoleh bahwa sebagian besar responden yang telah
melakukan alih fungsi lahan sawah adalah yang berusia 30-60 tahun. Sebesar 37%
responden berusia 30-45 tahun, 37% berusia 46-60 tahun. Sedangkan diatas 60
menunjukkan bahwa petani yang pernah melakukan alih fungsi sawah cenderung
masih berumur produktif pada tahun 2015, namun mereka lebih memilih
menggantikan sawah mereka menjadi penggunaan lainnya.
4.4.3 Jumlah Tanggungan
Banyaknya tanggungan dalam keluarga mempengaruhi besarnya pengeluaran.
Semakin besar pengeluaran, maka pendapatan yang dihasilkan juga seharusnya
semakin besar. Maka dari itu, banyaknya tanggungan akan mendorong kepala
keluarga untuk lebih giat dalam usaha meningkatkan pendapatan agar keperluan
hidup dapat terpenuhi. Adapun sebaran jumlah tanggungan petani dimulai dari 0-7
jiwa per keluarga. Pada tahun 2015, jumlah tanggungan keluarga petani yang
dijadikan responden dapat dilihat pada Gambar .
Gambar 4. Jumlah Tanggungan Responden Tahun 2015 (diolah)
Gambar 4. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebagian besar petani yang
pernah melakukan alih fungsi sawah memiliki tanggungan sebanyak 2 -4 jiwa.
Sebanyak 23% responden memiliki jumlah tanggungan kurang dari 2 jiwa dan
13% memiliki tanggungan lebih dari 4 jiwa. Banyaknya tanggungan tidak
dijadikan beban oleh kepala keluarga karena pada usia produktif, anak dan istri
4.4.4 Pengalaman Bertani
Sebagian besar penduduk di lokasi penelitian berprofesi sebagai petani.
Kebanyakan dari mereka sudah bertani sejak kecil, membantu orang tua dan
keluarga. Kegiatan pertanian sudah merupakan kegiatan turun-temurun yang telah
dilaksanakan. Pengalaman bertani menunjukkan seberapa lama petani telah
melakukan kegiatan pertanian persawahan.
Gambar 5. Pengalaman Bertani Responden Tahun 2015 (diolah)
Berdasarkan Gambar 5. diperoleh bahwa pengalaman bertani yang dimiliki oleh
petani responden tergolong lama. Sebanyak 47% responden telah bertani selama
15-30 tahun. Ada pula yang memiliki pengalaman bertani dibawah 15 tahun yaitu
sebesar 13%. Sebanyak 30% responden telah bertani selama 31-45 tahun dan
5.1 Laju Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Pura
Penurunan luas lahan atau alih fungsi lahan padi sawah di Kecamatan Tanjung
Pura terjadi hampir setiap tahunnya. Laju alih fungsi lahan tahun 2008-2014 dapat
dilihat pada Gambar 6.
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, 2008-2014 (diolah)
Gambar 6. Perubahan Luas Lahan Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2008-2014
Gambar 6. menunjukkan laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura
selama tujuh tahun terakhir (2008-2014) memiliki rata-rata sebesar 7,58%.
Walaupun luas lahan pada tahun 2010 dan 2012 tidak mengalami penurunan
(tetap) serta penambahan luas lahan seluas 5 ha pada tahun 2013, besarnya
penurunan luas lahan pada tahun lainnya mengakibatkan penurunan yang nyata
terhadap proporsi luas sawah terhadap luas Kecamatan Tanjung Pura yaitu dari
29,71% pada tahun 2008 menjadi 15,23% pada tahun 2014 (Lampiran 2.).
Besarnya penurunan luas lahan yaitu sebesar 2.190 ha atau tersisa hanya sebesar
55,5% dari total luas lahan sawah tahun 2008. 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014