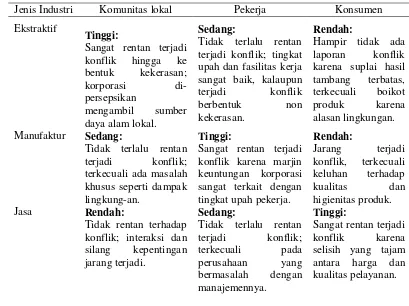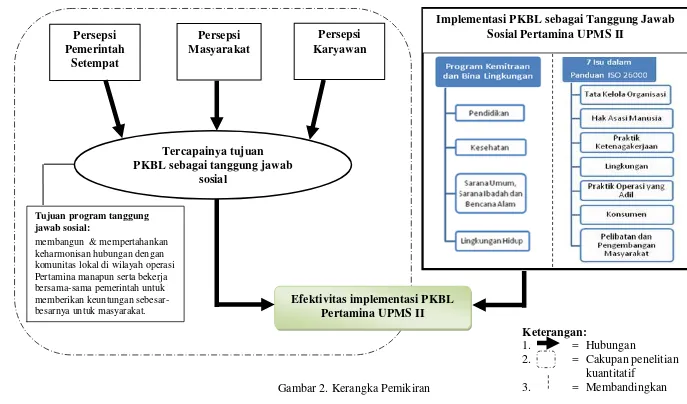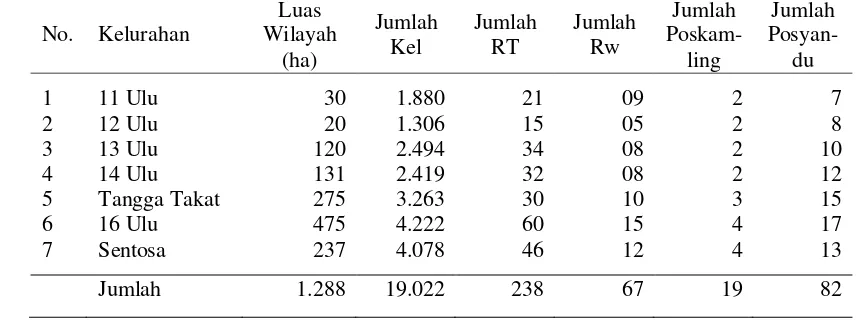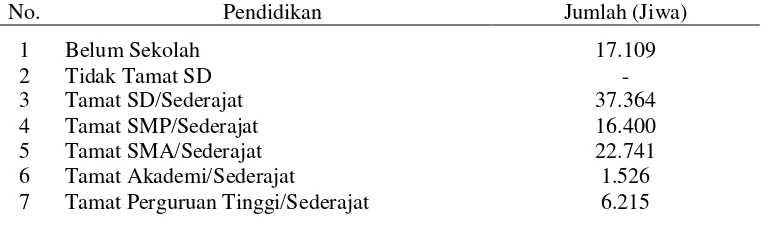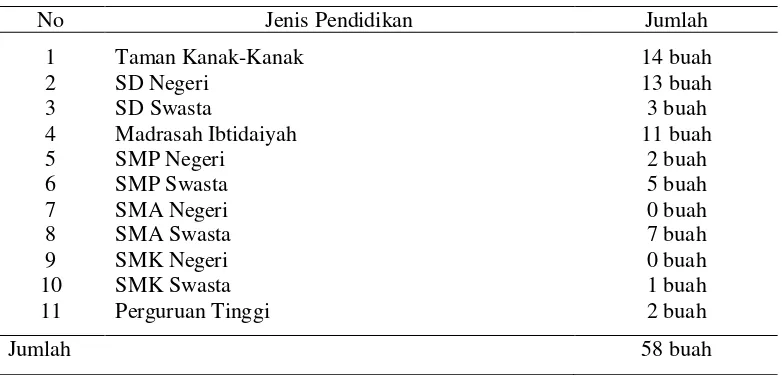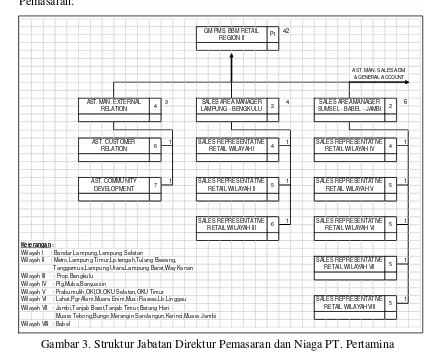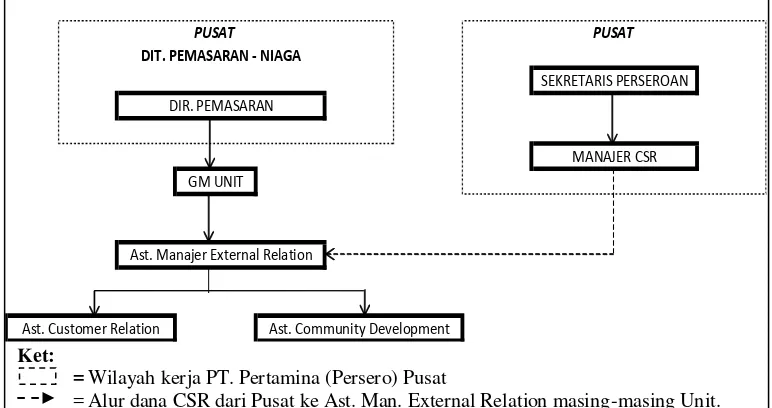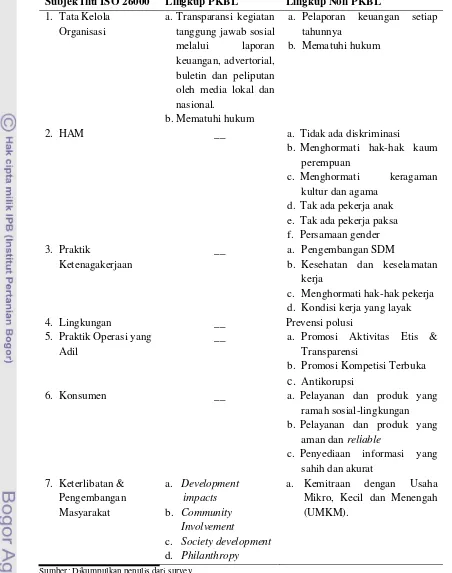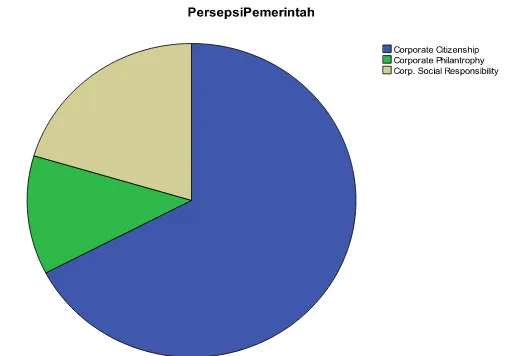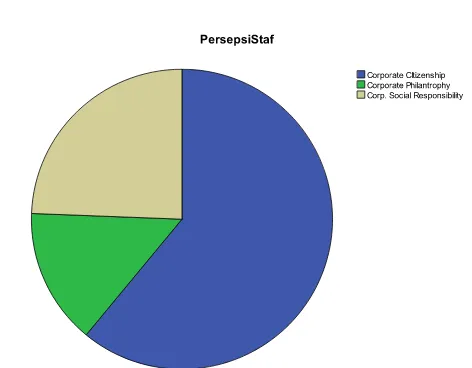SERTA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASINYA
(Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas Seberang Ulu II, Sumatera Selatan)
SRI ARMA SEPRIANI
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
ABSTRACT
SRI ARMA SEPRIANI Stakeholders’ perception of Partnership Program and Community Development of Government-owned Corporation and the effectiveness of the implementation. Supervised by FREDIAN TONNY NASDIAN
This study is about the stakeholders’ perception of partnership program and community development (PKBL) and the effectiveness of the implementation which doing by PT. Pertamina in Seberang Ulu II community, South Sumatera. This study use qualitative and quantitative approach with triangulation and survey method. Informant is the staff from External Relation, Human Resources and Environment function. Respondent is people who are the employee of PT. Pertamina Retail Region II, the local government staffs and Seberang Ulu II community, both participants and non participants of PKBL. This study focused on the assessment of the effectiveness of PKBL according to guidelines of ISO
26000, and also the correlation between stakeholders’ perceptions and PKBL
success rate for identifying the effectiveness of PKBL implementation.
Based on result, PKBL implementation can only fill two of ISO 26000
core subjects, namely good governance organizations issue, and also community involvement and community development issue. It means that according to ISO
26000, the effectiveness of PKBL implementation is low. Beside that, the majority
of stakeholders’ perception is Corporate Social Responsibility and the success rate of PKBL implementation is low. There’s significant correlation between perception of Corporate Citizenship and Corporate Social Responsibility with success rate of PKBL, but not in Corporate Philantrophy. Therefore, the effectiveness of the implementation of PKBL is directly proportional to success rate of PKBL, then the effectiveness of PKBL implementation is low too.
.
RINGKASAN
SRI ARMA SEPRIANI. PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BUMN DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASINYA (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas Seberang Ulu II, Sumatera Selatan). Di bawah bimbingan
Fredian Tonny Nasdian.
Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki definisi yang beragam sehingga wujudnya pun diartikan beragam. Tanggung jawab sosial perusahaan pada BUMN umumnya diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pertamina UPMS II di Seberang Ulu, Sumatera Selatan pun menerapkan PKBL sebagai tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengkaji sejauh mana efektivitas PKBL sebagai tanggung jawab sosial perusahaan bila ditilik dari tujuan internal tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan persepsi pemangku kepentingannya serta dari pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial ISO 26000. Pemangku kepentingan perlu diperhatikan sebab mereka yang terpengaruh atau mempengaruhi keputusan dan aktivitas bisnis perusahaan.
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi PKBL yang diterapkan oleh Pertamina UPMS II dan mengkaji sejauh mana implementasi
PKBL Pertamina UPMS II memenuhi „standar kinerja‟ Social Responsibility
menurut pedoman ISO 26000. Pedoman pelaksanaan tersebut difokuskan pada
tujuh subjek inti ISO 26000, yaitu isu tata kelola organisasi yang baik, isu hak asasi manusia, isu tenaga kerja, isu lingkungan, isu konsumen, isu praktik operasi
yang adil serta isu keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Penelitian ini juga
bertujuan mengidentifikasi persepsi karyawan Pertamina UPMS II, masyarakat dan pemerintah Kecamatan Seberang Ulu II mengenai tanggung jawab sosial
perusahaan kemudian mengkaji hubungan antara persepsi ketiga pemangku
kepentingan tersebut dengan efektivitas implementasi PKBL Pertamina UPMS II.
Persepsi pemangku kepentingan tersebut dikategorikan menjadi Corporate
Citizenship, Corporate Philantrophy dan Corporate Social Responsibility.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKBL Pertamina UPMS II belum merangsang partisipasi aktif sasaran programnya. Sasaran program juga belum tergolong mandiri. Keberlanjutan suatu program dari PKBL pun sangat bergantung pada pengambil keputusan, yaitu Pertamina UPMS II. Ketidakmandirian masyarakat mengakibatkan mereka sangat mengandalkan bantuan dari pemilik modal untuk meneruskan suatu kegiatan. Menurut pedoman ISO 26000, implementasi PKBL baru memenuhi subjek inti tata kelola organisasi yang baik serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Artinya, menurut pedoman ISO 26000, implementasi PKBL sebagai tanggung jawab sosial belum efektif.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi mayoritas persepsi
seluruh responden pemangku kepentingan berada pada kategori Corporate Social
Responsibility. Persepsi pada masing-masing pemangku kepentingan yang
diperoleh adalah mayoritas persepsi pemerintah setempat berupa Corporate
Corporate Social Responsbility. Tidak ada perbedaan mayoritas persepsi antara pemerintah lapisan pimpinan dengan lapisan staf serta karyawan pengambil keputusan dengan karyawan nonpengambil keputusan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, terdapat perbedaan persepsi pada masyarakat peserta dengan karyawan non peserta dan pada penggolongan masyarakat menurut pekerjaannya.
Tingkat keberhasilan menurut pemangku kepentingan menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai tingkat keberhasilan PKBL adalah rendah. Hasil uji Kruskal-Wallis H menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penilaian tingkat
keberhasilan pada masing-masing persepsi. Namun, hasil uji korelasi Spearman‟s
rho menunjukkan bahwa hanya pasangan data Corporate Citizenship dan tingkat
keberhasilan serta Corporate Social Responsibility dan tingkat keberhasilan yang
memiliki korelasi yang signifikan, sedangkan pasangan data Corporate
PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
SERTA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASINYA
(Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas Seberang Ulu II, Sumatera Selatan)
SRI ARMA SEPRIANI
Skripsi
Sebagai Bagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Pada
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh:
Nama Mahasiswa : Sri Arma Sepriani
NIM : I34061168
Judul Skripsi : Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN serta Efektivitas
Implementasinya
(Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas Seberang
Ulu II, Sumatera Selatan)
dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor.
Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi
Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS
NIP. 19580214 198503 1 004
Mengetahui,
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Ketua
Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, M.S
NIP. 19550630 198103 1 003
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL
“PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BUMN SERTA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASINYA (STUDI KASUS PT. PERTAMINA (PERSERO) DI KOMUNITAS SEBERANG ULU II, SUMATERA SELATAN)” BELUM
PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN
TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN MANAPUN UNTUK TUJUAN
MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA
MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA
SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG
PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN PIHAK LAIN KECUALI
SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.
DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA
DAN SAYA BERSEDIA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERNYATAAN
INI.
Bogor, Mei 2011
Sri Arma Sepriani
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 25
September 1988 di Palembang. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara,
putri bungsu dari Bapak Aruji Hamiba, S.Pd dan Ibu Muslimah, S.Pd. Penulis
menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah 3 Plaju
(1994-2000), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTP Negeri 20
Palembang (2000-2003), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4
Palembang (2003-2006). Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam
beberapa kegiatan organisasi, seperti Pramuka dan Paskibra. Penulis juga
merupakan Ketua 1 OSIS SLTPN 20 Palembang periode 2001-2002, Sekretaris 1
Perwakilan Kelas (PK) SMAN 4 Palembang periode 2003-2004, Ketua 1 PK
SMAN 4 Palembang periode 2004-2005 serta Sekretaris Umum English Debate
Club (EDC) SMAN 4 Palembang periode 2004-2005.
Tahun 2006, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui Jalur
USMI (Undangan Saringan Masuk IPB) dan memilih Mayor Sains Komunikasi
dan Pengembangan Masyarakat. Selama menjadi mahasiswa IPB, penulis aktif
dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Penulis tergabung dalam
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia (BEM FEMA) sebagai
staf divisi Sosial dan Lingkungan Hidup Kabinet Laskar Pelangi periode
2007-2008 dan Kabinet Heroik periode 2007-2008-2009. Penulis juga menjadi Ketua Panitia
Seminar Nasional “Let‟s CSR on Campus” tahun 2009, Ketua Panitia pelatihan
“CSR Training on Campus” tahun 2009 dan anggota divisi Humas dan Danus
kepanitiaan Indonesian Ecology Expo 2009 (INDEX 2009). Selain aktif di
organisasi dan kepanitiaan, penulis juga menjadi Asisten Dosen untuk mata kuliah
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
mencurahkan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Persepsi Pemangku
Kepentingan Terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN serta
Efektivitas Implementasinya (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas
Seberang Ulu II, Sumatera Selatan)” dapat terselesaikan. Penulis juga
mengucapkan terimakasih untuk Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS yang telah
membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan berbagai saran dan
masukannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, baik melalui kritik, saran,
maupun dukungan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Skripsi ini membahas mengenai PKBL sebagai bentuk tanggung jawab
sosial BUMN. Fokus skripsi ini adalah mengkaji efektivitas implementasi PKBL
menurut pedoman pelaksanaan ISO 26000 dan pencapaian tujuan internal
tanggung jawab sosial Pertamina dengan melihat persepsi tiga pemangku
kepentingan. Penulisan Skripsi ini merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan masukan dan perbaikan yang dapat membantu
penyempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak
banyak.
Bogor, Mei 2011
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah memberikan rahmat-Nya dan kemudahan dalam segala hal sehingga skripsi
ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini
tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan
ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS selaku dosen pembimbing skripsi atas
bimbingan, arahan, serta sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan
Skripsi ini;
2. Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS selaku dosen penguji utama, Heru Purwandari,
S.P, M.Si selaku dosen penguji wakil Departemen SKPM dan Martua
Sihaloho, S.P, M.Si selaku dosen uji petik skripsi, terimakasih atas masukan,
kritik dan arahannya yang sangat berharga dalam penulisan skripsi;
3. Ayahanda Aruji Hamiba, S.Pd dan Ibunda Muslimah, S.Pd, serta kakek dan
nenekku tersayang: H. Mat Tjik (alm), Hj. Tjik Iba (alm), H. Harun Djakfar
(alm) dan Hj. Rosidah, terimakasih untuk untaian doa, dukungan dan
semangat yang tak henti diberikan pada penulis;
4. Saudara-saudaraku: Eka Armawati, S.Pd, Bandarsa, S.Pd, Archimedes, S.E,
Dwi Armasusanti, S.E, Muhammad Yusuf Fikri, S.E, terimakasih untuk
semangat dan doanya;
5. Papa H. Agusman Bargal, Mama Hj. Mastoh, Tante „Ria‟ Nur Mulia, Kak Uli,
Kak Helmi, Ayuk Mara, Mas Basuki dan keponakan lucuku: Bima,
terimakasih untuk dukungan dan doanya;
6. Muhammad Rizki Allgusma, S.S yang selalu mendukung dan mendoakan
kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi. Terimakasih untuk
enam tahun kebersamaan yang berharga.
7. Mas Robert, Mbak Vega Pita, Mas Habibie, Mas Untung, Pak Kumis dari
Fungsi External Relation Pertamina UPMS II, Mas Kerangga Jaya „SDM‟,
mahasiswa magang di fungsi ER, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya
dalam penelitian dan magang di Pertamina UPMS II;
8. Pemerintah di Kecamatan SU II: Bapak Camat Heri A. Rasuan, S.H, Bapak
Sekcam M. Ichsanul A, S.Sos, M.Si, Bapak dan Ibu Lurah di wilayah
Kecamatan SU II, serta seluruh staf di kantor kecamatan dan ketujuh
kelurahan yang telah membantu dan bekerjasama dalam penelitian untuk
skripsi ini;
9. Para responden penelitian di wilayah Kecamatan Seberang Ulu II yang sudah
meluangkan waktunya untuk „diganggu‟ oleh penulis, terimakasih untuk
bantuan dan kerjasamanya;
10. Mas Mahmudi Siwi dan Mas Reza Ramayana, terimakasih untuk dukungan
moral, buku-buku dan diskusi yang sangat membantu proses penulisan skripsi
ini;
11. My Bestie: Rinaldy Yusuf, S.KPM, terimakasih atas doa, semangat, sindiran, saran, kritik dan bantuannya dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi
ini;
12. Wisma Pelangi 73: Kak Lia, Linda, Ita, Nunu, terimakasih atas semangatnya.
Nunu „Nurul Qomariasih‟, terimakasih pula atas bantuannya dalam pengolahan data penelitian;
13. Quadra Pop Girls: Na, Mpit, Niaw, Dion, Ami, terimakasih untuk semangat, dukungan, doa dan tawa-tangisnya;
14. Sahabat-sahabat sesama insomaniac: Aditya Wahyu Purnama, Ferdiansyah,
Inerema FDP, M. Idrus Alamsyah, St. Rahayu Pratami Lexianingrum,
member grup alumni PK SMAN 4, member grup alumni SLTPN 20,
terimakasih telah setia menemani penulis mengerjakan Skripsi hingga subuh;
15. Abdillah Apri Sudarmanto, Yovan Dupriliandika Zefta dan Muhammad Iqbal
Pangindoman yang setiap saat menanyakan perkembangan penulisan skripsi,
terimakasih untuk bantuan, doa dan semangatnya; dan
16. Teman-teman KPM‟43, Bu Susi, Mbak Icha, Mbak Maria serta semua pihak
yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ... xi
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang... 1
1.2 Perumusan Masalah ... 4
1.3 Tujuan Penelitian ... 7
1.4 Kegunaan Penelitian ... 7
BAB II PENDEKATAN TEORITIS ... 9
2.1 Tinjauan Pustaka... 9
2.1.1 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) ... 9
2.1.2 Konsep PKBL... 19
2.1.3 Konsep Persepsi... 2.1.4 Konsep Pemberdayaan ... 22
2.1.5 Konsep Efektivitas ... 23
2.2 Kerangka Pemikiran ... 24
2.3 Hipotesa Penelitian ... 28
2.3.1 Hipotesa Pengarah... 28
2.3.2 Hipotesa Uji ... 28
2.4 Definisi Operasional ... 28
2.5 Definisi Konseptual ... 28
BAB III METODE PENELITIAN ... 32
3.1 Metode Penelitian ... 32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 33
3.3 Teknik Penentuan Informan, Subjek Kasus dan Responden ... 33
3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 36
3.4.1 Pengamatan Berperanserta ... 37
3.4.2 Penelusuran Dokumen ... 37
Halaman
3.5 Teknik Analisis Data ... 38
BAB IV PROFIL KOMUNITAS DAN PERUSAHAAN ... 40
4.1 Profil Komunitas... 40
4.2 Profil Perusahaan ... 44
4.2.1 Profil Fungsi External Relation (ER) ... 45
4.3 Ikhtisar ... 48
BAB V PEDOMAN PELAKSANAAN SOCIAL RESPONSIBILITY DAN IMPLEMENTASI PKBL PERTAMINA UPMS II ... 50
5.1 Pedoman Pelaksanaan Social Responsibility... 50
5.2 Implementasi PKBL ... 63
5.3 Ikhtisar ... 69
BAB VI PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PKBL ... 73
6.1 Persepsi Pemangku Kepentingan... 73
6.2 Ikhtisar ... 97
BAB VII PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PKBL ... 99
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN ... 105
8.1 Kesimpulan... 105
8.2 Saran ... 107
DAFTAR PUSTAKA ... 109
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Seberang Ulu II pada Agustus 2010 .. 41
Tabel 2. Jumlah Keluarga, RT, RW, Poskamling, Posyandu dan Luas Wilayah
Masing-masing Kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu II ... 41
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan SU II tahun
2007 ... 42
Tabel 4. Sarana Pendidikan di Kecamatan SU II Tahun 2007 ... 43
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan menurut Kelurahan Tahun
2007 ... 43
Tabel 6. Frekuensi Persepsi Tiga Pemangku Kepentingan Mengenai Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 73
Tabel 7. Frekuensi Persepsi Pemerintah Kecamatan Seberang Ulu II Mengenai
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 75
Tabel 8. Frekuensi Persepsi Pemerintah Lapisan Staf Kecamatan SU II
Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 76
Tabel 9. Frekuensi Persepsi Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu II
Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 83
Tabel 10. Frekuensi Persepsi Masyarakat Peserta PKBL Pertamina UPMS II
Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 84
Tabel 11. Frekuensi Persepsi Masyarakat Non Peserta PKBL Pertamina UPMS
II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 85
Tabel 12. Frekuensi Persepsi Responden Ibu Rumah Tangga Peserta Mengenai
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 87
Tabel 13. Frekuensi Persepsi Responden Ibu Rumah Tangga Non Peserta
Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 88
Tabel 14. Frekuensi Persepsi Responden Swasta Mengenai Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 89
Tabel 15. Frekuensi Persepsi Responden PNS Mengenai Tanggung Jawab Sosial
Halaman
Tabel 16. Frekuensi Persepsi Responden Karyawan Pertamina UPMS II
Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 93
Tabel 17. Frekuensi Persepsi Karyawan Lapisan Non Pengambil Keputusan
Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 95
Tabel 18. Persepsi Pemangku Kepentingan Pertamina UPMS II Tahun 2010... 97
Tabel 19. Distribusi Tingkat Keberhasilan PKBL Berdasarkan Kategori Persepsi
Pemangku Kepentingan Pertamina UPMS II Tahun 2010 ... 99
Tabel 20. Distribusi Tingkat Keberhasilan PKBL Menurut Persepsi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Matriks Tingkat Dinamika Konflik Korporasi-Stakeholder ... 19
Gambar 2. Kerangka Pemikiran ... 27
Gambar 3. Struktur Jabatan Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina ... 46
Gambar 4. Bagan Alur Sumber Dana CSR PT. Pertamina (Persero) ... 47
Gambar 5. Matriks Perbandingan Subjek Inti ISO 26000 dan Lingkup PKBL serta Non PKBL ... 70
Gambar 6. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Pemangku Kepentingan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 74
Gambar 7. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Pemerintah Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 755
Gambar 8. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Pemerintah Lapisan Staf Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 77
Gambar 9. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 83
Gambar 10. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Peserta PKBL Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial PerusahaanTahun 2010 ... 85
Gambar 11. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Non Peserta PKBL di Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 86
Gambar 13. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Responden Ibu
Rumah Tangga Non Peserta di Kecamatan SU II Mengenai
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 88
Gambar 14. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Responden Swasta di
Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tahun 2010 ... 90
Gambar 15. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Responden PNS
Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 89
Gambar 16. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Karyawan Pertamina
UPMS II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun
2010 ... 94
Gambar 17. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Karyawan Non
Pengambil Keputusan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diwajibkan untuk
melaksanakan program pembinaan pada usaha kecil bahkan sebelum disahkannya
UU tentang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Pembinaan usaha kecil oleh
BUMN mulai dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pedoman
pembinaan usaha kecil tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian sampai
akhirnya menjadi UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang diperkuat dengan
Peraturan Menteri Negara No. 5 tanggal 27 April 2007 tentang Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)
yang berlaku hingga saat ini.
Program Kemitraan BUMN dan Bina Lingkungan atau biasa disebut
PKBL adalah program untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi
ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam rangka
mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya
pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha
dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri tentang BUMN No. 5
tahun 2007, Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari
bagian laba BUMN, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana
dari bagian laba BUMN. Besaran dana untuk dua program ini adalah masing-Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan masing-Usaha Milik Negara dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,
Tahun 2007, tahun yang sama dengan pengesahan UU tentang Perseroan
Terbatas No. 40, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
memberikan sambutan dalam sebuah Forum CSR-UKM 2007 dengan tema
“Seminar & Pameran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengembangan
Usaha Kecil dan Menengah”. Dalam seminar dan pameran ini, Menteri Negara
Koperasi dan UKM Indonesia menyebutkan bahwa sejak tahun 1989, BUMN
telah berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial dengan membantu
pengusaha UKM dan program tersebut dikenal dengan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL).2 Ketua Panitia Khusus UU Perseroan Terbatas, Akil
Mochtar, menyebutkan juga bahwa salah satu alasan tanggung jawab sosial harus
diatur adalah karena kewajiban tanggung jawab sosial sudah diterapkan pada
BUMN dalam bentuk kewajiban menyisihkan sebagian besar laba bersihnya untuk
keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar
BUMN (Fajar 2010). Dengan kata lain, seringkali tanggung jawab sosial pada
BUMN diartikan sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran BBM Retail Region II Sumbagsel
atau yang selanjutnya disebut Pertamina UPMS II merupakan salah satu unit
pemasaran dari PT. Pertamina (Persero) yang memiliki wilayah operasi pada lima
provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan
Lampung dengan pusat lokasinya berada di Kecamatan Seberang Ulu II,
Palembang, Sumatera Selatan. Pada awal berdirinya, perusahaan minyak yang
beroperasi di wilayah Palembang ini dikuasai oleh Belanda. Berbagai fasilitas
yang diperoleh karyawan perusahaan di masa penguasaan Belanda, baik berupa
sarana tempat tinggal maupun kemudahan memperoleh akses terhadap sarana
kesehatan dan pendidikan untuk keluarga karyawan dalam sebuah kompleks milik
perusahaan tentu memperlihatkan perbedaan yang ada antara perusahaan dan
masyarakat. Setelah Indonesia merdeka dan secara resmi mengambil alih
perusahaan tersebut, berbagai fasilitas pra kemerdekaan tersebut masih ada yang
bertahan hingga sekarang. Dengan kata lain, meski tidak semencolok seperti
2
sebelum kemerdekaan, jarak sosial antara perusahaan dan penduduk setempat
tersebut masih terlihat.
Kota Palembang saat ini memang belum terlepas dari masalah
ketenagakerjaan dan mencoloknya kesenjangan sosial. Seperti yang ditulis dalam
website kepolisian wilayah Sumatera Selatan, mencoloknya kesenjangan sosial serta masalah ketenagakerjaan merupakan ancaman dalam menjaga ketertiban dan
keamanan masyarakat Palembang. Sementara itu, masyarakat Palembang
cenderung temperamental dan suka membawa senjata tajam3. Kondisi ini tentu
semakin menyulut kriminalitas di Kota Palembang, termasuk Kecamatan
Seberang Ulu (SU) II.
Beroperasi di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan
ketimpangan sosial yang mencolok seperti yang umumnya terjadi pada wilayah
dengan kerekatan sosial yang rendah sebenarnya bukanlah sebuah hal yang
menguntungkan bagi sebuah bisnis. Perusahaan harus berusaha keras untuk
memperoleh lisensi sosialnya dalam beroperasi di wilayah seperti ini. Pertamina
UPMS II tentu menyadari hal ini. Ketika peraturan mengenai kewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial bagi perseroan diberlakukan, perusahaan
yang telah lebih dulu melaksanakan Program Kemitraan dan Bina lingkungan ini
lalu mengadopsi konsep PKBL sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan
dijalankan oleh fungsi External Relation (ER). Dengan konsep PKBL sebagai
bentuk tanggung jawab sosial perusahaannya, maka Pertamina UPMS II telah
mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk program tanggung jawab sosialnya.
Namun, ekspektasi pemangku kepentingan, terutama pemangku kepentingan
eksternal perusahaan seringkali lebih tinggi dari apa yang dapat dilakukan
perusahaan. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut
bagaimana efektivitas implementasi PKBL sebagai tanggung jawab sosial Pertamina UPMS II di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
3
1.2 Perumusan Masalah
PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran BBM Retail Region II Sumbagsel
adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang pemasaran produk minyak dan gas
bumi. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka perusahaan ini
harus melakukan pembinaan usaha kecil dan menengah serta bina lingkungan atau
PKBL. Namun, pada tahun 2007, saat UU tentang Perseroan Terbatas No. 40
diberlakukan, Pertamina yang mengelola sumberdaya alam juga dikenai
kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di masyarakat, tanggung jawab
sosial sesungguhnya adalah jalan bagi perusahaan untuk memperoleh „izin sosial‟
(berupa dukungan) dari masyarakat dalam beroperasi (Warhurst dalam Sukada
et.al. 2007) walau utamanya pelaksanaan tanggung jawab sosial tetap diawali dengan manajemen dampak berupa upaya meminimumkan dampak negatif dan
memaksimumkan dampak positif atas kehadiran perusahaan. Pada Pertamina
UPMS II, tanggung jawab sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk PKBL dengan
berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, serta sarana
prasana dan bencana alam.
Lokasi dimana Pertamina UPMS II beroperasi adalah wilayah dengan
ketimpangan sosial yang mencolok serta tingkat kriminalitas yang tinggi. Tentu
bukan sebuah hal yang mudah untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam
beroperasi di wilayah seperti ini. Disamping itu, ekspektasi pemangku
kepentingan eksternal perusahaan seringkali lebih tinggi dari apa yang dapat
dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, secara garis besar, pertanyaan yang akan
dikaji lebih lanjut adalah bagaimana efektivitas implementasi PKBL sebagai
tanggung jawab sosial Pertamina UPMS II di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Terkait implementasi tanggung jawab sosial, International Organization
for Standardization (ISO) telah membuat panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang tidak hanya berlaku untuk jenis perusahaan tertentu saja, tapi berlaku
di semua jenis perusahaan. Meski tidak semua bagian dari standar internasional
yang dikenal sebagai ISO 26000 ini sesuai untuk semua jenis perusahaan, namun
yang termasuk dalam cakupan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut antara
lain tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, isu
lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen serta keterlibatan dan
pengembangan masyarakat. Adapun komponen panduan ISO 26000 lainnya
adalah prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, isu-isu terkait tanggung jawab sosial
dan cara untuk menyatukan kegiatan tanggung jawab sosial ke dalam strategi,
sistem, praktik dan proses-proses yang telah berlangsung dalam organisasi.
Lantas, ketika konsep PKBL pada Pertamina UPMS II diadopsi untuk menjadi
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, maka muncul pertanyaan:
bagaimana implementasi PKBL Pertamina UPMS II dan sejauh mana implementasi tersebut dapat memenuhi „standar kinerja‟ Social Responsibility menurut panduan ISO 26000?
Stakeholder engagement adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan mengetahui kepentingan mereka
terhadap keputusan dan aktivitas perusahaan maka perusahaan dapat
mengidentifikasi serta mengatasi dampak operasinya terhadap para pemangku
kepentingan tersebut. Namun, seringkali persepsi atau cara para pemangku
kepentingan tersebut dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah
sesuai dengan makna tanggung jawab sosial itu sendiri sehingga ekspektasi atau
harapan mereka terhadap perusahaan menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi
perusahaan. Selisih antara harapan dan kenyataan yang terjadi ini bukanlah hal
yang menguntungkan bagi perusahaan sebab berpeluang menciptakan konflik
antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Pada perusahaan yang bergerak
di bidang ekstraktif seperti Pertamina UPMS II, pemangku kepentingan yang
paling rentan untuk terjadi konflik dengan perusahaan adalah komunitas lokal.
Artinya, masyarakat lokal adalah pemangku kepentingan yang penting untuk
diperhatikan persepsinya oleh Pertamina UPMS II. Selain masyarakat lokal,
pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga merupakan pemangku kepentingan
kritis yang penting untuk diperhatikan perusahaan. Kemudian, pemangku
kepentingan perusahaan tidak hanya berupa pemangku kepentingan eksternal saja
seperti masyarakat lokal dan pemerintah. Pemangku kepentingan internal seperti
mengkaji efektivitas PKBL Pertamina UPMS II, menjadi penting untuk
mengetahui terlebih dahulu bagaimana persepsi karyawan Pertamina UPMS
II, masyarakat dan pemerintah Kecamatan Seberang Ulu II mengenai tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri?
Pertamina UPMS II tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai dalam
implementasi tanggung jawab sosialnya. Seperti yang dituangkan dalam website
PT. Pertamina, tujuan dari Program Social Responsibility and Community
Development PT. Pertamina (Persero) adalah membangun dan mempertahankan keharmonisan hubungan dengan komunitas lokal di wilayah operasi Pertamina
manapun serta bekerja bersama-sama pemerintah untuk memberikan keuntungan
sebesar-besarnya untuk masyarakat. Tujuan eksternal tanggung jawab sosial PT.
Pertamina (Persero) adalah untuk membantu pemerintah Indonesia memperbaiki
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melalui pelaksanaan
program-program yang membantu pencapaian target MDG‟s. Kemudian, tujuan internal
tanggung jawab sosial PT. Pertamina (Persero) adalah untuk membangun
hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan
untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi terutama dalam membangun
reputasi korporasi. Untuk mencapai tujuan internal ini, PT. Pertamina di seluruh
wilayah operasi di Indonesia memberlakukan kriteria tanggung jawab sosial
Pertamina, yaitu bermanfaat, berkelanjutan, dekat dengan wilayah operasi,
publikasi dan mendukung PROPER dengan 4 strategic initiatives, yaitu
pendidikan, kesehatan, lingkungan serta infrastruktur dan peduli bencana. Namun,
seringkali persepsi atau cara para pemangku kepentingan dalam memaknai
tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah sesuai dengan pemaknaan tanggung
jawab sosial oleh perusahaan sendiri hingga ekspektasi atau harapan mereka
terhadap perusahaan menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi perusahaan. Selain itu,
ketika fokus pencapaian perusahaan mengutamakan pemerintah dan masyarakat,
seringkali pemangku kepentingan internal merasa diabaikan. Oleh karena itu,
menjadi penting untuk diungkap bagaimana hubungan antara persepsi dari
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana
efektivitas implementasi PKBL Pertamina UPMS II di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan utama ini akan dijawab melalui tujuan-tujuan khusus penelitian, yaitu:
1. Mengidentifikasi implementasi PKBL yang diterapkan oleh Pertamina UPMS
II.
2. Mengkaji sejauh mana implementasi PKBL Pertamina UPMS II memenuhi
„standar kinerja‟Social Responsibility menurut panduan ISO 26000.
3. Mengidentifikasi persepsi karyawan Pertamina UPMS II, masyarakat dan
pemerintah Kecamatan Seberang Ulu II mengenai tanggung jawab sosial
perusahaan.
4. Mengkaji hubungan antara persepsi ketiga pemangku kepentingan mengenai
tanggung jawab sosial perusahaan dan efektivitas implementasi dari PKBL
yang diterapkan Pertamina UPMS II.
1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Bagi penulis dan civitas akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan
bagi penulis sendiri, menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian
selanjutnya serta menambah perbendaharaan kepustakaan bagi Departemen
Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor di
bidang tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL.
2. Bagi instansi terkait
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi perusahaan
mengenai efektivitas implementasi PKBL menurut ISO 26000 dan persepsi
beberapa pemangku kepentingan perusahaan mengenai tanggung jawab sosial
perusahaan itu sendiri.
3. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat
mengenai program tanggung jawab sosial dan kaitannya dengan para
4. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan
kebijakan yang tepat terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan Badan
BAB II
PENDEKATAN TEORITIS
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang masih hangat dibicarakan hingga saat ini.
Berbagai perdebatan mengenai arti, standar pelaksanaan CSR serta wajib atau
tidaknya perusahaan memperhatikan kegiatan sosial dan lingkungan masih
mewarnai perkembangan konsep ini. Pengertian CSR yang muncul pun beragam
dan mempunyai penekanan pada dimensi yang berbeda-beda. Meski demikian,
hasil dari uji statistik yang dilakukan Alexander Dahlsrud terhadap tiga puluh
tujuh definisi CSR yang paling popular menunjukkan bahwa beragam definisi
tersebut memiliki konsistensi dalam lima dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial,
lingkungan, pemangku kepentingan dan sifat voluntari (Dahlsrud 2008 dalam
Jalal 2009).
Seiring perkembangannya, CSR didefinisikan dengan beragam. Beberapa
mengartikan CSR sebagai komitmen bisnis, sementara yang lain menyebutkan
bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah kewajiban. Namun,
terlepas dari hal tersebut, pada dasarnya berbagai perkembangan definisi dari CSR
ini semakin mendekatkan CSR dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Menurut Serageldin ([tidak bertahun]) dalam Sukada et al (2007), “pembangunan
berkelanjutan adalah suatu proses dimana generasi mendatang memperoleh modal
per kapita sebanyak yang telah diperoleh oleh generasi masa sekarang atau bahkan
lebih banyak lagi”. Modal yang dimaksud tersebut mencakup modal natural,
ekonomi, sosial, budaya, politik dan personal (Sukada et al 2007). Artinya,
tanggung jawab etis bisnis dan perusahaan mencakup dua dimensi di luar
ekonomi, yaitu aspek sosial dan lingkungan sehingga kata „social‟ dalam CSR harus dibaca sebagai „social and environmental‟. 4 Oleh karena itu, Sukada et al
(2007) dalam buku Membumikan Bisnis Berkelanjutan pun mendefinisikan CSR
4
sebagai segala upaya manajemen yang dilakukan entitas bisnis untuk mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial
dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan
dampak positif di setiap pilar.
Kegiatan CSR pada praktiknya seringkali hanya menekankan pada salah
satu aspek saja, tergantung pada definisi mana yang dianut oleh perusahaan atau
organisasi bisnis. Berbagai standar CSR yang berkembang dan populer di dunia
memang cenderung menekankan pada salah satu aspek saja akibat keberagaman
definisi CSR ini. Selain itu, membuat sebuah standar kinerja CSR yang universal
bukanlah suatu hal yang mudah. International Organization for Standardization
(ISO) pernah mencoba memprakarsai pembentukan standar universal mengenai
kinerja CSR ini, namun akhirnya malah menurunkan targetnya hanya menjadi
guidelines of social responsibility saja.5
CSR adalah sebuah istilah yang baru merebak di Indonesia. Tahun 2007
lalu, Indonesia menjadi negara pertama yang mengatur CSR ke dalam sebuah
regulasi dengan mengesahkan UU tentang Perseroan Terbatas No. 40 yang
mengatur mengenai tanggung jawab sosial atau CSR. Undang-undang Perseroan
Terbatas No. 40 pasal 74 tahun 2007 ayat satu menyatakan bahwa Perseroan
Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan
sumberdaya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu,
Pasal 74 ayat 2 menyatakan bahwa dana CSR dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran. Ayat ketiga pada pasal ini menekankan bahwa PT yang
tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dimana ayat keempat menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.6
2.1.1.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)
Sukada et al (2007) mendefinisikan CSR sebagai segala upaya manajemen
yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan
5
Ibid., halaman 60.
6
meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif di setiap
pilar. Definisi CSR dari Committee Draft ISO 26000 Guidance on Social
Responsibility pada tahun 2009 bahkan lebih rinci lagi, yaitu:
„Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.‟ (Draft ISO
26000 2009 dalam Jalal 2010)
Dari definisi tersebut, terlihat bahwa yang dimaksud dengan CSR utamanya
dimulai dengan manajemen dampak dari aktivitas bisnis atau perusahaan. Setiap
kegiatan perusahaan tentu disadari pasti memiliki dampak, baik positif maupun
negatif. Oleh karena itu, perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang turut
membantu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan harus
memaksimumkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif yang
ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun panjang, agar tidak merugikan
masyarakat saat ini maupun di masa mendatang. CSR juga berarti bahwa
perusahaan harus taat pada regulasi kemudian berusaha melampaui regulasi
(beyond compliance) tersebut dalam arti yang positif. Pada akhirnya, CSR akan menjamin keberlangsungan perusahaan selama mungkin bahkan dengan profit
yang tinggi sebab perusahaan telah diterima menjadi „bagian‟ dari komunitas
setempat sehingga aktivitas berbisnis menjadi lebih kondusif. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa CSR bukanlah suatu kegiatan amal dari perusahaan. CSR
merupakan bagian dari aktivitas bisnis berupa investasi sosial untuk memperoleh
profit sekaligus „lisensi sosial‟ dari para pemangku kepentingan perusahaan.
Perbedaan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan
menyebabkan konsep CSR sering disamakan bahkan dipertukarkan dengan
berbagai konsep lain yang sebenarnya berbeda. Beberapa konsep yang sering
tertukar dengan CSR adalah sebagai berikut (Sukada et al 2007):
1. Corporate Citizenship
Konsep ini sebenarnya lebih luas daripada CSR sebab corporate
kewajiban yang mendudukkan perusahaan pada posisi quasi state atau setengah negara. Konsep ini memandang perusahaan sebagai warga negara
yang mempunyai hak dan kewajiban. Namun, pada saat yang bersamaan,
perusahaan dipandang pula sebagai pihak yang menjamin dipenuhinya hak-hak
warga negara yang berada di wilayah jangkauan operasinya. Hal ini tentu
tidaklah dapat dipersamakan dengan konsep CSR.
2. Corporate Philanthropy
Konsep filantrofi perusahaan sesungguhnya jauh lebih sempit dibanding
CSR. CSR menuntut perusahaan bertanggung jawab meminimumkan dampak
negatif dan memaksimumkan dampak positif, sedangkan filantrofi hanya
berkenaan dengan pemberian sukarela dari perusahaan. CSR memandang
investasi sosial sebagai upaya memaksimumkan dampak positif (berkaitan
dengan pemangku kepentingan khusus bisnis perusahaan, terutama masyarakat
di wilayah dampak) sedangkan filantrofi tidak terlalu mempedulikan apakah
pemberian itu berkenaan dengan dampak operasi atau tidak.
3. Corporate Responsibility
Konsep ini dinilai terlalu luas atau tidak spesifik (ketika CSR sudah ada)
atau lebih mewakili tanggung jawab memaksimumkan keuntungan bagi
pemilik modal (ketika CSR belum ada). Konsep CR ini memang muncul
karena anggapan bahwa kata „social‟ dalam CSR dapat membawa
kesalahpahaman. Namun, penggunaan kata ini sesungguhnya dimaksudkan
menekankan bentuk tanggung jawab di luar tanggung jawab lain yang
sebelumnya sudah dijalankan. Kata „social‟ dalam CSR harus dibaca sebagai „social and environment‟; yang bahkan juga mencakup pengertian keuntungan ekonomi bagi pemangku kepentingan di luar pemilik modal. CSR harus
dipahami sebagai tanggung jawab pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
pada seluruh pemangku kepentingan di luar pemilik modal.
2.1.1.2 Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia
Indonesia yang menjadi negara pertama yang meregulasi kebijakan
mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menyebutkan pada UU tentang
Perseroan Terbatas No. 40 pasal 1 angka ketiga bahwa Tanggung Jawab Sosial
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.
Terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 pasal 74 tahun 2007 tersebut
memaparkan sebagai berikut:
1. Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau
bersangkutan dengan sumberdaya alam wajib menjalankan tanggung jawab
sosial dan lingkungan,
2. Dana CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
3. Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan
Pemerintah.
2.1.1.3 Standar Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR)
Standar kinerja CSR yang berkembang sangat beragam akibat berbagai
definisi yang berkembang mengenai CSR. Menurut catatan Urminsky, dari 258
standar CSR yang diidentifikasi, sebagian besar (67 persen) dibuat oleh
perusahaan sendiri, hingga pihak lain tak banyak yang mengetahui. Lalu, 11
persen dibuat oleh kumpulan perusahaan; 8 persen dibuat lewat proses multipihak;
7 persen dibuat oleh organisasi nonpemerintah; 3,5 persen dibuat asosiasi pekerja;
dan 0,4 persen dibuat oleh pemerintah. Dari sekian banyak standar CSR yang
teridentifikasi tersebut, hanya 8 persen yang menyatakan komitmen melaporkan
standar yang dipergunakan dan 6 persen saja yang tertarik pada pemantauan dan
evaluasi oleh pihak eksternal (Sukada et al 2007).
Terdapat tujuh standar CSR yang paling berpengaruh saat ini (Kathryn
Gordon dalam Sukada et al 2007). Ketujuh standar tersebut adalah Global
International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 2005 membuat suatu standar kinerja CSR yang tidak hanya menitikberatkan pada salah
satu aspek saja atau dengan kata lain standar kinerja CSR yang „menyeluruh‟.
Tetapi, hal ini tidaklah mudah. Dalam proses pembuatannya, standar kinerja CSR
yang diresmikan pada bulan November 2010 lalu ini akhirnya di„turun‟kan
menjadi hanya pedoman social responsibility saja.
Pedoman CSR atau ISO 26000 dalam draft terbarunya menyebutkan ada
tujuh core subjects yang menjadi pedoman pelaksanaan CSR7, yaitu:
1. Isu Tata Kelola Organisasi
‘Governance systems may vary, depending on the size and type of organization and the economic, political, cultural and social contexts in which it operates. Although governance processes and structures take many different forms, both formal and informal, all organizations make and implement decisions within a governance system. The governance system within an organization is directed by the person or group of persons having the authority and
responsibility for pursuing the organization’s objectives.’
Sistem tata kelola dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan ukuran
organisasi serta konteks ekonomi, politik, budaya dan sosial dimana mereka
beroperasi. Meskipun berbagai proses dan struktur tata kelola memiliki bentuk
yang berbeda-beda, baik formal dan informal, semua organisasi membuat dan
mengimplementasikan keputusan dalam sebuah sistem tata kelola. Sistem tata
kelola dalam organisasi diarahkan oleh orang atau sekelompok orang yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengejar tujuan organisasi.
2. Isu Hak Asasi Manusia
‘While the state has the primary obligation to protect, promote and uphold human rights, the Universal Declaration of Human Rights calls on every individual and every organ of society to play its part in securing the observance of the rights set forth in the Declaration. Hence an organization has a responsibility to safeguard human rights in its operations, as well as in its wider sphere of influence.’
Bila negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi, mempromosikan
dan menegakkan hak asasi manusia, maka Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia menghimbau setiap individu dan elemen masyarakat untuk memainkan
perannya dalam menjamin kepatuhan terhadap hak-hak yang tercantum dalam
7
Deklarasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi memiliki tanggung jawab untuk
menjaga hak asasi manusia dalam operasinya, serta dalam lingkup pengaruh yang
lebih luas.
3. Isu Praktik Ketenagakerjaan
‘The labour practices of an organization can have great impact on society and thereby can contribute significantly to sustainable development. The creation of jobs, as well as wages and other compensation paid for work performed are among an organization's most important economic impacts. Meaningful and productive work is an essential element in human development.’
Praktik buruh suatu organisasi dapat berdampak besar pada masyarakat
dan dengan demikian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap
pembangunan berkelanjutan. Penciptaan lapangan kerja, serta upah dan
kompensasi lainnya yang dibayarkan untuk pekerjaan yang dilakukan adalah salah
satu dampak ekonomi paling penting dari keberadaan organisasi. Bermakna dan
bekerja produktif adalah elemen penting dalam pembangunan manusia.
4. Isu Lingkungan
‘Addressing environmental issues is not only a precondition for the survival and prosperity of our generation; it is a responsibility our generation should fulfill so as to enable future generations to enjoy a sustainable global environment. An organization should be mindful that environmental responsibility is a part of the social responsibility of any organization.’
Isu-isu lingkungan tidak hanya merupakan prasyarat untuk kelangsungan
hidup dan kesejahteraan generasi kita; yang merupakan tanggung jawab yang
harus generasi kita harus penuhi sehingga memungkinkan generasi mendatang
untuk menikmati lingkungan global yang berkelanjutan. Sebuah organisasi harus
menyadari bahwa tanggung jawab lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab
sosial dari setiap organisasi.
5. Isu Praktik Operasi yang Adil
Praktek operasi yang adil akan memperbaiki lingkungan bila organisasi:
mendorong persaingan yang sehat, meningkatkan keandalan dan keadilan
transaksi komersial, mencegah korupsi dan mempromosikan proses politik yang
adil. Organisasi harus menggunakan kekuatan relatif mereka dan posisi dalam
hubungan mereka dengan organisasi-organisasi lain untuk mempromosikan hasil
positif.
6. Isu Konsumen
‘Consumers are among an organization's important stakeholders. An organization's operations and output have a strong impact on those who use its goods or services, especially when they are individual consumers. Consumers are referees in the competitive marketplace, and their preferences and decisions have a strong influence on the success of most organizations.’
Konsumen adalah salah satu pemangku kepentingan organisasi. Operasi
dan output suatu organisasi memiliki dampak yang kuat pada mereka yang
menggunakan barang atau jasa, terutama ketika mereka adalah konsumen
individu. Referensi konsumen di pasar yang kompetitif, serta preferensi dan
keputusan mereka memiliki pengaruh kuat terhadap keberhasilan sebagian besar
organisasi.
7. Isu Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat
‘The need for contributions to social and economic development in order to reduce poverty and improve poor social conditions is universally accepted. The critical need to address issues of social and economic development is reflected in the United Nations Millennium Declaration.’
Kebutuhan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi untuk
mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat miskin
secara universal diterima. Kebutuhan kritis untuk menangani masalah-masalah
pembangunan sosial dan ekonomi tercermin dalam Deklarasi Milenium PBB.
2.1.1.4 Definisi Stakeholder (Pemangku Kepentingan)
Menurut Sukada et al (2007), “perusahaan bertanggung jawab kepada
siapa pun yang terpengaruh operasinya”. Sukada et al (2007) juga memaparkan
bahwa pemangku kepentingan mengacu pada “persons and groups that affect or
Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menimbang derajat relevansi
pemangku kepentingan perusahaan (Mitchell et al 1997 dalam Sukada et al 2007),
yaitu kekuasaan, legitimasi dan urgensi. Kekuasaan adalah derajat kemampuan
pemangku kepentingan untuk mempengaruhi perusahaan melalui penggunaan
unsur-unsur koersif atau pemaksaan; insentif atau disinsentif material; dan
normatif atau simbolik. Legitimasi operasional perusahaan berasal dari perilaku
yang disetujui norma-norma yang berlaku setempat. Urgensi didefinisikan sebagai
klaim pemangku kepentingan untuk tindakan segera yang didasarkan pada
sensitivitas waktu atau sejauh mana keterlambatan dapat diterima; atau sepenting
apa pemenuhan klaim itu terhadap status hubungan dengan perusahaan.
Driscoll dan Starik (2004) dalam Sukada et al (2007) menambahkan
kedekatan (proximity) menjadi kriteria keempat dalam pertimbangan derajat
relevansi tersebut. Dari sejumlah penelitian disimpulkan kedekatan spasial sama
pentingnya dengan urgensi. Artinya, komunitas yang bermukim lebih dekat
dengan perusahaan merupakan pemangku kepentingan yang harus dianggap
penting. Lalu, dengan menggunakan keempat kriteria yang telah diajukan,
disimpulkan bahwa lingkungan fisik merupakan pemangku kepentingan yang sah
dari perusahaan.
Sukada et al (2007) memaparkan bahwa organisasi bisnis memiliki dua
kategori pemangku kepentingan, yakni primer dan sekunder. Pemangku
kepentingan primer adalah pemilik, konsumen, karyawan, pemasok dan mitra
bisnis. Di luar itu, tergantung dari lingkungan di mana perusahaan beroperasi.
Semua perusahaan memiliki pemangku kepentingan sekunder kritis yang
keberadaannya berperan penting terhadap keberlangsungan operasionalnya.
Masyarakat dan pemerintahan yang berwenang merupakan dua diantaranya. Lalu,
perusahaan juga menghadapi sebarisan pemangku kepentingan sekunder khusus
yang muncul karena kepentingan tertentu, aktivitas bisnis, serta tujuan perusahaan
sendiri. Pemangku kepentingan ini termasuk diantaranya media massa, kelompok
masyarakat sipil, ornop, organisasi internasional mitra bisnis, asosiasi dagang,
maupun asosiasi industri.
Menurut Handy (2003) dalam Radyati (2008), kini tujuan keberadaan
lebih baik dengan tujuan tidak hanya memaksimalkan nilai pemegang saham,
akan tetapi juga memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan
(stakeholders). Stakeholders perusahaan ada yang di dalam perusahaan (internal stakeholders), dan ada yang berada di luar perusahaan (external stakeholders).
Internal stakeholders terdiri dari para karyawan dan seluruh anggota perusahaan,
termasuk pemegang saham. External stakeholders terdiri dari pemasok, komunitas
lokal, masyarakat luas, pesaing, pemerintah, kompitetitor dan masyarakat dunia.
Bila hubungan dengan pemangku kepentingan tidak ditangani dengan baik
oleh perusahaan, maka dapat berujung pada konflik. Konflik antara perusahaan
dan masyarakat sering terjadi terutama pada perusahaan-perusahaan yang
bergerak di bidang ekstraktif. Situasi konflik tentu bukanlah hal yang
menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, penguatan kohesi sosial penting
untuk dilakukan perusahaan. Dengan kuatnya kerekatan sosial, sebuah masyarakat
cenderung lebih menerima perbedaan dan mengelola konflik secara rasional
sebelum berkembang menjadi perseteruan yang brutal (Amri dan Sarosa 2008).
Prayogo (2008) menetapkan tiga stakeholder penting yang sering
bermasalah dalam relasinya dengan korporasi, yaitu komunitas lokal, pekerja dan
konsumen. Dengan menggunakan indikator dan parameter yang sama, dapat
diperbandingkan tingkat dinamika konflik korporasi dengan para stakeholder-nya.
Gambar 1 berikut ini menunjukkan gambaran umum tingkat dinamika konflik
Gambar 1. Matriks Tingkat Dinamika Konflik Korporasi-Stakeholder
Secara umum, terdapat kecenderungan bahwa tingkat dinamika konflik
tinggi dapat terjadi pada interaksi: (1) korporasi dengan komunitas lokal pada
industri ekstraktif; (2) korporasi dengan pekerja pada industri manufaktur; dan (3)
korporasi dengan konsumen pada industri jasa. Pola dinamika konflik ini dapat
diperlakukan sebagai sebuah kecenderungan, namun sangat membantu
menjelaskan variasi tingkat dinamika konflik antar jasa industri (Prayogo, 2008).
2.1.2 Konsep PKBL
Menurut UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 88, BUMN dapat
menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha
kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN (Ayat 1) dan ketentuan
lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba tersebut diatur dengan
Keputusan Menteri (Ayat 2).8 Lalu, Keputusan Menteri BUMN No.
Kep-236/MBU/2003 yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari UU no. 19 tahun 2003
8
DPR RI, 2003, Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
menyebutkan pada Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan Program Kemitraan
BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah
program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan
mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (Ayat 3) dan Program
Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh
BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian
laba BUMN (Ayat 4).9 Keputusan Menteri tersebut diperkuat kembali dengan
Peraturan Menteri tentang BUMN no. 5 tahun 2007.
Rincian panduan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
dipaparkan pada Peraturan Menteri tentang BUMN no. 5 tahun 2007.10 Khusus
untuk Program Bina Lingkungan, Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri ini
menyatakan bahwa dana untuk Program Bina Lingkungan bersumber dari
penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 persen serta hasil bunga
deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan. Pada ayat 3 pasal
9 ini disebutkan bahwa untuk Perum, besarnya dana Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sedangkan untuk
Persero, besaran dana tersebut ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Namun, dalam kondisi tertentu, besarnya dana Program Kemitraan dan
dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak
dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri atau RUPS (ayat 4). Dana dari
laba dikurangi pajak yang telah ditetapkan tersebut diberikan selambat-lambatnya
45 hari setelah penetapan (ayat 5). Lalu, pembukuan dana Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan ini dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan
BUMN Pembina (ayat 6). KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, http://202.51.31.250/id/files/peraturan/Kepmen/KEPMEN_236%20Thn%202003%20program %20kemitraan%20BUMN%20dengan%20usaha%20kecil%20dan%20program%20bina%20lingkungan.pdf,
diakses pada 6 Mei 2010, halaman 2.
a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun,
penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa giro
dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya.
b. Setiap tahun berjalan sebesar 70 puluh persen dari jumlah dana Program BL
yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.
c. Setiap tahun berjalan sebesar 30 persen dari jumlah dana Program BL yang
tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina
dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana
Program BL tahun berikutnya.
e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
1) Bantuan korban bencana alam;
2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3) Bantuan peningkatan kesehatan;
4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
5) Bantuan sarana ibadah;
6) Bantuan pelestarian alam;
f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.
2.1.3 Konsep Persepsi
Menurut Ruslan (2006), persepsi adalah suatu proses memberikan makna
yang berakar dari berbagai faktor , yakni:
1. latar belakang budaya, kebiasaan dan adat-istiadat yang dianut seseorang atau
masyarakat;
2. pengalaman masa lalu seseorang/kelompok tertentu menjadi landasan atas
pendapat atau pandangannya;
3. nilai-nilai yang dianut (moral, etika dan keagamaan yang dianut atau nilai-nilai
yang berlaku di masyarakat); dan
4. berita-berita dan pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai
pengaruh terhadap pandangan seseorang. Bisa diartikan bahwa berita-berita
yang dipublikasikan dapat menjadi pembentuk opini masyarakat.
Menurut Pareek (1996) dalam Sobur (2003), “persepsi adalah proses
memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data”. Persepsi dalam
perspektif ilmu komunikasi dapat disebut sebagai inti komunikasi, sedangkan
interpretasi sebagai inti persepsi yang identik dengan decoding dalam proses
komunikasi (Sobur, 2003). Menurut Wenburg dan Wilmot ([tidak bertahun])
dalam Mulyana (2000) dalam Sobur (2003), “persepsi dapat didefinisikan sebagai
cara organisme memberi makna”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah
suatu proses memberikan makna, pandangan atau penafsiran terhadap suatu pesan
atau informasi berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa atau
hubungan-hubungan yang diperoleh sebelumnya mengenai pesan tersebut.
2.1.4 Konsep Pemberdayaan
Upaya pemberdayaan (empowerment) menurut Nasdian (2003) merupakan
suatu upaya menumbuhkan peranserta dan kemandirian sehingga masyarakat baik
di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki
kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada
sumberdaya, memiliki kesadaran kritis serta mampu melakukan pengorganisasian
dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan
dilingkungannya. Dua elemen pokok pemberdayaan adalah partisipasi dan
kemandirian. Pemberdayaan dilakukan agar warga komunitas mampu
berpartisipasi untuk mencapai kemandirian.
Menurut Nasdian (2003), “partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil
oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri,
dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana
mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif”. Titik tolak dari partisipasi
adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut
sebagai subjek yang sadar. Partisipasi dikategorikan menjadi dua, yaitu:
1. warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau
dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain;
2. partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah
mereka sendiri.11
11