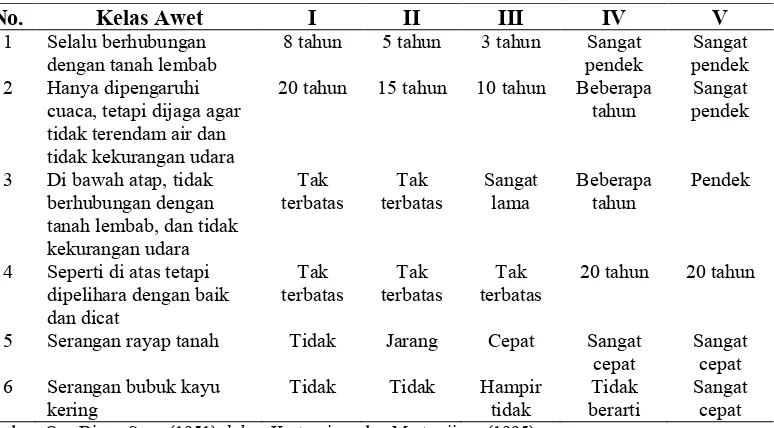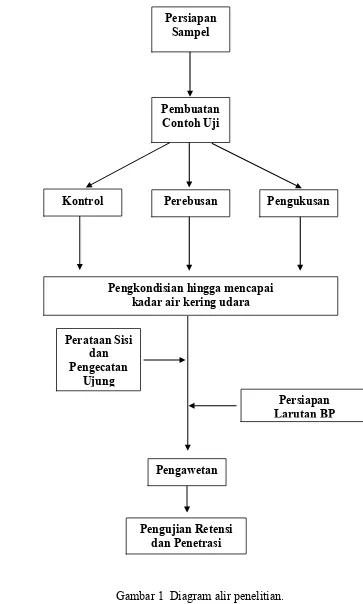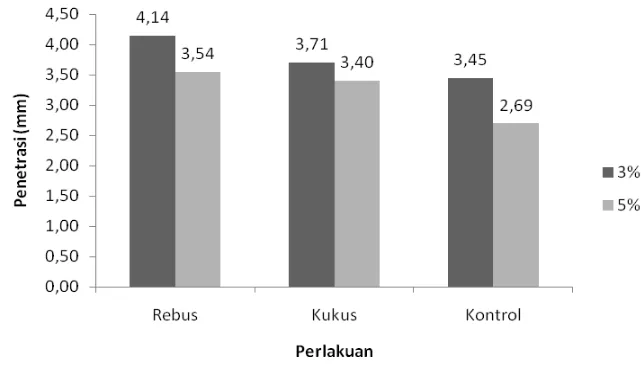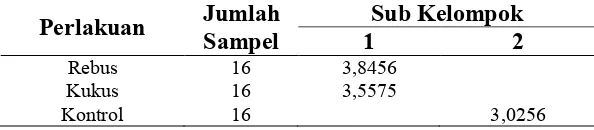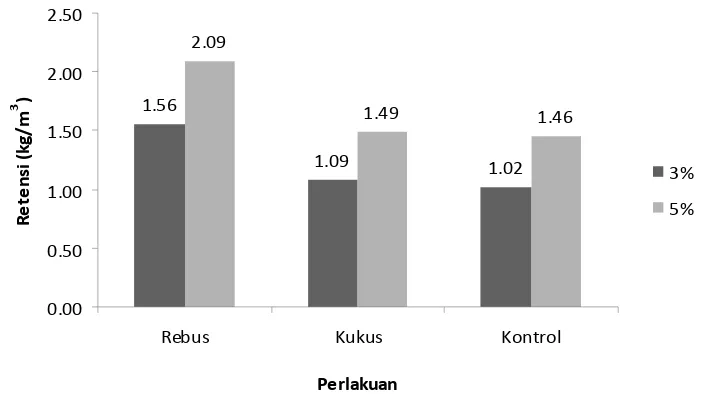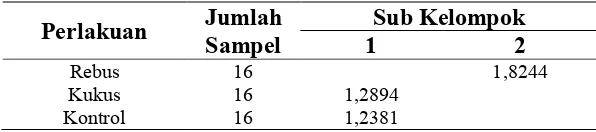" #!$%$
&'() * +)', " #!$%$ &-)(* (. '))& ( )/*)& 0) . *1 keterawetan yang sukar, sehingga membutuhkan perlakuan awal sebelum kayu diawetkan untuk meningkatkan permeabilitas kayu agar bahan pengawet dapat mudah masuk. Penelitian tentang pengaruh perebusan dan pengukusan pada kayu mindi terhadap penetrasi dan retensi bahan pengawet masih sangat terbatas. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh perbedaan perlakuan awal sebelum kayu diawetkan khususnya perebusan dan pengukusan terhadap penetrasi dan retensi bahan pengawet Diffusol-CB sehingga diketahui perlakuan yang optimum untuk menghasilkan kayu awetan mindi terbaik.
Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga batang kayu mindi berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 280 cm dari bagian pangkal batang yang diperoleh dari usaha penggergajian sekitar Jonggol. Bahan lainnya terdiri dari diffusol-CB sebagai bahan pengawet, cat altex, etanol, HCl, asam salisilat, asam rubianat, aseton, amonia, , dan akuades.
Balok terlebih dahulu dipotong-potong untuk menghasilkan sampel yang berukuran 5 cm x 5 cm x 20 cm, lalu disortir untuk menjamin keseragaman dalam hal kadar air, bentuk dan berat, porsi bagian gubal dan teras, serta kualitas kayu (tanpa cacat). Setelah disortir, kayu kemudian direbus dan dikukus. Kayu-kayu hasil perebusan dan pengukusan tersebut selanjutnya diserut sehingga saat diawetkan ukuran sampel adalah 4 cm x 4 cm x 20 cm. Metode pengawetan yang digunakan adalah proses rendaman dingin selama 48 jam dengan konsentrasi larutan bahan pengawet 3% dan 5%. Dengan demikian maka jumlah total contoh uji yang digunakan adalah 48 sampel, masing-masing delapan kali ulangan untuk perebusan, pengukusan, dan kontrol (tanpa perlakuan).
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlakuan perebusan memberikan nilai penetrasi dan retensi yang terbaik. Perebusan yang diikuti oleh proses pengawetan dengan bahan pengawet berkonsentrasi 3% menghasilkan nilai penetrasi bahan pengawet Diffusol-CB khususnya senyawa boron yang terdalam (4,14 mm), dan perebusan yang diikuti oleh proses pengawetan dengan bahan pengawet berkonsentrasi 5% menghasilkan nilai retensi yang tertinggi (2,09 kg/m3). Perlakuan awal khususnya perebusan dan pengukusan sebelum kayu mindi diawetkan dengan bahan pengawet Diffusol-CB ternyata mampu meningkatkan nilai penetrasi dan retensi bahan pengawet. Namun, rata-rata nilai penetrasi dan retensi yang diperoleh dari penelitian ini masih belum memenuhi nilai standar sebagaimana SNI 03-5010.1-1999.
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “ &-)(* (. '))& ( )/*)& 0) . *1 )+* ,)0 2/)& 2 ( )')3 & 2()4,
')& 2 &4, 3)') )+* ,&', 9 adalah
benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan
belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga
manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan
maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan
dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Bogor, April 2011
Judul Skripsi : Pengaruh Perbedaan Perlakuan Awal (Sebelum Kayu Diawetkan) terhadap Penetrasi dan Retensi CB
pada Kayu Mindi ( L.)
Nama : Indra Mulyadi
NIM : E24051383
Menyetujui: Komisi Pembimbing
Pembimbing Utama
Prof. Dr. Ir. Iding M. Padlinurjaji NIP. 130354166
Pembimbing Kedua
Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS NIP. 19630106 198703 1 004
Mengetahui:
Ketua Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
segala limpahan rahmat, karunia, kasih sayang, petunjuk, ridho dan
hidayah-Nyalah penulis memperoleh segala kekuatan dan kemudahan dalam mengerjakan
skripsi yang berjudul : &-)(* (. '))& ( )/*)& 0) . *1 )+* ,)0 2/)& 2 ( )')3 & 2()4, ')& 2 &4, 3)') )+* ,&',
9
Segala upaya dalam menyusun skripsi ini telah penulis lakukan, namun
penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis ingin
mengucapkan permohonan maaf dan dengan senang hati penulis akan menerima
berbagai kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna
penyempurnaan lebih lanjut.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. M. Iding
Padlinurjaji dan Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS selaku dosen pembimbing.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu, dan adik tercinta serta
seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya. Ungkapan terima kasih
juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penulis
dapat menyelesaikan studi di IPB.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala
bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bukan hanya
bermanfaat bagi penulis tetapi dapat pula bermanfaat bagi pembaca pada
umumnya.
Bogor, April 2011
Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 28 Agustus 1988 sebagai anak
pertama dari empat bersaudara dari pasangan Eddi Iskandar (Bapak) dan Parni
(Ibu).
Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Waluya Cikarang pada tahun 1999,
pendidikan menengah pertama di SLTPN 1 Cikarang pada tahun 2002, sedangkan
pendidikan menengah atas di SMUN 1 Cikarang pada tahun 2005. Pada tahun
yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur SPMB dan
setahun kemudian memilih Departemen Teknologi Hasil Hutan Fakultas
Kehutanan IPB.
Selama pendidikan penulis mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan
yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hasil Hutan (HIMASILTAN)
Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan. Penulis juga telah melaksanakan
Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Indramayu - Linggarjati (2007),
Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi
(2008) dan Praktek Kerja Lapang (PKL) di KBM Industri Kayu Cepu, Batokan,
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat
dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini
berjudul Pengaruh Perbedaan Perlakuan Awal (Sebelum Kayu Diawetkan)
terhadap Penetrasi dan Retensi -CB pada Kayu Mindi (
L.).
Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada :
1. Prof. Dr. Ir. M. Iding Padlinurjaji dan Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS selaku
dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan
serta motivasi selama penulis menyusun proposal skripsi ini.
2. Dr. Ir. Gunawan Santosa, MS (DMNH), Ir. Agus Priyono, MS (DKSH), dan
Ir. Iwan Hilwan, MS (DSVK) selaku dosen penguji wakil masing-masing
departemen di lingkup Fakultas Kehutanan IPB.
3. Kedua orang tua yang dengan sabar dan tulus senantiasa memberikan
dukungan moril maupun materil serta do’a yang selalu diberikan.
4. Tanteku Dhyana Nur yang telah memberikan dukungan moril maupun materil
kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Segenap tenaga kependidikan di Departemen Hasil Hutan yang telah melayani
dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Christin Anggraeni yang telah memberikan bantuan dukungan dan dorongan
kepada penulis.
7. Rekan-rekan THH 42: Bayu, Fahriyan, Isran, Riva, Ardiansyah, Dina, Yudo,
Abdur, Haerul, Oki, Bagus, Peppy, Ridho, Yoki, Ali, Fandi, dan rekan-rekan
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan
kebersamaannya.
Bogor, April 2011
Halaman
2.3 Metode Pengawetan Kayu. ... 5
2.4 Bahan Pengawet. ... 9
2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawetan. ... 13
2.6 Pengukusan. ... 14
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 29
. DAFTAR PUSTAKA . ... 30
Halaman
Tabel 1 Klasifikasi Keawetan Kayu di Indonesia ... 4
Tabel 2 Analisis sidik ragam pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan, konsentrasi bahan pengawet, serta inteaksi keduanya terhadap penetrasi boron ... 24
Tabel 3 Hasil uji Duncan tentang pengaruh perlakuan awal terhadap
penetrasi ... 25
Tabel 4 Analisis sidik ragam pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan, konsentrasi bahan pengawet, serta inteaksi antara
perlakuan dan konsentrasi terhadap retensi bahan pengawet ... 26
Halaman
Gambar 1. Penetrasi boron... ... 23
Gambar 2. Penetrasi tembaga ... ... 23
Gambar 3. Rata-rata nilai penetrasi boron pada seluruh kombinasi
perlakuan... 23
Halaman
Lampiran 1. Rata-rata penetrasi (mm) pada masing-masing perlakuan dan tingkat konsentrasi bahan pengawet ... 33
! ! )2)(
)/)&-Kelangkaan bahan baku kayu berkualitas cenderung meningkat dari tahun
ke tahun mengingat semakin berkurangnya produktifitas dan kualitas tegakan
hutan alam yang ada. Dari 46 juta m3 kebutuhan kayu bulat selama tahun 2008,
total produksi yang mampu dihasilkan dari berbagai kawasan hutan hanya sekitar
32 juta m3 (BPS 2009). Oleh karena itu untuk saat ini maupun masa yang akan
datang sebagian besar kebutuhan kayu untuk berbagai keperluan diperkirakan
akan sangat bergantung pada kayu-kayu hasil Hutan Tanaman Industri (HTI), dari
hutan rakyat, dan dari kebun.
Kayu-kayu hasil hutan tanaman dan dari hutan rakyat umumnya bersifat
inferior dibandingkan kayu-kayu hutan alam, khususnya dari segi keawetan dan
kekuatannya karena kayu dihasilkan dari pohon yang pertumbuhannya cepat.
Pohon yang cepat tumbuh pada umumnya menghasilkan kayu dengan kandungan
ekstraktif dan kerapatan kayu yang lebih rendah serta dinding sel yang lebih tipis.
Akibatnya keawetan alami kayu menjadi berkurang (sangat rentan terhadap
berbagai serangan organisme perusak), dan kurang kuat (kelas kuat yang lebih
rendah). Agar kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan dengan nilai guna yang
setara atau mendekati kayu-kayu sejenis dari hutan alam, maka diperlukan
perlakuan khusus terkait dengan peningkatan mutu kayu sebelum digunakan.
Salah satu perlakuan yang dapat dilakukan adalah dengan mengawetkan kayu.
Kayu mindi ( ) merupakan salah satu jenis yang banyak
digunakan dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman. Kayu dengan corak yang
indah ini ditujukan sebagai bahan baku pembuatan ( ). Karena
memiliki keawetan alami yang rendah dan keterawetan yang sedang sampai sukar
(Wahyudi . 2007), proses peningkatan kualitas kayu mindi perlu segera
ditemukan agar umur pakai produk dan kekuatan kayu semakin bertambah. Proses
peningkatan mutu yang diterapkan haruslah bersifat mudah dan murah sehingga
dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Apabila proses peningkatan mutu yang
beragam. Hal ini secara tidak langsung akan mengatasi masalah kelangkaan bahan
baku industri perkayuan.
Pengawetan kayu merupakan suatu proses memasukkan bahan pengawet
ke dalam kayu dengan tujuan untuk meningkatkan masa pakai kayu. Prosesnya
sangat bervariasi mulai dari yang sederhana (tanpa tekanan) hingga yang canggih
(menggunakan tekanan dan vakum) bergantung pada nilai penetrasi dan retensi
yang diinginkan. Pada umumnya semakin canggih proses yang diterapkan, akan
semakin besar pula nilai penetrasi dan retensi yang dihasilkan untuk jenis yang
sama.
Penetrasi dan retensi dipengaruhi oleh permeabilitas kayu. Semakin tinggi
permeabilitas, semakin dalam penetrasi yang terjadi. Penetrasi yang dalam
memungkinkan semakin bertambahnya nilai retensi. Mengingat kayu mindi
tergolong sukar hingga sedang dimasuki oleh bahan pengawet (kurang
permeabel), maka diperlukan perlakuan awal tertentu terhadap kayu sebelum
diawetkan. Perlakukan awal berupa perebusan, pengukusan, atau menginfeksi
kayu dengan jamur dan bakteri diketahui mampu meningkatkan permeabilitas
kayu (Ishikawa . 2004).
Mengingat perlakuan menginfeksi kayu dengan jamur dan bakteri
tergolong rumit dan mahal sehingga sulit diterapkan dimasyarakat, maka
penelitian ini difokuskan pada pengaruh perebusan dan pengukusan terhadap nilai
retensi dan penetrasi bahan pengawet pada kayu mindi.
! *7*)& & ,2,)&
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh perbedaan perlakuan
awal sebelum kayu diawetkan (perebusan dan pengukusan) terhadap penetrasi dan
retensi bahan pengawet Diffusol-CB pada kayu mindi sehingga diketahui
perlakuan yang optimum untuk menghasilkan kayu awetan mindi terbaik.
! $ )&5))2 & ,2,)&
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai
pihak khususnya pengguna kayu mindi dalam rangka pemanfaatan kayu secara
; ! &-)0 2)& )+*
Tarumingkeng (2000) menyebutkan bahwa pengawetan kayu tidak lain
adalah proses memasukkan bahan-bahan beracun (pestisida) yang mampu
menolak bahkan membunuh hama. Hunt dan Garrat (1986) menyatakan bahwa
pada prinsipnya pengawetan kayu adalah proses memasukkan bahan pengawet ke
dalam kayu dengan tujuan untuk melindungi kayu atau memperpanjang umur
pakai kayu sehingga dapat mengurangi frekuensi penggantian kayu pada
bangunan konstruksi permanen atau bangunan semi permanen. Tindakan
pengawetan dapat juga bertujuan agar kayu lebih tahan terhadap api (Padlinurjaji
1980).
Secara umum, pengawetan kayu adalah perlindungan kayu terhadap semua
faktor yang dapat merusak yang pada akhirnya menyebabkan kayu menjadi
hancur. Dalam pengertian praktis, pengawetan kayu bermakna meningkatkan
keawetan alami kayu dengan perlakuan bahan kimia yang bersifat racun terhadap
serangga, jamur, dan faktor perusak lain.
Sebelum diawetkan, kayu harus sudah betul-betul dikerjakan agar setelah
diawetkan kayu tidak perlu dikerjakan lagi. Demikian juga kadar air kayu harus
disesuaikan dengan cara pengawetan yang akan dilakukan, misal kayu harus
dalam keadaan basah apabila akan diawetkan dengan proses difusi, tetapi harus
dalam keadaan kering atau setengah kering apabila akan diawetkan dengan cara
rendaman atau dengan proses vakum/tekan (Padlinurjaji 1980).
Keefektifan suatu bahan pengawet sebagian tergantung pada daya
racunnya atau kemampuan menjadikan kayu itu beracun terhadap
organisme-organisme atau makhluk perusak yang makan atau masuk ke dalam kayu untuk
memperoleh perlindungan (Hunt dan Garrat 1986). Penetrasi adalah dalamnya
penembusan bahan pengawet ke dalam kayu, sedangkan retensi adalah jumlah
bahan pengawet yang tinggal dalam kayu yang dinyatakan dalam kg/m3 (SNI
03-5010.1-1999). Kayu yang sudah diawetkan umum disebut dengan istilah kayu
)0 2)& ')& 2 ()0 2)& )+*
Menurut Hunt dan Garrat (1986), keawetan kayu ialah daya tahan suatu
jenis kayu terhadap organisme perusak yang datang dari luar tubuh kayu itu
sendiri. Keawetan alami ditentukan oleh zat ekstraktif yang bersifat racun
terhadap organisme perusak tadi, sehingga organisme perusak tidak sampai masuk
atau tinggal didalam kayu dan merusak kayu. Dengan sendirinya keawetan alami
ini akan bervariasi sesuai dengan variasi jumlah serta jenis zat ekstraktif yang ada.
Klasifikasi Keawetan Kayu di Indonesia disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi Keawetan Kayu di Indonesia
6 )4 0 2 < <
Sumber: Oey Djoen Seng (1951) Kartasujana dan Martawijaya (1995)
Keterawetan kayu adalah mudah-tidaknya kayu untuk ditembus oleh bahan
pengawet sampai mencapai retensi dan penetrasi tertentu yang secara ekonomis
menguntungkan dan efektif untuk mencegah faktor perusak kayu. Menurut
Tobing (1977), keterawetan kayu sangat bervariasi. Kayu gubal mempunyai
keterawetan yang lebih tinggi karena bagian ini sebelumnya berfungsi sebagai
penyalur air dan hara dari akar ke daun. Kayu teras mempunyai sifat keterawetan
yang kurang baik karena sudah memiliki deposit-deposit lain termasuk ekstraktif
yang menutupi sel-sel kayu. Keterawetan atau permeabilitas kayu sering disebut
Menurut Hunt dan Garrat (1986), treatibilitas kayu dibagi kedalam tiga
golongan, yaitu:
a) Sarang (permeabel): kayu dapat dipenetrasi seluruhnya atau mudah diimpregnasi.
b) Sedang (moderat): penetrasi lateral sebesar ¼-½ inci (0,6-1,2 cm) dapat dicapai dalam waktu 2-3 jam dibawah tekanan.
c) Sukar ( ): kayu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai penetrasi sedalam 1/8-¼ inchi (0,3-0,6 cm) dibawah tekanan.
$ 26' &-)0 2)& )+*
Secara garis besar metode pengawetan menurut Hunt dan Garrat (1986);
Tsoumis (1991) dapat dibagi atas 4 golongan yaitu:
1. Metode pengawetan tanpa tekanan, dimana kayu-kayu diawetkan secara pelaburan/penyemprotan, pencelupan, rendaman, rendaman dingin dan rendaman panas-dingin.
2. Metode pengawetan dengan tekanan atau vakum, dimana kayu-kayu diawetkan dalam silinder tertutup dan diberi tekanan atau diberi vakum.
3. Metode difusi, dimana kayu-kayu basah atau kayu segar diawetkan dengan bahan-bahan pengawet yang berkonsentrasi tinggi
4. , dimana cara ini digunakan hanya untuk batang yang
baru ditebang.
Metode pengawetan tanpa tekanan terdiri dari pelaburan/penyemprotan
( ), pencelupan ( ), rendaman ( ), rendaman
dingin ( ), dan rendaman panas-dingin ( ). Metode
dengan tekanan dan vakum tekan terdiri dari metode sel penuh ( ) dan sel
kosong ( ).
Dalam cara ini, bahan pengawet dilaburkan/disemprotkan ke
permukaan kayu yang telah dikeringkan lebih dahulu dan dibiarkan dalam
beberapa waktu. Pelaburan bahan pengawet dapat dilakukan beberapa kali,
yang biasa dilakukan apabila pelaburan pertama telah mengering. Hasilnya
dipengaruhi oleh mudah tidaknya kayu dipenetrasi dan jumlah bahan
pengawet yang dilaburkan. Biasanya digunakan bahan pengawet
yang tidak mudah berfiksasi. Penetrasi yang dicapai dangkal sehingga
perlindungan kayu tidak maksimal.
Dalam cara ini kayu-kayu diawetkan dengan mencelupkannya ke
dalam larutan bahan pengawet selama beberapa detik atau beberapa menit.
Agar hasilnya lebih baik, sebaiknya kayu-kayu tersebut dikeringkan lebih
dahulu. Cara ini lebih menguntungkan dari cara pelaburan karena
penetrasinya lebih baik pada retakan-retakan dan lubang-lubang kayu serta
waktu kontak yang lebih lama dengan bahan pengawet, akan tetapi
biasanya lebih mahal karena memerlukan peralatan tambahan serta jumlah
bahan pengawet yang lebih banyak. Biasanya larutan bahan pengawet
yang digunakan adalah atau . Perlu diingat
bahwa penetrasinya juga dangkal.
!
Dalam cara ini kayu-kayu direndam di dalam tanki-tanki yang berisi
bahan pengawet larut air selama beberapa hari atau beberapa minggu.
Umumnya lama perendaman maksimum 2 minggu. Retensi yang cepat
terjadi dalam 2-3 hari pertama, setelah itu retensi berjalan sangat lambat.
Karena retensi yang rendah maka konsentrasi bahan pengawet harus lebih
tinggi dibanding untuk proses tekanan. Salah satu cara rendaman yang
mendapat paten di Inggris pada tahun 1832 disebut " . Disini kayu direndam selama 7-10 hari dalam larutan
(sublimat) 0,67%. " ini mengalami modifikasi dan cara baru ini disebut # " dimana bahan pengawet yang digunakan
adalah campuran 0,67% dengan NaCl 1%. Dalam kedua
cara ini, digunakan peralatan-peralatan yang tahan karat. Saat ini senyawa
merkuri sudah tidak digunakan lagi mengingat dampak negatif yang dapat
ditimbulkannya.
$ !
Dalam cara ini, kayu-kayu diawetkan dengan cara merendam
beberapa hari atau beberapa minggu. Umumnya digunakan bahan
pengawet . Lebih dari separuh retensi terjadi pada hari
pertama (24 jam pertama). Penetrasi pada kayu-kayu yang tidak
mengalami pengeringan lebih dulu biasanya sangat dangkal. Juga cara ini
kurang baik hasilnya bila dilakukan terhadap jenis-jenis kayu daun lebar
karena retensi dan penetrasinya dangkal.
% !
Cara ini mendapat paten dalam tahun 1867 atas nama C.A. Seely dan
dikenal juga dengan nama atau .
Disini kayu-kayu yang telah dikeringkan direndam di dalam bahan
pengawet panas, kemudian dipindahkan ke dalam bahan pengawet dingin.
Untuk melaksanakan proses ini ada beberapa cara yaitu (Hunt dan Garrat
1986):
1. Memindahkan kayu-kayu yang telah direndam dalam bahan pengawet yang dipanaskan ke tanki lain dimana bahan pengawet relatif dingin.
2. Dengan membuang bahan pengawet panas dan segera diganti dengan bahan pengawet dingin.
3. Dengan menghentikan pemanasan dan membiarkan kayu serta bahan
pengawet tadi menjadi dingin bersama-sama.
& '
Pada umumnya dilakukan didalam suatu tabung silinder tertutup.
Dibandingkan dengan metode-metode lain, metode tekanan mempunyai
beberapa keuntungan yaitu a) proses pengawetan relatif lebih cepat, b)
proses pengawetan dapat dikontrol sehingga retensi/penetrasi dapat diatur
sesuai dengan keinginan dan dengan sendirinya pemakaian bahan
pengawet menjadi lebih efisien, serta c) retensi lebih tinggi serta
penetrasinya lebih dalam dan merata. Adapun kelemahannya adalah a)
memerlukan alat-alat yang khusus yang harganya mahal sehingga
investasinya tinggi, b) kayu-kayu yang akan diawetkan harus diangkut
sehingga menambah biaya dalam transportasi, dan c) alat-alat yang
(
Sesuai dengan namanya maka dalam metode ini seluruh/sebagian
besar masuknya bahan pengawet ke dalam kayu adalah berdasarkan
prinsip difusi. Agar hasil retensi dan penetrasi cukup dalam maka kadar air
kayu yang diawetkan harus cukup tinggi serta konsentrasi bahan pengawet
yang tinggi. Biasanya bahan pengawet yang digunakan adalah berbentuk
pasta atau , yang tidak mudah berfiksasi.
Beberapa metode difusi yang dikenal antara lain adalah (Hunt dan
Garrat 1986):
a. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk
membentuk endapan didalam kayu yang tahan terhadap pelunturan. Hal ini dilakukan dengan mula-mula merendam kayu segar ke dalam
larutan dan kemudian merendam ke dalam larutan
. Dengan masuknya , maka
terbentuklah endapan di dalam kayu dimana endapan
ini bersifat racun terhadap organisme perusak kayu serta tahan terhadap pelunturan.
) Dalam cara ini, bahan pengawet yang digunakan adalah berbentuk pasta atau dan disapukan ke seluruh permukaan kayu setelah kayu dilapisi dengan bahan yang ' . Kemudian dibiarkan selama ± 30 hari. Lamanya proses ini tergantung pada ukuran dan jenis kayu yang diawetkan. Retensi minimum yang disarankan adalah ¼ - ½ (4-8 kg/m3).
*
Metode ini mendapat paten pada tahun 1838 atas nama penemunya
yaitu Dr. Boucheri dari Perancis. Semula metode ini dilakukan terhadap
pohon-pohon yang baru ditebang, dimana cabang-cabang, ranting-ranting
dan daunnya masih lengkap. Bahan pengawet diberikan dari pangkal
batang dan mengalir keseluruh pohon (pada kayu gubal) karena adanya
transpirasi oleh daun.
Metode ini mengalami perubahan yang dibuat oleh Mathis (Inggris)
dimana sekarang ini, proses ini hanya dilakukan untuk log atau poles yang
baru ditebang. Bahan pengawet disimpan pada sebuah bak setinggi 10 m
dari tanah, dan dialirkan ke pangkal batang melalui slang atau pipa. Proses
ini dapat dilihat pada ujung batang. Biasanya digunakan bahan pengawet
( # ), karena mempunyai keuntungan dibandingkan bahan-bahan pengawet larut air yang tidak berwarna, dimana mudah
dilihat apakah proses sudah cukup atau belum.
" ) )& &-)0 2
Hunt dan Garrat (1986) menyebutkan bahwa bahan pengawet kayu ialah
bahan-bahan kimia yang apabila diterapkan secara baik pada kayu, akan membuat
kayu itu tahan terhadap serangan cendawan, serangga, atau cacing-cacing kapal.
Efek perlindungannya itu tercapai dengan menjadikan kayu itu beracun atau kalis
terhadap organisme yang menyerangnya. Bahan-bahan pengawet ini dapat berupa
senyawa-senyawa kimia murni atau campuran dari senyawa-senyawa.
Bahan-bahan pengawet ini sangat berbeda dalam sifat, harga, keefektifan, dan kecocokan
penggunaannya di bawah kondisi-kondisi pemakaian yang berbeda-beda.
Suatu bahan kimia harus mampu menembus kayu sampai cukup dalam,
apabila diinginkan daya proteksi yang tinggi. Penutupan ( ) permukaan
kayu tidak cukup efektif sebab apabila kayu itu mengering bahan penutup ini akan
mudah pecah, hilang, atau retak-retak. Bahan-bahan padat dan sangat kental tidak
dapat meresap kedalam kayu.
Sifat korosif dari bahan pengawet kayu adalah sifat yang tidak diinginkan,
sebab hal ini merusak logam dari alat pengawetannya dan paku serta logam
pengokoh lainnya yang mungkin dimasukkan ke dalam kayu itu.
Menurut Tsoumis (1991), bahan pengawet dibagi dalam tiga golongan
yaitu: (a) bahan pengawet berupa minyak, (b) bahan pengawet larut minyak, dan
(c) bahan pengawet larut air.
2.4.1 Bahan pengawet berupa minyak, khususnya kreosot.
Kreosot dihasilkan dari destilasi batubara dan bahan ini mengandung
berbagai macam senyawa yang beberapa diantaranya sangat efektif
terhadap faktor-faktor perusak kayu. Bahan pengawet ini telah digunakan
lebih dari 100 tahun dan memberikan hasil yang baik.
Kreosot mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan antara lain
sangat beracun terhadap cendawan, serangga dan , permanen,
pengawetan, tidak bersifat korosif terhadap metal, penetrasi mudah
dikontrol, dan harganya murah. Disamping sifat-sifat yang
menguntungkan, kreosot juga mempunyai kekurangan-kekurangan seperti
baunya tidak enak, mempunyai tendensi meleleh terutama bila
disingkapkan terhadap sinar matahari, kayu menjadi tidak dapat dicat,
merangsang kulit dan komposisi kimianya sangat bervariasi.
2.4.2 Bahan pengawet larut minyak
Banyak yang bersifat sangat beracun terhadap organisme perusak
kayu, akan tetapi umumnya sangat mahal serta tidak baik digunakan
secara tunggal. Beberapa bahan pengawet ini sangat mudah menguap
(# ) sehingga tidak tahan lama di dalam kayu. Selain itu karena bersifat korosif terhadap metal, tidak stabil pada penyingkapan di udara
terbuka, resistensinya rendah terhadap pelunturan, berbahaya terhadap
manusia dan binatang, bau yang keras dan lain sebagainya.
Dari berbagai macam bahan pengawet golongan ini baru 3 macam
yang nyata-nyata efektif berdasarkan + , #
+ -+, +. dalam Hunt dan Garrat (1986) yaitu
(PCP), , dan *
. Sayangnya meskipun PCP mempunyai sifat-sifat yang lebih
baik, penggunaan PCP sudah sejak lama dilarang karena sangat berbahaya
bagi manusia dan lingkungan.
2.4.3 Bahan pengawet larut air
Sifat-sifat yang menguntungkan dari bahan pengawet kelompok ini
antara lain: a) dapat diangkut dalam bentuk padat atau dalam konsentrasi
tertentu ke tempat penggunaan, sedangkan bahan-bahan pelarutnya (air)
harganya murah, b) formulasinya mudah diatur agar bersifat racun
terhadap cendawan atau serangga, c) kayunya tetap bersih dan dapat dicat,
d) umumnya tidak berbau, dan e) tidak meninggikan sifat bakar kayu dan
dapat dikombinasikan dengan bahan penghambat api ( ).
Keburukan dari bahan pengawet ini adalah bahan ini membasahkan
kembali kayu sehingga menimbulkan perubahan dimensi kayu. Karena itu
bahan pengawet larut air adalah pada umumnya mudah tercuci atau mudah
luntur (Padlinurjaji 1985).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka bahan pengawet yang baik haruslah
memiliki sifat-sifat, diantaranya adalah:
a) Bersifat racun terhadap organisme perusak kayu walaupun dalam konsentrasi yang sangat rendah.
b) Permanen.
c) Mudah diimpregnasikan (daya penetrasi tinggi) serta mudah dikontrol.
d) Aman didalam pengangkutan dan penggunaan.
e) Tidak bersifat korosif
f) Tersedia dalam jumlah yang banyak.
Bahan pengawet -CB adalah bahan pengawet kayu larut air yang
berbentuk garam yang terdiri dari asam borat, boraks, tembaga dan khromium
dengan formulasi CuSO4 (32,4%), H3BO3 (21,6%), dan Na2Cr2O7 (36,0%). Bahan
berbentuk pasta berwarna coklat gelap serta berbau. Menurut Hunt dan Garrat
(1986), -CB merupakan salah satu bahan pengawet yang larut air.
Senyawa bor sudah lama dikenal sebagai salah satu bahan yang dapat
dipakai untuk mempertinggi daya tahan kayu terhadap api. Penelitian selanjutnya
menunjukkan bahwa senyawa bor itu dapat pula mempertinggi daya tahan kayu
terhadap jamur. Menurut Jayanetti (1978), kayu yang diawetkan dengan senyawa
bor tidak sesuai untuk dipasang pada struktur yang berhubungan dengan tanah
(lembab) atau sering kena hujan karena fiksasinya rendah.
Beberapa sifat persenyawaan bor (Supriana 1978) adalah:
1) Beracun terhadap jamur dan serangga perusak kayu, tetapi tidak berbahaya bagi manusia maupun ternak.
2) Dapat digunakan baik dengan proses tekanan maupun dengan proses difusi.
3) Tidak korosif terhadap logam, tidak berbau dan tidak merubah warna kayu sehingga dapat digunakan untuk mengawetkan alat rumah tangga yang terbuat dari kayu.
Senyawa tembaga yang digunakan sebagai bahan pengawet kayu larut air
pada umumnya dalam bentuk sulfat, biasanya pentahidrat (CuSO4.5H2O),
hidroksida (Cu(OH)2), oksida (CuO), dan dalam basa-basa karbonat terutama
Cu2(OH)2CO3. Cu(OH)2CO3 biasanya berbentuk bubuk yang berwarna hijau
dengan kandungan tembaga ± 55%. Ia diperoleh dengan menambahkan larutan
tembaga sulfat kepada larutan natrium karbonat. Tembaga sulfat adalah senyawa
tembaga yang paling penting dan merupakan sumber utama untuk kebanyakan
senyawa tembaga lainnya (Hatford 1973 Nicholas and Siau 1973).
Tembaga sulfat merupakan anti hama yang baik dan sangat baik untuk
melawan jamur. Kelemahan utama tembaga sulfat adalah adanya korosif yang
tinggi terhadap besi. Kelemahan lainnya adalah daya larutnya yang tinggi dalam
air sehingga mudah tercuci kembali. Tembaga sulfat sangat cocok untuk
mencegah serangan rayap apabila kayu yang diawetkan bebas dari pengaruh
pelunturan.
Senyawa khrom digunakan di dalam bahan pengawet kayu dalam bentuk
dikromat natrium (Na2Cr2O7.2H2O), potasium dichromat (K2Cr2O7), sodium
khromat (Na2CrO4) dan asam kromat (HCrO3). Dikhromat natrium berwarna
merah jingga, berbentuk garam kristal, sangat mudah larut dalam air, yaitu sekitar
69-70% (Hartford 1973 Nicholas and Siau 1973). Potasium dikhromat
lebih mahal daripada garam natrium tetapi karena sifat kurang higroskopik, maka
ia banyak digunakan sebagai campuran bahan pengawet.
Senyawa khrom digunakan secara luas sebagai campuran tambahan bahan
pengawet kayu larut air. Senyawa khrom tersebut dicampurkan dalam bentuk
dikhromat, khromat, asam khromat, atau trioksida khromium. Perkembangan
selanjutnya digunakan khrom asetat sebagai campuran . Selanjutnya
dikatakan bahwa garam khrom yang paling efektif adalah yang mengandung
trioksida khromium yang tinggi. Akan tetapi karena harganya mahal dan juga
daya larutnya rendah maka jarang digunakan.
Pada awalnya penggunaan garam khrom dimaksudkan untuk mencegah
atau mengurangi sifat karat (korosif) dari beberapa bahan pengawet kayu terhadap
sodium bikhromat) adalah untuk mengurangi sifat mudah luntur dari kebanyakan
bahan pengawet garam.
Semua bahan pengawet kayu yang mengandung khrom dapat
menyebabkan iritasi pada kulit atau selaput lendir. Dengan demikian hendaknya
dijaga jangan sampai larutan bahan pengawet tersebut masuk ke dalam luka yang
terbuka serta perlu dihindarkan terjadinya sentuhan pada binatang atau tanaman
(Padlinurjaji . 1977).
# )/26( 5)/26( +)&- 13 &-)(* , 5 /2,=,2)4 &-)0 2)&
Efektifitas pengawetan tidak hanya ditentukan oleh sifat-sifat yang
dimiliki oleh bahan pengawet, akan tetapi juga ditentukan oleh jumlah bahan
pengawet yang masuk kedalam kayu (retensi) serta kedalamannya (penetrasi).
Paling tidak besarnya retensi serta penetrasi bahan pengawet harus dapat
melindungi bagian-bagian sebelah dalam kayu yang tidak dimasuki oleh bahan
pengawet tersebut.
Tingkat retensi dan penetrasi yang bisa dicapai ditentukan oleh struktur
anatomi kayu, persiapan kayu sebelum diawetkan, metode pengawetan, serta jenis
dan konsentrasi larutan bahan pengawet (Hunt dan Garrat 1986; Tsoumis 1991).
%
Yang berpengaruh terhadap retensi dan penetrasi antara lain trakeida,
pori (pembuluh), serabut dan saluran damar. Kecuali serabut, ketiga
struktur yang disebut tadi berfungsi sebagai saluran, sehingga didalam
pengawetan aliran bahan pengawet ditentukan oleh jumlah, ukuran serta
kondisi ketiga struktur tadi.
Serabut sebenarnya berfungsi hanya sebagai peneguh batang
(pemberi tenaga mekanis) sehingga dengan sendirinya sel-sel ini
mempunyai dinding yang relatif lebih tebal sehingga sulit untuk ditembus
bahan pengawet. Akan tetapi untuk jenis tertentu seperti hickory, justru
masuknya bahan pengawet sebagian besar adalah melalui serabutnya.
% '
Untuk mencapai retensi dan penetrasi yang memuaskan, kayu-kayu
dimaksudkan antara lain pengulitan, pengeringan, and , dan
(pembuatan celah-celah kecil pada permukaan kayu).
% '
Metode pengawetan yang berbeda akan memberikan retensi dan
penetrasi yang berbeda. Perbedaan yang jelas terutama terdapat antara
metode tekanan dengan metode tanpa tekanan.
% $ / '
Masing-masing jenis bahan pengawet mempunyai daya penetrasi
yang berbeda-beda sehingga dengan sendirinya penetrasi yang dicapai
berbeda-beda pula. Dalam kondisi pengawetan yang sama, retensi dan
penetrasi yang lebih baik diperoleh dengan mempergunakan bahan
pengawet larut air daripada bahan pengawet minyak/larut minyak.
> &-*/*4)&
Perlakuan pengukusan kayu memiliki beberapa keuntungan, antara lain
mengeluarkan kandungan air dan resin dari dalam kayu serta meningkatkan
permeabilitas kayu (Ishikawa . 2004). Pengukusan ' pada suhu 120oC selama 25 jam dapat mengurangi kadar air kayu dari 38% menjadi 9,7%,
sedangkan pengukusan pada suhu 110oC selama 35 jam dapat mengurangi kadar
air kayu dari 40% menjadi 10% (Bovornsethanan dan Wongwises 2007).
Pengukusan kayu 0 # L. sebelum pengeringan mempengaruhi
sifat absorbsi kayu. Penurunan kadar air kesetimbangan yang signifikan terjadi
setelah pengukusan (Majka dan Olek 2007). Pengukusan kayu meningkatkan
permeabilitas arah radial karena rusaknya jaringan yang tidak berlignin,
contohnya pada pengukusan beberapa jenis pinus (Walker 1993). Menurut Coggin
(1981) dalam Eaton dan Hale (1993), pengukusan kayu sitka spruce (
) selama 6 jam meningkatkan penetrasi arah radial.
Suhu dan lama pengukusan bervariasi, tergantung dari jenis dan dimensi
kayu. Suhu pengukusan berkisar antara 100-125oC dan lama pengukusan berkisar
antara 1 hingga 20 jam. Pengukusan yang terlalu lama dengan suhu tinggi dapat
Menurut Hunt and Garrat (1986), pengukusan dan pemvakuman kayu
sebelum diawetkan pada suhu 245oF atau lebih rendah dan
selanjutnya divakum selama 1 jam atau lebih menyebabkan berkurangnya kadar
air kayu sehingga menyebabkan kayu lebih mudah diawetkan. Menurut standar
+ , # 1 + dalam Hunt and Garrat (1986), suhu
pengukusan tidak melebihi 240oF dan lama pengukusan tidak lebih dari 6 jam.
? ( .*4)&
Perebusan meningkatkan kadar air kayu. Pada perebusan yang lebih lama,
kadar air kayu akan terdistribusi lebih merata. Perebusan juga meningkatkan laju
penurunan kadar air saat kayu dikeringkan. Menurut Kurniati (1990), laju
penurunan kadar air kayu kamper yang telah direbus meningkat selama 6 hari
pertama sedangkan pada keruing hanya selama 4 hari pertama proses
pengeringan. Dijelaskan pula bahwa perebusan dan juga pengukusan tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap regangan absolut total dan nilai penyusutan
kayu namun mengakibatkan terjadinya perubahan warna kayu. Dibandingkan
pengukusan ternyata perebusan mengakibatkan perubahan warna yang lebih
mencolok.
% )+* ,&',
Pohon mindi atau geringging ( L.) anggota suku
, merupakan jenis pohon cepat tumbuh dan selalu hijau di daerah tropis.
Tinggi pohon dapat mencapai 40 m dengan tinggi bebas cabang 20 m dan
diameter sampai 185 cm (Martawijaya . 2005). Pohon mindi berbatang lurus,
silindris, tegak, tidak berbanir; tajuk ringan menyerupai payung; serta berakar
tunggang dalam dan berakar cabang banyak. Di kebun rakyat daerah Cimahpar,
Bogor pohon mindi pada umur 10 tahun mencapai ketinggian bebas cabang
sekitar 10 m dengan diameter 38,20 cm.
Kulit batang (papagan) berwarna abu-abu coklat, beralur membentuk
garis-garis dan bersisik. Pada pohon yang masih muda memiliki kulit licin dan
berlentisel. Daun majemuk ganda menyirip ganjil, anak daun berbentuk bundar
telur atau lonjong, pinggir helai daun bergirigi. Bunga majemuk malai, pada
(biseksual) atau bunga jantan dan bunga betina pada pohon yang sama. Buah bulat
atau lonjong, tidak membuka, ukuran 2-4 cm x 1-2 cm, kulit luarnya tipis dan
licin saat muda dan berkeriput bila tua, sedangkan kulit dalamnya keras. Buah
yang masih muda berwarna hijau, sedangkan yang masak berwarna kuning.
Dalam satu buah umumnya terdapat 4-5 biji, berukuran kecil (3,5 mm x 1,6 mm),
lonjong, dan licin. Biji kering berwarna hitam
(www.mail-archive.com/[email protected]/msg01923.html.).
Daerah penyebaran alaminya di India dan Burma, tetapi sudah banyak
ditanam di daerah tropis dan sub tropis. Di Indonesia banyak ditanam di
Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Irian Jaya (Martawijaya . 2005). Mindi
tumbuh pada dataran rendah hingga dataran tinggi (0-1200 m di atas permukaan
laut) dengan curah hujan rata-rata per tahun 600-2000 mm, dan dapat tumbuh
pada berbagai tipe tanah. Tumbuhnya subur pada tanah berdrainase baik, tanah
yang dalam, tanah liat berpasir, serta toleran terhadap tanah dangkal, tanah asin
dan basa.
Kayu teras berwarna merah coklat muda keunguan, gubal berwarna putih
kemerah-merahan dan mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras. Serat lurus
atau agak berpadu, berat jenis rata-rata 0,53 (Martawijaya . 2005).
Penyusutan dari keadaan basah sampai kering tanur 3,3% (radial) dan 4,1%
(tangensial). Kayu mindi tergolong kelas kuat III-II, setara dengan mahoni,
sungkai, meranti merah, dan kelas awet IV-V. Pengeringan alami, pada papan
tebal 2,5 cm dari kadar air 37% sampai 15% memerlukan waktu 47 hari, dengan
kecenderungan pecah ujung dan melengkung. Pengeringan dalam kilang yang
dianjurkan adalah pada suhu 60-80ºC dengan kelembaban nisbi 80-40%.
Kayu mindi sudah terbukti baik sebagai bahan baku mebel untuk ekspor
dan domestik karena kayunya bercorak indah, mudah dikerjakan dan dapat
mengering tanpa cacat (Martawijaya . 2005). Mebel kayu mindi dapat terdiri
dari kayu utuh atau merupakan kombinasi antara kayu utuh dan panel kayu yang
dilapisi venir mindi. Produk lantai kayu biasanya berupa parket atau mozaik.
Bahan baku untuk lantai berupa parket, kayu lapis indah (multipleks) dan berupa
produk perekatan terdiri dari 3 lapis kayu gergajian atau bagian bawah venir
gergajian mindi tebal 5 mm dipakai untuk bagian atas lantai parket 3 lapis dan
produknya di ekspor. Di sisi lain, kayu mindi yang berukuran kecil dapat
digunakan sebagai bahan untuk membuat barang kerajinan
$ ! )/2* ')& 13)2
Penelitian dilaksanakan mulai Juni hingga Agustus 2010 di Laboratorium
Sifat Dasar Kayu dan Laboratorium Kimia Hasil Hutan, Departemen Hasil Hutan
Fakultas Kehutanan IPB Darmaga Bogor.
$ ) )& ')& )2
Bahan utama yang digunakan adalah kayu mindi ( )
berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 280 cm dari bagian pangkal
batang yang diperoleh dari usaha penggergajian sekitar Jonggol. Umur tanaman
tidak diketahui dengan pasti.
Bahan pengawet yang dipakai adalah -CB dengan bahan aktif
garam 90%, cat Altex, bahan kimia seperti etanol, HCl, asam salisilat, asam
rubianat, aseton, amonia, , dan akuades.
Peralatan yang digunakan antara lain adalah timbangan analitik, kompor,
# , bak/wadah plastik, dandang, gelas piala, alat semprot, kuas, sarung tangan, , termometer, , koran bekas, kertas amplas dan alat tulis.
$ $ (64 '*( & ,2,)& ) 1.*)2)& @6&26 *7,
Tiga buah balok yang berukuran 6 cm x 12 cm x 280 cm dipotong terlebih
dahulu hingga mendapatkan beberapa sampel yang ukurannya 5 cm x 5 cm x 20
cm. Agar sampel yang digunakan seragam, maka dilakukan penyortiran contoh uji
meliputi keseragaman relatif dalam hal kadar air, bentuk dan berat, porsi bagian
gubal dan teras, serta kualitas kayu (tanpa cacat).
Setelah disortir, sampel kemudian diambil secara acak untuk
masing-masing perlakuan (perebusan, pengukusan, dan kontrol/tanpa perlakuan) dan
untuk perlakuan konsentrasi larutan bahan pengawet (3% dan 5%).
Masing-masing kombinasi perlakuan dilakukan sebanyak delapan kali ulangan. Dengan
demikian, maka jumlah total contoh uji yang digunakan ada sebanyak 3 x 2 x 8 =
. ( .*4)& ')& 3 &-*/*4)& @6&26 *7,
Sebelum diawetkan, contoh uji direbus dan dikukus secara terpisah. Untuk
perebusan: contoh uji disusun dalam dandang kemudian diisi air, lalu dipanaskan
sampai mendidih (100°C) dan dipertahankan selama 60 menit. Untuk pengukusan:
contoh uji dikukus dalam # pada suhu 212oF selama 30 menit. Setelah direbus dan dikukus, semua contoh uji kemudian dikering-udarakan hingga
mencapai kadar air kering udara (14-17)%. Selanjutnya penampang contoh uji
diserut hingga rata sehingga ukuran akhir contoh uji saat diawetkan menjadi 4 cm
x 4 cm x 20 cm. Kedua permukaan bagian ujung contoh uji kemudian dilapisi
dengan cat Altex secara merata untuk mencegah masuknya bahan pengawet dari
arah longitudinal, lalu dibiarkan mengering sempurna.
@ &-)0 2)&
! (4,)3)& )(*2)& .) )& 3 &-)0 2
Konsentrasi larutan bahan pengawet 3% dibuat dengan cara melarutkan 3
bagian bahan pengawet dalam 97 bagian air lalu diaduk rata, sedangkan
konsentrasi 5% dibuat dengan cara melarutkan 5 bagian bahan pengawet dalam 95
bagian air lalu diaduk rata.
( &')1)& @6&26 *7, ') )1 .) )& 3 &-)0 2
Perendaman contoh uji dalam larutan bahan pengawet dilakukan selama
48 jam dengan tinggi larutan bahan pengawet sekitar 10 cm di atas tinggi susunan
contoh uji yang paling atas. Sebelum direndam, contoh uji diukur kembali kadar
airnya dengan , ditimbang berat awalnya dan diukur volumenya.
Kemudian disusun rapi di dalam bak rendaman dengan jarak antar contoh uji
minimal 10 mm dan antar susunan diberi ganjal ( ) tipis dari kayu mindi.
Pada susunan yang paling atas setelah ganjal kemudian diberikan pemberat untuk
mencegah mengambangnya contoh uji saat larutan bahan pengawet dimasukkan
ke dalam bak rendaman. Setelah perendaman selesai, contoh uji diangkat dan
ditiriskan, lalu ditimbang untuk menghitung nilai absorpsi dan retensi yang
terjadi. Contoh uji selanjutnya dikeringudarakan untuk menentukan nilai
Gambar 1 Diagram alir penelitian. (4,)3)&
)13
1.*)2)& 6&26 7,
6&2(6 ( .*4)& &-*/*4)&
&-/6&',4,)& ,&--) 1 &@)3), /)')( ),( / (,&- *')()
&-*7,)& 2 &4, ')& & 2()4,
&-)0 2)&
(4,)3)& )(*2)& ()2))& ,4,
')& &- @)2)&
7*&-$ ( ,2*&-)& ( 2 &4,
Retensi bahan pengawet dihitung berdasarkan selisih berat sebelum dan
sesudah pengawetan dengan rumus:
R = (B1 –B0) / V x K
dimana:
R = Retensi bahan pengawet (kg/m3)
B1 = Berat kering contoh uji setelah di awetkan (kg) B0 = Berat kering contoh uji sebelum diawetkan (kg) V = Volume contoh uji (m3)
K = Konsentrasi larutan bahan pengawet (%)
" &-*/*()& 3 & 2()4,
Sebelum pengukuran penetrasi dilakukan, perlu disiapkan larutan-larutan
pereaksi untuk mengetahui adanya boron dan tembaga dalam kayu dengan cara
sebagai berikut:
.
Bahan pereaksi untuk boron adalah 2 gram ekstrak kurkuma dalam 100
ml alkohol (pereaksi A), serta 80 ml alkohol dan 20 ml HCl yang dijenuhkan
dalam asam salisilat (pereaksi B), sedangkan pereaksi untuk tembaga adalah
larutan 1 bagian amonia pekat dan 6 bagian air suling (pereaksi A), serta 5 g
asam rubianat dalam 900 ml alkohol ditambah 600 ml aseton (pereaksi B).
.
Contoh uji dipotong melintang pada bagian tengahnya dimana satu
penampang untuk uji penetrasi boron dan satu penampang untuk uji penetrasi
tembaga. Untuk masing-masing pengujian, dilakukan penyemprotan larutan
pereaksi A dan B secara berurutan setelah yang pertama mengering terlebih
dahulu. Permukaan penampang kayu yang dimasuki oleh senyawa boron akan
memperlihatkan warna merah oranye, sedangkan yang tidak akan berwarna
kuning. Untuk uji tembaga, bagian yang dimasuki oleh senyawa tembaga akan
berwarna gelap kebiruan, sedangkan yang tidak dimasuki oleh bahan pengawet
Penetrasi masing-masing senyawa aktif dihitung dengan rumus:
P = (P
1+ P
2+ P
3+ P
4) / 4
dimana:
P = Penetrasi rata-rata
P1 = Rata-rata penetrasi pada sisi atas
P2 = Rata-rata penetrasi pada sisi bawah
P3 = Rata-rata penetrasi pada sisi kiri
P4 = Rata-rata penetrasi pada sisi kanan
$ " &-6 ) )& )2)
Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan rancangan percobaan
faktorial acak lengkap dengan persamaan:
Yijk = µ + Ai + Bj + ε ijk
dimana:
Yijk = Hasil pengamatan pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan
pada taraf ke-i, konsentrasi bahan pengawet ke-j, dan ulangan ke-k µ = Nilai rataan umum
Ai = Pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan pada taraf ke-i
Bj = Pengaruh konsentrasi bahan pengawet pada taraf ke-j
k = Ulangan
Εijk = Galat percobaan
Analisis ragam untuk mengetahui pengaruh tiap faktor maupun interaksi
antar faktor terhadap retensi dan penetrasi dilakukan dengan menggunakan
program SPSS 15.0. Selanjutnya, untuk hasil analisis ragam yang menunjukkan
adanya pengaruh yang nyata dilakukan uji lanjut Duncan dengan selang
<
" ! & 2()4,
Pada semua kombinasi perlakuan yang dilaksanakan diketahui bahwa
hanya senyawa boron yang secara nyata masuk ke dalam kayu (Gambar 1). Unsur
tembaga hanya terdapat di bagian terluar permukaan kayu dengan penetrasi yang
sangat dangkal (Gambar 2). Kondisi ini terjadi karena tembaga sangat cepat
berfiksasi sehingga sulit masuk ke dalam kayu, sebaliknya boron yang tidak
mudah berfiksasi dapat menembus kayu dengan lebih dalam (Padlinurjaji .
1977).
Gambar 1. Penetrasi boron Gambar 2. Penetrasi tembaga
Hasil pengukuran penetrasi boron pada berbagai kombinasi perlakuan
disajikan pada Gambar 3, sedangkan rekapitulasinya disajikan pada Lampiran 1.
Tabel 2 memuat hasil analisis sidik ragamnya.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan perebusan yang
dilanjutkan dengan pengawetan menggunakan bahan pengawet berkonsentrasi 3%
memberikan nilai penetrasi boron yang paling dalam (4,14 mm), sedangkan
kontrol (tanpa perlakuan awal: tidak direbus/tidak dikukus) yang diawetkan
menggunakan bahan pengawet berkonsentrasi 5% memberikan nilai penetrasi
yang paling dangkal (2,69 mm). Diketahui pula bahwa perlakuan awal (sebelum
kayu diawetkan) secara umum cenderung meningkatkan nilai penetrasi, namun
peningkatan konsentrasi bahan pengawet dari 3% ke 5% cenderung
mengakibatkan berkurangnya nilai penetrasi boron. Keadaan yang pertama
membuktikan bahwa perebusan dan atau pengukusan meningkatkan permeabilitas
kayu, sedangkan hal yang kedua terkait dengan viskositas larutan bahan
pengawet. Hal ini sesuai dengan hasil analisis sidik ragamnya (Tabel 2).
Perebusan akan mengakibatkan rusaknya selaput noktah sehingga noktah
menjadi terbuka, sedangkan pengukusan mengakibatkan berkurangnya daerah
amorph (Ishikawa . 2004; Hill 2006). Dampak perebusan lebih tinggi
dibandingkan dengan pengukusan karena pada pengukusan tidak semua mulut
noktah akan terbuka. Mulut noktah yang masih tersumbat akan menghalangi
masuknya bahan pengawet. Itulah sebabnya, permeabilitas pada kayu mindi yang
direbus akan lebih tinggi dibandingkan dengan permeabilitas pada kayu yang
dikukus.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Syarif (2010) maupun
hasil penelitian Apriyanto (2010) yang menggunakan kayu durian sebagai contoh
uji dimana perebusan maupun pengukusan meningkatkan nilai penetrasi,
sedangkan peningkatan konsentrasi bahan pengawet cenderung menurunkan nilai
penetrasi.
Tabel 2. Analisis sidik ragam pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan, konsentrasi bahan pengawet, serta interaksi keduanya terhadap penetrasi boron
Dari Tabel 2 diketahui bahwa perlakuan awal sebelum kayu diawetkan dan
konsentrasi bahan pengawet berpengaruh nyata terhadap nilai penetrasi boron,
sedangkan interaksi keduanya tidak berpengaruh secara nyata. Selanjutnya
berdasarkan hasil uji Duncan diketahui bahwa perlakuan perebusan dan
pengukusan cenderung meningkatkan nilai penetrasi (Tabel 3): perebusan dan
pengukusan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penetrasi.
Tabel 3. Hasil uji Duncan pengaruh perlakuan awal terhadap penetrasi
( )/*)& ;*1 )
Menurut Hunt dan Garrat (1986), selain dipengaruhi oleh struktur anatomi
kayu, penetrasi juga dipengaruhi oleh persiapan kayu sebelum diawetkan, metode
pengawetan, konsentrasi bahan pengawet, dan lama perendaman. Dengan
demikian, maka lama perendaman dan konsentrasi bahan pengawet yang
digunakan dalam penelitian ini perlu disempurnakan. Lama perendaman perlu
ditingkatkan, tetapi konsentrasi larutan bahan pengawet tetap dipertahankan atau
lebih rendah dari 3%.
" 2 &4,
Rata-rata nilai retensi bahan pengawet pada berbagai perlakuan awal dan
tingkat konsentrasi bahan pengawet pada kayu mindi disajikan pada Gambar 4,
sedangkan rekapitulasi hasil pengukuran disajikan pada Lampiran 2. Tabel 4
memuat hasil analisis sidik ragamnya.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa retensi rata-rata akibat perlakuan
perebusan berturut-turut adalah 1,56 kg/m3 (konsentrasi 3%) dan 2,09 kg/m3
(konsentrasi 5%), sedangkan rata-rata retensi akibat pengukusan adalah 1,09
kg/m3 (konsentrasi 3%) dan 1,49 kg/m3 (konsentrasi 5%). Pada kayu kontrol
(konsentrasi 5%). Diketahui pula bahwa retensi tertinggi terjadi pada perlakuan
perebusan dan selanjutnya diawetkan dengan bahan pengawet berkonsentrasi 5%
(2,09 kg/m3), sedangkan retensi terendah pada kayu kontrol dan diawetkan dengan
bahan pengawet berkonsentrasi 3% (1,02 kg/m3). Secara umum dapat dikatakan
Gambar 4. Rata-rata nilai retensi bahan pengawet pada seluruh kombinasi perlakuan
Tabel 4. Analisis sidik ragam pengaruh perlakuan awal (sebelum kayu diawetkan) dan konsentrasi bahan pengawet, serta interaksi antara perlakuan awal dan konsentrasi terhadap retensi bahan pengawet
*1. ( ()7)2
Keterangan *) berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95%
Dari Tabel 4 diketahui bahwa interaksi antara perlakuan awal (sebelum
kayu diawetkan) dan konsentrasi larutan bahan pengawet tidak berpengaruh
terhadap nilai retensi, sedangkan pengaruh tunggal dari perlakuan awal atau pun
konsentrasi bahan pengawet berpengaruh nyata. Untuk mengetahui pengaruh
Tabel 5. Hasil uji Duncan tentang pengaruh perlakuan awal terhadap retensi bahan
Dari tabel di atas diketahui bahwa perlakuan perebusan dan pengukusan
cenderung meningkatkan nilai retensi. Peningkatan retensi pada kayu yang
dikukus relatif lebih rendah dibandingkan pada kayu yang direbus, bahkan tidak
berbeda jauh dengan retensi pada kayu kontrol. Hasil penelitian ini sama dengan
hasil penelitian Apriyanto (2010), tetapi berbeda dibandingkan dengan hasil
penelitian Syarif (2010). Menurut Syarif (2010), perlakuan perebusan pada kayu
durian sebelum diawetkan cenderung menurunkan nilai retensi. Hal yang terakhir
ini membuktikan adanya pengaruh perbedaan jenis kayu karena berbeda dalam hal
struktur anatomi dan komponen kimiawi dinding sel.
Tingginya nilai retensi bahan pengawet pada kayu yang direbus dibanding
kayu kontrol maupun kayu yang dikukus diduga terkait dengan perbedaan
reaktifitas dinding sel, dalam hal ini jumlah gugus hidroksil bebas yang ada.
Semakin banyak gugus hidroksil bebasnya, akan semakin banyak pula senyawa
aktif dari bahan pengawet yang mampu diikat. Sebagai akibatnya, akan semakin
besar pula nilai retensi yang diperoleh.
Perebusan akan mengakibatkan melemahnya ikatan hidrogen yang ada dan
rusaknya selaput noktah sehingga noktah menjadi terbuka, sedangkan pengukusan
mengakibatkan berkurangnya daerah amorph (Ishikawa . 2004; Hill 2006).
Dampak perebusan lebih tinggi dibandingkan dengan pengukusan karena pada
pengukusan tidak semua ikatan hidrogen akan terpengaruh dan tidak semua mulut
noktah akan terbuka. Ikatan hidrogen yang lemah tersebut mudah lepas saat kayu
mencapai kondisi kering udara, sedangkan mulut noktah yang masih tersumbat
akan menghalangi masuknya bahan pengawet. Itulah sebabnya, reaktifitas dinding
sel pada kayu yang direbus akan lebih tinggi dibandingkan dengan reaktifitas pada
Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa rata-rata nilai retensi yang
diperoleh masih belum memenuhi nilai standar, baik untuk penggunaan di dalam
maupun di luar ruangan. Secara umum rata-rata nilai retensi yang diperoleh lebih
rendah dari nilai standar (1,02 hingga 2,09 kg/m3 berbanding 8 kg/m3 (di bawah
atap) dan 11,0 kg/m3 (di luar atap) sebagaimana SNI 03-5010.1-1999).
Dari penelitian ini diketahui bahwa secara umum perlakuan perebusan
akan menghasilkan rata-rata penetrasi maupun retensi yang paling baik pada
<
4,13* )&
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Perlakuan awal khususnya perebusan dan pengukusan sebelum kayu mindi
diawetkan dengan bahan pengawet Diffusol-CB dapat meningkatkan nilai
penetrasi dan retensi bahan pengawet.
2. Peningkatan konsentrasi bahan pengawet Diffusol-CB dari 3% ke 5% dapat
meningkatkan nilai retensi, tetapi cenderung menurunkan nilai penetrasi.
3. Dalam penelitian ini, perebusan memberikan nilai penetrasi dan retensi yang
lebih baik dibandingkan dengan pengukusan. Perebusan yang diikuti dengan
proses pengawetan menggunakan bahan pengawet berkonsentrasi 3% akan
menghasilkan nilai penetrasi bahan pengawet Diffusol-CB khususnya senyawa
boron yang terdalam (4,14 mm), sedangkan perebusan yang diikuti dengan
proses pengawetan menggunakan bahan pengawet berkonsentrasi 5% akan
menghasilkan nilai retensi yang tertinggi (2,09 kg/m3).
4. Rata-rata nilai penetrasi dan retensi yang diperoleh dari penelitian ini tidak
memenuhi nilai standar sebagaimana SNI 03-5010.1-1999.
)()&
Untuk memperoleh kayu mindi awetan dengan nilai penetrasi dan retensi
yang memenuhi persyaratan SNI 03-5010.1-1999, maka kombinasi ideal antara
perlakuan perebusan dan konsentrasi bahan pengawet perlu disempurnakan. Lama
perendaman kayu mindi dalam larutan bahan pengawet perlu ditingkatkan,
sedangkan lama perebusan sebelum kayu diawetkan dan konsentrasi bahan
Apriyanto B. 2010. Pengaruh Pengukusan Terhadap Retensi dan Penetrasi
Diffusol CB pada Kayu Durian ( Murr.). Skripsi
Departemen Teknologi Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.
Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Pertanian. 2009. 2 ! 3 44*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
Bovornsethanan S. and S. Wongwises. 2007. ' '
. Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT). Bangkok, Thailand.
Eaton and Hale 1993. , 5 6 . Chapman & Hale.
London.
Hill C. 2006. Wood Modification: Chemical, Thermal and Other Processes. Wiley. England.
Hunt G. M. dan G. A. Garrat. 1986. Pengawetan Kayu. Edisi 1 cetakan 1: Penerjemah Mohamad Yusuf. Jakarta: Akademika Pressindo.
Ishikawa A., N. Kuroda and A. Kato. 2004. 3 '
. The Japan Wood Research Society.
Jayanetti D. L. 1978. A guide to the boron diffusion treatment. Forestry for Industrial Development Wood Preservation for the Rural Sector. Eighth World Forestry Congress. Jakarta.
Kartasujana I. dan A. Martawijaya. 1995. Kayu Perdagangan Indonesia. Lembaga Penelitian Hasil Hutan Bogor.
Kurniati L. 1990. Pengaruh Perebusan dan Pengukusan terhadap Pengeringan
Kayu Kamper ( ) dan Keruing ( ).
Skripsi Departemen Teknologi Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.
Majka J. and W. Olek. 2007. 7 ) 7 8 -0 # 9 .
, ) " 3 .
Department of Mechanical Engineering and Thermal Techniques August Cieszkowski Agricultural University of Poznan.
Martawijaya A., I. Kartasujana., Y.I Mandang., S.A Prawira., dan K. Kadir. 2005. Atlas Kayu Jilid II (Edisi Kedua). Departemen Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Bogor. Indonesia
Nicholas D.D. and J. F. Siau. 1973. Factor influencing the treatability of wood. D. D. Nicholas (7 .. Wood Deterioration and Its Prevention by Preservative Treatments. Syracuse University Press, New York.
_______________. 1985. Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Kelunturan Bahan Pengawet Wolmanit CB dan Basilit CFK dari Kayu Pinus. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
_______________., T.L. Tobing., A. Ruzani., A. Sukarta., dan A. Widjaja. 1977. Rendaman Dingin Larutan Wolmanit CB Terhadap Lima Jenis Kayu pada Berbagai Tingkat Konsentrasi dan Waktu Rendam. Proyek Penelitian Pengembangan Efisiensi Penggunaan Sumber-sumber Kehutanan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
SNI 03-5010.1-1999. Pengawetan untuk Rumah dan Gedung.
http://www.dephut.go.id/IFORMASI/SNI/pkupg.HTM. [Diunduh 18 September 2009].
Supriana N. 1978. Keterawetan Empat Puluh Jenis Kayu Indonesia. Lembaran Penelitian.
Syarif F. 2010. Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perebusan Terhadap Penetrasi dan Retensi Bahan Pengawet Diffusol-CB pada Kayu Durian. Skripsi Departemen Teknologi Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.
Tarumingkeng R.C. 2000. Manajemen Deteriorasi Hasil Hutan. UKRIDA press. Bogor.
Tobing T.L. 1977. Pengawetan Kayu Lembaga Kerjasama Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Tsoumis G. 1991. Science and Technology of Wood: Structure, properties, utilization. Van Nostrand Reinhold. New York.
Wahyudi I., F. Febrianto, L. Karlinasari, J. Suryana, D.S. Nawawi dan Nurhayati.
2007. Kajian Potensi Unit Pengawetan Kayu 0 :
; Fakultas Kehutanan IPB dalam rangka Mendukung Pengembangan
: 3 di IPB. Departemen Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. Laporan Akhir.
Walker J.C.F. 1993. , . Chapman & Hall. London.
Lampiran 1. Rata-rata penetrasi (mm) pada masing-masing perlakuan dan tingkat konsentrasi bahan pengawet.
A. Direbus lalu diawetkan dengan konsentrasi 3%
6' & 2()4, 11 / )2) ()2)
Keterangan: Nilai pencilan ( ) tidak diikutkan dalam perhitungan
B. Direbus lalu diawetkan dengan konsentrasi 5%
6' & 2()4, 11 / )2) ()2)
Keterangan: Nilai pencilan ( ) tidak diikutkan dalam perhitungan
C. Dikukus lalu diawetkan dengan konsentrasi 3%
D. Dikukus lalu diawetkan dengan konsentrasi 5%
E. Kayu kontrol yang kemudian diawetkan dengan konsentrasi 3%
6' & 2()4, 11 / )2) ()2)
Keterangan: Nilai pencilan ( ) tidak diikutkan dalam perhitungan
F. Kayu kontrol yang kemudian diawetkan dengan konsentrasi 5%
Lampiran 2. Data retensi (kg/m3) masing-masing perlakuan dan tingkat konsentrasi bahan pengawet
A. Direbus lalu diawetkan dengan konsentrasi 3%
)&-)& 6' 6&4 &
B. Direbus lalu diawetkan dengan konsentrasi 5%
)&-)& 6' 6&4 &
C. Dikukus lalu diawetkan dengan konsentrasi 3%
D. Dikukus lalu diawetkan dengan konsentrasi 5%
E. Kayu kontrol yang kemudian diawetkan dengan konsentrasi 3%
)&-)& 6' 6&4 &
F. Kayu kontrol yang kemudian diawetkan dengan konsentrasi 5%