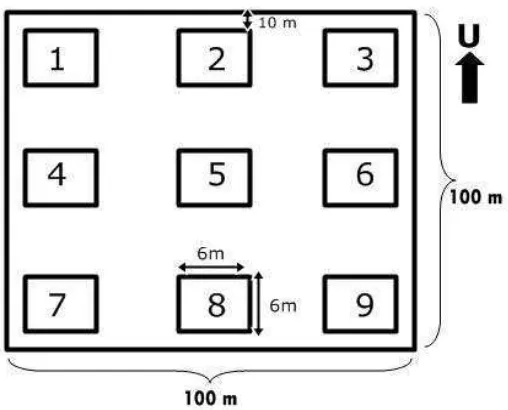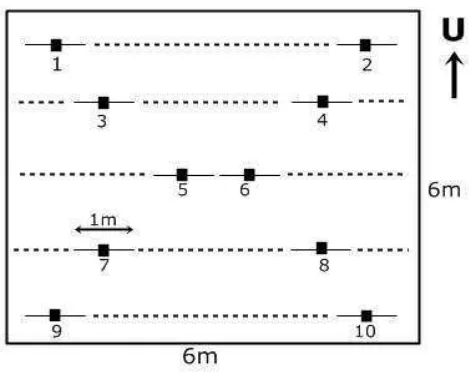ABSTRAK
POLA SEBARAN DAN INTENSITAS SERANGAN HAMA KUTU PERISAI (AULACASPIS TEGALENSIS ZEHNTN) PADA BEBERAPA VARIETAS TEBU DI PT GUNUNG MADU PLANTATIONS LAMPUNG
TENGAH
Oleh
Java Samando
Kutu perisai (Aulacaspis tegalensis Zehntn) adalah salah satu hama tanaman tebu
di PT GMP Lampung Tengah yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil
tanaman tebu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pola sebaran hama
A. tegalensis dan menduga intensitas serangannya pada varietas tebu yang diduga
mempunyai tingkat ketahanan berbeda, yaitu: tahan (GMP-3), sedang (GP-11),
dan rentan (RGM00-869). Penelitian dilaksanakan di lahan pertanaman tebu PT
GMP Lampung Tengah dengan metode survei. Pengamatan terhadap
masing-masing varietas terdiri dari 9 ulangan dan dari setiap ulangan diamati 10 tanaman
sampel. Untuk menentukan pola sebaran hama, data pengamatan dianalisis
dengan uji Poisson dan binomial negatif, sedangkan data intensitas serangan
dianalisis ragam dan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf nyata 5%. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebaran A. tegalensis antar tanaman pada varietas
GMP-3 dan GP-11 adalah mengelompok, sedangkan pada varietas RGM00-869
tanaman dari ketiga varietas tersebut adalah mengelompok. Hasil pendugaan
intensitas serangan terdapat beda nyata antara varietas GMP-3 dengan GP-11 dan
RGM00-869. Dari 90 tanaman sampel pada tiap varietas yang diamati, didapati
tanaman terserangA. tegalensis pada varietas GMP-3 sebesar 50%, GP-11
73,33%, dan RGM00-869 77,78%.
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Gunung Madu Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 10 Februari 1991, yang
merupakan putra pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Herman
Hadiwijaya dan Ibu Teguh Tur Maryani.
Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Gunung Madu,
Lampung Tengah pada tahun 2003; Sekolah Menengah Pertama di SMP Satya
Dharma Sudjana Gunung Madu pada tahun 2006; dan Sekolah Menengah Atas di
SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis
terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian,
Universitas Lampung.
Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi
kemahasiswaan Lembaga Studi Mahasiswa Pertanian (LS-MATA) periode 2011/
2012 dan menjabat sebagai Ketua Komisi di Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Pertanian periode 2011/2012. Penulis pernah menjadi Asisten Dosen
pada mata kuliah Mikrobiologi Pertanian, Ilmu Hama Tumbuhan Umum, dan
Bioekologi Hama Tumbuhan. Pada tahun 2012 penulis melaksanakan Praktik
Umum di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (BALLITRO) Bogor, dan
tahun 2013 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kemu, Kecamatan Banjit,
Lembar Persembahan
Syukur Alhamdulillah kuucapkan padaMu Ya Allah, atas segala
nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada hambaMu ini.
Sebuah karya kecilku ini kupersembahkan untuk
kedua orang tuaku Herman Hadiwijaya dan Teguh Tur Maryani,
yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih
sayang dan kesabaran. Semua pengorbanan yang diberikan
takkan cukup jika diungkapkan dengan kata-kata dan takkan
terbalaskan olehku sampai kapanpun.
Adikku Zariya Alfath yang menjadi adik sekaligus sahabat di
dalam keluarga, memotivasi untuk lebih baik lagi.
untuk
“
Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dan
hanya kepada Tuhanmu, hendaklah engkau berharap
”(QS. Al Insyiraah : 5 dan 8)
“
Apabila kamu tidak dapat memberikan kebaikan kepada orang lain
dengan kekayaanmu, berilah mereka kebaikan dengan wajahmu yang
berseri-seri, disertai akhlak baik
”(Nabi Muhammad SAW)
“
Hiduplah untuk melahirkan apa-apa yang terbaik yang ada di
dalam diri kita. Tuhan tidaklah menciptakan kita hanya untuk sekedar
memenuhi dunia ini
”“
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang
tersenyum bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan
pada kematianmu semua orang menangis sedih dan hanya kamu
sendiri yang tersenyum
”SANWACANA
Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga
skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada
junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.
Penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik
moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :
1. Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc., selaku pembimbing utama atas
bimbingan, saran, motivasi, dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ir. Solikhin, M.P., selaku pembimbing kedua atas bimbingan, saran, motivasi,
dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama penelitian dan penyusunan
skripsi.
3. Dr. Ir. I Gede Swibawa, M.S., selaku pembahas atas bimbingan, saran dalam
penyusunan skripsi.
4. Ir. Indriyati, selaku pembimbing akademik atas kesabaran, saran, motivasi,
dalam membimbing penulis mencapai gelar sarjana.
5. Syaefudin, S.P., selaku pembimbing lapang atas saran, bimbingan selama
penulis melakukan penelitian di PT GMP.
6. Pak Broto, Mas Ali, dan Mas Muni, atas saran dan bantuan tenaga selama
7. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung.
8. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Ketua Jurusan Agroteknologi.
9. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S., selaku Ketua Bidang Proteksi Tanaman.
10. Para Dosen Agroteknologi, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
11. Terima kasih yang sebesarnya untuk Ayahanda, Ibunda, dan Adikku tercinta,
atas segala pengorbanan, cinta kasih, dan doa tulus yang tak pernah putus
dipanjatkan.
12. Syarif Hidayat, S.P., rekan penelitian atas candatawa, ide-ide, kerjasama, dan
semangat mencapai sarjana. Semoga kita semua sukses dan persahabatan
dapat terus terjalin.
13. Sahabatku Adam, Andri, Doni, Deni, Deri, Gagat, Ganda, Hardy, Heri, Jamal,
Komang, Okto, Riki, Suhendri, Bang Leo, Bang Parman, Bang Alex, Catur,
Cindy, atas bantuan, kebersamaan dan candatawa. Semoga kita semua sukses
dan persahabatan dapat terus terjalin.
14. Irene Zaqyah, atas kebersamaan, kasih sayang, pengertian, kesabaran, dan
dukungan moral yang diberikan kepada penulis.
15. Beberapa teman AGT angkatan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, atas bantuan
dan kebersamaannya.
Bandar Lampung, November 2014
Penulis,
DAFTAR ISI ... Error! Bookmark not defined. 1.2 Tujuan Penelitian ... ... Error! Bookmark not defined. 1.3 Kerangka Pemikiran ... ... Error! Bookmark not defined. 1.4 Hipotesis ...
... Error! Bookmark not defined. II. TINJAUAN PUSTAKA ... 8
2.1 Tanaman Tebu ... ... Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Informasi Geografis dan Syarat Tumbuh Tanaman Tebu ... ... Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Botani Tanaman Tebu ... ... Error! Bookmark not defined. 2.2 Kutu Perisai (Aulacaspis tegalensis Zehnt.) ... ... Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Asal-Usul dan Klasifikasi A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Siklus Hidup A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan
dan Perkembangan A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 2.3 Pola Sebaran Hama ...
... Error! Bookmark not defined. III. BAHANDAN METODE ... 18
3.2 Bahan dan Alat ... ... Error! Bookmark not defined. 3.3 Metode Penelitian ... ... Error! Bookmark not defined. 3.4 Pelaksanaan Penelitian ... ... Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Pendugaan Pola Sebaran A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 3.4.2 Pendugaan Intensitas Serangan ... ... Error! Bookmark not defined. 3.5 Analisis Data ... ... Error! Bookmark not defined.
3.5.1 Pendugaan Pola Sebaran A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 3.5.2 Pendugaan Intensitas Serangan ...
... Error! Bookmark not defined.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 23 4.1 Hasil Pengamatan ... ... Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Pola Sebaran ... ... Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Intensitas Serangan ... ... Error! Bookmark not defined. 4.2 Pembahasan ...
... Error! Bookmark not defined. V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 31
5.1 Kesimpulan ... ... Error! Bookmark not defined. 5.2 Saran ...
... Error! Bookmark not defined. PUSTAKA ACUAN ... ... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Pendugaan pola sebaran A. tegalensis antar tanaman yang dianalisis
dengan uji Poisson dan binomial negatif. ... ... Error! Bookmark not defined. 2. Pendugaan pola sebaran A. tegalensis antar ruas pada tanaman
yang dianalisis dengan uji Poisson dan binomial negatif. ... ... Error! Bookmark not defined. 3. Intensitas serangan A. tegalensis pada tebu varietas RGM00-869,
GP11, dan GMP3. ... ... Error! Bookmark not defined. 4. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar tanaman pada varietas
RGM 00-869 (transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 5. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar tanaman pada varietas GP 11
(transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 6. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar tanaman pada varietas GMP 3
(transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 7. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar ruas pada tanaman pada
varietas RGM 00-869 (transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 8. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar ruas pada tanaman pada
varietas GP 11 (transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 9. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar ruas pada tanaman pada
10. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran
A. tegalensisantar tanaman pada varietas RGM 00-869. ... ... Error! Bookmark not defined. 11. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran
A. tegalensisantar tanaman pada varietas GP 11. ... ... Error! Bookmark not defined. 12. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran
A. tegalensisantar tanaman pada varietas GMP 3. ... ... Error! Bookmark not defined. 13. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran
A. tegalensisantar ruas pada tanaman pada varietas RGM 00-869. .... ... Error! Bookmark not defined. 14. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran
A. tegalensisantar ruas pada tanaman pada varietas GP 11. ... ... Error! Bookmark not defined. 15. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran
A. tegalensisantar ruas pada tanaman pada varietas GMP 3. ... ... Error! Bookmark not defined. 16. Data intensitas serangan A. tegalensis pada varietas RGM 00-869. ... ... Error! Bookmark not defined. 17. Data intensitas serangan A. tegalensis pada varietas GP 11. ... ... Error! Bookmark not defined. 18. Data intensitas serangan A. tegalensis pada varietas GMP 3. ... ... Error! Bookmark not defined. 19. ANOVA intensitas serangan A. tegalensis pada varietas
RGM 00-869,GP 11, GMP 3. ... ... Error! Bookmark not defined. 20. BNT intensitas serangan A. tegalensis pada varietas RGM 00-869,
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Telur kutu perisai. ...
... Error! Bookmark not defined. 2. Perisai A. tegalensis. ...
... Error! Bookmark not defined. 3. Petak percobaan dalam penelitian. ...
... Error! Bookmark not defined. 4. Pola penentuan unit sampel pada plot percobaan. ...
... Error! Bookmark not defined. 5. Populasi A. tegalensis antar tanaman dari sampel tebu varietas GMP 3
umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 6. Populasi A. tegalensis antar tanaman dari sampel tebu varietas GP 11
umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 7. Populasi A. tegalensis antar tanaman dari sampel tebu varietas
RGM 00-869umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 8. Jumlah populasi A. tegalensis antar ruas tanaman pada varietas GMP3
umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 10. Jumlah populasi A. tegalensis antar ruas tanaman pada varietas GP11
umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 11. Persentase intensitas serangan A. tegalensis. ...
... Error! Bookmark not defined. 12. Ruas batang terserang A. tegalensis. ...
... Error! Bookmark not defined. 13. Tanaman tebu dalam plot (ulangan). ...
... Error! Bookmark not defined. 14. Tanaman tebu dalam titik sampel. ...
... Error! Bookmark not defined. 15. Pengamatan tanaman yang terserang A. tegalensis....
... Error! Bookmark not defined. 16. Penghitungan populasi A. tegalensis tiap ruas. ...
1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Masalah
Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) adalah satu anggota famili
rumput-rumputan (Poaceae) yang merupakan tanaman asli tropika basah, namun masih
dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropika (Direktorat Jenderal
Perkebunan, 2009). Tebu mengandung serat-serat atau sabut dengan persentase
12,5% dari bobot tebu dan cairan manis yang disebut nira dengan persentase
87,5%. Di dalam nira terdiri dari air (75-80%) dan bahan kering (20-25%).
Bahan kering tersebut ada yang larut dan tidak larut dalam nira. Gula yang
merupakan produk akhir dari pengolahan tebu terdapat dalam bahan kering yang
larut dalam nira dengan kadar hingga 20% (Indriani dan Sumarsih, 1992).
Selain menghasilkan gula, tebu juga menghasilkan limbah atau hasil sampingan
berupa ampas, tetes, dan blotong. Ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai pakan
ternak, bahan baku pembuatan pupuk, dan untuk bahan bakar di pabrik gula.
Tetes tebu yang merupakan sisa dari proses pengkristalan gula pasir dapat
dimanfaatkan untuk pembuatan etanol dan bahan pembuatan monosodium
glutamate (MSG). Sedangkan blotong yang merupakan hasil samping dari proses
2
Produksi gula tebu nasional dari tahun 2010 sampai tahun 2013 berturut-turut
sebesar 2,3 juta ton, 2,2 juta ton, 2,4 juta ton, dan 2,5 juta ton. Hasil produksi ini
belum mampu mencukupi kebutuhan gula dalam negeri yang mencapai 5,7 juta
ton, yang terdiri dari 2,96 juta ton untuk konsumsi langsung masyarakat dan 2,74
juta ton untuk keperluan industri (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013a). Untuk
memenuhi kebutuhan gula tersebut, sejak tahun 2002 Pemerintah RI
melaksanakan Program Swasembada Gula Nasional antara lain melalui upaya
rehabilitasi tanaman tebu dengan bongkar ratoon dan rawat ratoon secara intensif,
penyediaan benih unggul bermutu melalui kultur jaringan, peningkatan kapabilitas
petani melalui pemberdayaan petani, serta langkah-langkah ekstensifikasi dengan
perluasan areal dan pembangunan pabrik gula baru (Direktorat Jenderal
Perkebunan, 2013b).
Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu penentu keberhasilan
usaha produksi gula karena hama dan penyakit dapat menurunkan produksi
tanaman sehingga menimbulkan kerugian. Serangan hama dan penyakit pada
pertanaman tebu dapat menurunkan produksi dan rendemen tebu 10-50% dalam
kondisi serangan sedang sampai berat (P3GI, 2008). Di daerah Jawa Barat dan
Jawa Timur, kerugian hasil akibat serangan penggerek pucuk tebu diperkirakan
mencapai Rp. 163.531.890,00 dari total luas areal terserang 111.982 ha. Kerugian
yang disebabkan oleh hama tebu di Indonesia ditaksir dapat mencapai 75%.
Lebih dari 100 jenis hama menyerang tanaman tebu dan sebagian besar hama
tersebut berasal dari jenis serangga (Pusat Penelitian dan Pengembangan
3
Salah satu hama yang menyerang pertanaman tebu di PT GMP Lampung Tengah
adalah kutu perisai Aulacaspis tegalensis Zehntn yang tergolong di dalam Famili
Diaspididae, Ordo Hemiptera. Serangan hama ini secara konsisten meningkat dan
semakin meluas hingga menyerang semua varietas tebu yang ditanam pada lahan
produksi PT GMP (R&D PT GMP, 2001). Serangan kutu perisai pada
pertanaman tebu dapat menurunkan produksi tanaman tebu secara kualitas (pol,
brix, rendemen) dan kuantitas (bobot batang). Pada kriteria serangan berat, kutu
perisai A. tegalensis dapat menyebabkan penurunan pol sebesar 15%, brix 10%,
dan rendemen 8%. Pol menunjukkan kandungan sukrosa pada cairan gula yang
ditentukan dengan metode polarisasi; brix merupakan jumlah total padatan terlarut
pada larutan gula dengan menggunakan alat refraktometer yang dilengkapi dengan
timbangan; dan rendemen adalah kandungan gula tanaman tebu (Sunaryo dan
Hasibuan, 2003).
Beberapa teknik pengendalian dilakukan untuk mengatasi hama kutu perisai, salah
satunya dengan penggunaan insektisida kimiawi sintetis yang diaplikasikan
dengan penyemprotan (MIPC dan dichlorvos) dan penaburan (fipronil dan
karbofuran). Akan tetapi penggunaan pestisida secara intensif dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang salah satunya adalah
terbunuhnya organisme nir-sasaran (musuh alami) (Hasibuan, 2004).
Untuk mengurangi pengaruh negatif dari penggunaan pestisida sintetik,
seyogyanya pengendalian hama tanaman tebu dilaksanakan berdasarkan
penetapan status hama dan pengambilan keputusan pengendalian hama yang
4
sistem pemantuan hama tanaman adalah sampling (penerokan) populasi hama.
Sampling merupakan proses pengambilan dan pengamatan sebagian populasi
(berupa sampel) untuk menduga keadaan keseluruhan individu pada populasi.
Sampel yang diamati harus dapat mewakili populasi, sehingga taksirannya tepat
untuk menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Untung, 2006).
Pada tahap awal, salah satu informasi yang penting diketahui dalam metode
sampling populasi hama adalah pola sebaran hama yang diduga populasinya. Pola
sebaran hama adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil sampling, karena
kesalahan dalam menentukan sifat sebaran hama akan mengakibatkan kesalahan
dalam pendugaan populasi sebenarnya. Pola persebaran hama dapat ditelaah
secara horisontal maupun vertikal. Menurut Tarumingkeng (1994), pola sebaran
spasial horisontal ditentukan berdasarkan jumlah individu atau contoh yang
ditemukan pada suatu waktu dan luasan tertentu, sedangkan pola sebaran spasial
vertikal ditentukan berdasarkan letak posisi ketinggian satwa dari permukaan
tanah.
Pola sebaran populasi hama kutu perisai perlu diteliti agar metode pengambilan
sampel dan metode pengendalian yang dilakukan bisa lebih terarah, efektif dan
efisien. Disamping itu, hal lain yang perlu dilakukan sebelum melakukan
tindakan pengendalian hama adalah menaksir terlebih dahulu kondisi serangan
hama di lapang agar dapat ditentukan teknik dan saat pengendalian yang tepat,
serta kebutuhan sarana pengendalian yang diperlukan. Menurut Sudarsono dan
5
dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat serangan hama pada saat
pengendalian dilaksanakan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian untuk
mempelajari pola sebaran hama kutu perisai A. tegalensis dan untuk menduga
tingkat serangannya pada beberapa varietas tebu.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Mempelajari pola sebaran kutu perisai A. tegalensis pada varietas tebu yang
diduga tahan, sedang, dan rentan terhadap serangan hama A. tegalensis.
2. Menduga intensitas serangan kutu perisai A. tegalensis pada varietas tebu yang
memiliki tingkat ketahanan berbeda terhadap serangan hama A. tegalensis
(tahan, sedang, dan rentan).
1.3 Kerangka Pemikiran
Kutu perisai menyerang tanaman tebu dengan cara mengisap cairan batang yang
telah beruas. Tanaman tebu yang terserang berat kutu perisai menunjukkan gejala
pertumbuhan batang terhambat, diameter batang lebih kecil, daun berdiri,
daun-daun bagian bawah mengering, ruas tebu kotor dan warna bercak pucat pada ruas
yang terserang (Bidang Tanaman PTPN VII, 1997 dalam Ferliyansyah, 2006).
Pada serangan awal, kutu perisai tidak menimbulkan gejala apapun dan tanaman
masih tampak sehat, karena pada kondisi itu populasi kutu perisai yang ada pada
tanaman masih rendah dan kemungkinan kutu perisai masih dalam fase nimfa
6
setelah itu menusukkan styletnya secara dangkal pada substrat tanaman, sehingga
kemampuan merusaknya masih rendah (Williams, 1970).
Penanaman varietas tahan termasuk dalam pengendalian secara teknik budidaya
dan merupakan salah satu cara pengendalian hama yang cukup baik, karena
biayanya murah dan tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Suatu
varietas dikatakan resisten (tahan) hama apabila varietas tersebut pada suatu saat
sama-sama mendapat serangan hama dengan populasi hama yang sama, ternyata
kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan varietas lainnya. Semakin tahan
suatu varietas tanaman terhadap serangan hama, maka semakin kecil intensitas
hama itu menyerang. Sehingga asumsinya, bahwa jumlah individu hama pada
varietas tanaman yang tahan akan lebih rendah dibandingkan pada varietas yang
rentan. Jumlah individu hama yang menyerang tanaman tersebut yang akan
digunakan dalam pendugaan pola sebaran hama.
Hasil penelitian Williams (1970) menunjukkan bahwa karakter tanaman
mempengaruhi pola dan intensitas serangan A. tegalensis. Hubungan antara
A. tegalensis dengan tanaman inangnya sangat erat dan karakter inang seperti
perbedaan sifat morfologi antar inang menentukan sebaran dan kemelimpahannya
secara horisontal. Pelepah daun yang membungkus batang mempunyai peranan
penting pada perkembangan serangan kutu di batang. Pelepah daun luasnya
bervariasi menurut umur daun dan varietas tebu. Nimfa cenderung tinggal
berdekatan dengan koloninya, sehingga pertumbuhan koloni lebih tampak
7
Pertumbuhan tanaman inang seperti perpanjangan batang yang cepat memiliki
pengaruh terhadap kutu, ruas batang yang panjang dan berpelepah renggang
diduga mempunyai pengaruh positif untuk pertumbuhan koloni A. tegalensis.
Di antara jenis-jenis tebu yang dibudidayakan di PT GMP, terdapat beberapa
varietas yang mempunyai tingkat ketahanan berbeda-beda terhadap A. tegalensis.
Menurut Saefudin (komunikasi pribadi, 2013), varietas tebu di PT GMP yang
diketahui tahan, sedang, dan rentan terhadap serangan A. tegalensis berturut-turut
adalah GMP 3, GP 11, dan RGM 00-869. Varietas GMP 3 memiliki pelepah yang
melekat rapat dan lebih sulit diklentek dibandingkan dengan varietas GP 11 dan
RGM 00-869, sehingga populasi A. tegalensis pada varietas GMP 3 akan lebih
rendah daripada varietas yang lain, karena A. tegalensis lebih menyukai tanaman
tebu dengan pelepah yang melekat renggang.
1.4 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan pada penelitian
ini adalah :
1. Keragaman varietas tebu mempengaruhi pola sebaran hama A. tegalensis.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tanaman Tebu
2.1.1 Informasi Geografis dan Syarat Tumbuh Tanaman Tebu
Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) telah dikenal sejak beberapa abad yang
lalu oleh bangsa Persia, Cina, India, kemudian menyusul bangsa Eropa. Pada
sekitar tahun 400-an tanaman tebu telah ditemukan tumbuh di Pulau Jawa dan
Sumatera, dan dibudidayakan secara komersial oleh imigran Cina (Direktorat
Jenderal Perkebunan, 2009). Tebu termasuk dalam tumbuhan yang dapat ditanam
di daerah tropis dan subtropis, lebih kurang pada daerah antara 390LU dan 390LS.
Di daerah tropis, tanaman tebu dibudidayakan di negara-negara seperti Thailand,
Filipina, Malaysia, India, dan Indonesia. Sedangkan di daerah subtropis budidaya
tebu banyak dijumpai di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Australia, dan Hawai
(Tim Penulis PTPN XI, 2010). Di Indonesia, sentra perkebunan tebu terutama di
daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI-Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera
Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo (Direktorat Jenderal
Perkebunan, 2009).
Tebu dapat tumbuh dari dataran rendah hingga dataran tinggi pada ketinggian
1400 m diatas permukaan laut (dpl), tetapi pada ketinggian mulai +1200 m (dpl)
9
adalah 1.500-2.500 mm per tahun dengan hujan tersebar merata. Produksi yang
maksimum dicapai pada kondisi yang memiliki perbedaan curah hujan yang
ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau. Suhu yang baik untuk tanaman
tebu berkisar antara 240C hingga 300C, dengan kelembaban nisbi yang
dikehendaki adalah 65-70%, dan pH tanah 5,5-7,0. Kecepatan angin yang
optimum untuk pertumbuhan tebu kurang dari 10 km/jam, karena angin dengan
kecepatan lebih dari 10 km/jam akan merobohkan tanaman tebu (Tim Penulis
PTPN XI, 2010).
Menurut Sudiatso (1982), tekstur tanah yang cocok untuk tanaman tebu adalah
tekstur tanah ringan sampai agak berat dengan kemampuan menahan air yang
cukup. Kedalaman (solum) tanah untuk pertumbuhan tanaman tebu minimal 50
cm dengan tidak ada lapisan kedap air. Syarat topografi lahan tebu adalah
berlereng panjang, rata, dan melandai. Bentuk permukaan lahan yang baik untuk
pertumbuhan tebu adalah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng
0– 8 % .
2.1.2Botani Tanaman Tebu
Secara taksonomi, tanaman tebu tergolong ke dalam famili rumput-rumputan
(Poaceae). Klasifikasi ilmiah tanaman tebu adalah sebagai berikut (The Columbia
10
Secara morfologi, tanaman tebu memiliki sistem perakaran serabut yang terbagi
menjadi dua, yaitu akar tunas dan akar setek. Akar tunas adalah akar yang
tumbuh dari mata tunas, sedangkan akar setek adalah akar yang tumbuh pada
cincin akar batang. Akar setek tidak berumur panjang, sedangkan akar tunas
berumur panjang dan merupakan akar permanen (Miller et al., 2006).
Menurut Heinz (1987), batang tanaman tebu tidak bercabang dan terbagi atas dua
bagian yaitu buku dan ruas. Buku adalah bagian dari batang yang
menghubungkan antara ruas satu dengan ruas berikutnya. Pada buku terdapat
mata tunas tempat melekatnya pelepah daun. Pada ruas terdapat jalur munculnya
tunas dan lapisan lilin yang berbatasan dengan bagian bawah buku. Batang tebu
memiliki warna dan bentuk yang berbeda-beda. Warna batang ada yang merah,
kuning, dan hijau. Bentuk batang ada yang lurus, bengkok, cekung, dan cembung.
Daun tebu tumbuh dari buku pada salah satu sisi batang, dan posisi daun pada
batang biasanya berlawanan arah secara silih berganti (membentuk dua barisan).
Panjang daun dapat mencapai 1 m dengan lebar mencapai 10 cm. Stomata
terdapat pada kedua sisi permukaan daun. Kepadatan stomata lebih banyak pada
permukaan bawah daun daripada permukaan atas daun (James, 2004). Menurut
Miller et al., (2006), ketika tanaman tebu berubah dari fase vegetatif ke fase
generatif pembentukan daun akan terhenti dan mulai terjadi pembungaan. Bunga
tebu merupakan bunga majemuk yang berbentuk malai. Dalam satu malai
terdapat beribu-ribu bunga kecil yang masing-masing memproduksi satu biji.
11
2.2 Kutu Perisai (Aulacaspis tegalensis Zehnt.)
2.2.1 Asal-Usul dan Klasifikasi A. tegalensis
Kutu perisai Aulacaspis tegalensis Zehnt. muncul di Mauritius pada abad ke-19
atau mungkin lebih awal, tetapi serangan yang serius di lapang terjadi mulai tahun
1913 (De Charmoy, 1913 dalamWilliams, 1970). Serangga ini disebut kutu
perisai karena berada didalam lapisan lilin yang berbentuk seperti perisai sehingga
kutu ini tidak tampak dari luar. Klasifikasi kutu perisai adalah sebagai berikut
(Encyclopedia of life, 2013):
Spesies : AulacaspistegalensisZehnt.
Kata diaspididae berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia (ditengah) dan aspis
(perisai bulat). Disebut demikian karena hama ini tampak seperti sisik yang bulat
atau perisai. Hama ini ada yang hanya hidup di satu jenis tanaman dan ada pula
yang menyerang beberapa jenis tanaman, bahkan ada yang memakan segala
macam tanaman (Pracaya, 2007).
Menurut Kalshoven (1981), A. tegalensis merupakan hama tebu di Pulau Jawa.
Spesies lain dari golongan yang sama antara lain A. madiunensis, Chionaspis
saccharifolia, Pinnaspis aspidistrae latus, Odonaspis saccharicaulus, dan
Uniaspis citri Comst. Kutu A. tegalensis dapat menyerang berbagai macam klon
12
Kutu A. tegalensis mempunyai ukuran tubuh yang tergolong kecil, jika sudah
dewasa panjangnya hanya 1,32 mm. Kutu perusak tebu ini tinggal dalam perisai
yang terbuat dari bahan lilin hasil sekresinya sendiri dan lapisan lilin batang tebu,
yang berukuran panjang 2,39 mm (Tim Kutu Perisai, 2002).
2.2.2 Siklus Hidup A. tegalensis
Siklus hidup A. tegalensis berkisar antara 3 hingga 9 minggu. Siklus hidup di
dataran rendah bervariasi dari 3-3,5 minggu di pertengahan musim panas dan
sampai 7 minggu di pertengahan musim dingin. Sedangkan di dataran tinggi
siklus hidup beragam antara 4 hingga 8 minggu (Williams, 1970). Menurut Rao
dan Sankaran (1969, dalam Sunaryo dan Hasibuan, 2003) kutu perisai dapat
menghasilkan telur 150-250 butir yang diletakkan dalam perisai pelindung. Hasil
penelitian Williams (1970) menjelaskan bahwa telur hama ini berbentuk silindris,
panjangnya 250-280 µm dan diameter 110 µm, berwarna kuning dan dibungkus
lapisan lilin putih. Telur diletakkan di dalam perisai kutu betina. Setelah menetas
perkembangan selanjutnya terdiri dari dua instar pada betina dan empat instar
13
Gambar 1. Telur kutu perisai (Sumber : Sunaryo, komunikasi pribadi PT GMP 2014).
Instar pertama atau perayap (crawler) warnanya sama dengan telur, bentuknya
lonjong, punya mata, antena, tungkai, dan di ujung belakang (posterior) terdapat
dua ekor rambut (setae). Stadia ini yang bisa berpindah atau bisa dikatakan nimfa
aktif sampai menusukkan stiletnya ke tanaman inang, kemudian menetap, dan
mulai mengeluarkan lilin membentuk perisai. Jenis kelamin jantan dan betina
terlihat setelah ganti kulit pertama yaitu pada instar ke-2 ketika bentuk tubuh dan
perisainya berbeda. Betina memiliki bentuk perisai seperti buah pir, dengan ujung
kepala melebar. Sedangkan jantan memiliki bentuk memanjang dengan ujung
anterior menyempit dan bentuk perisai menyerupai tabung silindris. Selanjutnya
perkembangan pradewasa jantan dan betina memerlukan waktu yang sama yaitu
32 hari, penggabungan stadia prapupa dan pupa jantan sama dengan waktu untuk
sklerotisasi pada instar kedua betina, dan ganti kulit terakhir bersamaan waktunya
14
Dewasa betina terbuahi sesudah ganti kulit terakhir, ukurannya meningkat dan
perisainya melebar ke samping dan ke belakang selama masa pre-oviposisi
(Gambar 2). Semakin tua warnanya akan merah jambu sebagai tanda adanya telur
di dalam tubuh betina. Dewasa jantan akan segera kawin dengan cara naik keatas
perisai betina dan menggerak-gerakan abdomennya kebawah untuk memasukkan
organ kopulasinya yang tajam lewat tepi perisai betina (Williams, 1970).
Gambar 2. Perisai A. tegalensis (Sumber : Sunaryo, komunikasi pribadi PT GMP 2014).
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan A. tegalensis
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kutu
perisai A. tegalensis, secara umum sebagai berikut (Williams, 1970) :
15
Karakter tanaman inang seperti pelepah yang rapat mencegah kutu untuk sampai
pada permukaan batang. Sebaliknya, pelepah yang tidak cukup rapat lebih
disukai kutu untuk berkembang. Pelepah daun melindungi kutu dari cuaca, dari
gesekan antartanaman, dan dari musuh alami. Pertumbuhan tanaman yang pesat
dan perpanjangan batang yang cepat,baik untuk perkembangan kutu. Saat
tanaman mencapai kemasakan akhir, inang menjadi kurang cocok untuk kutu
perisai. Keberadaan musuh alami juga merupakan faktor biotik yang berpengaruh
terhadap perkembangan kutu A. tegalensis. Beberapa musuh alami yang diketahui
memiliki peranan dalam menekan perkembangan kutu A. tegalensis, antara lain
predator Cybocephalus mollis (Coleoptera; Nitidullidae), Lindorus lophanthae
(Coleoptera;Coccinellidae), Chilocorus nigritus (Coleoptera; Coccinellidae), dan
parasitoid Tetrastichus sp. (Hymenoptera; Eulophidae), Adelencyrtus femoralis
(Hymenoptera; Encyrtidae), Aspidiotiphagus fuscus (Hymenoptera; Aphelinidae).
2.2.3.2 Faktor Abiotik
Faktor abiotik yang berpengaruh terhadap perkembangan kutu A. tegalensis
adalah iklim. Daerah yang lebih kering lebih berpeluang untuk terserang dan
serangan berat sering terjadi secara luas dimana rerata curah hujan kurang dari
1400 mm. Sementara itu serangan lebih ringan dan lebih jarang terjadi pada saat
curah hujan tinggi hingga sekitar 1800 mm. Perkembangan kutu akan cepat saat
temperaturnya tinggi, sedangkan angin berpengaruh terhadap pemencaran kutu ke
16
2.3 Pola Sebaran Hama
Pola sebaran serangga hama yang diamati di lapangan merupakan faktor penting
yang harus diperhatikan dalam menentukan metode pengambilan sampel.
Menurut Odum (1998), pada dasarnya ada tiga sifat sebaran serangga yaitu: (1)
reguler atau seragam, (2) random atau acak, dan (3) clumped atau mengelompok.
Serangga yang memiliki sebaran seragam mengikuti distribusi teoritik binomial
positif. Sebaran seragam terjadi apabila diantara individu-individu populasi
terjadi persaingan yang keras atau karena ada teritorialisme. Serangga yang
memiliki sebaran random atau acak mengikuti distribusi teoritik Poisson. Sebaran
ini terjadi apabila faktor-faktor (kondisi dan sumber daya) lingkungan di area
yang ditempati bersifat seragam. Hal ini berarti bahwa probabilitas individu
untuk menempati satu situs tidak berbeda dengan menempati situs lain, dan
kehadiran suatu individu di suatu situs tidak akan mempengaruhi kehadiran
individu lainnya. Serangga yang memiliki sebaran clumped atau mengelompok
mengikuti sebaran teoritik binomial negatif. Sebaran mengelompok paling umum
dijumpai di alam. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan yang jarang seragam,
walaupun dalam luasan (area) yang relatif sempit. Selain hal tersebut, pola
reproduksi spesies yang pesat dan perilaku serangga yang hidup berkoloni juga
dapat mendorong terbentuknya kelompok.
Menurut Ludwig & Reynold (1988) sifat sebaran hama dapat ditentukan dari
perhitungan nilai tengah (μ) dan ragam (σ2). Apabila nilai σ2<μ maka sebaran
hama adalah teratur atau seragam, jika nilai σ2= μ maka sebaran hama adalah
17
distribusi frekuensi statistik dapat digunakan untuk lebih memastikan sebaran
hama. Distribusi Poisson untuk pola acak, distribusi binomial negatif untuk pola
III. BAHAN DAN METODE
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada lahan pertanaman tebu PT Gunung Madu
Plantations, Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada bulan Desember 2013.
3.2 Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah koloni kutu perisai A. tegalensis dan varietas tebu
GMP3, GP11, RGM00-869 berumur 6 bulan yang merupakan tanaman tebu yang
berasal dari tanaman sebelumnya yang telah ditebang dan sudah mengalami dua
kali keprasan (ratoon 2). Sedangkan alat yang digunakan adalah kaca pembesar
untuk melihat dan mengamati keberadaan A. tegalensis pada tanaman percobaan,
label pengamatan, dan tali rafia sebagai penanda tanaman yang diamati, meteran
untuk mengukur luasan petak dan plot percobaan, hand counter dan alat tulis
19
3.3 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara mengamati keberadaan
dan menghitung jumlah kutu A. tegalensis pada sampel tanaman tebu varietas
GMP 3, GP 11, dan RGM 00-869. Dari masing-masing varietas dipilih satu
lokasi untuk pengamatan. Pemilihan lokasi pengamatan berdasarkan riwayat
serangan kutu A. tegalensis yang dimiliki sebelumnya. Pada lokasi ditentukan
satu petak secara acak seluas 1 ha yang digunakan sebagai petak percobaan. Pada
petak percobaan ini ditentukan plot percobaan secara sistematis sebanyak 9 plot
dengan ukuran 6 x 6 m (Gambar 3). Tiap plot percobaan terdapat 5 baris
tanaman. Pada plot percobaan ditentukan 10 unit sampel secara diagonal dengan
ukuran masing-masing unit sampel adalah 1 m dalam baris, sehingga tiap baris
terdapat 2 unit sampel (Gambar 4).
20
Gambar 2. Pola penentuan unit sampel pada plot percobaan.
3.4 Pelaksanaan Penelitian
3.4.1 Pendugaan Pola Sebaran A. tegalensis
Pada unit sampel dipilih 1 tanaman secara sistematis yang digunakan sebagai
tanaman sampel. Tanaman sampel yang dipilih adalah tanaman yang berada di
bagian tengah unit sampel. Selanjutnya pendugaan pola sebaran A. tegalensis
antar ruas pada tanaman dilakukan dengan mengelupas pelepah yang menutupi
ruas batang tanaman sampel sampai batas dengan hanya menyisahkan lima
pelepah daun teratas. Setelah itu diamati keberadaan kutu A. tegalensis pada tiap
ruas dan dihitung jumlahnya secara manual dengan bantuan kaca pembesar dan
handcounter. Pada pengamatan pendugaan pola sebaran A. tegalensis antar
tanaman, dilakukan dengan menghitung jumlah kutu yang terdapat pada tiap
21
3.4.2 Pendugaan Intensitas Serangan
Pengamatan pendugaan intensitas serangan A. tegalensis dilakukan secara visual
berdasarkan populasi hama yang terdapat pada tanaman sampel. Sampel tanaman
yang diamati sama dengan sampel tanaman yang dipilih pada pengamatan
pendugaan pola sebaran. Batang tanaman yang terdapat populasi
A. tegalensis dihitung satu (terserang), kemudian dihitung berapa jumlah batang
tanaman tebu yang terserang dari 90 tanaman sampel yang diamati pada setiap
varietas.
3.5 Analisis Data
3.5.1 Pendugaan Pola Sebaran A. tegalensis
Data hasil pengamatan ditabulasikan dan dianalisis untuk mendapatkan nilai
tengah (mean), ragam (variance), dan indeks dispersi (indeks of dispersion, ID).
Selanjutnya dianalisis dengan uji Poisson dan binomial negatif (Ludwig &
Reynold, 1988) menggunakan perangkat pengolah data Microsoft Quickbasic
untuk lebih memastikan sebaran A. tegalensis. Dalam analisis ini, nilai akhir χ2
hitung yang diperoleh dari uji Poisson dibandingkan dengan nilai χ2 tabel 0,05.
Apabila nilai χ2hitung < χ2
tabel maka kesimpulannya adalah gagal menolak
hipotesis bahwa sebaran hama ini mengikuti pola Poisson (acak). Sebaliknya, jika
nilai χ2hitung > χ2
tabel maka terjadi penolakan terhadap hipotesis bahwa sebaran
hama ini mengikuti pola Poisson (acak), sehingga dilakukan uji lanjutan dengan
uji binomial negatif untuk lebih memastikan lagi bahwa pola sebaran hama ini
22
disimpulkan gagal menolak hipotesis bahwa sebaran hama ini mengelompok.
Sebaliknya, jika nilai χ2hitung > χ2
tabel maka terjadi penolakan terhadap
hipotesis binomial negatif bahwa sebaran hama ini mengelompok.
3.5.2 Pendugaan Intensitas Serangan
Data hasil pengamatan dihitung intensitas serangannya. Adapun rumus yang
digunakan untuk menghitung persentase intensitas serangan adalah :
I = x 100% Keterangan :
I = Intensitas serangan (%) n = Jumlah batang yang terserang N = Jumlah batang yang diamati
Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan sidik ragam (ANOVA) dan
dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf nyata 5% dengan
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :
1. Karakteristik tebu tidak berpengaruh terhadap pola sebaran A. tegalensis antar
ruas pada tanaman. Pola sebaran A. tegalensis pada varietas GMP 3, GP 11,
dan RGM 00-869 adalah mengelompok.
2. Karakteristik tebu berpengaruh terhadap pola sebaran A. tegalensis antar
tanaman. Pola sebaran A. tegalensis pada varietas GMP 3 dan GP 11 adalah
mengelompok, sedangkan pada varietas RGM 00-869 ada diantara acak dan
mengelompok.
3. Ketahanan varietas tebu berpengaruh terhadap intensitas seranganA.
tegalensis.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan setelah penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian
lanjutan dengan perbedaan karakteristik tanaman yang lebih kompleks, umur
PUSTAKA ACUAN
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. 2014. Informasi Komoditas Tebu. http://disbun.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/666. Diakses pada tanggal 11 Mei 2014.
Direktorat Jenderal Perkebunan. 2009. Komoditas Tanaman Tebu.
http://ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/images/pdf/tebu.pdf. Diakses pada tanggal 22 Juni 2013.
Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013a. Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan 2008-2013.http://ditjenbun.pertanian.go.id/ tinymcpuk/ gambar/file/Produksi_Estimasi_2013.pdf. Diakses pada tanggal 27 April 2014.
Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013b. Kebutuhan Gula Nasional Mencapai 5700 Juta Ton Tahun 2014. http://ditjenbun.pertanian.go.id/
setditjenbun /berita-172-dirjenbun--kebutuhan-gula-nasional-mencapai-5700-juta-ton-tahun-2014.html. Diakses pada tanggal 27 April 2014.
Encyclopedia of Life. 2013. Aulacaspis tegalensis. http://eol.org/pages/836016/ names. Diakses pada tanggal 22 Mei 2014.
Ferliyansyah. 2006. Daya Mangsa Predator Chilocorus melanophthalmus
Muslant. Pada Berbagai Kepadatan Populasi Kutu Perisai Aulacapsis tegalensis. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 35 hlm.
Hasibuan, R. 2003. Pengendalian Hama Terpadu. Penerbit Universitas Lampung Cetakan Pertama. 103 hlm.
Hasibuan, R. 2004. Evaluasi Lapang Terhadap Dampak Aplikasi Insektisida Isoprocarb Pada Serangga Predator dan Hama Kutu Perisai Aulacaspis Tegalensis Zhnt. (Homoptera: Diaspididae) di Pertanaman Tebu. J.HPTTrop. 4(2):69-74.
Heinz, D.J. 1987. Sugarcane Improvement through Breeding. Elsevier Science Publishing Company Inc. New York. 604 hlm.
33
James, G. 2004. Sugarcane Second Edition. Blackwell Publishing Company. UK. 211 hlm.
Kalshoven, L.G.E. 1981. The Pest of Corps In Indonesia. Revised and Translated by P.A Van Der Laan. Ichtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta. 701 hlm.
Ludwig, J.A. dan J.F. Reynold. 1988. Statistical Ecology: A Primer on Methods and Computing. John willey and Sons. San Diego. 337 hlm.
Miller, J.D., R.A. Gilbert., D.C. Odera. 2006. Sugarcane Botany: A Brief View. University of Florida. SS-AGR-234. http://edis.ifas.ufl.edu/sc034. Diakses pada tanggal 23 Mei 2014.
Misran, E. 2005. Industri Tebu Menuju Zero Waste Industry. Jurnal Teknologi Proses 4(2) Juli 2005: 6-10.
Odum, E.P. 1998. Dasar-Dasar Ekologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 697 hlm.
P3GI. 2008. Konsep Peningkatan Rendemen Untuk Mendukung Program Akselerasi Industri Gula Nasional. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. 26 hlm.
Pemberton, S.G and R.W. Frey. 1984. Quantitative Methods in Ichnology : Spatial Distribution Among Population. Lethaia 17: 33-49.
Pracaya. 2007. Hama Penyakit Tanaman Edisi Revisi. Penebar Swadaya. Yogyakarta. 428 hlm.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. 2013. Penggerek Pucuk Tebu: Hama Penting Tanaman Tebu. http://perkebunan.litbang.deptan.go.id/. Diakses tanggal 10 Mei 2014.
R & D PT GMP. 2001. Kutu Perisai (Aulacaspis tegalensis Zehnt. :
Diaspididae). Publikasi Intern Research and Development PT Gunung Madu Plantations.
Sudarsono, H dan S. Pramono. 1998. Penggerek Batang Prionoxystes sp. (Lepidoptera: Cossidae) Pada Pertanaman Gmelina arborea L. Agihan dan Pengendaliannya Dengan Metarhizium anisopliae. Universitas Lampung. Bandar Lampung.Bulletin Hama dan Penyakit Tumbuhan
10(1): 13-18.
34
Sunaryo dan R. Hasibuan. 2003. Perkembangan Kutu Perisai Aulacaspis tegalensis Zehnt. dan Pengaruh Tingkat Serangannya terhadap Penurunan Hasil Tanaman Tebu di PT Gunung Madu Plantations, Lampung Tengah. J.HPT Trop. 3(2); 1-5.
Suwarto dan Y. Octavianty. 2010. Budidaya 12 Tanaman Perkebunan Unggulan. Edisi Kesatu. Jakarta: Penebar Swadaya. 260 hlm.
Tarumingkeng, R.C. 1994. Dinamika Populasi: Kajian Ekologi Kuantitatif. Pustaka
Sinar Harapan dan Universitas Kristen Krida Wacana. Jakarta. 284 hlm.
The Columbia Encyclopedia. 2013. Sugarcane. http://www.encyclopedia.com/ topic/sugarcane.aspx. Diakses pada tanggal 21 Mei 2014.
Tim Kutu Perisai. 2002. Pengendalian Kutu Perisai Aulacaspis tegalensis Zehnt. Di Gunung Madu Plantations Th 2002/2003. Lampung Sugar Training Centre. PT Gunung Madu Plantations. Lampung Tengah.
Tim Penulis PTPN XI. 2010. Panduan Teknik Budidaya Tebu. PT Perkebunan Nusantara XI. Surabaya. 204 hlm.
Untung, K. 2006. Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu. Edisi Kedua.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 348 hlm.
Laba, I.W., A. Rauf., U. Kartosuwondo., M. Soehardian. 2008. Fenologi Pembungaan dan Kelimpahan Populasi Kepik Diconocoris hewetti (Dist.)(Hemiptera: Tingidiae) Pada Pertanaman Lada.Jurnal Littri
14(2): 43-53.
Williams, J.R. 1970. Studies on The Biology, Ecology and Econonomic
Importance of The Sugarcane Scale Insect Aulacaspis tegalensis (Zhnt)
(Diaspididae) in Mauritius. MSIRA, Reduit, Mauritius. Bull. Ent. Res.