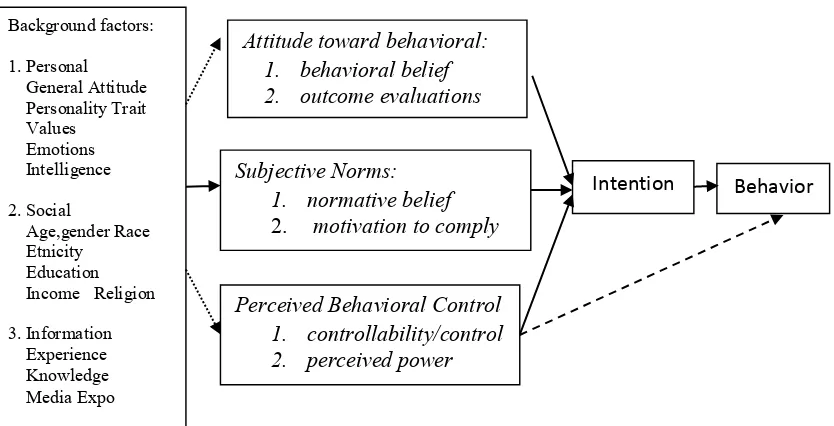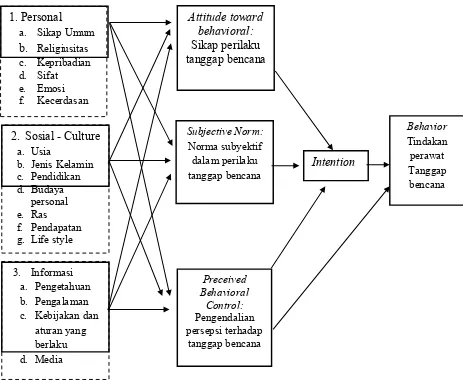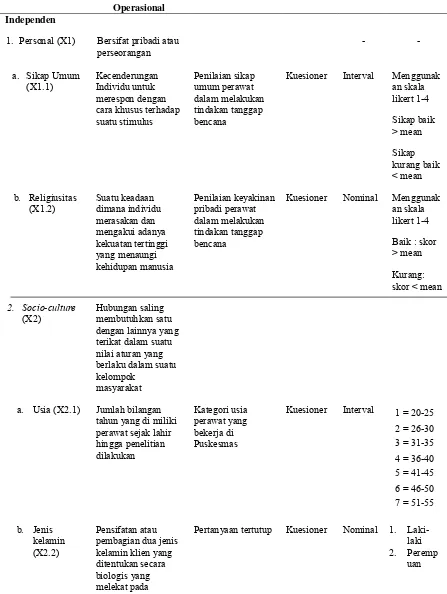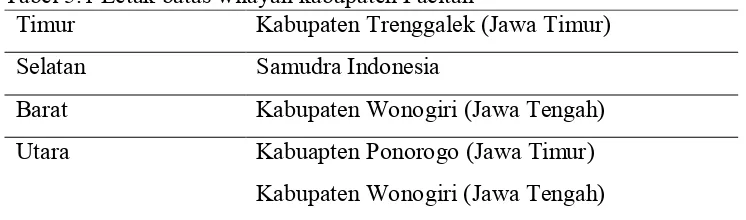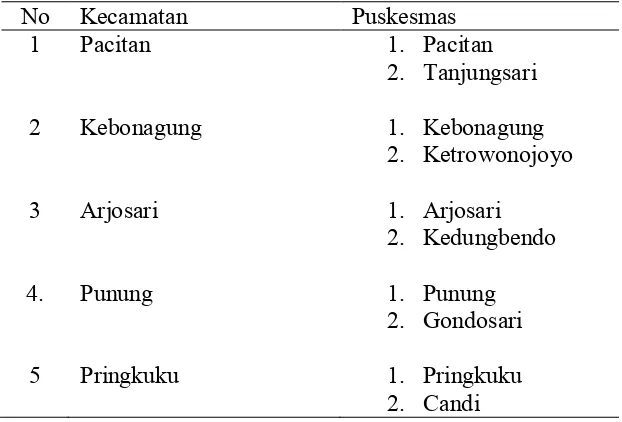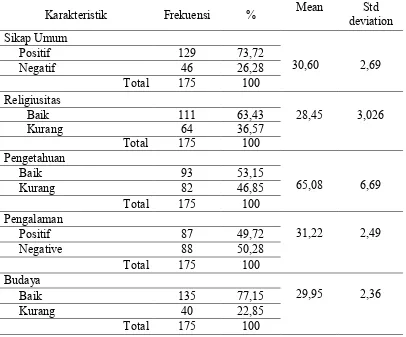TESIS
PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN
BUDAYA LOKAL
SETYO KURNIAWAN NIM. 1316141513031
PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TESIS
PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN
BUDAYA LOKAL
SETYO KURNIAWAN NIM. 1316141513031
PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN
BUDAYA LOKAL
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Keperawatan (M.Kep) dalam Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga
SETYO KURNIAWAN NIM. 131614153031
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri. Semua sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar
Nama : Setyo Kurniawan NIM : 131614153031 Tanda Tangan :
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
Sebagai sivitas akademik Universitas Airlangga Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Setyo Kurniawan NIM : 131614153031
Program Studi : Magister Keperawatan Departemen : Keperawatan Medikal Bedah Fakultas : Keperawatan
Jenis Karya : Tesis
Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, setuju untuk memberikan kepada Universitas Airlangga Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
“Pengembangan Model Tindakan Keperawatan Dalam Tanggap Bencana Berbasis
Theory Planned Behaviour Dalam Konteks Kearifan Budaya Lokal”
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan ini, maka Universitas Airlangga berhak untuk menyimpan, megalihmediakan/format, mengelola kedalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Surabaya Pada tanggal : 6 Agustus 2018
Yang Menyatakan,
INCREASING DEVELOPMENT MODEL IN DISASTER NURSING RESPONSE BASED ON THEORY PLANNED BEHAVIOUR IN A LOCAL
WISDOM
EXECUTIVE SUMMARY
Disasters are a serious dysfunction that occurs in a society or community that results in widespread losses, whether material, economic or environmental losses that exceed the capabilities of affected communities (Yan et al., 2015). East Java is one of the areas in Indonesia with potential disasters that have the worst impact. The number of casualties, economic losses and environmental damage is not small. Pacitan regency is one of 38 districts in East Java Province which has huge potential of natural disasters. Earthquakes, landslides, the potential for tsunamis is a threat to residents around Pacitan regency. The last disaster that struck Pacitan was the flash flood that occurred on 28 November 2017, where as many as 1,879 people fled, 19 people died, 14 victims were struck by landslides. Nurses are part of the first responder in disaster management needs to be better prepared in caring for mass casualties (Wenji et al., 2014) including starting when finding victims, stabilizing to make referrals. However, the field is still found in the victim immediately evacuated without any optimal stabilization process. According to Labrague et al. (2016) a nurse needs to have knowledge and skills on disaster and disaster management. From interviews conducted on 8 September 2017 to 14 disaster nurses, 2 nurses working in referral hospitals stated that they had received unstable casualty referrals.
This research use cross sectional approach. The sample in this research is all nurse of Puskesmas of Pacitan Regency, then with technique of sampling non probability sampling with purposive sampling method so get 175 nurse of Puskesmas of Pacitan Regency as respondent in this research. Inclusion criteria used to select the sample include: 1). Minimum 2 years nurse stay in Pacitan area. 2). Nurses who have emergency emergency training certificates with AHA / ERC / ILCOR guidelines at least in 2005. 3). Nurse who already has a diploma of higher education nursing (minimum Diploma 3). Based on the Partial Least Square Test indicates that: 1). Personal factors affect the behavior toward behavioral with the value of parameter coefficient of 0.149 and the value of t = 2.182> 1.96. 2). Personal factors affect the Subjective Norm with the parameter coefficient value of 0.216 and the value of t = 2.248> 1.96. 3). Personal factors affect the Perceived Behavioral Control with parameter coefficient value of 0.315 and the value of t = 4.099> 1.96. 4). Social-culture factor related to attitude toward behavioral with parameter coefficient value 0,037 and value t = 0,714 <1,96. 5). Social-culture factor influenced Subjective Norm with parameter coefficient value 0,244 and value t = 3,207> 1,96. 6). Social-culture factor influenced Perceived Behavioral Control with parameter coefficient value 0,136 and t value = 2,034> 1,96. 7). Factor of information influence toward behavior toward behavioral with value of parameter coefficient 0,732 and value t = 17,268> 1,96. 8). Factor of information not related to Subjective Norm with coefficient value of parameter -0,057 and value t = 0,780 <1,96. 9). Factor of information not related to Perceived Behavioral Control with value of parameter coefficient 0,086 and value t = 1,102 <1,96. 10). attitude toward behavioral have an effect on Intension with parameter coefficient value 0,192 and value t = 3,356> 1,96. 11). Subjective Norm effect on Intension with parameter coefficient value 0,496 and t value = 6,561> 1,96. 12). Perceived Behavioral Control has no effect on Intension with coefficient parameter value 0,074 and value t = 1,174 <1,96. 13). Intension has no effect on behavior (Behavior) with value of parameter coefficient 0,109 and value t = 1,649 <1,96
PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN
BUDAYA LOKAL RINGKASAN
Bencana adalah sebuah gangguan fungsi serius yang terjadi di suatu masyarakat atau komunitas yang mengakibatkan kerugian yang meluas, baik kerugian material, ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat terdampak bencana (Yan et al., 2015). Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi bencana yang memiliki dampak terburuk. Jumlah korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi bencana alam yang sangat besar. Gempa bumi,tanah longsor, potensi terjadi tsunami adalah ancaman bagi penduduk di sekitar wilayah Kabupaten Pacitan. Bencana terakhir yang melanda Pacitan adalah banjir bandang yang terjadi tanggal 28 November 2017, di mana sebanyak 1.879 warga mengungsi, 19 orang meninggal, 14 korban tertimpa tanah longsor. Perawat merupakan bagian dari first responder dalam penanganan bencana perlu dipersiapkan dengan lebih baik dalam merawat korban massal (Wenji et al., 2014) termasuk mulai saat menemukan korban, melakukan stabilisasi hingga melakukan rujukan. Akan tetapi dilapangan masih di temukan korban segera di evakuasi tanpa ada proses stabilisasi yang optimal. Menurut Labrague et al., (2016) seorang perawat perlu memiliki pengetahuan dan skill mengenai bencana dan manajemen bencana. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan tanggal 8 september 2017 terhadap 14 orang perawat bencana, 2 orang perawat yang bekerja di rumah sakit rujukan menyatakan bahwa pernah menerima rujukan korban bencana yang masih belum stabil.
keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia (Leininger, 2002). Leinenger berpendapat bahwa kombinasi pengetahuan tentang pola praktik keperawatan transcultural dengan kemajuan tekhnologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan perawatan kesehatan orang banyak dan berbagai kultur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perawat Puskesmas Kabupaten Pacitan, yang kemudian dengan tekhnik sampling non probability sampling dengan metode
purposive sampling sehinggadi dapatkan 175 orang perawat Puskesmas
Kabupaten Pacitan sebagai responden dalam penelitian ini. Kriteria inklusi yang digunakan untuk memilih sample antara lain: 1). Perawat yang minimal selama 2 tahun tinggal di wilayah Pacitan. 2). Perawat yang memiliki sertifikat pelatihan kegawat daruratan dengan guideline AHA/ERC/ILCOR minimal tahun 2005. 3). Perawat yang telah memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan (minimal Diploma 3). Berdasarkan Uji Partial Least Square menunjukkan bahwa : 1). Faktor personal berpengaruh terhadap attitude toward behavioral dengan nilai koefisiensi parameter 0,149 dan nilai t = 2,182 > 1,96. 2). Faktor personal berpengaruh dengan Subjective Norm dengan nilai koefisiensi parameter 0,216 dan nilai t = 2,248 > 1,96. 3). Faktor personal berpengaruh pada Perceived Behavioral Control dengan nilai koefisien parameter 0,315 dan nilai t = 4,099 > 1,96. 4). Faktor social-culture berhubungan dengan attitude toward behavioral dengan nilai koefisien parameter 0,037 dan nilai t = 0,714 < 1,96. 5). Faktor social-culture berpengaruh terhadap Subjective Norm dengan nilai koefisien parameter 0,244 dan nilai t = 3,207 > 1,96. 6). Faktor social-culture berpengaruh terhadap Perceived Behavioral Control dengan nilai koefisien parameter 0,136 dan nilai t = 2,034 > 1,96. 7). Faktor information berpengaruh terhadap attitude toward behavioral dengan nilai koefisien parameter 0,732 dan nilai t = 17,268 >1,96. 8). Faktor information tidak berhubungan dengan Subjective Norm dengan nilai koefisien parameter -0,057 dan nilai t = 0,780 < 1,96. 9). Faktor information tidak berhubungan dengan Perceived Behavioral Control dengan nilai koefisien parameter 0,086 dan nilai t = 1,102 < 1,96. 10). attitude toward behavioral berpengaruh pada Intension dengan nilai koefisien parameter 0,192 dan nilai t = 3,356 > 1,96. 11). Subjective Norm berpengaruh terhadap Intension dengan nilai koefisien parameter 0,496 dan nilai t = 6,561 > 1,96. 12). Perceived Behavioral Control tidak berpengaruh terhadap Intension dengan nilai koefisien parameter 0,074 dan nilai t = 1,174 < 1,96. 13). Intension tidak ada pengaruh terhadap perilaku (Behaviour) dengan nilai koefisien parameter 0,109 dan nilai t = 1,649 < 1,96
INCREASING DEVELOPMENT MODEL IN DISASTER NURSING RESPONSE BASED ON THEORY PLANNED BEHAVIOUR IN A LOCAL
WISDOM
ABSTRACT
Introduction: Disaster is a serious dysfunction that occurs in a society or
community that results in widespread losses with many victims. Various efforts continue to be made to develop the ability of human resources in the face of disaster. Actually on real disaster situations still found the victim immediately brought to definitive care without optimal stabilization process. So there is found many DOA (Death On arrival) when the victims comes to intra hospital. The purpose of this study is to validate the model hypothesis that influences the behavior of the disaster response nurses. Method: This study used cross-sectional
design. 175 nurses in Pacitan, Indonesia follow this study by purposive sampling. The data taken are the factors that influence behavior on Theory Planned Behavior and local cultural wisdom. Result and Analysis: Significantly personal factors
relate to attitude (t=2.182), Information relates to attitude (t=17.268), social culture is not related to attitude (t = 0.714), intension is not related to behavior (t = 1.649). Discussion and Conclusion: Personal factors and information obtained
affect a person to behave and have an intention in disaster response, but ultimately not necessarily someone willing to take disaster response measures in accordance with the intention. This is become principal and to be background factor on SPGDT (General Emergency Life Support)
PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN
BUDAYA LOKAL
ABSTRAK
Introduction: Bencana merupakan gangguan fungsi serius yang terjadi di suatu
masyarakat atau komunitas yang mengakibatkan kerugian yang meluas dengan angka korban tidak bisa dikatakan sedikit. Bermacam upaya terus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana. Akan tetapi masih di temukan korban segera di bawa tanpa proses stabilisasi optimal. Dan pada situasi nyata bencana masih di dapatkan angka DOA (Death On Arrival) ketika korban masuk ke dalam fase intra hospital. Tujuan dari penelitian ini adalah memvalidasi hipotesis model yang mempengaruhi perilaku perawat tanggap bencana. Method: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. 175 orang perawat se Kabupaten Pacitan di pilih dengan purposive sampling. Data yang diambil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pada Theory Planned Behavior dan kearifan budaya lokal. Result and Analysis:
Secara signifikan faktor personal berhubungan dengan attitude (nilai t=2,182), Informasi berhubungan dengan attitude (nilai t=17,268), sosial culture tidak berhubungan dengan attitude (nilai t=0,714), intension tidak berhubungan dengan behavior (t=1,649). Discussion and Conclusion: faktor personal dan informasi
yang didapatkan mempengaruhi seseorang untuk bersikap dan memiliki suatu niat dalam tanggap bencana, akan tetapi pada akhirnya belum tentu seseorang mau melakukan tindakan tanggap bencana sesuai dengan niatnya. Situasi ini yang menjadi prinsip latar belakang dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
DAFTAR ISI
SAMPUL LUAR ... i
SAMPUL DALAM... ii
PRASYARAT GELAR ... iii
PERNYATAAN ORISINALITAS ... iv
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS ... v
LEMBAR PENGESAHAN TESIS ... vi
KATA PENGANTAR... vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI ... ix
EXECUTIVE SUMMARY ... x
DAFTAR SINGKATAN... xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN... 1
2.1.2 Sikap (Attitude toward behavioral)... 10
2.1.3 Subjective Norm ... 13
2.1.4 Perceived Behavioral Control ... 14
2.1.5 Variabel Lain Yang Mempengaruhi ... 16
2.2 Perilaku ... 19
2.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi terbentuknya Perilaku... 20
2.2.2 Domain Perilaku Kesehatan ... 22
2.3 Definisi Bencana... ... 28
2.3.1 Jenis-jenis Bencana Alam ... 29
2.3.2 Disaster Management ... 33
2.3.3 Peran Perawat Dalam Bencana ... 36
2.3.4 Religiusitas dan Bencana... 37
2.4.1 Konsep Transkultural ... 40
2.4.2 Peran dan Fungsi Keperawatan Transkultural ... 42
2.4.3 Kearifan Budaya Lokal Pacitan ... 43
2.5 Keaslian Penelitian ... 47
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL... 55
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian... 55
3.2 Hipotesis Penelitian... 57
BAB 4 METODE PENELITIAN... 59
4.1 Desain Penelitian... 59
4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Sampling 4.2.1 Populasi... 59
4.2.2 Sampel dan Besar Sample... 59
4.2.3 Teknik Sampling... 60
4.3 Variabel Penelitian 4.3.1 Variabel Independen... 60
4.3.2 Variabel Dependen... 61
4.4 Definisi Operasional... 62
4.5 Instrumen Penelitian ... ... 64
4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas ... 65
4.7 Lokasi dan Waktu Pengambilan Data Penelitian... 66
4.8 Prosedur Pengumpulan Data………. 66
4.9 Kerangka Kerja Penelitian... 68
4.10 Analisis Data... 69
4.11 Pengujian Hipotesis... 70
4.12 Etika Penelitian... 71
BAB 5 HASIL PENELITIAN ... 7
5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 7
5.1.1 Geografi ... 7
5.1.2 Topografi dan Iklim ... 7
5.1.3 Kependudukan ... 7
5.1.4 Wilayah Peka Bencana dan Wilayah Kritis... 7
5.1.5 Sarana Kesehatan ... 7
5.2. Karakteristik Responden Penelitian ... 5.2.1 Socio-Cultur Responden... 5.2.2 Karakteristik Faktor Latar Belakang ... 8
5.2.3 Karakteristik Faktor Pembentuk Sikap ... 8
5.2.4 Karakteristik Faktor Pembentuk Perilaku ... 8
5.3.Analisis Inferensial Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behavior ... 8
5.3.1 Evaluasi Model Pengukuran atau outer model ... 8
5.3.2 Pengujian Model Struktural atau inner model ... 8
5.3.3 Pengujian Hipotesis... 8
5.4.Hasil Focus Grup Discussion (FGD) ... 9
BAB 6 PEMBAHASAN ... 9
6.1. Pengaruh Faktor Personal Terhadap Attitude Toward Behavioral pada Tindakan Perawat Tanggap Bencana ... 9
6.2. Pengaruh Faktor Personal Terhadap Subjective Norm pada Tindakan Perawat Tanggap Bencana ... 9
6.3. Pengaruh faktor personal dengan Perceived Behavioral Control dalam perilaku tanggap bencana ... 9
6.4. Pengaruh faktor Social-culture dengan attitude toward behavioral dalam perilaku tanggap bencana ... 6.5. Pengaruh Social-culture dengan Subjective Norm dalam perilaku tanggap bencana ... 10
6.6. Pengaruh Social-culture dengan Perceived Behavioral Control dalam perilaku tanggap bencana ... 10
6.7. Pengaruh Information dengan attitude toward behavioral dalam perilaku tanggap bencana ... 10
6.8. Pengaruh Information dengan Subjective Norm dalam perilaku tanggap bencana……… 10
6.9. Pengaruh Information dengan Perceived Behavioral Control dalam perilaku tanggap bencana ... 10
6.10. Pengaruh attitude toward behavioral terhadap Intension dalam perilaku tanggap bencana ... 10 6.11. Pengaruh Subyektive Norm terhadap Intension dalam perilaku tanggap bencana ... 11
6.12. Pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap Intension dalam perilaku tanggap bencana ... 11
6.13. Pengaruh Intension terhadap perilaku (Behaviour) tanggap bencana ... 11
6.14. Temuan Penelitian ... 11
6.15. Keterbatasan Penelitian ... 12
BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN ... 12
7.1 Simpulan ... 12
7.2 Saran ... 12
DAFTAR PUSTAKA ... 12
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel Keaslian Penelitian... 46 Tabel 4.1 Variabel Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Tindakan
Keperawatan Dalam Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned
Behaviour Dalam Konteks Kearifan Budaya
Lokal... 61
Tabel 4.2 Definisi Operasional Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Dalam Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behaviour Dalam Konteks Kearifan
Budaya Lokal... 62
Tabel 5.1 Letak batas wilayah kabupaten Pacitan………... 74 Tabel 5.2 Distribusi Puskesmas di wilayah Kabupaten Pacitan……….. 77 Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik
Sosio-Culture……… 79
Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan karakteristik personal (Sikap umum, Religiusitas) Informasi (Pengetahuan, Pengalaman, Budaya)………... 80 Tabel 5.5 Distribusi responden berdasarkan attitude toward
behavioral, subyektive norm, perceived behavioral control
……… 81
Tabel 5.6 Distribusi responden berdasarkan Intension dan
Behavior……….………. 82
Tabel 5.7 Perhitungan measuremen model (outer model) pada Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di Kabupaten Pacitan………. 84 Tabel 5.8 Perhitungan measuremen model (inner model) pada Model
Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di Kabupaten Pacitan …………... 86 Tabel 5.9 Hasil perhitungan uji t (T-Test) pada Model Peningkatan
Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory
Planned Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di
Tabel 5.10 Goodness of fit (GoF) pada Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned
Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di
Kabupaten Pacitan……….. 90 Tabel 5.19 Hasil FGD pada Model Peningkatan Tindakan
Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned
Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 2005)... 8
Gambar 2.2 Model Konsep Teori Transkultural (Leineinger, 2002)…….. 42
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Berbasis Theory Planned Behaviour, Transkultural Model, dan Culture, Context and
Behaviour... 55
Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Tindakan Keperawatan dalam Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behaviour dalam Konteks Kearifan Budaya Lokal………... 68
Gambar 5.1 Measurement model (outer model)………. 83
Gambar 5.2 Measurement model (inner model)………. 85
Gambar 5.3 Structural model (Pengujian hipotesis)……… 87
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
Lampiran 1 : Inform Consent………..………... 1
Lampiran 2 : Kuesioner Background Faktor………... 2
Lampiran 3 : Kuesioner Sikap Umum……….. 3
Lampiran 4 : Kuesioner Religiusitas………... 4
Lampiran 5 : Kuesioner Pengetahuan………... 5
Lampiran 6 : Kuesioner Sikap Terhadap Tindakan Tanggap Bencana… 7
Lampiran 7 : Kuesioner Pengalaman……… 9
Lampiran 8 : Kuesioner Norma Subyektif……….. 10
Lampiran 9 : Kuesioner Perceived Behavioral Control……….. 11
Lampiran 10 : Kuesioner Intensi……… 12
Lampiran 11 : Kuesioner Budaya……….. 13
Lampiran 12 : Lembar Observasional……….. 14
Lampiran 13 : Panduan Teknis FGD……… 15
Lampiran 14 : Keterangan Lolos Kaji Etik……….. 21
Lampiran 15 : Rekomendasi Penelitian... 22
Lampiran 16 : Modul Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana
DAFTAR SINGKATAN
3 A : Amankan diri, Amankan lingkungan, Amankan korban
AHA : American Heart Association
ATLS : Advance Trauma Life Support
BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ERC : European Resuscitation Council
FGD : Focus Group Discussion
ICN : International Council of Nursing
IGD : Instalasi Gawat Darurat
ILCOR : The International Liaison Committee On Resuscitation
PBC : Perceived Behavioral Control
PLS : Partial Least Square
SAR : Search And Rescue
SN : Subyektive Norm
SPGDT : Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
TPB : Theory of Planned Behaviour
TRA : Theory Reaction of Action
BAB 1 PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
Badan Kesehatan Dunia WHO, mendefinisikan bahwa bencana adalah
sebuah gangguan fungsi serius yang terjadi di suatu masyarakat atau komunitas
yang mengakibatkan kerugian yang meluas, baik kerugian material, ekonomi atau
lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat terdampak bencana (Yan et
al., 2015). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mencatat
bahwa selama tahun 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana di Indonesia, naik 35%
jika dibandingkan dengan jumlah bencana pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 92% adalah bencana hidrometeorologi yang didominasi oleh banjir,
longsor dan puting beliung. Selama tahun 2016 telah terjadi 766 bencana banjir,
612 longsor, 669 puting beliung, 74 kombinasi banjir dan longsor, 178 kebakaran
hutan dan lahan, 13 gempa, tujuh gunung meletus, dan 23 gelombang pasang dan
abrasi. Dampak yang ditimbulkan bencana telah menyebabkan 522 orang
meninggal dunia dan hilang, 3,05 juta jiwa mengungsi dan menderita, 69.287 unit
rumah rusak dimana 9.171 rusak berat, 13.077 rusak sedang, 47.039 rusak ringan,
dan 2.311 unit fasilitas umum rusak. (www.bbc.com).
Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi
bencana yang memiliki dampak terburuk. Jumlah korban kematian, luka-luka,
kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan tidak bisa dikatakan sedikit.
Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Propinsi Jawa
Kedaruratan dan Logistik BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
wilayah Pacitan yang dikutip dari Radar Madiun tanggal 6 Agustus 2016, mulai
bulan Januari hingga bulan Juli ada sekitar 326 kejadian bencana, seperti gempa
bumi dan tanah longsor. Akan tetapi dari situs BPBD Pacitan dan situs Dinas
Kesehatan Kabupaten Pacitan tidak di sebutkan data jumlah korban luka-luka dan
meninggal. Pada tanggal 28 November 2017 telah terjadi banjir besar yang
melanda wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil Press Release yang di
umumkan oleh BPBD Pacitan per tanggal 30 November 2017 di dapatkan data
sebanyak 1.879 warga mengungsi yang tersebar di 8 titik pengungsian, 19 orang
meninggal di mana 5 diantaranya karena terseret arus banjir, 14 korban tertimpa
tanah longsor, 5 orang sedang dalam proses pencarian oleh tim penyelamat.
Bermacam upaya terus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan
sumber daya manusia dalam menghadapi bencana, akan tetapi tingginya angka
korban kejadian bencana tidak dapat di hindari. Perawat sebagai salah satu bagian
dari first responder dalam penanganan bencana perlu dipersiapkan dengan lebih
baik dalam merawat korban massal (Wenji et al., 2014) termasuk mulai saat
menemukan korban, melakukan stabilisasi hingga melakukan rujukan. Akan tetapi
dilapangan masih di temukan situasi bahwa korban yang ditemukan segera di
bawa tanpa ada proses stabilisasi yang optimal. Menurut Labrague et al., (2016)
seorang perawat perlu memiliki pengetahuan dan skill mengenai bencana dan
manajemen bencana.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan tanggal 8 september 2017
terhadap 14 orang perawat bencana, 3 orang perawat menjawab korban harus
bencana dengan memberikan oksigen menggunakan nasal, pasang cairan infus,
hentikan perdarahan semampunya lalu korban segera dirujuk secepatnya.
Sedangkan 2 orang perawat lainnya yang bekerja di rumah sakit rujukan
menyatakan bahwa pernah menerima korban bencana yang masih belum stabil
saat dirujuk ke IGD Rumah Sakit.
Keperawatan sebagai bagian dari first responder dituntut untuk selalu siap
sedia memberikan keilmuan dan keterampilan terkait bencana dan manajemen
bencana untuk memberikan pertolongan kepada setiap yang membutuhkan dalam
keadaan apapun termasuk dalam situasi tanggap bencana (Baack and Alfred,
2013). Menurut Martinsen dalam Alligood, (2014), seorang perawat memiliki
tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk
membantu orang lain sebagai sesama manusia dalam berbagai kondisi baik saat
sedang dalam tugas sebagai profesional maupun sedang tidak dalam tugas
profesional termasuk dalam situasi bencana. Pelaksanaan tindakan keperawatan
pada situasi tanggap bencana memiliki tantangan tersendiri. Berbagai macam
dinamika yang terjadi saat bencana, karakteristik masing-masing individu
perawat, serta pengalaman positif maupun negatif, emosi termasuk rasa bangga,
takut, komitmen ikut mempengaruhi bagaimana tindakan keperawatan diberikan.
(Hammad et al., 2012).
Sebagai upaya meningkatkan tindakan keperawatan pada saat response
bencana, maka perlu adanya suatu pengembangan model aplikatif tentang
peningkatan kemampuan tindakan keperawatan perilaku tanggap bencana. Theory
of Planned Behavior mempunyai dasar pendekatan beliefs yang membentuk niat
Dengan pembentukan sebuah model yang berbasis Theory of Planned Behavior
diharapkan tim perawat tanggap bencana dan seluruh perawat khususnya di
wilayah Kabupaten pacitan di harapkan mampu meningkatkan kemampuan
tindakan dalam menolong korban bencana. Sehingga angka korban bencana yang
selamat diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.
1. 2 Rumusan Masalah
Bagaimana model pendekatan Theory of Planned Behavior terhadap
peningkatan tindakan keperawatan tanggap bencana dalam konteks kearifan
budaya lokal di Kabupaten Pacitan.
1.3Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan umum
Mengembangkan model peningkatan tindakan keperawatan tanggap
bencana berbasis Theory of Planned Behavior dalam konteks kearifan budaya
lokal di wilayah Kabupaten Pacitan.
1.3.2 Tujuan khusus
1 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (personal) terhadap attitude
toward behavioral dalam perilaku tanggap bencana
2 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (personal) terhadap subjective
Norm dalam perilaku tanggap bencana
3 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (personal) terhadap perceived
behavioral control dalam perilaku tanggap bencana
4 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (social-culture) terhadap attitude
5 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (social-culture) terhadap
subjective norm dalam perilaku tanggap bencana
6 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (social-culture) terhadap
perceived behavioral control dalam perilaku tanggap bencana
7 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (information) terhadap attitude
toward behavioral dalam perilaku tanggap bencana
8 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (information) terhadap
subjective norm dalam perilaku tanggap bencana
9 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (information) terhadap perceived
behavioral control dalam perilaku tanggap bencana
10 Menganalisis hubungan attitude toward behavioral terhadap intension dalam
perilaku tanggap bencana
11 Menganalisis hubungan subyektive norm terhadap intension dalam perilaku
tanggap bencana
12 Menganalisis hubungan perceived behavioral control terhadap intension
dalam perilaku tanggap bencana
13 Menganalisis hubungan perceived behavioral control terhadap perilaku
(behaviour) dalam perilaku tanggap bencana
14 Menganalisis hubungan intension terhadap perilaku (behaviour) tanggap
1.4Manfaat Penelitian 1.4.1 Teoritis
Hasil penyusunan model tindakan keperawatan tanggap bencana berbasis
Theory of Planned Behavior sebagai kerangka pemikiran dan rujukan dalam
pengembangan Ilmu Keperawatan pada tanggap bencana.
1.4.2 Praktis
Hasil penyusunan model ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan
ataupun masukan dalam upaya meningkatkan keilmuan perawat tanggap bencana
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Theory of Planned Behavior
Teori Perilaku yang direncanakan (Theory of Planned Behavior) yang
disingkat dengan TPB pertama kali di usulkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985
melalui artikelnya “from intension to behaviour”, teori ini merupakan
pengembangan lebih lanjut dari TRA (Theory Reaction Action) yang di usulkan
bersama oleh Martin Fisbein dan Icek Ajzen pada tahun1980. Seperti pada teori
TRA, faktor inti dari TPB adalah niat individu dalam melakukan perilaku tertentu.
Niat diasumsikan sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku.
Secara umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam perilaku maka semakin
besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan (Ajzen, 1991).
Ajzen (1991) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu
persepsi terhadap pengendalian yang dapat dilakukan (perceived behavioral
control). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang
dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain,
dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh
sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol
yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol
Gambar 2.1 The Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005),
Theory of Planned Behavior mempunyai dasar pendekatan beliefs yang
membentuk niat (intention) dan mendorong individu untuk menampilkan atau
melakukan suatu perilaku tertentu. Beliefs dipengaruhi oleh beberapa faktor latar
belakang individu, antara lain yaitu faktor personal yang meliputi (nilai, emosi,
dan kognisi), faktor sosial yang meliputi (usia, jenis kelamin, ras, budaya,
pendapatan, dan agama), serta faktor referensi/informasi yang meliputi
(pengetahuan, pengalaman, dan media) (Ajzen, 2005)
Theory of Planned Behavior (TPB) menyampaikan bahwa perilaku yang
ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi/niat untuk berperilaku.
1) behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu
perilaku (beliefs strength) dan evaluasi atas hasil tersebut (outcome
evaluation)
2) normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain
(normative beliefs) dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut
(motivation to comply)
3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control
beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung
dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Hambatan
yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari
dalam diri sendiri maupun dari lingkungan .
Secara berurutan, behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku
positif atau negatif, normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang
dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subjektif (subjective norm)
dan control beliefs menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol
perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002) dalam (Nursalam, 2015).
2.1.1 Intensi
Dikutip dari (Nursalam, 2015), Ajzen (1988, 1991) mengungkapkan
bahwa intensi merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan
mencoba suatu perilaku, dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk
melakukan sebuah perilaku. Selain itu intensi (niat) dapat di definisikan sebagai
seseorang berperilaku karena faktor keinginan, kesengajaan atau karena memang
sudah direncanakan. Niat berperilaku (behavioral intention) masih merupakan
suatu keinginan atau rencana. Dalam hal ini, niat belum merupakan perilaku,
sedangkan perilaku (behavior) adalah tindakan nyata yang dilakukan.
Intensi merupakan faktor motivasional yang memiliki pengaruh pada
perilaku, sehingga orang dapat mengharapkan orang lain berbuat sesuatu
berdasarkan intensinya (Ajzen 1988, 1991). Pada umumnya, intensi memiliki
korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh karena itu dapat digunakan untuk
meramalkan perilaku.
Menurut Fishbein dan Ajzen (1985), intensi diukur dengan sebuah
prosedur yang menempatkan subjek di suatu dimensi probabilitas subjektif yang
melibatkan suatu hubungan antara dirinya dengan tindakan. Menurut Theory of
Planned Behavior, intensi memiliki 3 determinan, yaitu: sikap, norma subjektif,
dan kendala-perilaku-yang-dipersepsikan (Ajzen, 1988). Pengukuran intensi dapat
digolongkan ke dalam pengukuran belief. Sebagaimana pengukuran belief,
pengukuran intensi terdiri atas 2 hal, yaitu pengukuran isi (content) dan kekuatan
(strength). Isi dari intensi diwakili oleh jenis tingkah laku yang akan diukur,
sedangkan kekuatan responsnya dilihat dari rating jawaban yang diberikan
responsden pada pilihan skala yang tersedia. Contoh pilihan skalanya adalah
mungkin-tidak mungkin dan setuju-tidak setuju.
2.1.2 Sikap (Attitude toward behavioral)
Dikutip dari (Nursalam, 2015), menurut Ajzen (2005) sikap merupakan
besarnya perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek (favorable) atau
dan Chaiken (1993) dalam Aiken (2002) mendefinisikan sikap sebagai
kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi suatu
identitas dalam derajat suka dan tidak suka. Sikap dipandang sebagai sesuatu yang
afektif atau evaluatif. Konsep sentral yang menentukan sikap adalah belief.
Menurut Fishbein dan Ajzen (1985), belief merepresentasikan pengetahuan yang
dimiliki seseorang terhadap suatu objek, di mana belief menghubungkan suatu
objek dengan beberapa atribut. Kekuatan hubungan ini diukur dengan prosedur
yang menempatkan seseorang dalam dimensi probabilitas subjektif yang
melibatkan objek dengan atribut terkait. Menurut Fishbein dan Ajzen (1985),
sikap seseorang terhadap suatu objek sikap dapat diestimasikan dengan
menjumlahkan hasil kali antara evaluasi terhadap atribut yang diasosiasikan pada
objek sikap (belief evaluation) dengan probabilitas subjektifnya bahwa suatu
objek memiliki atau tidak memiliki atribut tersebut (behavioral belief). Atau
dengan kata lain, dalam theory of planned behavior sikap yang dimiliki seseorang
terhadap suatu tingkah laku dilandasi oleh belief seseorang terhadap konsekuensi
(outcome) yang akan dihasilkan jika tingkah laku tersebut dilakukan (outcome
evaluation) dan kekuatan terhadap belief tersebut (belief strength). Belief adalah
pernyataan subjektif seseorang yang menyangkut aspek-aspek yang dapat
dibedakan tentang dunianya, yang sesuai dengan pemahaman tentang diri dan
lingkungannnya (Ajzen, 2005).
Dikaitkan dengan sikap, belief mempunyai tingkatan atau kekuatan yang
berbeda beda, yang disebut dengan belief strength. Kekuatan ini berbeda-beda
pada setiap orang dan kuat lemahnya belief ditentukan berdasarkan persepsi
(Fishbein & Ajzen, 1975). Sebagai salah satu komponen dalam rumusan intensi,
sikap terdiri atas belief dan evaluasi belief Fishbein & Ajzen, 1975 dalam Ismail
& Zain, 2008), seperti rumus berikut ini:
Berdasarkan rumus di atas, sikap terhadap perilaku tertentu (AB)
didapatkan dari penjumlahan hasil kali antara kekuatan belief terhadap outcome
yang dihasilkan (bi) dengan evaluasi terhadap outcome (ei). Dengan kata lain,
seseorang yang percaya bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan sebuah
outcome yang positif, maka ia akan memiliki sikap yang positif. Begitu juga
sebaliknya, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan suatu
tingkah laku akan menghasilkan outcome yang negatif, maka seseorang tersebut
juga akan memiliki sikap yang negative terhadap perilaku tersebut.
Pengukuran sikap tidak bisa didapatkan melalui pengamatan langsung,
melainkan harus melalui pengukuran respons. Pengukuran sikap ini didapatkan
dari interaksi antara belief content- outcome evaluation dan belief strength. Belief
seseorang mengenai suatu objek atau tindakan dapat dimunculkan dalam format
respons bebas dengan cara meminta subjek untuk menuliskan karakteristik,
kualitas dan atribut dari objek atau konsekuensi tingkah laku tertentu. Fishbein &
Ajzen menyebutnya dengan proses elisitasi. Elisitasi digunakan untuk
menentukan belief utama (salient belief ) yang akan digunakan dalam penyusunan
2.1.3 Subjective Norm
Dikutip dari (Nursalam, 2015), Norma subjektif merupakan kepercayaan
seseorang mengenai persetujuan orang lain terhadap suatu tindakan (Ajzen, 1988),
atau persepsi individu tentang apakah orang lain akan mendukung atau tidak
terwujudnya tindakan tersebut. Norma subjektif adalah pihak-pihak yang
dianggap berperan dalam perilaku seseorang dan memiliki harapan pada orang
tersebut, dan sejauh mana keinginan untuk memenuhi harapan tersebut. Jadi,
dengan kata lain bahwa norma subjektif adalah produk dari persepsi individu
tentang belief yang dimiliki orang lain. Orang lain tersebut disebut referent, dan
dapat merupakan orang tua, sahabat, atau orang yang dianggap ahli atau penting.
Terdapat dua faktor yang memengaruhi norma subjektif: normative belief, yaitu
keyakinan individu bahwa referent berpikir ia harus atau harus tidak melakukan
suatu perilaku dan motivation to comply, yaitu motivasi individu untuk memenuhi
norma dari referent tersebut.
Rumusan norma subjektif pada intensi perilaku tertentu, dirumuskan
sebagai berikut (Fishbein & Ajzen, 1975):
Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa norma subjektif
adalah persepsi seseorang terhadap orang-orang yang dianggap penting bagi
dirinya untuk berperilaku atau tidak berperilaku tertentu, dan sejauhmana
umum dapat ditentukan oleh harapan spesifik yang dipersepsikan seseorang, yang
merupakan referensi (anjuran) dari orang-orang yang di sekitarnya dan oleh
motivasi untuk mengikuti referensi atau anjuran tersebut.
Berdasarkan rumus di atas, norma subjektif (SN) didapatkan dari hasil
penjumlahan hasil kali normative belief tentang tingkah laku i (bi) dan dengan
motivation to comply/ motivasi untuk mengikutinya (mi). Dengan kata lain bahwa,
seseorang yang yang memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok yang
cukup berpengaruh terhadapnya (referent) akan mendukung ia untuk melakukan
tingkah laku tersebut, maka hal ini akan menjadi tekanan sosial untuk seseorang
tersebut melakukannya. Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa orang lain yang
berpengaruh padanya tidak mendukung tingkah laku tersebut, maka hal ini
menyebabkan ia memiliki norma subjektif untuk tidak melakukannya.
Pengukuran norma subjektif sesuai dengan antesedennya, yaitu
berdasarkan 2 skala: normative belief dan motivation to comply. Maka
pengukurannya juga diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian keduanya. Norma
subjektif sama halnya dengan sikap, belief tentang pihak-pihak yang mendukung
atau tidak mendukung didapatkan dari hasil elisitasi untuk menentukan belief
utamanya.
2.1.4 Precieved Behavioral Control
Dikutip dari (Nursalam, 2015), kendali-perilaku-yang-dipersepsikan
(perceived behavior control) merupakan persepsi terhadap mudah atau sulitnya
sebuah perilaku dapat dilaksanakan. Variabel ini diasumsikan merefleksikan
pengalaman masa lalu, dan mengantisipasi halangan yang mungkin terjadi
tentang kemudahan atau kesulitan untuk berperilaku tertentu. Terdapat dua
asumsi mengenai kendali perilaku yang dipersepsikan. Pertama, kendali perilaku
yang dipersepsikan diasumsikan memiliki pengaruh motivasional terhadap
intensi. Individu yang meyakini bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk
berperilaku, tidak akan memiliki intensi yang kuat, meskipun ia bersikap positif,
dan didukung oleh referents (orang-orang di sekitarnya) (Ajzen 1988). Kedua,
kendali-perilaku yang-dipersepsikan memiliki kemungkinan untuk memengaruhi
perilaku secara langsung, tanpa melalui intensi, karena ia merupakan substitusi
parsial dari pengukuran terhadap kendali aktual (Ajzen, 1988).
Perceived behavioral control sama dengan kedua faktor sebelumnya yaitu
dipengaruhi juga oleh beliefs. beliefs yang dimaksud adalah tentang ada/ hadir
dan tidaknya faktor yang menghambat atau mendukung performa tingkah laku
(control belief ). Berikut adalah rumus yang menghubungkan antara perceived
behavioral control dan control belief:
Kendali perilaku yang dipersepsikan/PBC didapat dengan menjumlahkan
hasil kali antara keyakinan mengenai mudah atau sulitnya suatu perilaku
dilakukan (control belief) dan kekuatan faktor i dalam memfasilitasi atau
menghambat tingkah laku (power belief). Dengan kata lain, semakin besar
persepsi seseorang mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki (faktor
semakin besar perceived behavioral control yang dimiliki seseorang. Pengukuran
perceived behavioral control yang dapat dilakukan hanyalah mengukur persepsi
individu yang bersangkutan terhadap kontrol yang ia miliki terhadap beberapa
faktor penghambat atau pendukung tersebut. Beberapa faktor yang dipersepsi
sebagai penghambat atau pendorong tersebut didapatkan dari proses elisitasi untuk
mendapatkan belief yang utama.
2.1.5 Variabel Lain yang Mempengaruhi
Dikutip dari (Nursalam, 2015), menurut Ajzen, 2005 dalam Ramadhani,
2009 bahwa variabel lain yang memengaruhi intensi selain beberapa faktor utama
tersebut (sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan PBC), yaitu variabel yang
memengaruhi atau berhubungan dengan belief. Beberapa variabel tersebut dapat
dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1. Faktor personal
Faktor personal adalah sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat
kepribadian (personality traits), nilai hidup (values), emosi, dan
kecerdasan yang dimilikinya.
2. Faktor sosial
Faktor sosial antara lain adalah usia, jenis kelamin (gender), etnis,
pendidikan, penghasilan, dan agama.
a) Usia
Secara fisiologi pertumbuhan dan perkembangan seseorang dapat
digambarkan dengan pertambahan usia. Pertambahan usia
diharapkan terjadi pertambahan kemampuan motorik sesuai dengan
seseorang pada titik tertentu akan mengalami kemunduran akibat
faktor degeneratif. Umur adalah rentang kehidupan yang diukur
dengan tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 tahun
sampai 40 tahun, dewasa madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa
lanjut > 60 tahun. Umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang
dihitung sejak dilahirkan. Usia yang lebih tua umumnya lebih
bertanggung jawab dan lebih teliti dibanding usia yang lebih muda.
Hal ini terjadi kemungkinan karena yang lebih muda kurang
berpengalaman. Menurut umur/usia berkaitan erat dengan tingkat
kedewasaan atau maturitas seseorang. Kedewasaan adalah tingkat
kedewasaan teknis dalam menjalankan tugas-tugas, maupun
kedewasaan psikologis. Azjen (2005) menyampaikan bahwa pekerja
usia 20-30 tahun mempunyai motivasi kerja relatif lebih rendah
dibandingkan pekerja yang lebih tua, karena pekerja yang lebih
muda belum berdasar pada landasan realitas, sehingga pekerja muda
lebih sering mengalami kekecewaan dalam bekerja. Hal ini dapat
menyebabkan rendahnya kinerja dan kepuasan kerja, semakin lanjut
usia seseorang maka semakin meningkat pula kedewasaan teknisnya,
serta kedewasaan psikologisnya yang akan menunjukkan
kematangan jiwanya. Usia semakin lanjut akan meningkatkan pula
kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, mengendalikan
emosi, berpikir rasional, dan toleransi terhadap pandangan orang lain
b) Jenis Kelamin
Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua
jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat
pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin
laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar
berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki
jakun (adam’s apple) dan memproduksi sperma. Sedangkan
perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk
melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai
alat menyusui.
c) Pendidikan
Azjen (2006) menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan
seseorang akan memengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhannya
sesuai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda
yang pada akhirnya memengaruhi motivasi kerja seseorang. Dengan
kata lain bahwa pekerja yang mempunyai latar belakang pendidikan
tinggi akan mewujudkan motivasi kerja yang berbeda dengan
pekerja yang berlatar belakang pendidikan rendah. Latar belakang
pendidikan memengaruhi motivasi kerja seseorang. Pekerja yang
berpendidian tinggi memiliki motivasi yang lebih baik karena telah
memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dibandingkan
dengan pekerja yang memiliki pendidikan yang rendah. Menurut
seseorang akan dapat meningkatkan kematangan intelektual
sehingga dapat membuat keputusan dalam bertindak.
3. Faktor informasi
Faktor informasi adalah pengalaman, pengetahuan dan ekspose pada
media. Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi
setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.
Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar
pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang
lain, media massa maupun lingkungan.
Variabel-variabel dalam background factor ini memengaruhi belief dan
pada akhirnya berpengaruh juga pada intensi dan tingkah laku. Keberadaan faktor
tambahan ini memang masih menjadi pertanyaan empiris mengenai seberapa jauh
pengaruhnya terhadap belief, intensi dan tingkah laku. Namun, faktor ini pada
dasarnya tidak menjadi bagian dari TPB (Theory Planned Behaviour) yang
dikemukakan oleh Ajzen, melainkan hanya sebagai pelengkap untuk menjelaskan
lebih dalam determinan tingkah laku manusia
2. 2 Perilaku
Perilaku adalah kumpulan reaksi, perbuatan, aktifitas, gabungan gerakan,
tanggapan, atau jawaban yang dilakukan seseorang seperti proses berpikir,
bekerja, hubungan seks, dan sebagainya. Notoatmodjo (1992) mendefenisikan
perilaku sebagai totalitas dari penghayatan dan aktivitas yang memengaruhi
totalitas respon, semua respon juga sangat tergantung pada karakteristik
seseorang (Pieter and Lubis, 2010).
Menurut (Notoatmodjo, 2010) perilaku merupakan hasil hubungan antara
perangsang (stimulus) dan tanggapan (respon) dan respons. Perilaku kesehatan
adalah suatu respon seseorang (organisme) terhadap stimulus yang berkaitan
dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta
lingkungan.
2.2.1 Faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku
Menurut (Pieter and Lubis, 2010), perilaku dipengaruhi oleh lima faktor
antara lain :
1. Emosi
Emosi adalah reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau
perubahan-perubahan secara mendalam dan hasil pengalaman dari
rangsangan eksternal dan keadaan fisiologis. Emosi menyebabkan seseorang
terangsang untuk memahami objek atau perubahan yang disadari sehingga
memungkinkannya untuk mengubah sikap atau perilakunya. Bentuk-bentuk
emosi yang berhubungan dengan perubahan perilaku yaitu rasa marah,
gembira, bahagia, sedih, cemas, takut, benci, dan sebagainya.
2. Persepsi
Persepsi adalah pengalaman-pengalaman yang dihasilkan melalui indra
penglihatan, pendengaran, penciuman. Persepsi seseorang mampu
3. Motivasi
Hasil motivasi akan diwujudkan dalam bentuk perilaku, karena dengan
motivasi individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan fisiologis,
psikologis dan sosial.
4. Belajar
Belajar adalah salah satu dasar memahami perilaku manusia, karena belajar
berkaitan dengan kematangan dan perkembangan fisik, emosi, motivasi,
perilaku sosial dan kepribadian. Melalui belajar orang mampu mengubah
perilaku dari perilaku sebelumnya dan menampilkan kemampuannya sesuai
kebutuhannya.
5. Inteligensi
Inteligensi adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap
situasi-situasi baru secara cepat dan efektif serta memahami berbagai
interkonektif dan belajar dengan menggunakan konsep-konsep abstrak
secara efektif.
Menurut pendapat (Green, 2005) kesehatan seseorang dipengaruhi oleh
faktor perilaku (behavior causes) dan faktor di luar perilaku (non behavior
causes). Perilaku kesehatan ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yaitu :
1. Faktor Predisposisi (Predisposing faktor)
Terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, status
social dan nilai-nilai.
Faktor pendukung meliputi tersedianya atau tidak tersedianya fasilitas
kesehatan/ sarana-sarana kesehatan misalnya:. Puskesmas, obat-obatan
dan jamban.
3. Faktor Pendorong (reinforcing faktor)
Terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain
yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.
Perilaku adalah sesuatu yang kompleks yang merupakan resultan dari
berbagai macam aspek internal maupun eksternal, psikologis maupun fisik.
Perilaku tidak berdiri sendiri dan selalu berkaitan dengan faktor-faktor lain.
Pengaruhnya terhadap status kesehatan dapat langsung maupun tidak langsung.
2.2.2 Domain Perilaku Kesehatan
(Bloom, 1908) dalam (Notoatmodjo, 2010) membagi perilaku dalam tiga
domain/ranah yaitu: pengetahuan, sikap dan tindakan/ praktik. Dalam
perkembangan selanjutnya para ahli pendidikan dan untuk kepentingan hasil
pendidikan, ketiga domain ini dapat diukur dari :
1. Pengetahuan
Pengetahuan yang merupakan domain yang sangat penting untuk
terjadinya tindakan merupakan hasil dari “tahu” dimana terjadinya
setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu,
misalnya: pengetahuan tentang materi pembelajaran yang diberikan
oleh narasumber. Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif
a. Tahu (know)
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya, termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah
mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh
bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.
b. Memahami (comprehension)
Memahami diartikan sebgai suatu kemampuan menjelaskan secara
benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi
materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek
atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh,
menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang
dipelajari.
c. Aplikasi (application)
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi
yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).
Aplikasi di sasni dapat diartikan penggunaan hukum, rumus, metode,
prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
d. Analisis (analysis)
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau
suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam
suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama
e. Sintesis (shynthesis)
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan
yang baru. Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menyusun
formulasi baru dari formulasi-formulasi yang sudah ada.
Menurut Rogers (1974) dalam (Notoatmodjo, 2010), perilaku yang
didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak
didasari oleh pengetahuan. Proses pembentukan perilaku adalah sebagai berikut:
a. Awareness (kesadaran)
Orang menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap
stimulus.
b. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tertentu. Di
sinilah sikap objek mulai timbul.
c. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus
tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik
lagi.
d. Trial, subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa
yang dikehendaki oleh stimulus.
e. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan,
kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.
2. Sikap
Allport (1954) dalam (Notoatmodjo, 2010) menjelaskan bahwa
sikap itu mempunyai 3 komponen pokok, yakni: 1) Kepercayaan
emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek, 3)
Kecenderungan untuk bertindak (trend to behave). Ketiga komponen ini
secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total attitude). Sikap
terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:
a. Menerima (receiving)
Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan
stimulus yang diberikan (objek).
b. Merespon (responding)
Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan
tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Suatu usaha
untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan,
lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang menerima ide
tersebut.
c. Menghargai (valuing)
Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan
orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat
tiga.
d. Bertanggung jawab (responsible)
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan
segala risiko adalah sikap yang paling tinggi.
Menurut (Sarwono, 2012) sikap dapat dibentuk atau berubah melalui lima
a. Adopsi
Adopsi merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi
berulang dan terus-menerus dimana semakin lama akan diserap ke
dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap.
b. Eferensiasi
Berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman sejalan dengan
bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang terjadi dianggap sejenis,
sekarang dianggap lepas dari jenisnya. Objek tersebut dapat terbentuk
pula secara tersendiri.
c. Integrasi
Pembentukan sikap dapat terjadi secara bertahap, dimulai dengan
berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan hal tertentu.
d. Trauma
Trauma adalah suatu cara pembentukan atau perubahan sikap melalui
suatu kejadian secara tiba-tiba dan mengejutkan sehingga meninggalkan
kesan mendalam dalam diri individu tersebut. Kejadian tersebut akan
membentuk atau mengubah sikap individu terhadap kejadian sejenis.
e. Generalisasi
Generalisasi adalah suatu cara pembentukan atau perubahan sikap
karena pengalaman traumatik pada diri individu terhadap hal tertentu,
dapat menimbulkan sikap negatif terhadap semua hal yang sejenis atau
sebaliknya.
1. Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang
bersangkutan seperti selektifitas. Kita tidak dapat menangkap seluruh
rangsangan dari luar melalui persepsi, oleh karena kita harus memilih
rangsangan mana yang akan kita dekati, dan mana yang harus dijauhi.
Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan dalam diri.
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar manusia, yaitu: sifat
objek yang dijadikan sasaran sikap, kewibawaan orang yang menggunakan
suatu sikap, media komunikasi yang digunakan dalam penyampaian sikap,
dan situasi pada saat sikap terbentuk.
3. Praktik atau tindakan
Menurut (Sunaryo, 2004), suatu sikap pada diri individu belum tentu
terwujud dalam suatu tindakan. Agar sikap terwujud dalam perilaku nyata
diperlukan faktor pendukung (support) atau suatu kondisi yang
memungkinkan. Tingkatan praktik meliputi:
a. Persepsi (perception)
Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan
yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama.
b. Respon terpimpin (guided response)
Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai
c. Mekanisme (mechanism)
Individu dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau
sudah menjadi kebiasaan adalah indikator praktik tingkat tiga.
d. Adopsi (adoption)
Adopsi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dan dimodifiasi
dengan baik tanpa mengurangi kebenaran dari tindakan tersebut.
Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama pada orang dewasa dimulai
pada domain kognitif yang berarti bahwa subjek tahu terlebih dahulu terhadap
stimulus yang berupa materi atau objek di luarnya. Hal ini kan menimbulkan
respon batin dalam bentuk sikap subjek terhadap objek yang diketahui. Rangsang
yang telah diketahui dan disadari tersebut akan menimbulkan respon yang lebih
jauh lagi yaitu berupa tindakan terhadap atau sehubungan dengan stimulus.
2. 3 Defini Bencana
Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah suatu
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman
2.3.1 Jenis-Jenis Bencana
Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, antara
lain:
a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah longsor.
b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2010),
jenis-jenis bencana antara lain:
a. Gempa Bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan
dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.
Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke
seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat
menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat
menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya
tanah longsor, runtuhan batuan, dan kerusakan tanah lainnya yang merusak
berupa, kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat runtuhnya
bendungan maupun tanggul penahan lainnya.
b. Tsunami diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang
ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif
tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran.
Kecepatan tsunami yang naik ke daratan (run-up) berkurang menjadi
sekitar 25-100 Km/jam dan ketinggian air.
c. Letusan Gunung Berapi adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik
yang dikenal dengan istilah "erupsi". Hampir semua kegiatan gunung api
berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas
lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu
yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang
merupakan cairan pijar (magma). Magma akan mengintrusi batuan atau
tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi.
Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis
muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi apapun jenis
produk tersebut kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi
kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko merusak dan
mematikan.
d. Tanah Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau
batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng
akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng
tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada