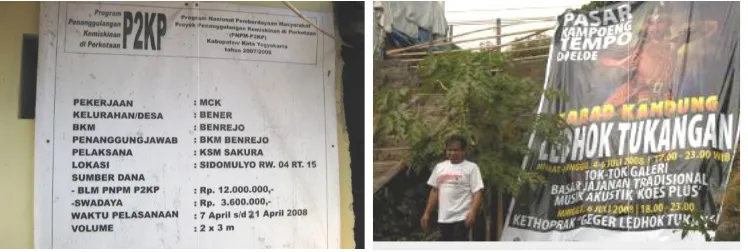STRATEGI MENCIPTAKAN KAMPUNG HALAMAN
(HOME) DI KALANGAN KAUM MISKIN KOTA
Studi Kaum Miskin Kota di RW 04, kampung Sidomulyo, Kricak, Kelurahan Bener, Yogyakarta.
Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta
Pembimbing: Dr. St. Sunardi Dr. G. Budi Subanar, SJ
Hagung Hendrawan NIM: 056322004
MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA
iv
Kampung Sidomulyo adalah salah satu dari beberapa kampung di
Yogyakrata dengan kategori kumuh. Pada tahun 1966 kebijakan pemerintah
Yogyakarta dalam wujud rasia gabungan membawa akibat pada sejumlah besar
gelandangan dan pengemis yang ada di pusat-pusat kota direlokasi pada sebuah
tanah tegalan di wilayah Karangrejo di Selatan Kampung Sidomulyo. Sejak saat
itu, sekitar 200 keluarga gelandangan dan pengemis tinggal di sana. Sampai
selanjutnya pada 1976 mereka diminta meninggalkan barak penampungan di
Karangrejo, dan untuk kemudian bersama-sama menempati lahan-lahan sewa di
sebelahnya, yang kini adalah bagian dari RW 04 Kampung Sidomulyo. Penelitian
ini tentang bagaimana pengalaman kaum miskin kota menciptakan dan
menghidupi sebuah gagasan tentang kampung halaman mereka yang baru di kota?
Bagaimana perasaan kerasan dan betah itu diupayakan dalam sebuah kondisi yang
senantiasa mengalami penolakan dan keterasingan?
Penelitian ini menjadi penting karena memberi sudut pandang yang
berbeda dari penelitian lain tentang kelompok miskin kota di Yogyakarta yang
jumlahnya tidak cukup banyak. Seperti misalnya, memberikan sudut pembacaan
yang kurang bersifat positivistik dibandingkan cara Clinard dan Lewis membaca
tentang kebudayaan mereka sebagai refleksi akan hadirnya sebuah kebudayaan
v
dari dosen pembimbing, Bapak Sunardi dan Romo G. Budi Subanar. Selain
mereka berdua, yaitu adalah rekan-rekan yang dulu pernah dan sampai kini masih
aktif dalam kegiatan di Yayasan Pondok Rakyat, seperti Tri dan Yoshi. Mereka
berdua telah membantu saya menemukan orientasi penelitian, serta sumbangsih
pada perolehan sumber-sumber literatur mengenai kampung di Yogyakarta.
Akhirnya, yang paling memberikan motivasi adalah istri dan kedua anakku:
Agnes, Wisang dan Bagas.
Kepada mereka semua saya ucapkan banyak terimakasih, dan kepada
mereka jugalah tesis ini saya persembahkan dengan segala kelebihan dan
kekurangan dalam penulisan. Bagi saya pribadi, tesis ini adalah pengalaman
menulis yang sangat menyenangkan, menegangkan, serta memberi sejuta
pengetahuan baru yang penting bagi kesadaran saya. Kajian budaya (cultural studies) itu menarik, dan harus!
Yogyakarta, 18 September 2009.
vi
penulisan tesis ini disebut sebagai “Kaum Miskin Kota”), yang bermukim di kampung-kampung di sepanjang bantaran kali di Yogyakarta, merupakan orang-orang yang terasing dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik kota. Keberadaan mereka sering dianggap sebagai sumber persoalan kota. Orang-orang ini sadar bahwa keberadaan mereka tidak pernah diterima di kota. Anehnya, banyak di antara mereka yang tidak ingin kembali ke desa asal, dan bahkan mengindentifikasikan kampung halaman (home) mereka justru di kota. Jika demikian halnya, bagaimanakah pengalaman orang-orang ini menghidupi gagasan tentang home mereka di kota? dan bagaimana pula cara kota mengasingkan mereka? Kedua hal inilah yang dipersoalkan dalam tesis ini. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pengalaman kaum miskin kota yang bermukim di kampung Sidomulyo di Yogyakarta.
Argumen yang dikembangkan dalam tesis ini yaitu, bahwa kaum miskin kota sesungguhnya merupakan sosok stranger, yang dekat secara fisik, tapi jauh secara sosial. Keberadaan mereka di kota dianggap sebagai ancaman, yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk penolakan, intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi oleh aparat negara dan juga oleh warga kota biasa. Selain berbagai aturan kebijakan dan program-program yang membatasi ruang gerak mereka, juga infrakstruktur fisik kota berikut fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya ibarat menara-menara panoptik yang berusaha menjauhkan orang-orang ini dari ranah-ranah publik di kota. Walaupun senantiasa dalam keadaan terasing, tidak berarti bahwa kelompok masyarakat marjinal ini menjadi pasif dan pasrah. Mereka senantiasa berusaha untuk kerasan dan betah, baik semasa dalam pengembaraan, maupun setelah menetap di sebuah kampung di kota. Seperti misalnya dengan cara membangun solidaritas dalam kelompok, berusaha mendapatkan status kependudukan legal, merubah fisik rumah dan kampung tempat tinggal, serta mengusahakan perijinan untuk menempati lahan-lahan yang menjadi hunian mereka. Pengalaman home yang lain barangkali berupa upaya mereka dalam mewujudkan relasi sosial yang hangat di dalam lingkungan keluarga. Selain itu, keterlibatan mereka dengan para aktivis dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak sipil kelompok ini, telah memberikan rasa aman dari tindakan represif aparat kota, bahkan telah menghasilkan peluang-peluang bagi mereka untuk memperdengarkan suaranya dan membela hak-hak sipil mereka sendiri.
vii KAMPUNG DAN PEMUKIMAN KUMUH DI YOGYAKARTA ... 20
A. Sejarah Kota Yogyakarta ... 22
B. Kampung di Yogyakarta ... 24
C. Kampung-kampung di bantaran kali ... 27
1. Lingkungan Fisik Pemukiman Bantaran Kali ... 31
2. Jenis Pekerjaan ... 32
3. Citra Hitam ... 33
4. Tingkatan Sosial ... 35
D. Perbaikan dan memudarnya citra hitam kampung ... 37
E. Kesimpulan ... 41
BAB III PEMUKIMAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI SIDOMULYO ... 43
A. Sejarah Kampung Sidomulyo ... 43
B. Lingkungan Fisik ... 49
C. Asal-Usul dan Pekerjaan Warga ... 56
D. Keseharian di Kampung ... 62
viii BAB IV
MENCIPTA KAMPUNG HALAMAN ... 77
A. Gelandangan sebagai the Object of Fear ... 78
1. Desa sebagai lingkungan yang asing ... 81
2. Kota yang memusuhi ... 83
3. Terasing dari ruang-ruang simbol modernitas kota ... 90
4. Pengalaman-pengalaman keterasingan ... 93
5. Bersedekah sebagai wujud dilema kota atas keberadaan kaum miskin kota ... 94
6. Kesimpulan ... 96
B. Mencipta Kampung Halaman di Kota ... 97
1. Kampung halaman semasa mengembara ... 98
2. Memperoleh Legalitas sebagai Warga Kota ... 102
3. Membangun Rumah dan Kampung ... 104
4. Keluarga sebagai Home ... 108
5. Aktivis dan Perorganisasian Massa ... 112
C. Narasi yang lain ... 114
1. Home dalam budaya bertahan hidup dan kekerasan ... 115
2. Sebuah pengalaman home yang mengambang ... 119
BAB V. PENUTUP ... 121
DAFTAR PUSTAKA
1
A. Latar Belakang
Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang
menghadapi persoalan urbanisasi. Arus urbanisasi dan ledakan penduduk di luar
kemampuan daya dukung kota, membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang
kota yang umumnya tidak menguntungkan kaum miskin kota yang marjinal.
Kaum miskin kota ini semakin terdesak ke daerah pinggiran kota, ke
perkampungan kumuh, dan atau menduduki wilayah kosong untuk di huni.
Kampung dan pemukiman mereka biasanya tidak mempunyai fasilitas publik
seperti jalan atau air bersih yang memadai. Pemukiman mereka sangat padat,
kotor, dan semrawut. Kampung-kampung tempat tinggal mereka sering disebut
sebagai sumber persoalan Kota.
Kampung-kampung seperti Badran, Code, Kricak, Sidomulyo, Papringan,
Nggedangan, Tukangan dan Juminahan adalah contoh perkampungan yang
terletak di bantaran-bantaran kali di Yogyakarta. Perkampungan tersebut pernah,
dan masih dikategorikan sebagai kampung kumuh dan liar. Kampung-kampung
ini menjadi tempat tinggal kaum miskin kota seperti gelandangan, pengemis,
anak-anak jalanan dan waria yang datang ke Yogyakarta untuk mencari
penghidupan yang lebih baik ketimbang kehidupan mereka terdahulu di desa asal.
Selain bermukim di perkampungan semacam itu, kaum miskin kota yang lain juga
membangun gubuk-gubuk hunian mereka di sepanjang lintasan rel kereta api.
kereta api yang sudah tidak beroperasi1. Sebagian hunian lainnya dapat dapat
dijumpai di sudut-sudut belakang pasar.
Pemukiman-pemukiman kaum miskin kota semacam ini lekat dengan citra
hitam karena cara hidup penghuninya yang dipandang tidak sesuai dengan aturan
dan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Profesi mereka
secara sosial dianggap rendah, seperti sebagai pemulung, penarik becak,
pengamen. Selain dianggap rendah, orang-orang di permukiman kumuh juga
dianggap mempunyai profesi yang lekat dengan persoalan moralitas dan tindak
kejahatan seperti pencuri, penjudi, tukang pukul, gali, pekerja seks. Selain profesi
mereka yang dipandang rendah, wilayah tempat tinggal mereka yang ”tidak
lumrah”, gelap gulita di antara tanaman perdu dan ilalang yang tinggi dengan
rumah-rumah seadanya yang berdiri di atas tanah-tanah bekas kuburan semakin
memperburuk citra penghuninya. Gubuk-gubuk tempat tinggal mereka kerap
dianggap sebagai tempat persembunyian para pencuri, tempat berjudi, dan juga
praktik-praktik prostitusi. Keadaan ini semakin melengkapi dan menegaskan
anggapan bahwa kampung-kampung seperti ini adalah kampung tempat tinggal
orang-orang tidak baik.
Perkampungan kumuh dan liar ini jumlahnya tidak menyusut, melainkan
terus bertambah dan menyebar dari pusat-pusat kota sampai ke wilayah pinggiran.
Rumah-rumah yang baru bertambah banyak dari hari ke hari, dan rumah-rumah
yang lama disewakan dan diperjual belikan kepada pendatang-pendatang yang
1
baru. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan fisik kota,
rumah-rumah liar yang dahulu gubuk, kini berubah menjadi lebih permanen, ada juga
yang dibangun bertingkat. Jalan-jalan dan ruang-ruang kampung ditata rapi, tidak
lagi kotor dan kumuh. Bantaran kali juga tidak gulita karena listrik sudah masuk.
Saluran air minum resmi juga tersedia sampai ke rumah-rumah. Beberapa
kampung bahkan berubah status dari ilegal menjadi legal, seperti misalnya Ledok
Code di Gondolayu yang kini secara resmi berada dalam wilayah kelurahan
Kotabaru. Walaupun demikian, anggapan sebagai kampung kumuh dan tempat
tinggal orang-orang ”tidak baik” sulit dihilangkan dari benak masyarakat
kebanyakan.
Sampai sekarang, diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum miskin kota
masih saja terjadi, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat pembaca di harian
Kedaulatan Rakyat tanggal 4 Juli 2002 berikut:
”.. Masyarakat dan pedagang Pasar Prambanan merasa resah dan gelisah dan menahan diri dengan keberadaan anak-anak jalanan yang tinggal di los pasar Prambanan sebagai rumah singgah. Kami heran kok bisa los pasar yang tadinya dibangun untuk menampung para pedagang buah yang tersebar di halaman pasar berubah fungsi menjadi rumah singgah. Adakah pejabat yang menerima upeti dari pengelola rumah singgah? Ulah anak jalanan yang memuakkan, bahkan berulangkali melakukan pencurian di sekitar pasar itu menunjukkan bahwa dana untuk mengelola rumah singgah anak jalanan menjadi sia-sia? Kami mohon pemerintah segera memindahkan rumah singgah dan dikembalikan sebagaimana fungsinya. Kami tidak ingin rumah singgah tersebut dipindah sendiri oleh masyarakat. Bila budaya menghakimi sendiri itu terjadi, tentu saja akan mengurangi wibawa pemerintah. Ibaratnya Pemda menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak”.2
2
Sebenarnya penghuni kampung kumuh secara sosial dan ekonomi tidak
homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang
beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat di pemukiman
kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan
ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. Kondisi hunian rumah dan
pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang
kurang mampu atau miskin. Frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam
penggunaan ruang-ruang yang ada mencerminkan kesemrawutan tata ruang dan
ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.3 Orang-orang yang menempati
pemukiman di sepanjang bantaran kali berbeda secara sosial, ekonomi, politik
dengan umumnya masyarakat di kota. Kategori-kategori budaya yang berkembang
diantara mereka barangkali pula berbeda dengan kebanyakan warga kota.
Keadaan mereka yang serba marjinal dan menempati pemukiman dengan label
ilegal, liar, dan kumuh disinyalir membawa pada bentuk kebudayaan yang
spesifik.
Penelitian ini bertujuan mengkaji pengalaman kelompok miskin kota
dalam upaya mereka menciptakan dan memaknai rumah tinggalnya. Dengan cara
apakah pengalaman home pada kelompok ini diupayakan dan dipelihara? Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengalaman home mereka dibandingkan kebanyakan warga kota?
Lokasi penelitian bertempat di RW 04 di kampung Sidomulyo, Kricak,
Kelurahan Bener, Yogyakarta. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena
3
orang-orang yang kini bermukim di kampung ini merupakan kaum miskin kota
yang dahulunya adalah gelandangan, pengemis, anak-anak jalanan dan waria di
Yogyakarta sebelum pindah dan menetap di kampung. Sebagian besar dari mereka
telah mendiami rumah-rumah di Sidomulyo selama lebih dari 40 tahun.
B. Permasalahan
Pokok persoalan dalam tesis ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian
pertama adalah bagaimanakah kota telah mengasingkan keberadaan kaum miskin
kota? dan pengalaman apakah yang dialami oleh kaum miskin sehubungan dengan
pengasingan oleh kota? Kedua, adalah apabila kota senantiasa mengasingkan
keberadaan mereka, lalu bagaimanakah perasaan betah kerasan dan betah
diciptakan dan dihidupi? atau bagaimanakah pengalaman kaum miskin kota
menghidupi gagasan tentang home mereka di kota yang telah mengasingkan keberadaan mereka?
C. Signifikansi penelitian
Pertama, tidak banyak penelitian mengenai pemukiman ilegal di kota-kota
di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Dengan demikian, kita dapat berkesimpulan
bahwa pemahaman kita akan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan
kelompok masyarakat marjinal ini dapat dikatakan masih kurang. Penelitian ini
diharapkan menambah pengetahuan kita tentang kehidupan masyarakat pada
hunian-hunian liar. Dengan demikian diharapkan dapat dipergunakan bagi para
Kedua, penelitian-penelitian terdahulu seperti Clinard4 dan Lewis5
menyimpulkan bahwa kebudayaan di kampung-kampung kumuh berbeda secara
tegas dengan kebudayaan warga kota kebanyakan. Guiness6, Khudori7 dan
Hasyim8 sedikit banyak sepakat bahwa ciri-ciri kebudayaan kemiskinan seperti
yang dipaparkan oleh Clinard memang sungguh ada pada warga di pemukiman
ilegal. Meski demikian, proses-proses perubahan dari kampung ilegal, hitam dan
kumuh menjadi kampung lumrah dan baik-baik tidak mendapat tempat oleh
penelitian-penelitian sebelumnya, dan bagaimana proses perubahan itu dijelaskan?
Simbol-simbol kebudayaan manakah yang ”digantikan?” dan digantikan dengan
simbol yang bagaimana? Bagaimanakah hybriditas kebudayaan yang terbentuk
karena persentuhan dengan kebudayaan kota?
Ketiga adalah peningkatan laju urbanisasi yang tinggi mengakibatkan apa
yang disebut dengan gejala urbanisation of poverty9, yaitu perpindahan penduduk desa mencari peruntungan di kota-kota besar, dan mengakibatkan terkonsentrasi
dan meluasnya penduduk miskin ke wilayah-wilayah perkotaan. Pemahaman akan
persoalan-persoalan hunian ilegal di kota-kota diharapkan berkontribusi pada
penyusunan kebijakan dan strategi kesiagaan untuk mengurangi gejala dan
dampak di masa mendatang.
4
Clinard Marshal B, “Slums and Community Develoment. Experiment in Self-Help”, New York, The Free Press, 1970
5
Lewis Oscar, “The Culture of Poverty”, Trans-Action I, November 1963 6
Guiness, Patrict. “Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung”, Singapore Oxford University Press, Oxford New York, 1986
7
Khudori, Darwis, ”Menuju Kampung Pemerdekaan. Membangun masyarkat Sipil dari Akar-akarnya. Belajar dari Romo Mangun di Kali Code”, Yayasan Pondok Rakyat, Yogyakarta 2002 8
Hasyim, Mustofa W, ”Kali Code: Pesan-pesan Api”, Yayasan Pondok Rakyat, Cetakan pertama, 2005
9
D. Tinjauan Pustaka
Budaya Kemiskinan mudah ditemui di daerah-daerah kumuh di seluruh
dunia, khususnya negara-negara berkembang. Mereka biasanya adalah para
gelandangan, pengemis, anak jalanan, asongan, pekerja seks komersial, dan pelaku
tindak kejahatan seperti pencopet dan pencuri. Mereka hadir di kota-kota besar, di
stasiun kereta api, terminal bis, pusat-pusat pertokoan, lokalisasi prostitusi, dan
belakang pasar. Orang-orang ini bermukim di gubuk-gubuk seadanya, dan
mendiami bilik-bilik sempit untuk ditempati beramai-ramai. Hunian-hunian liar
semacam ini, mudah dijumpai di sepanjang lintasan kereta api, tempat
pembuangan sampah, bawah jalan tol dan penyebrangan, sepanjang bibir-bibir
sungai, atau di kampung-kampung padat di belakang kawasan pertokoan. Kawasan
pemukiman mereka disebut sebagai sarang pertumbuhan kejahatan, perjudian, dan
kenakalan remaja, dan disebutkan bahwa orang-orang ini sulit keluar dari budaya
semacam itu. Seolah-olah budaya ini diwariskan oleh lingkungannya kepada
generasi-generasi selanjutnya. Inilah kurang lebih gambaran mengenai budaya
kemiskinan menurut Oscar Lewis10. Selanjutnya, Clinard menyebut ada tiga ciri
dominan pada pemukiman kumuh, yaitu perilaku yang menyimpang, budaya
pemukiman kumuh, serta apatisme dan keterasingan sosial 11.
Seperti Lewis, Clinard menunjukkan ciri perilaku menyimpang seperti
kejahatan dan kenakalan remaja, pelacuran, perjudian dan minuman keras mudah
dijumpai di pemukiman kumuh. Kebudayaan pemukiman kumuh kurang lebih
serupa dengan budaya kemiskinan, di mana pada pemukiman kumuh kehidupan
10
Darwis Khudori ,“Menuju Kampung Pemerdekaan”, hal. 117 11
berbentuk kelompok-kelompok, berpusat di suatu kawasan di mana mudah
ditemukan kawan, warung, dan tempat peminjaman uang. Tidak ada keterpisahaan
antara ruang privat dan publik. Kekacauan dan keributan antara penduduk jarang
reda, kehidupan diwarnai spontanitas, pergaulan yang lebih bebas, dan
pengalaman seksual lebih dini. Kekerasan lebih dihargai dibandingkan diplomasi,
dan toleransi yang tinggi terhadap kenakalan, kejahatan dan perilaku menyimpang
lainnya. Selain itu, ada semacam sikap penuh curiga dengan dunia luar, seperti
pegawai pemerintah, politisi, pekerja sosial, dan golongan orang kaya atau
menengah. Fasilitas umum tidak digunakan semestinya, dan cenderung dianggap
sebagai ancaman yang berasal dari orang luar. Pengangguran, keinginan
menabung rendah, termasuk ketiadaan cadangan makanan, dan biasanya hadir
praktik-praktik pegadaian dan lintah darat. Mengenai apatisme dan keterasingan
sosial, Clinard menyebutkan bahwa penghuni pemukiman kumuh turut
membatinkan kepada dirinya sendiri tentang apa yang dibatinkan oleh masyarakat
kebanyakan mengenai diri mereka. Masyarakat umum sering beranggapan bahwa
penampilan fisik dan kesulitan hidup orang-orang di pemukiman kumuh adalah
pencerminan dari ”inferioritas alami” (natural inferiority) mereka, atau singkatnya dianggap sebagai manusia rendah, atau mahluk yang rendah. Anggapan ini
mengakibatkan keterasingan mereka dari masyarakat luas, keterlemparan dari
partisipasi sosial, ekonomi dan politik perkotaan, dan tidak memungkinkan untuk
berkomunikasi atau memperdengarkan suaranya. Kenyataan ini secara
Pendapat Lewis dan Clinard menuai kritik bahwasannya kondisi
keterpurukan kelompok miskin kota tidaklah disebabkan oleh adanya ”budaya
kemiskinan” atau perilaku dan nilai yang hidup pada si miskin, melainkan oleh
adanya ketimpangan struktur dalam sistem sosial keseluruhan. Mangin, juga
McGee mengemukakan konsep alternatif mengenai ”petani di kota” yang melihat
bahwa kebanyakan kelompok miskin kota adalah petani yang hijrah ke kota, yang
berusaha mengintegrasikan atau mengadaptasikan kebudayaan desa dengan
kebudayaan kota. Dengan demikian dapat dijelaskan mengapa kelompok miskin
kota cenderung bekerja dalam sektor ekonomi informal ketimbang berada di
sektor formal. Hal ini lebih dikarenakan orang-orang desa yang bermigrasi ini
tidak mempunyai akses dan ketrampilan yang memadai untuk dapat berpartisipasi
ke dalam sektor ekonomi formal12. Gejala hadirnya pemukiman kumuh lebih
disebabkan masuknya ekonomi kapitalis ke pedesaan yang penduduknya padat,
dan secara struktural diperas oleh perkotaan. Seperti dalam revolusi hijau, yang
mengakibatkan ketergantungan pedesaan terhadap masukan dari luar.
Kongkritnya, petani-petani di desa tidak bisa mandiri lagi, mereka membutuhkan
traktor, bibit unggul, pestisida, mesin giling, pupuk, yang semuanya harus
didatangkan dari kota. Keadaan ini mengakibatkan matinya sistem produksi
pedesaan, dan pengangguran di desa-desa, yang pada gilirannya memaksa
perpindahan penduduk desa ke kota. Hanya kawasan-kawasan seperti di bantaran
12
kali, dan sepanjang rel kereta api yang dapat bersahabat dengan mereka, karena
untuk tinggal, tempat lain yang lebih baik tidaklah mungkin secara materi.
Pekerjaan-pekerjaan seperti penjaja makanan, asongan, tukang becak, pemulung,
adalah hal yang memang paling bisa dilakukan untuk bertahan hidup: sebuah
pekerjaan yang tidak perlu ketrampilan khusus dan perijinan yang resmi.
Keadaan ini mengungkapkan bahwa penghuni pemukiman kumuh itu
secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik berusaha berintegrasi dengan
kehidupan masyarakat kota, meski justru merugikan mereka. Secara sosial mereka
mempunyai teman, kelompok, dan juga berorganisasi. Mereka tidak berkehendak
kembali ke desa, bahkan mengidentifikasikan ”rumah”-nya adalah di kota bukan
di desa. Mereka berkehendak memperoleh pelayanan atau memanfaatkan fasilitas
dan kelembagaan kota, tetapi tidak diterima. Kehadiran mereka tidak diakui atau
ditolak. Mereka tidak dilayani oleh sistem birokrasi pemerintah, ditolak di
rumah-rumah-sakit, di institusi-institusi resmi orang kota.
Secara budaya, pemukim ini dipandang rendah, dilarang masuk ke
kampung-kampung ”resmi” saat memulung sampah, disebut-sebut sebagai sumber
kekerasan, kesemrawutan dan persoalan-persoalan moralitas kota. Secara
ekonomi, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan menyumbang pada
pertumbuhan ekonomi kota. Mengolah sampah, memasok barang mentah,
menghasilkan barang konsumsi murah, tetapi tidak dapat mengakses pinjaman
resmi, atau memperoleh pekerjaan formal. Mereka harus berusaha dengan
kekuatan sendiri agar bisa terus bertahan hidup. Orang-orang ini juga tidak apatis
oleh negara dan elit kota, seperti pada kasus-kasus penggusuran, razia preman, dan
pemenjaraan. Dapat disimpulkan bahwa, mereka berada di pemukiman kumuh
atau liar bukanlah disebabkan oleh adanya budaya kemiskinan melainkan karena
mereka dibuat sedemikian rupa oleh struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya
kota sehingga mereka miskin.
E. Kerangka Teoritis
Penjelasan tentang pemukiman kumuh dan liar yang ada selama ini
dibedakan dari dua sudut teori, yaitu teori marjinalitas dan teori ketergantungan13.
Teori marjinalitas melihat gejala pemukiman kumuh sebagai hasil dari
kepindahan penduduk di pedesaan ke perkotaan yang secara sosial, ekonomi,
budaya dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan kota. Secara sosial
penghuni pemukiman kumuh mengalami disorganisasi internal dan isolasi
ekternal. Secara budaya, mereka mengikuti pola hidup tradisional pedesaan dan
terkungkung dalam budaya kemiskinan sebagaimana diungkapan oleh Lewis dan
Clinard. Secara ekonomi, mereka hidup seperti parasit karena lebih banyak
menyerap sumber-sumber daya kota ketimbang menyumbang pada pertumbuhan
kota, boros, konsumtif dan cepat puas. Secara politik, mereka cenderung apatis,
dan enggan berpartisipasi dalam kehidupan politik, mudah terpengaruh oleh
gerakan-gerakan politik revolusioner karena kondisi frustasi mereka, disorganisasi
sosial dan ketidakpastian masa depan yang mereka alami.
13
Kebalikan dengan teori marjinalitas, teori ketergantungan memandang
bahwa kondisi keterpurukan kelompok miskin kota disebabkan oleh adanya
ketimpangan struktur dalam sistem sosial keseluruhan, atau singkatnya, teori ini
menyimpulkan bahwa penghuni di pemukiman kumuh merupakan sekelompok
masyarakat yang secara sosial ditolak, secara budaya dihina, secara ekonomi
diperas dan secara politik ditekan oleh struktur-struktur dominan masyarakat yang
ada. Mereka tinggal dan hidup di pemukiman kumuh bukan karena marjinal atau
berbudaya kemiskinan melainkan karena sistem sosial masyarakat luas memaksa
mereka menjadi marjinal.
Teori ketergantungan dipandang lebih mendekati kenyataan, dan lebih
membantu dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di perkotaan, dan lebih
khusus lagi persoalan pemukiman kumuh di kota. Berpedoman pada ini, persoalan
pemukiman kumuh berarti penyelesaian terhadap “akses” kelompok miskin kota
terhadap sistem sosial politik dan ekonomi, serta mengurangi dominasi
kebudayaan kemiskinan yang memenjarakan kelompok ini. Menurut Parwoto
(1985), akar penyelesaian pemukiman sesungguhnya tidak bertolak dari kondisi
fisik atau pemukiman tersebut, melainkan bermula dari cara pandang “pola dasar”
berpikir sebagai titik tolak untuk memilih, merumuskan dan mengembangkan
teori sebagai landasan definisi dan tindakan”14.
Selanjutnya cara-cara pandang yang ada, dalam praktiknya menghasilkan
dua jenis tindakan dalam penyelesaian persoalan pemukiman di perkotaan.
Kelompok cara pandang pertama (yaitu paradigma ekonomi, kesejahteraan, dan
14
penolakan, berikut cabang-cabangnya) memandang perumahan dari dua solusi
terpisah, yaitu perumahan atau hunian sebagai obyek, dan penghuni sebagai
subyek yang harus dilayani. Pemerintah dianggap sebagai satu-satunya lembaga
yang paling bertanggung-jawab sekaligus juga yang paling tepat dan mampu.
Sumber-sumber daya dikelola melalui sistem kontrol terpusat.
Kelompok kedua, yang diwakili oleh Paradigma Sumber Daya, melihat
pembangunan perumahan sebagai hubungan antara unsur-unsur pendapatan, harga
perumahan, biaya perumahan dan aset. Istilah aset mengacu kepada keseluruhan
sumberdaya yang dimiliki oleh penghuni, termasuk kependudukan, informasi,
tanah, dan lainnya. Dengan demikian pemerintah dipandang sebagai fasilitator
ketimbang pemrakarsa yang memberikan iklim kondusif bagi penghuni di
pemukiman kumuh untuk membangun perumahan mereka sendiri. Paradigma ini
membawa pada tindakan yang mendudukkan penghuni sebagai pelaku utama,
sedangkan tugas pemerintah dan industri lebih mendorong prakrasa mereka
sebagai titik tolak proyek pemukiman.
Paparan di atas menunjukkan bahwa kebudayaan pemukiman kumuh
benar-benar berlainan dengan kebudayaan warga kota dan kampung lumrah
kebanyakan. Hal yang justru membawa pada stigmatisasi bagi penghuni
pemukiman kumuh, berikut dampak-dampak lanjutannya, seperti misalnya
tindakan kekerasan oleh aparat negara dan oleh masyarakat biasa. Beberapa
penelitian mengungkapkan bahwa kebudayaan pemukiman kumuh tidaklah
berbeda secara tegas dengan kebudayaan masyarakat kota umumnya. Guiness,
atau kelas-kelas sosial, tetapi juga hidup gagasan mengenai kerukunan yang
menghasilkan ”harmoni”15. Dikatakan bahwa perkelahian antar warga kampung
jarang terjadi, dan kalaupun ada mudah diselesaikan. Di sana ada semacam
gagasan solidaritas antar penghuni ilegal, dan hadir berbagai saluran komunikasi
melalui berbagai jalur-jalur informal seperti misalnya profesi dan
paguyuban-paguyuban tukang becak, tukang parkir dan sebagainya16. Guiness dan Hasyim
sedikit banyak memberikan pandangan bahwa penghuni kampung ilegal tidaklah
berbeda secara tegas dengan warga kota kebanyakan.
Dalam perkembangannya, kampung Code di kelurahan Kotabaru
Yogyakarta merupakan salah satu kampung liar dan tidak baik, yang telah
mengalami perubahan secara fisik dan sosial, menjadi kampung legal dan
baik-baik. Di sana, ada perubahan simbol-simbol kebudayaan dari yang ilegal menjadi
legal, dari yang kumuh menjadi rapi. Pekerjaan-pekerjaan perbaikan tata-ruang
dan hunian-hunian warga di kampung Code oleh Romo Mangun (tahun
1983-1987) adalah salah satu contoh penggantian tanda kebudayaan dari yang kumuh,
liar, tidak teratur, menjadi tanda kebudayaan yang bersih, rapi, dan indah.
Dalam Postmodern ethic, Bauman berusaha memetakan berbagai pendekatan mengenai konsep stranger untuk menganalisis kebudayaan masyarakat modern. Stranger adalah bukan tetangga (neighbor), bukan pula sosok asing (aliens) tapi sekaligus merupakan keduanya. Mereka adalah sosok asing yang dekat secara fisik sekaligus tetangga yang jauh secara sosial17. Dia mengatakan
bahwa dalam masyarakat konsumsi, seorang stranger bisa menjadi daya tarik
15
Ibid., Guiness, Patrict. “Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung”, Bagian Kesimpulan. 16
Hasyim, Mustofa W. “Kali Code: Pesan-pesan Api” 17
karena perbedaan yang dimiliki, misalnya dalam turisme. Walaupun demikian,
stranger lebih banyak menciptakan kepanikan, atau oleh Bauman disebut sebagai obyek ketakutan (stranger as object of fear) yang senantiasa menciptakan perasaan terancam18. Kaum miskin kota barangkali merupakan sosok stranger
sebagaimana diutarakan oleh Bauman. Mereka ini dekat secara fisik tapi jauh
secara sosial, dan keberadaannya merangsang timbulnya kepanikan dan perasaan
terancam. Sehingga bisa dipahami, kenapa keberadaan mereka selalu diupayakan
untuk ditertibkan oleh aparat negara, misalnya dengan menerapkan berbagai
kebijakan dan program untuk mencegah kehadiran dan menertibkan keberadaan
miskin kota dari wilayah-wilayah publik di perkotaan. Seperti penerapan sejumlah
persyaratan untuk mendapatkan KTP (bagi yang sudah lama bermukim) dan
KIPEM (kartu Identitas Penduduk Musiman) bagi pendatang baru atau penduduk
sementara, membuat diskriminasi pelayanan bagi pendatang
sementara/non-permanen dan menindak serta memberikan sanksi bagi pelanggar administrasi
kependudukan19, termasuk pembangunan tempat-tempat penampungan
gelandangan dan pengemis, dan pembangunan rumah-rumah singgah untuk
anak-anak jalanan oleh Dinas Sosial.
Perasaan terancam oleh karena keberadaan kaum miskin kota juga terjadi
pada masyarakat biasa. Wujud dari perasaan terancam tersebut, berlanjut pada
bentuk penolakan yang dapat dengan mudah ditemui di gang-gang kampung,
seperti hadirnya papan bertuliskan ”pemulung dilarang masuk”. Perasaan terancam
18
Mike Featherstone, “Global culture: nationalism, globalization, and modernity : a Theory, Culture, & Society Special Issue”, SAGE Publication , 1990. Hal 143
19
oleh kehadiran kaum miskin kota ini dapat menghasilkan kepanikan yang meluas,
yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi suatu tindakan represif seperti razia,
penangkapan, dan pemulangan paksa. Barangkali pula oleh karena kaum miskin
kota adalah obyek ketakutan bagi simbol modernitas kota, maka citra hitam dan
stigma-stigma buruk atas keberadaan mereka di tengah masyarakat kota menjadi
langgeng.
Melihat kenyataan ini, barangkali rumah-tinggal (home) merupakan sebuah pengalaman yang traumatik20 sebagaimana banyak diberitakan oleh media-media
massa (khususnya televisi) ketika terjadi tindakan penggusuran oleh negara
terhadap pemukiman yang tidak memiliki ijin resmi.
Definisi home sendiri pada dasarnya tersusun atas sebuah dikotomi yang membatasi siapa orang-dalam (inside home) dan siapa orang-luar (outside home); pelanggaran atas batas-batas ini, menghadirkan kegelisahan bagi orang-dalam21.
Oleh sebab itu, selama hadir sebuah artikulasi atas sebuah gagasan atau visi
tentang home, maka akan selalu hadir sebuah sosok imajiner orang luar. Dalam wilayah domestik, artikulasi ini bisa berwujud dalam peningkatan sistem
keamanan hunian rumah tangga, membangun pagar tinggi, dan tembok-tembok
dengan kawat berduri atau pecahan-pecahan kaca. Selain itu, pengalaman home
selalu memiliki beberapa aspek akan hadirnya pengalaman memperoleh perasaan
aman, relasi yang hangat, dan kendali atas privasi dan properti. Hasil pengamatan
Hebdige terhadap kelompok pekerja kelas bawah di Inggris mengemukakan bahwa
20
David Morley, ”Home Territories: Media, Mobility, and Identity”, Routledge. Place of Publication: New York. Publication Year: 2000. Hal 27
21
konsep kewarganegaran tidak berakar pada ketersediaan ruang, melainkan
ditentukan oleh kepemilikan atas properti. Serupa dengan Hebdige, dalam
analisisnya tentang politik representatif homeless, Neil Smith mengatakan bahwa keberadaan mereka di ruang-ruang publik di kota sering kali berbenturan dengan
struktur kekuasaan yang senantiasa mengusahakan agar keberadaan mereka
dihapuskan dari wilayah publik – misalnya dipindahkan ke tempat penampungan
atau ke taman-taman kota, dipaksa meninggalkan gedung-gedung terlantar yang
dijadikan tempat tinggal mereka. Ada semacam upaya secara terus menerus untuk
menghapus kehadiran para homeless dari ruang-ruang publik di pusat-pusat kota. Lebih lanjut, Heller dan Vincent Descomber mengatakan bahwa gagasan tentang
home tidak (selalu) memerlukan kehadiran ruang fisik, melainkan sebagai ruang virtual (ruang yang dibayangkan), di mana seseorang yang berada dalam ruang
virtual itu merasa diterima tanpa banyak catatan kaki22.
F. Metodologi Penelitian
Pada awalnya penelitian dilakukan secara grounded research dengan cara melakukan penelitian partisipatoris berupa pengamatan di wilayah penelitian dan
berbicara dengan berbagai orang dari kaum miskin kota yang tinggal di
Sidomulyo. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti merumuskan pokok
persoalan tesis dan menyusun kerangka teoritis yang tepat untuk menjawab pokok
persoalan tersebut. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan cara menelusuri
informasi sekunder, diskusi-diskusi kelompok, observasi partisipatif dan
wawancara semi terstruktur. Berkenaan dengan siapa yang akan diwawancarai
22
akan dipilih individu-individu dari kelompok miskin kota, warga biasa, unsur
pemerintah, dan pekerja kemanusiaan. Observasi partisipatif, berarti peneliti akan
berkunjung di kampung-kampung, bertemu dan berbincang-bincang dengan
masyarakat, dan mengamati keseharian individu-individu dan kelompok tertentu.
G. Penyajian tesis
Bagian pertama dari penulisan tesis ini dimulai dengan gambaran singkat
mengenai bidang yang hendak diteliti baik secara obyektif dan juga subyektif;
meliputi latar belakang penelitian, masalah penelitian, metode dan signifikasi
penelitan. Dalam Bab pendahuluan dipaparkan pula secara ringkas mengenai
tema-tema dari hasil-hasil penelitian tentang bidang dan topik kajian serupa yang
telah dilakukan oleh penelitian-penelitian lain, dan dilanjutkan dengan pertanyaan
mengapa tema ini masih penting untuk diteliti. Bab ini juga memuat tentang
rumusan masalah yang hendak dikaji melalui penelitian ini, serta secara ringkas
menuliskan tentang Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis yang digunakan
dalam penelitian.
Bab II dari tesis ini merupakan latar belakang historis sebagai setting
empiris. Bagian ini menceritakan setting sosio historis kota Yogyakarta sebagai
wilayah di mana penelitian ini berlangsung. Pada Bab ini akan diulas secara
singkat mengenai sejarah kota Yogyakarta, dan selanjutnya mengenai
perkembangan kampung-kampung di Yogyakarta yang awal mulanya berangkat
pertumbuhan fisik dan ekonomi kota. Keberadaan kampung-kampung kumuh di
bantaran kali di Yogyakarta di bahas secara singkat yang meliputi lingkungan
fisiknya, asal usul dan jenis profesi penghuninya serta citra hitam yang melekat
padanya. Selanjutnya dipaparkan pula mengenai program-program perbaikan
kampung yang turut menyumbang pada memudarnya citra hitam
kampung-kampung seperti ini.
Bab III berupa deskripsi mengenai lingkungan fisik dan sosial di mana
kelompok sosial yang menjadi subyek penelitian ini bermukim, yaitu di RW 04,
Kampung Sidomulyo, Kricak, Kelurahan Bener, Yogyakarta. Pembahasan
meliputi sejarah kampung Sidomulyo yang terkait dengan keberadaan kelompok
miskin kota yang bermukim di Sidomulyo, perkembangan lingkungan fisik
kampung dan pemukiman. Dilanjutkan dengan deksripsi mengenai asal-usul dan
pekerjaan kelompok miskin kota di sana, serta keseharian di kampung dan
kategori sosial, tingkat ekonomi serta citra hitam yang melekat pada pada
pemukiman itu.
Bab IV yaitu analisis dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama membahasa
tentang miskin kota sebagai the object of fear, yaitu membahas tentang pengalaman keterasingan miskin kota. Bagian kedua yang menjadi pokok
permasalan dari tesis ini, membahas tentang pengalaman miskin kota memaknai
dan menciptakan kampung halaman (home) mereka sejak dalam masa pengembaraan dari kota ke kota, ataupun setelah mereka tinggal dan menetap di
Bab V adalah penutup, merupakan kesimpulan dari pokok yang
dipermasalahkan oleh penelitian ini, dan kemudian di lanjutkan dengan Daftar
20
Kehadiran pemukiman-pemukiman tidak resmi dan bercitra kumuh tidak
dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan sosial, ekonomi, politik kota,
khususnya kebijakan yang menyangkut tata kelola kota. Persoalan ini telah
menjadi isu penting pemerintah kolonial sejak tahun 1900, sebagaimana tertuang
dalam Mindere Welvaart Onderzoek (penelitian tentang penurunan tingkat kesejahteraan) bahwa pemerintah kolonial perlu segera melakukan
perbaikan-perbaikan atas persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh ledakan penduduk,
kehancuran akibat perang kemerdekaan dan pertikaian politik, serta gejala
urbanisasi di kota-kota di Jawa dan semakin akutnya kemiskinan di
wilayah-wilayah pedesaan.1
Kebijakan Politik Etis yang dilancarkan pada dua dekade pertama awal
abad ke-20 dianggap sebagai solusi utama menyangkut persoalan-persoalan
tersebut. Kebijakan ini menghasilkan berbagai program pendidikan, emigrasi,
irigasi, dan perbaikan kampung, kesehatan, pendirian lumbung desa, dan
pembangunan bank-bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, antara tahun
1900-1940-an, kota-kota kolonial atau kota-kota Indies berkembang sejalan dengan
pertumbuhan perekonomian pada sektor tertentu, seperti pertambangan,
perkebunan, perdagangan dan industri. Disinyalir bahwa perkembangan kota-kota
itu menjadi tempat kelahiran kaum urban baru yang terdiri dari kaum terpelajar,
1
birokrat atau priyayi, kaum profesional, kaum pengusaha dan pedagang dari
kalangan Bumi Putra atau Pribumi. Kota-kota kolonial itu antara lain adalah
Jakarta (Batavia), Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan
Makasar. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang begitu pesat tidak bisa lagi
diantisipasi lagi oleh daya dukung kota-kota kolonial ini secara layak.2
Ledakan penduduk yang terjadi di kota-kota kolonial yang bersifat
konsentrik, membawa dampak seperti diungkapkan dalam banyak studi antara
lain, P.J.M. Nas,3 dan Hartshorn4, bahwa tekanan arus urbanisasi yang melonjak
begitu cepat membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang kota yang pada
umumnya kurang menguntungkan kelompok masyarakat marjinal. Kelompok ini
semakin terdesak ke daerah pinggiran kota, ke pemukiman-pemukiman kumuh,
dan atau menduduki wilayah kosong untuk kemudian ditempati. Sering kali
mereka juga harus berpuas diri dengan berbagai fasilitas publik yang sangat
minim, jauh berbeda dengan warga kota yang secara ekonomi lebih maju.5
Pada bagian selanjutnya dari Bab ini, akan diuraikan mengenai pola
pengembangan kota Yogyakarta yang secara historis juga bersifat konsentrik dan
mengalami tekanan arus urbanisasi. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab
terdesaknya sebagian masyarakat ke daerah-daerah pemukiman yang kumuh.
2
Djoko Suryo, “Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990”, The 1st International Conference on Urban History Surabaya, August 23rd-25th 2004, hal 01
3
P.J.M. Nas, “Kota di Dunia Ketiga, Pengantar Sosiologi Kota”, (Bhratara Karya Aksara, 1984). 4
Asa Hartshorn, “Interpreting The City, An Urban Geography”, (John Wiley & Son, 1980). 5
A. Sejarah Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta berawal dari sebuah Kota Istana atau Kota Kraton
bernama Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak di daerah agraris pedalaman
Jawa dibangun pada 1756 oleh Sultan Hamengku Buwono I (Pangeran
Mangkubumi). Pendirian kota ini dilakukan setelah terjadi peristiwa Palihan
Nagari atau Pembagian Dua Kerajaan (Surakarta-Yogyakarta) pada 1755 sebagai
hasil Perjanjian Giyanti (Sunan Paku Buwono III dan Sultan Mangkubumi).
Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai yang pertama-tama merancang tata-kota
Yogyakarta. Ia sendiri yang memilih letak di mana pusat kerajaan akan didirikan,
yaitu pada sebuah wilayah dataran di antara Gunung Merapi di Utara dan Laut
Selatan serta diantara dua sungai (yaitu Winongo di Barat dan Code di Timur).
Kraton ini dikelilingi benteng yang berbentuk kurang lebih persegi dan
dihubungkan ke daerah-daerah lain melalui berbagai jalan besar seperti jalan besar
di bagian Utara Kraton sebagai poros kota (sekarang Jalan Malioboro), jalan yang
menghubungkan bagian Timur seperti ke Kotagede dan Imogiri tempat makam
raja-raja Mataram terdahulu. Pertumbuhan kota yang lebih pesat berlangsung pada
akhir abad ke 19 ketika dibangun jalan kereta api yang menghubungkan Yogya
dengan Surakarta dan Semarang (1872), lalu dengan Jawa Barat (1877). Seiring
dengan pertumbuhan dan pertambahan penduduk, beberapa prasarana kota mulai
dibangun seperti penerangan kota dengan lampu gas (1890), jaringan air minum
(1918), listrik (1921), diikuti dengan saluran-saluran pembuangan atau drainase.6
6
Pertumbuhan kota Yogyakarta selanjutnya banyak ditentukan oleh
pembangunan lembaga-lembaga pendidikan sejak akhir abad 19. Selama masa
pendudukan Jepang, semua sekolah Belanda diubah menjadi sekolah Indonesia.
Pertambahan penduduk dan sekolah-sekolah yang cepat terjadi pada masa revolusi
(1945-1950) ketika pemerintah dan badan-badan swasta ramai-ramai mendirikan
sekolah rakyat (sekolah dasar) dan menengah. Pada masa itu pula didirikan
universitas negeri yang pertama yaitu sekolah tinggi Islam yang kemudian
menjadi Institut Agama Islam Negeri yang kini menjadi Universitas Islam Negri
(1945), selanjutnya adalah Universitas Islam Indonesia sebagai universitas swasta
pertama di Indonesia (1948), dan Universitas Gadjah Mada (1949). Pada
masa-masa itu, Yogyakarta menjadi kota tujuan belajar bagi pemuda-pemuda dari
seluruh tanah air, dan memperoleh predikat, Kota Sepeda, karena para pelajar dan
mahasiswa umumnya naik sepeda pergi-pulang sekolah atau kuliah. Sejak masa
revolusi sampai tahun 1950-an dan 1960-an kota Yogyakarta juga menjadi pusat
kelahiran seniman dan karya-karya seni dari berbagai cabang seni, seperti seni
lukis, sastra, teater, patung, musik, dan banyak bermunculan sanggar-sanggar seni.
Seni pedalangan dan seni tari tradisional Jawa juga berkembang di kota ini, di
samping seni-seni modern. Tidak mengherankan apabila pada periode itu juga
kota Yogyakarta mendapat sebutan sebagai Kota Budaya. Selanjutnya pada masa
berikutnya ketika boom-turisme, Yogyakarta adalah salah satu kota tujuan wisata terpenting di Indonesia.7
7
Secara fisik kota Yogyakarta juga mengalami perluasan dari tahun ke
tahun. Antara tahun 1959-1996 terjadi perluasan fisik kota dari 1.885 ha menjadi
6.687 ha, dengan kecepatan pemekaran rata-rata 150 ha per tahun.8 Perluasan fisik
kota sejalan dengan kebutuhan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
tekanan akibat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Desa-desa di pinggir
kota mengalami proses pengkotaan, dan lahan-lahan yang dahulu sawah berubah
fungsi menjadi pertokoan dan hunian-hunian.9 Para pendatang yang datang
mencari peluang-peluang ekonomi bersedia tinggal di tempat-tempat yang sempit
dan padat karena ruang hunian dan pemukiman layak tidak terjangkau. Kelompok
masyarakat marjinal menempati lahan-lahan kosong di sepanjang rel kereta api, di
sekitar tempat pembuangan sampah, di belakang-belakang pasar, di sepanjang
aliran-aliran sungai. Trotoar pejalan kaki berbagi fungsi dengan ratusan penjual
makanan, bangunan-bangunan tidak berijin berdiri di tanah-tanah negara.
Kamar-kamar kos murah di pinggir kali penuh sesak dihuni.
B. Kampung di Yogyakarta
Sesuai dengan konsep kebudayaan tradisional Jawa, Kota Istana
Yogyakarta itu ditempatkan sebagai ibu kota negara kerajaan dan menjadi pusat
pemerintahan dan politik bagi wilayah kerajaannya, dengan sebutan sebagai
wilayah Negara Agung (Pusat Negara). Konsep dan struktur kerajaan semacam ini
berlangsung sejak masa kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung hingga masa
8
Agus Suryanto, “Perubahan Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 1959-1996”. Disertasi dalam Ilmu Geografi UGM, (2002), hlm. 346.
9
Kesultanan Yogyakarta.10 Pada awal perkembangannya pemukiman kota
Yogyakarta cenderung memusat di sekitar Kraton, di sebelah Selatan dan Utara.
Pemukiman tempat tinggal penduduk lambat laun tumbuh di sekitar poros yang
melintasi istana dari ujung Timur ke ujung Barat, dan kemudian alun-alun utara,
jalan Malioboro, hingga ke Tugu. Istana atau Kraton yang terletak di pusat kota
dikelilingi oleh bangunan benteng dan wilayah yang ada di dalamnya dikenal
sebagai daerah “Jero Beteng” (di dalam benteng), sedangkan di luar wilayah Jero
Beteng di sebuat dengan daerah “Jaba Beteng” (di luar benteng). Tempat-tempat
pemukiman di dalam dan di luar benteng, lazim diberi nama sesuai dengan
pekerjaan dari penduduk yang menempatinya, disesuaikan dengan nama
bangsawan sebagai penguasanya, atau asal-usul penduduknya. Seperti misalnya,
Kampung Kemitbumen menjadi tempat tinggal abdi dalem kemit bumi yang bertugas sebagai pembersih kraton, kampung Suryadiningratan merupakan daerah
kekuasaan Pangeran Suryadiningratan, atau kampung menduran dan bugisan
merupakan wilayah kediaman prajurit kraton yang berasal dari etnis Madura dan
etnis Bugis.11
Penduduk Bangsa Eropa dan bangsa asing lainnya pada umumnya bekerja
pada bidang-bidang birokrasi pemerintahan, keamanan, perkebunan, dan
leveransir kebutuhan hidup. Mereka tinggal di sekitar pemukiman masyarakat
Eropa di Loji Besar, Loji Kecil, Kota Baru, dan Sagan. Kelompok etnik orang
Arab dan Cina umumnya memiliki aktivitas di bidang perekonomian seperti
10
Otto Soemarwoto. “Towards Jogja, The Eco-City. The Regional Agenda 21 for Sustainable Tourism Development in the Special province of Yogyakarta”. Laporan Penelitian untuk Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Tanpa angka Tahun).
11
pedagang, pemungut cukai pasar, rumah gadai, rumah persewaan candu, serta
menjadi perantara antara orang Barat dan orang Bumi Putra. Mereka umumnya
tinggal di Pecinan, Sayidan, Kranggan, dan Loji kecil.12
Pecahnya Perang Dunia II dan datangnya Pemerintahan Pendudukan
Jepang pada 1942, telah membawa berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda dan
Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berlanjut dengan Revolusi Kemerdekaan
1945-1949. Perkembangan terakhir tersebut telah membawa kemunduran
penduduk bangsa Eropa di Kota Yogyakarta. Banyak orang-orang Belanda
kembali ke Negeri Belanda dan tidak kembali lagi ke Yogyakarta. Sebaliknya,
selama masa pendudukan Jepang 1942-1945 sejumlah orang Jepang datang dan
diam di kota Yogyakarta. Sementara itu pada masa pecah perang kemerdekaan,
banyak penduduk meninggalkan kota untuk mengamankan diri, sehingga dapat
diduga penduduk kota Yogyakarta berkurang. Akan tetapi, sebaliknya, selama
tahun 1945-1949 Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, dan banyak
pejabat pemerintahan dan tokoh-tokoh nasional dari Jakarta atau Jawa Barat hijrah
ke Yogyakarta. Baru setelah tahun 1950 kota Yogya berkembang ke segala arah,
seiring dengan perkembangan administrasi, komunikasi, transportasi, dan
pendidikan modern.
Selanjutnya, setelah tahun 1965 kawasan-kawasan pemukiman baru
bermunculan di luar pusat kota. Malioboro dan sekitarnya menjadi pusat
pertokoan dan hiburan yang ramai. Penduduk yang tergolong berpunya menjauhi
keramaian. Golongan berpenghasilan rendah dan yang lebih miskin berkumpul di
12
dekat keramaian, khususnya di bantaran kali dan rel kereta api yang melintasi
kota. Menurut ingatan dan penuturan warga, sebenarnya kehadiran kampung yang
pada masa sekarang dianggap kumuh dan liar ini, seperti misalnya Badran, sudah
mulai ada sejak masa kolonial. Konon (diceritakan dari mulut ke mulut) daerah
Badran termasuk dalam wilayah kekuasaan Pangeran Diponegoro, pada masa
Kasultanan Hamengkubuwono VII. Perang Diponegoro (1825-1830) disinyalir
sebagai salah satu akibat dari pembangunan rel kereta api oleh pemerintah
Kolonial tanpa seijin Pangeran Diponegoro. Pada masa keruh ini, seorang pamong
kesultanan menggadaikan tanah Bumijo kepada penduduk etnis Cina untuk
dijadikan daerah pemakaman, tapi tidak mendapat restu dan kemudian wilayah
pemakaman itu dialihkan di daerah Badran sebagai ganti tanah Bumijo. Maka
sejak saat itu sampai sekarang, Badran dikenal sebagai salah satu tempat
pemakaman etnis Cina di Yogyakarta. Dalam peta yang dikeluarkan oleh
pemerintah Kolonial pada tahun 1925 (jogjakarta en omstreken) terlihat bahwa daerah tersebut memang merupakan daerah pemakaman untuk etnis Cina dengan
beberapa pemukiman di tengahnya13.
C. Kampung-Kampung di Bantaran Kali
Penamaan kampung-kampung di bantaran kali atau sepanjang rel-rel tidak
berorientasi pada keberadaan Kraton. Kricak misalnya, menurut penuturan warga
berasal usul dari para pendatang yang bekerja sebagai pekerja pemecah batu kali
menjadi kerikil (batu kricak’an). Nama kampung Tungkak yang secara harafiah
13
berarti tumit, kadang disangkut-pautkan dengan kisah Ki Ageng Mangir, kadang
juga dikaitkan dengan kondisi penghuninya yang kebanyakan adalah gelandangan
dan pengemis sebagai kelompok masyarakat yang paling rendah secara sosial.14
Sumber tertulis tentang sejarah kehadiran pemukiman-pemukiman di bantaran kali
tidak banyak. Guiness menulis bahwa hingga tahun 60-an, hanya tepian Sungai
Code bagian hulu yang dihuni. Selebihnya, kedua tepi sungai dipadati oleh
tanaman liar. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi, beberapa
orang mulai tinggal di pinggir sungai di sebelah selatan jembatan Gondolayu.15
Guiness juga menyebutkan bahwa selama pergolakan di tahun 1940-an, penduduk
tepi sungai terus bertambah walaupun banyak juga penduduk yang meninggal
akibat kelaparan, sakit, dan perang. Jumlah ini terus bertambah bersamaan dengan
pindahnya pegawai sipil dan pegawai pemerintahan lain ke Yogyakarta ketika
kota ini menjadi ibukota Negara. Pemukiman tidak resmi di sepanjang bantaran
Kali Code antara lain Kampung Code Nggondolayu, Juminahan, Mergangsang,
dan Sayidan. Pemukiman di sepanjang Kali Winongo antara lain Ledok Jatimulyo,
Kricak Kidul, Sidomulyo, Ledok Badran. Sepanjang Kali Gadjahwong antara lain
Papringan, Nggedangan, dan Ledok di daerah Plumbon. Tetapi, tidak sedikit
pemukiman di sepanjang bantaran kali yang tidak memiliki “nama” resmi
sebagaimana kampung-kampung tersebut di atas, dan hanya berupa
bangunan-bangunan rumah semi permanen yang dihuni beberapa keluarga selama puluhan
tahun. Seperti misalnya di daerah Sapen, terdapat sebuah kampung yang berdiri
14
Mohammad Zamzam Fauzannafi, “Institusionalisasi Kampung Tungkak”, Jurnal Kampung, Yayasan Pondok Rakyat, tanpa tahun. Hal 57
15
di bibir tebing Kali Gadjahwong yang telah dihuni selama bertahun-tahun. Akses
masuk menuju ke pemukiman itu adalah sebuah pintu ukuran standar yang
dipasangkan pada tembok pagar keliling sebuah komplek perumahan yang telah
dilubangi.
Kebanyakan kampung dan pemukiman di bantaran kali memuat cerita
masa lalu yang mirip satu sama lainnya. Seperti misalnya sudah dihuni jauh
sebelum kemerdekaan, lalu kembali sepi ketika Peristiwa G30S, dan kembali
ramai dan memadat sejak tahun 70-an seiring dengan perkembangan infrastruktur
kota dan meningkatnya urbanisasi dari desa-desa dan wilayah di luar di
Yogyakarta. Lambat laun, rumah-rumah di bantaran kali disewakan dan atau
diperjual-belikan kepada pendatang yang baru. Bangunan fisik yang awalnya
berupa gubug seadanya perlahan-lahan mulai mengarah pada material bangunan
yang lebih bersifat permanen. Jalan-jalan kampung mulai diperbaiki, diperlebar
sedikit, kemudian diperkeras. Ketika listrik mulai masuk, pohon-pohon perdu,
ilalang, bambu-bambu besar yang rimbun dan tampak seram mulai memudar.
Asal-usul penghuninya pun beragam dan berbagi dalam aneka profesi dalam
pekerjaan-pekerjaan mencari penghidupan.
Kampung dan pemukiman di bantaran kali sebagian besar menempati
lahan-lahan yang disebut dengan istilah wedhikengser, yaitu daratan baru yang muncul akibat timbunan pasir (yang berasal dari gunung merapi) yang hanyut oleh
arus sungai selama ratusan tahun. Tanah wedhikengser ini sebenarnya tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundangan tanah nasional. Menurut penelitian
Pertanahan Kota Yo
leh negara yang pelaksanaannya dilakuka
Dijelaskan lebih lanjut, sebagai tanah negara, m
gser tanpa ijin berarti melanggar ketentuan un 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah
mikian, tanah-tanah wedhikengser ini dihuni o yang datang ke Yogyakarta, dan beberapa wila
hikengser dimiliki secara sah (dalam arti be di sana, misalnya tuan-tuan tanah di wilayah w
Pola Penguasaan dan Upaya Penataan Lingkangan Tana Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Yogyakarta” s Hukum Universitas Gadjah Mada, Mei 2002. Hal. 68
1. Lingkungan Fisik Pemukiman Bantaran Kali.
Proses pembangunan rumah-rumah di pemukiman sepanjang kali biasanya
dibangun oleh individu-individu dengan pertolongan keluarga, tetangga, dan
kerabat seturut dengan peluang-peluang atas ketersediaan lahan, kondisi
keuangan, kategori sosial, dan politik kota, tanpa didahului oleh sebuah blue-print
rancangan kampung secara utuh. Kepemilikan tanah dan bangunan sampai
sekarang tetap dalam kondisi “tidak resmi” dalam arti tidak mempunyai hak milik
atas lahan dan bangunan dari otoritas pemerintah. Rumah-rumah dan bangunan
didirikan dengan pola-pola yang tidak biasa (berbeda dengan model perumahan
atau pemukiman lumrah lainnya). Material bangunan tidak berat, berasal dari
bahan-bahan yang murah dan mudah diperoleh. Perbaikan atau pengembangan
hunian berkembang setiap saat tergantung pada keadaan atau perasaan aman
seperti merasa bebas dari penggusuran.
Rumah yang satu dengan yang lain dibangun berdekatan, kadang berbagi
dinding. Satu rumah bisa dihuni oleh beberapa keluarga. Setiap keluarga biasanya
mempunyai perabotan-perabotan dasar seperti perkakas untuk memasak, mencuci,
menyimpan, tempat untuk tidur, juga radio dan televisi. Di dalam kampung
banyak terdapat gang-gang (jalan kampung) di mana aktivitas keseharian dan
interaksi antar warga terjadi di sana. Ruang privat dan ruang publik kabur, tidak
tegas. Bagi penghuni kampung bantaran kali, sungai yang melintasi kampungnya
adalah anugrah, di mana berbagai aktivitas keseharian warga, industri rumahan,
2. Jenis Pekerjaan
Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja
di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor
informal.17 Pekerjaan-pekerjaan ini antara lain pemulung sampah, penarik becak,
Satpam, karyawan toko, cleaning service, tukang reparasi sepeda/ becak, tukang bangunan, kuli, penggali pasir, buruh cuci, pembantu rumah tangga, pengamen,
tukang reparasi radio, pedagang kecil, serabutan, warung kelontong18. Ada juga
yang berprofesi sebagai pengemis, meski amat jarang disebutkan. Dari
pengamatan Dharwis Khudori dan pengalaman penulis di kampung-kampung
semacam ini, sebagian besar penghuni bantaran Kali Code memperoleh
penghasilan dari hasil memulung sampah, baik laki-laki dan perempuan. Sampah
hasil pulungan disetorkan kepada pedagang atau juragan rosok. Sebagian
berprofesi sebagai penarik becak dengan cara menyewa dari juragan atau membeli
dengan cara mencicil. Para penarik becak ini mudah ditemui di sudut dan
pusat-pusat keramaian di Yogyakarta. Mereka biasanya pulang setiap malam, tapi tidak
sedikit yang menggunakan becaknya sebagai tempat beristirahat melepas malam.
Selain kedua profesi ini, kelompok terbesar lainnya adalah pekerjaan serabutan,
yakni bekerja apa saja, asal tidak perlu ketrampilan. Dahulu banyak dijumpai
tukang semir sepatu, kini pekerjaan serabutan misalnya sebagai tukang parkir,
penitipan sepeda motor, kuli, dan mengamen.19
17
Suparlan, Parsudi “Segi Sosial dan Ekonomi Pemukiman Kumuh”, tanpa tahun. hal 3 18
Diolah dari berbagai sumber baik tertulis dan hasil pengamatan di komunitas 19
3. Citra Hitam
Jaman dulu, kampung-kampung bantaran kali dianggap menakutkan dan
diberi label sebagai kampung wong-ngisor kali (orang bawah sungai), tempat tinggal gali, dan tempat tinggal orang-orang yang tidak baik. Kampung-kampung
ini diingat oleh kebanyakan warga kota sebagai daerah yang gelap-gulita, dengan
tetumbuhan perdu dan ilalang, dan kuburan-kuburan Cina (bong). Hanya beberapa
orang saja yang berani memasuki kawasan-kawasan seperti ini. Para tukang becak
akan menurunkan penumpangnya di pinggir jalan raya dan menolak mengantar
sampai dalam. Aparat (polisi dan tentara) akan menghentikan pengejaran para
penjahat kota jika buruan sudah masuk kampung-kampung itu.
.... seperti dalam kasus daerah Badran, pada akhirnya – dalam banyak ingatan – ia banyak dilukiskan dalam gambaran yang seram-seram. Dari gambaran tersebut misalnya memunculkan wajah perampok kereta api yang keberadaannya sudah ada sejak jaman Belanda, para gali, jawara, pencuri, penjudi, hingga pekerja seks.20
20
Sebagaimana dikutip oleh Kusen Alipah Hadi dari Dwibulanan Warta Kampung, edisi 09, tahun 2002, Jurnal Kampung, Yayasan Pondok Rakyat, tanpa tahun, hal 42.
Pada kurun waktu 1970 – 1980 berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di
Yogyakarta dilakukan oleh sosok yang disebut gali. Mereka melakukan
pemerasan di terminal-terminal bus, Stasiun Tugu, tempat perhentian kendaraan
umum, serta tempat perjudian dan prostitusi. Para gali oleh aparat dianggap
bersembunyi atau tinggal di kampung-kampung seperti Badran, Code dan Kricak.
Oleh sebab itu, patroli dan razia, termasuk penculikan dan interogasi kerap
dilakukan. Persoalan gali membuat resah warga kota, maka dimulailah operasi
perburuan gali pada akhir Maret 1983. Kampung-kampung di bantaran kali Code
dan Winongo menjadi sangat mencekam. Desingan peluru hampir tiap malam
terdengar, aparat bersenjata lengkap berpatroli dan mengetuk rumah-rumah
penduduk, menanyakan nama, siang dan malam. Orang-orang hilang begitu saja,
ada yang kemudian ditemukan tergeletak mati di parit-parit di pinggir jalan
kampung, ada yang tidak jelas keberadaannya dalam waktu lama.21
Praktik-praktik kekerasan oleh aparat tidak saja ditujukan kepada
pelaku-pelaku tindak kejahatan seperti para gali. Bentuk praktik kekerasan yang lain
seperti diskriminasi terhadap penghuni bantaran kali juga menjadi anggapan
umum pada kebanyakan warga kota di luar pemukiman bantaran kali.
.... Para pemulung sampah .... dianggap sebagai sampah masyarakat kota. ... Para gelandangan ini mengakui status sosial mereka yang rendah dengan menghindari pertemuan pandang dengan penduduk kampung waktu mereka sedang memulung sampah, berpura-pura tidak memperhatikan orang-orang kampung dan kegiatan mereka. 22
21
Dari berbagai sumber seperti Jurnal Kampung, juga dari penuturan warga di Sidomulyo, serta ingatan penulis tentang suasana pada masa-masa itu semasa semasa tinggal di daerah Kricak Kidul dan Jatimulyo antara tahun 1980-1984
22
4. Tingkatan Sosial
Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen.
Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang
beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman
kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan
ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.23 Menurut pengalaman dan
penelitian Guiness di kampung Ledok Code di tahun 80-an, para gelandangan
yang menetap di pinggir kali Code itu meninggalkan desanya karena
menginginkan peningkatan ekonomi mereka. Kebanyakan mereka datang sebagai
pelarian karena tidak tahan lagi hidup di desa, misalnya karena perlakuan buruk
dari orang tua angkatnya, karena dipaksa kawin, karena tanah keluarganya telah
dijual. Biarpun kecil kemungkinan sukses di kota, mereka tidak ingin kembali di
desa. Biasanya, sebelum datang ke Yogya, mereka telah berkeliling
(menggelandang) dari kota ke kota, tidur di kaki lima, bertahan hidup dengan
pekerjaan apa adanya seperti menarik becak, memulung, kuli pasar, termasuk
mencopet atau mencuri. Baru setelah itu menetap di Yogya. Sebagian pendatang
ini kemudian menetap di kampung-kampung itu. Kestabilan ini memungkinkan
terbentuknya kepemimpinan informal di kalangan mereka. Para pemimpin
informal muncul diantara mereka yang telah menunjukkan keberanian menentang
penggusuran, menunjukkan kepandaian dan kenekatan dalam berkelahi.
Sementara tidak ada lembaga politik dan sosial yang mengakui mereka, para
pemimpin informal lah yang menguasai mereka, mewakili mereka terhadap
23
pihak luar dan mengatur hubungan diantara mereka. Setiap penduduk yang
dianggap liar ini tidak terikat oleh aturan-aturan kehidupan masyarakat pada
umumnya. Selanjutnya, kebanyakan dari penghuni tidak resmi ini mengharap
dapat tinggal di kampung-kampung resmi, tempat mereka dapat hidup tenang.
Meski demikian, kenyataannya hal ini sulit sekali, karena untuk dapat tinggal di
suatu kampung resmi, mereka harus memiliki dokumen resmi dari desa asal. Di
samping itu, mereka juga tidak punya kenalan di kampung-kampung resmi yang
dapat menampung mereka atau memberi pekerjaan kepada mereka untuk
sementara.
Masyarakat pendatang yang dianggap liar semacam penduduk bantaran
kali selalu tunduk kepada dua struktur kekuasaan. Yang pertama, struktur
kekuasaan resmi yakni organisasi territorial pemerintahan sipil dan militer. Yang
kedua, struktur kekuasaan tidak resmi, yang diciptakan oleh masyarakat sendiri,
yang dikuasai oleh sekelompok elite (seperti para tuan tanah, gali, pensiunan
militer).24 Pengalaman Darwis di Ledok Code menyebutkan terdapat tiga
golongan dalam struktur kemasyarakatan yaitu kelompok kaum awam, kelompok
elite, dan kelompok kelana. Kelompok awam adalah kelompok yang paling lemah,
berasal dari desa, ingin hidup tentram dan tidak suka berkelahi (kalaupun pernah
biasanya selalu kalah). Kelompok elite merupakan yang paling kuat. Terdiri atas
jagoan atau orang-orang yang pernah bersekolah, dan biasanya mereka
berpengalaman dengan kehidupan keras di kota. Mereka ini diceritakan suka
bertindak seenaknya, dan berkomplot memeras kelompok awam. Kelompok
24