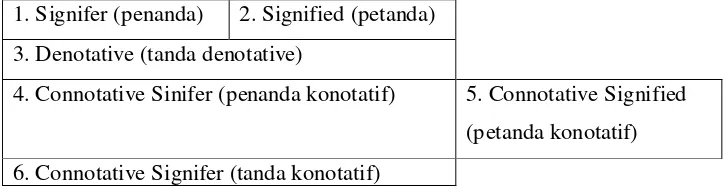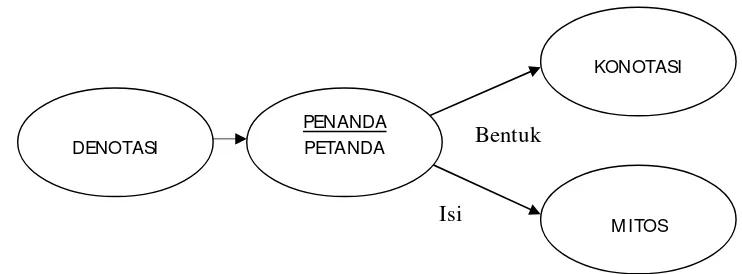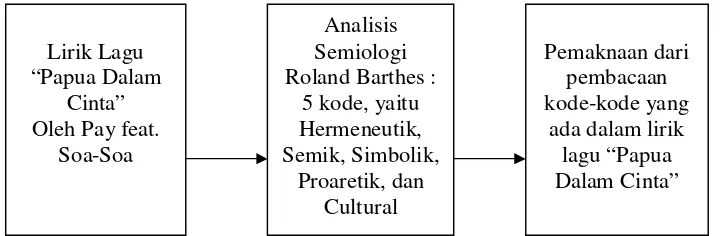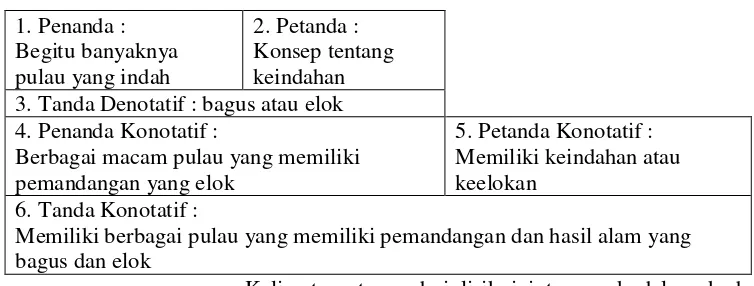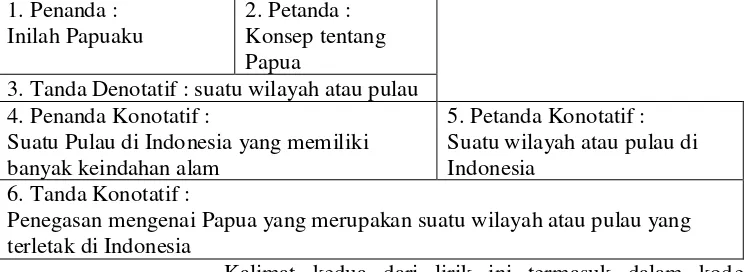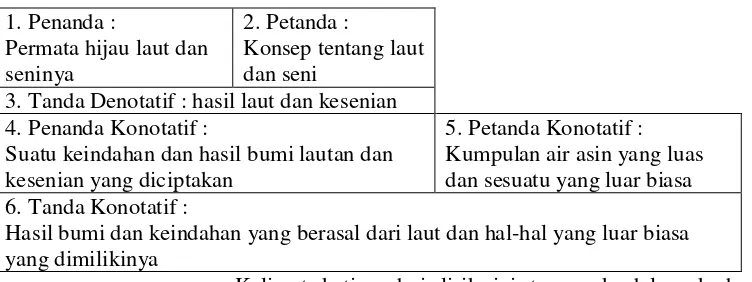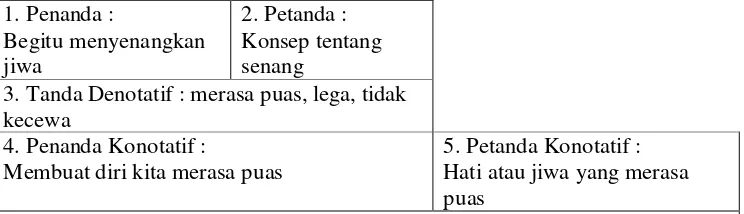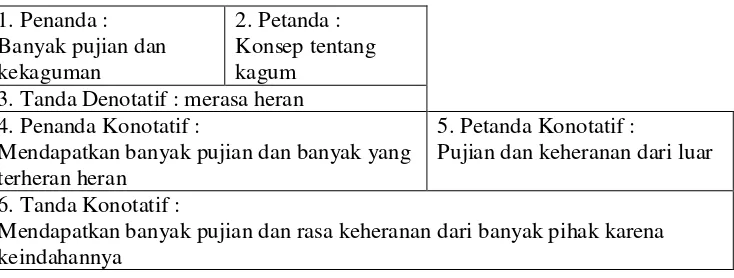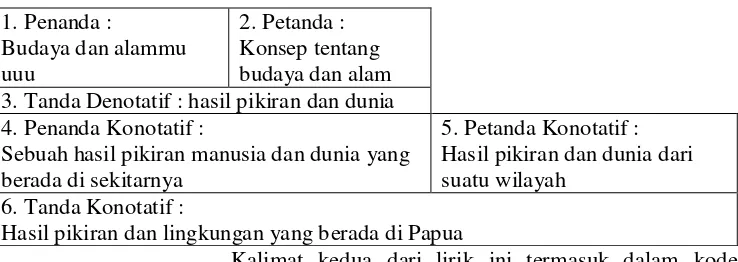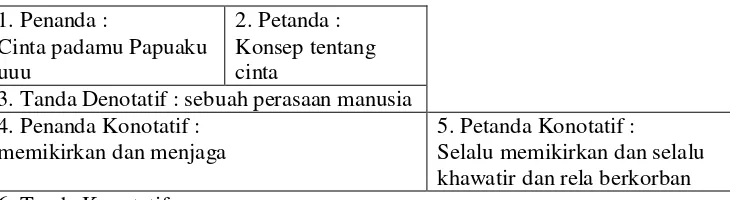S K R I P S I
Diajukan untuk memenuhi sebagai per syar atan memper oleh Gelar Sar jana
pada FISIP UPN “Veter an” J awa Timur
Oleh :
LULUT NILOT PALASARI
NPM. 0843010073
YAYASAN KESEJ AHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” J AWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
ii
Disusun oleh :
LULUT NILOT PALASARI
NPM. 0843010073
Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Menyetujui,
Dosen Pembimbing,
Dr s. Saifuddin Zuhr i, M.Si
NPT. 3 7000 94 0035 1
Mengetahui,
D E K A N
Disusun Oleh :
LULUT NILOT PALASARI NPM. 08 43010 073
Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pembanguan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 13 Juni 2012
Menyetujui,
Mengetahui, DEKAN
Dr a. Ec. Hj. Supar wati, M.Si PEMBIMBING UTAMA
Dr s. Syaifuddin Zuhr i, M.Si NPT. 370069400351
Tim Penguji:
1. Ketua
J uwito, S.Sos, M.Si NPT. 3 6704 95 0036 1 2. Seker tar is
Dr s. Syaifuddin Zuhr i, M.Si NPT. 370069400351
3. Anggota
yang dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan lirik lagu “Papua Dalam Cinta” yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa. Penelitian ini menaruh perhatian pada pemaknaan lirik lagu “Papua Dalam Cinta” yang diciptakan oleh Pay dan dipopulerkan oleh Pay featuring Soa-Soa. Penelitian ini didasarkan pada kecintaan bangsa Indonesia terhadap keindahan alam dan kekayaan alam Papua.
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Dalam penilitian ini peneliti menggunakan pendekatan semiologi Roland Barthes atau semiotik Saussure.
Hasil penelitian ini adalah lagu “Papua Dalam Cinta” berisi tentang sebuah ajakan untuk menumbuhkan kecintaan bangsa Indonesia terhadap Papua dan ajakan untuk selalu menjaga keindahan alam Papua.
ABSTRACT
LULUT NILOT PALASARI, THE LITERAL MEANING OF “PAPUA DALAM CINTA” SONG LYRIC (Semiology Study of the Literal Meaning of “Papua Dalam Cinta” Song Lyric brought by Pay feat. Soa-Soa)
The purpose of this study was to determine the meaning of the lyrics to "Papua Dalam Cinta" which was created and popularized by the Pay feat. Soa Soa. The research was concerned with the meaning of the lyrics to "Papua Dalam Cinta" which was created by the Pay and popularized by the Pay-Soa Soa featuring. The study was based on the love of the natural beauty of Indonesia and Papua's natural wealth.
This study used a qualitative descriptive method. In this study researchers used the approach of Roland Barthes semiology or semiotics of Saussure.
The results of this study is the song "Papua Dalam Cinta" contains a call to foster a love of Indonesia to Papua and call to always maintain the natural beauty of Papua.
atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang
berjudul “PEMAKNAAN LIRIK LAGU “PAPUA DALAM CINTA” (Studi
Semiologi Pemaknaan Lir ik Lagu “Papua Dalam Cinta” yang dipopulerkan
oleh Pay feat. Soa Soa).
Sekalipun penulis harus mengalami berbagai kesulitan, tetapi
bersyukur bahwa SKRIPSI ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis
menyadari bahwa di dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan.
Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya :
1. ALLAH SWT untuk anugerah, hidayah, inspirasi serta tuntunan yang
senantiasa mengilhami penulis.
2. Keluarga Tercinta, yang selalu menjadi tujuan utama penulis untuk selalu
melakukan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak saya yang telah
membantu dalam penulisan Skripsi ini baik secara moriil ataupun secara
materril.
3. Juwito, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP
UPN “Veteran” Jatim.
4. Drs. Syaifuddin Zuhri, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu
6. Sahabat-sahabat luar biasa yang tak sekedar memotivasi hingga selesainya
Skripsi ini: Ajeng, Risca, Tata, Mas Sigit dan juga Ak.family at AK UPN
Radio.
7. Cho Kyuhyun yang secara tidak langsung telah memberikan semangat untuk
saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan atas keterbatasan halaman ini,
untuk segala bentuk bantuan yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
Demikian Skripsi ini ditulis, penulis berharap semoga Skripsi ini
bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi di masa yang akan datang. Penulis
menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna. Mohon Kritik dan sarannya .
Surabaya, Juni 2012
HALAMAN JUDUL ... i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ... iii
KATA PENGANTAR ... iv
DAFTAR ISI ... vi
DAFTAR GAMBAR ... ix
DAFTAR LAMPIRAN ... xiii
ABSTRAKSI ... xiv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 14
1.3. Tujuan Penelitian ... 14
1.4. Manfaat Penelitian ... 15
1.4.1. Manfaat Teoritis ... 15
1.4.2. Manfaat Praktis ... 15
BAB II KAJ IAN PUSTAKA ... 16
2.1. Landasan Teori ... 16
2.1.5. Makna dan Pemaknaan... 28
2.1.6. Teori-Teori Makna ... 30
2.1.7. Semiotika dan Semiologi Komunikasi ... 32
2.1.8. Semiologi Roland Barthes ... 34
2.1.8.1. Kode Pembacaan ... 40
2.2. Kerangka Berfikir ... 43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 45
3.1. Metode Penelitian ... 45
3.2. Korpus Penelitian ... 46
3.3. Analisis Semiotik ... 49
3.4. Unit Analisis ... 50
3.5. Teknik Pengumpulan Data ... 50
3.6. Metode Analisis Data ... 51
3.7. Teknis Analisis Data ... 52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 53
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ... 53
4.2. Penyajian Data dan Analisis Data ... 55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 141
5.1. Kesimpulan ... 141
5.2. Saran ... 142
1.1 Latar Belakang Masalah
Belakangan ini semakin banyak dijumpai berita-berita mengenai
masalah dan konflik-konflik di media massa, baik media cetak, media
elektronik, maupun media online di Indonesia ini. Satu contoh wilayah
yang sering menjadi sorotan media di Indonesia mengenai konflik yang
sering terjadi di daerahnya adalah Papua. Konflik yang terjadi di Papua ini
tidak hanya mengenai konflik ekonomi namun sudah menjalar ke
permasalahan konflik sosial, budaya dan politik. Masalah ini sudah ada
dari jaman dahulu kala, namun sampai sekarang masih belum ada jalan
keluar dan penyelesaiannya.
Sejarah Papua hampir dapat diidentikan dengan sejarah konflik
dan kekerasan. Bila merunut ke belakang, ketika terjadi perselisihan antara
Belanda dan Indonesia mengenai status politik Papua Barat saat itu,
masing-masing melakukan unjuk kekuatan. Dengan seruan Tri Komando
Rakyat (Trikora), militer Indonesia yang waktu itu berbasis di Aboina
(Maluku) terus dimobilisir sampai ke Papua. Sementara militer Belanda
telah menyiapkan diri untuk berkonfrontasi dengan militer Indonesia.
Ketegangan tersebut teratasi dengan diserahkannya Papua kepada
(
http://hankam.kompasiana.com/2011/11/01/kekerasan-di-papua-politisasi-dan-strukturasi/).
Mirisnya keadaan di Papua sekarang ini membuat banyak
tanggapan yang bermacam-macam dari masyarakat. Ada yang mengecam
keras ada yang masih mengambil sisi positif dari hal tersebut. Para tokoh
masyarakat berlomba-lomba menyatakan opini dan pemikirannya nya
melalui berbagai media. Para musisi di Indonesia juga tidak mau kalah
untuk ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat mereka. Dan agar
masyakat dapat dengan mudah menerima pesan tersebut para musisi
tersebut menuangkan pesannya dalam lagu-lagu yang mereka ciptakan.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Little John mengenai
komunikasi. Komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh makna,
tanda-tanda adalah basis dari seluruh komunikasi (Little John dalam
Sobur, 2003 : 15). Manusia dengan perantara tanda-tanda dapat melakukan
komunikasi dengan sesamanya. Banyak hal yang bisa dikomunikasikan di
dunia ini, termasuk juga melalui sebuah media dalam menyampaikan
pesannya, salah satunya adalah musik dan lagu.
Musik dan lagu merupakan salah satu kegiatan komunikasi,
karena di dalamnya terdapat proses penyampaian pesan dari pencipta lagu
tersebut kepada khalayak pendengarnya. Pesan yang terkandung dalam
sebuah lagu merupakan representasi dari pikiran atau perasaan dari
disampaikan biasanya bersumber dari frame of reference (kerangka acuan)
dan field of experience (pengalaman).
Musik merupakan hasil budaya manusia yang menarik diantara
banya hasil budaya yang lain. Dikatakan menarik karena musik memegang
peranan yang sangat banyak di berbagai bidang. Seperti jika dilihat dari
psikologinya, musik kerap menjadi sarana kebutuhan manusia dalam
hasrat akan seni dan beraksi. Dari segi sosial musik dapat sebagai cermin
tatanan sosial yang ada dalam masyarakat saat musik tersebut diciptakan.
Musik dapat dikatakan sebagai bahasa universal, dapat juga diartikan
sebagai media ekspresi masyarakat, baik itu kalangan bawah hingga
lapisan yang paling atas. Tanpa disadari musik juga mempengaruhi
kehidupan sosial di dalam kehidupan masyarakat, sehingga musik banyak
tercipta dari tema yang cukup beraneka ragam mulai dari masalah
percintaan, kehidupan sehari-hari, seni budaya, agama, olahraga, mode
maupun sebagai alat kontrol sosial dan kritik terhadap salah satu pihak
seperti pemerintahan. Musik diartikan sebagai ungkapan perasaan yang
dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian atas suatu suara. Ungkapan yang
dikeluarkan melalui suara manusia disebut dengan vokal sedangkan
ungkapan yang dikeluarkan melalui bunyi alat musik disebut intrumental
(Subagyo, 2006:4).
Musik sendiri menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
memiliki makna bunyi-bunyian yang ditata enak dan rapi. Dari definisi di
lagu yang dinyanyikan biasanya terdiri dari komponen-komponen yang
saling melengkapi dan saling bergantung. Komponen tersebut antara lain
paduan alat musik dalam satu instrumen, suara vokal dan yang terakhir
adalah lirik lagunya itu sendiri. Instrumen dan kekuatan vokal penyanyi
adalah sebagai tubuh sedangkan lirik lagu adalah jiwa atau nyawa
penggambaran musik itu sendiri.
Musik dalam sebuah lagu adalah sebuah lirik yang diberikan
instrumental akor dan melodi, meskipun terlihat sederhana, namun proses
pembuatan sebuah lagu dibutuhkan keahlian menulis lirik lagu hingga
keahlian dalam berimajinasi menciptakan sebuah ide, meskipun dalam
prakteknya lirik tersebut berdasarkan pengalaman pribadi atau keadaan
sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Lirik lagu merupakan sebuah
komunikasi verbal yang memiliki sebuah makna pesan di dalamnya.
Sebuah lirik lagu bila tepat memilihnya bisa memiliki nilai yang sama
dengan ribuan kata atau peristiwa, juga secara individu maupun memikat
perhatian. Kekuatan lirik lagu adalah unsur yang sama penting bagi
keberhasilan bermusik, sebab pesan yang disampaikan oleh pencipta lagu
ternyata tidak berasal dari luar diri pencipta lagu tersebut, dalam artian
bahwa pesan tersebut bersumber pada pola pikir serta kerangka acuan
(frame of reference) dan pengalaman (field of experience) sebagai hasil
integrasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Lirik lagu mungkin juga
Musik merupakan satu kesatuan dari nada, lirik, bahkan visual
(video klip) yang diciptakan berdasarkan perasaan pencipta musik tersebut
yang kemudian diterjemahkan ke dalam musik. Isi tanda musik dalam hal
ini adalah emosi yang dibangkitkan dalam diri pendengar, jadi apabila
seseorang menangkap sebuah musik yang berupa ungkapan yang diubah
menjadi sebuah nada dan lirik maka pendengar tersebut akan ikut
merasakan ungkapan terhadap perasaan-perasaan tersebut. Lirik lagu dapat
pula sebagai sarana sosialisasi dalam pelestarian terhadap suatu sikap atau
nilai. Oleh karena itu, ketika sebuah lirik lagu diaransir dan
diperdengarkan kepada masyarakat tanggung jawab yang besar atas
tersebar luasnya sebuah keyakinan, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu
(Setianingsih, 2003:7-8).
Dapat dikatakan musik yang di dalamnya terdapat lirik sebuah
lagu adalah sebuah proses komunikasi, hal ini seperti diungkapkan Tubbs
and Moss dalam Human Communication : Proses komunikasi itu
sebenarnya mencangkup pengiriman pesan dari sistem syaraf ke sistem
syaraf orang lain, dengan maksud untuk menghasilkan semua makna yang
sama dalam benak pengirim. Pesan verbal melakukan hal tersebut melalui
kata-kata yang merupakan unsur dari bahasa dan kata-kata, sudah jelas
merupakan sebuah simbol (Tubbs, 2001:72).
Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi
ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian maupun kelompok.
orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi
instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi). Perasaan
tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan non verbal. Harus diakui
musik juga dapat mengekspresikan perasaan, kesadaran, dan bahkan
pandangan hidup (Mulyana, 2003:21).
Setiap kata mengandung makna, makna itu sudah ada yang jelas,
tetapi juga ada makna yang kabur. Setiap kata dapat saja mengandung
lebih dari satu makna. Dapat saja sebuah kata mengacu pada sesuatu yang
berbeda sesuai dengan lingkungan pemakainya. Hubungan makna tampak
pula jika dirangkaikan satu dengan yang lain sehingga akan terlihat makna
dalam pemakaian bahasa. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan
karena mempunyai banyak makna, sehingga musik tidak hanya bunyi
suara belaka.
Musik juga memainkan peran dalam evolusi manusia, dibalik
perilaku dan tindakan manusia terdapat pikiran dan perkembangan diri
dipengaruhi oleh musik. Pemakaian bahasa pada sebuah karya seni
berbeda dengan penggunaan bahasa sehari-hari atau dalam kegiatan lain.
Musik berkaitan erat dengan setting sosial terhadap masyarakat tempat dia
berada, sehingga mengandung makna yang tersembunyi dan berbeda di
dalamnya.
Dalam hal ini representasi makna di dalam suatu musik dan lirik
lagu dapat mengandung arti yang bermacam-macam. Konsep representasi
konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga
tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negoisasi dan disesuaikan
dengan situasi yang baru. Intinya adalah : makna akan inheren dalam suatu
dunia ini, ia selalu dikonstruksikan, diproduksi, lewat proses representasi.
Ia adalah hasil dari praktek pertandaan. Praktek yang membuat sesuatu hal
bermakna sesuatu (Juliastuti, 2000 : 1).
Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto (Rahmawati, 2001:1)
bahwa musik berkaitan erat dengan setting awal sosial kemasyarakatan
dan gelaja khas akibat interaksi sosial dimana lirik lagu menjadi penunjang
dalam musik tersebut dalam menjembatani isu-isu sosial yang terjadi.
Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekamto dalam Rahmawati
(2001:1) yang menyatakan :
“Musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan tempat dia berada. Musik merupakan gejala khas yang dihasilkan akibat adanya interaksi sosial, dimana dalam interaksi tersebut manusia menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Disinilah kedudukan lirik sangat berperan, sehingga dengan demikian musik tidak hanya bersuara belaka, karena juga menyangkut perilaku manusia sebagai individu maupun kelompok sosial dalam wadah pergaulan hidup dengan wadah bahasa atau lirik sebagai penunjangnya.”
Berdasarkan kutipan di atas, sebagai lirik lagu dapat berkaitan pula dengan
situasi sosial dengan isu-isu sosial yang sedang berkembang di dalam
bangsa Indonesia.
Musik juga dapat digunakan sebagai media penyampaian suatu
pesan kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan berbagai macam, mulai
pesan yang hanya bertujuan memperlihatkan akan kecintaan, kebencian,
bersangkutan dengan kecintaan, kebencian, nasionalisme, dan lain-lain
tersebut. Salah satu contoh pesan yang disampaikan adalah pentingnya
kecintaan khususnya terhadap negara dan daerahnya sendiri. Menurut arti
di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “cinta” mempunyai arti selalu
teringat dan terpikir di dalam hati.
Dalam lirik lagu ini para generasi muda bangsa kita sudah
kekurangan akan nilai rasa kecintaan terhadap bangsanya, mereka sibuk
mencari hal-hal lain daripada bangsa dan wilayahnya, merusak dan
menelantarkan bangsanya, memandang rendah terhadap kebudayaannya,
bersikap acuh tak acuh terhadap saudara sebangsanya, dan asik dengan
budaya yang ada di luar sehingga melupakan akan bangsanya. Namun
beberapa musisi dan grup band di Indonesia berusaha menunjukkan
kepeduliannya terhadap bangsa Indonesia, sebagai contoh adalah Band
Coklat, Band Gigi, dan Iwan Fals. Mereka merupakan beberapan contoh
band dan musisi yang ada di Indonesia yang berani mengangkat tema rasa
cinta dan kepedulian terhadap bangsanya, selain itu ada juga Pay, seorang
musikus Indonesia yang juga anggota dari band BIP dan grup Soa Soa,
sebuah grup pendatang baru yang berasal dari Papua yang mengangkat
tema cinta terhadap bangsa dalam lagunya yang berjudul “Papua Dalam
Cinta”.
Karena keprihatinannya terhadap berbagai masalah di Papua, Pay
coba mengekspesikannya melalui sebuah lagu. "Gue rasa lebih tepat musik
Dan, di samping itu mau membangunkan mental warga Papua. Cuma kata
teman-teman yang asli dari sana, enggak terlalu gitu-gitu amat, tapi karena
beritanya begitu terus, gue dan teman-teman spontan aja buat lagu untuk
Papua," terang Pay ditemui usai tampil di Studio Dahsyat RCTI, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (18/2/2012)
(
http://music.okezone.com/read/2012/02/18/386/578236/papua-dalam-cinta-pay).
Lirik yang terdapat dalam lagu “Papua Dalam Cinta” ini
mencerminkan tentang kritik sosial terhadap beberapa konflik yang sering
terjadi di Papua belakangan ini dan pandangan masyarakat di Indonesia
yang seolah olah menganggap masyarakat Papua sebelah mata dengan kata
lain meremehkan. Konflik yang terjadi di Papua belakangan ini telah
membuat beberapa kerugian, tidak hanya kerugian materi namun kerugian
sosial sehingga terjadinya perpecahan. Menurut Guru Besar Universitas
Syiah Kuala mengatakan jika dicermati lebih jauh, konflik Papua
sesungguhnya begitu kompleks dan mencakup berbagai sektor kehidupan
masyarakat yang ada di Bumi Cenderawsih. Mulai dari persoalan sejarah,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan
(
http://berita.liputan6.com/read/348358/pengamat-konflik-papua-bukan-persoalan-separatis-semata).
Salah satu konflik yang sampai sekarang masih sering menjadi
sorotan media dan masyarakat adalah kasus Freeport. Kasus Freeport ini
masalah yang ditimbulkannya, mulai kasus penjarahan kekayaan alam,
perusakan lingkungan, pemiskinan, sampai kasus kekerasan terhadap
warga pribumi di Papua. Sehingga dalam realitanya di Papua sudah
banyak terjadi perpecahan saudara dan diskriminasi sosial.
“Dulu kami tak pernah kekurangan, semuanya sudah disediakan
di alam. Untuk makan tinggal mengambil sagu, untuk lauk tinggal mencari
ikan atau berburu di hutan,” ungkap Gergorius Okoare, tokoh muda suku
Kamoro, Timika. Namun segalanya berubah ketika pendatang yang datang
dari peradaban lain begitu terobsesi untuk mengambil
sebanyak-banyaknya dari dalam tanah mereka. Konflik dalam pemanfaatan sumber
daya alam pun mulai mengemuka (Kompas, 2007:32-33). Keadaan
diperparah oleh konflik-konflik bersenjata yang kian mengental : konflik
antar suku, serta konflik antara masyarakat adat dan Freeport, terus terjadi
di sekitar areal konsensi tambang mereka. Salah satunya adalah insiden
pada Februari 2006 yang lalu (Kompas, 2007:35).
Operasi perusahaan tambang tembaga dan
emas Freeport McMoran telah berlangsung setengah abad dan
kontrak karyanya sudah beberapa kali diperpanjang. Kerugian dan
kerusakan yang diakibatkannya telah melahirkan berbagai protes dan
perlawanan yang ditindas keras aparat keamanan Indonesia
(http://suaraperempuanpapua.org/index.php?option=com_content&view=a
Sebagai contoh perpecahan saudara yang terjadi di Papua adalah
perang suku yang terjadi di Kampung Muara Distrik Karubaga, Kabupaten
Tolikara, Papua. Bentrok di kampung Karubaga ini dipicu masalah
keluarga (
http://news.okezone.com/read/2010/07/13/340/352661/perang-suku-pecah-di-papua-4-orang-tewas). Tidak hanya itu, konflik perang
antar saudara di Papua juga terjadi di wilayah Kabupaten Puncak dan
Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Ketua BEM Papua menyebut tiga tokoh
kunci yang menurutnya adalah pemicu konflik. Tiga tokoh itu adalah
Lukas Enembe, Elvis Tabuni dan Simon Alom. Konflik ini disebabkan
karena adanya penembakan dan perang suku yang menyebabkan puluhan
nyawa warga melayang (
http://politik.kompasiana.com/2012/02/05/tiga-tokoh-pemicu-konflik-papua/).
Papua juga masih mengalami diskriminasi bahkan oleh negara.
Menurut penyataan Paskalis Kossay, anggota DPR RI dari daerah
pemilihan Provinsi Papua, menyatakan bahwa segala bentuk pernyataan
elite Jakarta selama ini hanyalah wacana di atas kertas, karena pada
kenyataannya Papua masih mengalami proses diskriminasi dan
peminggiran. Ia mengatakan itu di Jakarta, Selasa (16/8/2011), merespons
pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang antara lain
mengatakan, membangun Papua harus dilakukan dengan hati. “Tetapi
faktanya, Papua didiskriminasi oleh negara. Terbukti, (Undang Undang)
ujarnya menandaskan (
http://www.surya.co.id/2011/08/16/papua-masih-alami-diskriminasi).
Bagi masyarakat Papua hal ini memang dirasakan sangat
mengganggu dan meresahkan. Seperti layaknya manusia mereka juga
menginginkan keadaan wilayahnya yang tentram, aman, dan nyaman.
Kerinduan semua elemen masyarakat akan kedamaian, ketenangan dan
ketentaraman hidup di Kota Jayapura, diharapkan menjadi satu
pemahaman bersama semua unsur masyarakat Kota Jayapura yang
pluralitas. Keprihatinan itu diungkapkan berbagai unsur masyarakat di
Kota Jayapura yang diwakili para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik serta perwakilan Paguyuban yang
ada di Kota Jayapura. Ungkapan Keprihatinan itu disampaikan kepada
Wali Kota dan Muspida dalam suatu pertemuan khusus “Cofee Morning”,
Kamis (18/8/2011) di Kantor Wali Kota Jayapura. Keprihatinan,
sehubungan dengan situasi Keamanan di Kota Jayapura, tepatnya di
Kampung Nafri dan sekitarya yang mengakibatkan timbulnya rasa tidak
nyaman dimasyarakat Kota Jayapura yang pluralitas. Banyak masukan
diberikan para Tokoh Agama kepada Wali Kota, pun sebaliknya, masukan
diberikan unsur masyarakat Paguyuban dan Pemuda, agar Pemerintah
Kota Jayapura segera mengambil langkah langkah dan bertindak
menetralisir keadaan dengan memberikan rasa nyaman kepada semua
masyarakat (
Dapat dikatakan bahwa masyarakat Papua disini sebenarnya telah
merindukan kebebasannya tersebut. Karenanya banyak aksi perlawanan
dan perjuangan masyarakat Papua untuk mewujudkan kebebasan di
wilayahnya. Namun mereka seolah berjuang untuk perdamaian tersebut
seorang diri dan bahkan ada dari beberapa lapisan masyarakat yang
menganggap sepele hal tersebut. Pemerintah seolah acuh tak acuh terhadap
keadaan ini sehingga dari tahun ke tahun masih saja tidak ada titik cerah
dari masalah yang dialami masyarakat Papua ini.
Dari beberapa fenomena di atas maka peneliti melihat bahwa lagu
yang dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa yang berjudul “Papua Dalam
Cinta” ini menarik untuk direpresentasikan atau diteliti. Oleh karena itulah
dalam penelitian ini peneliti menaruh perhatian mengenai konflik dan
masalah-masalah yang terjadi di Papua yang telah mengakibatkan
perpecahan, kerusakan alam, dan konflik-konflik sosial lainnya. Peneliti
meneliti lagu ini karena lagu ini adalah sebuah bentuk pesan yang
diberikan untuk masyarakat agar masyarakat kembali bersatu dan
mencintai Papua yang tercinta ini.
Dalam penilitian ini peneliti menggunakan pendekatan semiologi
Roland Barthes atau semiotik Saussure. Dimana lebih lengkapnya
saussure meletakkan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan
pemilahan significant (penanda) dan signifie (petanda). Significant adalah
bunyi yang bermakna (aspek material), yakni apa yang dari ditulis atau
mental) dari bahasa. (Barthes, 1985:382 dalam Kurniawan, 2001:14) dan
Roland Barthes yang menekankan kepada text.
Lebih ringkasnya peneliti disini meneliti tentang suatu sistem
tanda, salah satunya bagaimana Pay feat. Soa Soa membuat lagu tersebut
dengan memberi makna pada lagu tersebut dan seperti apa Pay feat. Soa
Soa mereferensikan fenomena ke dalam sistem tanda komunikasi berupa
lirik lagu.
Penelitian tentang suatu sistem penilitian ini secara khusus untuk
mengetahui bagaimana pemaknaan dalam lirik lagu “Papua Dalam Cinta”
yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa dan berdasarkan
latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah studi
semiologi untuk mengetahui pemaknaan dalam lirik lagu “Papua Dalam
Cinta” yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pay feat. Soa Soa.
1.2 Per umu san Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
“Bagaimana pemaknaan lirik lagu “Papua Dalam Cinta” yang dibawakan
oleh Pay feat. Soa Soa ?”
1.3 Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
“Papua Dalam Cinta” yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pay feat. Soa
Soa.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teor itis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan pada perkembangan serta pendalaman pribadi studi
komunikasi dengan menganalisis semiotika dalam lirik lagu “Papua
Dalam Cinta” dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan
serta menambah referensi perpustakaan khususnya ilmu
komunikasi kepada peneliti lain.
1.4.2 Manfaat Pr aktis
Membantu pembaca dan penikmat musik dalam
memahami apa maksud dari lirik lagu “Papua Dalam Cinta”
sehingga pesan yang terdapat dalam lagu tersebut dapat diterima
dengan baik, dan dapat membuat masyarakat lebih mengenal Papua
lebih dalam lagi sehingga menimbulkan simpati dan rasa cinta dan
sebagai sarana persuasif bagi masyarakat agar dapat menambah
2.1. Landasan Teor i
2.1.1. Musik
Musik adalah suatu suara atau bunyi-bunyian yang diatur
menjadi satu yang menarik dan menyenangkan. Dengan kata lain
musik dikenal sebagai sesuatu yang terdiri dari atas nada dan ritme
yang mengalun secara teratur. Musik juga memainkan peran dalam
evolusi manusia, dibalik tindakan dan perilaku manusia terdapat
pikiran dan perkembangan, ini dipengaruhi oleh musik. Seni musik
merupakan salah satu seni untuk menyampaikan ekspresi. Ekspresi
yang disampaikan sekarang ini bukan hanya mengandung unsur
keindahan seperti tema-tema percintaan, namun belakangan ini
banyak tercipta tema-tema yang berisi permasalahan sosial dan
realitas yang ada pada masyarakat.
Musik dapat tercipta karena didorong oleh kondisi sosial,
politik, dan ekonomi masyarakat, musik adalah cermin masyarakat,
musik juga diilhami oleh perilaku masyarakat, dan sebaliknya
perilaku umum masyarakat dapat terilhami oleh musik tertentu.
Perilaku umum masyarakat dapat berupa permasalahan sosial,
ataupun harapan yang diidamkan (Rachmawati dalam Ayuningtyas,
2006:9).
Sistem tanda musik adalah oditif, namun untuk mencapai
pendengarannya, pengubahan musik dalam mempersembahkan
kreasinya dengan perantara pemain musik dalam bentuk sistem
tanda tertulis. Bagi Semiotikus musik, adanya tanda-tanda
perantara, yakni musik yang dicatat dalam partitur orkestranya. Hal
ini sangat memudahkan dalam menganalisis karya musik dengan
teks. Itulah sebabnya mengapa penelitian musik terarah pada
sintakis.
Meski demikian, tidak ada semiotika tanpa semantik. Jadi,
juga tidak ada semiotik musik tanpa semantik musik. Semantik
musik, bisa dikatakan harus senantiasa membuktikan hak
kehadirannya (Van Zoest, 1993:120-121).
Salah satu hal terpenting dalam sebuah musik adalah lirik
lagu. Sebagaimana bahasa dapat menjadi sarana atau media
komunikasi untuk mencerminkan realitas sosial yang ada pada
masyarakat. Lirik lagu dapat pula menjadi sarana untuk sosialisasi
dan pelestarian terhadap suatu sikap atau nilai. Oleh karena itu,
ketika sebuah lirik lagu mulai diaransir dan diperdengarkan kepada
khalayak, nilai-nilai, bahkan prasangka tertentu.
Dapat dikatakan bahwa musik merupakan bagian dari
dari lahir hingga akhir hayat, musik juga menyentuh segala lapisan
sosial masyarakat dari bawah hingga atas.
Mantle Hood, seorang pelopor Ethnomusicology dari USA
memberikan defini tentang Ethnomusicology sebagai studi musik
dari segi sosial dan kebuadayaan (Bandem, 1981:41). Musik itu
dipelajari melalui peraturan tertentu yang dihubungkan dengan
bentuk kesenian lainnya termasuk bahasa, falsafah, dan agama
(Sobur, 2003:148).
Dalam sebuah tulisannya ihwal perkembangan
ethnomusicology ini, I Made Bandem (1981:41) menuturkan :
Kendati ethnomusicology itu umurnya kurang dari seratus
tahun, namun uraian tentang musik eksotik sudah dijumpai jauh sebelumnya. Uraian-uraian tersebut ditulis oleh para penjelajah dunia, utusan-utusan agama, orang-orang yang suka berziarah dan para ahli filologi. Pengenalan musik Asia di dunia Barat semula dilakukan oleh Marcopolo musik Cina oleh de Halde (1735), dan J.M. Amiot (1779), serta musik Arab oleh Andres (1787).
Musik pop adalah merupakan suatu bagian yang
terpenting di sekian banyak cabang seni pertunjukkan. Musik ini
digandrungi oleh setiap lapisan masyarakat. Di dalam musik ini
merupakan sebuah rasa nasionalisme yang sangat berpengaruh
pada bangsanya.
Musik juga dapat dengan mudah masuk ke berbagai
lapisan masyarakat, baik menengah ke atas ataupun menengah ke
bawah, tua maupun muda, kaya maupun miskin. Dapat dikatakan
pencipta dan penyanyi ini memilih musik sebagai media
penyampaian pesannya tentang kedamaian kepada khalayak. Hal
ini agar pesan mengenai perdamaian yang ingin disampaikannya
mudah masuk dan diterima oleh masyarakat sehingga pesan
tersebut menjadi sarana persuasi agar masyarakat dapat
menciptakan perdamaian tersebut.
2.1.2. Lir ik Lagu
Perkembangan lirik lagu di Indonesia sudah mulai muncul
sejak setelah merebut kemerdekaan. Pada paruhan pertama
dasawarsa 1950-an. Pada waktu itu masih dilakukan yang
dinamakan “musikalisasi syair” yaitu menggarap
komposisi-komposisi lagu terhadap puisi-puisi yang terlebih dahulu diciptakan
oleh penyair terpandang (Rachmawati, 2000:42).
Lirik lagu dalam musik yang sebagaimana bahasa, dapat
menjadi sarana atau media komunikasi untuk mencerminkan
realitas sosial yang beredar dalam masyarakat. Lirik lagu dapat
pula digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi dan pelestarian
terhadap suatu sikap atau nilai. Oleh karena itu, ketika sebuah lirik
diaransir dan diperdengarkan kepada khalayak yang mempunyai
tanggung jawab yang besar atas tersebar luasnya sebuah keyakinan,
nilai-nilai bahkan prasangka tertentu (Setianingsih, 2003:7-8).
menggambarkan nasionalisme, sebagai wujud cinta tanah air
terhadap bangsa dan negara.
Musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan
tempat dia berada. Musik merupakan gejala khas yang dihasilkan
akibat adanya interaksi sosial, dimana dalam interaksi tersebut
manusia menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Disinilah
kedudukan lirik sangat berperan, sehingga dengan demikian musik
tidak hanya bunyi suara belaka, karena juga menyangkut perilaku
manusia sebagai individu maupun kelompok sosial dalam wadah
pergaulan hidup dengan wadah bahasa atau lirik sebagai
penunjangnya.
Penelitian lirik lagu merupakan penelitian makna isi pesan
dalam lirik lagu tersebut. Dimana lirik lagu merupakan suatu
produk yang salah satu sumbernya adalah situasi sosial. Dimana
lirik lagu di dalamnya, kemudian merefleksikan dalam sistem tanda
berupa lirik lagu. Maka, dapat dikatakan bahwa lirik lagu “Papua
Dalam Cinta” milik Pay feat Soa-Soa merupakan proses
komunikasi yang mewakili seni karena terdapat pesan yang
terkandung dalam simbol lirik lagu tersebut yang sengaja
digunakan oleh komunikator sebagai pencipta lagu untuk
disampaikan kepada komunikan dengan bahasanya tentang suatu
Namun dalam hal ini bahasa verbal yang berupa kata-kata yang
tertuang dalam teks lirik lagu.
Dalam lirik lagu “Papua Dalam Cinta” ini terdapat
kalimat-kalimat persuasif yang menyatakan ajakan bagi masyarakat
untuk menjaga dan mewujudkan rasa cinta tanah air tersebut. Pay
sendiri menuliskan kalimat-kalimat tersebut dengan latar belakang
situasi sosial yang tengah terjadi di Indonesia, yaitu konflik-konflik
di Papua itu sendiri yang mengakibatkan perpecahan dan kerusuhan
sehingga dibutuhkan suatu penyampaian pesan untuk menjaga dan
mewujudkan rasa cinta tanah air tersebut. Jadi dalam penulisan
suatu lirik lagu haruslah mengandung sebuah pesan dan makna
yang jelas agar pesan yang ingin disampaikan melalui lirik lagu
tersebut dapat diterima, diikuti, dan dilakukan.
2.1.3. Penger tian Cinta
Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat
dan ketertarikan pribadi. Dalam konteks filosofi cinta merupakan
sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan
kasih sayang. Pendapat lainnya, cinta adalah sebuah aksi/kegiatan
aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa
pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu,
menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun
Cinta adalah suatu perasaan yang positif dan diberikan
pada manusia atau benda lainnya. Bisa dialami semua makhluk.
Penggunaan perkataan cinta juga dipengaruhi perkembangan
semasa. Perkataan sentiasa berubah arti menurut tanggapan,
pemahaman dan penggunaan di dalam keadaan, kedudukan dan
generasi masyarakat yang berbeda. Sifat cinta dalam pengertian
abad ke 21 mungkin berbeda daripada abad-abad yang lalu.
Ungkapan cinta mungkin digunakan untuk meluapkan perasaan
seperti berikut:
1. Perasaan terhadap keluarga
2. Perasaan terhadap teman-teman, atau philia
3. Perasaan yang romantis atau juga disebut asmara
4. Perasaan yang hanya merupakan kemahuan, keinginan hawa
nafsu atau cinta eros
5. Perasaan sesama atau juga disebut kasih sayang atau agape
6. Perasaan tentang atau terhadap dirinya sendiri, yang disebut
narsisisme
7. Perasaan terhadap sebuah konsep tertentu
8. Perasaan terhadap negaranya atau patriotisme
9. Perasaan terhadap bangsa atau nasionalisme
Penggunaan istilah cinta dalam masyarakat Indonesia dan
Malaysia lebih dipengaruhi perkataan love dalam bahasa Inggris.
agape dan storge. Namun demikian perkataan-perkataan yang lebih
sesuai masih ditemui dalam bahasa serantau dan dijelaskan seperti
berikut:
1. Cinta yang lebih cenderung kepada romantis, asmara dan
hawa nafsu, eros
2. Sayang yang lebih cenderung kepada teman-teman dan
keluarga, philia
3. Kasih yang lebih cenderung kepada keluarga dan Tuhan,
agape
4. Semangat nusa yang lebih cenderung kepada patriotisme,
nasionalisme dan narsisme, storge
Cinta adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi
yang mendalam. Menurut Erich Fromm, ada empat syarat untuk
mewujudkan cinta kasih, yaitu perasaan, pengenalan, tanggung
jawab, perhatian, saling menghormati.
Untuk menunjukkan cinta kepada Indonesia dan Papua ini
dapat diwujudkan dalam hal yang beragam. Misalnya, dengan tidak
melakukan kekerasan, melakukan hal-hal yang menyebabkan
peperangan, menghormati hak orang lain, menciptakan keadaan
yang aman dan tentram, tidak merusak lingkungan, dll. Keadaan ini
dapat diciptakan bila pada masing-masing individu benar-benar
rasa cinta tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan,
kondisi, dan keahlian.
Keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi
karena konflik antara individu-individu dalam kelompok tersebut
atau karena adanya konflik antara bagian-bagian kelompok tersebut
sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara
kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Ada bagian atau
segolongan dalam kelompok itu yang ingin merebut kekuasaan
dengan mengorbankan golongan lainnya; ada kepentingan yang
tidak seimbang, sehingga timbul ketidak-adilan; ada pula
perbedaan faham tentang cara-cara memenuhi tujuan kelompok
tersebut dan lain sebagainya; kesemuanya itu mengakibatkan
perpecahan di dalam kelompok tadi, sehingga timbullah perubahan
dalam struktrunya. Tercapainya keadaan stabil tersebut sedikit
banyak juga tergantung pada faktor kepemimpinan dan ideologi
yang dengan berubahnya struktur, mungkin juga mengalami
perubahan-perubahan (Soekanto, 1982:157).
Jadi suatu konflik atau masalah dan perebutan kekuasaan
di dalam suatu kelompok masyarakat bukanlah suatu keadaan yang
didasari oleh tanpa sebab. Hal ini merupakan usaha manusia untuk
mendapatkan nilai-nilai dirinya di masyarakat yang ditunjukkan
melalui simbol-simbol atau atribut di atas. Namun, sebaiknya usaha
suatu konflik atau perpecahan apalagi sampai terjadinya kekerasan.
Hal ini dapat didapatkan dengan didasari oleh iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kecintaan kita terhadap bangsa
dan negara serta kecintaan kita terhadap sesama umat manusia.
2.1.4 Papua
Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang
terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur
West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan
negara Papua Nugini atau East New Guinea.
Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua
bagian barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat terutama
oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan separatis yang
ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara
sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah
ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea
atau Dutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia Indonesia, wilayah ini dikenal
sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973.
Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada
saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang
Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No.
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003,
disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan
Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah
Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan
bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun
kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi
wilayah Provinsi Papua pada saat ini.
Sejarah Papua tidak bisa dilepaskan dari masa lalu
Indonesia. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara
Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia.
Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua
merupakan pulau terbesar ke-dua di dunia setelah Greenland.
Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari
Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea,
Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal
sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah
wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas
koloni Inggris. Populasi penduduk diantara kedua negara
sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, namun kemudian
dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.
Pulau Papua banyak mengandung bahan galian golongan
kapur, Gamping, Uranium, dll. Dan juga dengan adanya
tumbukkan lempeng ini sehingga mengangkat banyak fosil makluk
hidup yang berupa Minyak, Gas Bumi dan Batubara. Selain itu,
pulau Papua memiliki Hutan Tropis yang sangat lebat karena
berada pada jalur Katulistiwa serta memiliki hasil laut yang banyak
karena berada di Lautan Pasifik yang sangat luas.
Dari hal inilah yang menyebabkan Pribumi Papua menjadi
melarat di atas kekayaan Alamnya sendiri bagaikan seekor Tikus
yang mati di atas lumbung Padi. Oleh sebab itu, pulau ini menjadi
rebutan setiap bangsa-bangsa dan menjadi daerah konflik yang
berkepanjangan sehingga banyak menimbulkan korban penduduk
asli (Indigenous Peoples) dan pelanggaran-pelanggaran terhadap
hak-hak dasar masyarakat asli Papua.
Pada abad ke-15 sampai ke-17 dan abad ke-18 awal,
Papua dikenal sebagai daerah yang rawan untuk ditempati karena
Penduduknya sangat berbahaya. Oleh karena itu, Papua adalah
merupakan daerah yang belum berpemerintahan sendiri (Non Self
Government Territory). Pada masa itu, banyak timbul peperangan
diantara suku-suku sehingga muncul seorang Panglima Perang
yang hebat, yaitu Mambri dari pulau Biak dibawah komando Raja
Kurabesi.
Peninggalan arkeologi yang tersebar hampir di seluruh
bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. "Jika dikelola dengan
baik, peninggalan arkeologi di Papua yang sangat beragam bisa
menjadi obyek wisata yang menarik para wisatawan untuk
berkunjung ke Papua," kata Peneliti Balai Arkeologi Jayapura,
Klementin Fairyo di Jayapura, Rabu (21/7/2010).
Menurut Klementin, sejauh ini benda cagar budaya yang
terdapat di wilayah Papua belum mendapatkan perhatian dan
pengelolaan yang optimal sebagai aset pariwisata. Padahal, pada
hakikatnya seluruh peninggalan arkeologi tidak ternilai harganya
sebab hanya sekali dibuat pada suatu peristiwa di masa lalu. "Itulah
sebabnya benda-benda cagar budaya harus dilestarikan sehingga
dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan," katanya.
(http://jalanasik.com/content/view/1667/31/)
2.1.5. Makna dan Pemaknaan
Brown dalam Sobur (2001:255-256) mendefinisikan
makna sebagai kecenderungan (disposisi) total untuk menggunakan
atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. Terdapat banyak
bentuk bahasa. Terdpat banyak komponen dalam makna yang
dibangkitkan suatu kata atau kalimat. Namun kita terlebih dahulu
harus membedakan pemaknaan secara lebih tajam tentang
istilah-istilah yang nyaris berimpit antara apa yang disebut (1) terjemah,
Membuat terjemah adalah upaya mengemukakan materi
atau substansi yang sama dengan media yang berbeda, media
tersebut mungkin berupa bahasa yang satu ke bahasa yang lain, dari
verbal ke gambar dan sebagainya. Pada penafsiran, kita tetap
berpegang pada materi yang ada, dicari latar belakangnya,
konteksnya, agar dapat dikemukakan konsep atau gagasannya lebih
jelas. Ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir
manusia untuk mengungkapkan hal dibalik yang tersajikan. Materi
yang tersajikan dilihat dari tanda-tanda atau indikator pada sesuatu
yang lebih jauh lagi. Memberikan makna merupakan upaya lebih
jauh dari penafsiran dan mempunyai kesejajaran dengan
ekstrapolasi. Pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratif
manusia, indrawija, daya pikirnya dan akal budinya. Materi yang
tersajikan seperti juga ektrapolasi, dilihat tidak lebih dari
tanda-tanda atau indikatornya bagi sesuatu yang lebih jauh. Di balik yang
tersajikan bagi ektrapolasi terbatas dalam artian empirik logik,
sedangkan pada pemaknaan dapat pula menjangkau yang etik atau
pun yang transedental.
Semantik adalah ilmu mengenai makna kata-kata, suatu
definisi yang menurut S.I. Hayakawa dalam Mulyana (2001:257)
tidaklah buruk bila orang-orang tidak menganggap bahwa
pencarian makna kata mulai dan berakhir dengan melihatnya dalam
(linguistik), yang punya banyak dimensi, simbol merujuk pada
objek si dunia nyata, pemahaman adalah perasaan subjektif kita
mengenai simbol itu dan referen adalah objek yang sebenarnya
eksis di dunia nyata.
Makna dapat pula digolongkan ke dalam makna konotatif.
Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya (faktual) seperti
yang kita temukan dalam kamus. Karena itu makna denotatif lebih
bersifat publik. Sejumlah kata denotatif, namun banyak kata juga
bermakna konotatif, lebih bersifat pribadi, yakni makna di luar
rujukan objektifnya. Dengan kata lain, makna konotatif lebih
bersifat subjektif daripada makna denotatif.
2.1.6. Teor i-Teor i Makna
Beberapa teori tentang makna dikembangkan oleh Alston
(1964:11-26) dalam Sobur (2001:259) diantaranya adalah:
1. Teori Acuan (Referential Theory)
Teori acuan merupakan salah satu jenis teori makna yang
mengenali atau mengidentifikasi makna suatu ungkapan
dengan apa yang diacunya atau dengan hubungan acuan.
2. Teori Ideasional (The Ideational Theory)
Teori Ideasional adalah suatu jenis teori makna yang
mengenali atau mengidentifikasi makna ungkapan dengan
tersebut. Dalam hal ini, teori ideasional menghubungkan
makna atau ungkapan dengan suatu ide atau representasi
psikis yang ditimbulkan kata atau ungkapan tersebut kepada
kesadaran. Atau dengan kata lain, teori ideasional
mengidentifikasikan makna E (expression atau ungkapan)
dengan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ditimbulkan E
(expression). Jadi pada dasarnya teori ini meletakkan gagasan
(ide) sebagai titik sentral yang menentukan makna suatu
ungkapan.
3. Teori Tingkah Laku (Behavioral Theory)
Teori tingkah laku merupakan salah satu jenis teori makna
mengenai makna suatu kata atau ungkapan bahasa dengan
rangsangan-rangsangan (stimuli) yang menimbulkan ucapan
tersebut. Teori ini menanggapi bahasa sebagai semacam
kelakuan yang mengembalikan pada teori stimulus dan
respon. Makna menurut teori ini, merupakan rangsangan
untuk menumbuhkan perilaku tertentu sebagai respon kepada
rangsangan itu tadi.
Penelitian ini dapat dikatakan berlandaskan pada teori
ideasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya ide atau gagasan yang
datang dari pencipta lagu berdasarkan cerita nyata yang menjadi
inspirasi dalam menciptakan sebuah karya lagu. Melalui cerita
tersebut ke dalam sebuah ungkapan yang dituangkan dalam
lirik-lirik lagu yang penuh makna. Berdasarkan teori idensional, peneliti
berusaha untuk melakukan pemaknaan terhadap lirik lagu “Papua
Dalam Cinta”.
2.1.7. Semiotika dan Semiologi Komunikasi
Kata “Semiotika” berasal dari bahasa dari bahasa yunani,
“semion” yang berarti tanda atau “seme” yang berarti penafsiran
tanda. Semiotika sendiri berakar dari studi klasik dan skolastik atas
seni logika, retorika dan poetika.
Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk
mengkaji suatu tanda. Tanda adalah perangkat yang kita pakai
dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah
masyarakat dan hidup bersama manusia. Semiotika, atau dalam
istilah Barthes, semiologi pada dasarnya hendak mempelajari
bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things).
Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa
informasi, dalam hal nama objek itu hendak berkomunikasi, tetapi
juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Barthes,
1998:179, Kurniawan, 2001:53).
Bagi seseorang yang tertarik dengan semiotik, maka tugas
utamanya adalah mengamati (observasi) terhadap fenomena gejala
Tanda sebenarnya representasi dari gejala yang dimiliki sejumlah
kriteria, seperti : nama (sebutan), peran, fungsi, tujuan, keinginan.
Semiotika seperti kata Lechte (2001:191) adalah teori
tentang tanda dengan penandaan. Lebih jelasnya lagi, semiotika
adalah suatu disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi
yang terjadi dengan sarana signs ‘tanda-tanda’ dan berdasarkan
pada signs system (code) ‘sistem tanda ’(Segers, 2000:4),
Hjelmslev (dalam Chistomy, 2001:7) mendefinisikan tanda sebagai
“suatu keterhubungan antara wahana ekspresi (expression plan)
dan wahana isi (content plan)”. Charles Morris (dalam Segers,
2000:5) menyebutkan semiosis sebagai suatu “proses tandanya,
yaitu proses ketika sesuatu merupakan tanda bagi beberapa
organisme”. Dari beberapa definisi di atas maka semiotik atau
semiosis adalah ilmu atau proses yang berhubungan dengan tanda.
Pada dasarnya semiosis dapat dipandang sebagai suatu
proses tanda dapat diberikan dalam istilah semiotika sebagai suatu
hubungan antara lima istilah, yaitu :
S (s, i, e, r , c)
S adalah untuk semiotic relation (hubungan semiotik); s
untuk sign (tanda); i adalah untuk interpreter (penafsiran); e adalah
untuk effect atau pengaruh; r untuk reference (rujukan); e untuk
2.1.8. Semiologi Roland Bar thes
Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir
strukturalisasi yang getol mempraktikkan model linguistik dan
semiologi saussuren. Ia juga intelektual dan kritikus sastra Perancis
yang ternama, eksponens penerapan struktualisme dan semiotika
pada studi sastra. Barthes (2001:208) menyebutkan sebagai tokoh
yang memainkan peranan sental struktualisme tahun 1960-an dan
70-an. Barthes berpendapat bahasa adalah sebuah sistem tanda
yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu
dalam waktu tertentu. Ia mengajukan pendapat ini dalam writing
Degree Zero (1953, terj. Inggris 1977) dan Critical Essays (1964,
terj. Inggris 1972).
Sedangkan pendekatan karya struktualis memberikan
perhatian terhadap kode-kode yang digunakan untuk menyusun
makna struktualisme merupakan suatu pendekatan yang secara
khusus memperhatikan struktur karya atau seni.
Linguistik merupakan ilmu tentang bahasa yang sangat
berkembang menyediakan metode dan istilah dasar yang dipakai
oleh seseorang semiotikus dalam mempelajari semua sistem-sistem
sosial lainnya. Semiologi adalah ilmu tentang bentuk, sebab ia
mempelajari pemaknaan secara terpisah dari kandungan
Dalam pengkajian tekstual, Barthes menggunakan analisis
naratif struktual yang dikembangkannya. Analisis naratif struktual
secara metologis berasal dari perkembangan awal atas apa yang
disebut linguistik struktural sebagaimana perkembangan akhirnya
dikenal sebagai semiologi teks atau semiotika. Jadi secara
sederhana analisis naratif struktual dapat disebut juga sebagai
semiotika teks karena memfokuskan diri pada naskah. Intinya sama
yakni mencoba memahami makna suatu karya dengan menyusun
kembali makna-makna yang tersebar dengan suatu cara tertentu
(Kurniawan, 2001:89).
Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam
studinya tentang tanda adalah peran pembaca konotasi, walaupun
merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar
berfungsi. Barthes secara panjang lebar mengulas apa yang sering
disebutnsebagai sistem pemaknaan tataran kedua yang dibangun
diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya (Sobur, 2004:68-69).
Sastra merupakan contoh paling jelas sistem pemaknaan
tatanan kedua yang dibangun sebagai sistem yang petama. Sistem
kedua yang dibangun sebagai sistem yang pertama. Sistem kedua
ini oleh Barthes disebut konotatif, yang dalam mitologisnya secara
tegas ia bedakan dari denotatif atau sistem pemaknaan tatanan
1. Signifer (penanda) 2. Signified (petanda)
3. Denotative (tanda denotative)
4. Connotative Sinifer (penanda konotatif) 5. Connotative Signified
(petanda konotatif)
6. Connotative Signifer (tanda konotatif)
Gambar 2.1 Peta Tanda Roland Bar thes
Sumber: Paul Cobley dan Litza Jansa, 1999 dalam Alex Sobur, 2004:69
Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotative
(3) terdiri atas penanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda
denotative adalah juga petanda konotative (4). Dengan kata lain,
hal tersebut merupakan unsur material: jika Anda mengenal tanda
“singa”, barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan
keberanian menjadi mungkin (Cobley dan Janz, 1999:51 dalam
Sobur, 2004:69).
Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak hanya
sekedar memiliki makna tambahan. Namun, juga mengandung
makna kedua bagian tanda denotatif yang melandasi
keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes yang
sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussuren yang
hanya berhenti pada tatanan denotatif.
Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi
dalam pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang
dimengerti oleh Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi
“sesungguhnya” bahkan kadang kala juga dirancukan dengan
referensi atau acuan. Proses signifikasi yang secara tradisional
disebut sebagai denotasi ini biasanya mengacu pada penggunaan
bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang terucap. Akan
tetapi di dalam semiologi Roland Barthes dan para pengikutnya,
denotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru
lebih diasosiasikan dengan keterbatasan makna dan dengan
demikian sebagai reaksi yang paling ekstrim melawan keharfiahan
denotasi yang bersifat operisit ini, Barthes mencoba menyingkirkan
dan menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah konotasi
semata-mata. Penolakan ini mungkin terasa berlebihan, namun ia tetap
berguna bagi sebuah koreksi atas kepercayaan bahwa makna
“harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah (Budiman,
1999:22 dalam Sobur, 2004:70-71).
Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi
ideologi yang disebut sebagai “mitos” dan berfungsi untuk
mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai
dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Budiman,
2001:28 dalam Sobur, 2004:1). Di dalam mitos juga terdapat pula
tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. Namun, sebagai suatu
sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan
tataran kedua. Di dalam mitos pula petanda dapat memiliki
pemunculan sebuah konsep secara berulang-ulang dalam bentuk
yang berbeda-beda.
Semiologi Roland Barthes tersusun atas
tingkatan-tingkatan sistem bahasa. Umumnya Barthes mebuatnya dalam dua
tingkatan bahasa, bahasa dalam tingkatan pertama adalah sebagai
objek dan bahasa tingkat kedua disebut sebagai metabahasa.
Bahasa ini merupakan suatu sistem tanda yang memuat penanda
dan petanda tingkat pertama sebagai petanda baru nada dalam taraf
yang lebih tinggi. Sistem tanda pertama kadang disebutnya sebagai
konotasi atau sistem retoris atau mitologi.
Konotasi dan metabahasa adalah cerminan yang
berlawanan satu sama lain. Metabahasa adalah operasi yang
membentuk mayoritas bahasa-bahasa ilmiah yang berperan dalam
sistem riil, dan dipahami sebagai petanda di luar kesatuan
penanda-penanda asli, di luar alam deskriptif. Sedangkan konotasi meliputi
bahasa-bahasa yang sifat utamanya sosial dalam hal pesan literatur
memberi dukungan bagi makna kedua dari sebuah tatanan
(Kurniawan, 2001:68).
Mengenai bekerjanya tanda dari tatanan kedua adalah
melalui mitos. Mitos biasanya mengacu pada pikiran bahwa mitos
itu keliru, namun pemakaian yang biasanya itu adalah bagi
penggunaan oleh orang yang tak dipercaya. Barthes menggunakan
adalah cerita yang digunakan oleh suatu kebudayaan untuk
menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas suatu
alam. Mitos primitif berkenaan dengan hidup dan mati, manusia
dan dewa, baik dan buruk. Mitos kita yang bertaktik-taktik adalah
tentang maskulininitas dan feminitas, tentang keluarga, tentang
keberhasilan, atau tentang ilmu. Bagi Barthes, mitos merupakan
cara berfikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk
mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Barthes
memikirkan mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep terkait.
Bila konotasi merupakan pemaksaan tatanan kedua dari petanda,
maka mitos pemaknaan tatanan kedua dari petanda (Fiske,
2006:121).
Bentuk
Isi
Gambar 2.2 Dua Tatanan Peta ndaan Bar thes
Sumber : Fiske, 2006:120-123
Pada tatanan kedua, sistem tanda dalam tatanan pertama
disisipkan ke dalam sistem budaya. DENOTASI
PENANDA PETANDA
Barthes menegaskan bahwa cara kerja pokok mitos adalah
untuk menaturalisasikan sejarah. Ini menunjukkan kenyataan
bahwa mitos sebenarnya merupakan produk kelas sosial yang
mencapai dominasi melalui sejarah tertentu. Mitos menunjukkan
makna sebagai alami, dan bukan bersifat historis atau sosial. Mitos
memistifikasi atau mengaburkan asal-usulnya sehingga memiliki
dimensi, dan membuat suatu mitos tersebut tidak bisa diubah, tapi
juga cukup adil (Fiske, 2006:123).
Dalam hal ini “pembaca”lah yang memberikan makna dan
penafsiran. “Pembaca” mempunyai kekuasaan absolut untuk
memaknai sebuah hasil karya (lirik lagu) yang dilihatnya, bahkan
tidak harus sama dengan maksud pengarang. Semakin cerdas
pembaca itu menafsirkan, semakin cerdas pula karya lirik dalam
lagu itu memberikan maknanya. Wilayah kajian “teks” yang
dimaksud Barthes memang sangat luas, mulai bahasa verbal seperti
karya sastra hingga fashion atau cara berpakaian. Barthes melihat
seluruh produk budaya merupakan teks yang bisa dibaca secara
otonom dari penulisnya.
2.1.8.1. Kode Pembacaan
Segala sesuatu yang bermakna tergantung pada
kode. Menurut Roland Barthes di dalam teks biasanya
petanda tekstual (baca:leksia) dapat dikelompokkan.
Setiap atau masing-masing leksia dapat dimasukkan ke
dalam salah satu dari lima kode ini. Kode-kode ini
menciptakan sejenis jaringan. Adapun kode pokok
tersebut yang dengannya seluruh aspek tekstual yang
signifikasi dapat dipahami, meliputi aspek sintagmatik dan
semantik sekaligus, yaitu menyangkut bagaimana
bagian-bagiannya berkaitan satu sama lain dan berhubungan
dengan dunia luar teks.
Lima kode yang ditinjau oleh Barthes adalah
kode hermeneutika (kode teka-teki), kode Proaretik, kode
budaya, kode semantik, dan kode simbolik (Kurniawan,
2001:69).
1. Kode hermeneutik atau kode teka-teki berkisar pada
satuan-satuan yang dengan berbagai cara berfungsi
untuk mengartikulasi suatu persoalan, penyelesainnya,
atau bahkan menyusun semacam teka-teki (enigma) dan
sekedar memberi isyarat bagi penyelesainnya
(Barthes,1990:17). Pada dasarnya kode ini adalah
sebuah kode “pencitraan”, yang dengannya sebuah
narasi dapat mempertajam permasalahan, menciptakan
ketegangan dan misteri, sebelum memberikan
2. Kode proaretik atau kode tindakan lakukan
dianggapnya pelengkapan utama teks yang dibaca
orang, artinya antara lain semua teks yang bersifat
naratif.
3. Kode Gnomik atau kode kultural (budaya) banyak
jumlahnya. Kode ini merupakan acuan teks ke
benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi oleh
budaya. Menurut Barthes, realisme tradisonal
didefinisikan oleh budaya apa yang telah diketahui.
Rumusan suatu budaya adalah hal-hal kecil yang telah
dikondifikasikan (Sobur, 2004:66).
4. Kode Semik atau konotatif banyak menawarkan banyak
sisi. Dalam proses pembacaan, pembaca menyusun satu
tema. Ia melihat bahwa konotasi kata atau fase tertentu
dalam teks dikelompokkan dengan konotasi kata atau
fase yang mirip. Jika melihat kumpulan satuan konotasi
melekat, kita menemukan suatu tema di dalam cerita.
Perlu dicatat bahwa Barthes menganggap bahwa
denotasi sebagai konotasi sebagai yang paling kuat dan
yang paling “akhir”.
5. Kode Simbolik (tema) merupakan suatu aspek
pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural,
struktural. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa
makna berasal dari beberapa oposisis biner atau
pembedaan baik dalam taraf bunyi menjadi fenom
dalam proses produksi wicara, maupun taraf oposisi
psikoseksual yang melalui proses.
2.2 Ker angka Berfikir
Manusia adalah Homo Semioticus dimana masing-masing
individu mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda-beda dalam
memaknai suatu objek atau peristiwa. Manusia dapat memproklamasikan
sesuatu, apa saja sebagai tanda karena hal itu dapat dilakukan oleh semua
manusia (Van Zoest, 1993 : xvi dalam Sobur, 2004: 14).
Oleh karena itu latar belakang pengalaman (field of experience)
dan pengetahuan (frame of reference) yang berbeda pada setiap individu
tersebut. Dalam menciptakan sebuah pesan komunikasi, dalam hal ini pesan
disampaikan dalam bentuk lagu, maka pencipta lagu juga tidak terlepas dari
dua hal di atas.
Begitu juga peneliti dalam memakai tanda dan lambang yang ada
dalam objek, juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki
peneliti melakukan interpretasi tanda yang berbentuk tulisan “Papua Dalam
Cinta” dalam hubungannya dalam pemkanaan dengan menggunakan metode
semiologi dari Roland Barthes, sehingga akhirnya memperoleh hasil dari
Data-data berupa lirik lagu “Papua Dalam Cinta”, kata-kata dan
rangkaian kata dalam lirik lagu tersebut kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode signifikasi dua tahap (two order of signification) dari
Roland Barthes, sehingga akhirnya dapat diperoleh hasil dari interpretasi
data mengenai pemaknaan lirik lagu tersebut. dimana pada tataran pertama
tanda denotatif (denotative sign) terdiri atas penanda dan petanda (signifier
signified) dan pada tataran kedua tanda denotatif (denotative sign) juga
merupakan penanda konotatif (conotative signified) yang akan membentuk
tanda konotatif (conotative signifier) sehingga muncul petanda konotatif
(conotative sign). Dalam tahap kedua dari tanda konotatif akan muncul
mitos yang menandai masyarakat yang berkaitan dengan budaya dan
sekitarnya. Kemudian teks akan dimaknai dengan menggunakan lima
macam kode Barthes, yaitu kode Hermeneutik kode semik, kode simbolik,
kode proatik, dan kode kultural untuk pemaknaan melalui dari pembacaan
dari kode-kode tersebut akan diungkap dalam substansi dari pesan dibalik
lirik lagu “Papua Dalam Cinta”.
Gambar 2.3 Bagan Ker angka Ber pik ir Peneliti