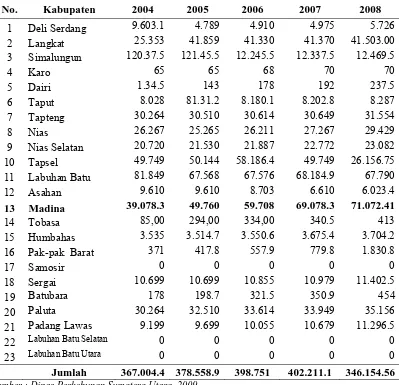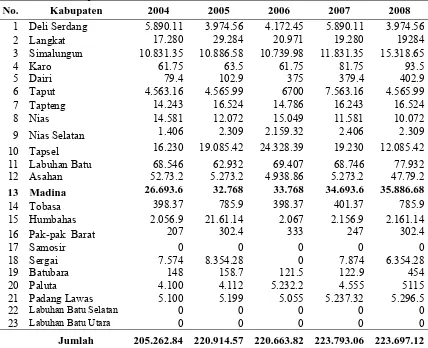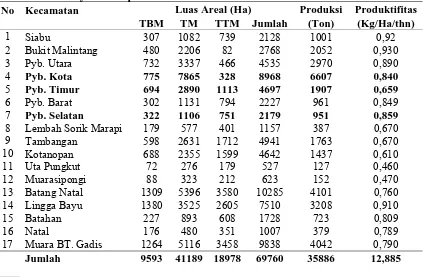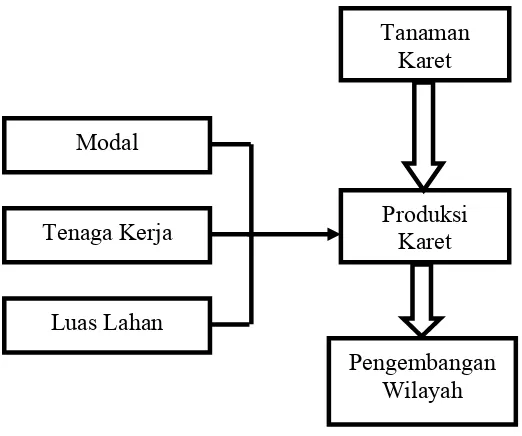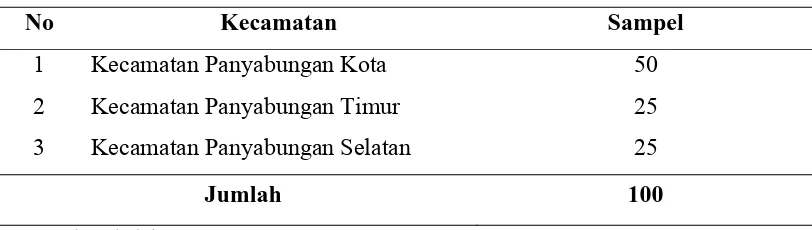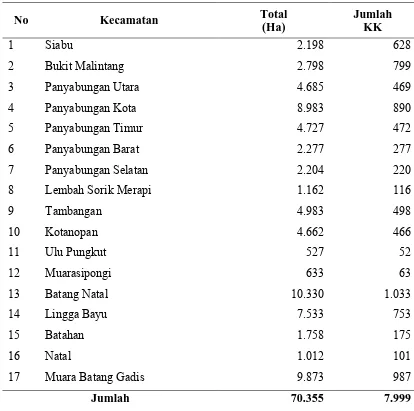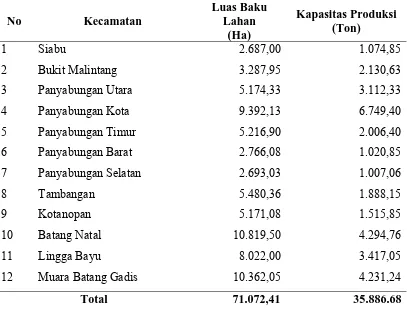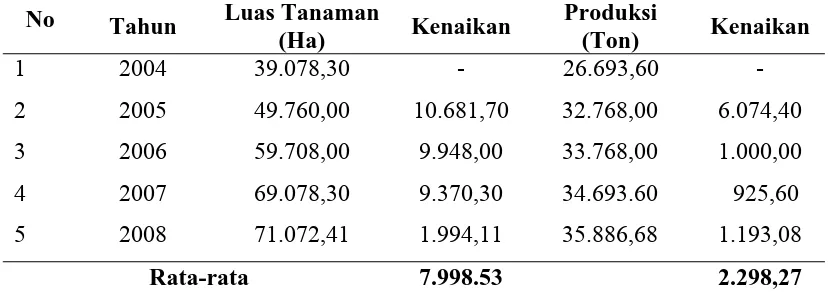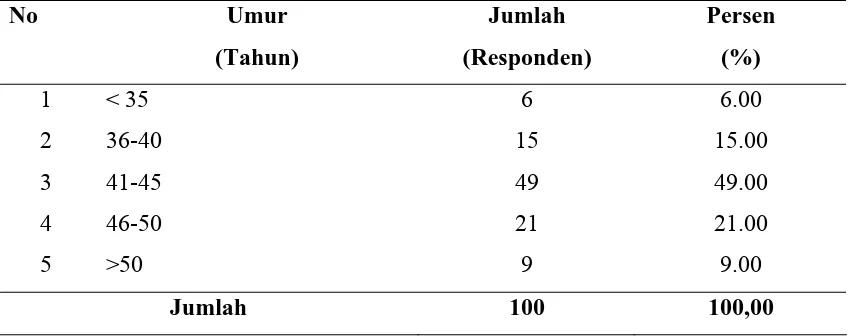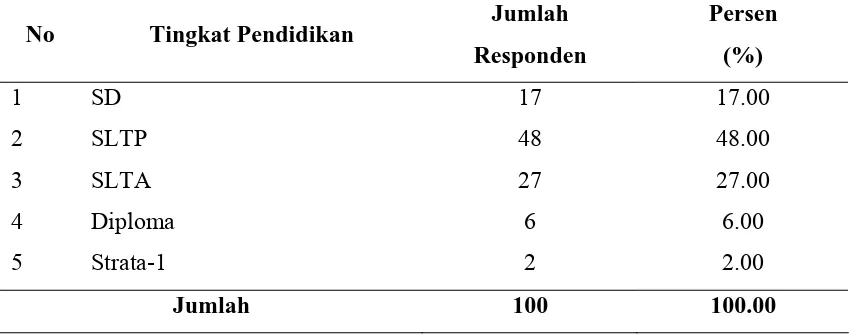PERANAN KOMODITAS KARET TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TESIS
Oleh
ALI SAHBANA
087003002/PWD
S
E K O L A H
P A
S C
A S A R JA
NA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PERANAN KOMODITAS KARET TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh
ALI SAHBANA
087003002/PWD
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridhoNyalah
tesis yang berjudul “PERANAN KOMODITAS KARET TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN MANDAILING
NATAL”, ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Sekolah Pascasarjana Program
Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) Universitas
Sumatera Utara.
Dengan selesainya tesis ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa
hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pembimbing:
Bapak Prof. Ir. Zulkifli Nasution, MSc, Ph.D (Ketua), Bapak Kasyful Mahalli, SE
M.Si (Anggota), dan Bapak Drs. HB. Tarmizi SU (Anggota).
Demikian juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B. MSc., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Bachtiar Hassan Miraza dan Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si.,
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah
dan Perdesaan (PWD) Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ir. Rahmanta, MS, Bapak Ir. Agus Purwoko, MSi dan Drs. Rujiman,
MA., selaku Dosen Pembanding.
4. Kepada seluruh dosen dan pegawai di Program Studi Perencanaan
Pembangunan.
5. Ayahanda Sahaban Nasution dan Ibunda Nurhayani Nasution atas semua
6. Kepada seluruh staff pegawai dinas perkebunan Kabupaten Mandailing Natal,
khususnya Abangda Muhammad Yasir, yang telah membantu penulis dalam
penulisan tesis ini.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan
rendah hati penulis menerima saran dan kritik membangun dari semua pihak demi
kesempurnaan tulisan ini.
Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini memberi arti dan manfaat.
Medan, Pebruari 2010
Penulis
RIWAYAT HIDUP
Ali Sahbana, dilahirkan pada tanggal 22 Desember 1984 di Hutasiantar, Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, sebagai anak Pertama dari empat bersaudara, dari Ayahanda Sahaban Nasution dan (alm) Ibunda Sangkot Lubis.
Pendidikan formal penulis, dimulai dari Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar Negeri 142574 selesai pada Tahun 1997, Sekolah Menengah Pertama pada MTS-MI Panyabungan selesai pada Tahun 2000, Sekolah Menengah Atas pada SMU I Panyabungan selesai pada Tahun 2003, Pendidikan S-1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara selesai pada Tahun 2007.
ABSTRACT
Ali Sahbana, "Role of Rubber as a Commodity in the Regional Economic Development of Mandailing Natal District ", under the supervision of Prof Ir. Zulkifli Nasution, MSc, PhD (Chair), Kasyful Mahalli, SE, MSi (Member), and Drs. HB. Tarmizi, SU (Member).
Rubber is one of the plantation commodities in Indonesia. This commodity has been known and cultured for a relatively longer than the other plantation commodities. In the early period of rubber culturing, Indonesia used to be the first rubber producing country in the world before being replaced by Malaysia which began to culture rubber some time after Indonesia did. The Province of Sumatera Utara is known as one of the natural rubber exporters which exports the rubber produced in various districts. Mandailing Natal District is one of the rubber producing districts whose latex production kept increasing from 2004 to 2008.
The purposes of this study were to examine the influence of work capital, man power, and land area on rubber production and to analyze the role of rubber as a commodity in the regional economic development of Mandailing Natal District.
The research method used in this study was multiple linear regression method. The data for this study were primary data obtained from the rubber smallholders in Mandailing Natal District and secondary data obtained from related institutions.
The result of study showed that work capital, man power, and land area had an influence on rubber production in Mandailing Natal District. Rubber produced by the smallholders canpush output increase and input demand that it can play its role in increasing income, increasing job opportunity, and pushing the regional economic growth of Mandailing Natal District.
This study recommends that the District Government of Mandailing Natal 1) needs to make a policy to increase the response and ability the farmers (smallholders) in developing their rubber plantations through the provision of work capital and the regulation of rubber trade system that can benefit the farmers, 2)needs to improve the rubber processing technology to increase the efficiency that more output (latex) can be produced from the input (rubber) that the farmers have a bargaining power to obtain the biggest economic benefit and are able to compete, and 3) needs to do further research on rubber and its by-products through rubber industry.
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL... viii
DAFTAR GAMBAR... ix
DAFTAR LAMPIRAN... xi
BAB I. PENDAHULUAN... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 7
1.3. Tujuan Penelitian ... 7
1.4. Manfaat Penelitian ... 8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA... 9
2.1 Karet ... 9
2.2. Teori Produksi ... 11
2.3. Modal... 17
2.4. Tenaga Kerja... 18
2.5. Luas Lahan ... 22
2.6. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat... 25
2.7. Konsep Pembangunan Wilayah... 27
2.8. Pembangunan Ekonomi Wilayah ... 31
2.9. Penelitian Terdahulu... 32
2.10. Kerangka Pikir Penelitian ... 38
2.11. Hipotesis Penelitian ... 40
BAB III. METODE PENELITIAN... 41
3.1. Lokasi Penelitian... 41
3.2. Jenis dan Sumber Data ... 41
3.3. Populasi dan Sampel ... 42
3.4. Metode Analisis Data ... 43
3.5. Definisi Variabel Operasional... 45
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN... 46
4.1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal ... 46
4.2. Deskripsi Sektor Pertanian Mandailing Natal... 48
4.3. Kinerja Pengembangan Komoditi Karet... 50
4.3.2. Luas Komoditi Karet... 52
4.4. Karakteristik Responden... 52
4.4.1. Umur ... 52
4.4.2. Tingkat Pendidikan ... 53
4.4.3. Pekerjaan ... 54
4.4.4. Lama Bermukim... 55
4.4.5. Lama Berkebun Karet ... 56
4.5. Sumber Modal ... 57
4.6. Modal... 58
4.7. Tenaga kerja ... 59
4.8. Produksi Karet ... 60
4.9. Luas Lahan ... 60
4.10. Faktor yang mempengaruhi Produksi Karet di Kabupaten Mandailing Natal ... 61
4.11. Peranan Komoditas Karet Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Mandailing Natal ... 66
BABV. KESIMPULAN DAN SARAN... 75
5.1. Kesimpulan ... 75
5.2. Saran ... 75
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1.1 Luas Penanaman TM dan TBM / Ha Perkebunan Karet Rakyat
Menurut Kabupaten di Sumatera Utara 2004-2008 ... 5
1.2. Perkembangan Produksi / Ton Perkebunan Karet Rakyat Menurut Kabupaten di Sumatera Utara 2004-2008 ... 6
2.1. Daftar Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Madina Tahun 2008 ... 10
3.1 Jumlah Sampel ... 43
4.1. Penyerapan Tenaga Kerja Keluarga Dari Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2008 ... 49
4.2. Lokasi Sentra Produksi, Luas Baku Lahan, dan Kapasitas Produksi Komoditi Karet di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2008 ... 51
4.3. Luas Komoditi Karet di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2004 - 2008... 52
4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Umur ... 53
4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan... 54
4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan ... 55
4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bermukim ... 55
4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Berkebun Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal ... 56
4.9. Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Modal Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal ... 57
4.10. Distribusi Responden Berdasarkan Besarnya Modal Awal Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal ... 58
Digunakan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal... 59
4.12. Distribusi Responden Berdasarkan Produksi Perkebunan Karet Rakyat
di Kabupaten Mandailing Natal ... 60
4.13. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan Perkebunan Karet
Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal... 61
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
1 Kuesioner Penelitian ... 82
2 Tabulasi Data ... 84
3 Hasil Uji Regresi ... 87
4 Dokumentasi Penelitian ... 88
5 Peta Kabupaten Mandailing Natal ... 91
ABSTRACT
Ali Sahbana, "Role of Rubber as a Commodity in the Regional Economic Development of Mandailing Natal District ", under the supervision of Prof Ir. Zulkifli Nasution, MSc, PhD (Chair), Kasyful Mahalli, SE, MSi (Member), and Drs. HB. Tarmizi, SU (Member).
Rubber is one of the plantation commodities in Indonesia. This commodity has been known and cultured for a relatively longer than the other plantation commodities. In the early period of rubber culturing, Indonesia used to be the first rubber producing country in the world before being replaced by Malaysia which began to culture rubber some time after Indonesia did. The Province of Sumatera Utara is known as one of the natural rubber exporters which exports the rubber produced in various districts. Mandailing Natal District is one of the rubber producing districts whose latex production kept increasing from 2004 to 2008.
The purposes of this study were to examine the influence of work capital, man power, and land area on rubber production and to analyze the role of rubber as a commodity in the regional economic development of Mandailing Natal District.
The research method used in this study was multiple linear regression method. The data for this study were primary data obtained from the rubber smallholders in Mandailing Natal District and secondary data obtained from related institutions.
The result of study showed that work capital, man power, and land area had an influence on rubber production in Mandailing Natal District. Rubber produced by the smallholders canpush output increase and input demand that it can play its role in increasing income, increasing job opportunity, and pushing the regional economic growth of Mandailing Natal District.
This study recommends that the District Government of Mandailing Natal 1) needs to make a policy to increase the response and ability the farmers (smallholders) in developing their rubber plantations through the provision of work capital and the regulation of rubber trade system that can benefit the farmers, 2)needs to improve the rubber processing technology to increase the efficiency that more output (latex) can be produced from the input (rubber) that the farmers have a bargaining power to obtain the biggest economic benefit and are able to compete, and 3) needs to do further research on rubber and its by-products through rubber industry.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Indonesia yang berada pada ekosistem tropis memiliki iklim tropis (wilayah
dengan ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut), iklim sub tropis (dataran
tinggi) dan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang terkaya di dunia. Dengan
kondisi yang demikian hampir semua produk hayati yang ada didunia dapat
dihasilkan di Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan komparatif (comparative
advantage) pada produk-produk hayati (Saragih, 1999).
Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia. Komoditas
ini sudah dikenal dan dibudidayakan dalam kurun waktu yang relatif lebih lama
daripada komoditas perkebunan lainnya. Sayangnya, posisi Indonesia yang pada awal
pembudidayaan` karet merupakan penghasil karet utama dunia sudah digantikan oleh
Malaysia, yang sebenarnya masih belum lama dalam hal membudidayakan karet
(Siregar, 1995). Luas areal tanaman karet di Indonesia pada tahun 2006 adalah seluas
3,31 juta Ha dengan produksi nasional karet sebesar 2,27 juta Ton karet kering (KK)
dengan produksi terbanyak berasal dari Sumatera (Deptan, 2006). Sumatera Utara
adalah dikenal sebagai salah satu pengekspor karet alam. Karet alam ini berasal dari
berbagai daerah di Sumatera Utara, salah satu diantaranya adalah Kabupaten
Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas daerah 662.070 ha atau 9,23
persen dari wilayah propinsi Sumatera Utara. Ditinjau dari potensi lahan, Kabupaten
Mandailing Natal memiliki potensi yang sangat luas untuk pengembangan tanaman
perkebunan yang terdiri dari tanah milik swasta maupun tanah rakyat. Luas areal
tanaman perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal 111.778,5 Ha yang terdiri dari
Perkebunan Rakyat seluas 96.280,2 Ha dan Perkebunan swasta 15.498,3 Ha,
sehingga pertambahan luas areal selama tahun anggaran 2008 adalah 3.432,77 atau
3,16 persen. Untuk itu luas tanaman perkebunan di kabupaten Mandailing Natal
sebanyak 16,88 persen dari total luas perkebunan Kabupaten Mandailing Natal
(Dinas Perkebunan Madina, 2009). Subsektor perkebunan merupakan subsektor
pertanian yang secara tradisional merupakan salah satu penghasil devisa negara.
Sebagian besar tanaman tersebut merupakan usaha perkebunan rakyat, sedangkan
sisanya diusahakan oleh perkebunan besar baik milik pemerintah maupun milik
swasta (Soetrisno L,1999).
Perkebunan dapat diartikan berdasarkan fungsi pengelolaan. Jenis tanaman
dan produk yang dihasilkan. Berdasarkan fungsi, perkebunan diartikan sebagai usaha
untuk menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, devisa negara dan
pemeliharaan Sumber Daya Alam. Berdasarkan pengelolaan dapat dibagi menjadi
perkebunan rakyat, perkebunan besar milik negara atau swasta, perkebunan
perusahaan inti rakyat dan perkebunan unit pelaksanaan proyek
Produksi karet alam sangat penting dikembangkan karena memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan dengan komoditas lainnya, yaitu : dapat tumbuh pada
berbagai kondisi dan jenis lahan, serta masih mampu dipanen hasilnya meskipun pada
tanah yang tidak subur, mampu membentuk ekologi hutan yang pada umumnya
terdapat pada daerah lahan kering beriklim basah, sehingga karet cukup baik
menanggulangi lahan kritis, dapat memberikan pendapatan harian bagi petani yang
mengusahakannya, memiliki prospek harga yang cukup baik karena kebutuhan karet
dunia semakin meningkat (Deptan, 2006).
Perkebunan rakyat dicirikan oleh produksi yang rendah, keadaan kebun yang
kurang terawat, serta rendahnya pendapatan petani. Rendahnya produktivitas
perkebunan karet rakyat juga disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki oleh
petani, sehingga petani tidak mampu untuk menggunakan teknik-teknik budidaya
yang sesuai dengan syarat-syarat tekhnis yang diperlukan. Dan rendahnya produksi
tanaman karet juga disebabkan oleh usia pohon karet yang sudah sangat tua
(Deptan, 2003).
Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia masih memerlukan
usaha ke arah peningkatan produksi. Salah satu faktor teknis yang perlu
dipertimbangkan adalah rendahnya mutu penyadapan. Kenyataan ini tidak hanya
terjadi pada areal pertanaman karet rakyat, tetapi juga di perkebunan-perkebunan
besar milik pemerintah. Padahal sifat perlakuan teknis penyadapan karet berkaitan
pohon. Pada sisi lain, perkembangan sistem panen tanaman karet yang dilakukan
melalui pelukaan kulit pohon sudah berkembang pesat.
Di Indonesia tampaknya usaha menetapkan penyadapan karet yang benar
masih memerlukan waktu lagi, karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa
penyadapan tanaman karet kita belum sepenuhnya mengikuti pedoman baku.
Kenyataan menunjukkan betapa banyak areal pertanaman karet yang mutu
penyadapannya sangat memprihatinkan. Dengan demikian, selain produksinya rendah
juga umur pohon layak sadap menjadi semakin singkat. Dengan kata lain,
penyadapan tanaman karet di Indonesia merupakan prioritas utama agar pangsa pasar
dan pelestarian produksi dapat diantisipasi (Siregar, 1995).
Perdagangan karet alam memiliki rantai tataniaga yang panjang. Begitu
banyak pihak yang berperan dan ikut menentukan sejak lateks keluar dari kebun
hingga diterima oleh konsumen (pabrik pengolahan). Kejadian-kejadian di dalam
negeri produsen karet seperti sistem politik yang berubah bias ikut berpengaruh.
Jumlah produksi dari beberapa Negara dan jumlah permintaan yang naik atau turun,
perubahan kebijaksanaan stok Negara pembeli, situasi politik Internasional, kondisi
industri yang menggunakan karet sebagai bahan baku, persaingan dengan karet
sintetis, perkembangan situasi moneter internasional, dan perkembangan ekonomi
secara keseluruhan ikut berperan pula. Untuk melihat luas penanaman karet rakyat di
Tabel 1.1. Luas Penanaman TM dan TBM / Ha Perkebunan Karet Rakyat Menurut Kabupaten di Sumatera Utara 2004-2008
No. Kabupaten 2004 2005 2006 2007 2008
1 Deli Serdang 9.603.1 4.789 4.910 4.975 5.726 2 Langkat 25.353 41.859 41.330 41.370 41.503.00 3 Simalungun 120.37.5 121.45.5 12.245.5 12.337.5 12.469.5
4 Karo 65 65 68 70 70
5 Dairi 1.34.5 143 178 192 237.5
6 Taput 8.028 81.31.2 8.180.1 8.202.8 8.287 7 Tapteng 30.264 30.510 30.614 30.649 31.554 8 Nias 26.267 25.265 26.211 27.267 29.429 9 Nias Selatan 20.720 21.530 21.887 22.772 23.082 10 Tapsel 49.749 50.144 58.186.4 49.749 26.156.75 11 Labuhan Batu 81.849 67.568 67.576 68.184.9 67.790 12 Asahan 9.610 9.610 8.703 6.610 6.023.4
13 Madina 39.078.3 49.760 59.708 69.078.3 71.072.41
14 Tobasa 85,00 294,00 334,00 340.5 413 15 Humbahas 3.535 3.514.7 3.550.6 3.675.4 3.704.2 16 Pak-pak Barat 371 417.8 557.9 779.8 1.830.8
17 Samosir 0 0 0 0 0
18 Sergai 10.699 10.699 10.855 10.979 11.402.5
19 Batubara 178 198.7 321.5 350.9 454
20 Paluta 30.264 32.510 33.614 33.949 35.156 21 Padang Lawas 9.199 9.699 10.055 10.679 11.296.5
22 Labuhan Batu Selatan 0 0 0 0 0
23 Labuhan Batu Utara 0 0 0 0 0
Jumlah 367.004.4 378.558.9 398.751 402.211.1 346.154.56 Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Utara, 2009.
Dari Tabel 1.1. diatas luas penanaman karet di Kabupaten Madina dari tahun
2004 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami pertambahan di mana pertambahan
luas lahan tertinggi pada tahun 2005 sebesar 27,33% dan terendah pada tahun 2008
sebesar 2,89% dan sampai dengan tahun 2008 luas lahan karet rakyat sebesar
Untuk melihat produksi karet rakyat menurut kabupaten di Sumatera Utara
dapat di lihat pada Tabel 1.2. berikut ini:
Tabel 1.2. Perkembangan Produksi / Ton Perkebunan Karet Rakyat Menurut Kabupaten di Sumatera Utara 2004-2008
No. Kabupaten 2004 2005 2006 2007 2008
1 Deli Serdang 5.890.11 3.974.56 4.172.45 5.890.11 3.974.56 2 Langkat 17.280 29.284 20.971 19.280 19284 3 Simalungun 10.831.35 10.886.58 10.739.98 11.831.35 15.318.65
4 Karo 61.75 63.5 61.75 81.75 93.5
5 Dairi 79.4 102.9 375 379.4 402.9
6 Taput 4.563.16 4.565.99 6700 7.563.16 4.565.99 7 Tapteng 14.243 16.524 14.786 16.243 16.524 8 Nias 14.581 12.072 15.049 11.581 10.072
9 Nias Selatan 1.406 2.309 2.159.32 2.406 2.309
10 Tapsel 16.230 19.085.42 24.328.39 19.230 12.085.42 11 Labuhan Batu 68.546 62.932 69.407 68.746 77.932 12 Asahan 52.73.2 5.273.2 4.938.86 5.273.2 47.79.2
13 Madina 26.693.6 32.768 33.768 34.693.6 35.886.68
14 Tobasa 398.37 785.9 398.37 401.37 785.9 15 Humbahas 2.056.9 21.61.14 2.067 2.156.9 2.161.14 16 Pak-pak Barat 207 302.4 333 247 302.4
17 Samosir 0 0 0 0 0
18 Sergai 7.574 8.354.28 0 7.874 6.354.28
19 Batubara 148 158.7 121.5 122.9 454
20 Paluta 4.100 4.112 5.232.2 4.555 5115
21 Padang Lawas 5.100 5.199 5.055 5.237.32 5.296.5
22 Labuhan Batu Selatan 0 0 0 0 0
23 Labuhan Batu Utara 0 0 0 0 0
Jumlah 205.262.84 220.914.57 220.663.82 223.793.06 223.697.12
Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Utara,2009.
Dari Tabel 1.2. diatas perkembangan produksi karet di Kabupaten Madina
dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami peningkatan di mana
kenaikan produksi tertinggi pada tahun 2005 sebesar 22,76% dan terendah pada tahun
2007 sebesar 2,74% dan pada tahun 2008 produksi karet rakyat sebesar 35.886.68
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan
menganalisis pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Mandailing Natal melalui
sub sektor perkebunan dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul
“Peranan Komoditas Karet Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah Di
Kabupaten Mandailing Natal”
1.2.Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaruh modal, tenaga kerja dan luas lahan terhadap produksi
karet di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bagaimanakah peranan komoditas karet terhadap pengembangan wilayah di
Kabupaten Mandailing Natal.
1.3.Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat
ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk mengkaji pengaruh modal, tenaga kerja dan luas lahan terhadap
produksi karet di kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengkaji peranan komoditas karet terhadap pengembangan wilayah di
20
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai bahan masukan bagi petani karet tentang pengaruh modal, tenaga
kerja dan luas lahan terhadap produksi karet di Kabupaten Mandailing Natal
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah ataupun lembaga lainnya untuk
menentukan strategi usahatani dan tataniaga, dalam usaha meningkatkan
produksi karet dan pendapatan petani.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang
berhubungan dengan penelitian.
4. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh modal dan
tenaga kerja terhadap produksi karet di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Sebagai bahan pendukung untuk kegiatan penelitian yang sejenis atau
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Karet
Karet alam merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting, baik untuk
lingkup internasional dan teristimewa bagi Indonesia. Di Indonesia karet merupakan
salah satu hasil pertanian terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara.
Hasil devisa yang diperoleh dari karet cukup besar bahkan Indonesia pernah
menguasai produksi karet dunia dengan melibas negara-negara lain dan negara asal
tanaman karet sendiri (Soetedjo R, 1979). Tanaman karet mulai dikenal di Indonesia
sejak 1876. Henry A. Wickham memasukkan beberapa biji karet ke kebun percobaan
pertanian di Bogor, dan kemudian disusul pemasukan bibit-bibit karet berikutnya
tahun 1890, 1896, dan 1898. Walaupun demikian, memerlukan waktu yang cukup
lama untuk membudidayakan tanaman ini
Mula-mula karet berkembang pesat di Malaysia dan Ceylon. Di Indonesia
perkebunan besar karet baru di mulai di Sumatera pada tahun 1902 dan di Jawa
1906. sejak saat itulah perkebunan karet mengalami perluasan yang cepat walaupun
terjadi pula masa suram. Disamping berkembangnya perkebunan besar yang
diusahakan oleh para pengusaha perkebunan, berkembang pula
perkebunan-perkebunan karet yang diusahakan oleh rakyat (petani karet) terutama di luar Jawa,
yang masih banyak tanah ladang yang mudah di jadikan perkebunan-perkebunan
besar karet dapat memperbaiki kembali perkebunannya. Pada tahun 1941, perkebunan
perkebunan besar mencapai produksi 300.000 ton. Dewasa ini, karet merupakan
bahan baku yang mengahasilkan lebih dari 50.000 jenis barang. Dari produksi karet
alam, 46 % digunakan untuk pembuatan ban dan selebihnya untuk karet busa, sepatu
dan dan beribu-ribu jenis barang lainnya ( Setyamidjaja, D,. 1993 ).
Untuk melihat luas areal, produksi dari produktifitas perkebunan karet rakyat
di Kabupaten Madina dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini :
Tabel 2.1 Daftar Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Madina Tahun 2008
Luas Areal (Ha) Produksi Produktifitas No Kecamatan
TBM TM TTM Jumlah (Ton) (Kg/Ha/thn)
1 Siabu 307 1082 739 2128 1001 0,92
Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Madina
Ket : TBM = Tanaman Belum Menghasilkan TM = Tanaman Menghasilkan TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan
Tanaman karet, Hevea brasiliensis Muell. Agr, adalah anggota famili
banyak getah susu. Tanaman karet mengalami gugur daun sekali setahun pada musim
kemarau, di Sumatera Utara terjadi pada bulan Februari-Maret. Setelah gugur daun,
terbentuk bunga bila tanaman karet telah berumur 5-7 tahun, tergantung pada tinggi
tempat di atas permukaan laut. Masa produktif tanaman karet adalah 25-30 tahun
(Sianturi, 2001).
Tanaman karet adalah tanaman daerah tropis. Daerah yang cocok untuk
tanaman karet adalah pada zone antara 15 LS dan 15 LU, curah hujan yang cocok
tidak kurang dari 2000 mm. Optimal 2500-4000 mm/tahun. Tanaman karet tumbuh
optimal di dataran rendah, yaitu pada ketinggian 200 m dpl sampai 600 m dpl dengan
suhu 25-35 C (Setyamidjaja, D, 1993).
2.2. Teori Produksi
Biaya kesempatan adalah nilai sumber daya dalam penggunaan yang terbaik.
Biaya kesempatan perlu dipertimbangkan dalam mengukur seluruh biaya produksi.
Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang berbentuk
kas, sedangkan biaya implisit adalah biaya dikeluarkan dalam proses produksi dalam
bentuk nonkas. Keuntungan ekonomi adalah penerimaan dikurangi semua biaya,
tercakup di dalamnya pengembalian normal untuk manajemen dan modal. Biaya
marjinal adalah perubahan biaya total yang berkaitan dengan perubahan satu unit
output. Sedangkan, biaya inkremental dapat diartikan sebagai tambahan biaya total
Fungsi biaya rata-rata atau unit-1 kadang-kadang lebih berguna dari fungsi
biaya total dalam pengambilan keputusan suatu usaha di sektor pertanian. Fungsi
biaya rata-rata dapat diperoleh dengan membagi fungsi biaya total yang relevan
dengan output. Biaya marjinal adalah perubahan biaya total yang berkaitan dengan
perubahan output (output). Fungsi biaya marjinal berpotongan dengan fungsi biaya
total rata-rata dan fungsi biaya variabel rata-rata di titik minimum ke dua fungsi
tersebut.
Fungsi biaya rata-rata jangka panjang akan:
(a) Menurun, apabila skala pengembalian dalam produksi adalah meningkat,
(b) Konstan, apabila skala pengembalian dalam produksi adalah konstan, dan
(c) Meningkat, apabila skala pengembalian dalam produksi adalah menurun.
Fungsi biaya rata-rata jangka panjang adalah merupakan kurva amplop dari
sejumlah kurva biaya rata-rata jangka pendek. Pada tingkat output yang hasilnya di
spesifikasi tingkat keuntungan ekonomi diperoleh dengan membagi keuntungan
ditambah biaya tetap total dengan kontribusi keuntungan.
Analisis titik impas adalah spesial pada kasus analisis keuntungan di mana
keuntungan diharuskan sama dengan nol. Suatu usaha dapat dikatakan tinggi tingkat
pengungkitannya apabila biaya tetap adalah relatif lebih besar (tinggi) dari pada biaya
variabel. Pada umumnya, penggunaan analisis pengungkitan operasi menyatakan
secara tidak langsung tingginya tingkat risiko keuntungan sepanjang waktu. Dalam
arti kata, peningkatan nilai pengungkitan operasi menyatakan lebih bervariasinya
Menurut Kay (dalam Prayitno, 1986), faktor produksi tenaga kerja terdiri dari
dua unsur yaitu jumlah dan kualitas. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan dapat
dipenuhi dari tenaga kerja keluarga yang tersedia maupun dari luar keluarga.
Sedangkan kualitas yang mencirikan produktivitas tenaga kerja tergantung dari
keterampilan, kondisi fisik, pengalaman dan latihan.
Dalam kasus petani miskin, rendahnya produktivitas tenaga kerja erat
kaitannya dengan kualitas manusianya itu sendiri. Tingkat pendidikan yang rendah,
kekurangan gizi, dan keterbatasan-keterbatasan yang lain merupakan penyebab
rendahnya produktivitas tenaga kerja, lambatnya adopsi teknologi baru, kurangnya
kreatifitas dan rasionalisasi berusaha.
Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang
bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu
hasil pertanian. Modal usahatani terdiri dari modal tetap dan modal kerja untuk
pembelian input variabel yang digunakan dalam proses produksi. Selain tanah, modal
merupakan faktor produksi yang langka bagi petani miskin. Oleh karena itu, rumah
tangga golongan ini diduga hanya mampu mengerjakan jenis-jenis pekerjaan yang
mengandalkan tenaga dan atau sedikit modal.
Petani adalah pemimpin atau manager dalam usahataninya yang mengatur
organisasi produksi secara keseluruhan. Ia memutuskan berapa banyak pupuk yang
dibeli dan digunakan, berapa kali tanah dibajak dan diratakan, berapa kali rumput
disamping tenaga kerja dari keluarga sendiri. Berkaitan dengan itu, maka tingkat
keterampilan petani mempunyai peranan yang sangat penting. Keterampilan
manajemen dari petani dapat diukur dari tingkat pendidikan atau latihan yang pernah
diperoleh.
Keempat faktor produksi tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain
dalam mempengaruhi produksi dan pendapatan petani. Untuk menganalisis pengaruh
faktor produksi tersebut terhadap produksi dan pendapatan petani miskin dapat
digunakan fungsi produksi.
Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan
hubungan antara tingkat output dan tingkat/kombinasi penggunaan input-input.
Analisis dan estimasi hubungan tersebut dikenal sebagai Analisis Fungsi Produksi.
Analisis Fungsi produksi yang paling umum digunakan dalam bidang
pertanian dan lebih dikenal dibandingkan dengan fungsi lainnya. adalah fungsi
produksi Cobb-Douglas. Keunggulan fungsi ini adalah pangkat dari fungsi atau
koefisien βi (i = 1,2 …n) merupakan elastisitas produksi (Ep) yang dapat digunakan
secara langsung dan penjumlahan dari koefisien tersebut dapat menduga bentuk skala
usaha (return to scale) atau tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.
Dengan skala usaha akan dapat diketahui apakah kegiatan suatu usaha tani yang
diteliti dapat mengikuti kaidah increasing, constant atau decreasing return to scale.
Untuk menduga skala usaha atau tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor
produksi dapat digunakan elastisitas produksi. Elastisitas produksi didefinisikan
pendugaan parameter dengan menggunakan model Cobb-Douglas adalah merupakan
elastisitas produksi.
Dalam analisis fungsi produksi, hubungan output dan input biasanya
ditunjukkan dalam bentuk hubungan fungsi sebagai berikut :
Q = f (X1, X2, X3, … Xn)
i Keterangan:
Q = tingkat output/produksi (dependent variable)
X1, X2, X3, … Xn = Faktor produksi atau input (independent variable).
Dari fungsi produksi tersebut dapat dirobah kedalam beberapa bentuk atau
model matematik. Dalam fungsi produksi pertanian pada umumnya hubungan antara
output dan input menunjukkan hubungan yang non linier. Salah satu bentuk fungsi
produksi sederhana yang sering digunakan dalam analisis fungsi produksi pertanian
adalah bentuk fungsi produksi eksponensial yang biasa ditulis :
Q = b0. X1b1. X2b2…. Xnbn.
Q = produksi
X1, X2, … Xn = Faktor produksi
b1, b2, … bn = Koefisien elastisitas produksi
Menurut Hayami-Ruttan (dalam Prayitno, 1986), fungsi eksponensial dapat
dirobah menjadi fungsi produksi linier “ double log “ dengan transformasi logaritma
sebagai berikut :
Keistimewaan bentuk fungsi produksi ini karena mudah interpretasinya yaitu
koefisien dari fungsi produksi sekaligus menunjukkan elastisitas produksi dari faktor
produksi yang bersangkutan, dan koefisien itu juga dapat menunjukkan seberapa
besar hubungan antara tiap faktor produksi terhadap produksi.
Besarnya koefisien elastisitas produksi menunjukkan apakah petani
berproduksi pada tahap yang rasional atau tidak rasional dilihat dari efisiensi tehnis.
Menurut Mubyarto (1979), tahap produksi rasional apabila elastisitas produksi antara
0 < Ep < 1. Apabila elastisitas produksi lebih besar dari satu, maka masih ada
kesempatan bagi petani untuk mengatur kembali kombinasi dan penggunaan faktor
produksi sedemikian rupa sehingga dengan jumlah faktor produksi yang sama dapat
menghasilkan produksi total yang lebih besar. Dalam keadaan demikian, produksi
disebut belum efisien sehingga tidak rasional. Sebaliknya apabila elastisitas produksi
lebih kecil dari nol, maka produksi total sudah mulai menurun dan produksi marjinal
sudah negatif. Keadaan ini disebut tidak rasional karena penambahan penggunaan
faktor produksi justru mengakibatkan produksi total menurun.
Adanya ketiga tahap produksi tersebut, menurut Kay adalah karena adanya
sifat dari fungsi produksi yang dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut “
The Law of Diminishing Return “. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam
input ditambah penggunaannya sedangkan input lain tetap, maka tambahan output
yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan mulai menaik,
yang dihasilkan dari penambahan satu unit variabel tersebut disebut Marginal
Physical Product (MPP) dari input tersebut.
2.3. Modal
Dalam pengertian ekonomi modal adalah barang atau uang yang
bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru.
Karena modal menghasilkan barang-barang baru atau merupakan alat untuk
memupuk pendapatan maka akan menciptakan dorongan dan minat untuk
menyisihkan kekayaannya maupun hasil produksi dengan maksud yang produktif dan
tidak untuk maksud keperluan yang konsumtif.
Dalam pengertian sehari-hari modal diartikan sebagai tabungan masyarakat
yang setiap saat dapat digunakan untuk membeli saham perusahaan atau obligasi
pemerintah ataupun untuk untuk dipinjamkan kepada orang lain. Modal dinyatakan
nilainya dalam bentuk uang yang merupakan sebagai alat pengukur nilai dari modal
tersebut.
Menurut Suryana (2000), akumulasi modal merupakan keharusan bagi
kegiatan/pembangunan ekonomi suatu negara terlebih bagi negara-negara
berkembang, karena pembangunan itu sendiri memerlukan modal. Meskipun
demikian dapat disadari bahwa modal bukanlah satu-satunya yang penting dalam
menggerakkan pembangunan, karena ada beberapa faktor lainnya seperti skill,
enterpreuner, sistem pemerintahan yang efisien, kesanggupan untuk menciptakan dan
Modal diharapkan dapat diciptakan untuk menahan diri dalam bentuk
konsumsi, dengan tujuan pendapatannya akan dapat lebih besar lagi di masa yang
akan datang. Pengembangan pembangunan ekonomi akan terlaksana bila
pembentukan modal berjalan baik. Oleh sebab itu pembangunan yang berhasil akan
tetap berusaha meningkatkan modalnya.
2.4. Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan resources, tepatnya human resources atau sumber
daya manusia yang berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Peranan
tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat besar terhadap perkembangan
ekonomi, demikian pula pada sektor industri yang banyak berorientasi kepada sektor
padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.
Menurut Suryana (2000), bahwa penduduk dapat berperan sebagai sumber
tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, dan tenaga usahawan yang diperlukan
untuk memimpin dan menciptakan kegiatan pembangunan ekonomi. Dengan
demikian penduduk bukan merupakan salah satu faktor produksi saja, tetapi juga
yang paling penting merupakan sumber daya yang menciptakan dan mengembangkan
teknologi serta yang mengorganisir penggunaan berbagai faktor produksi.
Selanjutnya Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa tenaga kerja dan bukan
tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tiap-tiap negara memberikan batasan
umur berbeda. Misalnya, India menggunakan batasan umur 14 sampai 60 tahun. Jadi
orang yang berumur dibawah 14 tahun atau diatas 60 tahun digolongkan sebagai
bukan tenaga kerja.
Menurut Sukirno (2000), bahwa golongan penduduk yang tergolong sebagai
angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15-64 tahun, kecuali: (i) ibu
rumah tangga yang lebih suka menjaga keluarganya daripada bekerja, (ii) penduduk
muda dalam lingkungan umur tersebut yang masih meneruskan pelajarannya di
sekolah atau universitas, (iii) orang yang belum mencapai umur 65 tetapi sudah
pensiun dan tidak mau bekerja lagi, (iv) pengangguran sukarela-yaitu golongan
penduduk dalam lingkungan umur tersebut yang tidak secara aktif mencari pekerjaan.
Selanjutnya Dumairy (1997), mengatakan tenaga kerja dipilah ke dalam dua
kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan
kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau
mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan mencari
pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau
penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan
sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah
(pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tetapi
bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya
Pengertian tenaga kerja dalam (www.nakertrans.go.id) adalah: Setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja
guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU
tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk
melakukan pekerjaan.
Pengertian bekerja menurut indikator ketenagakerjaan adalah: “Jika telah
melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau
keuntungan paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama satu minggu yang
lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu
dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi”.
Menurut BPS (2001) membagi tenaga kerja (employed) atas 3 (tiga) macam,
yaitu:
a) Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah
jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan
uraian tugas.
b) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah
tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu.
c) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed),
adalah tenaga kerja dengan jam kerja ≤ 1 jam per minggu.
Simanjuntak (1998) menyatakan Tenaga kerja atau manpower terdiri dari
angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force terdiri dan:
(1) golongan yang bekerja, (2) golongan yang menganggur atau mencari pekerjaan.
Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari: (1) golongan bersekolah, (2) golongan
yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan.
menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering juga
dinamakan potential labor force.
Transformasi dari bukan angkatan kerja ke angkatan kerja (terutama bagi
tenaga kerja wanita) sangat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain:
a) Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin besar
keinginannya untuk masuk dalam pasar kerja.
b) Tingkat sosial yang lebih tinggi, mempunyai perasaan rendah diri apabila tidak
bekerja.
c) Kondisi ekonomi rumah tangga yang mengharuskan wanita bekerja.
d) Semakin panjang usia harapan hidup.
e) Adanya fasilitas atau kemudahan-kemudahan lain yang tersedia menyebabkan
waktu yang dibutuhkan untuk mengurus rumah tangga berkurang sehingga
peluang untuk bekerja diluar rumah sangat besar.
f) Banyak terbuka lapangan kerja baru.
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di
Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang ikut
berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna
memenuhi kebutuhan masyarakat.
2.5. Luas Lahan
Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam usaha
Hakim (1986), mengatakan bahwa pengertian lahan (land) tidak sama dengan
tanah (soil). Lahan (land) mencakup pengertian yang lebih luas yaitu meliputi seluruh
kondisi lingkungan seperti iklim, sumber air, tanah, tofografi, dan sebagainya.
Sedangkan tanah (soil) merupakan benda alam yang mempunyai sifat fisik, kimia dan
biologi tertentu, berdimensi tiga dan merupakan bagian dari lapisan bumi terluar. Jadi
lahan dapat mencakup berbagai jenis tanah.
Menurut Rayes (2007), dalam kaitan sumberdaya alam dikenal istilah tanah
dan lahan yang pengertiannya sering rancu. Dikatakan bahwa pengertian lahan lebih
luas dari tanah, dimana sumberdaya lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang
terdiri atas iklim, topografi, tanah, hidrologi dan vegetasi dimana pada batas-batas
tertetu mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Dengan demikian dalam
pengertian lahan tanah termasuk di dalamnya.
Nuhung (2006), menyebutkan lahan sebagai faktor produksi utama dan
merupakan barometer untuk mengukur kemajuan petani selaku pelaku utama
pembangunan pertanian.
Rayes (2007) permasalahan utama yang berhubungan dengan usaha pertanian
adalah tersedianya luas lahan yang relatif tetap. Sementara dengan meningkatnya
kebutuhan manusia akan pangan yang diproduksi dari lahan tersebut, menyebabkan
meningkatnya tekanan terhadap lahan. Lahan merupakan faktor produksi yang tidak
dapat digantikan dengan media lain. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah penting
mengetahui tingkat kesesuaian dan faktor-faktor pembatasnya untuk penggunaan
Suparmoko (1997), berpendapat bahwa manusia umumnya mulai mengolah
tanah dari yang paling subur terlebih dahulu, kemudian kalau tanah yang paling subur
itu sudah langka adanya, maka manusia beralih ke tanah yang tingkat kesuburannya
lebih rendah yang produktivitas lahannya semakin merosot. Sebagian besar petani
mengusahakan lahan pertanian dengan luas lahan yang sempit sehingga tidak mampu
mengangkat kesejahteraan petani, sementara masih banyak lahan marginal yang dapat
diolah ataupun diusahai.
Danarti (1999), bahwa dalam situasi krisis ekonomi berkepanjangan yang
terjadi akhir-akhir ini, lahan tidur ibarat tambang emas yang dincar banyak orang.
Dari lahan tersebut dapat dihasilkan komoditas pertanian yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan peluang pasar cukup baik.
Menurut Direktorat Jendral Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen
Pertanian (2008), bahwa banyak terdapat lahan-lahan pertanian terlantar atau lahan
yang sementara belum diusahakan secara optimal yang apabila diberikan sentuhan
teknologi maka lahan dimaksud dapat menghasilkan produksi yang optimal pula.
Upaya dimaksud disebut sebagai lahan optimasi lahan.
Kegiatan optimasi lahan merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan
sumberdaya lahan menjadi lahan usaha tani baik tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, perternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung
lahan sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. Kegiatan
tentang lahan, perbaikan fisik dan kimia tanah bahkan kepada peningkatan
infrastruktur usaha tani yang diperlukan.
Hakim (2002), mengemukakan bahwa sumberdaya lahan yang semakin
langka mendorong perilaku persaingan masyarakat ekonomi ke arah yang semakin
tidak sehat dan cenderung merusak. Konsentrasi penguasaan sumberdaya lahan pada
pihak-pihak tertentu semakin memperbesar porsi masyarakat yang terperdayakan
karena kehilangan akses terhadap sumberdaya dasarnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam konteks agribisnis, aspek pokok yang
akan ditelaah terutama adalah menyangkut pemilikan/penguasaan lahan serta pola
penggunaan lahan. Perlu dilihat sejauh mana aspek-aspek ini menentukan kinerja
sistem, dan selanjutnya ditentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang bagaimana
yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan kondisi riil pola pemilikan/
penguasaan serta pengguna lahan yang ada sehingga kinerja sistem semakin
meningkat.
Rahmawaty (2002), mengatakan bahwa upaya pemanfaatan lahan dalam
rangka pembangunan pertanian khususnya pertanian tanaman pangan tidak hanya
terbatas pada upaya peningkatan produksi dengan menggunakan lahan subur, tetapi
juga diarahkan pada pamanfaatan lahan marginal dan harus mempertimbangkan
keberlanjutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
Menurut Rossiter (1994), penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensinya
akan mengakibatkan produktivitas menurun, degradasi kualitas lahan dan tidak
untuk mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemanfaatan
sumberdaya lahan perlu disesuaikan dengan kondisi agroekologinya, agar usaha
pertanian tersebut dapat berkesinambungan.
Menurut Barlowe (1986), faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan
lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor
institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik
seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan
kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan
pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan
politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.
2.6. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Menurut Sumodiningrat (1997), pemberdayaan merupakan upaya untuk
membangun potensi dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan
kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Selanjutnya Mas"oed (1993), mendefinisikan pemberdayaan rakyat sebagai
upaya memberi daya atau kekuatan kepada rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat
harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan 3 jalur.
1. Menciptakan suasana atau lklim yang memungkinkan potensi rakyat dapat
berkembang.
3. Pemberdayaan bermakna pula melindungi, artinya dalam proses pemberdayaan
harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah.
Pemberdayaan ekonomi rakyat harus disertai dengan menciptakan
peluang-peluang bagi masyarakat lapisan bawah yang ada untuk berpartisipasi dalam
pembangunan. Dengan demikian daerah mampu mengatasi keterbelakangan
masyarakatnya dan memperkuat posisi daya saing mereka dalam bidang ekonomi.
Secara sederhana, pembangunan daerah dapat diartikan sebagai upaya sistematis
untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat suatu daerah ke arah
yang lebih baik secara terus menerus. Dalam upaya itu, kebijakan umumnya terfokus
pada pengembangan aspek-aspek ekonomi dari kehidupan manusia, sehingga
pembangunan daerah seringkali disebut juga sebagai pembangunan ekonomi daerah.
Pembangunan ekonomi masyarakat dipahami sebagai perubahan struktur dan
upaya peningkatan kemampuan masyarakat, penguasaan teknologi, dan pembentukan
modal (capital accumulation). Perubahan tersebut merupakan kunci dari
pengembangan ekonomi masyarakat yang tumbuh berkembang.
Peningkatan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat suatu daerah bukan
merupakan tanggungjawab aparat daerah saja. Dalam pemberdayaan pembangunan
ekonomi masyarakat, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah harus
proaktif, secara terus menerus melakukan tindakan-tindakan pemberdayaan ekonomi
masyarakat didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (potensi
sumberdaya manusia, potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sarana/prasarana
pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah dalam proses pembangunan
untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan
ekonomi masyarakat.
Menurut Sumodiningrat (1997), setiap anggota masyarakat disyaratkan
berperan serta dalam proses pembangunan (full employment), mempunyai
kemampuan yang sama (equal productivity) dan bertindak rasional (efficient).
Selanjutnya menurut Tjiptoherijanto (1999), bahwa kelompok usaha produktif
hanya akan tumbuh dan berkembang jika ada: a) Potensi penduduk yang berbakat dan
memiliki kemampuan berusaha atau berwiraswasta, b) Rangsangan untuk melakukan
inovasi, dan c) Iklim yang memungkinkan realisasi potensi kewirausahaan atau
kewiraswastaan.
2.7. Konsep Pembangunan Wilayah
Peningkatan produksi memang merupakan salah satu ciri produk dalam proses
pembangunan, selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses
pembangunan mencakup perubahan komposisi produksi, perubahan pada pola
pengguflaan (alokasi), sumberdaya produksi (productive resources) diantara
sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian (distribusi), kekayaan dan
pendapatan diberbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka
kelembagaan (institusional framework) dalam kehidupan masyarakat secara
Wilayah sebagai suatu kesatuan geografis memiliki potensi bagi
dijalankannya suatu aktifitas pembangunan dan pengembangan wilayah. Dan wilayah
(region) juga merupakan suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan.
Pengertian unit geografi adalah ruang sehingga bukan merupakan aspek fisik tanah
saja, tetapi lebih dan itu meliputi aspek-aspek lain seperti, ekonomi, biologi, sosial
dan budaya (Wibowo dan Soetriono, 2004).
Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan
dalam arti yang seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang
sebagian dan keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu
masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi suatu usaha masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi, mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya
dan keseluruhan usaha-usaha pembangunan juga meliputi pembangunan social,
politik dan kebudayaan.
Dengan demikian pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya
didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita
penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Todaro, 2000).
Dengan demikian pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting yaitu:
1. Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus.
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
Suatu perekonomian baru dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan
bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus Menurut
Todaro (2000) kekacauan politik dan kemunduran sektor ekspor, misalnya dapat
mengakibatkan kemunduran suatu perekonomian dalam tingkat kegiatan
ekonominya.
Pembangunan wilayah pada kondisi demikian, memerlukan adanya
penanggulangan yang terkoordinasi. Cara pemecahannya yaitu melalui upaya
penggalian dan pembangunan potensi-potensi yang secara terkoordinasi atau terpadu.
Hal inilah yang menyebabkan perlu adanya konsep pembangunan yang bersifat
regional.
Menurut Tarigan (2003) setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah
lebih bebas dalam menetapkan sektor atau komoditi yang diprioritaskan
pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk sector yang memiliki
keunggulan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan
dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang, sehingga perekonomian
daerah dapat berkembang dan stabil.
Pertumbuhan ekonomi biasanya diulas dalam bentuk total barang dan jasa
yang dihasilkan oleh seluruh warga atau masyarakat pada suatu wilayah, sehingga
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayahnya, dan bahkan dapat mengekspor
barang dan jasa tersebut. Ini menunjukkan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi
wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk
maupun lasa ke luar wilayah, baik keluar wilayah dalam Negara itu maupun ke luar
uang dan wilayah lain, termasuk dalam penghasilan ekspor. Kegiatan ekspor adalah
semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan
uang dan dan luar wilayah (Tarigan,2003).
Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terarah secara berkelanjutan akan
mampu meningkatkan kemampuan wilayah tertentu untuk berkembang, dimana
perkembangan wilayah tersebut salah satu pilar utamanya adalah perkembangan
ekonomi wilayah. Pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya
untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar
wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah.
Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi,
budaya dan geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah
lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi,
potensi dan permasalahan wilayah bersangkutan (Riyadi, 2002).
Demikian halnya Hartshorne dalam Fadillah (2001) memformulasikan
wilayah sebagai suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam beberapa aspek tertentu
berbeda dengan area lain. Unit area ini adalah merupakan obyek yang konkrit dengan
kerakteristik yang unik.
Demikian halnya pengembangan wilayah tersebut harus menselaraskan
penggunaan potensi daerah secara baik dan benar, hal mi sesuai dengan pendapat
Miraza (2000) bahwa pengembangan wilayah adalah pemanfaatan potensi wilayah,
baik potensi alam maupun potensi buatan, harus dilaksanakan secara fully dan
kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dalam hal ni perlunya dititik beratkan
adanya pelaksanaan secara eficiency yang artinya pengembangan dan pembangunan
tersebut harus diarahkan secara tepat guna untuk kepentingan bersama.
Tujuan utama dan pengembangan wilayah adalah menyerasikan berbagai
kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan
sumberdaya yang ada di dalamnya dapat optimal mendukung kegiatan kehidupan
masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan
(Riyadi, 2002).
2.8. Pembangunan Ekonomi Wilayah
Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan
daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah
pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri,
termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi
pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di
pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi
wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari
berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana
pembangunan ekonomi daerah (Darwanto, 2008).
Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi
bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah
yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk
mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya,
akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi
pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja
pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan,
pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga
tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.
Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan
jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu
mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan
bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar
pengembangan ekonomi wilayah yang perlu diperhatikan adalah:
1. Mengenali ekonomi wilayah
2. Merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.
(Darwanto, 2008)
2.9. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang telah dilakukan terhadap tanaman karet, menunjukkan bahwa
perkembangan produksi tanaman karet masih sangat layak untuk dikembangkan,
sehingga produksi karet di Indonesia dapat ditingkatkan kembali, beberapa penelitian
Hutagalung, (1993) melakukan peneletin terdahulu berjudul ”Beberapa
Masalah Tata Produksi Dan Pemasaran Karet Rakyat di Kecamatan Padang
Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan “. Menunjukkan bahwa penambahan luas
tanah garapan dan penggunaan input biaya produksi dalam usaha petani karet masih
dapat menaikkan produksi dan pendapatan petani. Penelitian ini juga menyimpulkan
bahwa pendapatan petani karet masih dapat ditingkatkan lagi dengan pendayagunaan
seluruh potensi sumberdaya yang mereka miliki baik sumberdaya alam maupun
sumberdaya manusia. Perlunya pemerintah mengadakan perbaikan sistem pemasaran
berupa mempersingkat saluran tata niaga yaitu dengan memanfaatkan lembaga
koperasi, kebijakan perpajakan, ekspor, dan lain-lain. Kurangnya peremajaan petani
terhadap karet yang sudah tua, akhirnya pendapatan petani merosot.
Sitepu (2007) melakukan peneletin terdahulu berjudul ”Analisis Produksi
Karet Alam (Havea Brasiliensis) Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah”. Karet
merupakan komoditi yang memiliki pasar yang cukup besar, baik dalam negeri
maupun luar negeri. Produksi Indonesia banyak ditunjang oleh adanya perkebunan
karet rakyat akan memiliki arti yang penting sekali didalam upaya peningkatan
pendapatan kesejahteraan petani serta upaya peningkatan devisa serta prekonomian
Indonesia pada umumnya. Berkaitan dengan pengembangan budidaya tanaman karet
diwilayah Sumatera Utara, penlitian ini di fokuskan pada pengaruh permintaan pasar,
harga karet, dan tenaga kerja terhadap luas lahan dan produksi karet.
Subjek penelitian ini adalah keseluruhan perkebunan karet di Sumatera Utara.
luas lahan dan produksi karet. Objek Penelitian ini adalah luas lahan dan produksi
karet Sumatera Utara sebagai indikator pengembangan perkebunan karet di Sumatera
Utara. Pengujian hipotesa penelitian menggunakan metode analisis statistik dengan
regresi ganda. Memperhatikan pengaruh pasar terhadap pengembangan wilayah di
Sumatera Utara, maka disarankan a) Perlu dibuat beberapa kebijakan oleh pemerintah
Propinsi Sumatera Utara maupun pengelola perdagangan karet alam untuk
meningkatkan perkebunan karet, melalui pemberian modal usaha serta pengaturan
sistem perdagangan karet alam yang memberikan keuntungan bagi petani, b) Perlu
diupayakan kebijakan yang menyangkut pengembangan industri produk turunan karet
alam.
Rahmanto (2004) melakukan penelitian dengan judul ” Dampak Liberalisasi
Perdagangan Global dan Perubahan Kondisi Ekonomi-Politik Domestik Terhadap
Dinamika Perdagangan Luar Negeri Kelompok Komoditas Berbasis Pertanian di
Indonesia”. Pengaruh periode krisis ekonomi (1997-2002) terhadap kelompok
komoditas hasil perkebunan seperti karet yang tadinya mengalami kondisi defisit
cenderung bersifat positif atau berdampak mengurangi defisit, kecuali untuk
kelompok komoditas gula masih berpengaruh meningkatkan defisit, meskipun tidak
nyata secara statistik. Kondisi yang demikian diperkirakan disebabkan oleh
penurunan volume impor yang cukup signifikan sebagai akibat schock depresiasi
rupiah terhadap Dollar Amerika yang tajam dan berfluktuasi, sedangkan pengaruh
periode krisis ekonomi terhadap kelompok komoditas yang tadinya mengalami
untuk kelompok komoditas karet dan hasil olahannya berpengaruh sangat nyata
menurunkan surplus, sedangkan untuk kelompok komoditas lemak dan minyak
nabati/hewani serta buah dan kacang-kacangan yang dapat dimakan berpengaruh
nyata meningkatkan surplus.
Sadikin, dkk (2005) melakukan penelitian dengan judul ”Dampak
Pembangunan Perkebunan Karet Rakyat Terhadap Kehidupan Petani di Riau”.
Proses pembangunan wilayah (daerah) di Provinsi Riau sering menghadapi banyak
masalah yang cukup komplek. Selain luasnya wilayah dan banyak Pulau,
permasalahan muncul karenan disebabkan oleh adanya keragaman aksesibilitas antar
daerah, teknologi, sumberdaya manusia dan tingkat perkembangan pembangunan.
Keadaan seperti ini lebih kentara di daerah pedesaan. Di mana sebagian besar
masyarakat Riau yang tinggal di pedesaan adalah sebagai petani karet-rakyat yang
umumnya tingkat kesejahteraan mereka masih dalam kondisi yang memprihatinkan.
Sejauh ini strategi dan langkah kebijakan Pemerintah untuk membangun dan
mengembangkan perkebunan karet-rakyat telah dilaksanakan, seperti (a)
Pembentukan pusat-pusat pengolahan karet di beberapa daerah sentra produksi
dengan tujuan menampung dan mengolah lateks dari hasil perkebunan rakyat dan
untuk memperbaiki mutu olahannya, (b) Melakukan pembinaan perkebunan rakyat
dengan membentuk unit pelaksana proyek (UPP) yang lebih populer di Propinsi Riau
dikenal dengan proyek SRDP. Meskipun program ini berfungsi sebagai pembinaan
petani-karet secara menyeluruh dari masalah budidaya sampai ke persoalan
manfaat kepada petani kebun, terlebih lagi bagi masyarakat miskin lain di pedesaan.
Penyebabnya adalah; strategi pembangunan perkebunan lebih condong/berorientasi
kepada peningkatan produksi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan
memperbesar devisa negara. Sementara, aspek persoalan sosial kemasyarakatan
seperti lembaga-lembaga lokal dan berbagai relasi produksi di tingkat lokal yang
terkait langsung dengan upaya meningkatkan tarap kehidupan masyarakat di
pedesaan terkesan diabaikan.
Dirjen Perkebunan (2007) melihat perkembangan baik dari segi konsumsi
maupun produksi karet dunia, dalam tahun-tahun mendatang dipastikan masih akan
terus meningkat. Indonesia merupakan penghasil karet sekaligus sebagai salah satu
basis manufaktur karet dunia. Tersedianya lahan yang luas memberikan peluang
untuk menghasilkan karet alami yang lebih besar lagi dengan menambah areal
perkebunan karet. Tetapi lebih utama dari itu, produksi karet alam bisa ditingkatkan
dengan meningkatkan teknologi pengolahan karet untuk meningkatkan efisiensi,
dengan demikian output (latex) yang dihasilkan dari input (getah) bisa lebih banyak
dan menghasilkan material sisa yang semakin sedikit. Meskipun pasar karet alam
lebih sedikit dibanding dengan pasar karet sintetik, namun produksi maupun
konsumsi karet alam masih cukup besar. Salah satu kelebihan dari karet alam antara
lain dilihat dari segi kestabilan harganya yang tidak terpengaruh secara langsung oleh
harga minyak dunia. Tidak demikian halnya dengan harga karet sintetik yang terkena
Parhusip (2008) potensi pasar karet alam dalam jangka panjang masih cukup
baik yang disebabkan kebutuhan karet merupakan kebutuhan dasar dalam keperluan
sehari-hari dan beberapa negara berkembang mengalami pertumbuhan industrialisasi
yang cukup tinggi seperti Cina, India dan Brasil. Pergerakan harga karet dunia juga
menunjukkan tren positif dan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar karet
diharapkan dapat bekerjasama dengan produsen lain untuk dapat menjaga posisi
harga yang tetap menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan strategi
mengurangi frekwensi sadapan karet atau mengatur perluasan/peremajaan lahan agar
lebih optimal dapat mengatur pasokan ke pasar internasional. Pengembangan karet
alam diharapkan dapat dioptimalisasi melalui kedua line usaha baik on farm maupun
off farm. Permasalahan produktivitas lahan merupakan permasalahan utama dalam
pengembangan on farm termasuk kualitas bahan baku olahan yang masih rendah.
Kondisi tersebut diharapkan dapat dijembatani dengan pola plasma antara perkebunan
rakyat dengan perkebunan besar dalam peningkatan hasil dan harga. Pola plasma
tersebut diharapkan juga dapat menjembatani perbankan dalam pemberian fasilitas
kredit terkait dengan kemampuan manajemen dan jaminan yang selama ini masih
menjadi kendala utama dalam meningkatkan kemampuan permodalan perkebunan.
Menghadapi tantangan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis
keuangan global, Indonesia sebagai salah satu produsen utama karet alam diharapkan
dapat mengoptimalkan kondisi pasar karet jangka panjang melalui peningkatan
produktivitas lahan dan kebijakan yang mendukung seluruh aspek komoditas karet
Damanik (2000) melakukan penelitian dengan judul penelitian ” Analisis
Dampak Pengembangan Komoditas Perkebunan Terhadap Perekonomian Wilayah di
Propinsi Sumatera Utara ” (1). Komoditas perkebunan di propinsi Sumatera Utara
merupakan komoditas ekspor. Oleh karena pemasukan devisa negara melalui ekspor,
adalah hal yang sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengurangi
defisit neraca pembayaran. Komoditas perkebunan tetap perlu dikembangkan
terutama pada wilayah yang relatif mempunyai tingkat pendapatan dan kesempatan
kerja yang tinggi dibanding wilayah lainnya, sehingga dengan cara demikian selain
ada pemasukan devisa untuk negara juga dapat dijadikan instrument dalam
mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di propinsi Sumatera Utara. (2).
Komoditas perkebunan dalam menciptakan nilai tambah (pendapatan) dan
kesempatan kerja lebih rendah dibandingkan sektor pertanian. (3). Komoditas
pertanian yang berorientasi pada pasar domestik seperti padi, ternak, kelapa dan
sayuran serta buah-buahan pada umumnya mempunyai kemampuan dalam
menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja yang tinggi.
2.10. Kerangka Pikir Penelitian
Pembangunan suatu wilayah hendaknya Iebih memperhatikan potensi yang
ada di wilayahnya. Pembangunan yang berbasis kemampuan dan potensi wiayah itu
sendiri pada gilirannya akan semakin memperkokoh ekonomi wilayah itu sendiri.
Demikian hanya Kabupaten Mandailing Natal yang sejak lama dikenal sebagal