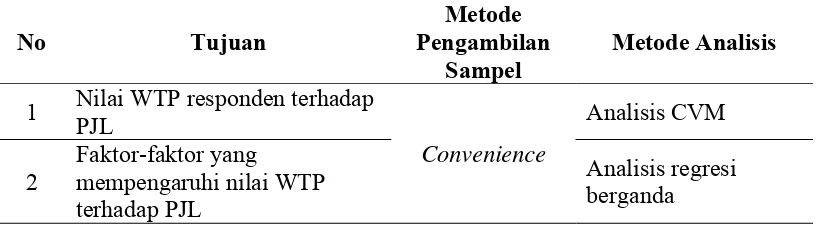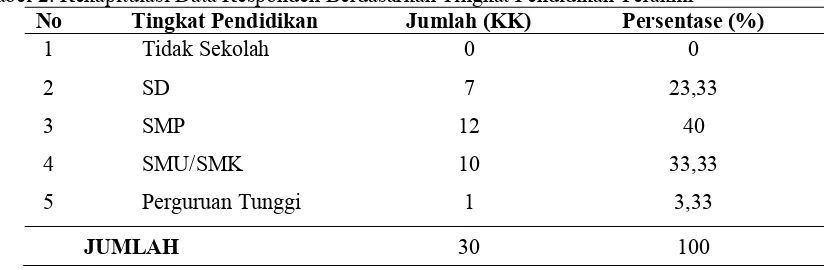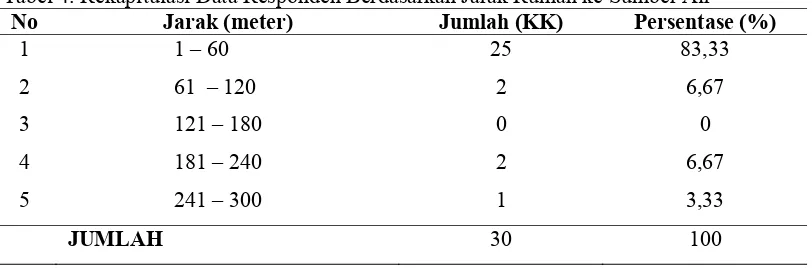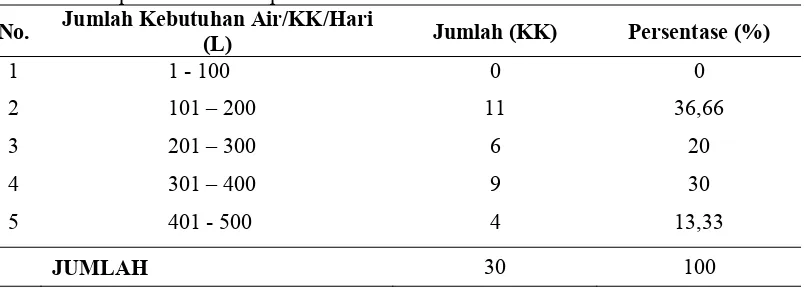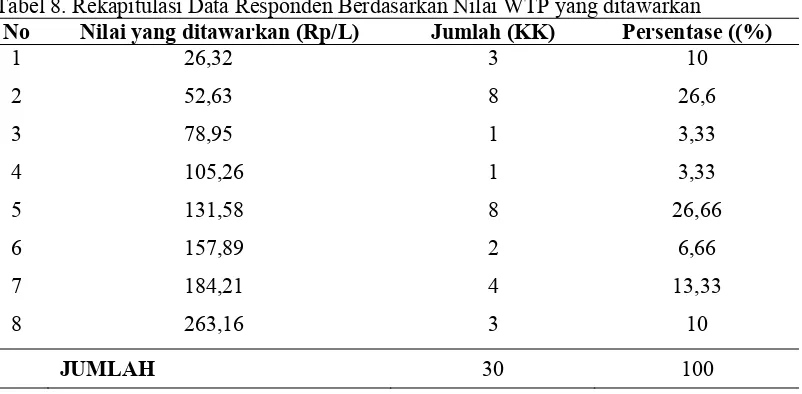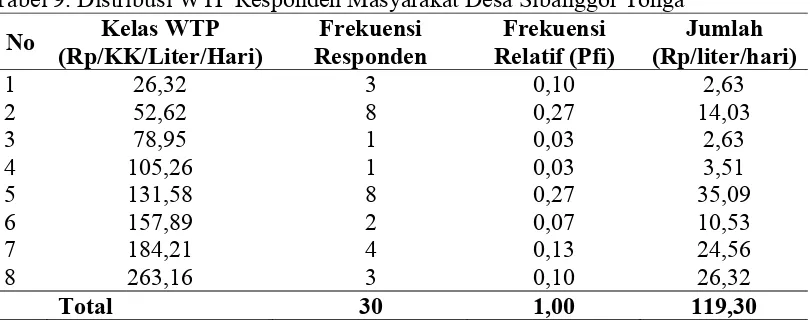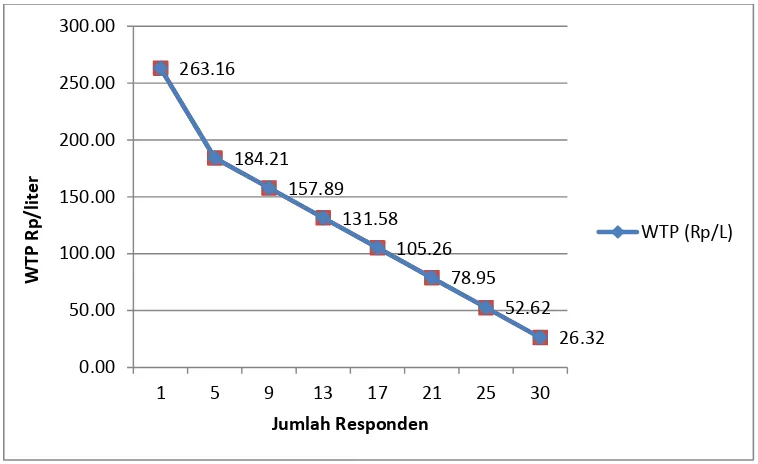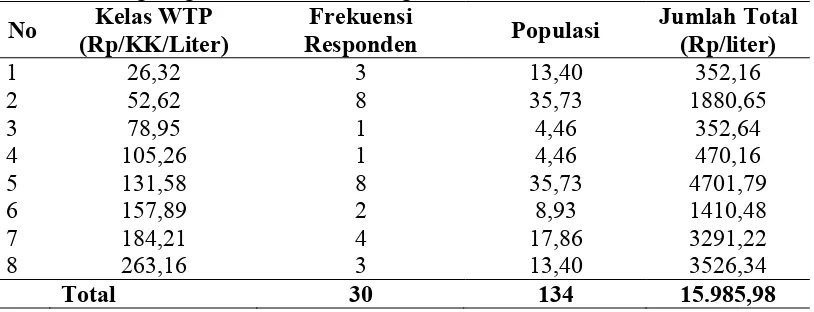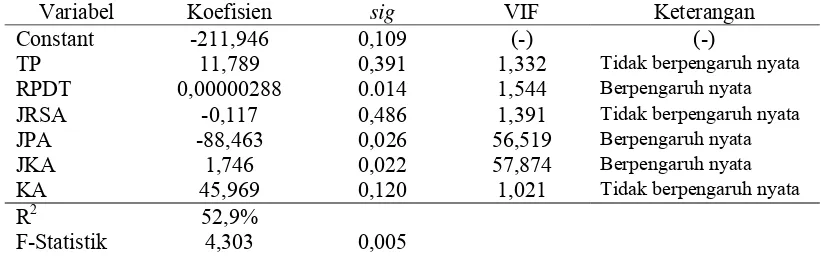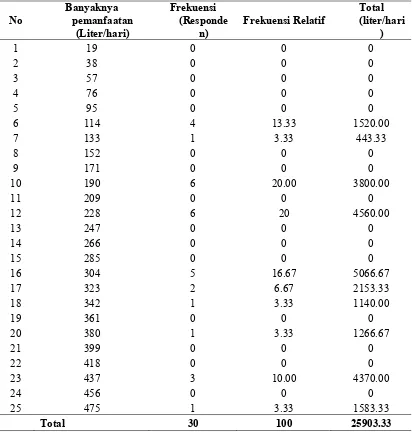ANALISIS WILLINGNESS TO PAY MASYARAKAT
TERHADAP MATA AIR AEK ARNGA DI DESA SIBANGGOR
TONGA, KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI,
KABUPATEN MANDAILING NATAL
SKRIPSI
Oleh :
Siti Maryam Nasution 101201133 Manajemen Hutan
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Penelitian :
Analisis Willingness To Pay Masyarakat Terhadap Mata Air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.
Nama : Siti Maryan Nasution
Nim :
101201133
Menyetujui Komisi Pembimbing
Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut., M.P Nip. 1974081200003001
Mengetahui
Ketua Program Studi Kehutanan
ABSTRACT
Siti Maryam Nasution (101 201 133). Analysis of Willingness to pay people to springs in the village of Aek Arnga Sibanggor Tonga, Puncak Sorik Marapi
District, Mandailing Natal Regency. Under the guidance of Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si and Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut., MP.
Water is one of important element in human life. Water is also used for various purposes including for drinking, domestic use, and all other activities are directly related to human welfare. This research was aimed to explore the value of willingness to pay (WTP) society to the economic instruments of payment for environmental services, the factors that affect the willingness of respondents to make payment for environmental services and the factors that affect the value of such willingness. Respondent's willingness to pay for environmental services is influenced by several factors: the average income, the number of water users, and the amount of water needs.
WTP values of this research is the value that will be given by the respondents to the environmental services generated by springs Aek Arnga per liter per family. The mean WTP values of respondents is Rp. 119.30 / KK / liter / day while the total value of WTP is Rp. 15985.98 / liter / day. Number of environmental services Aek springs Arnga by society as much. 9,454,715.45 liters / year. While the potential value of the use of springs Aek Arnga obtained from multiplying the number of environmental services by the community with the average WTP values that are exploiting the potential value of Rp. 1,127,947,553.18 / year that can be done to restore the ecology of the forest area of 10.23 Ha.
ABSTRAK
Siti Maryam Nasution (101201133). Analisis Willingness to pay masyarakat terhadap mata air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik
marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah bimbingan Dr. Agus Purwoko, S.Hut.,M.Si dan Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut.,MP.
Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Air juga dipergunakan untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk minum, keperluan rumah tangga, dan segala aktifitas lainnya yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai willingness to pay (WTP) masyarakat terhadap instrumen ekonomi yaitu pembayaran jasa lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesedian responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan tersebut. Kesediaan responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rata-rata pendapatan, jumlah pengguna air, dan jumlah kebutuhan air.
Nilai WTP dalam penelitian ini adalah nilai yang akan diberikan oleh responden terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan oleh mata air Aek Arnga per liter per KK. Nilai rataan WTP responden adalah Rp. 119,30/KK/liter/hari sedangkan nilai total WTP adalah Rp. 15.985,98/liter/hari. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan mata air Aek Arnga oleh masyarakat sebanyak. 9.454.715,45 liter/tahun. Sedangkan nilai potensial pemanfaatan mata air Aek Arnga didapatkan dari perkalian jumlah pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat dengan nilai
rataan WTP sehingga nilai potensial pemanfaatan adalah sebesar Rp. 1.127.947.553,18/tahun yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekologi hutan
seluas 10,23 Ha.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
usulan penelitian ini.
Penelitian Ini Berjudul Analisis Willingness To Pay Masyarakat Terhadap
Mata Air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi,
Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis nilai
kesediaan membayar jasa lingkungan hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
nilai kesediaan membayar jasa lingkungan hutan di desa Sibanggor Tonga,
Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Purwoko, S.Hut.,
M.Si. selaku dosen pembimbing pertama dan Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut.,M.P
selaku dosen pembimbing kedua saya serta kepada seluruh teman-teman yang
telah mendukung dalam usulan penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih
terdapat banyak kekurangan baik itu dari struktur penulisan maupun
penyampaiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca
agar dapat memperbaiki dalam penulisan usulan penelitian ini. Demikianlah
penulis ucapkan terima kasih. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita
semua.
Medan, April 2014
DAFTAR ISI
Metode Penilaian Jasa Lingkungan ... 12
Contingen Valuation Method (CVM) ... 12
Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 17
KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN Letak Geografis dan Batas Wilayah ... 22
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden ... 24
1. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden ... 24
2. Tingkat Pendapatan Responden ... 25
3. Jarak Rumah ke Sumber air ... 25
4. Jumlah Pengguna Air ... 26
5. Jumlah Kebutuhan Air ... 26
6. Kualitas Air ... 27
7. Nilai Willingness to pay (WTP) yang Ditawarkan ... 27
Analisis Willingness to Pay Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga ... 28
1. Membangun Pasar Hipotesis (Setting-up the Hypotethical Market). 28 2. Menghitung Dugaan Nilai Rata-rata WTP (Estimating Mean WTP/EWTP) ... 29
3. Memperkirakan Kurva WTP (Estimating Bid Curve) ... 29
4. WTP Agregat atau Total WTP (TWTP) ... 30
5. Evaluasi Pelaksanaan Contingen valuation method (CVM) ... 31
5.a. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Willingness To pay ... 32
Analisis Pembayaran Jasa Lingkungan Terhadap Biaya Pemulihan Ekologi Hutan ... 35
DAFTAR TABEL
Hal
1. Rancangan Prosedur Penelitian dan Analisis Data ... 17
2. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir ... 23
3. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Tingkat pendapatan ... 24
4. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jarak rumah Ke Sumber Air ... 24
5. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jumlah pengguna Air ... 25
6. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jumlah Kebutuhan Air ... 25
7. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Kualitas Air ... 26
8. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Nilai WTP yang Ditawarkan ... 26
9. Distribusi WTP Responden Masyarakat Desa Sibanggor Tonga ... 27
10.Total WTP Responden Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga ... 29
11.Hasil Analisis Nilai WTP Responden Masyarakat Desa Sibanggor Tonga ... 30
ABSTRACT
Siti Maryam Nasution (101 201 133). Analysis of Willingness to pay people to springs in the village of Aek Arnga Sibanggor Tonga, Puncak Sorik Marapi
District, Mandailing Natal Regency. Under the guidance of Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si and Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut., MP.
Water is one of important element in human life. Water is also used for various purposes including for drinking, domestic use, and all other activities are directly related to human welfare. This research was aimed to explore the value of willingness to pay (WTP) society to the economic instruments of payment for environmental services, the factors that affect the willingness of respondents to make payment for environmental services and the factors that affect the value of such willingness. Respondent's willingness to pay for environmental services is influenced by several factors: the average income, the number of water users, and the amount of water needs.
WTP values of this research is the value that will be given by the respondents to the environmental services generated by springs Aek Arnga per liter per family. The mean WTP values of respondents is Rp. 119.30 / KK / liter / day while the total value of WTP is Rp. 15985.98 / liter / day. Number of environmental services Aek springs Arnga by society as much. 9,454,715.45 liters / year. While the potential value of the use of springs Aek Arnga obtained from multiplying the number of environmental services by the community with the average WTP values that are exploiting the potential value of Rp. 1,127,947,553.18 / year that can be done to restore the ecology of the forest area of 10.23 Ha.
ABSTRAK
Siti Maryam Nasution (101201133). Analisis Willingness to pay masyarakat terhadap mata air Aek Arnga di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik
marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah bimbingan Dr. Agus Purwoko, S.Hut.,M.Si dan Dr. Kansih Sri Hartini, S.Hut.,MP.
Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Air juga dipergunakan untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk minum, keperluan rumah tangga, dan segala aktifitas lainnya yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai willingness to pay (WTP) masyarakat terhadap instrumen ekonomi yaitu pembayaran jasa lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesedian responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan tersebut. Kesediaan responden untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rata-rata pendapatan, jumlah pengguna air, dan jumlah kebutuhan air.
Nilai WTP dalam penelitian ini adalah nilai yang akan diberikan oleh responden terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan oleh mata air Aek Arnga per liter per KK. Nilai rataan WTP responden adalah Rp. 119,30/KK/liter/hari sedangkan nilai total WTP adalah Rp. 15.985,98/liter/hari. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan mata air Aek Arnga oleh masyarakat sebanyak. 9.454.715,45 liter/tahun. Sedangkan nilai potensial pemanfaatan mata air Aek Arnga didapatkan dari perkalian jumlah pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat dengan nilai
rataan WTP sehingga nilai potensial pemanfaatan adalah sebesar Rp. 1.127.947.553,18/tahun yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekologi hutan
seluas 10,23 Ha.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hutan sebagai sumberdaya alam (resources) mempunyai fungsi ganda
yaitu sebagai penghasil kayu dan sebagai penghasil kenyamanan seperti penghasil
oxigen, penyerap CO2, pengatur tata air, pencegah erosi, serta ruang hidup untuk
flora dan fauna. Tanah di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan
air hujan sehingga air meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Banyak kota yang
menggantungkan diri terhadap persediaan air dari hutan dengan sungai-sungai
yang mengalir sepanjang tahun (Sianturi, 2001).
Berdasarkan bentuk/wujudnya, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi
dua macam yaitu: manfaat tangible dan manfaat intangible. Manfaat tangible
antara lain: kayu, hasil hutan ikutan, dan lain-lain. Sementara manfaat intangible
antara lain: pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, dan lain-lain
(Arifudin, 1990).
Mata air Aek Arnga ini berada di sekitar pegunungan Sorik Marapi yang
mengalir menuju pedesaan Sibanggor Tonga. Mata air ini digunakan masyarakat
sebagai pasokan air minum, kebutuhan rumah tangga dan juga aliran mata air ini
digunakan pada lokasi pemandian umum masyarakat. Mata air ini merupakan
salah satu mata air dari beberapa mata air yang paling banyak digunakan untuk
kebutuhan masyarakat karena kualitas mata air yang masih terjaga kebersihan dan
kesehatannya (Dinas Kecamatan Puncak Sorik Marapi).
Mata air Aek Arnga juga berada pada kawasan DAS Taman Nasional
Batang Gadis (TNBG) yaitu pada Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak
kawasan TNBG, mata Air Aek Arnga merupakan salah satu mata air yang sangat
bersih dan jernih karena juga merupakan mata air yang berada di sekitar hutan dan
pegunungan (Dinas Kecamatan Puncak Sorik Marapi).
Analisis WTP telah banyak digunakan untuk melakukan penilaian
terhadap jasa lingkungan dari hutan dan perbaikan kualitas lingkungan di daerah
aliran sungai. Dalam analisis WTP ini dilakukan pembentukan pasar hipotetik
yaitu kualitas lingkungan dari kawasan Puncak yang lebih baik dari kondisi pada
saat ini, melalui upaya pencegahan konversi hutan, penghijauan dan
pengembangan hutan rakyat. Kesediaan membayar masyarakat untuk membayar
perbaikan lingkungan ini menggambarkan manfaat ekonomi dari keberadaan
hutan (Merryna, 2009).
Air merupakan salah satu unsur yang penting di dalam kehidupan. Air
juga dipergunakan untuk beberapa kepentingan diantaranya untuk minum, masak,
mencuci, dan segala aktifitas lain yang langsung berhubungan dengan
kesejahteraan manusia. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan
peningkatan kebutuhan air bersih. Air bersih yang tersedia di alam semakin buruk
kondisinya sehingga air menjadi tidak tersedia dengan baik secara kuantitatif dan
kualitatif. Suatu saat nanti, air akan menjadi barang yang mahal karena
pengelolaan untuk mendapatkan air yang baik secara kuantitatif dan kualitatif
memerlukan biaya yang sangat tinggi (Merryna, 2009).
Menurut Fauzi (2006), air saat ini merupakan barang publik yang dapat
dinikmati oleh siapapun. Air juga merupakan barang ultra essential bagi
kelangsungan hidup manusia. Tanpa air, manusia tidak akan mungkin bisa
paradox atau paradoks air dan berlian, dimana air yang begitu esential dinilai
begitu murah sementara berlian yang sebatas perhiasan dinilai begitu mahal.
Rumusan Masalah
Permasalahan ketersediaan air yang baik secara kualitatif dan kuantitatif
saat ini merupakan problematika yang sering terjadi. Problematika ini tidak hanya
terjadi pada masyarakat perkotaan namun juga pada masyarakat pedesaan yang
memiliki sumber daya alam yang melimpah. Keterbatasan pendanaan sering kali
menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut dengan baik
sehingga dikhawatirkan suatu saat nanti sumber daya alam tersebut mengalami
degradasi yang akan merugikan berbagai pihak.
1. Berapakah besarnya WTP responden terhadap pembayaran jasa lingkungan
Mata Air Aek Arnga?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai WTP responden terhadap
pembayaran jasa lingkungan?
Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis nilai kesediaan pembayaran jasa lingkungan oleh responden
untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP responden
Manfaat
Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:
1. Penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap khasanah keilmuan ekonomi
sumberdaya dan lingkungan bagi akademisi dan peneliti
2. Sebagai bahan acuan dalam penerapan kebijakan pengelolaan mata air Aek
Arnga di Kecamatan Puncak Sorik Marapi
3. Bahan ilmu pengetahuan untuk masayarakat setempat mengenai ilmu
ekonomi sumberdaya dan lingkungan khususnya mengenai pembayaran jasa
TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Fauzi (2006), sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang
dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya itu sendiri memiliki dua aspek
yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan
dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya
dan bagaimana teknologi digunakan. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya
adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang
bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan tersebut
seperti ikan, kayu, air bahkan pencemaran sekalipun dapat dihitung nilai
ekonominya karena diasumsikan bahwa pasar itu eksis (market based), sehingga
transaksi barang dan jasa tersebut dapat dilakukan.
Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam (kekayaan alam)
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan
hidupnya. Sumber daya alam terbagi dua yaitu sumber daya alam hayati dan
sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya
alam biotik yaitu semua yang terdapat di alam (kekayaan alam) berupa makhluk
hidup. Sedangkan sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam abiotik
adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa
benda mati (Ramathan, 1997).
Air merupakan kebutuhan utama bagi setiap insan di permukaan bumi baik
manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Setiap kegiatan mereka tidak lepas
dari kebutuhan akan air, bahkan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Tubuh
manusia itu sendiri, lebih dari 70% tersusun dari air, sehingga ketergantungannya
kebutuhan pertanian, industri, maupun kebutuhan domestik, termasuk air bersih.
Hal ini berarti bahwa pertambahan jumlah penduduk yang terus menerus terjadi,
membutuhkan usaha yang sadar dan sengaja agar sumber daya air dapat tersedia
secara berkelanjutan (Cholil, 1998).
Sumber daya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat
dikonsumsi baik langsung maupun tidak langsung juga dapat menghasilkan
jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat dalam bentuk lain, misalnya manfaat
amenity seperti keindahan, ketenangan dan sebagainya. Manfaat tersebut sering
kita sebut sebagai manfaat fungsi ekologis yang sering tidak terkuantifikasikan
dalam perhitungan menyeluruh terhadap nilai dari sumber daya. Nilai tersebut
tidak saja nilai pasar barang yang dihasilkan dari suatu sumber daya melainkan
juga nilai jasa lingkungan yang ditimbulkan oleh sumber daya tersebut
(Fauzi, 2006).
Secara umum, willingness to pay (WTP) atau kemauan/keinginan untuk
membayar didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dibayarkan seorang konsumen
untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Zhao & Kling (2005) menyatakan
bahwa WTP adalah harga maksimum dari suatu barang yang ingin dibeli oleh
konsumen pada waktu tertentu. Sedangkan Horowith & McConnell (2001)
menekankan pengertian WTP pada berapa kesanggupan konsumen untuk membeli
suatu barang. WTP itu sebenarnya adalah harga pada tingkat konsumen yang
merefleksikan nilai barang atau jasa dan pengorbanan untuk memperolehnya
(Simonson & Drolet, 2003). Disisi lain, WTP ditujukan untuk mengetahui daya
beli konsumen berdasarkan persepsi konsumen. Dinauli (1999) diacu dalam
Untuk memahami konsep WTP konsumen terhadap suatu barang atau jasa
harus dimulai dari konsep utilitas, yaitu manfaat atau kepuasan karena
mengkonsumsi barang atau jasa pada waktu tertentu. Setiap individu ataupun
rumah tangga selalu berusaha untuk memaksimumkan utilitasnya dengan
pendapatan tertentu, dan ini akan menentukan jumlah permintaan barang atau jasa
yang akan dikonsumsi. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang
mau atau ingin dibeli atau dibayar (willingness to buy or willingness to pay) oleh
konsumen pada harga tertentu dan waktu tertentu (Perloff, 2004). Utilitas yang
akan didapat oleh seorang konsumen memiliki kaitan dengan harga yang
dibayarkan yang dapat diukur dengan WTP. Sejumlah uang yang ingin dibayarkan
oleh konsumen akan menunjukkan indikator utilitas yang diperoleh dari barang
tersebut (PSE-KB UGM (2002) diacu dalam Nababan dan Simanjuntak (2008)
Secara teoritik, Hokby & Sodergvist (2001) dan Anstine (2001)
mengemukakan bahwa metode WTP dibuat untuk menunjukkan pilihan-pilihan
antara kombinasi harga dan kuantitas yang berbeda, dimana utilitasnya dapat
dimaksimumkan oleh seorang individu atau konsumen. Dengan menggunakan
fungsi permitaan Marshallian, mereka mengemukakan hubungan antara utilitas
dan WTP.
Jasa Lingkungan
Jasa lingkungan adalah produk sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
berupa manfaat langsung (tangible) dan manfaat tidak langsung (intangible) yang
meliputi antara lain jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata
keunikan, keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon
(Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2006).
Jasa lingkungan yang ada saat ini suatu saat nanti akan mengalami
penurunan kualitas. Salah satu instrumen ekonomi yang dapat mengatasi
penurunan kualitas lingkungan dalam penelitian ini adalah pembayaran jasa
lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan adalah suatu transaksi sukarela yang
menggambarkan suatu jasa lingkungan yang perlu dilestarikan dengan cara
memberikan nilai oleh penerima manfaat kepada penerima manfaat jasa
lingkungan (Wunder, 2005).
Fungsi Jasa Lingkungan
Menurut Wunder (2005), suatu ekosistem menyediakan suatu jasa
lingkungan yang memiliki empat fungsi penting yaitu :
1. Jasa penyediaan (provising services), jasa penyediaan yang dimaksud disini
adalah penyediaan sumber daya alam berupa sumber bahan makanan,
obatobatan alamiah, sumber daya genetik, kayu bakar, serat, air, mineral dan
lain-lain.
2. Jasa pengaturan (regulating services), jasa pengaturan yang dimaksud disini
adalah jasa lingkungan memiliki fungsi menjaga kualitas udara, pengeturan
iklim, pengaturan air, pengontrol erosi, pengaturan untuk menjernihkan air,
pengaturan pengelolaan sampah, pengaturan untuk mengontrol penyakit,
pengaturan untuk mengurangi resiko yang menghambat perbaikan kualitas
lingkungan dan lain-lain.
3. Jasa kultural (cultural services), jasa cultural yang dimaksud disini adalah
dan spiritual, pengetahuan, inspirasi, nilai estetika, hubungan sosial, rekreasi,
dan lain-lain.
4. Jasa pendukung (supporting services), jasa pendukung yang dimaksud disini
adalah jasa lingkungan sebagai produksi utama yang memproduksi oksigen.
Produk jasa lingkungan hutan atau kawasan konservasi umumnya dibagi
dalam 4 (empat) kategori berupa (Wunder, 2005) :
1) Penyerap dan penyimpangan karbon (carbon sequestration and storage)
2) Perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity protection)
3) Perlindungan daerah aliran sungai (watershed protection)
4) Keindahan bentang alam (landscape beauty)
Terkait dengan pemanfaatan air, hutan memberikan jasa lingkungan
manfaat berupa memperbaiki kualitas air dengan mengurangi sedimentasi dan
erosi, mengatur aliran dan supply air melalui kemampuan penyerapan, mengisi air
bawah tanah dan menyimpannya, mencegah dan mengurangi bencana akibat air
seperti banjir, menahan air hujan pada sistem pengakaran selama musim hujan
dan secara perlahan melepaskan air selama musim kemarau.
Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan
Menurut Nahib (2006) Indonesia merupakan negara yang kaya akan
sumberdaya alam. Sumberdaya alam (baik renewable dan non renewable)
merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia.
Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak
sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi (Fauzi, 2004).
Menurut Sudarna (2007), produk jasa yang dapat dihasilkan dari ekosistem
manfaat yang besar sebagai penunjang kehidupan yang mampu mendukung dan
menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Di sisi lain produk jasa itu sendiri dapat
dinilai hingga memperoleh nilai ekonomi. Nilai suatu sumberdaya alam terbagi
menjadi nilai manfaat (use values) dan nilai tak termanfaatkan (non use values).
Nilai manfaat sumberdaya alam (misal hutan) terdiri dari manfaat langsung (direct
use value) seperti kayu, manfaat tidak langsung (indirect use value) seperti jasa
lingkungan dan manfaat pilihan (option use value).
Penentuan nilai ekonomi lingkungan merupakan hal yang sangat penting
sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan sumberdaya alam yang
semakin langka. Valuasi ekonomi bermanfaat untuk mengilustrasikan hubungan
timbal balik antara ekonomi dan lingkungan yang diperlukan untuk melakukan
pengelolaan sumberdaya alam yang baik, dan menggambarkan keuntungan atau
kerugian yang berkaitan dengan berbagai pilihan kebijakan dan program
pengelolaan sumberdaya alam sekaligus bermanfaat dalam menciptakan keadilan
dalam distribusi manfaat sumberdaya alam. Maka valuasi ekonomi dengan
menggunakan nilai uang akan dapat menunjukkan nilai indikasi penerimaan dan
kehilangan manfaat atau kesejahteraan akibat kerusakan lingkungan
(Tampubolon, 2008).
Penggunaan metode analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis)
yang konvensional sering tidak mampu menjawab permasalahan dalam
menentukan nilai sumber daya karena konsep biaya dan manfaat sering tidak
memasukkan manfaat ekologis di dalam analisisnya (Fauzi, 2006). Oleh karena
itu lahirlah pemikiran konsep valuasi ekonomi, khususnya valuasi non-pasar
Willingness to Pay atau kesediaan untuk membayar adalah kesediaan
individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian
terhadap sumberdaya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas
lingkungan (Hanley dan Spash, 1993).
Mekanisme pasar dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar:
kesepakatan yang diatur sendiri (self-organized private agreements), skema
pembayaran publik (public payment schemes) dan skema pasar terbuka (open
trading schemes). Dalam setiap kategori ditemukan beragam mekanisme pasar
menurut tingkat keterlibatan publik di dalamnya. Transaksi-transaksi yang
termasuk di dalam kesepakatan biasanya bersifat tertutup, antar pihak-pihak yang
memperoleh manfaat dan yang menjadi penyedia jasa lingkungan. Karena jasa
DAS seringkali dianggap "barang publik", maka skema pembayaran publik
merupakan mekanisme finansial yang paling sering dimanfaatkan untuk
melindungi jasa DAS. Skema pasar terbuka merupakan skema yang paling jarang
diterapkan dibandingkan dengan kedua mekanisme lainnya dan cenderung lebih
banyak diterapkan di negara-negara yang sudah maju. Pemerintah mendefinisikan
dan menentukan batas-batas komoditas jasa yang dapat diperjual belikan. Lalu
dibuat regulasi yang dapat menciptakan munculnya permintaan. Dalam hal ini,
diperlukan kerangka regulasi yang kuat. Di sisi lain, setiap sistem perdagangan
kredit yang berbasis pasar mempersyaratkan kerangka transparansi, penghitungan
yang akurat, dan sistem verifikasi (Purwanto, 2003).
Dengan adanya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan
sumber daya air secara terpadu maka diharapkan PJL yang sebelumnya baru
masyarakat pedesaan. Sebelum adanya realisasi dari pelaksanaan PJL pada taraf
masyarakat sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penetapan pihak penyedia jasa
lingkungan beserta lokasi penyedia jasa lingkungan kemudian pembentukan
kelembagaan serta aturan-aturan yang mengatur mekanisme PJL (Merryna,2009).
Metode Penilaian Nilai Jasa Lingkungan
Metode penilaian ekonomi terhadap barang lingkungan sampai saat ini
telah berkembang sekitar 15 jenis metode menurut Yakin (1997). Diantaranya
adalah the Dose-Response Method (DRM), Hedonic Price Method (HPM), Travel
Cost Method (TCM), dan the Averting Behaviour Method (ABM). Namun, yang
paling populer saat ini adalah Contingent Valuation Method (CVM) dan superior
karena bisa mengukur dengan baik nilai penggunaan (use values) dan nilai dari
non pengguna (non use values).
Contingent Valuation Method (CVM)
Menurut Fauzi (2006), metode CVM ini sangat tergantung pada hipotesis
yang akan dibangun. Misalnya, seberapa besar biaya yang harus ditanggung,
bagaimana pembayarannya, dan sebagainya. Metode CVM ini secara teknis dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu teknis eksperimental melalui simulasi dan teknik
survei. Metode CVM sering digunakan untuk mengukur nilai pasif sumber daya
alam atau sering juga dikenal dengan nilai keberadaaan. Metode CVM pada
dasarnya bertujuan untuk mengetahui keinginan membayar dari masyarakat
terhadap perbaikan lingkungan dan keinginan menerima kompensasi dari
kerusakan lingkungan.
Contingent Valuation Method (CVM) adalah metode teknik survei untuk
terhadap komoditi yang tidak memiliki pasar seperti barang lingkungan
(Yakin, 1997). CVM menggunakan pendekatan secara langsung yang pada
dasarnya menanyakan kepada masyarakat berapa besarnya Willingness to Pay
(WTP) untuk manfaat tambahan dan/atau berapa besarnya Willingness to Accept
(WTA) sebagai kompensasi dari kerusakan barang lingkungan. Dalam penelitian
ini, pendekatanyang digunakan adalah pendekatan WTP.
Tujuan dari CVM adalah untuk menghitung nilai atau penawaran yang
mendekati dari barang-barang lingkungan jika pasar dari barang-barang tersebut
benar-benar ada. Oleh karena itu, pasar hipotetik (kuisioner dan responden) harus
sebisa mungkin mendekati kondisi pasar yang sebenarnya. Responden harus
mengenal dengan baik komoditas yang ditanyakan dalam kuisioner. Responden
juga harus mengenal alat hipotetik yang digunakan untuk pembayaran.
Kelebihan Contingent Valuation Method (CVM)
Penggunaan CVM dalam memperkirakan nilai ekonomi suatu lingkungan
memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut :
1. Dapat diaplikasikan pada semua kondisi dan memiliki dua hal penting yaitu
seringkali menjadi satu-satunya teknik untuk mengestimasi manfaat dan dapat
diaplikasikan pada berbagai konteks kebijakan lingkungan.
2. Dapat digunakan dalam berbagai macam penilaian barang-barang lingkungan
di sekitar masyarakat.
3. Dibandingkan dengan teknik penilaian lingkungan lainnya, CVM memiliki
kemampuan untuk mengestimasi nilai non-pengguna. Dengan CVM,
seseorang mungkin dapat mengukur utilitas dari penggunaan barang
4. Meskipun teknik dalam CVM membutuhkan analisis yang kompeten, namun
hasil dari penelitian menggunakan metode ini tidak sulit untuk dianalisis dan
dijabarkan.
Kelemahan Contingent Valuation Method (CVM)
Teknik CVM memiliki kelemahan yaitu munculnya berbagai bias dalam
pengumpulan data. Bias dalam CVM menurut Hanley dan Spash (1993) terdiri
dari :
1. Bias Strategi (Strategic Bias)
Adanya responden yang memberikan suatu nilai WTP yang relatif kecil
karena alasan bahwa ada responden lain yang akan membayar upaya peningkatan
kualitas lingkungan dengan harga yang lebih tinggi kemungkinan dapat terjadi.
Alternatif untuk mengurangi bias strategi ini adalah melalui penjelasan bahwa
semua orang akan membayar nilai tawaran rata-rata atau penekanan sifat hipotetis
dari perlakuan. Hal ini akan mendorong responden untuk memberikan nilai WTP
yang benar.
Mitchell dan Carson (1989) diacu dalam Hanley dan Spash (1993)
menyarankan empat langkah untuk meminimalkan bias strategi yaitu :
a) Menghilangkan seluruh pencilan (outliner)
b) Penekanan bahwa pembayaran oleh responden adalah dapat dijamin
c) Menyembunyikan nilai tawaran responden lain
d) Membuat perubahan lingkungan bergantung pada nilai tawaran
Sedangkan Hoehn dan Randall (1987) diacu dalam Hanley dan Spash
(1993) menyarankan bahwa bias strategi dapat dihilangkan dengan menggunakan
2. Bias Rancangan (Design Bias)
Rancangan studi CVM mencakup cara informasi yang disajikan, instruksi
yang diberikan, format pertanyaan, dan jumlah serta tipe informasi yang disajikan
kepada responden.
3. Bias yang Berhubungan dengan Kondisi Kejiwaan Responden (Mental Account Bias)
Bias ini terkait dengan langkah proses pembuatan keputusan seorang
individu dalam memutuskan seberapa besar pendapatan, kekayaan, dan waktunya
yang dapat dihabiskan untuk benda lingkungan tertentu dalam periode waktu
tertentu.
4. Kesalahan Pasar Hipotetik (Hypotetical Market Error)
Kesalahan pasar hipotetik terjadi jika fakta yang ditanyakan kepada
responden di dalam pasar hipotetik membuat tanggapan responden berbeda
dengan konsep yang diinginkan peneliti sehingga nilai WTP yang dihasilkan
menjadi berbeda dengan nilai yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan studi CVM
tidak berhadapan dengan perdagangan aktual, melainkan suatu perdagangan atau
pasar yang murni hipotetik yang didapatkan dari pertemuan antara kondisi
psikologi dan sosiologi prilaku. Terjadinya bias pasar hipotetik bergantung pada :
a) Bagaimana pertanyaan disampaikan ketika melaksanakan survei.
b) Seberapa realitistik responden merasakan pasar hipotetik akan terjadi.
c) Bagaimana format WTP yang digunakan.
Solusi untuk menghilangkan bias ini salah satunya yaitu desain dari alat
survei sedemikian rupa sehingga maksimisasi realitas dari situasi yang akan diuji
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan di pedesaan sekitar Mata air Aek Arnga yaitu
Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik marapi, Kabupaten Mandailing
Natal. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (purposive) karena
lokasi tersebut terletak dimana mata air mengalir melewati Desa Sibanggor
Tonga. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juni
2014.
Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kalkulator dan
perangkat Komputer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar
kuisioner, Microsoft Excel 2007, dan Software Statistic Peckage for Social
Science (SPSS) versi 17.0
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan
data sekunder. Data primer yang digunakan adalah brupa hasil wawancara
langsung dengan responden melalui kuisioner. Sedangkan data sekunder yang
digunakan adalah data yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintahan di
lokasi penelitian dan instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan upaya
konservasi mata air Aek Arnga.
Penentuan Jumlah Responden
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
convenience sampling yaitu pengambilan responden yang mudah ditemui dan
secara sengaja rumah tangga mana yang menggunakan jasa lingkungan mata air
Aek Arnga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Responden diambil
sebanyak 30 KK dari 134 KK Desa Sibanggor Tonga.
Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian dengan rancangan tujuan, metode pengambilan sampel
dan metode analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Rancangan Prosedur Penelitian dan Analisis data
No Tujuan
Metode Pengambilan
Sampel
Metode Analisis
1 Nilai WTP responden terhadap PJL
Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan
dan analisis data dilakukan secara manual dan menggunakan perangkat komputer
yaitu menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS 17.0.
Analisis Nilai WTP Responden terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Tahap-tahap dalam melakukan penelitian untuk menentukan WTP dengan
menggunakan CVM dalam penelitian ini meliputi (Hanley dan Spash, 1993) :
1. Membuat Pasar Hipotetik (Setting Up the Hypotetical Market)
Pasar hipotetik dibentuk atas dasar menurunnya kualitas suatu lingkungan
jasa air sebagai pemasok kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Sibanggor
Tonga. Selain itu, tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah untuk
pengelolaan mata air Aek Arnga yang kualitas dan kuantitasnya semakin
menurun. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan salah satu instrumen
2. Menghitung Dugaan Nilai Rata-Rata WTP (Calculating Average WTP)
Willingness to pay (WTPi) dapat diduga dengan melakukan nilai rata-rata
dari penjumlahan keseluruhan nilai WTP dibagi dengan jumlah responden.
Dugaan rataan WTP dibagi dengan rumus :
EWTP = ∑ 1 ………....… Persamaan (1)
Dimana:
EWTP = Dugaan rataan WTP
Wi = Nilai WTP ke-i
Pfi = Frekuensi Relatif
n = Jumlah responden
i = Responden ke-i yang bersedia melakukan pembayaran jasa lingkungan
3. Menjumlahkan Data (Agregating Data/TWTP)
Penjumlahan data merupakan proses dimana nilai tengah penawaran
dikonversikan terhadap total populasi yang dimaksud. Setelah menduga nilai
tengah WTP maka dapat di duga nilai WTP dari rumah tangga dengan
menggunakan rumus :
TWTP WTPi P ………...………Persamaan( 2)
dimana :
TWTP = Total WTP
WTPi = WTP individu sampel ke-i
ni = Jumlah sampel ke-i yang bersedia membayar sebesar WTP
N = Jumlah sampel
i = Responden ke-i yang bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan
4. Analisis Fungsi Willingness to Pay (WTP)
Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi WTP responden. Model yang digunakan adalah model regresi
linier berganda. Persamaan regresi besarnya nilai WTP dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
WTPi = + KAi + BJAi + JKAi + JRSAi + TPi +
RPDTi + …...Persamaan (3)
WTPi = Nilai WTP Responden (Rp/liter)
= Konstanta
,…, = Koefisien regresi
KA = Penilaian kualitas air (bernilai 5 jika “sangat jernih”, bernilai 4 jika
jernih”, bernilai 3 jika “biasa”, bernilai 2 jika “kotor”, bernilai 1
jika
sangat kotor)
JPA = Jumlah pengguna air (orang)
JKA = Jumlah kebutuhan air (liter/hari/KK)
JRSA = Jarak rumah ke mata air (m)
TP = Tingkat pendidikan (tahun)
RPDPT = Rata-rata pendapatan rumah tangga (Rp/bulan)
i = Responden ke-i (i = 1, 2,…., n)
= Galad
Variabel yang diduga mempengaruhi secara positif adalah penilaian
kualitas air, jumlah pengguna air, jumlah kebutuhan air, jarak rumah ke sumber
kualitas air adalah semakin baik penilaian kualitas air oleh responden maka akan
mempengaruhi peluang kesediaan responden dalam membayar pembayar jasa
lingkungan. Interpretasi jumlah pengguna air dalam rumah tangga adalah semakin
banyak pengguna maka diduga akan mempengaruhi peluang responden dalam
kesediaannya membayar pembayaran jasa lingkungan.
Interpretasi jumlah kebutuhan air adalah jika jumlah kebutuhan air untuk
rumah tangga semakin besar maka mempengaruhi peluang kesediaan responden
untuk membayar pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya konservasi.
Interpretasi jarak rumah ke sumber air adalah semakin dekat rumah responden
dengan sumber air maka akan mempengaruhi peluang kesediaan responden untuk
melakukan pembayaran jasa lingkungan. Interpretasi tingkat pendidikan
responden adalah semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka akan
mempengaruhi peluang kesediaan responden untuk membayar pembayaran jasa
lingkungan. Interpretasi rata-rata pendapatan adalah semakin tinggi tingkat
pendapatan responden maka akan mempengaruhi responden untuk melakukan
pembayaaran jasa lingkungan.
5. Uji Statistik t
Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh
masing-masing variabelnya (Xi) mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat setempat
(Yi) sebagai
variabel tidak bebas prosedur pengujiannya (Ramanathan, 1997) adalah sebagai
t hit(n-k) =
Jika thit (n-k) < tabel, maka H0 diterima, artinya variabel (Xi) tidak berpengaruh
nyata terhadap (Yi)
Jika thit (n-k) > tabel, maka H0 ditolak, artinya variabel (Xi) berpengaruh nyata
KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN
Letak Geografis dan Batas Wilayah
Mata air Aek Arnga merupakan bagian dari DAS Taman Nasional Batang
Gadis (TNBG) yang secara administratif berlokasi Desa Sibanggor Tonga,
Kecamatan Puncak Sorik Marapi, kabupaten Mandailing Natal (Madina). Secara
geografis lokasi ini terletak pada 99o 42’ 39,4” BT dan 00o 42’ 39,4” LS.
Kawasan Sibanggor Tonga merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian
909 mdpl (meter di atas permukaan laut) dan merupakan daerah vulkanis aktif
dengan jenis tanah yang rawan erosi dan longsor, serta curah hujan tinggi.
Mata Air Aek Arnga ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Selatan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambangan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
(Dinas Kecamatan Puncak Sorik Marapi)
Aksesibilitas Lokasi
Lokasi mata air ini dapat dijangkau dengan berjalan kaki, karena lokasi
mata air yang berada pada kawasan hutan dan kelilingi oleh persawahan
masyarakat. Perjalanan menuju sumber mata air memerlukan waktu kurang lebih
15 menit dari kawasan pemukiman Desa Sibanggor Tonga.
Kependudukan dan Sosial Ekonomi Mayarakat
Berdasarkan data yang diperoleh, Kecamatan Puncak Sorik Marapi
747,27 Ha. Penduduk pada kecamatan ini mayoritas bersuku Batak Mandailing
dan seluruhnya beragama Islam. Sarana prasarana yang tersedia pada desa ini
adalah mesjid, puskesmas pembantu, sekolah dasar (SD Negeri Sibanggor
Tonga).
Penduduk desa ini sebagaian besar menggantungkan kehidupan dan mata
pencahariannya pada sektor:
1. Pertanian, perkebunan, dan peternakan, yaitu pertanian berupa padi,
palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan berupa karet dan
coklat. Serta peternakan berupa ayam, itik, dan domba.
2. PNS dan Pegawai wasta
3. Jasa dan Perdagangan Hasil Bumi, Pedagang makanan dan minuman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini adalah penduduk asli yang bermukim di
Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang merupakan bagian
terpenting dari penelitian karena dari responden dapat diketahui
karakteristik/parameter objek penelitian secara lebih baik. Jumlah keseluruhan
responden yang menjadi objek penelitian adalah 30 orang. Parameter dari
penelitian ini dapat digolongkan ke dalam beberapa aspek diantaranya adalah:
tingkat pendidikan , tingkat pendapatan, jarak responden ke mata air, jumlah
pengguna air, jumlah kebutuhan air, kualitas air, dan nilai Willingness to Pay
(WTP) yang ditawarkan responden.
1. Tingkat Pendidikan Terakhir
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Desa Sibanggor Tonga
diperoleh bahwa, tingkat pendidikan terakhir responden didominasi oleh Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Hal ini dikarenakan rata-rata responden yang
diwawancarai adalah pada waktu dahulunya mengalami putus sekolah karena
kekurangan biaya hidup.
Tabel 2. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
No Tingkat Pendidikan Jumlah (KK) Persentase (%)
1 Tidak Sekolah 0 0
2 SD 7 23,33
3 SMP 12 40
4 SMU/SMK 10 33,33
5 Perguruan Tunggi 1 3,33
2. Tingkat Pendapatan
Bedasarkan hasil wawancara, dapat dilihat pada table 3 bahwa tingkat
pendapatan responden yang paling dominan adalah antara Rp. 800.000 –
1.600.000 yaitu sebesar 46,66 % dan pendapatan yang paling jarang adalah
antara Rp.2.400.000 – 3.200.000. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan responden
yang mayoritas sebagai petani dan pedagang yang penghasilannya tidak tetap.
Tabel 3. Rekapitulasi Data Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan
No Tingkat Pendapatan (Rupiah) Jumlah (KK) Persentase (%)
1 ≥ 800.000 9 30
2 < 800.000 – 1.600.000 14 46,66
3 < 1.600.000 – 2.400.000 2 6,66
4 < 2.400.000 – 3.200.000 1 3,33
5 < 3.200.000 – 4000.000 4 13,33
JUMLAH 30 100
3. Jarak Rumah Ke Sumber Air
Jarak ke mata air ini merupakan jarak yang ditempuh oleh responden
menuju sumber air untuk mendapatkan air sebagai keperluan rumah tangga. Data
tersebut dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jarak Rumah ke Sumber Air
No Jarak (meter) Jumlah (KK) Persentase (%)
1 1 – 60 25 83,33
2 61 – 120 2 6,67
3 121 – 180 0 0
4 181 – 240 2 6,67
5 241 – 300 1 3,33
4. Jumlah Pengguna Air
Jumlah pengguna air merupakan jumlah anggota keluarga dari
masing-masing responden yang diwawancarai yang turut memanfaatkan mata air.
Rekapitulasi datanya dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Rekapitula Data Responden Berdasarkan Jumlah Pengguna Air
No. Jumlah Pengguna Air (orang) Jumlah (KK) Persentase (%)
1 1 - 2 5 16,66
2 3 – 4 12 40
3 5 - 6 8 26,66
4 7 – 8 4 13,33
5 9 - 10 1 3,33
JUMLAH 30 100
5. Jumlah Kebutuhan Air
Jumlah kebutuhan air setiap rumah tangga berbeda-beda, hal ini
diakibatkan jumlah pengguna air yang berbeda dan penggunaan masing-masing
orang yang tidak sama. Rekapitulasi datanya dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jumlah Kebutuhan Air
No. Jumlah Kebutuhan Air/KK/Hari
(L) Jumlah (KK) Persentase (%)
1 1 - 100 0 0
2 101 – 200 11 36,66
3 201 – 300 6 20
4 301 – 400 9 30
5 401 - 500 4 13,33
6. Kualitas Air
Kualitas air ini dapat dinilai oleh responden sendiri , memberikan
penilaian mata air sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan criteria yang telah
ditentukan pada kuisioner. Rekapitulasi datanya dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Penilaian Kualitas Air
No Penilaian Kualitas Air Jumlah (KK) Persentase (%)
1 Sangat Jernih 4 13,33
2 Jernih 26 86,66
3 Biasa 0 0
4 Kotor 0 0
5 Sangat Kotor 0 0
JUMLAH 30 100
7. Nilai Willingness to Pay (WTP) yang Ditawarkan
Nilai WTP adalah nilai rupiah yang ditawarkan oleh masing-masing
responden sebagai biaya konservasi mata air yang telah dimanfaatkan bersama
oleh masyarakat. Rekapitulasi datanya dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Nilai WTP yang ditawarkan
No Nilai yang ditawarkan (Rp/L) Jumlah (KK) Persentase ((%)
1 26,32 3 10
2 52,63 8 26,6
3 78,95 1 3,33
4 105,26 1 3,33
5 131,58 8 26,66
6 157,89 2 6,66
7 184,21 4 13,33
8 263,16 3 10
Analisis Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga
Pendekatan Contingent Valuation Method (CVM) dalam penelitian ini
digunakan untuk menganalisis WTP responden terhadap pembayaran jasa
lingkungan yang akan diterapkan di mata air Aek Arnga. Hasil pelaksanaan CVM
adalah sebagai berikut :
1. Membangun Pasar Hipotetik (Setting-up the Hypothetical Market)
Pasar hipotetik yang telah dibangun pada saat penelitian adalah situasi
hipotetik yang digambarkan berdasarkan keadaan lingkungan mata air Aek
Arnga masa sekarang dan perkiraan di masa mendatang, yaitu memberikan
gambaran lingkungan mata air yang sekarang masih terjaga dengan baik apabila
suatu saat mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai hal antara lain
pertumbuhan penduduk, tinggi-rendahnya curah hujan akan mempengaruhi
jumlah ketersediaan air, kegiatan manusia yang turut mengganggu kualitas dan
kuantitas air seperti halnya juga lama atau pendeknya musim kemarau akan
memberikan dampak buruk terhadap masyarakat, misalnya berkurangnya pasokan
air minum, tidak ada air bersih untuk keperluan rumah tangga, dan rusaknya
sistem irigasi persawahan. Untuk semua dampak tersebut akan memerlukan
penanggulangan yang cukup serius.
Memberikan berbagai penjelasan tentang usaha konservasi mata air yang
akan membawa perubahan-perubahan yang positif terhadap lingkungan mata air
dan lingkungan masyarakat sehingga responden akan memperoleh gambaran yang
jelas tentang situasi hipotetik yang dibangun mengenai upaya perbaikan kualitas
dan kuantitas mata air Aek Arnga. Dengan alasan-alasan tersebut, upaya yang
adalah suatu instrumen ekonomi berupa pembayaran jasa lingkungan untuk
menanggulangi penurunan tersebut.
2. Menghitung Dugaan Nilai Rata-rata WTP (Estimating Mean WTP/EWTP) Dugaan nilai WTP (EWTP) responden dihitung berdasarkan data distribusi
WTP responden dan dengan menggunakan rumus persamaan (1). Data distribusi
WTP responden dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Distribusi WTP Responden Masyarakat Desa Sibanggor Tonga No Kelas WTP
Kelas WTP responden diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu nilai
terkecil sampai nilai terbesar WTP yang ditawarkan responden. Dengan
demikian dapat diperoleh nilai rata-rata WTP (EWTP) sebesar
Rp. 119,30/KK/liter/hari
3. Memperkirakan Kurva WTP (Estimating Bid Curve)
Kurva WTP responden berdasarkan nilai WTP responden terhadap jumlah
responden yang memilih nilai WTP tersebut. Gambar 1 dapat menjelaskan kurva
Gambar 1. Kurva Penawaran WTP terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan
Berdasarkan dugaan kurva penawaran WTP dapat dihitung surplus
konsumen yang akan diperoleh masyarakat. Surplus konsumen adalah surplus
atau kelebihan yang diterima responden karena nilai WTP yang diinginkan lebih
tinggi daripada nilai WTP rata-ratanya. Perhitungan surplus konsumen dapat
didasarkan pada rumus :
SK = ∑(WTPi - P) dimana WTPi>P
Keterangan:
SK = Surplus Konsumen
WTPi = WTP responden ke-i
P = WTP rata-rata
Sehingga surplus konsumen responden terhadap pembayaran jasa
lingkungan mata air Aek Arnga adalah sebesar Rp. 25.73/KK/liter.
Nilai total (TWTP) responden dihitung berdasarkan data distribusi WTP
responden dengan rumus persamaan (2), dari kelas WTP dikalikan dengan
frekuensi relatif (ni / N) kemudian dikalikan dengan populasi dari tiap kelas WTP.
Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total WTP
(Rp/liter) oleh responden. Hasil perhitungan TWTP dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Total WTP Responden Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga
No Kelas WTP
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai total WTP dari populasi
adalah sebesar Rp. 15.985,98/liter/hari
5. Evaluasi Pelaksanaan Contingen valuation Method (CVM)
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang diperoleh cukup baik
karena dihasilkan nilai R2 sama dengan 52,9 %. Hal ini sesuiai sengan pernyataan
Kurniawan (2008) yaitu semakin besar nilai R2 maka semakin baik model regresi
yang diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian tentang lingkungan yang
berhubungan dengan prilaku manusia sehingga nilai R2 tidak harus selalu besar.
Oleh karena itu, hasil pelaksanaan CVM dalam penelitian ini masih dapat
diyakini kebenaran dan keandalannya. Selain itu nilai koefisien korelasi R adalah
Hal ini sesuai dengan pernyataan Colton dalam Yasril dan Kasjono (2009) bahwa
korelasi kuat dengan R = 0,51 – 0,57.
5.a.Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Willingness to Pay Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP maka
telah ditetapkan 6 variabel independen yang berpotensi mempengaruhi variabel
dependen yaitu penilaian terhadap : Tingkat Pendidikan (TP), Rata-rata
Pendapatan (RPDT), Jarak Responden ke Sumber Air (JRSA), Jumlah Pengguna
Air (JPA), Jumlah Kebutuhan Air (JKA), dan Kualitas Air (KA). Sehingga dalam
pengujian selanjutnya akan didapatkan variabel yang diduga akan mempengaruhi
atau tidak mempengaruhi nilai WTP. Hasil analisis nilai WTP responden dapat
dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Hasil Analisis Nilai WTP Responden Masyarakat Desa Sibanggor Tonga
Variabel Koefisien sig VIF Keterangan Constant -211,946 0,109 (-) (-) TP 11,789 0,391 1,332 Tidak berpengaruh nyata RPDT 0,00000288 0.014 1,544 Berpengaruh nyata JRSA -0,117 0,486 1,391 Tidak berpengaruh nyata JPA -88,463 0,026 56,519 Berpengaruh nyata JKA 1,746 0,022 57,874 Berpengaruh nyata KA 45,969 0,120 1,021 Tidak berpengaruh nyata
R2 52,9%
F-Statistik 4,303 0,005
Ket: Taraf kepercayaan 95%
Model yang dihasilkan dalam penelitian ini cukup baik. Hal ini
ditunjukkan oleh R2 sebesar 52,9 %, yang berarti 52,9 % keragaman WTP
responden dapat diterangkan oleh keragaman variabel-variabel penjelas yang
terdapat dalam model, sedangkan sisanya 47,1 % diterangkan oleh variabel lain
yang tidak terdapat dalam model. Nilai Fhitung sebesar 4.303 dengan nilai Sig
secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap nilai WTP responden terhadap
pembayaran jasa lingkungan yang dilakukan pada taraf 95%.
Model yang dihasilkan dalam analisis ini adalah :
WTPi = - 211,946 + 45,969 KA – 88,463 JPA + 1,746 JKA - 0,117 JRSA + 11,789 TP + 0,00000288 RPDT
Pada hasil regresi yang telah dilakukan terdapat tiga variabel yang
berpengaruh nyata terhadap nilai WTP pada taraf kepercayaan 95 % yaitu
rata-rata pendapatan (RPDT), jumlah kebutuhan air (JKA), dan jumlah pengguna air
(JPA) . Variabel yang tidak berpengaruh nyata dengan taraf kepercayaan
95 % adalah tingkat pendidikan (TP), kualitas air (KA), dan jarak rumah ke
sumber air (JRSA). Pernyataan berpengaruh atau tidaknya suatu variabel
diperoleh dari nilai sig yaitu apabila sig < 0,05 maka variavel akan berpengaruh
nyata dan begitu juga sebaliknya untuk variable yang tidak berpengaruh nyata.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Algifari (2000) bahwa dalam kasus ekonomi dan
bisnis seringkali dijumpai perubahan suatu variabel disebabkan oleh beberapa
variabel lain.
Variabel rata-rata pendapatan rumah tangga (RPDT) memiliki nilai Sig
sebesar 0,014 yang artinya bahwa variabel ini berpengaruh nyata terhadap nilai
WTP responden pada taraf nyata α (5 persen). Nilai koefisien bertanda positif
(+) berarti bahwa dengan pendapatan responden yang tergolong rendah, tetapi
responden tetap berkeinginan memberi nilai WTP yang tinggi seperti halnya
responden yang rata-rata pendapatannya tinggi, hal ini disebabkan masyarakat
pada Desa Sibanggor Tonga nilai ekonomi yang tergolong rendah sudah bisa
pendapatannya untuk sebagai upaya konservasi mata air Aek Arnga dalam
bentuk pembayaran jasa lingkungan.
Variabel jumlah kebutuhan air memiliki Sig sebesar 0,022 yang artinya
variabel ini berpengaruh nyata pada taraf α (5 persen). Nilai koefisien yang
bertanda positif (+) berarti bahwa semakin besar jumlah kebutuhan air yang
responden peroleh dari mata air Aek Arnga maka responden akan memberikan
nilai WTP yang semakin tinggi, hal ini disebabkan bahwa semakin besar jumlah
air yang dimanfaatkan responden dari mata air Aek Arnga maka responden
semakin menyadari bahwa di masa yang akan datang akan terjadi penurunan
kuantitas dari mata air Aek Arnga sehingga diperlukan suatu upaya konservasi
untuk mencegah penurunan tersebut. Menurut Afifah (2013) bahwa masyarakat
mempunyai kewajiban untuk melakukan konservasi terhadap sumber air, agar
sumber air sebagai jasa lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya konservasi adalah dana.
Variabel penilaian terhadap Jumlah Pengguna Air memiliki nilai Sig
sebesar 0,026 yang artinya bahwa variabel ini berpengaruh nyata terhadap nilai
WTP responden pada taraf α (5 persen). Nilai koefisien bertanda negatif (-)
berarti bahwa banyaknya jumlah keluarga yang menggunakan air dalam rumah
tangga tidak seimbang dengan nilai WTP responden yang ditawarkan untuk
biaya upaya konservasi dalam mencegah penurunan kualitas air di masa
mendatang, yaitu responden memberikan penawaran WTP yang rendah dengan
jumlah pemakai yang banyak.
Variabel-variabel yang tidak mempengaruhi nilai WTP merupakan
melakukan pembayaran jasa lingkungan hutan. Dari hasil wawancara dengan
responden tentang kualitas air, tingkat pendidikan dan jarak rumah ke mata air
tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat. Hal yang selalu masyarakat
pertimbangkan dalam pembayararan jasa lingkungan adalah melihat dari
pendapatan, jumlah pengguna air dan jumlah kebutuhan air mereka. Masyarakat
merasa perlu membayar jasa lingkungan hidup berupa mata air tersebut
berdasarkan pendapatan karena hidup keluarga responden sangat berantung pada
mata air. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cholil (1998) yang menyatakan bahwa
tubuh manusia itu sendiri, lebih dari 70% tersusun dari air, sehingga
ketergantungannya akan air sangat tinggi. Manusia membutuhkan air yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, maupun kebutuhan domestik,
termasuk air bersih. Hal ini berarti bahwa pertambahan jumlah penduduk yang
terus menerus terjadi, membutuhkan usaha yang sadar dan sengaja agar sumber
daya air dapat tersedia secara berkelanjutan.
Analisis Pembayaran Jasa Lingkungan Terhadap Biaya Pemulihan Ekologi Hutan
Nilai potensial pemanfaatan jasa lingkungan merupakan total jumlah
pemakaian jasa lingkungan oleh masyarakat. Sebagai pengguna air, baik
pemerintah, swasta maupun masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam
melakukan kewajibannya untuk menjaga kelestarian hutan. Tanggung jawab ini
dapat kompensasi agar kebutuhan sumber air terpenuhi. Dan sebagai pengguna
merasa yakin bahwa dana yang dihimpun untuk pengelolaan sumber daya air
digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jasa
Nilai potensial pemanfaatan jasa lingkungan dari mata air Aek Arnga
didapatkan dari perkalian jumlah pemanfaatan jasa lingkungan dengan nilai
rata-rata WTP dari masyarakat Desa Sibanggor Tonga. Jumlah pemanfaatan jasa
lingkungan mata air Aek Arnga dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Mata Air Aek Arnga untuk Kebutuhan Rumah Tangga Masyarakat Desa Sibanggor Tonga
No
Nilai potensial lingkungan adalah total pemanfaatan jasa lingkungan
(25903,33 liter/hari) dikalikan dengan rata-rata WTP (Rp. 119,30 /liter ) maka
Rp. 3.090.267,27/hari atau Rp. 1.127.947.553,18/tahun dari total pemanfaatan
jasa lingkungan mata air Aek Arnga sebesar 25.903,33 liter/hari atau 9.454.715,45
liter/tahun.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Sumber Daya Alam
(2009) biaya pemulihan ekologi hutan per hektar per tahun adalah sebesar
Rp. 110.275.000 sehingga dengan nilai poensial tersebut dapat dilakukan untuk
pemulihan ekologi hutan seluas 10,23 Ha. Hasil perhitungan tersebut diketahui
bahwa nilai potensial pemanfaatan yang tergolong besar dapat memenuhi biaya
pemulihan ekologi hutan dan hal ini dapat mengurangi tingkat degradasi
lingkungan.
Kebijakan Pengelolaan Mata Air Aek Arnga melalui Pembayaran Jasa Lingkungan
Sampai saat ini pengelolaan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh mata air
Aek Arnga belum pernah ada. Padahal pengelolaan tersebut sangat diperlukan,
mata air ini merupakan pemasok air utama kebutuhan rumah tangga . Selain itu
pemanfaatan mata air Aek Arnga juga sebagai air untuk keperluan irigasi
persawahan yang membentang disepanjang daerah aliran mata air yang akan
memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas
mata air Aek Arnga.
Berdasarkan keterangan responden, pada bagian pemandian masyarakat
terdapat berbagai timbunan sampah yang ditinggalkan masyarakat sewaktu
melakukakn kegiatan pada pemandian yang nantinya dapat mempengaruhi
kualitas dan kuantitas air di mata air Aek Arnga. Sehingga diperlukan suatu
yang terpadu maka dampak yang dapat diharapkan adalah meningkatkan
kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan (PJL).
Dengan adanya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan
sumber daya air secara terpadu maka diharapkan PJL dapat diterapkan oleh
masyarakat pedesaan. Menurut pernyataan Merryna (2009) yaitu sebelum adanya
realisasi dari pelaksanaan PJL pada taraf masyarakat sebaiknya terlebih dahulu
dilakukan penetapan pihak penyedia jasa lingkungan beserta lokasi penyedia jasa
lingkungan kemudian pembentukan kelembagaan serta aturan-aturan yang
mengatur mekanisme PJL.
Lokasi penyedia jasa lingkungan bisa ditetapkan dimana saja, termasuk
pada dearah Kecamatan Puncak Sorik Marapi karena daerah ini merupakan lokasi
strategis dengan hutan yang masih terbilang bagus dan jasan lingkungan yang
melimpah. Di derah ini dapat ditentukan prosedur-prosedur pembayaran jasa
lingkungan dengan membuat berbagai pihak pemerintah maupun masyarakat
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Nilai rataan WTP responden adalah Rp.119,30/KK/liter/hari, untuk setiap
kepala keluarga (KK) yang membayar pembayaran jasa lingkungan sebagai
upaya konservasi mata air Aek Arnga dan total nilai WTP adalah
Rp. 15.985,12/liter. Nilai potensial pemanfaatan jasa lingkungan mata air Aek
Arnga adalah Rp. 1.127.947.553,18/tahun. Total biaya pemanfaatan jasa
lingkungan mata air Aek Arnga sebesar 9.454.715,45 liter/tahun.
2. Faktor yang mempengaruhi nilai Willingness to pay (WTP) adalah Rata-rata
Pendapatan Rumah Tangga (RPDT), Jumlah Kebutuhan Air (JKA), dan
Jumlah Pengguna Air (JPA).
3. Interpretasi variabel-variabel tersebut adalah : a) Interpretasi variabel rata-rata
pendapatan rumah tangga adalah dengan pendapatan responden yang
tergolong rendah, tetapi responden tetap berkeinginan memberi nilai WTP
yang tinggi, b) Interpretasi variabel jumlah kebutuhan air adalah semakin
besar jumlah kebutuhan air yang responden peroleh dari mata air Aek Arnga
maka responden akan memberikan nilai WTP yang semakin tinggi,
c) Interpretasi variabel Jumlah pengguna air adalah banyaknya jumlah
anggota keluarga yang menggunakan air dalam rumah tangga tidak seimbang
Saran
1. Diperlukan suatu pendekatan terhadap masyarakat mengenai Pembayaran
Jasa Lingkungan (PJL) yang akan dilakukan dan penyebaran informasi
mengenai dampak positif dan negatif dari diberlakukannya kebijakan PJL.
2. Diperlukan kebijakan dari pemerintah setempat untuk membuat suatu
mekanisme pembayaran jasa lingkungan kepada masyarakat agar masyarakat
lebih mudah untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan
3. Diharapkan kepada masyarakat dengan pendapatan dan penggunaan air
terbesar dapat memberikan kesediaan membayar yang lebih tinggi sehingga
DAPTAR PUSTAKA
Adirianto, B. 2012. Potensi Nilai Ekonomi Total Hutan Pendidikan Gunung Walat Sukabumi Jawa Barat. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
Afifah, KN. 2013. Analisis Willingness to pay Jasa Lingkungan Air untuk Konservasi di Taman Wisata Alam Kerandangan Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Program Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegiro. Semarang.
Algifari. 2000. Analisis Regresi: Teori, kasus, dan solusi. BPFE. Yogyakarta
Arifudin. 1990. Studi Permintaan Terhadap Manfaat Rekreasi di Kawasan Pelestarian Alam Cibodas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jurusan Manajemen hutan, Fakultas Kehutanan IPS. Bogor.
Cholil, M. 1998. Analisis Penurunan Muka Air tanah di Kotamadya Surakarta. Forum Geografi, 12(23). di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Dinas Kehutanan dam Perkebunan. 2006. Kajian Pembayaran Jasa Lingkungan.
Dinauli, H., 2001, Analisis Ability To Pay dan Willingness To Pay Tarif Angkutan Kota (Studi Kasus : Kotamadya Medan), Master Theses, ITB Central Library, Bandung, http://www.lib.itb.ac.id/ [17 Juli 2006]. Dryden Press.
Fauzi, A. 2006. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Hanley, N dan C. L. Spash. 1993. Cost-Benefit Analysis and Environmental. Edward Elgar Publishing England.
Hokby, S., and Tore Soderqvist, 2001, “Elasticities of Demand and Willingness To Pay for Environtmental Services in Sweden”, 11th Annual Conference of the European Association of Environtmental and Resource Economists, Southampton, UK, http://papers.ssrn.com/, pp.1-37 [14 Juli 2006].
Kurniawan,D. 2008. Regresi Linear. R Development Core Team (2008). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org [14 Agustus 2014]
Lembaga Sumber Daya Alam. 2009. Kerugian Negara Berdasarkan Kerusakan Lingkungan. Dalam laporan Lembaga Sumberdaya Alam. www.elsdainstitut.or.id/modul/audit/kehutanan/kerusakan.lingkungan.pdf. diakses pada tanggal [18 Desember 2011]
Merryna, A. 2009. Analisis Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Cirahab. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan
Manajemen. IPB. http://analisis willingness to pay.com. [7 Desember 2013].
Mitchell, B dan Carson. 1989. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
Nababan, T.S dan Juara S. 2008. Aplikasi Willingness to Pay Sebagai Proksi Terhadap Variabel Harga: Suatu Model Empirik dalam Estimasi Permintaan Energi Listrik Rumah Tangga. Visi (2008) 16 443 – 457 [14 Januari 2014].
Nahib, Irmadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya. Ilmiah Geomatika 12(1): 37-45
Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
Perloff, J. M., 2004, Microeconomics, Third Edition, Pearson Education Inc., Pearson Addison Wesley, New York, USA.
PSE-KP UGM (Pusat Studi Ekonomi-Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada), 2002, Analisis Tarif Listrik Regional di Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta (Laporan Akhir), Kerjasama PSE-KP UGM & PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Purwanto dkk. 2003. Praktek pengelolaan sumber daya lahan dan Hutan masyarakat tradisional kampung naga (land and forest management practice in kampong naga Traditional community). Pengelolaan DAS Dinamika Komunitas Vegetasi 9(3): 1-12
Ramathan, R. 1997. Introductory Economics with Applications. Philadelpia. The Research. Center for International Forestry Research.
Simonson, I., and Aimee Drolet, 2003, “Anchoring Effects on Consumers’ Willingness To Pay and Willingness To Accept”, Research Paper Series No. 1787, Stanford Graduate School of Business, http://papers.ssrn.com/, pp.1-38 [14 Juli 2006].
Tampubolon, R. 2008. Studi Jasa Lingkungan Di Kawasan Danau Toba. ITTO. Japan. http://www.forda-mof.org. [ 4 April 2014].
Wang, H., and Dale Whittington, 2006, “Willingness To Pay for Air Quality Improvement in Sofia, Bulgaria”, Development Research Group, World Bank, http://papers.ssrn.com/, pp.1-27 [14 Juli 2006].
Wunder, Sven. 2005. Payment for Enviromental Services : Some Nuts and Bolts.
Yakin, A. 1997. Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan: Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta : CV. Akademika Presindo.
Yasril dan HS Kasjono. 2009. Analisis Multivariat untuk Penelitian Kesehatan. Mitra Cendikia Press. Jogjakarta.