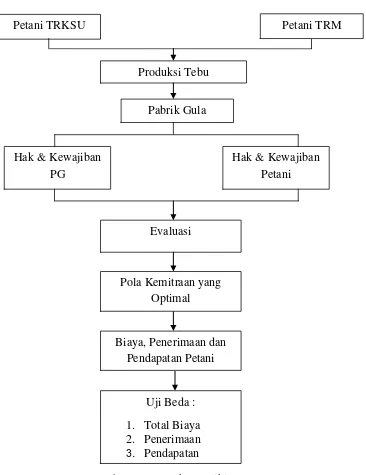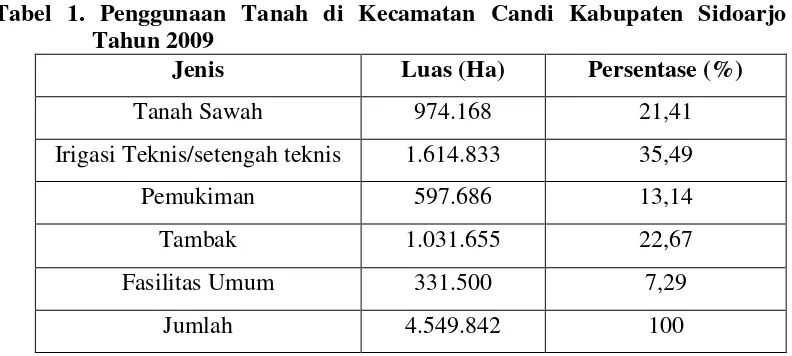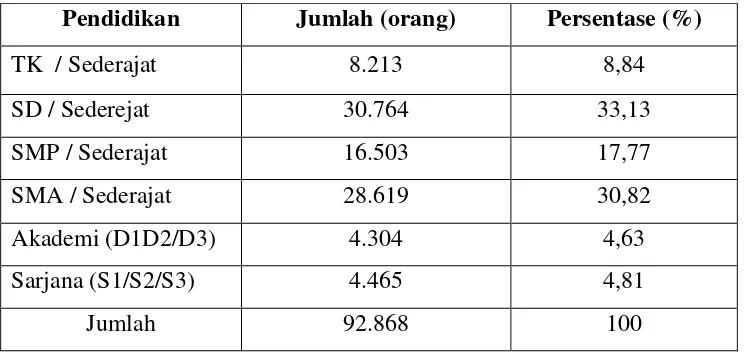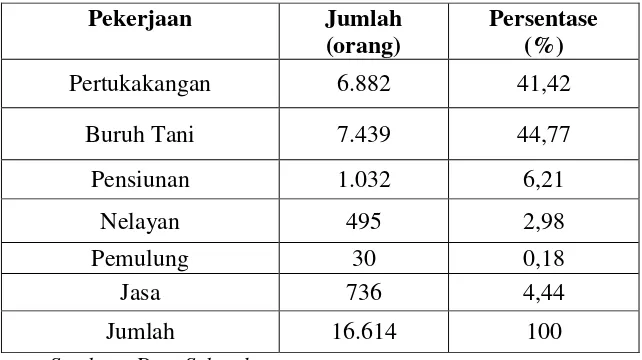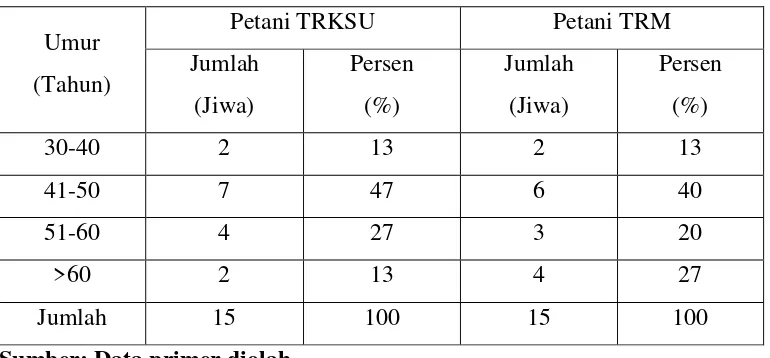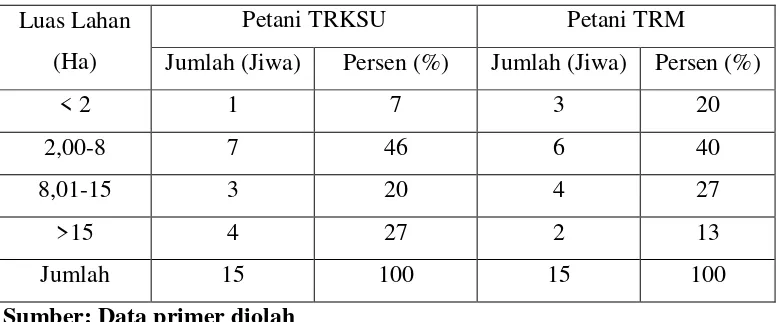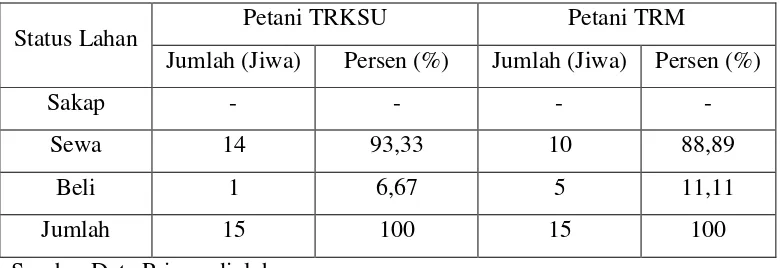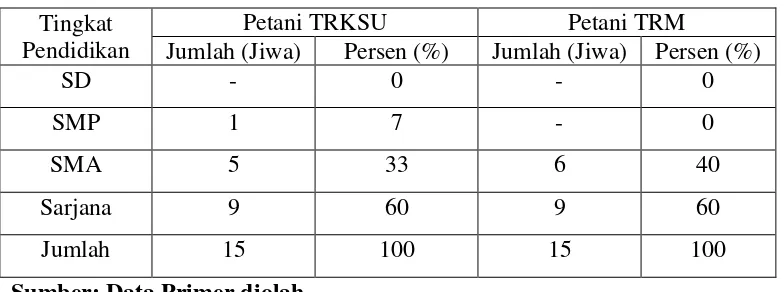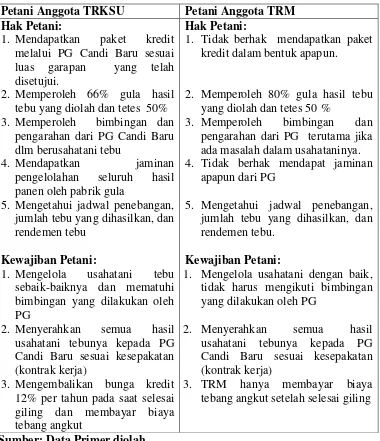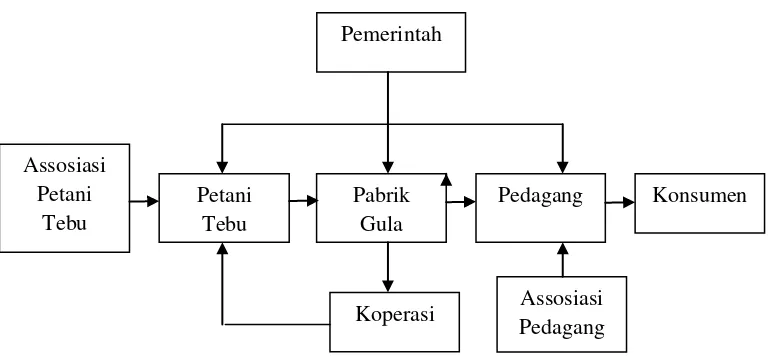SKRIPSI
Diajukan Oleh: RIANA DWIJAYANTI
NPM : 0724010013
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian
Program Studi Manajemen Agribisnis
Oleh:
RIANA DWIJAYANTI NPM : 0724010013
Kepada
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
RINGKASAN
Tebu merupakan salah satu tanaman yang banyak diusahakan oleh petani, sehingga tebu mempunyai arti penting dalam menyusun pendapatan petani, di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Untuk menjaga agar produksi gula jangan sampai menurun serta meningkatkan pendapatan khususnya petani tebu, langkah yang ditempuh pemerintah adalah melalui program kemitraan yang dikenal dengan Tebu Rakyat Mandiri dan Tebu Rakyat Kerja Sama Usahatani (Mirzawan, 2001).
Tujuan kemitraan yang sesungguhnya yaitu tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak dapat mencapai kesetaraan walau pada pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala. Kendala utama adalah isu rendemen. Selain itu masih terdapat pandangan bahwa masih ada hasil sampingan dari tebu yang tidak dibagi. Alasan utama peninjauan kembali ketentuan sistem bagi hasil adalah meningkatkan pendapatan petani sehingga pemasok bahan baku dan pabrik gula sebagai pemroses bahan baku yang sama-sama tidak mau dirugikan meskipun cara seperti itu sebenarnya kurang menguntungkan bagi pabrik gula, tetapi apabila ditunjang peningkatan mutu tebu bermanfaat bagi petani maupun pabrik gula (Mirzawan, 2001).
Kecamatan Candi, Sidoarjo merupakan salah satu kecamatan dimana banyak terdapat petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula Candi Baru. PG. Candi Baru sendiri menggunakan sistem kemitraan.dalam menyediakan bahan baku produksinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pelaksanaan kemitraan antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu mitra, mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kemitraan di Pabrik Gula Candi Baru, mengetahui harmonisasi kemitraan yang terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu mitra, dalam kaitannya dengan perjanjian kemitraan dan menganalisa perbedaan biaya usahatani, penerimaan dan pendapatan antara petani TRKSU dan petani TRM Pabrik Gula Candi Baru. Analisis dalam penelitian ini digunakan berbagai analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis uji beda rata-rata.
berjalan secara harmonis. Adapun harmonisasi yang terjadi yaitu kesadaran antara pihak PG. Candi Baru dan petani tebu mitra dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian, sehingga tercipta suatu kepuasan dari kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa harmonisasi yang terjadi berjalan dengan baik.
iv
skripsi penelitian dengan judul “KEMITRAAN ANTARA PETANI TEBU RAKYAT KERJASAMA USAHATANI (TR-KSU) DAN PETANI TEBU RAKYAT MANDIRI (TRM) DENGAN PABRIK GULA CANDI BARU DI KECAMATAN CANDI - SIDOARJO”.
Dalam melaksanakan skripsi penelitian mulai dari awal sampai dengan
selesainya skripsi penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada Bapak Dr. Ir. Zainal Abidin, MS selaku dosen pembimbing utama dan
Ibu Ir. Eko Priyanto, MP selaku dosen pembimbing pendamping yang telah
banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga dapat terselesaikannya
laporan skripsi ini. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Ir. Ramdan Hidayat, MS. selaku Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Ir. Indra Tjahaja Amir, MP. selaku Ketua Jurusan Manajemen
Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak/Ibu pimpinan dan staf dari PT. Pabrik Gula Candi Baru yang telah
mengijinkan dan membimbing penulis dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Pertanian khususnya jurusan Manajemen
Agribisnis atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis
v
“Twinie” atas support-nya dan menjadikan semua hal terlihat santai dan
menyenangkan.
7. Teman-temanku tersayang angkatan ‘07 dan kakak-kakak alumni atas
bantuan, dukungan, dan semua kebaikan kalian (sangat menyenangkan
ketika tahu bahwa kita tidak sendiri menghadapinya).
8. Semua pihak yang telah membantu secara moril dan materiil yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala kebaikan beliau-beliau dan teman-teman kepada penulis
dapat diterima dan diberkati Allah SWT, dan mendapatkan anugerah yang lebih
dari-Nya.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan
saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi
ini.. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Surabaya, Juni 2011
vi
KATA PENGANTAR ... ... viii
DAFTAR ISI ... ... x
DAFTAR GAMBAR... ... ix
DAFTAR TABEL... ... x
DAFTAR LAMPIRAN ... .... xii
I PENDAHULUAN... ... 1
1.1. Latar Belakang ... ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... ... 5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... ... 7
1.4. Ruang Lingkup ... 8
II TINJAUAN PUSTAKA... ... 9
2.1. Penelitian Terdahulu ... ... 9
2.2. Industri Gula di Indonesia ... .... 11
2.3.Kemitraan... 13
2.3.1. Pengertian dan Bentuk Kemitraan ... 13
2.3.2.Syarat Kemitraan Usaha Pertanian ... .. 19
2.3.3.Perjanjian Kerjasama ... .. 20
2.3.4. Kebijakan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) ... 21
2.3.5. Sistem Bagi Hasil ... 23
vii
IV. METODE PENELITIAN... 31
4.1. Penentuan Lokasi ... 31
4.2. Penentuan Populasi dan Sampel ... 31
4.3. Metode Pengumpulan Data ... 32
4.4. Metode Analisis Data ... 33
4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 35
V. KEADAAN WILAYAH ... 40
5.1. Keadaan Geografis ... 40
5.2. Keadaan Penduduk ... 41
5.3. Keadaan Sosial Ekonomi ... 41
5.3.1. Tingkat Pendidikan ... 42
5.3.2. Mata Pencaharian ... 43
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 45
6.1. Karakteristik Responden ... 45
6.1.1. Umur Responden ... 45
6.1.2. Luas Lahan Usahatani ... 47
6.1.3. Pendidikan Responden ... 48
6.2. Prosedur Pelaksanaan Pola Kemitraan Antara Petani dan PG. Candi Baru-Sidoarjo ... 50
6.2.1. Berdasarkan Pola Kerjasama yang Dijalin ... 53
viii
6.5. Analisis Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Petani
Tebu ... 66
6.6.1. Analisis Biaya Produksi ... 66
6.6.2. Analisis Penerimaan ... 68
6.6.3. Analisis Pendapatan ... 70
6.6. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Keputusan Petani Menjadi Anggota TRKSU di Pabrik Gula Candi Baru ... 73
6.7. Penyusunan Kebijakan Pergulaan di Indonesia ... 76
VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 74
7.1. Kesimpulan ... 78
7.2. Saran ... 79
ix
1. Diagram Kerangka Pemikiran ... 29
x
1. Penggunaan Tanah di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009 ... 41
2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Candi Tahun 2009 ... 42
3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Candi Tahun 2009 ... 43
4. Jumlah Responden Menurut Golongan Umur ... 46
5. Jumlah Responden Menurut Luas Kepemilikan Lahan ... 47
6. Status Lahan yang Dikerjakan Petani Tebu Mitra ... 48
7. Tingkat Pendidikan Responden ... 49
8. Hak dan kewajiban petani anggota TRKSU dan TRM ... 51
9. Respon Petani Tebu terhadap Harmonisasi Kemitraan dengan PG. Candi Baru ... 62
10. Total Biaya Produksi Usahatani Tebu pada Petani TRKSU dan TRM di PG Candi Baru-Sidoarjo ... 67
xi
15. Persentase Perbedaan Produksi, Biaya, Penerimaan dan
Pendapatan petani TRKSU dengan Petani TRM ... 74
16. Hasil Output SPSS Regresi faktor-faktor yang mempengaruhi
xii
1. Kuesioner Responden Petani TR-KSU dan TRM Wilayah
Kecamatan Candi-Sioarjo... 83
2. Biaya Produksi Tebu Petani TR-KSUdi Wilayah Kecamatan
Candi ... 88
3. Biaya Produksi Tebu Petani TRM di Wilayah Kecamatan Candi 89
4. Biaya Produksi Tebu per Hektar Petani TR-KSUdi Wilayah
Kecamatan Candi ... 90
5. Biaya Produksi Tebu per Hektar Petani TRM di Wilayah
Kecamatan Candi ... 91
6. Total Penerimaan Usahatani Tebu Pada Petani TRKSU di
Wilayah Kecamatan Candi ... 92
7. Total Penerimaan Usahatani Tebu Pada Petani TRM di
Wilayah Kecamatan Candi ... 93
8. Penerimaan per Hektar Usahatani Tebu Pada Petani TRKSU di Wilayah Kecamatan Candi ... 94
9. Penerimaan per Hektar Usahatani Tebu Pada Petani TRM di
Wilayah Kecamatan Candi ... 95
10. Total Pendapatan Usahatani Pada Petani TRKSU di Wilayah
Kecamatan Candi ... 96
11. Total Pendapatan Usahatani Pada Petani TRM di Wilayah
xiii
Dengan Menggunakan SPSS ... 98
14. Hasil Perhitungan Perbedaan Pendapatan Pada Petani TRKSU dan TRM Dengan Menggunakan SPSS ... 99
15. Surat Perjanjian antara PG. Candi Baru dengan Petani TRKSU .... 100
16. Surat Perjanjian antara PG. Candi Baru dengan Petani TRM ... 104
17. Hasil Output SPSS Regresi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tebu merupakan salah satu tanaman yang banyak diusahakan oleh petani,
sehingga tebu mempunyai arti penting dalam menyusun pendapatan petani, di
samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Untuk menjaga
agar produksi gula jangan sampai menurun serta meningkatkan pendapatan
khususnya petani tebu, langkah yang ditempuh pemerintah adalah melalui
program kemitraan yang dikenal dengan Tebu Rakyat Mandiri dan Tebu Rakyat
Kerja Sama Usahatani (Mirzawan, 2001).
Bentuk kerjasama yang terjalin antara petani dan PG Candi Baru ada dua
macam diantaranya adalah Tebu Rakyat Kerjasana Usaha (TRKSU) dan Tebu
Rakyat Mandiri (TRM). TRKSU merupakan kemitraan kerjasama usaha antara
petani tebu dengan pabrik gula, dimana pabrik gula memberikan biaya garap,
bibit, pupuk, hebrisida, dan alat-alat, selain itu petani diberikan bimbingan teknis
dan penyuluhan serta jaminan pengelolahan seluruh hasil panen oleh pabrik gula.
TRM merupakan bentuk kerjasama antara tebu rakyat dengan pabrik gula dimana
mengembangkan usahataninya secara swadaya dengan pengelolahan hasil
panennya oleh pabrik gula yang menjadi mitra kerjanya.
Pelaksanaan pola kemitraan ini, diharapkan dapat tercipta suatu usaha
pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan
keterampilan kelompok oleh perusahaan kemitraan melalui perwujudan sinergi
1. Saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan
bahan baku dan kelompok mitra memerlukan akses terhadap modal,
peningkatan pendapatan dan bimbingan manajemen serta teknologi.
2. Saling memperkuat dalam arti kelompok mitra maupun perusahaan mitra
sama-sama memperhatikan tanggungjawab moral dan etika bisnis,
sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing melalui
peningkatan daya saing.
3. Saling menguntungkan yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan
mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.
Sebagai pertimbangan rasionalitas dan azas manfaat, di masa mendatang
akan sulit bagi pabrik gula di Indonesia untuk tetap bertahan tanpa dukungan
bahan baku dari para petani. Pemerintah harus menyiapkan kesediaan dan
kemampuan memasok bahan baku sejumlah tertentu jika menginginkan pabrik
gula di daerah tersebut tetap beroperasi. Di samping itu hubungan “kemitraan” ini
merupakan suatu tuntutan obyektif dari pabrik gula untuk mencukupi kapasitas
gilingnya. Hubungan kemitraan ini dirintis antara lain dengan terbentuknya APTR
(Asosiasi Petani Tebu Rakyat), yang dari segi teori pengembangan oraganisasi
dapat dilihat sebagai perubahan yang menuntut pabrik gula untuk
mengembangkan organisasi melalui hubungan “kemitraan” dalam bisnisnya. Pola
didasarkan pada prinsip saling menguntungkan sebagai pemroses (mengolah tebu
menjadi gula). Keberadaan keduanya sejajar satu sama lain. Hal ini penting karena
hubungannya pada dasar strategis bisnis yang dilakukan oleh dua lembaga
bersama ataupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan
saling mengisi. Dalam kemitraan harus ada kodeterminasi (determinasi timbal
balik) karena aliansi strategis yang memacu kemitraan bila tidak dapat
kodeterminasi akan menjadi kemitraan semua, bahkan akan membentuk
eksploitasi baru. Terciptanya pola tersebut yang sinergis antara pabrik gula dan
petani akan mewujudkan kultur teknis yang saling menguntungkan (Win-win).
Menyatukan sikap dan perilaku yang heterogen akan membuat petani menyukai
visi dan misi yang sama dengan pabrik gula pembina (Mirzawan, 2001).
Tujuan kemitraan yang sesungguhnya yaitu tujuan yang diharapkan oleh
masing-masing pihak dapat mencapai kesetaraan walau pada pelaksanaannya
masih menemui beberapa kendala. Kendala utama adalah isu rendemen.
Penentuan rendemen pada sistem bagi hasil merupakan hal yang kritikal karena
menentukan pendapatan petani dan pabrik gula. Sering kali dijumpai di lapangan
perselisihan antara petani dan pabrik gula dalam masalah rendemen tebu. Petani
menganggap bahwa penentuan rendemen oleh pabrik gula tidak transparan dan
cenderung merugikan petani. Banyak orang berpendapat bahwa ketentuan sistem
bagi hasil tebu itu kurang adil karena pabrik gula yang “hanya” menggiling tebu
mendapatkan bagian yang cukup besar. Selain itu masih terdapat pandangan
bahwa masih ada hasil sampingan dari tebu yang tidak dibagi. Anggapan orang
demikian memang sepintas masuk akal, tetapi perusahaan gula berpendapat lain
karena ketentuan bagi hasil sangat ketat dalam kaitannya dengan pengoperasian
perusahaan secara ekonomis. Alasan utama peninjauan kembali ketentuan sistem
dan pabrik gula sebagai pemroses bahan baku yang sama-sama tidak mau
dirugikan meskipun cara seperti itu sebenarnya kurang menguntungkan bagi
pabrik gula, tetapi apabila ditunjang peningkatan mutu tebu bermanfaat bagi
petani maupun pabrik gula (Mirzawan, 2001).
Seperti yang dikutip dari media tertanggal 22 Juni 2010; puluhan petani
tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) mendatangi PG
X. Selain membawa potongan tebu, mereka juga menggelar beberapa poster berisi
tuntutan. Petani tebu mengeluhkan anjloknya rendemen tebu dari musim giling
pertama dengan rendemen 7.0, tapi saat ini turun menjadi 5.02. Ditambahkan, saat
buka giling 23 Mei 2010, rendemen tebu rakyat di PG X mencapai 7. Tapi
semakin hari jumlahnya terus menurun. Petani tebu menduga turunnya jumlah
rendemen ini lantaran ada permainan. Petani tebu berharap rendemen bisa kembali
meningkat. Sebab, jika turun drastis, petani tebu bisa merugi. Sayangnya harapan
petani tebu untuk bisa bertemu dengan pihak PG X ini tak tercapai. Pihak PG X
tak bersedia bertemu dan massa tak lama kemudian membubarkan diri
(www.beritajatim.com"air/isa").
Para petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat
Indonesia (APTRI) menggelar unjuk rasa menentang penerapan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen yang dibebankan ke petani tebu setiap kali
menjual tebu mereka ke pabrik gula. Mereka juga menentang beredarnya tebu
rafinasi di pasaran. Aksi ini mereka gelar dengan mendatangi pabrik-pabrik gula
yang menguasai pasaran dengan selisih Rp 1.500 per kilogram, kini dibebani PPN
( http://www.surya.co.id/ ).
Penyimpangan yang terjadi dalam konteks kemitraan antara petani tebu
dan pabrik gula sedikit-banyak dapat mempengaruhi proses produksi pabrik gula.
Jika demikian, maka dampak yang dirasakan tidak hanya oleh pihak pabrik gula
namun para petani tebu pun akan terkena imbasnya. Oleh karena itu maka
penelitian tentang kemitraan antara Pabrik Gula dengan petani tebu perlu
dilakukan agar dalam pelaksanaannya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan
namun sama-sama merasa saling diuntungkan.
1.2. Perumusan Masalah
Pabrik Gula Candi Baru dalam menjalankan proses produksinya tidak
lepas dari keterkaitan petani tebu sebagai pemasok bahan baku industri gula.
Kerjasama yang telah dibangun melalui hubungan kemitraan antara petani tebu
dengan Pabrik Gula (PG) sehingga terbentuk suatu kerjasama yang baik. Menurut
Fadjar (2006) meskipun pelaksanaan program kemitraan usaha perkebunan belum
dapat mengatasi ketimpangan (antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat)
secara maksimal, namun dengan pemberdayaan petani mitra dan juga perusahaan
mitra menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif, kelemahan tersebut
dapat diperbaiki.
Tingkat pendidikan petani yang masih rendah tentu dapat mempengaruhi
pola pikir mereka dalam menjalankan usahatani yang mereka kelola. Dampaknya
tentu akan berlanjut terhadap hasil usahatani mereka. Pemikiran yang masih
usahatani Tebu Rakyat (TR) kepada kelompok tani. Hal ini menyebabkan hasil
yang diperoleh kurang memuaskan dan kurang sesuai dengan harapan pabrik gula.
Demi tercapainya suatu pola kemitraan antara PG dengan petani kelompok
tani lebih erat lagi dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak tersebut,
maka tidak menutup kemungkinan banyak masalah yang dihadapi baik itu dari
pihak PG sendiri sebagai penyedia sarana produksi, mengadakan bimbingan dan
penyuluhan kepada petani TR yang bekerjasama dengan pihak pemerintah
maupun dari pihak peserta TR itu sendiri juga mengalami masalah. Masalah yang
sering terjadi misalnya: kerusakan panen, turunnya rendemen, kesulitan tebang
angkut dan lain-lain. Naik turunnya produksi tebu berpengaruh langsung pada
besar kecilnya rendemen yang dihasilkan, maka jelas ada kepentingan dari kedua
belah pihak untuk saling kerjasama yang baik dan harmonis agar produksi tebu
maupun hasil gula dapat meningkat.
Bertolak dari uraian di atas, maka penulis melihat kajian mendalam
terhadap rakyat kemitraan yang telah berjalan. Dari sini dapat dilakukan perbaikan
terhadap konsep dan pelaksanaan strategi kemitraan yang sedang berjalan, agar
menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku kemitraan.
Untuk itu penulis berkeinginan mengungkapakan permasalahan dan pelaksanaan
kemitraan antara Pabrik Gula Candi Baru dan petani tebu mitra. Sebagai langkah
awal dari penelitian, permasalahan yang ada dikemukakan dalam
pernyatan-pernyataan berikut ini :
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kemitraan antara Pabrik Gula Candi Baru
2. Apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan program kemitraan
tersebut?
3. Bagaimana harmonisasi kemitraan yang terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru
dengan petani tebu mitra?
4. Berapa perbedaan biaya usahatani, penerimaan dan pendapatan antara petani
TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani) dan petani TRM (Tebu Rakyat
Mandiri)?
1.3. Tujuan dan Manfaat
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk:
1. Mendiskripsikan prosedur pelaksanaan kemitraan antara Pabrik Gula Candi
Baru dengan petani tebu mitra.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kemitraan di Pabrik Gula
Candi Baru.
3. Mengetahui harmonisasi kemitraan yang terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru
dengan petani tebu mitra, dalam kaitannya dengan perjanjian kemitraan.
4. Menganalisa perbedaan biaya usahatani, penerimaan dan pendapatan antara
petani TRKSU dan petani TRM Pabrik Gula Candi Baru.
Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagi petani sebagai bahan untuk memperbaiki prosedur kemitraan yang telah
ada sehingga antara petani tebu dengan Pabrik Gula Candi Baru lebih saling
2. Bagi Pabrik Gula sebagai bahan tinjauan kemitraan di masa yang akan
datang.
3. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi kekurangan
dalam kemitraan khususnya antara Pabrik Gula dengan petani tebu di
Indonesia.
1.4. Ruang Lingkup
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja perkebunan tebu Pabrik Gula
Candi Baru dengan petani tebu dan Pabrik Gula sebagai objeknya. Data yang
digunakan sebagai acuan dari penelitian yaitu data yang terjadi pada musim tanam
2009/2010 atau pada musim giling tahun 2010. Data yang diperlukan dalam
penelitian ini yaitu (data primer dan data sekunder) yang menyangkut budidaya,
besarnya biaya, penerimaan, dan pendapatan petani tebu dengan kaitannya
terhadap kemitraan (pelaksanaan, harmonisasi dan kendala-kendala) yang terjadi
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Suatu teori atau konsep setelah diteliti di berbagai tempat hasilnya
menunjukkan tingkat ketepatan yang relatif sama, maka obyektivitas teori tersebut
cukup tinggi dan dapat digunakan untuk keperluan praktis diberbagai tempat
dengan alasan tersebut, maka dikemukakan berbagai penelitian terdahulu yang
sejenis dengan penelitian ini antara lain:
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriati dkk (2006) dengan judul Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat Dengan PTPN VII Unit Usaha Bungamayang Dalam Usahatani Tebu: Kasus Di Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara, menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas hubungan kemitraan antara petani tebu anggota Tebu Rakyat Kredit
(TRK) dengan Tebut Rakyat Bebas (TRB) dengan PTPN VII Unit Usaha
Bungamayang, terlihat dalam hal hak dan kewajiban petani, hak dan kewajiban
PTPN VII Unit Usaha Bungamayang, kredit, pengolahan, dan bagi hasil. Faktor
yang berhubungan dengan keputusan petani menjadi anggota TRK adalah faktor
modal, akses ke lahan, dan pengalaman. Sedangkan faktor luas lahan tidak
berhubungan dengan keputusan petani menjadi anggota TRK. Pendapatan
rata-rata petani TRK lebih besar dari pendapatan rata-rata-rata-rata petani TRB yaitu Rp
15.969.443,23 untuk petani TRK dan Rp 13.591.636,84 untuk petani TRB.
Menurut Setyawati (2003) melakukan penelitian dengan judul “Sistem
Kabupaten Kediri mengemukakan bahwa pelaksanaan sistem kemitraan antara
petani jagung Hibrida dengan PT. BISI Kediri berjalan dengan baik sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati sehingga secara ekonomi petani mitra
memperoleh peruntungan lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak
bermitra. Konsep model kemitraan yang sesuai dengan kemampuan dan dapat
dilaksanakan oleh petani yaitu petani memperoleh saprodi (pupuk, obat-obatan)
dibawah harga umum, penentuan harga beli oleh kedua belah pihak (petani dan
PT. BISI Kediri) serta surat perjanjian kerjasama harus dimiliki oleh kedua belah
pihak yaitu petani mitra dan PT. BISI Kediri.
Menurut Iin Kristyana Dewi (2001) melakukan penelitian dengan judul
“Studi tentang Pola Kemitraan Pada Pengusaha Padi di PT. Sang Hyang Seri
cabang Jawa Timur dan Bali (studi kasus di Dusun Kebon Waris, Kecamatan
Pandaan Kabupaten Pasuruan)” mengemukakan bahwa pola kemitraan yang
dijalin antara PT. Sang Hyang Seri dengan petani mitra dapat meningkatkan
pendapatan usahataninya. Serta pola kemitraan pengusaha benih padi secara
ekonomis layak diusahakan, karena hasil analisis B/C Ratio menunjukkan angka
9,2 yang artinya bahwa pengusaha benih padi oleh petani mitra dengan PT. Sang
Hyang Seri sangat layak untuk dikembangkan.
Berdasarkan gambaran penelitian terdahulu, maka penelitian ini berusaha
menelaah lebih lanjut mengenai :
1. Kemitraan pelaksanaan pola kemitraan yang dilakukan antara PG Candi
2. Telaah permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi antara PG dan
petani.
3. Telaah perbedaan pendapatan antara petani TRKSU dengan petani TRM.
2.2. Industri Gula di Indonesia
Permintaan gula secara nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan
industri pengolahan makanan dan minuman. Sebagai negara berpenduduk besar
dengan pendapatan yang terus meningkat, maka Indonesia amat potensial menjadi
salah satu konsumen gula terbesar di dunia. Dengan struktur pasar gula (white sugar maupun raw sugar) yang oligopolistik, terdapat resiko yang tinggi akan ketidakpastian dan ketidakstabilan harga. Ketidakstabilan harga akan
menyebabkan ketidakstabilan para petani tebu, yang berjumlah sekitar 343 ribu
rumah tangga petani. Selain itu, ketergantungan yang besar pada impor gula dapat
mengancam kemandirian Indonesia, disamping pengurasan devisa yang
diperlukan untuk pembangunan ekonomi serta pelunasan hutang luar negeri
(Anonymous, 2005)
Dilihat dari sisi sumber daya alam (SDA) dan iklim, Indonesia mempunyai
keunggulan komparatif sebagai produsen gula tebu, karena tebu merupakan
tanaman tropis yang secara alamiah telah tumbuh secara meluas di daerah tropis.
Hal ini dapat dibuktikan dari kenyataan Inustri gula Indonesia pernah jaya pada
periode penjajahan Belanda. Kejayaan itu tentunya hanya dapat diraih manakala
secara tepat dan efisien (baik di tingkat usahatani maupun di tingkat pabrik gula),
sehingga dapat memberikan keuntungan yang memadai.
Usahatani tebu pada umumnya dikelola oleh petani, sedangkan Pabrik
Gula dikelola oleh perusahaan gula. Keduanya bermitra, petani sebagai pemasok
bahan baku tebu dan PG mengolah tebu menjadi gula dalam suatu sistem bagi
hasil. Dalam hubungan kemitraan itu, kegiatan produksi gula sesungguhnya
terbagi menjadi dua bagian, yaitu petani menghasilkan gula dalam bentuk sukrosa
yang tersimpan dalam batang tebu, dan PG mengambil sukrosa dalam batang tebu
dan mewujudkannya dalam bentuk kristal. Hubungan produksi yang demikian itu
mengandung potensi konflik kepentingan, terutama pada saat pengaturan
pembagian manfaat.
Indonesia telah berubah dari negara eksportir gula pasir dunia menjadi
importir, hal ini disebabkan perkembangan produksi yang lambat apabila
dibandingkan dengan pertambahan yang cepat dari permintaan dalam negeri
sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kenaikan pendapatan per kapita.
Konsumsi gula di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat disebabkan
oleh pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta
semakin banyak industri memerlukan gula pasir sebagai bahan baku. Karena
produksi dalam negeri tidak mampu mengimbangi laju permintaan, sehingga
Indonesia terpaksa melakukan impor gula dalam jumlah yang besar untuk
menutupi kekurangan dalam negeri itu sendiri (Djoehana S dan Husaini A, 1992).
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Departemen
364/MPP/Kep/8/1999. Instrumen utama kebijakan tersebut adalah pembatasan
jumlah importir dengan hanya mengijinkan importirprodusen. Dengan kebijakan
ini, pemerintah dapat membatasi dan mengendalikan volume impor disamping
memiliki data yang lebih valid mengenai volume impor dan stok. Dengan
demikian, harga gula daam negeri dan harga gula di tingkat petani dapat
ditingkatkan (Anonymous, 2005).
Kebijakan importir-produsen tersebut ternyata masih kurang efektif, baik
untuk mengangkat harga gula di pasar domestik maupun mengontrol volume
impor. Walaupun tidak ada data pendukung yang memadai, kegagalan tersebut
terutama disebabkan oleh stok gula dalam negeri yang sudah terlalu banyak dan
adanya gula impor ilegal. Situasi ini membuat harga gula di pasar domestik tetap
rendah. Oleh karena itu, desakan petani dan pabrik gula terhadap pemerintah
untuk melindungi industri gula dalam negeri semakin kuat. Menanggapi tekanan
ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tarif impor melalui Keputusan menteri
Perindustrian dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/6/1999 yang memberlakukan
tarif impor gula sebesar 20 persen untuk raw sugar dan 25 persen untuk white
sugar. Walaupun masih menimbulkan kontroversi, kebijakan tarif impor ini secara
bertahap dapat mengangkat harga gula di pasar domestik (Sri Wahyuni, 2009).
2.3. Kemitraan
2.3.1. Pengertian dan Bentuk Kemitraan
Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak
atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama
suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya
kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis (Hafasah,
2000).
Kemitraan menurut pengertian umum adalah hubungan usaha antara kecil
dan atau koperasi dan usaha menengah atau besar yang disertai dengan bantuan
pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia, pemasaran, teknik industri,
modal kerja, kredit perbankan oleh usaha menengah atau besar dengan prinsip
saling menguntungkan. Khususnya untuk kemitraan antara Petani Tebu Rakyat
dengan Pabrik Gula diperlukan adanya ‘rasa saling mempercayai’ berkaitan
luasnya dengan jangkauan kerjasama, sehingga kepercayaan menjadi hal yang
amat penting.
Program kemitraan antara Pabrik Gula dengan petani dilakukan
berdasarkan kesepakatan yang melandasi yaitu peraturan pemerintah RI No.44
tahun 1997 tentang kemitraan (pasal 1) yaitu:
Ayat 1: kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha
menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling
memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
Ayat 2: usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang
mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 9 tahun
1995 tentang usaha kecil.
Ayat 3: usaha menengah dan atau usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang
besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha
kecil (Hafsah J, 2000).
Kemitraan mirip suatu rangkaian proses yang menurut John L. Mariotti
(1993) dalam Nurani (2008) dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya melalui membangun
strategi, melaksanakan dan terus memonitor dan mengevaluasi sampai target
sasaran tercapai. Proses ini benar-benar dicermati sejak awal sehingga
permasalahan yang timbul dapat diketahui baik besarnya permaslahan maupun
langkah-langkah yang perlu diambil. Di samping itu perubahan peluang dan pasar
yang timbul dapat segera diantisipasi sehingga target yang diinginkan dicapai
tidak mengalami perubahan. Rangkaian urutan proses pengembangan kemitraan
merupakan suatu urutan tangga yang disepakati secara beraturan dan bertahap
untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Dengan demikian kemitraan adalah bentuk hubungan kerjasama usaha
yang berjalan selama ini ada beberapa macam dan penerapannya disesuaikan
dengan kondisi perusahaan, petani, komoditas dan kondisi daerah setempat, antara
lain:
1. Berdasarkan Jangka Waktu
a. Kemitraan Insidentil
Merupakan model kemitraan yang didasari atas kepentingan
kegiatan yang bersangkutan telah selesai. Kemitraan seperti ini dijalin
pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil usahatani. Contoh:
Kemitraan antara petani sayuran dengan pasar swalayan.
b. Kemitraan Jangka Menengah
Merupakan kemitraan berdasarkan motif ekonomi bersama dalam
jangka menengah atau musim produksi tertentu. Kemitraan seperti ini dapat
dilakukan dengan atau tanpa perjanjian tertulis (kontrak atau kesepakatan).
Contoh: Perkebunan inti rakyat.
c. Kemitraan Jangka Panjang dan Terus Menerus
Merupakan kemitraan yang didasarkan atas saling ketergantungan
dalam hal pengadaan bahan, permodalan, menejemen, dan lain-lain.
Kemitraan seperti ini dilakukan dalam jangka panjang dan terus menerus
dalam skala besarperjanjian tertulis (kontrak atau kesepakatan). Contoh:
Pemilikan petani atau koperasi, misalnya tebu rakyat.
2. Bedasarkan Kerjasama yang Terjalin
a. Sistem Kontrak Kerja
Dalam pola ini petani atau koperasi dan perusahaan menjalin
hubungan kerjasama dengan melakukan kontrak kerja, baik dalam
penyediaan sarana produksi dari perusahaan maupun jaminan pemasaran
hasil produksi petani ke perusahaan dengan demikian kegiatan agribisnis
perusahaan yang hanya terbatas pada proses pengolahan (agroindustri) dan
b. Bentuk Kontrak Manajemen
Bentuk kemitraan dengan ini berupa bantuan menejemen usahatani
dari lembaga yang berpengalaman seperti, koperasi jasa menejemen maupun
perusahaan agroindustri yang telah memliki kemampuan dalam mengelolah
agribisnis kepada petani atau lembaga tani dalam ikatan kontrak. Dalam
pola ini koperasi jasa menejemen atau perusahaan agroindustri melayani
kegiatan menejerial usaha agribisnis yang dikembangkan petani atau
koperasi yang sekaligus melakukan bimbingan dan pembinaan kepada
petani dan pengurus koperasi.
c. Pola Unit Pelaksana Proyek
Pola ini menyertakan peran aktif pemerintah dalam pembentukan
usaha agribisnis. Sejak awal sampai saat dikonversikan kepada petani,
pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil
mendapatkan bantuan serta dukungan pembinaan dan pengendalian dari
pemerintah, berupa bantuan yang merupakan pinjaman yang harus
dikembalikan.
d. Perusahaan Inti Rakyat
Perusahaan agroindustri yang memiliki skala usaha besar bertindak
sebagai inti, sedangkan petani sekitarnya sebagai plasma inti yang sangat
besar peranannya dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil,
e. Perusahaan Petani
Petani atau koperasi yang pada umumnya kesulitan permodalan,
membentuk usaha patungan berupa suatu perusahaan baru (misalnya:
perusahaan penyalur saprotan) dengan perusahaan agroindustri yang
menyertakan saham masing-masing secara bertahap. Apabila petani atau
koperasi telah mampu menjalankan perusahaan maka pemilikan keseluruhan
saham dialihkan kepada petani atau koperasi.
f. Perusahaan Petani Terpadu
Pembentukan perusahaan baru dengan pola ini sama seperti pola
perusahaan petani, hanya saja dalam pola ini saham milik perusahaan tetap
pada perusahaan baru tersebut. Seluruh kegiatan agribisnis perusahaan
dilakukan bersama-sama, perusahaan semacam ini memerlukan perwakilan
petani atau koperasi dalam jajaran menejemen perusahaan baik pada tingkat
operasional maupun tingkat pengawasan.
3. Berdasarkan Sumber Dana Pengaturan Permodalan
a. Kerjasama dengan Sistem Bagi Hasil
Bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu antara petani dengan
perusahaan pembimbing dengan perhitungan yang telah ditetapkan dalam
perjanjian. Sumber permodalan kerjasama ini berasal dari perusahaan
pembimbing yang berupa sarana produksi seperti: bibit, pupuk dan
obat-obatan dan ditambah dengan biaya pengolahan tanah, pemeliharaan sampai
b. Sistem Kredit Koperasi
Diperlukan kerjasama antara tiga pihak yaitu: perusahaan, KUD,
perbankan. Sistem ini hanya dapat dilakukan dalam KUD dengan ketentuan
bahwa KUD mampu bertindak sebagai koordinator dan telah bebas dari
tanggungan kredit lama.
2.3.2. Syarat Kemitraan Usaha Pertanian
Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor:
946/Kpts/OT.210/10/1997, tentang syarat kemitraan usaha pertanian adalah
sebagai berikut:
1. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani atau nelayan dan
pengusaha kecil pertanian lainnya.
b. Memiliki teknologi dan menejemen yang baik.
c. Menyusun rencana kemitraan.
d. Berbadan hukum dan memiliki bonafiditas.
2. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh
pemerintah daerah.
3. Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan perjanjian
kemitraan terlebih dahulu.
4. Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk
kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah,
pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan yang memberikan
2.3.3. Perjanjian Kerjasama
Untuk meresmikan kerjasama kemitraan ini, perlu dilakukan dalam suatu
surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang
bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama itu
dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi hak dan kewajiban dari
masing-masing pihak yang menjalin kerjasama.
Adapun kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban Perusahaan (Pabrik Gula)
a. Melaksanakan bimbingan usahatani kepada petani tebu.
b. Penjaminan pinjaman petani kepada bank.
c. Melayani saprodi.
d. Menaati perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
2. Kewajiban Petani
a. Menyediakan lahan.
b. Mengerjakan lahan.
c. Memasarkan hasil kepada perusahaan.
d. Menaati perjanjian yang telah disepakati.
Kemitraan yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan
pengusaha kecil dan koperasi mempunyai beberapa alternatif dalam
pengembangan kemitraan yaitu:
1. Kemitraan inti plasma, yakni adanya perusahaan sebagai inti sedangkan plasma
2. Kemitraan subkontrak yaitu hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha
dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan
oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya.
3. Kemitraan dagang umum, yaitu hubungan kemitraan mitra usaha yang
mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan.
4. Kemitraan keagenan, yaitu salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha
kecil diberi hak khusu untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah
atau usaha besar sebagai mitra.
5. Waralaba, yaitu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan
perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi (Hafsah, 2000).
2.3.4. Kebijakan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)
Program tebu rakyat adalah salah satu program intensifikasi nasional yang
berujuan meningkatkan produksi gula dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
petani tebu beserta keluarganya, melalui peningkatan pendapatan dari lahan petani
yang ditanami tebu oleh petani itu sendiri, selain itu kerjasama kelompok tani
pada satu hamparan usahatani guna memanfaatkan potensi lahan, daya dan dana
secara optimal dengan menerapkan teknologi anjuran.
Teknologi anjuran (Hasta Usaha) adalah usaha dalam proses produksi tebu
dan gula yang terdiri dari :
1. Penggarapan tanah yang baik
2. Penangkapan pada masa tanam optimum
3. Penggunaan bibit varietas unggul
5. Pemeliharaan tanaman yang tetap
6. Pengendalian jasad pengganggu
7. Penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman
8. Perlakuan panen dan pasca panen secara efisien (Anonymous, 2005)
Dengan terbitnya Inpres Nomor 9 tahun 1975 maka sistem produksi gula
di Indonesia terutama pabrik-pabrik gula di Jawa yang tidak memiliki lahan Hak
Guna Usaha (HGU) yang cukup luas mengalami perubahan mendasar. Pengusaha
tanaman tebu untuk bahan baku produksi gula tidak lagi dilakukan dipabrik gula
dengan cara menyewa lahan petani, tetapi dilakukan diatas lahan miliknya sendiri
dengan dukungan bimbingan masal (BIMAS) yang terprogram (Anonymous,
2005).
Pokok-pokok Inpres tersebut adalah:
1. Mengalihkan perusahaan tanaman tebu dari sistem sewa tanah oleh pabrik
gula menjadi tebu rakyat yang diusahakan petani diatas lahan milik
sendiri.
2. Meningkatkan produksi gula dan pendapatan petani tebu dengan
melakukan intensifikasi pada tebu rakyat (baik yang berasal dari
pengalihan sewa tanah maupun tebu rakyat yang sudah ada, dan
selanjutnya dikelola dalam wadah yang sama dengan intensifikasi tanaman
panganan).
3. Menugaskan pabrik gula dalam fungsi dan peran sebagai pimpinan kerja
penyediaan bibit unggul, penyediaan dan pelayanan sarana produksi dan
pelayanan kredit.
4. Mengikutsertakan KUD dan bimbingan untuk mengkoordinasikan petani
tebu rakyat agar produksi dan pendapatannya meningkat (Hasibuan Edi,
2005).
2.3.5. Sistem Bagi Hasil
Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.
527/MPP/Kep/9/2004 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Produktifitas Industri
Gula antara lain. Petani bebas memilih antara Sistem Pembelian Tebu (SPT) atau
Sistem Bagi Hasil (SBH) melalui kesepakatan antara Pabrik Gula dengan petani
yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
1. Berdasarkan hablur bagian petani dan Pabrik Gula dihitung berdasarkan
ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk rendemen tebu sampai dengan 8,90 % maka hablur bagian
petani adalah 65 % dari rendemen tebu yang dicapai.
b. Pada rendemen tebu diatas 8,90% maka agar petani terangsang
meningkatkan efisiensinya, maka hablur bagian petani dihitung
dengan rumus :
T = 50,8 + 1,6 x R dan
P = 100 – T
Dimana :
T = Hablur bagian petani dalam persen dari rendemen tebu
R = Rendemen tebu dari tebu rakyat yang diolah Pabrik Gula.
Bagi penyerahan tebu yang menggunakan Sistem Bagi Hasil (SBH), selain
hasil gula yang menjadi hak petani maka petani juga memperoleh tetes sebesar 2
kg setiap kwintal tebu.
2. Berdasarkan SK. Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Pemitraan Tebu Rakyat di Jawa Timur pada musim giling namun 1998 :
a. Dengan memperhatikan kondisi gula sebagai komoditi prioritas, maka
percadangan areal untuk penanaman tebu di lahan sawah diatur secara
bergiliran dengan komoditi lain atas dasar musyawarah dala rembung
desa. Sedangkan tebu di lahan tegalan dapat dikembangkan
seluas-luasnya dengan memperhatikan aspek konservasi lahan.
b. Pembinaan tebu rakyat ditempuh melalui kemitraan antar petani/
kelompok tani dengan Pabrik Gula yang disesuaikan dengan kondisi
masing-masing daerah yaitu secara prioritas dapat berbentuk :
1) Tebu Rakyat (TR) Kredit yaitu tebu rakyat yang dikembangkan
oleh petani dengan memanfaatkan kredit koperasi primer untuk
anggotanya KKP (Kredit Ketahan Pangan) dengan bimbingan
teknis dan pengolahan hasil oleh perusahaan mitra.
2) Tebu Rakyat Mandiri, yaitu tebu rakyat yang dikembangkan oleh
petani dengan modal sendiri dengan bimbingan teknis dan
pengolahan hasilnya oleh perusahaan mitra.
3) Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani (TR KSU) yaitu tebu rakyat
pengelolaannya pada perusahaan mitra atas dasar kesepakatan
bersama yang saling menguntungkan dengan memperoleh jaminan
penghasilan tertentu dengan memanfaatkan Kredit Ketahanan
Pangan atau kredit lainnya.
4) Sewa lahan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pola ini
diterapkan dalam keadaan terpaksa dimana ketiga pola diatas tidak
dapat terlaksana.
c. Bentuk – bentuk pola kemitraan antara petani dengan Pabrik Gula
tersebut diatas, pelaksanaanya tergantung pada pilihan petani sendiri
yang ditentukan pada saat motivasi.
d. Untuk menunjang kelancaran kegiatan motivasi dan musyawarah
dengan petani perlu dibentuk tim pemandu.
2.4. Analisis Ekonomi Usahatani
Usahatani adalah kegiatan ekonomi karena ilmu ekonomi beperan dalam
membantu pengembangannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari
alokasi sumber yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan kehendak manusia
yang tidak terbatas. Pada posisi yang demikian petani harus mengalokasikan
sumber daya usahatani atau yang lebih sering disebut faktor usahatani.
Usahatani sebagai kegiatan ekonomi, tentunya ada faktor yang
mempengaruhinya. Faktor-faktor ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap
produksi usahatani antara lain; cabang usaha, faktor produksi khususnya modal
tersebut diantara keputusan-keputusan yang harus didasarkan prinsip-prinsip
ekonomi ialah :
1. Menentukan kegiatan apa saja faktor produksi yang harus dipakai di dalam
perusahaan.
2. Menentukan jumlah berbagai faktor produksi yang harus dipakai di dalam
setiap kegiatan.
3. Menentukan jumlah seluruh modal yang diperlukan.
4. Memilih sumber-sumber modal yang paling baik.
5. Menentukan jumlah modal yang sebaiknya diambil dari setiap sumber
yang dipilih.
Petani sebagai pengelola usahatani termasuk pembiayanya adalah
seseorang yang membutuhkan dan berperan dalam perencanaan kegiatan bisnis
yang meliputi penyediaan dan pengalokasian dana. Langkah-langkah yang perlu
diperhatikan di dalam pengelolaan usahatani adalah:
a. Memformulasikan tujuan usaha
b. Identifikasi permasalahan usahatani
c. Menganalisa secara ekonomi keluarga
d. Menetapkan keputusan usaha
III. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
3.1. Kerangka Pemikiran
Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh Pabrik Gula Candi Baru dengan
petani tebu mitra baik TRKSU (Tebu Rakyat Usahatani) maupun TRM (Tebu
Rakyat Mandiri) di daerah tempat penelitian dianggap sudah sesuai dengan
harapan, karena antara pihak Pabrik Gula dan petani tebu sudah merasakan
adanya hubungan kerjasama yang saling membutuhkan dan saling
menguntungkan. Pihak pabrik gula membutuhkan pasokan bahan baku gula
berupa tebu yang dapat diusahakan oleh petani tebu. Sedangkan peihak petani
tebu membutuhkan pabrik gula untuk mengolah lebih lanjut hasil dari usahatani
mereke yaitu berupa batang tebu. Petani juga memerlukan tambahan dana sebagai
modal dalam menjalankan usahataninya sedangkan pihak Pabrik Gula dapat
mengupayakan dana tersebut untuk membantu petani tebu dengan cara
memberikan dana pinjaman kepada petani yang bermitra dengan Pabrik Gula
tersebut. Namun di sisi lain terdapat permasalahan-permasalahan yang belum
didapatkan jalan keluarnya, diantaranya kadar rendemen yang diperoleh selalu
menurun, perluasan areal lahan tebu yang semakin sempit dan akhirnya
berpengaruh terhadap pendapatan petani. Selain itu nampaknya perlu dilakukan
penyempurnaan-penyempurnaan karena kedua belah pihak perlu pembenahan
untuk meningkatkan produksi sehingga perlu adanya kerjasama yang harmonis
antara PG dengan petani tebu mitra agar terwujud suatu pola kemitraan yang
Dalam pelaksanaan pola kemitraan antara PG Candi Baru dengan petani
tebu mitra banyak kendala baik teknis maupun non teknis. Dalam sistem Tebu
Rakyat (TR) petani tebu mitra menjadi pengusaha yang secara penuh menanggung
berbagai resiko atau kendala, misalnya: kerusakan panen, turunnya rendemen,
kesulitan tebang, pengangkutan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dari segi ini
patut dipahami bahwa pabrik gulapun tidak sama sekali terbebas dari resiko atau
kendala tersebut. Secara teknis memang tugas tersebut dan pekerjaan pabrik gula
jauh lebih ringan dan sederhana yaitu semata-mata bertugas “menggiling” tebu
petani untuk dijadikan gula. Namun dalam kenyataan tidak demikian halnya,
dalam pekerjaan-pekerjaan non teknis beban pekerjaan pabrik gula menjadi
bertambah berat.
Pendapatan petani yang bermitra dengan petani yang tidak bermitra
dengan PG sangat berbeda sekali karena petani yang bermitra dengan PG selalu
diberikan bimbingan massal dan diberi modal secara kredit misalnya sarana
produksi yang sudah disediakan oleh Koperasi petani tebu yang bermitra dengan
PG. Dengan bekal ilmu yang bertambah maka pola pikir petani menjadi berubah
sehingga petani bisa mengembangkan usahatani tebu dengan baik karena apabila
kualitas tebu yang dihasilkan bagus maka gula yang dihasilkan juga bermutu
bagus, sehingga nilai jual gula semakin meningkat dan kemudian menambah
pendapatan petani. Sedangkan petani yang tidak bermitra dengan PG
pendapatannya lebih sedikit dibanding dengan petani yang bermitra karena petani
Secara sistematis bagan alur pemikiran dalam penelitian ditunjukkan pada
gambar berikut ini :
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Hak & Kewajiban
PG
Hak & Kewajiban Petani
Petani TRKSU Petani TRM
Produksi Tebu
Pabrik Gula
Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Petani
Uji Beda :
1. Total Biaya 2. Penerimaan
3. Pendapatan Evaluasi
3.2. Hipotesis
Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
1) Pelaksanaan kemitraan antara petani tebu mitra dengan PG. Candi Baru telah
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2) Pendapatan petani TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani) lebih besar
dibandingkan dengan pendapatan petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri) di PG.
IV. METODE PENELITIAN
4.1. Penentuan Lokasi
Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) di kecamatan Candi, Sidoarjo. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan bahwa di kecamatan Candi, Sidoarjo terdapat petani-petani tebu
yang bermitra dengan Pabrik Gula Candi Baru. Pabrik Gula Candi Baru
merupakan Pabrik Gula yang berada di wilayah Sidoarjo dan terdapat kemitraan
antara petani dan Pabrik Gula dalam proses produksinya. Keadaan yang demikian
maka kecamatan tersebut layak digunakan sebagai lokasi penelitian.
4.2. Penentuan Populasi dan Sample
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani tebu yang
menjadi mitra Pabrik Gula Candi Baru – Sidoarjo. Penentuan responden dalam
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu tehnik penentuan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, dimana setiap sampel dipilih
atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang
telah ditentukan yaitu para petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula Candi
Baru – Sidoarjo yaitu petani TR-KSU (Tebu Rakyat Kerja Sama Usahatani) dan
TRM (Tebu Rakyat Mandiri). Dari data sekunder yang diperoleh, maka diketahui
populasi petani mitra yaitu 398 orang yang terdiri dari petani TR-KSU (Tebu
Rakyat Kerjasama Usahatani) sebanyak 353 orang dan petani TRM (Tebu Rakyat
Berdasarkan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga kerja maka penentuan
jumlah sample diperoleh 30 orang responden yang digunakan untuk sample. Hal
ini sesuai dengan pendapat Wirartha, M (2005) yang menyatakan bahwa untuk
penelitian yang akan menggunakan analisis data dengan statistik, ukuran sample
paling terkecil yang diambil sebanyak 30 responden.
Petani tebu yang diambil sample sebanyak 30 orang yang terdiri dari 15
petani TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani) dan 15 petani TRM (Tebu
Rakyat Mandiri). Selain 30 responden, juga terdapat 3 orang yang mewakili dari
pihak Pabrik Gula Candi Baru-Sidoarjo guna melengkapi hasil penelitian ini.
4.3. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini membutuhkan beberapa macam data agar penelitian dapat
berlangsung sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap
jenis dan sumber data yang digunakan. Adapun jenis dan sumber data yang
diperlukan meliputi:
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan secara langsung dari
responden dengan cara observasi dan wawancara dengan bantuan kuesioner.
Responden yang diwawancarai bukan hanya petani tebu (petani TRKSU dan
petani TRM) melainkan juga instansi pabrik gula itu sendiri. Dari kuesioner yang
disebarkan maka akan diperoleh data antara lain; data luas lahan, respon terhadap
kemitraan (meliputi ketentuan yang diberikan PG dalam kaitannya dengan
rata-rata, kendala yang sering dihadapi (baik dari segi ekonomi, teknis ataupun
sosial) dan usaha penangananya.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan instansi terkait
yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi: data luas tanah desa di
kecamatan Candi, jumlah penduduk, jumlah petani, data kemitraan antara petani
tebu dengan PG. Candi Baru tahun 2009/2010, data rata-rata per hektar biaya
ekonomi produksi, penerimaan dan pendapatan petani TRKSU (Tebu Rakyat
Kerjasama Usahatani) dan TRM (Tebu Rakyat Mandiri).
4.4. Analisis Data
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang sudah dijelaskan
terahulu, maka analisis dalam penelitian ini digunakan berbagai analisis yaitu:
1. Untuk menjawab tujuan 1 (prosedur pelaksanaan kemitraan), 2
(Kendala-kendala dalam pelaksanaan kemitraan) dan 3 (Harmonisasi kemitraan)
menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data yang bersifat
kualitatif yakni menggambarkan bagaimana pelaksanaan kemitraan antara
petani tebu dengan PG Candi Baru, mengetahui kendala-kendala yang
sering dihadapi oleh PG dan petani mitra, harmonisasi kemitraan yang
terjadi antara Pabrik Gula Candi Baru dengan petani tebu mitra.
2. Untuk menjawab tujuan keempat yaitu perbedaan biaya usahatani,
penerimaan dan pendapatan antara petani TRKSU (Tebu Rakyat
Kerjasama Usahatani) dan petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri) Pabrik
rata-rata ini digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan antara
petani TRKSU dengan petani TRM di PG Candi Baru yang mana hipotesis
statistiknya sebagai berikut:
H0 : Tidak terdapat perbedaan nyata mengenai biaya usahatani,
penerimaan dan pendapatan antara petani TRKSU (Tebu Rakyat
Kerjasama Usahatani) dengan petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri).
H1 : Terdapat perbedaan nyata mengenai biaya usahatani, penerimaan
dan pendapatan antara petani TRKSU dengan petani TRM.
Taraf kepercayaan yang digunakan 95% atau α = 0,05. Uji ini dilakukan
dengan terlebih dahulu menguji beda tidaknya keragamannya dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Dimana :
= Nilai varian pendapatan petani TRKSU
= Nilai varian pendapatan petani TRM
= Contoh ke i
= Rata-rata pendapatan petani TRKSU
= Rata-rata pendapatan petani TRM
= Jumlah contoh petani TRKSU
= Jumlah contoh petani TRM
Dengan kaidah pengujiannya:
a) Bila t hitung < t tabel 0,05 maka terima H0 dan tolak H1 artinya bahwa
pendapatan petani TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani) dengan
petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri) tidak terdapat perbedaan yang nyata.
b) Bila t hitung > t tabel 0,05 maka terima H1 dan tolak H0 artinya bahwa
pendapatan petani TRKSU dengan petani TRM terdapat perbedaan yang
nyata.
4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Pengertian ini menggunakan beberapa istilah dalam pengukuran variabel,
berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis dari
istilah-istilah yang digunakan dalam analisa adalah sebagai berikut:
1. TR (Tebu Rakyat)
TR adalah pengusahan tanaman tebu oleh petani yang dilakukan dalam
kaitannya dengan kerjasama kelompok tani pada suatu hamparan usahatani guna
memanfaatkan potensi lahan, daya dan dana secara optimal dengan menerapkan
teknologi anjuran.
2. TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani)
TRKSU adalah kemitraan kerjasama usaha antara petani tebu dengan pabrik
alat-alat, selain itu petani diberikan bimbingan teknis dan penyuluhan serta
jaminan pengelolahan seluruh hasil panen oleh pabrik gula.
3. TRM (Tebu Rakyat Mandiri)
TRM adalah bentuk kerjasama antara tebu rakyat dengan pabrik gula dimana
mengembangkan usahataninya secara swadaya dengan pengelolahan hasil
panennya oleh pabrik gula yang menjadi mitra kerjanya
4. Produksi Tebu
Produksi Tebu adalah jumlah tebu yang dihasilkan oleh petani pada satu kali
musim panen (±12 bulan). Untuk mengukur besarnya produksi tebu yaitu dengan
membagi jumlah tebu yang dihasilkan dengan luas lahan tebu. Satuan yang
digunakan pada umumnya yaitu ton/ha.
5. Usahatani Tebu
Usahatani Tebu adalah upaya petani dalam membudidayakan tanaman tebu
guna diambil hasilnya baik untuk dikonsumsi (rumah tangga) maupun dijual
(petani tebu dan pabrik gula) guna mendapatkan uang tunai.
6. Pendapatan / Keuntungan
Pendapatan atau Keuntungan adalah selisih antara seluruh penerimaan dengan
biaya total usahatani tebu selama satu musim tanam diukur dengan satuan rupiah
per masa panen (±12 bulan).
Rumus : π = TR – TC
Dimana : TR = penerimaan total (Total Revenue)
TC = biaya total (Total Cost)
7. Sistem Bagi Hasil
Sistem Bagi Hasil adalah tata cara penyerahan tebu dari petani/kelompok tani
kepada pabrik gula. Petani/kelompok petani menerima bagi hasil gula sesuai
kesepakatan dengan APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) yaitu 66:34 untuk mitra
TR-KSU (66% untuk petani dan 34% untuk PG) dan 80:20 untuk mitra TRM
(80% untuk petani dan 20% untuk PG).
8. Rendemen
Rendemen adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan
dengan persen. Bila dikatakan rendemen tebu 10%, artinya ialah bahwa dari
100kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg
(www.google.co.id/pengertian-rendemen).
9. Hablur
Hablur adalah gula sukrosa yang dikristalkan dan masih mengandung kotoran
tebu atau endapan (www.rudyct.com/pps702-ipb).
10. Penerimaan
Penerimaan adalah hasil produksi dikalikan dengan harga per satuan
produksi.
Rumus : TR = P x Q
Dimana: TR = Total Revenue/Total Penerimaan (Rp)
P = Harga Produksi (Rp)
11. Hak dan Kewajiban Perusahaan Mitra
Hak dan kewajiban digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan hubungan
kemitraan ini sehingga berjalan dengan lancar. Pada hubungan kemitraan, hak
petani tebu anggota merupakan kewajiban PG sedangkan kewajiban petani tebu
anggota merupakan hak dari PG mitra.
Adapun kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut (Sriati,
2006):
1. Kewajiban Perusahaan
a. Melaksanakan bimbingan usahatani kepada petani.
b. Penjaminan pinjaman petani kepada bank.
c. Melayani saprodi.
d. Menaati perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
2. Kewajiban Petani
a. Menyediakan lahan.
b. Mengerjakan lahan.
c. Memasarkan hasil kepada perusahaan.
d. Menaati perjanjian yang telah disepakati.
3. Hak Perusahaan
a. Mendapatkan jaminan lahan untuk usahatani tebu dari petani.
b. Mengawasi pelaksanaan usahatani tebu dari pra tanam hingga pasca panen.
c. Memperoleh hasil panen tebu dari petani.
4. Hak Petani
b. Mendapatkan pinjaman modal untuk usahatani tebu.
c. Mendapatkan pinjaman berupa saprodi untuk mempermudah petani dalam
mengerjakan usahataninya.
12. Harmonisasi Kemitraan
Harmonisasi Kemitraan adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan
dalam bermitra yang dijalankan oleh petani tebu mitra dengan Pabrik Gula Candi
Baru-Sidoarjo. Suatu keharmonisan dapat diukur melalui keselarasan antara
petaturan dengan pelaksanaan, tingkat kepercayaan oleh masing-masing pihak,
dan juga tingkat kepuasan yang dicapai dengan adanya suatu perjanjian.
13. Kemitraan
Kemitraan adalah kerajasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau
dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan
oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling
V. KEADAAN UMUM WILAYAH
5.1. Keadaan Geografis
Kecamatan Candi terletak kurang lebih 26 km dari kota Provinsi Surabaya
dan 6 km dari pusat kota Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Candi berada pada
ketinggian ± 4 meter dari permukaan air laut dan termasuk kedalam daratan
rendah dengan curah hujan rata-rata 2.100 mm/tahun dengan jumlah 29 hari.
Memiliki luas daerah 4.549.842 Ha yang terdiri dari 24 desa. Adapun batas
wilayah Candi antara lain sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Sidoarjo
Sebelah Timur : Kecamatan Sidoarjo
Sebelah Selatan : Kecamatan Tanggulangin dan Porong
Sebelah Barat : Kecamatan Tulangan
Kecamatan Candi merupakan salah satu wilayah di Kota Sidoarjo yang
memiliki Pabrik Gula dengan jumlah petani mitra yang cukup besar. Dipilihnya
Kecamatan Candi untuk suatu penelitian dikarenakan oleh sebagian besar
masyarakat di sekitar yang berprofesi sebagai petani tebu memilih untuk bermitra
dengan PG Candi Baru.
Penggunaan tanah di kecamatan Candi dari pemukiman penduduk,
perkebunan, pertanian, tegal, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya penggunaan
Tabel 1. Penggunaan Tanah di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009
Jenis Luas (Ha) Persentase (%)
Tanah Sawah 974.168 21,41
Irigasi Teknis/setengah teknis 1.614.833 35,49
Pemukiman 597.686 13,14
Tambak 1.031.655 22,67
Fasilitas Umum 331.500 7,29
Jumlah 4.549.842 100
Sumber : Data Sekunder
Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di
Kecamatan Candi sebagian besar untuk Irigasi teknis/setengah teknis yaitu
1.614.833 Ha atau sekitar 35,49 %. Sedangkan untuk tanah sawah 974.168 Ha
atau sekitar 21,41 %, untuk tanah pemukiman 597.686 Ha atau sekitar 13,14 %,
untuk Tambak 1.031.655 Ha atau 22,67 % dan untuk fasilitas umum 331.500 Ha
atau sekitar 7,29 %.
5.2. Keadaaan Penduduk
Berdasarkan data statistik Kantor Kecamatan Candi tercatat pada tahun
2009 jumlah penduduk di Kecamatan Candi sebanyak 124.724 jiwa yang terdiri
dari 62.309 orang pria dan 62.315 orang wanita.
5.3. Keadaan Sosial Ekonomi
Keadaan sosial ekonomi penduduk perlu diketahui dan dapat dilihat dalam
komposisi penduduk menurut mata pencaharian dan tingkat pendidikan. Dari sini
akan terlihat pola pikir yang akan dilakukan sebagai pengambilan keputusan
5.3.1. Tingkat Pendidikan
Dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, pendidikan
mempunyai peranan yang sangat penting. Tinggi rendahnya pendidikan
menentukan pola pikir dan cara mengambil keputusan dari suatu masyarakat.
Semakin tinggi pendidikan yang diterima maka semakin tinggi pula pengetahuan
yang dimilikinya. Tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat Kecamatan
Candi sangat beragam, hal ini yang akan mempengaruhi kemampuan dalam
menerima dan menerapkan teknologi baru yang dapat berguna bagi
pengembangan usahatani, khususnya usahatani tebu. Untuk mengetahui tingkat
pendidikan penduduk di Kecamatan Candi dapat dilihat pada tabel 2 :
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Candi Tahun 2009
Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%)
TK / Sederajat 8.213 8,84
Sumber : Data Sekunder
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk
Kecamatan Candi umumnya tamat SD yaitu sebanyak 30.764 orang atau sekitar
33,13%, tamat SMA / Sederajat sebesar 28.619 orang atau sekitar 30,82%, tamat
SMP sebanyak 16.503 orang atau sekitar 17,77 %, 8.213 orang atau 8,84% hanya
yang berpendidikan akademi sebanyak 4.304 orang atau sekitar 4,63 % dan
sisanya sebanyak 4.465 orang atau sekitar 4,81 % mampu menjalani pendidikan
hingga jenjang yang paling tinggi yaitu sarjana. Kondisi yang mendukung
tingginya tingkat pendidikan masyarakat antara lain disebabkan kesadaran
masyarakat yang sudah mengenal pentingnya pendidikan, keadaan ekonomi
masyarakat, selain itu juga disebabkan lokasi Kecamatan Candi dekat dengan
pusat kota Kabupaten Sidoarjo sehingga banyak terdapat fasilitas pendidikan yang
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat pendidikan yang tinggi.
5.3.2. Mata Pencaharian
Penduduk Kecamatan Candi mempunyai mata pencaharian yang beraneka
ragam sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing untuk mengetahui
jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 3, sebagai
berikut :
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Candi Tahun 2009
Pekerjaan Jumlah (orang)
Persentase (%)
Pertukakangan 6.882 41,42
Buruh Tani 7.439 44,77
Sumber : Data Sekunder
Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Candi
44,7 7%. Sedangkan yang bekerja di bidang pertukangan sebanyak 6.882 orang
atau sekitar 41,42 %, pensiunan sebanyak 1.032 orang atau sekitar 6,21 %, yang
bekerja di bidang jasa sebanyak 736 orang atau sekitar 4,44 % dan nelayan
sebanyak 495 orang atau sekitar 2,98 % sedangkan sisanya 30 orang atau 0,18 %
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN
6.1. Karakteristik Responden
Karakteristik merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap manusia dengan
karakteristik ini dapat dibedakan antara orang satu dengan yang lain. Pada
penelitian ini, responden mempunyai karakteristik yang berhubungan dengan
keberhasilan usahataninya. Karakteristik juga menunjukkan kondisi yang dimiliki
oleh petani yang penting artinya untuk mengetahui latar belakang dalam
berusahatani dan untuk mengukur sampai dimana kemampuan petani dalam
berusahatani.
6.1.1. Umur Responden
Umur seseorang akan mempengaruhi kecakapan serta cara kerja dalam
melakukan usahataninya selain itu umur petani juga dapat mempengaruhi petani
dalam menerima inovasi baru. Semakin tua umur seseorang akan semakin
menurun daya pikir orang tersebut sehingga dapat mempengaruhi petani dalam
menetapkan anjuran-anjuran usahataninya dengan maksud untuk mencapai
peningkatan produksi dan pendapatan.
Semakin tua umur seseorang maka semakin berpengalaman orang tersebut
sehingga bekal yang telah lama dalam berusahatani menjadikan orang lebih
bijaksana dalam menentukan langkah atau mengambil keputusan. Berbeda dengan
petani yang masih muda dan sehat yang dapat menyerap anjuran-anjuran serta
petunjuk-petunjuk teknik usahatani dengan baik. Disamping itu petani muda lebih
pentingnya umur petani mitra dalam penelitian ini sehingga tingkat umur petani
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Jumlah Responden Menurut Golongan Umur
Umur (Tahun)
Petani TRKSU Petani TRM
Jumlah
Sumber: Data primer diolah
Dari tabel 4 di atas dapat dilihat umur petani TRKSU (Tebu Rakyat
Kerjasama Usahatani) terbanyak pada rentang usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 7
orang dengan prosentase sebesar 47%, sedangkan umur petani TRM (Tebu Rakyat
Mandiri) paling banyak terdapat pada rentang usia 41-50 tahun sebanyak 6 orang
dengan prosentase sebesar 40%.
Hal ini berarti bahwa kebanyakan yang menjadi petani tebu yang bermitra
dengan PG Candi Baru, baik petani TRKSU (Tebu Rakyat Kerjasama Usahatani)
maupun petani TRM adalah petani yang berusia 41-50 tahun, karena mereka
mempunyai tingkat kedewasaan berusaha dan mempunyai banyak pengalaman
tentang bermitra dibandingkan dengan rentang usia di bawahnya. Hal tersebut
akan mempengaruhi produktivitas usahatani dan produksi gula, selain itu juga