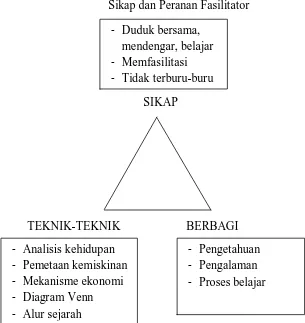BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1Evaluasi
2.1.1 Pengertian Evaluasi
Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa
evaluasi adalah penilaian, yaitu pemberian penilaian secara terus menerus. Sebagai
penilaian, bisa saja penilaian ini menjadi netral, positif, negatif atau bahkan
gabungan dari keduanya. Ketika sesuatu dievaluasi biasanya orang yang
mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.
Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu
rencana kegiatan atau program (Suharto, 2005: 119). Pengertian lain dikemukakan
oleh H.Weis (dalam Jones, 2001)yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu
aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektivitas suatu program
melalui indikator yang khusus, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk
perencanaan. Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, evaluasi semestinya
mempunyai tolak ukur atau target sasaran yang telah ditetapkan dari awal
perencanaan dan merupakan tujuan yang hendak dicapai (Siagian dan Suriadi, 2010:
117).
Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur secara objektif terhadap
pencapaian hasil yang telah dirancang dari suatu aktifitas atau program yang telah
dilaksanakan sebelumnya, yang mana hasil penilaian yang dilakukan menjadi umpan
balik bagi aktifitas perencanaan baru yang akan dilakukan berkenaan dengan aktifitas
Evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait (Parsons, 2001: 546):
1. Evaluasi kebijakan dan kandungan programnya;
2. Evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang
bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan program.
2.1.2 Fungsi Evaluasi
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan antara
lain (Dunn, 1999: 609):
1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja
kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat
dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan
seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu yang telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai
yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan
mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis
kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi
tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada
perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada
definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan.
Dari fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli, dapatlah
disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh
seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan
program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai program
2.1.3 Proses Evaluasi
Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaannya, secara umum evaluasi
terhadap program dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis (Siagian dan Suriadi,
2012 : 173) yaitu :
1. Penilaian atau perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menerapkan prioritas
terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.
2. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan
pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, di dalamnya meliputi apakah
pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada
perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya
direncanakan.
3. Penilaian atas aktivitas yang telah selesai dilaksanakan, yaitu menganalisis
hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang sebelumnya ditetapkan.
2.1.4 Tolak Ukur Evaluasi
Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang nantinya
dijadikan penilaian suatu program. Berhasil atau tidaknya program berdasarkan
tujuan yang dibuat sebelumnya harus memiliki tolak ukur, dimana tolak ukur ini
harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya.
Adapun yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi suatu program adalah:
1. Tolak ukur dalam evalusi pada tahap perencanaan
a. Mempunyai sebuah program yang akan disosialisasikan
b. Mempunyai sebuah tujuan yang akan disosialisasikan
2. Tolak ukur dalam evaluasi pada tahap pelaksanaan adalah :
a. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah direncanakan
b. Apakah tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan
c. Apakah metode-metode sesuai dengan yang telah direncanakan
d. Apakah sarana yang ada dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan
3. Tolak ukur evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan adalah :
a. Apakah hasil yang diperoleh (efektivitas dan efisiensi) sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai
b. Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan
terhadap perubahan (Suwito, 2002:16).
2.2 Program
Program adalah cara tersendiri dan khusus yang dirancang demi pencapaian
suatu tujuan tertentu. Dengan adanya suatu program, maka segala rancangan akan
lebih teratur dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, maka program
adalah unsur pertama yang harus ada bagi berlangsungnya aktivitas yang teratur,
karena dalam program telah dirangkum berbagai aspek, seperti:
1. Adanya tujuan yang mau dicapai
2. Adanya berbagai kebijakan yang diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.
3. Adanya prinsip-prinsip dan metode-metode yang harus dijadikan acuan dengan
prosedur yang harus dilewati.
4. Adanya pemikiran atau rancangan tentang anggaran yang diperlukan
5. Adanya strategi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas (Wahab
2.2.1 Identifikasi Program
Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan
untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu
seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:
1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau
sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya
juga diidentifikasikan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat
diakui oleh publik.
Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis
yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan
memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius
terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi
terbaik (Jones, 1996:295).
2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dari pelaku usaha untuk
memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawannya dan bertindak adil
terhadap berbagai pihak yang terkait dengan aktifitasnya, serta dengan ikhlas
menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk membiayai dan secara langsung atau
tidak langsung melakukan program-program yang bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama
Berdasarkan definisi yang dirumuskan secara sederhana tersebut, maka
pelaku usaha harus memiliki niat yang baik atau komitmen yang kuat untuk
menyisihkan sebagian dari hasil usaha atau keuntungan perusahaannya. Lebih dari
itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki niat dan kemauan menyisihkan
sebagian dari hasil usaha atau keuntungan perusahaannya, tetapi juga harus
bertanggung jawab dalam menjamin perumusan dan implementasi berbagai program
pemberdayaan masyarakat yang secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Mallen Baker mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu
hal bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pengelolaan terhadap
proses ekonominya dalam rangka menghasilkan suatu dampak positif secara
menyeluruh bagi masyarakat (Mallen Baker, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 10)
Pandangan lain tentang definisi tanggung jawab sosial perusahaan
dikemukakan oleh Bank Dunia yang mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial
perusahaan sebagai suatu persetujuan atau komitmen perusahaan agar bermanfaat
bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, bekerja dengan para
perwakilan dan perwakilan mereka, masyarakat setempat dan masyarakat dalam
ukuran lebih luas, untuk meningkatkan kualitas hidup dengan demikian eksistensi
perusahaan tersebut akan baik bagi perusahaan itu sendiri dan baik pula bagi
pembangunan (World Bank, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 10).
2.3.2 Manfaat dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan disadari makin penting karena
mampu memberikan jawaban atas setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan
mampu mendongkrak popularitas kini bergeser seiring dengan berjalannya waktu.
Pemahaman konsep pengembangan berkelanjutan menjadi bahasan utama dewasa in
jika membahas CSR. Dalam hal ini, perusahaan hanyalah menjalankan tanggung
jawab sosialnya dengan memperhatikan keberlanjutan, selebihnya masyarakat yang
menilai komitmen perusahaan hingga citra yang baik menjadi bonus bagi
perusahaan.
Suhandari (dalam Untung, 2008: 6) mengemukakan pelaksanaan CSR
memberikan manfaat bagi perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi atau citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko demi kepentingan positif perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi opersional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang luas.
6. Mereduksi biaya misalnya dengan pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10.Peluang mendapatkan penghargaan.
Pelaksanaan CSR memang tidak semata memberikan manfaat kepada
perusahaan, namun juga memberi manfaat bagi masyarakat yang menerimanya.
Pelaksanaan CSR dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup
sehingga tercapai kesejahteraan. Hal ini akan mengimbangi kemajuan yang dialami
oleh perusahaan di lingkungan sekitar sehingga secara tidak langsung kesuksesan
2.3.3 Ruang Lingkup Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Kehadiran perusahaan dipastikan melahirkan cost yang harus ditanggung
masyarakat setempat sebagai akibat dari berbagai bentuk pencemaran yang
ditimbulkan aktifitas ekonomi perusahaan sebagaimana telah dikemukakan. Oleh
karena itu, cost tersebut harus diimbangi dengan benefit bagi masyarakat setempat.
Adapun benefit bagi masyarakat setempat diupayakan dengan cara menetapkan
kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan yang
diperoleh yang akan digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan
pemberdayaan masyarakat setempat sehingga kesejahteraan perusahaan, khususnya
pemilik perusahaan juga diikuti oleh kesejahteraan masyarakat setempat.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat dinyatakan bahwa
tanggung jawab sosial perusahaan meliputi:
1. Bersedia menyisihkan sejumlah uang, misalnya 1% dari keuntungan
perusahaan untuk kepentingan masyarakat setempat.
2. Uang tersebut diperuntukkan sebagai pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat setempat.
3. Program pemberdayaan masyarakat setempat yang dilakukan dijamin dapat
digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Dengan demikian harus dipahami bahwa tanggung jawab sosial perusahaan
bukan sekedar kesediaan menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan. Hal
yang sangat substansial adalah, penggunaan dana yang disediakan secara efektif
harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat yang berkualitas, tepat dan berkesinambungan
2.3.4 Dasar Hukum Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pada awalnya tanggung jawab sosial perusahaan hanya dianggap sebagai
tanggung jawab etis, yang berarti cenderung bersifat suka rela dan tidak bersifat
mengikat. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan tersebut dalam wujud belas
kasihan atau kedermawanan sosial. Segelintir perusahaan bersedia menyisihkan
keuntungannya dan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk kasihan atau
kedermawanan sosial, bukan kewajiban. Kecenderungan ini ternyata secara umum
tidak menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan masyarakat setempat.
Upaya meningkatkan efektifitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat antara lain ditempuh dengan
mengubah kesan dan sifat tanggung jawab sosial perusahaan itu dari sebelumnya
bersifat etis atau sebagai etika menjadi tanggung jawab sosial perusahaan yang
bersifat wajib atau sebagai hukum.
Khususnya di Indonesia, menyangkut tanggung jawab sosial dari masa ke masa
telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995, dimana Pasal 2 butir 1
menyatakan bahwa wajib pajak organisasi ataupun orang pribadi dapat
menyumbangkan sampai dengan setinggi-tingginya dua persen dari
keuntungan atau penghasilan setelah pajak penghasilan yang diperolehnya
salam satu tahun pajak yang digunakan bagi pemberdayaan keluarga
prasejahtera dan keluarga sejahtera satu;
2. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996, diubah menjadi: wajib pajak
organisasi ataupun orang pribadi wajib memberikan konstribusi bagi
sebanyak dua persen dari keuntungan setelah pajak penghasilan dalam satu
tahun pajak;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dimana Pasal 2 butir e menyatakan
bahwa BUMN harus terlibat aktif memberikan bimbingan dan konstribusi
kepada perusahaan lemah, koperasi, dan masyarakat;
4. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep 236/MBU. 2003, mewajibkan
BUMN untuk mengimplementasikan program kerja sama dan program
pengembangan lingkungan.
5. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 433/MBU/2003, menyatakan bahwa
BUMN diwajibkan membentuk bagian tersendiri yang secara khusus
mengelola program pembinaan lingkungan dan
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana Pasal 15 butir b menyatakan
bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan; Pasal 17 menyatakan bahwa penanam modal yang
memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui wajib
menyediakan biaya secara bertahap untuk pemulihan lingkungan; Pasal 34
menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban program
tanggung jawab sosial akan dikenai hukuman yang bersifat administrasi; dan
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana ayat 1 menyatakan, bahwa
perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonominya di sektor dan/ atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib mengimplementasikan tanggung
jawab sosial perusahaan bagi masyarakat setempat dan lingkungan; ayat 2
menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat
setempat dan lingkungan adalah kewajiban perusahaan yang diperuntukkan
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; dan ayat 3 menyatakan
bahwa perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban dikenai hukuman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Siagian, 2012: 181).
2.3.5 Model Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Dalam kajiannya tentang model pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan, Wibisono (dalam Siagian dan Suriadi,2012:95) mengemukakan model
dalam bentuk kerja sama yang melibatkan tiga pihak. Adapun ketiga pihak tersebut
adalah perusahaan-masyarakat-pemerintah. Melibatkan tiga pihak dalam bentuk
kerja sama dalam proses pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan
dapat memaksimalkan kepuasan bagi perusahaan dan masyarakat.
Hal yang sangat penting dipahami adalah antara perusahaan, masyarakat dan
pemerintah dalam konteks implementasi tanggung jawab sosial perusahaan
dihubungkan garis kepentingan timbal balik. Setidaknya ada tiga bentuk kepentingan
yang melibatkan tiga pihak tersebut dalam suatu kerjasama, yaitu:
1. Secara konstitusional perusahaan adalah mitra pemerintah dalam rangka
memanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD
1945. Sehubungan dengan praktek bisnisnya dalam mengelola sumber daya
alam, maka perusahaan tergantung pada pemerintah, khususnya dalam rangka
mendapat izin usaha.
2. Perusahaan merupakan institusi yang senantiasa memberi dukungan kepada
pemerintah melalui pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sehingga
pemerintah memiliki biaya operasional dalam melakukan pengelolaan
negara adalah pajak, dan sumber utama pajak adalah para pelaku usaha atau
badan-badan usaha.
3. Kenyamanan aktivitas ekonomi oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh
perilaku masyarakat setempat terhadap perusahaan. Kondisi seperti ini
semakin pekat di era demokrasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia.
Selanjutnya perilaku masyarakat setempat terhadap perusahaan dipengaruhi
pula oleh perilaku perusahaan dalam memberikan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat setempat.
Dengan dukungan Bank dunia, Tom Fox, Halina Ward, dan Bruce Howard
pada tahun 2002 melakukan penelitian tentang implementasi program tanggung
jawab sosial perusahaan di negara-negara sedang membangun yang memfokuskan
diri pada peran yang dilakukan pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan
menghasilkan bahwa, setidaknya terdapat dua poros yang mungkin dilakukan pihak
pemerintah sehubungan dengan praktek ekonomi dan implementasi tanggung jawab
sosial perusahaan, yaitu:
Poros pertama, meliputi:
1. Pembagian wewenang.
Peran pemerintah disini berupa penyusunan standar minimum kinerja
perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan kemudahan
Peran pemerintah dalam hal ini adalah penciptaan kondisi yang
mendukung, bahkan dorongan bagi perusahaan yang
mengimplementasikan program tanggung jawab sosial secara efektif agar
menjadi pendorong atas perbaikan kehidupan sosial dan lingkungan.
Pihak pemerintah berperan sebagai unsur yang ikut terlibat dan
menjadi fasilitator dalam pemecahan masalah-masalah sosial dan
lingkungan.
4. Dukungan
Pihak pemerintah harus memberikan dukungan politik, dukungan
melalui kebijakan, atau dukungan laiinya kepada perusahaan maupun
masyarakat.
Poros kedua adalah:
1. Menetapkan dan menjamin pencapaian standar minimum
2. Kebijakan umum yang berkenaan dengan peran ekonomimya
3. Penfelolaan peusahaan melalui hukum
4. Penanaman modal yang mendukung dan bertanggung jawab
5. Belas kasihan dan pengembangan masyarakat
6. Penglibatan dan keterwakilan pemangku kepentingan
7. Produksi dan konsumsi yang mendukung tanggung jawab sosial
perusahaan
8. Setifikasi yang mendukung tanggung jawab sosial perusahanan ,
pemenuhan tanggung jawab yang berniulai keagungan dan sistem
manajemen
9. Keeterbukn dan pelaporan yang mendukung tanggung jawab ossila
Perusahaan
10.Proses yang mrlinatkan banyaak penjilat dalam rangka merumuskan
pedoman dan menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang diikuti di masa
Dalam upaya mencapai efektifitas implementasi tanggung jawab sosial
perusahaan, Saidi dan abidin mengemukakan sedikitnya ada empat model atau pola
yang secara umum dapat dilaksanakan di Indonesia, yaitu:
1. Model keterlibatan langsung
Perusahaan sendiri yang secara langsung melaksanakan program
tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Model yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
Perusahaan sendiri mendirikan yayasan atau organisasi sosial.
3. Model bermitra dengan pihak lain.
Pihak perusahaan melakukan kerjasama dengan organisasi lain,
dimana organisasi mitra kerjasama tersebutlah yang secara langsung
mengelola pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Model mendukung dan bergabung dalam konsortium.
Sejumlah perusahaan bekerjasama mendirikan organisasi sosial.
Selanjutnya organisasi sosial inilah yang secara langsung bertanggung
jawab sosial dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial
perusahaan (Saidi dan Abidin, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 99).
Sehubungan dengan uraian di atas, ada satu pertanyaan kunci berkaitan
dengan adanya beberapa alternatif model yang ada. Model manakah yang terbaik di
antara model pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang ada? Meskipun
jawaban atas pertanyaan ini sangat penting, namun kita tidak akan menemukan
jawaban itu dalam khasanah teoritis. Setidaknya ada dua alasan dari argumentasi
seperti ini, yaitu:
1. Model yang terbaik untuk diterapkan adalah model yang sesuai dengan
segi budaya, wawasan dan pendidikan, keterampilan, sosial ekonomi
maupun kohesi sosialnya. Semuanya merupakan variabel pengaruh
terhadap model implementasi program tanggung jawab sosial.
2. Penerapan suatu model implementasi program tanggung jawab sosial
menuntut berbagai tanggung jawab sosial menuntut berbagai konsekwensi
logis yang justru menjadi prasyarat implementasi dari model tersebut.
Oleh karena itu hal terpenting bukanlah menetapkan model tertentu dalam
implementasi program tanggung jawab sosial, melainkan kajian atas berbagai
konsekwnsi logis yang mengikuti penetapan implementasi model dimaksud. Berikut
ini diuraikan contoh-contoh model implementasi program tanggung jawab sosial
yang kami rekomendasikan lengkap dengan konsekwensi logisnya:
1. Model Perusahaan – Masyarakat
Penerapan model ini menuntut restrukturisasi organisasi perusahaan.
Intinya: dalam struktur organisasi perusahaan harus ada Unit CSR, Unit
Community Development atau Unit Pemberdayaan Masyarakat. Unit
tersebut harus setingkat manager, yang diisi oleh sederetan staf yang
terampil dalam perencanaan hingga evaluasi pengembangan masyarakat.
Dari berbagai kalangan profesi yang ada, maka kalangan profesi yang
paling tepat mengisi unit ini adalah profesi pekerja sosial, khususnya
pekerja sosial industri. Survey yang pernah dilakukan antara lain
menyimpulkan bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia cenderung
menerapkan bahwa penanggungjawab implementasi program tanggung
jawab sosial ditompangkan pada unit manager hubungan masyarakat.
Kecenderungan ini menimbulkan image negatif bagi masyarakat atau
jawab sosial hanya sebagai lipstik. Artinya, sesungguhnya perusahaan
tersebut tidak memiliki niat yang tulus dalam memberikan khidmat atas
kehadiran perusahaan tersebut bagi kehidupan masyarakat setempat.
Disamping itu kebijakan menjadikan program dan aktifitas tanggung
jawab sosial perusahaan merupakan wujud dari sikap mental instan dari
pelaku usaha. Cara berpikir seperti ini sangat keliru, karena image
masyarakat terhadap perusahaan tidak boleh digiring dan dipaksakan
melalui media massa adalah membentuk opini publik. Namun image
sesungguhnya jauh lebih agung dari sekedar opini publik.
2. Model Perusahaan – Pihak Ketiga – Masyarakat
Penerapan model ini tidak menuntut restrukrisasi organisasi
perusahaan. Pemilihan model ini menggambarkan bahwa perusahaan
memiliki niat yang baik untuk mengimplementasikan secara efektif
program tanggung jawab sosial, namun pelaku usaha menyadari bahwa
mereka tidak memiliki kompetensi untuk itu. Dalam kondisi seperti ini
maka yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah mencari pihak ketiga
yang memiliki sederetan staf yang berkompeten dalam implementasi
program tanggung jawab sosial. Pihak ketiga di sini boleh berupa
Yayasan atau bahkan institusi Perguruan Tinggi, tegasnya setingkat
Jurusan atau Departemen yang memang membidangi Pengembangan
Masyarakat, seperti Jurusan atau Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
baik di PTN maupun PTS. Untuk lebih menjamin efektifitas
pelaksanaannya, maka pihak perusahaan harus melakukan seleksi atas
pihak ketiga secara transparan, melalui kompetisi yang fair. Misalnya,
proposal dan mempresentasikannya baik secara sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama. Pihak perusahaan cukup menilai proposal dan
presentasinya, kemudian menetapkan pihak ketiga yang paling tepat
ditetapkan sebagai mitra kerja dan membuat ikatan kerja dalam jangka
waktu tertentu. Sejak pihak ketiga melaksanakan tugasnya, maka
perusahaan harus senantiasa melakukan pengawasan. Juga perlu
dilakukan evaluasi yang fair atas kinerja pihak ketiga yang menjadi mitra
kerja. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan bagi perusahaan
apakah akan melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut atau
memutuskannya dan mencari pihak ketiga laiinya yang dianggap lebih
berkompeten dalam menjalankan program tanggung jawab sosial
perusahaan (Siagian, 2012: 183).
2.3.6 Langkah-langkah Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Untuk lebih menjamin keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud
implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan, harusnya ditempuh
beberapa langkah sebagai berikut (Siagian dan Suriadi, 2012: 190) :
I. Pemilihan lokasi dan kelompok sasar
Pemilihan tempat dan kelompok sasar harus sesuai dengan
indikator yang disepakati oleh organisasi (perusahaan atau
organisasi lain yang secara sah bekerja sama dengan perusahaan),
pihak-pihak terkait (misalnya: pemerintah lokal), dan masyarakat
sendiri. Prinsip pertimbangan tempat yang diusulkan adalah
aktivitas lain, adanya kelompok mayarakat yang miskin dan perlu
diberdayakan, adanya dukungan pemimpin desa dan tokoh-tokoh
masyarakat desa, lokasi terjangkau bagi tim pemberdayaan
masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan alat yang tersedia.
II. Sosialisasi program pemberdayaan masyarakat itu kepada masyarakat
setempat.
Langkah ini meliputi berbagai aktivitas, seperti: pertemuan
formal dengan pemimpin dan pejabat pemerintah lokal tingkat
desa, pertemuan formal dengan masyarakat, kunjungan nonformal
dengan masyarakat setempat, meliputi : kunjungan ke rumah,
musyawarah kelompok, dan terlibat dalam aktivitas masyarakat.
Dengan demikian sosialisasi program pemberdayaan masyarakat
pada masyarakat setempat mendukung upaya peningkatan
pemahaman masyarakat setempat dan semua pihak yang terkait.
III. Proses pemberdayaan masyarakat
Sebagai suatu proses, maka pemberdayaan masyarakat
meliputi berbagai aktivitas, seperti:
a. Kajian keadaan desa partisipatif,
b. Pengembangan kelompok,
c. Penyusunan rencana dan implementasi aktivitas, dan
d. Pengawasan dan penilaian partisipatif.
IV. Pemandirian masyarakat
Pemberdayaan masyarakat adalah proses berkelanjutan dengan
tujuan kemandirian masyarakat setempat dalam upaya
pemberdayaan masyarakat secara pelan-pelan dikurangi dan
akhirnya akan berhenti. Peran tim pemberdayaan masyarakat
sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau
pihak lain dari masyarakat setempat yang dianggap mampu oleh
masyarakat. Walaupun tim pemberdayaan masyarakat telah
mundur, namun anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai
penasihat yang setiap saat bersedia datang jika diperlukan
masyarakat.
Masyarakat yang berbekal kearifan lokal, yang berasal dari pengalaman,
cenderung mempertahankan pendekatan sendiri yang justru berbeda dengan kalangan
akademik dan pemerintah. Hal paling utama disini adalah bagaimana caranya
menyatukan model pendekatan akademik, model pendekatan pemerintah, dan model
pendekatan masyarakat yaitu dengan model implementasi model pendekatan
Partisipatory Rapid Appraissal (PRA).
Hal yang sangat penting dan utama dalam PRA adalah semua pemangku
kepentingan harus dilibatkan dalam semua aktivitas dari tiap-tiap langkah yang telah
dikemukakan. Mekanisme penglibatan semua pemangku kepentingan dapat
ditempuh dengan berbagai langkah, seperti analisis pemegang kepentingan, PRA,
dan Focus Group Discussion. Ketiganya dapat digunakan secara bersamaan.
Model PRA dapat dilaksanakan jika tim pelaku pemberdayaan masyarakat
tidak berperan sebagai perancang untuk masyarakat setempat. Berbagai keterampilan
yang harus dimiliki dan diterapkan dalam aktivitas perencanaan partisipatif adalah
melakukan musyawarah kelompok terarah dan mendukung fasilitas untuk
menganalisis pola keputusan yang dilakukan masyarakat setempat dalam proses
Pendekatan atau model PRA lebih mengutamakan proses implementasi yang
melibatkan masyarakat, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai acuan
berikut:
1. Belajar dari masyarakat, dimana program pemberdayaan masyarkat harus
dipahami sebagai satu program dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.
Dengan demikian semua tahapan program harus menjadikan masyarakat
sebagai sumber data.
2. Orang luar (peneliti, staf perusahaan, staf organisasi mitra kerja perusahaan)
berperan sebagai fasilitator sedangkan orang dalam atau masyarakat setempat
sebagai pelaku. Orang luar harus menyadari keberadaannya sebagai fasilitator
saja.mereka tidak boleh tampil sebagai aktor utama atau tampil sebagai orang
yang lebih tahu.
3. Saling belajar dan saling berbagi pengalaman. Walaupun masyarakat
setempat lebih paham atas keadaan desanya dan mereka mempunyai kearifan
lokal, namun tidak selamanya mereka itu benar dan dibiarkan tidak berubah.
Dalam konteks ini, pekerja sosial harus mampu menempatkan posisi secara
proporsional, karena kesalahan dalam menempatkan posisi dapat berakibat
fatal, seperti runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pekerja sosial.
4. Santai dan informal. Aktivitas PRA menuntut penciptaan suasana yang
bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa, dan suasana informal. Dengan
suasana seperti ini maka masyarakat setempat akan menunjukkan sikap
terbuka. Dalam kondisi seperti ini masyarakat akan sangat rela dan lancar
mengeluarkan uneg-unegnya.
5. Penglibatan semua kelompok masyarakat. Suatu kekeliruan akan timbul jika
benar-benar mewakili semua elemen masyarakat. Jika anggapan seperti ini dianut
dan diterapkan, maka program pemberdayaan masyarakat itu hanya akan
memenuhi kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja.
6. Menghargai perbedaan. Dalam PRA, semangat dan sikap saling menghargai
atas perbedaan pendapat dan pandangan sangat diutamakan. Pendapat dan
pandangan yang berbeda-beda harus ditata dan diurutkan prioritasnya oleh
masyarakat setempat sebagai pemilik.
7. Triangulasi. Untuk memperoleh informasi yang kedalamannya data terjamin
dapat diterapkan cara triangulasi yang menganut asas konfirmasi ulang.
Untuk itu, berbagai informasi dari berbagai pihak harus dipertemukan dan
diperbandingkan. Dalam hal ini peranan fasilitator harus dapat ditampilkan
tim pemberdayaan masyarakat, seperti tergambar berikut ini:
Gambar 2.1
Sikap dan Peranan Fasilitator
SIKAP
TEKNIK-TEKNIK BERBAGI
- Duduk bersama, mendengar, belajar
- Memfasilitasi
- Tidak terburu-buru
- Analisis kehidupan
- Pemetaan kemiskinan
- Mekanisme ekonomi
- Diagram Venn
- Alur sejarah
- Pengetahuan
- Pengalaman
8. Mengoptimalkan hasil. Implementasi PRA memerlukan masa dan ahli,
pelaku, dan keterlibatan masyarakat setempat.
9. Belajar dari kesalahan. Melakukan sesuatu yang tidak benar dimaklumi
dalam PRA. Untuk itu, tiap-tiap kesalahan harus dijadikan sebagai pelajaran
untuk berbuat benar di masa depan.
10.Orientasi praktis. PRA berorientasi pada pemecahan masalah dan
pengembangan program. Untuk itu diperlukan tujuan sesuai dan memadai.
11.Berkelanjutan. Aktivitas PRA bukanlah suatu praktek aktivitas yang berhenti
setelah penggalian informasi dianggap cukup. Kepentingan-kepentingan dan
masalah-masalah masyarakat tidaklah tetap, tetapi berubah menurut waktu
sesuai dengan perubahan dalam masyarakat itu sendiri (Siagian dan Suriadi,
2012: 164).
Metode lain yang dapat diterapkan agar seluruh pemangku kepentingan
terlibat dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui Focus Group Discussion
(FGD). Pada awalnya FGD hanya digunakan sebagai alat mengumpul data dalam
penelitian. Namun di kalangan pelaku pemberdayaan masyarakat, FGD telah
digunakan dalam rangka implementasi pemberdayaan masyarakat.
FGD adalah metode khusus untuk pengelolaan musyawarah atau serangkaian
musyawarah. Melalui FGD masyarakat setempat mampu menyampaikan sikap,
pemikiran, gagasan, atau pemecahan suatu masalah dari topik yang didiskusikan.
Tujuan FGD adalah memperoleh pemahaman yang mendalam dari sudut
pandang dan pengalaman masyarakat, perasaan, pemglihatan, kepercayaan,
pengetahuan, dan sikap masyarakat berkenaan dengan topik yang diperbincangkan.
gagasan-gagasan baru. Bahkan FGD dapat digunakan sebagai media untuk menilai
program yang telah dilaksanakan. Lebih lengkapnya, FGD dapat digunakan untuk:
1. Pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi suatu
program, metode, kebijakan, hasil, dan pemanfaatan.
2. Mengidentifikasi masalah, hambatan, biaya, atau manfaat. Memotivasi
pemikiran baru, misalnya pemecahan yang optimum, peluang, keterkaitan
atau dampak yang sangat mungkin.
3. Menentukan prioritas atau batasan masalah.
4. Mendapat informas yang lebih mendalam.
5. Mendapat gambaran budaya atau kelompok masyarakat yang lebih akurat.
6. Melibatkan pendengar baru.
7. Mendapat respon lebih cepat. (Suedi, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 169).
Berdasarkan berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam upaya
pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelaku pemberdayaan
masyarakat harus terdiri dari tim yang diisi oleh orang-orang yang memiliki berbagai
bidang kompetensi. Hal ini sangat penting diperhatikan mengingat masalah-masalah
yang dihadapi masyarakat sangat berbeda-beda dan meliputi semua aspek kehidupan.
Artinya, jika pelaku pemberdayaan masyarakat adalah suatu organisasi, maka
organisasi itu harus diisi oleh berbagai pakar, sehingga dapat memberikan kontribusi
pemikiran bagi masyarakat setempat dan pemerintak lokal (Suedi, dalam Siagian dan
Suriadi, 2012: 169).
2.3.7 Jenis-jenis CSR/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Kotler dan Lee menyebutkan enam kategori kegiatan CSR, yaitu:
Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki
perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial
atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau
perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu
2. Cause related marketing (pemasaran terkait dengan kegiatan sosial)
Dalam kegiatan ini, perusahaan memiliki komitmen untuk
menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan
sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya
didasarkan kepada penjualan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
3. Corporate social marketing (pemasaran kemasyarakatan korporat)
Dalam kegiatan ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan
kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan
kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian hidup serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Corporate philanthropy (kegiatan filantropi perusahaan)
Dalam kegiatan ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam
bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut
biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau
pelayanan secara cuma-cuma.
5. Community volunteering (pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela)
Dalam kegiatan ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan,
rekan pedagang eceran atau para pemegang franchise agar menyisihkan waktu
mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal
6. Socially responsible business practice (praktik bisnis yang memiliki tanggung
jawab sosial)
Dalam kegiatan ini, perusahaan melaksanakan kegiatan bisnis melampaui
aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang
mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Komunitas yang dimaksud
dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi
nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum.
Sedangkan yang dimaksud dengan kesejahteraan mencakup di dalamnya
aspek-aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan, pemenuhan kebutuhan
psikologis dan emosional (Dwi Kartini, dalam Ardianto, 2011: 153).
2.3.8 Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Kesehatan oleh PT Tirta Sibayakindo di Desa Doulu Pasar: Program Akses Air Bersih dan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Desa Doulu Pasar merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sasaran
program CSR dari Danone Aqua. Pabrik dari perusahaan Aqua Danone tepat berada
di Desa Doulu Pasar, dimana selama ini perusahaan Danone Aqua memanfaatkan air
tanah yang berada di Desa Doulu Pasar. Sebagai rasa tanggung jawab perusahaan
terhadap tanggung jawab kondisi sosial masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah
“Corporate Social Responsibility atau CSR maka dari itu pihak perusahaan Danone
Aqua memfasilitasi Program Akses Air Bersih dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
kepada masyarakat Desa Doulu Pasar.
Desa Doulu Pasar terletak di kaki Gunung Sibayak dan diapit dua bukit atau
dipergunakan sebagai sumber mata air dari perusahaan DanoneAqua. Masyarakat di
Desa Doulu Pasar selama ini memanfaatkan air yang bersumber dari Danone Aqua
yang dialirkan dari sumber mata air yang ada dialirkan dengan sistem perpompaan ke
bak-bak penampungan yang berada dikawasan permukiman masyarakat.
Pelaksanaan program ini tidak hanya pada kegiatan peningkatan akses air
bersih saja tetapi juga melakukan kegiatan penyadaran serta pendidikan masyarakat
untuk memulai melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini
menggunakan pendekatan partisipatif dengan mengedepankan masyarakat yang
sebagai penerima manfaat mampu mengelola program pada saat implementasi
kegiatan serta diharapkan mampu nantinya mengoperasikan sistem air bersih yang
dihasilkan sebagai badan usaha milik masyarakat atau desa.
Pada saat implementasi kegiatan akan dilakukan beberapa tahapan kegiatan
yang dimulai dari perencanaan, transek, sosialisasi atau FGD, pembentukan
kelompok pengelola, pelaksanaan kontruksi, pendampingan operational serta
implementasi sistem air bersih berjalan yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu kegiatan yang mendukung dari
kegiatan air bersih karena setelah air bersihnya tersedia maka perilaku hidup bersih
dan sehatnya juga harus kita laksanakan. Dimana selama ini, masyarakat kurang
paham dan sadar maka kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat ini masyarakat mulai
sadar dan mulai memahami akan pentingnya pola hidup sehat. Beberapa kegiatan
2.3.9 Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Beranjak dari perspektif pekerjaan sosial, yang diperkaya dengan referensi
manajemen dan berbagai kajian umum tentang evaluasi program, ditawarkan rincian
evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:
I. Tingkat kebijakan perusahaan, meliputi aspek :
a. Model implementasi program tanggung jawab sosial
perusahaan yang diterapkan
b. Konsekwensi penerapan model implementasi program
tanggung jawab sosial perusahaan yang dipilih, seperti :
penyesuaian struktur organisasi, penyertaan pihak ketiga
sebagai mitra kerja atau pelaksana program, transparansi dan
fairness dalam menetapkan pihak ketiga sebagai mitra kerja
atau pelaksana program, pengawasan perusahaan terhadap
kinerja pihak ketiga sebagai mitra kerja.
II. Tingkat Administrasi perusahaan, meliputi aspek :
a. Kejujuran perusahaan dalam audit keuangan, termasuk
keuntungan perusahaan
b. Tingkat persentase keuntungan perusahaan yang disediakan
sebagai sumber anggaran bagi implementasi program tanggung
jawab sosial perusahaan
c. Ketetapan waktu audit keuangan perusahaan
d. Ketetapan waktu pembekalan anggaran yang diperuntukkan
bagi implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan
a. Model pelaksanaan program sebagai suatu social intervention,
apakah cenderung sektoral ataukah menerapkan pendekatan
komunitas?
b. Teknik perencanaan yang diterapkan
c. Model pelaksanaan needs and problems assessment (apakah
diterapkan model PRA, FGD, dan lain-lain) sehingga dapat
dipahami bagaimana pelaku program memposisikan
masyarakat sebagai kelompok sasar.
d. Kesesuaian antara program yang direncanakan dengan masalah
yang dihadapi dan keperluan masyarakat yang harus dipenuhi.
IV. Tingkat proses pelaksanaan program, meliputi aspek:
a. Ada tidaknya pelaku program berfungsi sebagai fasilitator dan
sejauh efektifitas pelaksanaan fungsi tersebut.
b. Posisi masyarakat sebagai kelompok sasar dalam proses
pelaksanaan program.
c. Kesesuaian aktifitas-aktifitas yang dilakukan sebagai wujud
pelaksanaan program dengan aktivitas-aktivitas yang telah
direncanakan sebelumnya.
d. Metode pelaksanaan program, seperti penerapan prinsip dan
metode pekerjaan sosial.
e. Progres persentase keterlibatan pelaku program dan
masyarakat sebagai kelompok sasar.
V. Tingkat luaran program, meliputi aspek:
a. Perubahan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang
b. Kemungkinan kesinambungan implementasi program di masa
mendatang
c. Tingkat kemandirian dan tingkat kebergantungan kelompok
sasar terhadap pelaku program dalam rangka kesinambungan
program di masa mendatang.
d. Persepsi dan respon masyarakat terhadap implementasi
program (seperti: tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman,
tingkat persetujuan, tingkat partisipasi, dan tingkat kepuasan
atas hasil yang dicapai atau dampak yang nyata terjadi)
(Siagian, 2012: 192).
2.3.10 Konsep-konsep Terkait
2.3.10.1 Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Konsep Good Corporate Governance antara lain menegaskan bahwa dalam
melakukan aktivitas ekonominya, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban
ekonomi dan hukum, tetapi segala aktivitas ekonominya harus pula didasarkan pada
etika. Berdasarkan pemikiran tersebut maka sekarang ini berkembang konsep etika
perusahaan yang sering juga dinamakan dengan etika bisnis. Konsep etika
perusahaan oleh banyak pihak diperjuangkan sebagai suatu panduan perilaku bagi
pelaku usaha (Siagian dan Suriadi, 2012: 51).
Gagasan perlunya penerapan Good Corporate Governance diilhami oleh
kajian tentang dampak dari sepak terjang para pelaku usaha yang sesungguhnya
muncul sebagai jawaban terhadap persaingan yang makin ketat dalam dunia usaha.
karena itu seluruh elemen dari suatu perusahaan harus dikerahkan dan diarahkan
untuk mendukung perusahaan dalam rangka pencapaian itu sendiri.
Terdapat lima prinsip pengelolaan perusahaan yang baik yang oleh para
pelaku usaha dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu:
1. Prinsip Keterbukaan (Transparency)
Prinsip ini menuntut keterbukaan atas informasi. Dalam kaitan ini
maka seluruh perusahaan dituntut memiliki kerelaan dan kemampuan,
memberikan informasi yang lengkap, benar atau akurat dan tepat waktu
kepada semua pemangku kepentingan.
2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip ini menuntut perwujudan atas kejelasan berkenaan dengan
fungsi, susunan, sistem, dan tanggung jawab tiap-tiap bagian yang ada
dalam suatu perusahaan. Melalui implementasi asas ini akan mampu
diwujudkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan kekuasaan serta
tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan
eksekutif perusahaan.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)
Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki kepatuhan
terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang sah atau
berlaku sah, seperti kepatuhan atas hukum yang perpajakan, hukum yang
berkenaan dengan hubungan antara pelaku-pelaku industri dan para
pekerjanya, hukum yang berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan
kerja, hukum yang berkenaan dengan perlindungan terhadap lingkungan,
hukum yang berkenaan dengan pemeliharaan hubungan yang harmonis
lain-lain. Implementasi prinsip ini akan menyadari para pelaku usaha
bahwa dalam tiap-tiap operasional perusahaannya, mereka bukan hanya
bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan,
tetapi juga memiliki tanggungjawab kepada seluruh pemangku
kepentingan.
4. Prinsip Kemandirian (Indepedency)
Prinsip ini menegaslan perlunya pengelolaan perusahaan secara
profesional tanpa adanya benturan-benturan kepentingan ataupun tekanan
dan campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan berbagai
hukum yang sah. Denga demikian profesionalisasi pengelolaan
perusahaan merupakan harga mati, dan berbagai variabel yang
menghalanginya harus dihindarkan.
5. Prinsip Keselarasan dan Kewajaran (Fairness)
Prinsip ini menuntut, bahwa dalam semua aktivitas ekonominya
perusahaan harus menghormati nilai-nilai keadilan, kepatutan atau
kewajaran dalam memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan
segala kepentingan masing-masing (Hasmadillah, dalam Siagian dan
Suriadi, 2012: 54).
2.3.10.2 Pembangunan Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan secara sederhana dapat diartikan sebagai
pembangunan yang memiliki kemampuan dalam menjamin kebersinambungan
pembangunan. Hal mana dilakukan dengan cara berikhtiar memenuhi keperluan
masa sekarang tanpa membahayakan peluang generasi yang akan datang dalam
pembangunan berkelanjutan memberikan perhatian terhadap kepentingan masa
sekarang dan kepentingan masa mendatang (Siagian dan Suriadi, 2012: 56).
Para pelaku usaha industri di negara-negara maju dan di negara-negara
sedang membangun dengan bebas melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam
yang tidak dapat diperbaharui. Praktek ini berlangsung dalam jangka waktu yang
berkepanjangan. Sedangkan di negara-negara miskin tidak mempunyai pilihan lain.
Mereka dipaksa menjual sumber daya alam mereka dalam jumlah yang sangat besar
dalam rangka membayar hutang kepada bangsa-bangsa lain. Akibat yang muncul
selanjutnya adalah pemanasan global, kepunahan berbagai spesies tumbuhan dan
satwa, penurunan kualitas tanah dan makin berkurangnya hamparan hutan,
meluasnya wabah penyakit, masalah kekeringan yang seterusnya mengakibatkan
masalah kelaparan, banjir dan lain-lain (World Business Council Development, dalam
Siagian dan Suriadi, 2012: 57).
Perserikatan Bangsa Bangsa melaksanakan konferensi khusus tentang
Masalah Lingkungan dan Pembangunan. Konferensi ini lebih dikenal dengan
Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Riode Janeiro, Brazil (Tinto, dalam Siagian dan
Suriadi, 2012). Konferensi ini mengangkat slogan “berpikir mendunia, bertindak
sesuai keadaaan setempat”. Slogan ini berupaya menggambarkan perlunya bertindak
bijaksana terhadap lingkungan. Oleh karena itu, maka Konferensi Tingkat Tinggi
Bumi ini berupaya menyadarkan perlunya menumbuhkan semangat kebersamaan
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh benturan antara
kelompok-kelompok pelaku pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan
dengan kelompok yang memperhatikan lingkungan.
Hasil utama implementasi Konferensi Tingkat Tinggi Bumi antara lain adalah
berbagai rancangan besar yang berkaitan dengan pembangunan berkesinambungan
yang didasarkan atas pemeliharaan lingkungan. Pembangunan ekonomi dan sosial
yang dimasukkan dalam tiga dokumen yang secara hukum wajib berlaku atau
mengikat dan tiga dokumen lainnya yang secara hukum tidak mengikat.
Adapun tiga persetujuan meliput i:
1. Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati. Konferensi ini
bertujuan melestarikan beraneka ragam sumber daya genetika, semua jenis
mahluk hidup, habitat, dan sistem lingkungan.
2. Persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan
Iklim Global. Persetujuan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepekatan
gas rumah kaca di atmosfer hingga pada tingkat yang dapat mencegah
campur tangan manusia yang berbahaya yang berkaitan dengan iklim.
Persetujuan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penyelesaian Masalah
Penurunan Kualitas Tanah. Persetujuan ini berupaya mencipta pemecahan
terhadap masalah rusaknya tanah. Penurunan kualitas tanah ini telah
mengurangi secara signifikan daya dukung suatu kawasan bagi kehidupan
manusia yang mendiaminya (Soejachman, dalam Siagian dan Suriadi, 2012).
Selanjutnya tiga dokumen lainnya yang secara hukum tidak mengikat
merangkum dua kesepakatan, yaitu:
1. Pendeklarasian Rio berkenaan dengan asas yang menekankan hubungan
antara lingkungan dan pembangunan. Asas tersebut dapat dilaksanakan secara
umum dalam rangka menjamin pemeliharaan lingkungan dan pembangunan
2. Dasar-dasar kebenaran pengelolaan hutan, yaitu pernyataan yang mengikat
tentang dasar-dasar kebenaran bagi satu pertujuan dunia tentang pengelolaan,
pelestarian dan pembangunan berkesinambungan dari semua jenis hutan.
3. Agenda 21 yang merupakan rancangan lengkap tentang program
pembangunan berkesinambungan saat memasuki abad ke-21. Disebutkan
dalam Agenda 21 bahwa selain pemerintah bangsa-bangsa di dunia,
badan-badan khusus Perserikatan Bangsa bangsa dan organisasi internasional
lainnya, maka seluruh lapisan masyarakat perlu memahami konsep
pembangunan berkesinambungan. Ditegaskan pula, bahwa terdapat sembilan
kelompok utama yang diharapkan terllibat dalam program ini, yaitu:
1. Organisasi non pemerintah (NGO/LSM)
2. Pemuda
3. Pekerja
4. Petani dan nelayan
5. Pemerintah lokal
6. Perempuan
7. Ilmuwan
8. Pemuka adat (Siagian dan Suriadi, 2012: 62).
2.3.10.3 Millenium Development Goals (MDGs)
Kesamaan kemauan dan perhatian terhadap masalah kemiskinan yang di
derita oleh masyarakat dari berbagai negara, terutama negara-negara miskin dan
sedang berkembang antara lain terwujud dengan kehadiran Pernyataan Perserikatan
negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Konferensi Tingkat Tinggi
Millennium pada tahun 2000.
Terdapat delapan tujuan dan sasaran yang dirangkum dalam Millennium
Development Goals yang harus dicapai sebelum 2015, yaitu:
1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah.
2. Pencapaian Sekolah Dasar secara umum.
3. Membangun kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Mengurangi tingkat kematian anak.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit serius lainnya.
7. Menjamin kesinambungan pembangunan lingkungan.
8. Mengembangkan kerjasama global bagi pembangunan.
MDGsmenempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama
pembangunan, memiliki tengat waktu dan kemajuan yang terukur. MDGs didasarkan
pada konsensus dan kemitraan global sambil menekankan tanggung jawab negara
berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka. Sedangkan negara maju
berkewajiban mendukung upaya tersebut.
Manfaat dari MDGs tidak semata-mata untuk mengukur target dan
menentukan indikator dari berbagai bidang pembangunan yang menjadi tujuan, tetapi
yang terpenting adalah bagaimana tujuan pembangunan millenium dikonkritkan
pelaksanaannya. Misalnya tidak saja menghitung berapa jumlah ibu yang meninggal
disebabkan melahirkan tetapi juga bagaimana menghentikan kematian ibu karena
2.3.10.4 Tiga Garis Dasar (Triple Bottom Line)
Upaya membatasi meluasnya sikap egosentris dari para pelaku usaha secara
tajam datang dari John Elkington. Melalui bukunya berjudul Cannibals with Forks,
the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business, Elkington (1997)
mengenalkan konsep tiga garis dasar (Triple Bottom Line). Dalam bukunya tersebut
Elkington mencoba menyadarkan para pelaku usaha bahwa jika pelaku ingin
aktivitas ekonomi perusahaannya berkesinambungan dan berjalan baik maka para
pelaku usaha tidak boleh hanya berorientasi pada satu fokus berupa keuntungan,
melainkan harus menjadikan tiga fokus sebagai orientasi aktivitas ekonomi yang oleh
Elkington dinamakan dengan konsep “3P”.
Cakupan yang harus menjadi pusat perhatian para pelaku usaha adalah selain
mengejar keuntungan perusahaan (Profit), pihak pelaku usaha juga harus
memperhatikan dan terlibat secara sungguh-sungguh dalam upaya pemenuhan
kesejahteraan masyarakat (People),serta turut berpera aktif dalam menjamin
pemeliharaan dan pelestarian lingkungan (Planet).
Suatu perusahaan tidak boleh lagi dihadapkan dengan unsur tanggung jawab
yang berpijak pada satu garis dasar saja, yaitu berupa aspek ekonomi yang senantiasa
hanya diukur berdasarkan keadaan keuangan sebagai gambaran dari tingkat dan
besarnya keuntungan perusahaan. Bagaimanapun perusahaan senantiasa dihadapkan
pada tanggung jawab yang berpijak pada tiga garis dasar yang mana dua garis
pertanggungjawaban lainnya adalah memperhatikan aspek sosial, khususnya
kesejahteraan masyarakat lokal dan pemeliharaan serta pelestarian lingkungan
sebagai umpan balik dari eksploitasi terhadap sumber daya alam (Elkington, dalam
Meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi memang sangatlah
penting. Namun demikian, suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah
memperhatikan pemeliharaan lingkungan. Dalam kaitan inilah sangat sesuai dan
diperlukan implementasi konsep tiga garis dasar atau “3P”yang dikembangkan
Elkington. Dengan demikian, para pelaku usaha harus menyadari bahwa jantung hati
aktivitas ekonomi mereka bukan hanya keuntungan, melainkan juga masyarakat
dengan segala keperluannya dan lingkungan dengan segala keperluannya juga
(Siagian dan Suriadi, 2012: 78)
2.4. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah aktualisasi dari tanggung
jawab sosial perusahaan yang lebih bermakna dari sekedar aktivtas clarityataupun
dimensi tanggung jawab sosial perusahaan lainnya: community relation. Hal ini
disebabkan karena dalam pelaksanaan community development, terdapat kolaborasi
kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi,
produktivitas dan berkelanjutan. Dalam perwujudan Good Corporate Governance
(GCG) maka Good Corporate Citizenship (GCC) merupakan komitmen dunia usaha
untuk mewujudkannya.
Dalam aktualisasi GCC, maka konstribusi dunia usaha turut untuk serta
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mengalami metamorfosis dari
aktivitas yang bersifat charity menjadi aktivitas yang lebih menekankan kepada
penciptaan kemandirian masyarakat, yakni program pemberdayaan. Metamorfosis
tersebut pernah diungkapkan (Za’im Zaidi, dalam Ambadar, 2008:35) secara detail
Tabel 2.1
Karateristik Tahap-tahap Kedermawanan Sosial
Paradigma Charity Philantropy Good Corporate
Citizenship (GCC)
Motivasi Agama, tradisi,
adaptasi
Pengelolaan Jangka pendek,
mengatasi akar
Pengorganisasian Kepanitiaan Yayasan/dana
abadi/
Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas dan
perusahaan
Kontribusi Hibah sosial Hibah
pembangunan
Hibah (sosial dan
pembangunan serta
keterlibatan sosial)
Inspirasi Kewajiban Kepentingan
bersama
-
Sumber: Za’im Zaidi, Sumbangan Sosial Perusahaan, 2003, hal 130
Berdasarkan keterangan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa terdapat hal penting
yang membedakan antara aktivitas charitydengan philanthropyantara lain bahwa
dalam aktivitas philanthropyaktivitas lebih di dorong oleh norma dan etika hukum,
bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, selain itu inspirasi aktivitas adalah untuk
Dengan demikian tampak bahwa community development merupakan
pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Khususnya di Indonesia,
pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan memang tampaknya lebih
cocok dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan aktivitas
tanggung jawab sosial perusahaan yang bernafaskan community development dapat
mencapai tujuan strategis perusahaan. Di samping untuk mencapai profit optimum
juga dapat bermanfaat bagi komunitas. Di sisi lain, dengan adanya aktivitas tersebut,
komunitas memiliki mitra yang peduli terhadap kemandiriannya (Ambadar, 2008:
35).
2.4.1 Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu
proses pengupayaan masyarakat yang di dalamnya terkandung gagasan dan maksud
kesadaran tentang martabat dan harga diri, hak-hak masyarakat mengambil sikap,
membuat keputusan dan selanjutnya secara aktif melibatkan diri dalam menangani
perubahan (Bahari, dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 152).
Dalam tulisan berjudul Community Development and a Postmodernism of
Resistance, Mary Lane (dalam Siagian dan Suriadi, 2012: 152) mengemukakan
bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu seni yang melakuka aktifitasnya
melalui pengembangan hubungan, mendorong masyarakat untuk bertemu,
membentuk jaringan kerja dan mengemukakan kepentingan, keinginan, dan harapan
mereka melalui bentuk pengungkapan yang kreatif.
Dari definisi yang dikemukakan Mary Lane, masyarakat diletakkan sebagai
subyek dan obyek. Dalam proses implementasi pemberdayaan masyarakat sebagai
suatu strategi dan pendekatan intervensi sosial, maka masyarakat harus dilibatkan
hidup masyarakat dengan menggunakan pengembangan kapasitas internal
masyarakat, sehingga program tersebut benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Pada prakteknya ruang lingkup program pemberdayaan masyarakat dapat
diawali dari ikhtiar sederhana dalam suatu kelompok kecil. Ikhtiar tersebut
selanjutnya dapat dikembangkan menjadi program dan aktivitas yang lebih luas, dan
pada kelompok sasar yang lebih luas pula. Efektivitas pemberdayaan masyarakat
dapat dicapai jika dirancang dalam masa panjang, melalui rancangan yang tepat,
menyeluruh dan akurat, mengembangkan ikhtiar dan dukungan anggota masyarakat
sebagai kelompok sasar, menguntungkan masyarakat, dan berakhir pada pengalaman
yang berkesan (Smith, dalam Siagian, 2012: 153).
Efektivitas program pembedayaan masyarakat hanya akan tercapai muatan
program tersebut berisikan peluang dan masyarakat bersikap tanggap. Selanjutnya
masyarakat sadar atas kemampuan dan keterbatasnya dan mau bertindak bersama
untuk mencapai keuntungan bersama, dan semua perubahan yang terjadi ditanggapi
secara positif (Smith, dalam Siagian 2012: 154).
Perencanaan dan pembuatan keputusan berkaitan dengan program
pembangunan kerap kali dilakukan secara top down, tanpa melibatkan tokoh-tokoh
maupun anggota masyarakat sendiri. Akibatnya, aktivitas yang menjadi muatan
program pembangunan tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat. Ketidakefektifan tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti (Siagian
dan Suriadi, 2012:156):
1. Akitvitas pembangunan yang tidak sesuai dengan keperluan masyarakat
setempat,
3. Masyarakat kurang dilibatkan dalam berbagai aktivitas dan tidak bertanggung
jawab atas program dan efektivitasnya,
4. Aktivitas yang dilakukan justru menciptakan ketergantungan yang justru
lebih menyusahkan daripada meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2.4.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai aktivitas yang mengikutinya
tidak menempatkan masyarakat sebagai penerima program dan bantuan, lalu
dicemooh dan disindir karena dikatakan mempunyai mental subsidi dan terlalu
tergantung kepada belas kasihan pihak berkuasa. Sebaliknya, konsep pemberdayaan
masyarakat justru menempatkan masyarakat secara sentral dan kepentingan
masyarakat senatiasa menjadi variabel utama dalam proses penyusunan unit-unit
aktivitas yang akan dilaksanakan.
Ginanjar Kartasamita mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan
masyarakat mencakup pengertian pengembangan masyarakat dan pembangunan yang
bertumpu pada masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat adalah suatu
aktivitas memampukan dan memandirikan masyarakat, dengan demikian masyarakat
akan meningkat derajatnya (Kartasasmita, dalam Siagian, 2012: 158).
Ada dua hal utama dari definisi yang dikembangkan Kartasasmita. Pertama,
pemberdayaan masyarakat bertumpu pada masyarakat. Hal ini berarti bahwa fokus
dan pusat pembangunan itu adalah manusia, tegasnya masyarakat, dan bukan
pemerintah, dalam arti alat pencitraan bagi pemerintah. Kedua, indikator
keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemampuan masyarakat
Dengan demikian yang paling utama dibangun adalah kapasitas masyarakat dalam
mensejahterakan diri sendiri.
Suatu proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien
memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan
ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan
pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan
kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara
lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Payne, dalam Adi, 2003:54).
Dalam proses implementasi pemberdayaan masyarakat dalam perspektif
pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial harus menerapkan berbagai prinsip, seperti
(Siagian dan Suriadi,2012: 154) :
1. Pemahaman atas masyarakat secara mendalam sebagai kelompok sasar.
Untuk itu, data yang berkaitan dengan masyarakat sebagai kelompok sasar
merupakan modal awal bagi pekerja sosial dalam menjalankan perannya.
2. Belajar dari kisah efektivitas program pemberdayaan masyarakat
sebelumnya. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perlu dukungan
keberhasilan yang pernah dicapai. Oleh karena itu adopsi metode dan
asas-asas dari program pemberdayaan masyarakat yang nyata telah berhasil
diterapkan perlu dilakukan.
3. Belajar dari kegagalan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat
yang pernah dilakukan. Harus diakui bahwa implementasi program
pemberdayaan masyarakat tidak serta merta mencapai keberhasilan. Oleh
karena itu, pekerja sosial senantiasa harus belajar dari pengalaman
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebelumnya, baik oleh diri
4. Melibatkan seluruh anggota masyarakat dengan semua pengetahuan dan
kemampuan mereka. Masyarakat adalah pihak yang paling tahu akan
kebutuhan dan masalah sendiri. Oleh karena itu pengetahuan dan kemampuan
mereka harus digali dan dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat.
5. Memberi tanggapan yang senantiasa lentur sesuai dengan keadaan dan
masalah yang ada. Pekerja sosial harus mampu menerima bagaimanpun
kondisi masyarakat. Bahkan harus belajar dari kondisi yang ada.
2.4.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat
Prinsip-prinsip yang sebaiknya dipegang dalam pemberdayaan masyarakat
(berdasarkan acuan dari ACSD, 2004):
1. Kerja sama, bertanggung jawab, mengetengahkan aktivitas komunitas yang
tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Mobilisasi individu-individu
untuk tujuan saling tolong menolong, memecahkan masalah, integrasi
sosial dan tindakan sosial.
2. Pada tingkat paling bawah, partisipasi harus ditingkatkan dan
mengedepankan demokrasi ideal dari partisipatori dalam kaitannya dengan
sifat apatis, frustasi dan perasaan-perasaan yang sering muncul berupa
ketidakmampuan dan tekanan akibat kekuatan struktural.
3. Sebanyak mungkin ada kemungkinan dan kesesuaian, community
development harus mempercayakan dan bersandar pada kapasitas dan
inisiatif dari kelompok relevan dan komunitas lokal untuk
mengidentifikasi masalah-masalah, merencanakan dan melaksanakan
4. Sumber daya komunitas (manusia, teknik dan finansial) dan kemungkinan
sumber daya dari luar komunitas harus dimobilisasi dan kemungkinan
untuk diseimbangkan dalam bentuk kesinambungan.
5. Kebersamaan komunitas harus dipromosikan dalam bentuk dua tipe
hubungan yaitu: 1. Hubungan sosial dalam keberbedaan kelompok
dipisahkan melalui kelas sosial atau perbedaan yang signifikan dalam
status ekonomi, suku bangsa, identitas ras, agama, gender, usia, lamanya
tinggal dan lainnya yang mungkin menyebabkan peningkatan atau
membuka konflik. 2. Hubungan struktural antara pranata-pranata tersebut.
6. Aktivitas-aktivitas seperti meningkatkan perasaan solidaritas diantara
kelompok marginal dengan mengaitkan kekuatan perkembangan dalam
sektor-sektor dan kelas sosial untuk mencari kesempatan ekonomi, sosial
dan alternatif politik (Ambadar, 2008: 37).
2.4.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dari pelaku usaha untuk
memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawannya dan bertindak adil
terhadap berbagai pihak yang terkait dengan aktivitasnya, serta dengan ikhlas
menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk membiayai dan secara langsung atau
tidak langsung melakukan program-program yang bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan utama
perusahaan yang dikelola (Siagian dan Suriadi, 2012: 148).
Berdasarkan definisi tersebut, tidak cukup hanya memiliki niat dan kemauan
harus bertanggung jawab dalam menjamin perumusan dan implementasi berbagai
program atau aktivitas pemberdayaan masyarakat yang secara nyata dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang mampu menjamin
peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat yang menjadi pemangku
kepentingan utama perusahaan yaitu program dan unit-unit aktivitas pemberdayaan
masyarakat.
Terdapat hubungan yang sangat erat antara konsep tanggung jawab sosial
perusahaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Secara lebih lugas hubungan
di antara keduanya adalah, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan program
yang terdiri dari berbagai unit aktivitas pemberdayaan masyarakat. Dengan perkataan
yang lebih sederhana dapat dikemukakan, bahwa wujud nyata implementasi
tanggung jawab sosial perusahaan adalah program pemberdayaan masyarakat.
Jika dikaji lebih mendalam kaitan antara konsep tanggung jawab sosial
perusahaan dan pemberdayaan masyarakat, dapat kita kemukan lebih rinci, bahwa
tanggung jawab sosial perusahaan adalah niat dan kewajiban hukum untuk
melakukan program dan aktivitas transformasi khidmat kehadiran perusahaan di
sekitar atau lingkungan masyarakat. Agar khidmat itu nyata dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui program dan aktivitas yang dikenal
dengan pemberdayaan masyarakat dan disusun serta dilaksanakan secara efisien dan
efektif atas dukungan dari para pekerja sosial profesional (Siagian dan Suriadi, 2012:
149).
2.4.5 Peranan Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Konflik yang kerap terjadi antara perusahaan dan masyarakat setempat harus