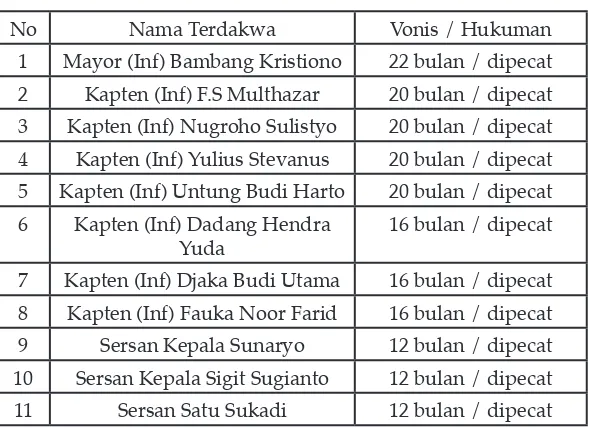Narasi Pembela HAM Berbasis Korban
Kata Pengantar
Reformasi 1998 adalah tonggak bersejarah untuk memancangkan kembali HAM di Indonesia, namun seberapa dekat kah kedua isu tersebut sehingga bisa berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan menelusuri hal-hal yang saling bertau-tan satu sama lain sepanjang sebelas tahun terakhir ini, seperti keberlangsun-gan penegakan HAM yang tidak bisa dilepaskan dari proses panjang dalam melakukan reformasi institusional, yang didahului dengan didirikannya Kom-nas HAM sebagai institusi yang didesain untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan HAM di Indonesia. Institusi tersebut diharapkan bisa menjalankan prinsipnya sebagai lembaga yang mandiri dan independen, khususnya dalam menjalankan amanat reformasi untuk mengusut semua ka-sus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sepanjang Orde Baru berkuasa. Namun dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak untuk mendukung proses reformasi berbagai halangan dan rintangan masih terus datang silih berganti, misalnya seperti kasus-kasus kekerasan dan anca-man kekerasan yang dialami oleh para pegiat HAM dan keanca-manusiaan, kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aksi premanisme yang dilakukan oleh kelompok sipil tertentu untuk merepresi kebebasan be-ragama dan berkeyakinan adalah potret kekerasan kerumunan yang tidak saja dimonopoli oleh negara yang acap melakukan tindakan destruktif, namun ke-kerasan kerumunan itu menyebar –bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja-.
Akibat dari tindakan kerumunan itu melahirkan polarisasi yang menempatkan masyarakat dalam ruang-ruang sempit, sebagian bahkan terpinggirkan akibat sekat pembatas yang menghalanginya. Polarisasi membagi masyarakat dalam dua dimensi. Pertama, kelompok masyarakat yang berkeinginan kuat untuk merubah keadaan dengan mulai mempelajari dinamika dari konsep HAM dan demokrasi. Kedua, kelompok masyarakat yang belum bisa menerima gagasan universalisme yang terkandung dalam HAM. kelompok terakhir ini akan ban-yak memandang HAM sebagai sebuah konsep yang digadang-gadangkan oleh negara-negara maju, bersinggungan dengan budaya barat dan tentu saja ber-tentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Eksistensi dari bentuk ekstrem polarisasi tersebut tidak saja mengancam posisi korban pelanggaran HAM yang masih setia menunggu dipulihkannya hak-hak mereka oleh negara, na-mun juga hadir kelompok rentan lainnya (wanita, anak-anak, penyandang ca-cat, kelompok minoritas, orang asli, aliran kepercayaan, dll) yang berpotensi mengalami kekerasan serupa.
sendiri menjadi refleksi bahwa negara sebagai entitas sosial politik formal mau -pun gerakan masyarakat sipil belum mampu mensosialisasikan HAM sebagai standar nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Hal lainnya yang juga menciptakan ruang ke-salah-kaprah-an di tengah masyarakat adalah ketika konsep HAM dipercayai sebatas tumpukan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang harus segera dituntaskan, tentu saja kondisi tersebut tidak membuka kesempatan untuk melihat esensi dari konsep HAM itu sendiri. Hadirnya tren ini diikuti dengan setumpuk konsekuensi yang menyertainya harus dihadapi bersama-sama tidak saja oleh para aktivis pegiat HAM dan kemanusiaan, me-lainkan juga segenap komponen bangsa yang memiliki perhatian luas dalam isu penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia.
Untuk itu, Human Rights Support Facilities (HRSF) yang didukung oleh Kon-traS, LBH Jakarta, HRWG, Yayasan Pulih serta Yayasan TIFA memandang perlu segera dilakukan upaya perlindungan terhadap mereka yang banyak melaku-kan aktivitas dalam memajumelaku-kan dan melindungi hak asasi manusia dan ke-bebasan dasar yang diakui secara universal, atau biasa dikenal dengan nama pembela HAM. Upaya perlindungan tersebut tidak saja menjamin keamanan para pembela HAM dalam situasi darurat, maupun jaminan untuk mendapat akses perlindungan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Selain itu HRSF juga mengemban misi untuk membangun jaringan solidaritas antar pembela HAM dengan ikut mengembangkan antar organisasi atau komunitas yang bisa mendukung upaya perlindungan tersebut.
Salahsatu aktivitas yang dilakukan oleh HRSF adalah melakukan penelitian pembela HAM berbasis korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam bentuk persoalan yang dihadapi oleh para pembela HAM yang meli-puti Pertama, kontribusi yang selama ini dilakukan korban dalam melakukan penegakan HAM. Kedua, sistem perlindungan yang selama ini dilakukan oleh korban sendiri ataupun dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya.
Ketiga, kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas advokasi kasus.
bertransformasi menjadi pembela HAM di lingkungan mereka masing-masing dan memberi banyak inspirasi dalam gerakan advokasi HAM di Indonesia.
Cuplikan pengalaman kesepuluh pembela HAM tersebut diambil dari latar belakang peristiwa baik yang langsung maupun tidak langsung dialami oleh
mereka. Dari cuplikan tersebut kita bisa mengidentifikasi ragam siasat yang
mereka pilih untuk membawa ruang perlawanan ke tengah-tengah komunitas, menumbuhkan keintiman solidaritas di tengah ancaman kekerasan dan keras-nya realitas kehidupan yang selalu membayangi mereka. Kisah Bedjo Untung berjuang selama puluhan tahun untuk melawan stigma yang terlanjur me-lekat dalam dirinya, diri para korban dan keluarga korban Tragedi 1965/1966, Wanma Yetty hingga kini masih berjuang untuk meraih keadilan bagi keluarga korban Tanjung Priok 1984, Azwar Kaili yang terus memotivasi para korban Talangsari dengan caranya sendiri untuk bangkit dan membangun perlawanan terhadap kuasa yang lalim. Hal yang sama juuga dilakukan oleh Ruyati Dar-win, Mugiyanto, Sumarsih, Suciwati, Zafrullah Pontoh, Kiswoyo, dan Mizar. Perjuangan mereka tidak saja bertujuan untuk memperoleh keadilan dan ke-benaran personal namun juga menularkan spirit perjuangan itu kepada komu-nitas korban/keluarga korban lainnya agar keadilan bisa benar-benar ditegak-kan.
Kami mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu keseluruhan proses Penelitian Pembela HAM Berbasis Korban. Ucapan itu terutama kami tujukan kepada para peneliti lapangan Wa-hyudi Akmaliyah Muhammad (KontraS), Febio Nesta – Muhammad Widodo (LBH Jakarta), Wakhit Hasyim (Yayasan Pulih). Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ali Nur Syahid, Indria Fernida, Papang Hidayat, Puri Ken-cana Putri dan Sri Suparyati yang mengawal proses penelitian dari awal hingga
proses finalisasi penyuntingan naskah buku ini. Tak lupa ucapan terima kasih
kami tujukan kepada Andi Achdian dan Hikmat Budiman yang telah meluang-kan waktu untuk memberi masumeluang-kan terhadap keseluruhan isi naskah.
Kami berharap dengan terbitnya buku ini maka kita bisa belajar banyak dari narasi perjuangan pembela HAM melalui pengalaman-pengalaman yang mer-eka tuturkan. Advokasi panjang tanpa lelah untuk saling menguatkan komuni-tas masing-masing melalui berbagai cara untuk mengekspresikan rasa keadilan dan kebenaran yang mereka damba-dambakan. Akhir kata selamat membaca dan berbagi pengalaman! Terima kasih.
Jakarta, 1 Desember 2009
Daftar Isi
Kata Pengantar
iii
Memperjuangkan Kebebasan Beragama
1
Ingatan yang Menjadi Peluru
13
Perjuangan yang Belum Selesai
39
Menagih Masa Lalu yang Dirampas
61
Meniti Jalan Tanpa Ujung
85
Berjuang dari Keterpurukan
99
Tulang Punggung Masa Depan itu Pergi untuk Selamanya
115
Dari Penjara ke Penjara
141
Sekilas Perjalanan Hidup Ustadz sang Pembela HAM
167
Menduduki Pabrik Sebagai Bukti Buruh Berdaulat
185
Memperjuangkan Kebebasan Beragama
Ahmad Zafrullah Pontoh
I. Menjadi Aktivis Jemaah Ahmadiyah Indonesia
Ahmad Zafrullah Pontoh, atau yang akrab disapa dengan nama belakang-nya saja, Pontoh, dilahirkan di Bolang Itang Sulawesi Utara, pada tahun 1952. Pontoh adalah putera keenam dari sembilan bersaudara. Ayahnya bekerja di Koperasi Rakyat (KOPRA) dan ibunya lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Keluarga Pontoh memang memiliki latar belakang yang unik, khu-susnya terkait dengan keragaman budaya yang dimiliki oleh mereka. Pontoh sendiri mengakui bahwa dirinya merupakan peranakan campuran antara Fili-pina Selatan (Mindanao), Banten, Bugis dan Bolang Itang.
Pontoh besar di dalam keluarga yang berlatar belakang Islam Ahmadiyah, di mana nilai-nilai keagamaan mewarnai pendidikannya sehari-hari di rumah. Ayahnya memiliki karakter pendiam namun tegas. Meskipun nilai-nilai agama selalu diterapkan dalam pengajaran sehari-hari, akan tetapi penanaman nilai-nilai agama itu tidak dilakukan dengan cara-cara memaksan. Dengan kata lain pendidikan kegamaaan a la moderat yang selalu ditanamkan di dalam kelu-arga Pontoh. Sedangkan sang ibu, lebih banyak menanamkan nilai-nilai yang bisa dijalankan untuk menjaga amanat.
Secara struktur sosial, Pontoh berasal dari keluarga yang relatif berpendidikan. Ayahnya pernah mengenyam pendidikan di Hollandsch Inlandsche School (HIS: Sekolah rendah dengan bahasa pengantar Belanda); saudara-saudara sekandungnya juga bisa menikmati pendidikan minimal setingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLA); sementara beberapa saudaranya yang lain sempat meng-enyam pendidikan di perguruan tinggi. Kondisi ini tentu saja ditopang den-gan kemampuan ekonomi keluarga Pontoh yang cukup memadai. Bahkan, ayahnya sering menampung orang-orang yang tidak mampu untuk tinggal di rumahnya, atau sekadar ikut menumpang tinggal.
Pontoh memperistri seorang perempuan yang berasal dari Qadian, India. Dari perkawinannya, ia dikarunia empat orang anak, di mana dua dari anaknya masih duduk di bangku kuliah dan dua lainnya masih bersekolah di seko-lah menengah atas dan sekoseko-lah dasar. Sehari-hari, Pontoh berprofesi sebagai mubalig pada jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk wilayah DKI Jakarta. Penghasilannya pun ia peroleh dari pekerjaannya itu. Sebagai mubalig, Pontoh mendapatkan beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang mo-bilitasnya, seperti fasilitas rumah dan kendaraan dinas. Selain itu, Pontoh juga memiliki beberapa bidang tanah di Bolang Itang, yang berasal dari waris dan pemberian.
Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, akan tetapi perkuliahan itu tidak ia teruskan karena Pontoh lebih memilih dunia kerja sebagai pilihan hidupnya. Untuk menunjang profesinya, Pontoh akhirnya memilih untuk mengikuti pendidikan mubalig di Rabwah, Pakistan. Tentu saja, pertimbangan itu ia lakukan dengan masak-masak, apalagi jika kita mengenal karakter Pon-toh lebih dalam, sebagai pribadi yang keras dan memiliki keteguhan hati.
Pilihan-pilihan yang ia ambil dalam hidup dilakukan dengan penuh konseku-ensi. Kerasnya kemauan dan sikap yang tidak mudah berubah atas sesuatu yang ia anggap benar menjadi hal yang senantiasa ia lakukan dalam perbuatan sehari-hari. Pontoh pun tidak pernah takut dalam menjalani kehidupan mau-pun menghadapi orang-orang dan kelompok yang menentang/berseberangan dengan keyakinannya. Sikap inilah yang membedakan Pontoh dari keban-yakan orang, ketegasan yang ia miliki sedikit banyak ia dapatkan dari ajaran agama yang ikut membentuk karakter internal dirinya.
II. Pontoh dan Kehidupan Sehari-harinya
Paham Ahmadiyah tampaknya telah mendarahdaging dalam kehidupan Pon-toh sejak kecil. Namun hadir fakta historis yang PonPon-toh tuturkan bisa dijadi-kan permulaan untuk melihat individu-individu yang menjalani keyakinan tersebut (baca: Ahmadiyah). Hidup dalam keluarga yang meyakini secara utuh paham Ahmadiyah, tidak serta merta membuat Pontoh langsung menjadi pengikut Ahmadiyah. Sejak kecil, Pontoh banyak dikenalkan dengan literatur yang membahas tuntas ajaran Ahmadiyah yang dibawa oleh ayahnya. Dari sana, perlahan-lahan Pontoh mulai menemukan adanya kebenaran dari ajaran Ahmadiyah. Hingga ia mengikuti proses baiat setelah ia menyelesaikan masa sekolahnya. Proses pem-baiat-an itu dilakukan di Mubagu, Sulawesi Utara.
Keinginan untuk menjadi mubalig mulanya adalah arahan yang dilakukan oleh ayahnya. Bahkan, jauh sebelum itu, Pontoh kecil telah didaftarkan sebagai anak wakaf, di mana kelak ketika ia menginjak usia dewasa, Pontoh dapat men-gabdikan dirinya kepada Jemaat Ahmadiyah. Ayahnya pun tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan Pontoh agar segera mengabdikan dirinya kepada Jemaat Ahmadiyah, tentu saja sebagai mubalig. Setelah menyelesaikan masa SMA, sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya, kembali mengingatkan Pontoh agar dirinya segera membuat pilihan hidup bagi masa depannya. Mulanya, Pontoh memilih untuk bekerja di bidang swasta. Pilihan itu ia lakukan karena mempertimbangkan bahwa orang-orang yang telah mewakafkan dirinya, ha-ruslah orang yang tidak lagi mengejar harta kekayaan dan sudah memiliki cu-kup uang simpanan untuk membiayai diri sendiri.
Putusan itu juga diikuti dengan berbagai godaan yang timbul ketika ia mem-persiapkan diri untuk melanjutkan sekolah ke Rabwah, Pakistan. Berbagai ta-waran kerja hingga iming-iming untuk melanjutkan kuliah yang berasal dari sanak saudaranya, tidak membuat Pontoh gentar untuk merubah keputusan-nya, melanjutkan sekolah agama di Rabwah.
Setelah menyelesaikan sekolah agama di Rabwah, Pontoh ditugaskan ke ber-bagai daerah untuk melakukan pembinaan keagamaan kepada anggota Ah-madiyah dan masyarakat umum. Tugasnya selaku mubalig membuat ia dan keluarga selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Daerah-daerah yang pernah ia tinggali di antaranya; Parung Bogor, Medan, dan Petojo DKI Jakarta. Di se-tiap lingkungan di mana ia tinggal, Pontoh sering melakukan kegiatan berkeli-ling kampung untuk sekadar menyapa para tetangga dan bersilaturahmi. Ke-giatan ini sudah menjadi kebiasaan di manapun ia menetap. KeKe-giatan ini pula yang membuat orang-orang di sekitar lingkungan tinggalnya cukup mengenal baik Pontoh.
Lingkungan di Petojo Jakarta Pusat, misalnya, tergolong lingkungan yang rela-tif aman. Letaknya yang strategis di wilayah ibukota dan cukup dekat dengan Istana Presiden, membuat lingkungan ini memiliki sistem pengamanan yang baik. Pontoh mengilustrasikan lingkungan tempat tinggalnya sebagai sebuah wilayah yang dilengkapi dengan pagar pengaman dan petugas keamanan. Pagar kompleks perumahan akan ditutup setelah melewati pukul 21.00 WIB. Rata-rata warga yang menghuni wilayah tersebut merupakan masyarakat golongan menengah ke atas. Meski pun tetap ada kelompok masyarakat yang kurang mampu tinggal di sana. Umumnya, mereka berprofesi sebagai pegawai dan ada pula yang bekerja sebagai pengusaha.
Hampir di setiap lingkungan yang ia kunjungi dan ia tinggali, Pontoh selalu menyempatkan diri untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh warga setempat. Kegiatan itu bisa berupa kegiatan kerja bakti, pengobatan massal dan berbagai macam bentuk kegiatan sosial lainnya.
III. Kekerasan dan Ancaman kekerasan yang Dialami
III.1. Peristiwa Medan
apakah mau tetap bertahan dengan segala risiko yang harus dihadapi; atau pergi meninggalkan lokasi untuk meminimalisir risiko. Pilihan kedua pun di-ambil oleh mereka, dengan menggunakan mobil milik salahsatu jamaah, Pon-toh dan para rombongan meninggalkan lokasi yang telah dikepung massa.
Masa yang mengepung rumah jamaah tersebut, telah bersiap dengan berbagai senjata seperti parang, pentungan dan sebagainya.Bahkan juga sebatang pohon sengaja ditumbangkan untuk menghalangi jalan Pak Pontoh dan rombongan. Namun akhirnya mereka bisa meloloskan diri dengan selamat. Pascaperistiwa itu, Pontoh mencoba untuk mengontak koneksi yang ia miliki di Pemda. Dari komunikasi yang ia bangun, langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa membantu proses pengamanan di lokasi kejadi-an. Komunikasi yang dibangun tersebut, diakui Pontoh memang sangat efektif untuk meredam gejolak penolakan kelompok masyarakat yang berseberangan dengan ajaran Ahmadiyah.
III.2. Peristiwa Parung
Peristiwa kekerasan lainnya yang terjadi adalah ketika JAI menyelenggarakan Jalsah Salanah di Parung Bogor, Juli 2005. Kegiatan yang seharusnya dilak-sanakan selama 3 hari, dari tanggal 8 hingga 10 Juli 2005 terpaksa harus diper-cepat prosesnya, akibat adanya penyerbuan yang dilakukan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok-kelompok LPPI, FPI dan GUII. Ke-lompok itu dipimpin langsung oleh Abdul Haris Umarela yang menyebut dir-inya sebagai Habib Abdurahman Assegaf bersama-sama Amin Djamaluddin.
menyam-paikan agar polisi segera memberikan pengamanan terhadap acara Jalsah Sala-nah. Acara tersebut sejatinya telah mendapatkan izin dari Mabes Polri, sehing-ga sudah menjadi kewajiban kepolisian setempat untuk mensehing-gamankan acara tersebut.
Pontoh mengatakan, pengepungan terbesar terhadap Pusat kegiatan Ahmadi-yah di Parung terjadi pada 15 Juli 2005. Sekitar 3000 orang berkumpul di de-pan Kampus Mubarak. Sebagian dari mereka bersenjatakan kayu dan bambu runcing menuntut pembubaran Ahmadiyah dan penutupan Kampus Mubarak. Akibatnya, dalam pengawalan polisi, sekitar 300 orang anggota Ahmadiyah yang berada di dalam kampus dievakuasi paksa untuk menghindari ancaman pembakaran kampus. Meskipun demikian, tetap saja, sebuah gedung Lajnah Imailah yang berjarak sekitar 300 meter di belakang kampus dirusak dan di-jarah oleh para penyerang. Kediaman Pontoh di Parung pun yang sedianya akan ia tempati bersama keluarga sebagai rumah dinas tidak luput dari sasaran para penyerang. Para penyerang membongkar rumah Pontoh dari belakang dan merusak serta menjarah harta benda yang ada di dalamnya. Pontoh men-gakui, sehari sebelum peristiwa pengepungan besar-besaran itu, ia sempat be-rada di Parung, akan tetapi karena ia harus berangkat ke Jakarta untuk mengisi pos yang kosong, Pontoh harus meninggalkan Parung.
III. Peristiwa Petojo
Ancaman kekerasan yang dilancarkan dari kelompok penentang Ahmadiyah juga masih dialami Pontoh ketika ia pindah ke wilayah Petojo, DKI Jakarta. Pasca penyerbuan Parung, kantor Pengurus Besar JAI yang awalnya berada di Parung, akhirnya dipindahkan ke Petojo. Rupanya informasi ini bocor ke habib Abdurrahman Assegaf. Beberapa kali Habib Abudrrahman Assegaf bersama anggotanya mendatangi masjid Petojo dan mengancam akan membakar mas-jid apabila plang mesmas-jid yang identik dengan Jemaat Ahmadiyah tidak segera diturunkan. Dalam kedatangan selanjutnya, Assegaf bahkan meminta agar Ah-madiyah segera membubarkan diri.
pi-hak Polda Metro Jaya membubarkan persiapan acara itu dengan melakukan pendekatan terhadap salahsatu ustadz masjid yang mengadakannya.
Pembubaran yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tidak membuat Habib Abdurrahman Assegaf gentar. Dalam beberapa kesempatan, Habib Abdurrah-man Assegaf selalu mendatangi masjid JAI Petojo. Kedatangannya itu selalu ditanggapi dengan respon positif oleh Pontoh sebagai bentuk silaturahmi an-tar sesama umat muslim. Di sinilah Pontoh memandang tugas ke-mubalig-an yang diembannya harus bisa digunakan untuk meluruskan berbagai pemaha-man yang keliru seputar Ahmadiyah itu sendiri. Hanya saja keinginannya un-tuk meluruskan pemahaman para penentang Ahmadiyah urung tersampai-kan, karena kedatangan mereka ternyata hanya bertujuan untuk mencaci-maki, mengancam, melakukan tindakan anarkis; tanpa pernah mau melakukan ko-munikasi lebih lanjut.
Pontoh menganggap, berbagai peristiwa yang menimpa Jemaat Ahmadiya di Indonesia selalu membawa hikmah tersendiri. Ajaran Ahmadiyah yang senan-tiasa meletakkan nilai-nilai kebenaran sebagai basis ajaran senansenan-tiasa akan mendapat banyak ujian dan cobaan. Peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Ahmadiyah seharusnya tidak membuat anggota Ahmadiyah mundur, na-mun kondisi ini harus bisa menyatukan mereka dalam ikatan solidaritas yang kokoh. Pontoh mengakui, beberapa anggota Ahmadiyah yang dulunya men-jauh, akibat peristiwa ini, kini kembali mendekat.
Seringnya peristiwa kekerasan yang menimpa kelompok Ahmadiyah, mem-buat jemaat-nya banyak mendapat kesempatan untuk tampil di muka publik untuk menyampaikan esensi utama dari ajaran Ahmadiyah. Padahal, sebelum adanya peristiwa itu, pekerjaan menyampaikan informasi seputar aktivitas Ah-madiyah bukanlah sebuah perkara gampang. Seringnya peristiwa kekerasan yang menimpa Ahmadiyah, membuat Pontoh dan keluarga seolah menjadi terbiasa dengan kondisi tersebut. Kondisi itu tidak serta merta mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi Pontoh. Hanya saja akibat yang bisa dirasakan secara langsung dari peristiwa itu adalah pekerjaan yang kian bertambah seir-ing waktu, tenaga dan pikiran yang harus disediakan Pontoh untuk mengad-vokasi kasus Ahmadiyah.
kampung yang harus dibela. Selain dari itu, sesungguhnya tidak ada perbe-daan mencolok yang bisa dirasakan antara orang-orang yang menjalankan pa-ham Ahmadiyah dengan masyarakat kebanyakan.
IV. Survivalitas Pontoh dalam Mengadvokasi Ahmadiyah
Pascapenyerangan Parung, Pontoh dipercaya oleh Amir Nasional Indonesia sebagai wakil Amir untuk berbicara kepada publik. Hal ini membuat Pontoh banyak muncul di pertemuan-pertemuan publik seperti di baik di seminar, diskusi publik, maupun talkshow di banyak media elektronik. Hampir di berb-agai kesempatan, Pontoh terlibat aktif mengikuti pertemuan-pertemuan untuk membicarakan isu-isu kebebasan beragama.
Persoalan ancaman dan kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah secara umum adalah persoalan yang terkait dengan hak ke-warga-negara-an yang sudah se-harusnyanya dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, langkah hukum yang diam-bil oleh JAI sebagai langkah utama dalam melakukan advokasinya merupakan pilihan yang tepat. Langkah hukum itu juga diikuti dengan berbagai bentuk pendekatan nonformal yang dilakukan dengan melibatkan dukungan dari ber-bagai pihak.
Selain ditunjuk sebagai juru bicara (wakil Amir Nasional Indonesia), Pontoh tetap menjalankan amanatnya sehari-hari sebagai seorang mubalig untuk wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Pontoh juga dipercaya untuk mengurus me-dia center JAI. Tugas-tugas baru itu membuat pekerjaan Pontoh menjadi be-gitu padat. Kini, ia tengah berharap untuk lebih mampu mengatur jadwal dan SDM yang bisa digunakan untuk mengoptimalisasi aktivitasnya. Sayangnya, harapannya itu tidak didukung dengan SDM yang memadai, yang akhirnya membuat Pontoh merasa keteteran sendiri.
Diakui oleh Pontoh, dirinya memang tidak banyak terlibat dalam advokasi ka-sus di bidang hukum, karena sudah ada orang-orang yang ditunjuk khuka-sus untuk membidangi hal tersebut. Meskipun demikian, dalam setiap pertemuan koordinasi yang melibatkan LBH jakarta maupun dengan organisasi pendu-kung lainnya, Pontoh tetap datang menghadirinya sebagai wakil Amir Nasi-onal Indonesia.
Ada perbedaan prinsipil dalam memandang kerja-kerja advokasi yang di-lakukan oleh organisasi pendamping dengan JAI. Misalnya, penggunaan aksi demonstrasi sebagai salah satu pilihan advokasi. Secara kelembagaan, JAI me-mandang aksi demonstrasi bukanlah pilihan yang efektif dalam melakukan ad-vokasi, karena tingkat kerawanannya terhadap aksi anarkis dan adanya kekha-watiran aksi tersebut bisa disusupi. Pilihan-pilihan langkah advokasi semacam itu tidak sejalan dengan sikap JAI yang lebih mengedepankan prinsip nir-ke-kerasan dan cinta kasih. Dan jika diperlukan, JAI akan lebih memilih prose-dur-prosedur formal, seperti mekanisme hukum. Alasan inilah yang seringkali menyebabkan JAI tidak pernah terlibat secara kelembagaan dalam beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh AKKBB. Namun demikian, JAI tidak pernah menghalangi bila para anggotanya sesuai dengan kapasitas personal, ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Pontoh hanya berharap para pendamping dapat memahami jalan pikiran dan sikap kelembagaan yang diambil JAI.
Sementara itu, dukungan terhadap perjuangan Pontoh dan JAI juga datang dari sanak keluarga yang tidak menganut paham Ahmadiyah. Pada umumnya, sanak keluarga Pontoh akan langsung menghubungi jika media massa mem-beritakan peristiwa kekerasan yang dialami JAI. Dan tidak sedikit dari mereka yang ikut memberikan semangat dan dukungan agar Pontoh tetap terus mem-perjuangkan apa yang telah diyakininya.
Keluarga Pontoh pada dasarnya tidak begitu khawatir atas peristiwa yang ter-jadi. Selain karena sang isteri berasal dari Qadian, di mana peristiwa-peristiwa kekerasan lebih sering terjadi di sana. Pontoh senantiasa mengajarkan agar ke-luarganya bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan bahwa cobaan akan selalu datang kepada ajaran yang benar.
Dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah dari pihak kepolisian bisa
di-katakan cukup siginifikan, dalam berbagai ancaman penyerangan yang datang
Pontoh bisa menggunakannya sebagai bagian dari koordinasi dengan aparat pemerintah; mulai dari tingkat RW hingga tingkat kecamatan.
V. Hubungannya dengan Korban Pelanggaran HAM Lain
Profesinya sebagai mubalig, memudahkan Pontoh untuk memanfaatkan fo-rum-forum JAI seperti khotbah Jumat, pengajian, serta rapat-rapat pengurus untuk berkomunikasi dan membagi informasi aktual dengan para anggota. Di sana, Pontoh sering memberikan semangat, motivasi dan hikmah yang bisa di-petik dari peristiwa yang menimpa mereka.
Tak jarang Pontoh melakukan kunjungan ke cabang-cabang JAI lainnya un-tuk memberikan penjelasan bagaimana langkah-langkah advokasi yang bisa dilakukan, sesuai pengalaman yang ia alami terkait kasus yang sedang me-reka hadapi itu. Selain menggunakan forum-forum tatap muka, dalam menja-lin komunikasi Pontoh juga sering menggunakan medium telepon, pesan sing-kat dan email.
Pontoh tidak saja aktif dalam pertemuan-pertemuan yang membahas kasus JAI. Dalam berbagai kesempatan, Pontoh pun sering menyempatkan dirinya untuk menghadiri pertemuan yang membahas kasus-kasus kebebasan beragama lain-nya, seperti dalam kasus yang menimpa komunitas Eden, dan kasus penutu-pan gereja. Pontoh memandang bahwa setiap bentuk penganiayaan, penyik-saan, hingga penistaan sebuah keyakinan tidak semestinya diterima oleh siapa pun. Jika itu terjadi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan, yang oleh siapa pun harus dibela. Pontoh begitu meyakini bahwa Islam telah mengajarkan nilai-nilai kedamaian, sehingga penting baginya untuk memper-juangkan hal itu bersama-sama dengan kelompok lain. Ia tidak dapat mema-hami, mengapa suatu perbedaan pikiran selalu direspon dengan penganiayaan
fisik.
VI. Efektifitas Advokasi JAI
Dalam proses advokasi JAI, Pontoh berusaha realistis dengan semua capaian yang berhasil diraih. Baginya, keberhasilan advokasi adalah ketika media mas-sa memuat berita sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak dipelintir sehingga dapat berakibat merugikan JAI. Di samping itu, respon aparat negara, khu-susnya kesigapan aparat keamanan dalam menangani setiap peristiwa yang terjadi, merupakan buah keberhasilan dari advokasi yang dilakukan.
dihada-pi dengan kepala dingin. Ancaman yang datang baik langsung maupun tidak langsung, ia tanggapi dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan. Selain membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah; mu-lai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Pemerintah Provinsi. Hal yang masih disayangkan oleh Pontoh adalah belum adanya mekanisme hukum yang bisa menjerat para pelaku yang masih melakukan kriminalisasi kepada mereka yang bergerak di bidang kemanusiaan.
Pontoh menyadari kemampuannya dalam bidang relasi masyarakat. aktivitas sehari-harinya yang banyak disibukkan dengan persoalan keagamaan, menun-tut Pontoh untuk bisa memahami konsep keagamaan dengan lebih baik. Menu-rutnya, logika hukum dengan logika agama tidak jauh berbeda, bahkan sama saja. Kemampuan inilah yang membuatnya dipercaya mewakili Amir Nasional Indonesia dalam berbagai forum dan kesempatan. Dengan kemampuannya itu, Pontoh menjadi tandem yang cukup tangguh bagi pihak-pihak yang me-miliki sudut pandang berbeda dengan JAI di dalam forum-forum diskusi dan talkshow.
Pontoh melihat penting dilakukan seminar-seminar atau pelatihan peningka-tan kapasitas bagi para korban termasuk dirinya agar menunjang kerja-kerja advokasi. Meskipun JAI sendiri dalam beberapa kesempatan pernah melaku-kan pelatihan semacam itu, namun dirasa masih tetap perlu mengintensifmelaku-kan pelatihan. Sejalan dengan hal ini, kiranya pelatihan yang membuka paradigma dan wawasan menjadi hal yang krusial dilakukan. Kebiasaan bekerja di dalam sistem, membuat Pak Pontoh dan korban-korban JAI lainnya tidak mampu mengembangkan metode advokasi yang dilakukan, meskipun kadang ide-ide yang positif muncul dari para korban sendiri.
Sedangkan secara ekonomi, sebagai bagian dari sistem JAI, belum dirasa perlu dilakukan. Oleh karena, iuran anggota yang selama ini dibayarkan cukup me-madai untuk membiayai kerja-kerja advokasi yang dilakukan.
VII. Perlindungan terhadap Korban
ter-hadap mereka yang datang, meskipun jelas mereka datang sembari melakukan ancaman-ancaman.
Sedangkan koordinasi dengan pihak jaringan, seperti AKKBB, LBH Jakarta, Komnas Jakarta, dan lain-lainnya, dilakukan oleh tim yang khusus untuk itu. Solidaritas yang dilakukan oleh jaringan dengan ikut mendampingi JAI dalam menghadapi kedatangan Assegaf dan kelompoknya, jelas sangat membantu Pak Pontoh dan JAI pada umumnya.
Ingatan Yang Menjadi Peluru
I. Doa-doa Yang Terkabulkan
Maria Katarina Sumarsih lahir pada 5 Mei 1952 di Salatiga, Jawa Tengah. Na-mun, tanggal lahir yang tertera di Kartu Penduduknya adalah 28 Desember 1950. Ini dilakukan untuk mensiasati agar ia bisa masuk sekolah rakyat un-tuk mengikuti kakak sepupunya. Kendati ia memalsukan tanggal kelahiran-nya, sebelum masuk Sekolah Rakyat itu ia sudah bisa membaca dan menulis. Karena itu ia langsung didaftarkan di kelas itu. Ia anak pertama dari enam bersaudara. Ia terlahir dari kultur budaya Jawa yang sangat kental di mana agama bukanlah menjadi faktor utama dalam mewarnai hidup seseorang. Orangtua Sumarsih menganut aliran kepercayaan Kejawen, meskipun secara formal bergama Islam1. Dalam kategori Cliffort Geert, orangtuanya Sumarsih
termasuk ke dalam Islam Abangan. Yang terpenting dalam penganut keper-cayaan ini adalah esensi prilaku dalam berbuat baik ketimbang ritual formal. Karena itu, orangtuanya selalu menasihati Sumarsih dan adik-adiknya bahwa yang terpenting dalam hidup sehari-hari harus ingat dan hormat pada yang memberi hidup dan kehidupan, harus selalu berbuat baik, menghormati setiap orang, jujur, dan waspada. Karena di dunia ada yang lebih berkuasa. Dalam menjalankan praktek ritual keagamaan pun mereka memberikan keleluasaan kepada anak-anaknya.
Pascaperistiwa 1965-1966 telah merubah struktur kekuasaan di Indonesia. Pada masa itu, orang yang tidak memeluk salah satu agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, akan dicap komunis. Selain itu, mereka akan ditangkap dan dipenjarakan. Alasan penangkapan dan pemenjaraan tersebut adalah den-gan dikeluarkannya UU/no 01/ PNPS tahun 1965 tentang pencegahan dan penodaan agama. Akibat Undang-Undang itu, bisa dipastikan, agama-agama lokal yang mengadopsi istilah agama ”resmi” bisa terancam pasal didalam-nya2. Sumarsih pun meminta kepada adik-adiknya untuk menentukan
pili-han agama. Dari 6 bersaudara, 3 orang memilih Islam dan 2 orang, termasuk Sumarsih, memilih Katholik. Ia memilih Katholik berawal dari pertemuan den-gan saudara sepupunya yang selalu menceritakan bagaimana tata kehidupan keluarga Katholik. Salah satu nilai dalam Katholik yang membuat ia terkesan adalah bahwa dalam kehidupan Katholik tidak boleh ada perceraian. Meskipun sederhana, tapi kata-kata itu mengandung makna terdalam untuk Sumarsih3.
Setelah selesai dari Sekolah Rakyat, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Eko-nomi Pertama yang kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah
mi Atas, di Salatiga, Jawa Tengah. Sejak kelas II SMEA pada tahun 1968 inilah ia mulai mengenal gereja Kristen lebih mendalam bersama teman-teman in-dekosnya. Yang dua orang di antaranya adalah siswi SPG Kristen. Di Gereja dekat tempat ia sekolah itu pula ia lebih menangkap pesan-pesan khotbah pen-deta ketimbang ayat-ayat Kitab Suci yang dahulu semasa kecil ia dapatkan. Sebulan setelah lulus SMEA, pada 21 Januari 1970 ayahnya meninggal dunia. Tulang punggung pencari nafkah pun berpindah kepadanya. Ia harus membi-ayai pendidikan untuk 4 orang adiknya. Keinginan untuk melanjutkan belajar ke jenjang lebih tinggi ia benamkan. Ia kemudian bekerja di kantor Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ia ditempatkan di panitia Pemili-han Suara Pemilu 1971. Setelah pemilu usai, ia bekerja sebagai Petugas Lapan-gan Keluarga Berencana di bawah BKKBN wilayah Kabupaten Semarang. Pada masa itu pula ia bersama teman-teman seusianya mendirikan Sekolah Menen-gah Pertama sekaligus sebagai tenaga pengajar4.
Pada hari Minggu, 5 Desember 1976, Sumarsih menerima Sakramen Pernika-han bersama Arief, lelaki yang ia kenal sejak tahun 1968 dari teman indekosnya yang kuliah di Universitas Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Mereka me-nerima sakramen pernikahan di Gereja Santo l’ara Martir Jepang, Salatiga. Se-belumnya, menjelang pernikahan, Sumarsih harus mengikuti pelajaran agama Katholik yang dibimbing Romo Ign. Wignyosumarto, MSC. Setelah dinyatakan lulus dan layak, ia dipermandikan pada 27 Oktober 1976. Sejak itu, setiap Mi-nggu pagi ia pergi ke Gereja Salatiga dengan bersepeda motor milik inventaris BKKBN dengan jarak tempuh 25 Km. Sebelum pernikahan, ia juga diminta un-tuk mengikuti kursus perkawinan sebanyak 4 pertemuan5. Sedangkan Arief,
sang suami, mengikuti kursus perkawinan di Jakarta.
Pada bulan April 1977, Sumarsih mengikuti suami pindah ke Jakarta. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Hadiah, Jelambar yang berada di dekat St. Kristophorus. Dengan suasana lingkungan umat gereja inilah rasa kekatholikan di dalam dirinya semakin tumbuh, meskipun ia belum begitu fasih dalam mengucapkan doa Salam Maria. Setiap Minggu ia bersama suami
4 Wawancara dengan Sumarsih, Keluarga korban Peristiwa Semanggi I, 16 Desember 2008.
selalu pergi berdoa ke Gereja St. Kristophorus. Sumarsih, dalam doanya, se-lalu meminta agar dikarunia seorang anak pertama laki-laki dan anak kedua seorang perempuan. Alasannya anak pertama laki-laki adalah karena ia lam-bang perlindungan. Namun, bukan berarti doa yang ia lantunkan itu bentuk pemaksaan, tapi satu keinginan lahiriah seorang ibu. Karena itu, ia dan suami telah menyiapkan sebuah nama dengan makna yang sama, yaitu Norma Ir-mawan untuk laki-laki dan Irma Normaningsih untuk perempuan. Nama itu mengandung harapan, kelak menjadi orang-orang yang mengetahui akan “norma” atau kaidah hukum yang berkeadilan, tanpa melupakan “irama” ma-syarakat yang penuh dinamika. Tambahan “wan” dan “sih” untuk membeda-kan laki-laki dan perempuan6.
Doa Sumarsih dikabulkan. Pada hari Senin, 15 Mei 1978, jam 12.05, ia melahir-kan seorang bayi laki-laki. Pada hari Rabu, 17 Mei, Romo J.G Beek SJ datang mengunjungi Sumarsih di rumah bersalin Sumber Waras, Jakarta Barat, dan memberikan berkat kepada anaknya. Atas permohonan Arief Priyadi, sang suami, Romo Beek memberikan nama permandian untuk anak mereka, yaitu Bernardinus Realino. Nama Bernadinus diambil dari seorang wali kota di be-nua Eropa yang sangat gigih memperjuangkan keadikan bagi rakyat tertindas, sedangkan Realino adalah nama asrama mahasiswa di Yogyakarta yang pernah didirikan oleh Romo Beek itu. Pada hari Minggu, 25 Juni 1978, si kecil Norma Irmawan dipermandikan di Gereja St. Kristophorus oleh Romo K.Bertens. 14 tahun, pada 23 April 1992, Norma Irmawan menerima sakramen penguatan di Gereja yang sama oleh Bapak Uskup Agung Jakarta Mgr. Loe Soekot SJ. Setelah mengkonsultasikan sendiri atas nama yang dipilih oleh Wawan, begitu Norma Irmawan biasa disapa, yaitu Yusuf, dalam surat Sakramen Penguatan namanya menjadi Bernardinus Yusuf Realino Norma Irmawan.
Sumarsih dan sang suami, setelah anak pertama lahir, pada akhir Desember 1978 pindah tempat tinggal. Mereka tinggal di sepetak tanah dengan bangunan rumah tua model Betawi Kedoya, Jakarta Barat. Rumah itu dibeli dari hasil jerih payah mereka selama bekerja di Jakarta. Setahun kemudian, ia melahirkan kembali seorang anak perempuan pada 14 Januari 1980. Arief lalu memberikan nama permandian kepada anak kedua yang sudah diberi nama Irma Norman-ingsih, yaitu Benedicta Rosalia. Lengkapnya menjadi Benedicta Rosalia Irma Normaningsih. Panggilan sehari-harinya adalah Irma. Selain mengajar di SMP Budi Murni, praktis kesibukan Sumarsih sejak tahun 1977-1982 adalah mengu-rus keluarga dan merawat anak-anaknya. Tak ayal, kehadiran Wawan dan Irma telah memberikan semangat dan harapan hidup keluarga Sumarsih. Kehidu-pan itu bertambah lengkap ketika ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal DPR-RI. Sedangkan Arief Priyadi bekerja
sebagai peneliti di CSIS yang saat itu dianggap menjadi “Think-Thank”-nya Orde Baru7.
Mereka lalu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katholik. Harapan-nya, selain bisa mendalami agama, Sumarsih juga bisa lebih banyak belajar dari kedua anaknya mengenai pendalaman Katholik Wawan dan Irma, sejak TK hingga SMP belajar di sekolah Bunda Hati Kudus, Jelambar Jakarta Barat. Setelah dianggap cukup dewasa untuk memilih, Sumarsih dan Arief mem-berikan kebebasan untuk anak-anaknya mengenai sekolah menengah atas yang diiinginkan. Wawan pun melanjutkan ke SMA Van Lith Pangudi Luhur di Muntilan, dan diikuti dengan kuliah di Universitas Atma Jaya Jakarta. Se-dangkan Irma, selepas dari SMU Negeri 65 Jakarta Barat, melanjutkan kuliah jurusan ekonomi D3 di Universitas Indonesia.
Betapa senangnya Sumarsih ketika melihat anak-anaknya bertumbuh men-jadi dewasa, terutama keduanya tumbuh menmen-jadi remaja yang tidak berma-salah. Baginya inilah puncak kebahagian yang sudah diraih selama hidup berumahtangga. Terlebih lagi, ia bersama suami dan anak-anaknya, sejak ta-hun 1986 sudah menempati rumah dinas Sekretariat Jenderal DPR-RI. Den-gan demikian, tidak ada “satu kekuranDen-gan apapun” sebagai sebuah keluar-ga. Hari-hari yang mereka lalui pun penuh suka dan duka yang merupakan bagian dinamika kehidupan bersama. Sebagai sebuah keluarga, Sumarsih dan Arief mencoba saling mengisi kekosongan di antara mereka dan anak-anaknya. Mereka saling berbagi tugas dalam pekerjaan rumah. Salah satu con-toh, apabila tidak ada pembantu, Wawan sering mencuci perabotan rumah tangga, dan Irma menyapu halaman dan mengepel lantai rumah. Sedangkan Sumarsih biasanya memasak untuk makan siang dan malam selepas pulang dari kantor.
Satu kebiasaan yang dipegang dalam keluarga ini adalah makan malam bers-ama. Selain mengeratkan suasana keluarga, makan malam menjadi ruang ber-bagi pengalaman, pertukaran pemikiran, dan informasi di keluarga Sumarsih. Selain itu, pada momen makan bersama inilah mereka bisa saling bercerita mengenai aktivitas seharian yang mereka lalui. Makan malam pun menjadi agenda wajib yang harus mereka penuhi, sesibuk apapun aktivitas yang dimil-iki. Kedekatan personal antara individu dengan yang lain pun menjadi sangat kental dalam keluarga itu. Memang, kedekatan Wawan dengan Sang Ayah, tidak sedekat dengan ibunya. Selain bisa memanjakan diri sebagai seorang anak, dengan Sang ibu, Wawan bisa menceritakan pelbagai hal yang meng-ganjal pikirannya. Karena itu, Sumarsih hampir tahu persis aktivitas
kan yang dijalankan anaknya dan juga beban pikiran yang kerap melandanya. 8
II. Jum’at Hitam
Pada hari Jumat, 13 November 1998, sekitar jam 16.00 Wawan menelepon ke rumah. Kebetulan yang berada di rumah saat itu hanyalah Arief, suami Sumar-sih. “Bapak kok sudah pulang?” tanya Wawan dengan penuh penasaran. “Iya, kat-anya ada himbauan dari Pangab Wiranto agar kantor-kantor segera memulangkan para karyawannya dan segera tutup” ujar Arief. Dengan naluriah seorang ayah, Arief pun meminta kepada Wawan agar segera pulang saja ke rumah, “ini berarti dalam keadaan gawat, kamu pulang saja”. Namun, permintaan itu tidak dapat di-penuhi Wawan mengingat kondisi tidak memungkinkan dirinya untuk segera pulang, “pengennya sih pulang, tapi bagaimana mungkin? Suasananya seperti perang! Jangankan untuk pakai motor, jalan kaki saja susah!. Arief mengiyakan pemakluman yang dijelaskan oleh anaknya dengan tidak lupa sambil menas-ehatinya, “Ya sudah, enggak pulang enggak apa-apa. Tapi hati-hati dan jaga diri baik-baik yah”. “Ya, Pak. Saya enggak pernah keluar kampus kok. Sudah ya Pak, daaagh!” jawab Wawan9.
Sebelumnya, Wawan telah menelepon Ibunya mengenai kondisi yang terjadi di sekitar lokasi Universitas Atmajaya. Namun saat itu sang ibu sedang dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumah pada jam 14.30. Alasan Sumarsih untuk lekas pulang adalah karena suasana kantor sudah tidak tenang. Sebagian besar anggota DPR mengatakan bahwa ada himbauan dari Jenderal Wiranto agar kantor-kantor tutup jam 15.00 WIB. Jalan-jalan di luar gedung DPR/MPR pun diblokir. Sesampainya di rumah pada jam 16.30 WIB, ia menonton berita yang disiarkan oleh stasiun televisi Indosiar. Saat menonton itulah ia melihat bagaimana mahasiswa tiba-tiba tertembak saat melakukan demonstrasi di ka-wasan Semanggi. Melihat itu ia menjerit, “Aduh ada yang kena!”. Pada jam 17.00 ia memindahkan channel televisi dari Indosiar menuju TPI.
Tiba-tiba telepon berdering. Ia mengangkat telepon itu. “Tante saya Ivon temannya Wawan. Wawan ada di mana?” tanya seorang perempuan dari gagang telepon itu. “Wawan di kampus, ada yang kena ya?” ujar Sumarsih penuh tanya. “Tenang saja Tante, Ivon akan mencari Wawan. Nanti Ivon telepon lagi ya...!”. Selang lima menit kemudian telepon kembali berdering. Sumarsih kembali
mengang-8 Sumarsih, “Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan”, dalam Melawan Pengingkaran, Jakarta: KontraS, 2006, hal. 69, Wawancara dengan Sumarsih, Keluarga Korban Peristiwa Semanggi I, 15 Desember 2008.
kat telepon itu. Dengan nada sedih suara telepon itu mengabarkan kepadanya, “Ibu Sumarsih, Wawan tertembak”, ujar Romo Sandiyawan Sumardi SJ. Belum se-lesai Romo Sandiyawan berbicara, Sumarsih berteriak histeris, “ada apa Romo? Wawan kenapa”. Saat itulah gagang telepon direbut Arief, sang suami, “Ya Romo, ada apa? Saya bapaknya Wawan”. “Ada berita buruk Pak. Wawan kena tembak. Bapak saya mohon segera ke Rumah Sakit Jakarta”. “Dengan mobil atau sepeda motor saja Romo?”. “Rumah bapak di mana? Kami jemput saja”. “Tidak usah Romo saya angkat datang sendiri” jawab Arief dengan wajah cemas. Sumarsih, dengan tergesa-gesa, langsung mencari kontak mobil, mengambil tas dan ganti baju sambil menangis membayangkan bagaimana nasib anak kesayangannya. Sumarsih dan Arief bergegas berangkat menuju Rumah Sakit Meruya Selatan. Mereka mampir sejenak di rumah adik iparnya yang tidak jauh dari rumah mereka. Dengan harapan, adik iparnya, yang merupakan anggota kepolisian, dapat
di-andalkan ketika nanti kondisi fisik Arief kelelahan. Sepanjang perjalanan, den -gan mobil yang disetir oleh adik iparnya Arief, Sumarsih tidak putus-putusnya berdoa rosario, “Tuhan Yesus, lindungilah Wawan, selamatkanlah anak saya, Bunda Maria tolonglah anak saya”. Dengan perasaan yang hampir putus asa membay-angkan kondisi anaknya, tiba-tiba ia berucap, “Selamat jalan Wan”. Ia tersentak dengan ucapannya sendiri. Ketika mulai sadar apa yang sedang diucapkan, ia berteriak, “tidak, tidak!!!”10.
Setelah mobil keluar dari jalan tol, mereka pun menuju jalan S. Parman. Na-mun baru sampai lampu merah yang berada di Tomang Raya, kendaraan mereka dihentikan oleh aparat keamanan. Mereka meminta bantuan kepada aparat keamanan itu agar mengawalnya menuju Semanggi dan Slipi. Alih-alih dibantu, mereka malah dibentak dan diusir, “Segera tinggalkan tempat ini, nanti mengundang massa, silahkan ibu cari jalan lain saja. Ibu jangan memanc-ing perhatian orang!!”. Padahal, Sumarsih sudah menunjukkan KTP dan kartu pengenal pegawai DPR-RI. Sumarsih yang saat itu keluar mobil bernegosiasi dengan aparat keamanan pun kembali ke mobil sambil menangis meratapi na-sib anaknya. Tidak putus-putusnya doa yang diucapkan agar anaknya tetap selamat hingga ia tidak sadar jalan apa saja yang sudah dilaluinya11.
Ketika mobil sampai di ujung jalan masuk pintu Rumah Sakit yang berada di jalan Sudirman, ia mendengar suara adzan magrib dan suasana yang begitu ka-otik. Kondisi itu membuat Sumarsih ingin turun dari kendaraan. Niat itu dice-gah oleh adiknya. Ia, dalam kendaraan, melihat bagaimana kerumunan orang berlari sekencang-kenyangnya dengan wajah penuh rasa takut dan lalu-lalang kendaraan yang melawan arah. Di jalan raya depan kampus Atma Jaya terli-hat sinar berwarna kemerah-merahan dengan kilat-kilat api yang meluncur di udara. Akibatnya, jalan aspal menjadi basah, meskipun saat itu tidak turun
jan. Saat itulah sebenarnya, aparat keamanan sedang menyemprotkan gas air mata dan juga air kimia kepada para mahasiswa yang melakukan demonstrasi.
Sesampainya di Rumah Sakit Jakarta, Sumarsih dan Arief bergegas menuju pintu utama. Sementara adiknya mencari tempat parkir. Sumarsih, tanpa pikir panjang, bertanya kepada para mahasiswa yang sedang duduk di halaman, “di mana Wawan, mahasiswa Atmajaya yang ditembak”. Saat itu Sumarsih mengalami kecemasan yang luar biasa hingga ia tidak menghiraukan keberadaan suamin-ya sendiri. Setibansuamin-ya di dalam rumah sakit, ia diinformasikan bahwa Wawan berada di basement. Sesaat mendengarkan kata basement, pikiran Sumarsih langsung terbayang pada kamar jenazah. Ia semakin tidak kuat membayang-kan itu. Tidak terasa, air mata keluar lagi dari matanya. Ternyata, di basement sudah banyak orang berkerumun, terutama mahasiswa-mahasiswi. Ia lalu di-peluk oleh beberapa mahasiswa itu, dan memintanya agar tabah menghadapi. Ia malah teriak meronta, “di mana Wawan, di mana Wawan anak saya”. Kamar pintu jenazah pun dibuka. Ia melihat Wawan berada di keranda terbuka. Tang-anya dilipat. Dua jempol kaki kanan dan kiri diikat kain putih. Wawan bercela-na pendek dengan mengebercela-nakan kaos putih. Sumarsih meraba seluruh badan anaknya. Ia memegang perut anaknya yang tipis, “Wan, kamu lapar?....Oh, Wan, kamu ditembak”. Dari kaosnya itu terlihat lubang yang disundutkan rokok yang disekelilingnya berwarna agak cokelat kemerahan. Seketika itu juga ia berdoa tanpa peduli apa yang keluar dari mulutnya12.
Selepas berdoa, ia segera menuju bagian administrasi untuk membawa pu-lang Wawan. Di depan pintu jenazah ia bertemu dengan Romo Al. Andang. Ia mengeluh, “Romo bagaimana sih cara berdoa yang benar? Semua doa saya dika-bulkan. Tapi, untuk keselamatan Wawan mengapa Tuhan tidak mengadika-bulkan. Tolong Mo, ajarin bagaimana berdoa yang benar”. Ternyata, administrasi keuangan untuk penanganan jenazah Wawan sudah diurus oleh Ita F. Nadia, Senior TruK. Saat ingin kembali ke kamar jenazah ia mendapatkan informasi bahwa Wawan akan diotopsi. Awalnya ia menolak. Setelah dikonsultasikan dengan Romo Andang, ia membolehkan. Wawan pun dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan mengendarai mobil ambulan. Dalam mobil itu Arief, Sumarsih, Kustini adiknya, Ita F. Nadia, dan seseorang yang belum dikenalnya. Saat mobil am-bulan melewati Universitas Atmajaya itu suasana masih mencekam. Tiba-tiba, suara tembakan mengenai badan mobil mereka. “Tundukan kepala, tundukan ke-pala, mobil kita ditembaki” teriak Ita F. Nadia13.
Sesampainya di RSCM Romo Andang, Romo A. Susilo Wijoyo Pr, dan seorang dokter yang diutus oleh TruK bergantian menunggu otopsi Wawan. Ita F Nadia sibuk menelepon guna mempersiapkan segala keperluan Wawan. Saat itulah
Sumarsih memintanya agar Wawan dicarikan peti, baju, dan apa saja yang ter-kait dengan pemakaman yang paling bagus. Sebenarnya, ia ingin memgam-bil pakaian Wawan di rumah. Namun, atas saran suami terkait dengan situasi Jakarta yang masih mencekam, ia mengurungkan niatnya. Betapa kagetnya dr Budi Sampurno, dokter yang mengotopsi Wawan. Menurutnya, Wawan ditembak oleh peluru tajam, dan baru kali ini ia melihat jenis peluru semacam itu. Sumarsih pun langsung menanyakan perihal itu kepada dokter tersebut, “kalau begitu, peluru ini canggih yah dok”. “Masalah canggihnya saya kurang tahu. Tapi baru kali ini saya melihat jenis peluru ini” ujar dokter itu keheranan. Arief sempat memegang dan mengamati peluru itu dengan seksama. Ia lalu memperlihatkan peluru itu kepada Sumarsih, tapi ditolaknya. Sumarsih dan Arif pun meminta kepada dr Budi Sampurno agar menyimpan peluru itu baik-baik sehingga tidak direkaya. Selain itu, mereka juga meminta agar dokter itu memberikan keterangan sama terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan, jika satu saat dibutuhkan untuk bahan pengadilan14.
Pada jam 24.30 jenazah Wawan telah diantarkan ke rumahnya. Di rumah itu telah banyak orang yang menunggu sejak sore. Alih-alih merasakan lelah, haus, dan lapar, pada malam terakhir bersama Wawan itu Sumarsih tetap se-tia menemani jenazah Wawan tanpa tidur sedikit pun. Malam itu, bersama
Setya Rini, teman sekantornya, ia diminta untuk merenung dan mereflesikan
diri sepanjang hidup yang pernah dilalui. “Wawan adalah sekuntum bunga yang belum sempat mekar. Orang-orang seperti Wawan inilah yang selalu diincar untuk dihabisi. Mbak Marsih jangan marah kepada Tuhan dan jangan gila” ujar Setya Rini meyakinkannya. Pada saat itu juga ia berdoa kepada Tuhan Yesus agar mau menerima persembahan Wawan semasa hidupnya dan juga untuk penembak anaknya agar ia bisa kembali menjadi manusia yang mengenal cinta kasih Tu-han15.
Pada sekitar jam 06.00 wartawan RCTI datang untuk mewawancarai Sumar-sih dan suaminya. Namun, hanya Arief saja yang mau menerima wawancara, sedangkan Sumarsih masih belum kuat untuk berbicara terkait dengan keper-gian anaknya. Wartawan itu meminta tanggapan Arief mengenai ucapan Pan-glima ABRI Jenderal Wiranto yang mengatakan bahwa aparat bersenjata en-tah itu TNI dan Polri yang bertugas di sekitar Semanggi itu tidak dipersenjatai dengan peluru tajam. Ia sungguh kesal dengan pernyataan itu, “Lalu, peluru yang mengenai korban hingga tewas itu punya siapa? Pemulung? Ya, dia ingin menghindar, dia ingin cuci tangan, dia ingin lari dari tanggung jawab. Dia me-mang pintar bersilat lidah dan bersilat sikap. Dia selalu putar otak untuk men-cari kambing hitam dan untuk membentengi diri”. Setelah itu, kerabat yang
14 Ibid
dikenal ataupun tidak datang silih berganti16.
Namun, pada saat rombongan polisi datang Sumarsi menjadi naik pitam. Ia begitu marah melihat mereka. Seketika itu pula ia langsung mengusir mereka. Baginya korps polisi yang mengakibatkan anaknya meninggal. Sementara pada jam 10.00 pagi, saat Adi Sumarnoto, Seksi Liturgi Lingkungan, akan menyiap-kan doa pemberangkatan Wawan ke gereja Maria Kusuma Karmel (MKK), tiba-tiba Romo Susilo Wijoyo datang dan berkenan memimpinnya. Betapa terkejut-nya Sumarsih. Ia melihat hampir di sepanjang jalan, dari rumah menuju gereja, banyak iring-iringan manusia mengantarkan Wawan. Di dalam hingga di hala-man gereja ribuan orang, baik Katholik maupun pemeluk agama yang lainnya, ribuan orang berkumpul mengantarkan kepergian Wawan. Dengan diiringi lagi Gugur Bunga, jenazah Wawan dibawa masuk ke dalam gereja dan diletak-kan di depan altar. Paduan suara pun mengiringi Misa yang khidmat itu. Misa Requirem diantarkan oleh 11 pastor, dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta Mgr. Julius Kardinal Daarmatmadja. Mereka mengenakan jubah berwarna merah se-bagai lambang tanda kemenangan17.
III. Mengumpulkan Derita Ingatan
Hidup ini seperti perahu yang berlayar di tengah samudera. Sejenak perahu yang saya tumpangi berlayar dengan tenang, kemudian tiba-tiba diguncang bajak laut yang ganas. Perahu itu karam dan kandas didasar laut yang curam. Saya menggelepar dari himpitan batu karang. Tak berdaya menahan jiwa yang terluka. Malapetaka itu mengingatkan nasehat kakek-nenek bahwa dalam hidup ada yang lebih berkuasa. Sang Hyang Widhi: Pencipta Langit dan Bumi, Yang Maha Segalanya; yang selalu
meleng-kapi segala kekurangan dan keterbatasan umat-Nya. Ketika lelah, DIA memberikan kekuatan. Ketika dihimpit derita, DIA memberi penghiburan. Ketika putus asa, DIA memberi pengharapan. 18
Ada dua hal yang didapatkan jika menelisik ungkapan Sumarsih di atas. Satu sisi ungkapan itu menunjukkan satu kepasrahan Sumarsih atas apa yang me-nimpa keluarganya dengan kehilangan anaknya. Di sisi lain, hal itu merupak-an satu harapmerupak-an agar Tuhmerupak-an memberikmerupak-an keadilmerupak-an untuk diri, keluarga, dmerupak-an anaknya. Tarik-menarik kondisi inilah yang menyebabkan ia berdiri di antara dua kutub, antara ingin melupakan atas peristiwa yang menimpa anaknya, dan juga kerinduan keadilan yang diimpikannya. Akhirnya ia memilih cara
16 Arief Priyadi, “Wawan, Tragedi Demi Tragedi, hal.76-77.
17 Sumarsih, Kasih Ibu Dipenggal Peluru, Dokumentasi Pribadi, tidak terbitkan, tanpa tanggal dan tahun, hal.7; Sumarsih, “Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan”, hal. 82-83.
untuk berdiri di tengah-tengah, yaitu menjauhkan diri dari komunitas dan ling kungan di mana ia bekerja dan bersosialisasi. Selain merasa telah gagal untuk membangun keluarga, ia, sebagai seorang ibu, merasa masa depannya suram dan menakutkan. Ia berencana untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Berita pengunduran dirinya menyebar di kantor. Atas saran beberapa mantan anggota DPR-RI dan juga teman-teman kantornya, ia pun urung mengundur-kan diri. Ia mengambil cuti besar selama 3 bulan.
Sejak itu, hidup Sumarsih menjadi berubah. Berhari-hari ia tidak dapat me ninggalkan ruang tamu, tempat Wawan diistirahatkan sementara. Ia sering duduk di pojok selama berjam-jam di dekat jendela ruang tamu itu sambil mengikuti dan menunggu perkembangan terbaru berita penembakan anaknya dari Kompas. Ia selama berbulan-bulan sering tidur di lantai dan gudang. Ia selalu berdoa setiap hari dengan linangan air mata yang terus membasahi; se-tiap bangun pagi diawali dengan membaca kitab suci dan berdoa, sekitar jam 07.30 ia pergi berdoa ke makam Wawan, saat siang datang pada jam 12.00 ti-dak lupa ia berdoa Rosario, pada jam 17.00 berdoa dengan mendaraskan Litani Nama Yesus yang tersuci, Litani Hati Yesus yang Mahakudus, dan Litani Santa Perawan maria, menjelang tidur ia juga melanjutkan doa dan terkadang me-nyanyikan kidung ketuhanan hingga jam 24.00, setiap kali terbangun tiba-tiba ia berdoa apa saja sesuai dengan keinginannya. Doa-doa itu tidak pernah putus ia panjatkan sebagai bentuk pelepasan amarah mengenai kepergian dan rasa kehilangan anaknya mendalam.19
Selama berminggu-minggu pula ia tidak merasa lapar. Namun saat lapar itu datang, ia tetap tidak bisa menelan nasi yang dikunyahnya. Semakin kuat ia mengunyah nasi itu untuk ditelan oleh kerongkongannya semakin kuat pula lubang itu menolak butiran nasi untuk masuk. Ia merasa lehernya terasa diikat ketika akan memakan nasi. Sejak itu, bahkan kini, ia berhenti untuk makan nasi, dan menjadikan nasi sebagai pantangan. Ia juga kerap berpuasa setiap hari Kamis, hari Jumat yang merupakan hari penembakan Wawan, dan juga hari Sabtu yang merupakan hari penguburan Wawan. Memang cara berpuasa Sumarsih berbeda dengan puasa yang selama ini dipraktikan oleh umat Islam. Laku puasa yang dilakukan olehnya adalah sekedar menahan lapar sampai jam-jam tertentu. Misalkan puasa sampai jam 17.00 atau pun sampai 18.00. Jika mau, ia bisa puasa seharian penuh hingga keesokan harinya. Akibat kelabilan ini membuat ia kerap bertengkar dengan Arief, sang suami, terkait dengan si-kapnya yang menutup diri kepada siapapun.
Praktis sejak saat itu kehidupan rumah tangga dipegang Arief dan Irma, adiknya Wawan. Di sini, Arief menjadi ayah sekaligus ibu untuk Irma dan juga
Sumarsih tentunya. Mulai dari menyapu, memasak, hingga mencukupi kebu-tuhan rumah tangga. Betapa tabahnya Arief. Ia begitu memahami perubahan drastis yang dialami isterinya. Melihat kondisi seperti itu, kepergian Wawan disikapi berbeda olehnya. Hal pertama yang dilakukan selepas Wawan diku-burkan adalah dengan mengirimkan surat-surat ucapan terima kasih kepada para aktivis yang selama ini memperjuangkan keadilan serta membantu kasus Wawan dan juga teman-teman sekampus dan seperjuangan dengan Wawan. Ia sadar bahwa satu saat akan berjuang dalam kesendirian. Teman kampus dan seperjuangan anaknya satu saat akan diwisuda, bekerja, dan membangun ke-hidupan sendiri sehingga kemungkinan besar mereka tidak ada waktu untuk menuntut keadilan. Sementara pegiat kemanusiaan akan disibukkan dengan kejahatan-kejahatan baru yang diciptakan elit politik dan sisa rejim Orde Baru untuk melupakan kejahatan masa lalu yang pernah dilakukannya. 20
Beban hidup yang dialami oleh keluarga Sumarsih agak tertangguhkan. Selepas Wawan dikuburkan, banyak dari kawan-kawan TRuK di mana ia
beraktivi-tas pada saat-saat tertentu mengadakan ibadat sabda dan refleksi di makam
Wawan. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke rumah Sumarsih dengan suasana hangat. Sapaan para pastor, frater meneguhkan kembali iman Sumarsih dan menguatkan jiwanya untuk bangkit dari masalah yang menim-pa. Selain itu, para mahasiswa dari pelbagai kampus di Jakarta, pegiat HAM KontraS selalu datang menemani Sumarsih, Irma, dan juga Arief hingga larut malam.
Dukungan juga datang dari keluarga terdekat Sumarsih. Ria, keponakan Wawan yang duduk di Tingkat Kanak-kanan (TK) St. Andreas selalu mencari-kan buku Satu Perjamuan Satu Jemaat untuknya. Kustini, adik Sumarsih, sela-lu memberikan buku Saat Teduh. Adik sepupunya, Menuk, sering berjam-jam membacakan Kitab Suci melalui pesawat telepon. Ibu Titiek, seorang pendeta yang juga wartawan majalah D&R sering menelepon memberikan rangkaian kata-kata doa dan kutipan ayat-ayat Kitab Suci. Di antaranya adalah Surat Pau-lus kepada Jemaat di Filipi 4:13, yang berbunyi, “Segala perkara dapat kutang-gung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”. Selain itu, wartawan dalam dan luar negeri banyak yang berkunjung ke rumah, salah satunya adalah wartawan Belanda. Menurut wartawan Belanda itu, tragedi 13 November 1998 adalah 10 kali lipat lebih besar bila dibandingkan dengan penembakkan ma-hasiswa Trisakti. Saat itu pihak aparat militer begitu kejam dan sangat brutal.
Satu persatu, dari pelbagai kunjungan sahabat, kerabat, dan juga yang memi-liki simpati dengan penembakan Wawan ke rumah. Dari sinilah Sumarsih mu-lai dapat menghimpun cerita bagaimana sebenarnya peristiwa penembakkan Wawan dan pesan apa saja telah disampaikan Wawan sebelum ia meninggal.
Menurut Ita F Nadia, senior TRuK, saat memberikan kesaksian dalam 40 hari meninggalnya Wawan, sebelum ditembak, bersama dengan 6 orang kawannya mengangkat dan menyemprotkan air hidran di depan kampus Atmajaya untuk menetralisir gas air mata. Ketika itu, berondongan peluru aparat militer men-garah ke kampus Atmajaya. Akibatnya, banyak korban yang berjatuhan. Ada tiga orang yang melompat kemudian tertembak di kaki, yang membungkuk terkena pundaknya. Saat ditembak, Wawan sedang dalam posisi mengangkat korban yang terkena tembakan di dadanya, dan dilehernya masih menggan-tung tas berisi obat-obatan.21
Di akhir hidupnya, ia hanya mengatakan, “haus, panas, haus...”. Kesaksian itu kemudian dikuatkan oleh Dian, wartawan Radio pada 12 April 2000, “Ibu, saya baru siap menemui Ibu. Karena saya tahu Ibu sangat mencintai Wawan. Sebelum ditembak ia ada di samping saya. Pada saat itu militer masuk ke dalam kampus. Di halaman kampus ada korban yang jatuh. Wawan, melihat hal itu, lalu meminta ijin kepada salah seorang aparat militer, “Pak, itu ada kor-ban. Boleh ditolong atau tidak?”. “Boleh, boleh...Silahkan” ujar militer itu. Wawan lalu melambaikan bendera putih sebagai tanda pihak netral yang akan me-nolong korban. Alih-alih diberikan ruang untuknya mengobati dan meme-nolong orang yang tertembak itu, ia malah ditembak juga dengan peluru panas yang mengenai dadanya.
Namun, dukungan itu bukan berarti melunakkan hati Sumarsih untuk membi-arkan yang lalu tetap berlalu. Ia tetap berusaha merelakan kepergian Wawan, tapi ia tidak merelakan bila pembunuh dari anaknya itu tidak diungkapkan. Ini tercermin dari sikapnya ketika pada hari Senin, 1 Desember 1998, 4 orang petu-gas Palang Merah Indonesia datang ke rumah mengantarkan santunan dari Negara berupa satu lembar cek senilai Rp.5.000.000,-, dengan lampiran surat ucapan belasungkawa dari Menteri Sosial, Yustika Baharsyah. Saat itu Sumar-sih sedang sendirian di rumah, Arief berada di kantor, sedangkan Irma kuliah. Cek itu ia terima. Tapi, ia, secara lisan dan ditulis di bawah tanda terima itu, meminta bantuan kepada empat orang PMI untuk memberikan sumbangan itu kepada orang yang menembak anaknya. Jika penembak itu tidak ditemukan, cek itu bisa diberikan kepada aparat militer yang bertugas pada hari Jumat Sore, 13 November 1998. Bila sulit ditemukan lagi, agar itu diberikan kepada 163 prajurit yang dikenakan sanksi. 22
Ia menangis sambil membenturkan kepala beberapa kali ke tembok setelah petugas PMI itu pergi. Ia merasa sudah hilang kepercayaannya kepada semua orang. Ia membatin bahwa tidak mungkin bantuan itu akan disampaikan ses-uai dengan permintaannya. Hanya menggantungkan doa kepada-Nya yang
dapat membuat tenang dan mengerti apa kiranya yang harus dilakukan. Ia lalu menelepon berkali-kali ke Departemen Sosial untuk bisa berbicara den-gan Ibu menteri, tapi tidak berhasil. Ia tidak putus asa. Ia menelepon dr. Ida Yusi Dahlan, Wakil Ketua Korbid Kesra Fraksi Golkar DPR-RI, pimpinan yang ia menjadi sekretarisnya di kantor. Ida Yusi Dahlan lalu membuatkan konsep surat untuk dikirim kepada Ibu Menteri Sosial. Namun, berhari-hari surat itu tidak mendapatkan respon. Atas saran Marlini, wartawan Femina, Sumarsih membuat surat terbuka pada rubrik surat pembaca di media massa. Ternyata cara itu dampaknya luar biasa. Setelah surat terbuka itu dimuat oleh beberapa media massa, beberapa minggu kemudian, teman Sumarsih sekantor memberi-tahukan bahwa keberanian mengembalikan santunan negara itu mendapatkan pujian beberapa anggota DPR-RI. Pengembalian santunan itu diangkat kem-bali dalam khotbah Romo Sandi dalam Misa di Jawa Timur.23
IV. Kasih Ibu Sepanjang Perlawanan
Di hadapan Tuhan saya bangga atas apa yang telah dikerjakan oleh anak saya. Tapi sebagai manusia saya tidak rela anak saya dibunuh. Dengan terbunuhnya anak saya itu terkait langsung dengan harga diri saya sebagai manusia. Hal itulah yang mendorong saya untuk tidak diam. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya diberikan kekuatan yang berlimpah dari-Nya. Sebab itu, saya kuat bertahan dalam melakukan tuntutan di dalam perjuangan, kuat dalam menghadapi masalah di dunia ini. Siapapun manusia itu tentu tidak akan tenang bila anaknya dibunuh. Jika saat ini banyak orang berkeinginan untuk melupakan masa lalu dan lebih baik menatap masa depan, tapi bagi saya masa lalu harus diselesaikan. Masa lalu adalah pijakan masa depan.24
Pada hari Senin, 12 Februari 1999 Sumarsih mulai masuk ke kantor. Ketika sam-pai kantor dan ingin menaiki gedung DPR di lantai 6 dengan menggunakan lift, badannya terasa goyah dan sempoyongan. Tidak terasa air mata mengalir dari matanya. Ia menyempatkan diri untuk bersandar tembok, istirahat sejenak sambil terus menangis. Ada teman kantor yang melihatnya. Ia lalu dipapah untuk menuju ruangan kerjanya. Alih-alih dapat bekerja dengan maksimal, di ruangan kerja itu pikirannya tetap kosong. Ia tidak dapat membaca surat-surat undangan anggota DPRI-RI. Semakin dicoba untuk membacanya, semakin dia tidak mampu menangkap pesan isi undangan itu. Perlu waktu berhari-hari ia harus menyesuaikan hidup tanpa Wawan anaknya dalam bekerja di kantor. Ia, terkadang, menyesali, mengapa begitu taat, patuh, dan loyal kepada penguasa Negara yang telah merenggut kebahagian hidup keluarganya.
Ia, saat kondisinya mulai agak stabil, pada hari Jumat pertama bulan Mei 1999
mengikuti misa perayaan Paskah karyawan-karyawati kawasan Slipi yang di pimpin oleh Romo Sandy di Gereja Salvator, Jakarta Barat. Selesai Misa, ia men-emui Romo Sandy dan mengkonsultasikan keinginannnya untuk berdemon-strasi aksi damai di bundaran Hotel Indonesia. Informasi itu ia dapatkan dari berita harian Kompas. Romo Sandy menyetujuinya, “Ya, nanti ikut Ibu Karli-na saja”. Atas sarannya juga, ia menghubungi KalyaKarli-na Mitra untuk ikut ber-demonstrasi. Di lembaga inilah ia melihat orang pada lalu-lalang mempersiap-kan peralatan untuk berdemonstrasi, salah satunya adalah sendok. Ia sangat heran, mengapa sendok dibutuhkan untuk itu. “Ibu Ita, kita demonstrasi bawa sendok untuk apa?”. “Ibu Sumarsih, nanti kalau ingin menyebrang jalan, dan tidak di-carikan jalan oleh Polisi, kita tinggal membunyikan saja dua sendok ini, ting ting ting, agar diberikan jalan”, jawab Ita F Nadia mencoba meyakinkannya.
Pada hari Jumat, Sumarsih pun datang ke bundaran Hotel Indonesia (HI). Di sekitar bundaran itu, polisi sudah berjaga-jaga dengan senjata, tameng, pen-tungan, panser, dan truk tronton. Ia lalu diperkenalkan dengan Shinta Nuri-yah Abdurrahman Wahid, Lies Markus, dan para aktivis perempuan lainnya. Agendanya saat itu pembacaan pernyataan, berjalan mengelilingi bundaran HI dengan membawa spanduk dan poster sambil bernyanyi lagu Ibu Pertiwi dan lagu-lagu perjuangan. Dalam demonstrasi itu, ia mengenakan kerudung dan kaca mata hitam agar tidak diketahui orang. Ini karena, sebagai seorang ibu yang diberi tugas untuk mengantarkan anaknya selama hidupnya di dunia tiba-tiba ditembak. Ia merasa malu dan gagal sebagai seorang ibu. Pada hari Jumat berikutnya, ia ditugaskan membaca pernyataan untuk solidaritas ma-syarakat Timor-timur yang sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan kehormatannya akibat tindakan militer melakukan tindakan kejahatan kema-nusiaan.
Pertemuan untuk melakukan konsolidasi internal dan juga penguatan solidari-tas kalangan korban dan keluarga korban dalam mempersiapkan peringatan satu tahun peristiwa Mei sering diadakan di Kantor TRuK yang beralamat di jalan Arus Dalam, Jakarta Timur. Dalam rapat itu diputuskan untuk melaku-kan unjuk rasa ke Istana menemui presiden B.J Habibie agar mempertanggung-jawabkan peristiwa Mei 1998 dan peristiwa Semanggi 13 November 1998 serta melakukan tabur bunga di depan kampus Atmajaya. Sebelum peringatan itu dimulai, beberapa hari sebelumnya, Sumarsih dan Arief diminta TRuK untuk menemui korban dan keluarga korban Tionghoa di daerah Cengkareng. Den-gan kehadiran mereka berdua, diharapkan dapat merinDen-gankan beban korban dan keluarga korban Tionghoa, bahkan kalau mungkin bisa ikut memperingati peristiwa Mei 1998. Saat itulah Sumarsih membatin, “Saya ini pasien, kok malah menjadi dokter”.
Dalam pertemuan itu Sumarsih mencoba membangkitkan kembali asa mereka yang putus dan membuka ruang untuk berbagi terhadap trauma yang meng-hinggapi, “bapak-bapak, ibu-ibu lahir di Indonesia, mata pencahariannya di Indonesia. Bedanya dengan saya, bapak-ibu kulitnya putih sedangkan saya hitam. Bapak-ibu mat-anya sipit, saya enggak. Supaya ibu-bapak bisa sama seperti saya, kalau mau datang dalam peringatan 12 Mei, saya menyarankan bapak-ibu memakai baju warna biru, hi-tam, ataupun coklat. Agar bapak-ibu tidak kelihatan putih sekali. Tidak begitu kelihatan matanya sipit”. Tidak disangka mereka datang dengan menggunakan beberapa angkutan Metromini.
Selain kalangan korban dan keluarga korban peristiwa Mei, dalam acara per-ingatan itu juga dihadiri dan didukung oleh pelbagai lapisan masyarakat. Pen-jagaan yang dibuat oleh TNI/Polri pun tidak kalah banyaknya. Sebagian be-sar kalangan korban dan keluarga korban membawa foto-foto keluarga yang meninggal sambil menangis. Hal itu tidak dilakukan oleh Sumarsih. Ia tidak tega memandang foto wajah anaknya. Sayang keluhan dan ratapan korban dan keluarga korban untuk memperingati peristiwa itu tidak didukung oleh aparat militer. Saat mereka ingin bergerak beberapa meter dari lapangan Mo-nas menuju Istana Merdeka sudah dihadang brikade polisi berlapis-lapis den-gan membawa tameng dan pentunden-gan. Selain itu aparat keamanan langsung memasang tanda garis polisi agar mereka tidak mendekati Istana Merdeka itu. Setelah bernegosiasi dengan alot, mereka dapat melakukan long march ke At-majaya untuk berdoa dan melakukan tabur bunga.
penuntutan keadilan, organisasi korban ini untuk memberdayakan dan men-guatkan solidaritas sesama korban, yaitu dengan mendirikan koperasi, aris-an, pengajiaris-an, dan aktivitas bermanfaat lainnya. Di sini, Sumarsih dan Arief mencari kalangan korban dan keluarga korban yang belum masuk dalam data TRuK. Namun, nama paguyuban korban itu berganti-ganti seiring dengan ter-jadinya kasus berdarah, yaitu peristiwa Semanggi II, dan tampuk kepemimpi-nan organisasi itu berpindah ke tangan Arief, mengingat Ali begitu sibuk dalam menghidup keluarganya.
Berawal dari sini, Sumarsih bersama paguyuban korban dengan didampingi Pegiat HAM Kontras dan TRuK melakukan upaya penuntutan dengan men-datangi kantor Pomdam Jaya untuk menemui Komandan Pomdam Jaya. Semula rombongan korban itu akan diterima olehnya, tapi ternyata justru diterima oleh Kabag Sidik, Kol.CPM.Ir. Wempy Happan. Mereka lalu meminta ijin untuk menunggu Komandan itu di aula, tapi tidak diperbolehkan. Mer-eka meminta ijin untuk menunggu dihalaman dan pinggiran gedung agar bisa berteduh tetap tidak boleh. Mereka malah diusir dan pintu pagar kantor itu digembok. Mereka lalu melakukan orasi di pinggir jalan dengan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dengan disiapkan dua truk tronton. Ketegangan sempat terjadi ketika ada seorang provokator masuk dalam rombongan korban dan meminta kordinator aksi untuk membubarkan diri. Sekitar jam 17.15 beberapa perwakilan korban dan keluarga korban saja yang diterima untuk melakukan audiensi oleh Komandan Pomdam Jaya, Kolonel Mungkono. Komandan itu memberikan keterangan yang standar bahwa saksi kasus Semanggi sudah cu-kup dan Pomdam tetap akan melakukan penyidikan.
Setelah itu, rombongan korban dan keluarga korban menuju Dephankam Pangab untuk melakukan penuntutan kembali. Belum sampai ke lokasi yang dituju, mereka sudah dihadang brikade polisi dengan peralatan lengkap di depan Pasar Sarinah Jalan MH.Thamrin. Satu-persatu kalangan korban dan keluarga korban serta pegiat HAM melakukan orasi. Tiba-tiba terdengar bu-nyi tembakan beruntun. Brikade polisi yang merapat itu membubarkan diri. Sumarsih kaget melihat kondisi itu. Para polisi muda datang memukuli para aktivis TRuK yang mempertahankan kunci mobil komando yang akan direbut oleh aparat polisi. Di sebelah kanan mobil, ia menyelipkan telapak tangan dip-inggang anak muda yang sedang pegang stir mobil, “ini tangan Ibu, ini tangan Ibu”. Tiba-tiba ia terlepas dari keroyokan polisi Sumarsih lalu pindah ke sebe-lah kiri mobil. Ia menarik telinga seorang polisi, “hei, ini manusia, hei kita sama-sama manusia”. Itu dilakukannya sambil menyelipkan tangan di tengah-tengah himpitan keroyokan polisi hingga menggapai dipinggangnya, “ini tangan Ibu, ini tangan Ibu. Anak muda itu itu bisa terlepas dari keroyokan tersebut.
dan juga yang dipukuli. Sebagian besar dari mereka ada yang keseleo, patah tulang, dan babak belur di tubuhnya. Dari kejauhan ia melihat Tigor,
kordina-tor lapangan aksi, dikeroyok dan dipukuli. Sumarsih secara refleks langsung
merebutnya dari kerumunan itu. Entah kenapa, para polisi muda itu pergi be-gitu saja. Ia dan Titiek, sektretaris Romo Sandy memapah Tigor yang kemu-dian roboh di tengah jalan aspal yang panas. Ia rebah dipangkuan Sumarsih. Sumarsih pun meminta bantuan, “tolong, tolong, taksi, taksi. Tigor bersuara lirih kepadanya, “Ibu, saya kena....”. Awalnya ia tidak mengira bahwa Tigor terkena t