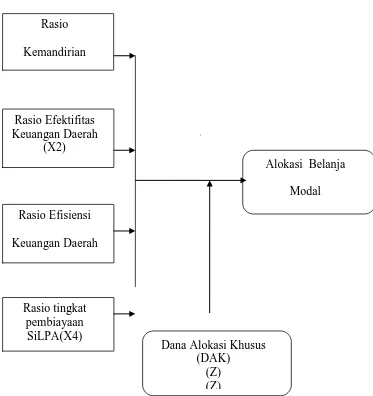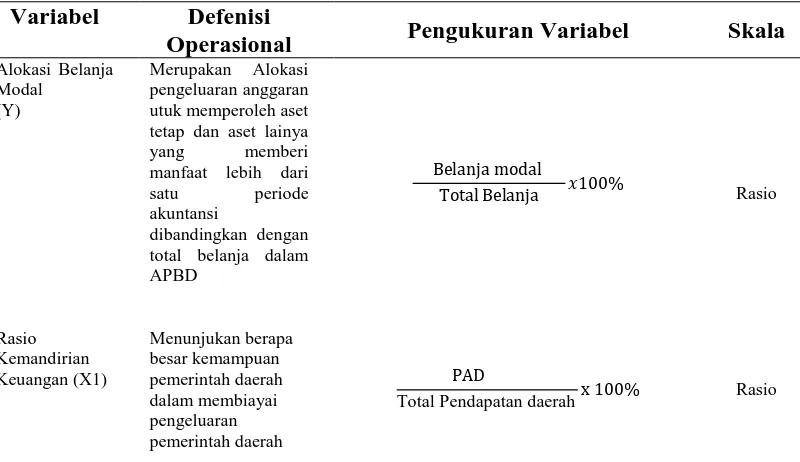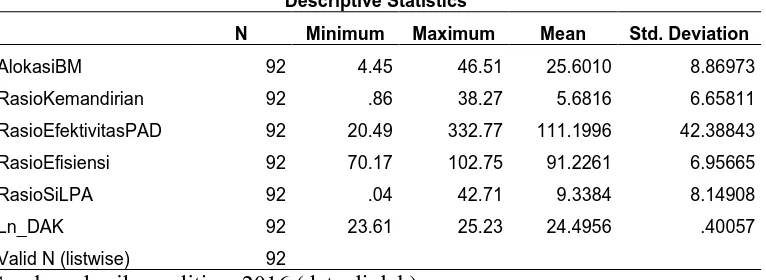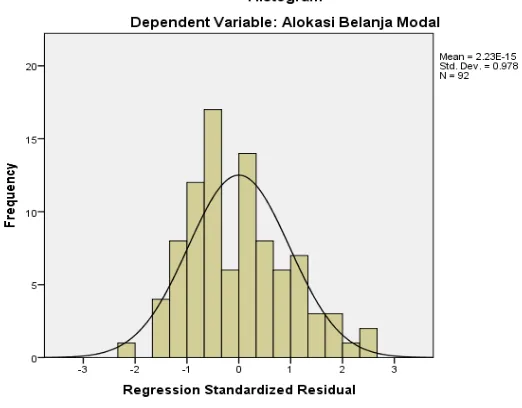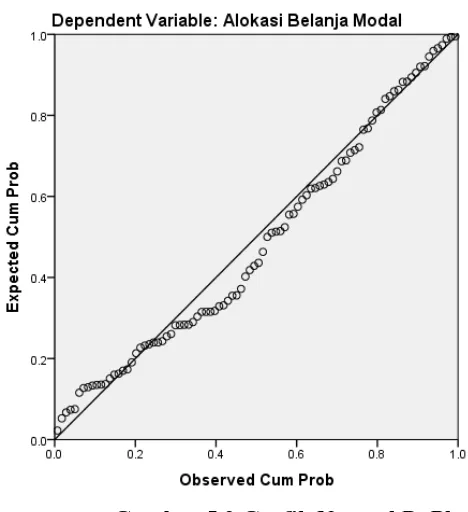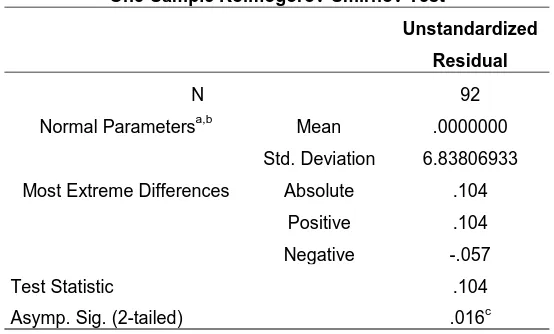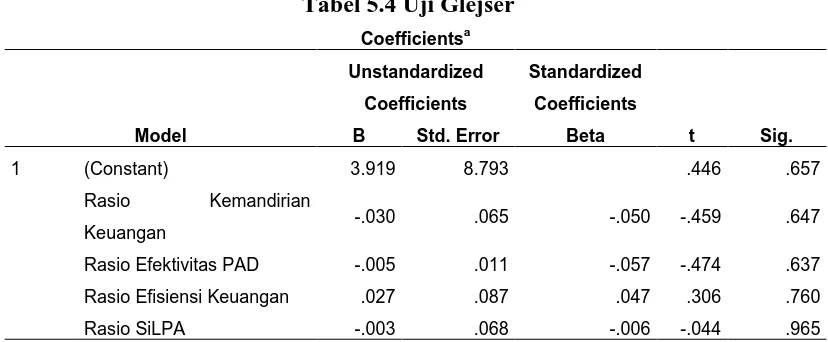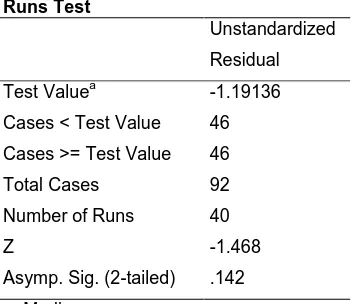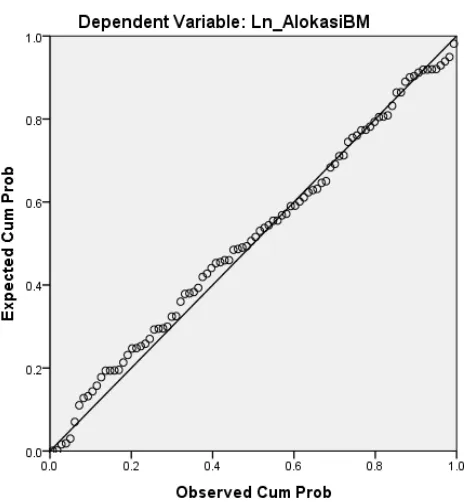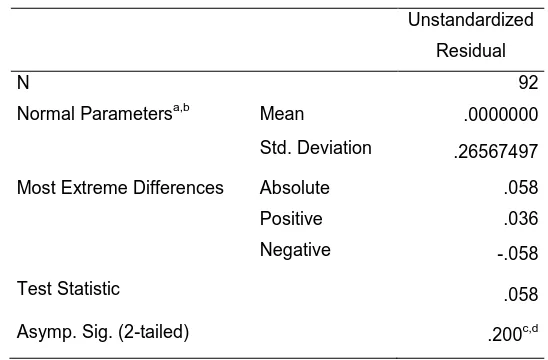BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
3.1 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual yang dikembangkan berdasarkan latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang diuji secara serempak dan
parsial. Peneliti mengindentifikasi 4 variabel independen (X) dan 1 variabel
moderating (Z) yang diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi alokasi belanja modal (Y). Model penelitian dapat dilihat pada
gambar 3.1 berikut ini:
Rasio Efektifitas Keuangan Daerah
(X2) Rasio
Kemandirian
Rasio tingkat pembiayaan
SiLPA(X4) Rasio Efisiensi
Keuangan Daerah
Alokasi Belanja
Modal
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual
Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya
pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Belanja modal
digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara
langsung dinikmati masyarakat/publik. Untuk membiayai belanja modal dibutuhkan
sumber-sumber dana yang cukup besar. Tiap kabupaten/kota memiliki jumlah dan
sumber pendanaan yang berbeda. Untuk mengoptimalkan jumlah dana untuk alokasi
belanja modal dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan
tersebut dapat diindentifikasi dengan melakukan analisis kinerja keuangan daerah.
Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator
keuangan. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio keuangan, yang
terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas,
rasio, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA
DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan
pembangunan daerah. Bila pembiayaan daerah diterima Menteri teknis dan
anggaranya ditampung dalam DAK maka tentunya daerah dapat mengalokasikan
belanja modalnya dalam jumlah yang semakin besar,. tentunya pemenuhan sarana
dan prasarana daerah semakin cepat terlaksana. Sehingga kemungkinan DAK dapat
menjadi pemoderasi hubungan Kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja
3.2 Hipotesis Penelitian
Menurut Sularso (2003), hipotesis adalah suatu pernyataan dugaan yang
logis mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang diwujudkan dalam
bentuk pernyataan yang dapat diuji. Variabel kinerja keuangan daerah yang diukur
dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi
keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA dianalisis untuk dapat
melihat masing-masing pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini, adalah :
1. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan
daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat
pembiayaan SiLPA, berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara secara serempak dan parsial.
2. DAK mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan daerah yang
diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio
efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi
BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kausal, yaitu mengindentifikasi hubungan
sebab akibat antara berbagai variabel (Erlina, 2008). Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio
kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan
daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA sebagai variabel independen; belanja
modal sebagai variabel dependen; DAK sebagai variabel moderating.
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dimulai
dari bulan Desember 2015 sampai dengan Juni 2016 seperti yang terlihat pada
Tabel Jadwal Penelitian di lampiran 1.
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota (25 Kabupaten dan 8 Kota),
dalam kurun waktu 4 tahun ( tahun 2011-2014). Metode pengambilan sampel yang
digunakan adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel.
4.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan pada peneltian ini merupakan
metode dokumentasi dimana data yang dikumpulkan oleh suatu instansi tertentu
adalah data sekunder, berupa data APBD dan laporan realisasi APBD Tahun
Anggaran 2010 s.d 2014 Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara yang
diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui
portal
(DJPK) di
Data tersebut merupakan kombinasi dari data runtut waktu (time-series) yaitu
data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu dan
secara cross-section yang dikumpulkan pada suatu titik tertentu (Lubis, 2012) yang
disebut dengan pooling data dengan combined model.
Data SiLPA menggunakan data realisasi SiLPA Tahun 2010 - 2013; data
alokasi belanja modal menggunakan data realisasi belanja modal dan total belanja
tahun 2011-2014; data DAK menggunakan data realisasi DAK tahun 2011-2014;
target PAD menggunakan data target PAD dalam data APBD tahun 2010-2013
sedangkan data untuk total pendapatan, total pengeluaran, dan total penerimaan
menggunakan data realisasi total pendapatan, realisasi total pengeluaran, dan
realisasi total penerimaan Tahun 2010-2013.
4.5 Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal (Y).
Variabel independen yang digunakan adalah kinerja keungan daerah yang yang
diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah (X1), rasio efektifitas PAD (X2),
rasio efisiensi keuangan daerah (X3), rasio tingkat pembiayaan SiLPA (X4) dan
1. Alokasi belanja modal (Y) didefinisikan sebagai alokasi pengeluaran anggaran
untuk memperoleh aset tetap dan aset lainya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi, yang dibandingkan dengan total belanja dalam APBD.
Variabel ini menggunakan skala pengukuran rasio. Alokasi belanja modal diukur
dengan formula :
Alokasi Belanja Modal = �������������������
Total belanja �100%
2. Rasio kemandirian keuangan daerah (X1) menunjukan kemampuan daerah
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan
yang diperlukan daerah. Variabel ini menggunakan skala pengukuran rasio.
Kemandirian Keuangan daerah diukur dengan formula :
Rasio kemandirian keuangan = ���
Total Pendapatan Daerah� 100%
3. Rasio efektifitas PAD (X2) menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.Variabel ini menggunakan skala
pengukuran rasio. Efektivitas PAD dapat diukur dengan :
Rasio Efektivitas = ������������
Target PAD � 100%
4. Rasio efisiensi keuangan daerah (X3) merupakan rasio yang menggambarkan
realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah.Variabel ini menggunakan
Rasio Efisiensi = ��������������������
Realisasi Penerimaan � 100%
5. Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA (X4), SiLPA didefinisikan sebagai selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.Variabel ini diukur dengan membandingkan jumlah SiLPA dengan
total belanja dan menggunakan skala pengukuran rasio.
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) (Z) didefinisikan sebagai dana yang bersumber
dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
Indikator yang digunakan pada variabel ini merupakan realisasi DAK Tahun
2011-2014 yang diubah dalam bentuk Logaritma natural (Ln).Variabel ini
menggunakan skala pengukuran rasio.
Dari uraian diatas, maka definisi operasional, pengukuran variabel serta skala
ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Defenisi
Operasional Pengukuran Variabel Skala Alokasi Belanja tetap dan aset lainya yang memberi
Rasio
Realisasi Penerimaan x 100% Rasio
Rasio tingkat
4.6 Metode Analisis Data
Untuk menganalisis, pencapaian tujuan penelitian serta pengujian hipotesis
yang diajukan, data yang yang sudah terkumpul diolah sesuai dengan kebutuhan
analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi berganda, yang bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan (hubungan)
variabel dependen bila dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen.
Untuk menguji variabel moderating dipilih menggunakan uji residual. Data
penelitian diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social
Persamaan regresi berganda ditunjukan dengan model :
Model I : Y = a+ b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+ b4 X4 + e (1)
Model II : Z = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X.3 + b4 X4 + e
| e | = a + b1 Y (2)
Keterangan :
Y adalah alokasi belanja modal
a adalah konstanta
b1 adalah koefisiensi regresi rasio kemandirian keuangan
b2 adalah koefisiensi regresi rasio efektifitas PAD
b3 adalah koefisiensi regresi rasio efisiensi keuangan daaerah
b4 adalah koefisiensi regresi rasio tingkat pembiayaan SiLPA
X1 adalah rasio kemandirian keuangan
X2 adalah rasio evektivitas PAD
X3 adalah rasio efisiensi keuangan daerah
X4 adalah rasio tingkat pembiayaan SiLPA
Z adalah Dana Alokasi Khusus (DAK)
e adalah error
4.6.1 Uji Asumsi Klasik
Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu dilakukan pengujian
asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar data dapat bermakna dan
bermanfaat. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
uji normalitas, uji multikolonieritaslinearitas, uji autokorelasi, dan uji
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian dilakukan dengan
2 cara,yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik yang digunakan
adalah uji statistik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Data dikatakan normal apabila nilai
Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2013).
2. Uji Multikolonieritaslinearitas
Uji multikolonieritaslinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel
independen (Ghozali, 2013). Pengujian multikolonieritaslinearitas dilakukan dengan
menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai yang umum
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritasleniaritas adalah nilai tolerance
≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainya. Masalah ini timbul
karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu obsevasi ke observasi
lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series)(Ghozali,
2013).Dalam penaksiran model regresi linear mengandung asumsi bahwa tidak
dilakukan dengan Run Test. Run Test sebagai bagian dari statistik non-parametrik,
dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang
tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa
residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data
residual terjadi secara random atau tidak (sistematis) (Ghazali, 2013).
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan uji Glejser. Ada dua tahapan yang
dilakukan dalam uji Glejser. Tahap pertama adalah melakukan regresi OLS dengan
menggunakan Y sebagai variabel dependen dan X1, X2, X3, X4 sebagai variabel
independen. Tahap kedua adalah dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap
variabel independen. Jika setiap variabel independen nilai signifikannya lebih besar
dari α (0,05) maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
4.6.1 Uji Hipotesis Penelitian
Uji hipotesis berupa uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau
nilai data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti (Erlina, 2008).
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji Statistik F, uji Statistik t
dan uji residual (moderating).
1. Koefesien Determinasi (R2)
Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2
yang mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).
2. Uji Statistik F
Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serempak terdahap
variabel dependen. Uji statistik F untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari
variabel independen terhadap variabel dependen bersama-sama. Menurut Ghozali
(2013) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen.
Kriteria uji :
1. Ho diterima dan Ha ditolak bila nilai sig >α (0,05) artinya secara serempak
semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Ho ditolak dan Ha diterima bila nilai sig < α (0,05) artinya secara serempak
semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
3. Uji statistik t
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen
secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat. Menurut
Ghozali (2006) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh
satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel
Kriteria pengujian :
1. Bila nilai sig < α (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya secara
parsial suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen.
2. Bila nilai sig > α (0,05) maka hipotesis nol (Ho) diterima dan Ha ditolak yang
artinya secara parsial suatu variabel independen berpengaruh tidak signifikan
terhadap variabel dependen.
4. Uji Residual
Pengujian variabel moderating dengan uji residual digunakan untuk mengatasi
kecenderungan akan terjadi multikolonieritaslinieritas yang tinggi antar variabel
independen (Ghozali, 2013). Uji residual menguji pengaruh deviasi dari suatu model
regresi dengan melihat Lack of Fit (ketidakcocokan) yang ditunjukkan oleh nilai
residual. Hipotesis moderating diterima jika terdapat ketidakcocokan dari deviasi
hubungan linear antara variabel independen. Kriteria uji residual adalah P Value
(Sig) < 0,05 dan nilai koefisien parameternya negatif , maka dapat memoderasi.
Tetapi, apabila P Value (Sig) > 0,05 dan nilai koefisien parameternya positif, maka
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Deskripsi Data Penelitian
Populasi penelitian ini terdiri dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara. Setelah dilakukan pengumpulan data, ditemukan bahwa ternyata tidak semua
kabupaten/kota memiliki SiLPA bernilai positif sehingga dari jumlah poopulasi,
hanya 23 kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel (Lampiran 2). Kurun waktu
data penelitian adalah 4 tahun amatan yaitu 2011-2014. sehingga diperoleh 92 unit
analisis data penelitian dengan deskriptif yang ditunjukkan. tabel 5.1 berikut:
Tabel 5.1 Deskriptif Data Penelitian Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
AlokasiBM 92 4.45 46.51 25.6010 8.86973
RasioKemandirian 92 .86 38.27 5.6816 6.65811
RasioEfektivitasPAD 92 20.49 332.77 111.1996 42.38843
RasioEfisiensi 92 70.17 102.75 91.2261 6.95665
RasioSiLPA 92 .04 42.71 9.3384 8.14908
Ln_DAK 92 23.61 25.23 24.4956 .40057
Valid N (listwise) 92
Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Tabel 5.1 deskriptif data penelitian menunjukan bahwa jumlah data penelitan
(N) adalah 92 unit analisis. Setiap variabel memiliki nilai maksimum dan nilai
minimum, rata-rata dan standar deviasi yang bervariasi, penjelasan untuk
masing-masing variabel dijabarkan sebagai berikut:
1. Alokasi Belanja Modal (Y)
Alokasi belanja modal yang diberikan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
sebesar 4,45 % dan tertinggi sebesar 46,51%. Rata-rata alokasi belanja modal
sebesar 25,6010 %
2. Rasio kemandirian keuangan daerah (X1)
Rasio kemandirian keuangan daerah memiliki kesenjangan yang cukup tinggi,
rasio terendah sebesar 0,86 % dan tertinggi sebesar 38,27 % dengan rata-rata
sebesar 5,6816 %, hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. qz
3. Rasio efektivitas PAD (X2)
Rasio efektifitas PAD memiliki rata-rata yang sangat tinggi yaitu sebesar
111,1996 %, hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota sangat baik
dalam pencapaian target PAD. Nilai terendah sebesar 20,49 % dan nilai
tertinggi sebesar 332,77 %
4. Rasio efisiensi keuangan daerah (X3)
Rasio efisiensi keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara
memiliki nilai terendah sebesar 70,17 % dan nilai tertinggi sebesar 102,75%
dengan rata-rata sebesar 102,75 %.
5. Rasio tingkat pembiayaan SiLPA (X4)
Rasio tingkat pembiayaan SiLPA memiliki kesenjangan yang cukup tinggi
antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, nilai terendah sebesar
0,04 % di Kabupaten Mandailing Natal dan nilai tertinggi sebesar 42,71 % di
Kabupaten Nias dengan rata-rata sebesar 9,3384 %
6. DAK (Z)
DAK tahun 2011-2014 Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara memiliki
5.2 Pengujian Data 5.2.1 Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji
uji normalitas, heteroskedastisitas, uji multikolonieritaslinearitas dan uji autokorelasi.
Data yang disajikakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan
gabungan data cross section dan time series.
5.2.1.1 Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada
penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, dengan analisis grafik dan analisis statistik
dengan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S).
1. Analisis Grafik
Gambar 5.2 Grafik Normal P- Plot
Gambar 5.1 menunjukkan bahwa variabel berdistribusi normal, dengan
grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang tidak menceng (swekness)
ke kiri atau ke kanan. Hasil yang sama ditunjukan grafik normal p-plot pada
Gambar 5.2, dimana terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan
penyebarannya mendekati garis diagonal. Namun penilaian normalitas berdasarkan
historgam dan grafik normal p-plot tersebut seringkali bersifat subjektif sehingga
diperlukan uji statistik untuk membuktikan variabel pegganggu atau residual
memiliki distribusi normal.
2. Analisis Statistik
Hasil Uji normalitas data dengan uji Kolmogrov-Smirnov (KS). Uji KS
dilakukan dengan membuat hipotesis :
H0 : Data residual terdistribusi normal
Kriterianya adalah :
H0 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) > 0,05
H1 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) < 0,05
Tabel 5.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 92
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation 6.83806933
Most Extreme Differences Absolute .104
Positive .104
Negative -.057
Test Statistic .104
Asymp. Sig. (2-tailed) .016c
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai test statistik Kolmogrov-Smirnov adalah
0,104 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 yang nilainya lebih kecil α = 0,05
(Asymp Sig = 0,016 < 0,05) sehingga hipotesis H0 ditolak, yang berarti data residual
tidak terdistribusi normal. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan hasil analisis
grafik yang telah dilakukan sebelumnya.
5.2.1.2 Uji Multikolonieritaslinearitas
Pengujian multikolonieritaslinearitas dilakukan dengan menggunakan VIF dan
nilai Tolerance. Data dikatakan tidak mengalami multikolonieritaslinearitas apabila
nilai Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. Hasil uji multikolonieritaslinearitas dapat
Tabel 5.3 Uji Multikolonieritaslinearitas
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
Rasio Kemandirian Keuangan .945 1.058
Rasio Efektivitas PAD .789 1.268
Rasio Efisiensi Keuangan .477 2.095
Rasio SiLPA .570 1.754
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal
b. Sumber : Data
Sumber : Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki
nilai VIF ≤ 10 dan nilai Tolerance ≥ 0,10, sehingga diantara data variabel
independen tidak bergejala multikolonieritaslinearitas.
5.2.1.3 Uji Heterokedasititas
Uji Heterokendasititas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Deteksi gejala heterokedasititas pada penelitian ini dilakukan dengan Uji
Glejser. Hasil Uji Glejser ditampilakan pada Tabel 5.4 berikut.
Tabel 5.4 Uji Glejser Coefficientsa
a. Dependent Variable: absut
Tabel 5.4 menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut Ut
(Absut). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan
5%. Dengan demikian, model regresi tidak bergejala hetroskedastisitas.
5.2.1.4 Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi linier berganda ada terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji
autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Run Test. Uji
Run Test dilakukan dengan membuat hipotesis :
H0 : Data tidak mengalami autokorelasi
H1 : Data mengalami autokorelasi
Kriterianya adalah :
H0 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) > 0,05
H1 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) < 0,05
Hasil uji run test pada penelitian ini, disajikan pada Tabel 5.5 berikut:
Tabel 5.5 uji Runs Test Runs Test
Unstandardized
Residual
Test Valuea -1.19136
Cases < Test Value 46
Cases >= Test Value 46
Total Cases 92
Number of Runs 40
Z -1.468
Asymp. Sig. (2-tailed) .142
a. Median
Berdasarkan Tabel 5.5 diatas, menunjukan bahwa nilai signifikansi sebesar
0,142 lebih besar α = 0,05 (Asym Sig 0,142 > α 0,05), sehingga data pada penelitian
ini tidak mengalami gejala autokorelasi.
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, dideteksi satu uji pada model
tidak memenuhi asumsi klasik yaitu uji normalitas. Untuk memenuhi asumsi klasik
maka data pada penelitian ini telah ditransformasi dalam bentuk Logaritma Natural
(Ln).
5.2.1.5 Uji Normalitas setelah transformasi data
Hasil Uji normalitas yang dilakukan setelah data ditransformasi dalam bentuk
Ln, meliputi analisis grafik dan analisis statistik, yaitu:
1. Analisis Grafik
Gambar 5.4 Grafik Normal P- Plot setelah transformasi data
Grafik histrogram yang ditunjukan gambar 5.3 menunjukkan pola distribusi
normal, yang terlihat dari pola distribusi yang tidak menceng ke kiri atau ke kanan.
Hasil yang sama ditunjukan grafik Normal P-Plot pada gambar 5.4 dimana terlihat
titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati garis
diagonal.
2. Analisis Statistik
Uji normalitas data dengan analisis statistik pada penelitian ini dilakukan
dengan uji Kolmogrov-Smirnov (KS). Hasil uji Kolmogrov-Smirnov (KS) setelah
Tabel 5.6 .One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test setelah transformasi data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 92
Normal Parametersa,b Mean .0000000
Std. Deviation .26567497
Most Extreme Differences Absolute .058
Positive .036
Negative -.058
Test Statistic .058
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
Test distribution is Normal.
Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai test statistik Kolmogrov-Smirnov adalah
0,058 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200 yang nilainya lebih besar α = 0,05
(Asymp Sig = 0,200 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual
terdistribusi normal. Hasil analisis statistik sejalan dengan analisis grafik, maka
model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas.
5.2.1.6 Uji Multikolonieritaslinearitas setelah transformasi data
Pengujian multikolonieritaslinearitas dilakukan dengan menggunakan VIF
dan nilai Tolerance. Data dikatakan tidak mengalami multikolonieritaslinearitas
apabila nilai Tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. Pengujian
multikolonieritaslinearitas setelah dilakukan transformasi data dalam bentuk Ln,
Tabel 5.7 Uji Multikolonieritaslinearitas setelah transformasi data
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
Ln_RasioKemandirian .886 1.129
Ln_RasioEfektivitasPAD .826 1.210
Ln_RasioEfisiensi .595 1.681
Ln_RasioSiLPA .766 1.306
Dependent variable : Ln_AlokasiBM Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Berdasarkan Tabel 5.7 terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki
nilai VIF ≤ 10 dan nilai Tolerance ≥ 0,10, sehingga diantara data variabel
independen tidak bergejala multikolonieritaslinearitas.
5.2.1.7 Uji Heterokedasititas setelah transformasi data
Hasil Uji Glejser setelah dilakukan transformasi data dalam bentuk Ln
ditampilkan pada Tabel 5.8 berikut:
Tabel 5.8 Uji Glejser setelah transformasi data Coefficientsa
Ln_RasioEfektivitasPAD -.051 .049 -.113 -1.032 .305
Ln_RasioEfisiensi .371 .276 .174 1.345 .182
Ln_RasioSiLPA -.007 .014 -.059 -.520 .605
a. Dependent Variable: absut1
Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Tabel 5.8 menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut Ut
5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan model regresi tidak bergejala
hetroskedastisitas.
5.2.1.8 Uji Autokorelasi setelah transformasi data
Hasil uji autokorelasi dengan Uji Runs Test setelah dilakukan transformasi
data dalam bentuk Ln ditampilkan dapat dilihat pada Tabel 5.9 dibawah ini:
Tabel 5.9 Uji Runs Test setelah transformasi data Runs Test
Unstandardized Residual
Test Valuea .00741
Cases < Test Value 46
Cases >= Test Value 46
Total Cases 92
Number of Runs 42
Z -1.048
Asymp. Sig. (2-tailed) .294
a. Median
Sumber : Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Berdasarkan Tabel 5.9 diatas, menunjukan bahwa nilai signifikansi sebesar
0,294 lebih besar α = 0,05 (Asym Sig 0,294 > α 0,05), sehingga data pada penelitian
ini tidak bergejala autokorelasi.
5.3 Pengujian Hipotesis
5.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama
Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini ditujukan untuk menguji
pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan
daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat
Sumatera Utara secara serempak dan parsial. Pengujian hipotesis pertama
menggunakan Uji Statistik F dan Uji Statistik t.
5.3.1.1 Koefisien determinasi ( R2)
Nilai koefisein determinasi ( R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu. Hipotesis pertama yang diuji pada penelitian
ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah,
rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan
SiLPA berpengaruh secara serempak dan parsial terhadap alokasi belanja modal.
Untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan
variabel independen dapat dilihat melalui nilai adjusted R square pada Tabel 5.10
berikut ini
Tabel 5.10 Nilai Koefisien Determinasi ( R2) Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 .713a .509 .486 .27171
a. Predictors: (Constant), Ln_RasioSiLPA, Ln_RasioKemandirian, Ln_RasioEfektivitasPAD,
Ln_RasioEfisiensi
b. Dependent Variable: Ln_AlokasiBM
Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Nilai adjusted R square yang ditunjukan Tabel 5.10 adalah sebesar 0,486. Hal ini
menunjukan bahwa 48,6 % variabel alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh
kinerja keuangan daerah yang diukur rasio kemandirian keuangan daerah, rasio
pembiayaan SiLPA, sedangkan sisanya sebesar 51,4 % dipengaruhi variabel lain
yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.
5.3.1.2 Uji statistik F
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang
dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara serempak terhadap variabel
independen. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 5.11 dibawah ini:
Tabel 5.11 Uji Statistik F
ANOVAa
Model
Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 6.658 4 1.664 22.544 .000b
Residual 6.423 87 .074
Total 13.081 91
a. Dependent Variable: Ln_AlokasiBM
b. Predictors: (Constant), Ln_RasioSiLPA, Ln_RasioKemandirian, Ln_RasioEfektivitasPAD, Ln_RasioEfisiensi
Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Berdasarkan Tabel 5.11 diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil
dari α = 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kinerja keuangan daerah yang
diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio
efisiensi keuangan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SiLPA
berpengaruh secara serempak terhadap alokasi belanja modal.
5.3.1.3 Uji statistik t
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen
Tabel 5.12 Uji Statistik t
Ln_RasioEfektivitasPAD (REP) .035 .082 .035 .424 .673
Ln_RasioEfisiensi (RE) -1.306 .461 -.276 -2.834 .006
Ln_RasioSiLPA(RSiLPA) .049 .023 .185 2.151 .034
a. Dependent Variable: Ln_AlokasiBM
Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Hasil uji Statistik t yang ditunjukkan oleh Tabel 5.12 dengan kriteria
pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05,
maka pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen adalah sebagai berikut:
Variabel kinerja keuangan daerah yang diukur dengan variabel rasio
kemandirian (RK) memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05
dengan koefisien regresi yang bernilai negatif maka dapat disimpulkan bahwa secara
parsial variabel rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
variabel alokasi belanja modal.
Variabel rasio efektifitas PAD (REP) memiliki tingkat signifikansi 0,673
lebih besar dari α = 0,05 dengan koefisien regresi bernilai positif maka dapat
disimpulkan bahwa secara parsial variabel efektifitas PAD berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap variabel alokasi belanja modal.
Variabel rasio efisiensi keuangan daerah (RE) memiliki tingkat signifikansi
disimpulkan bahwa secara parsial variabel rasio efisiensi keuangan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap variabel alokasi belanja modal.
Variabel rasio tingkat pembiayaan SiLPA (RSiLPA) memiliki tingkat
signifikansi 0,034 lebih kecil dari α = 0,05 dengan koefisien regresi bernilai positif
maka dapat disimpulkan secara parsial variabel rasio tingkat pembiayaan SiLPA
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel alokasi belanja modal.
Berdasarkan nilai-nilai koefisien yang ditunjukan pada Tabel 5.12, dapat
disusun persamaan regresi berganda, sebagai berikut :
Alokasi_BM = 9,226 - 0,278 RK + 0,035 REP – 1,306 RE + 0,049 RSiLPA
Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diuraikan penjelasan sebagai
berikut:
a. Konstanta sebesar 9,226 bermakna bahwa alokasi belanja modal akan tetap
sebesar konstanta jika variabel independen bernilai nol
b. Varibel rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan
terhadap alokasi belanja dengan nilai koefisien 0,278 artinya setiap penambahan
rasio kemandirian keuangan sebesar 1%, akan menurunkan alokasi belanja
modal tahun berikutnya sebesar 0,278% dengan asumsi variabel lain konstan.
c. Variabel rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dengan nilai koefisien
sebesar 0,035 namun tidak signifikan terhadap alokasi modal.
d. Variabel rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap
alokasi belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 1,306 artinya setiap
penambahan rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 1% akan menurunkan
alokasi belanja modal tahun berikutnya sebesar 1,306 % dengan asumsi variabel
e. Variabel rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif signifikan
terhadap alokasi belanja dengan nilai koefisien 0,049 artinya setiap penambahan
rasio tingkat pembiayaan SiLPA sebesar 1% akan menaikan alokasi belanja
modal tahun berikutnya sebesar 0,049 % dengan asumsi variabel lain konstan.
5.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua
5.3.2.1 Uji Residual
Pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini dilakukan dengan uji residual.
Pengujian ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis bahwa variabel DAK
sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan antara variabel kinerja
keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio
efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA
dengan variabel alokasi belanja modal. Hasil uji residual disajikan pada Tabel 5.13
dan Tabel 5.14 dibawah ini.
Tabel 5.13 Hasil Regresi untuk Uji Residual Coefficientsa
Ln_RasioEfektivitasPAD (RE) .004 .120 .004 .037 .970
Ln_RasioEfisiensikeuangan(REK) .018 .671 .004 .026 .979
Ln_RasioSiLPA (RSilPA) -.073 .033 -.262 -2.214 .029
a. Dependent Variable: Ln_DAK
Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Berdasarkan Hasil Regresi yang ditunjukan Tabel 5.13 dapat disusun
persamaan untuk hasil pengujian hipotesis kedua, yaitu :
Hasil olahan data yang disajikan Tabel 5.13 bertujuan untuk memperoleh
nilai residual dari variabel moderating, nilai residual tersebut kemudian
ditransformasi menghasilkan nilai absolut residual. Nilai absolut residual tersebut
diregresikan dengan belanja modal yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 5.14
dibawah ini:
Tabel 5.14 Hasil Uji Residual Coefficientsa
a. Dependent Variable: AbsRes_1
Sumber : hasil penelitian, 2016 (data diolah)
Berdasarkan data pada Tabel 5.14 maka model uji residual dapat disusun
bentuk persamaan, yaitu :
|e| = 0,595 - 0,086 AlokasiBM
Sebuah variabel bisa dikatakan sebagai variabel moderating apabila nilai
signifikan < nilai α = 0,05 dan memiliki nilai koefisien yang negatif. Tabel 5.14
menunjukan bahwa tingkat signifikansi alokasi belanja modal sebesar 0,141 lebih
besar dari α = 0,05 dan nilai koefisien bertanda negatif. Jadi, dapat ditarik
kesimpulan bahwa variabel DAK tidak mampu memoderasi hubungan variabel
kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah,
rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan
5.4 Pembahasan hasil penelitian
Hasil pengujian dari hipotesis pertama menyimpulkan bahwa variabel kinerja
keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio
efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA
secara serempak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan
secara parsial, variabel kinerja kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio
kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya; rasio tingkat
pembiayaan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal
tahun berikutnya; rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap alokasi belanja modal.
Hasil pengujian dari hipotesis kedua menyimpulkan bahwa variabel DAK
tidak mampu memoderasi hubungan variabel kinerja keuangan daerah yang diukur
dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi
keuangan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA dengan variabel alokasi belanja
modal
6.4.1 Pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal
Hasil pengujian pengaruh variabel kinerja keuangan daerah yang diukur
dengan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal dengan
uji t menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0,278 dan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05, hal ini menunjukan bahwa
rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
keuangan daerah tidak searah dengan alokasi belanja modal, dimana semakin
meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah akan menurunkan alokasi belanja
modal tahun berikutnya. Hasil penelitiaan ini sejalan dengan penelitian Gerungan,
Saerang, dan Pontoh (2013) dan Verawaty, Merina, dan, Sari (2015) yang
menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif
signifikan terhadap alokasi belanja modal namun penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan Fitri (2013) dan Ardhini (2011) yang menyatakan
bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi
belanja modal tahun berikutnya.
Rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan
yang diperlukan daerah. Suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan
jumlah belanja modal untuk pelayanan publik (Ardhini, 2011). Rata-rata tingkat
kemandirian keuangan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara adalah sebesar
5,68 % (Tabel 5.1), hal ini menunjukan bahwa pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Utara mampu mengelola PAD nya, walaupun masih tetap
bergantung kepada pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, kemungkinan hal ini
disebabkan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,
mengalokasikan PAD kepada belanja-belanja lain selain belanja modal atau dengan
kata lain belanja modal bukan menjadi prioritas sehingga kenaikan rasio kemandirian
6.4.2 Pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio Efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal
Hasil pengujian pengaruh variabel kinerja keuangan daerah yang diukur
dengan rasio efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal dengan uji t
menunjukan hasil bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,35 dan tingkat signifikansi
sebesar 0,673 yang lebih besar dari α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa rasio
efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja
modal. Pengaruh tidak signifikan, menunjukan bahwa rasio efektivitas PAD tidak
memiliki peranan penting dalam pengalokasian belanja modal.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Martini dan Dwirandra (2015)
dan juga Fitri (2014) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal, namun tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Sularso dan Restianto (2011) serta Arsa (2015)
yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal.
Rasio efektivitas yang tinggi, mencerminkan kemampuan daerah yang
sudah baik dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tidak berpengaruhnya rasio
efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal, walaupun rata-rata rasio efektivitas
PAD mencapai 111,19 % (Tabel 5.1) kemungkinan disebabkan oleh PAD yang
diperoleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tidak dialokasikan
untuk belanja modal namun untuk belanja lain, seperti belanja barang dan jasa,
belanja pegawai dan belanja lain-lain. Hal ini akan berimbas pada terhambatnya
6.4.3 Pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal
Hasil pengujian pengaruh variabel kinerja keuangan daerah yang diukur
dengan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal dengan uji t
menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien regresi sebesar -1,306 dan tingkat
signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa
rasio efektifitas keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi
belanja modal. Pengaruh negatif menunjukan arti bahwa rasio efektifitas keuangan
daerah tidak searah dengan alokasi belanja modal, dimana semakin meningkatnya
rasio efektivitas keuangan daerah akan menurunkan alokasi belanja modal tahun
berikutnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Martini dan Dwirandra
(2015) dan juga penelitian Gerungan, Saerang, dan Pontoh (2013) serta Ardhini
(2011) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya, namun hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fitri (2014) yang menyatakan rasio
efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output
dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efisiensi keuangan daerah
maka akan menurunkan alokasi belanja modal tahun berikutnya. Pengaruh negatif
rasio efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal kemungkinan
disebabkan karena penggunaan keuangan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Utara kurang efisien yang digambarkan oleh tingginya rata-rata
rasio efisiensi keuangan daerah yaitu sebesar 91,22 % (Tabel 5.1). Tingginya rasio
pengeluaran namun tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan daerah, sehingga
terjadi pemborosan belanja daerah namun tidak digunakan untuk belanja modal
secara maksimal. Selama ini, pengeluaran daerah didominasi oleh belanja pegawai
dan belanja operasional lainnya sedangkan porsi belanja modal relatif kecil. Hal lain
yang diduga menjadi penyebab rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh
negatif terhadap alokasi belanja modal adalah kemungkinan pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tidak semuanya menerapkan Standar
Analisis Biaya dalam menyusun anggaran kegiatan/program, sehingga kemungkinan
banyak kegiatan/program tidak efisien (tidak wajar) dalam penganggaran biayanya.
6.4.4 Pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal
Hasil pengujian pengaruh variabel kinerja keuangan daerah yang diukur
dengan rasio tingkat pembiayaan SiLPA daerah terhadap alokasi belanja modal
dengan uji t menunjukan hasil bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,049 dan
tingkat signifikansi sebesar 0,034 yang lebih kecil dari α = 0,05, hal ini menunjukkan
bahwa rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap
alokasi belanja modal. Pengaruh positif menunjukkan arti bahwa rasio tingkat
pembiayaan SiLPA searah dengan alokasi belanja modal, dimana semakin
meningkatnya tingkat pembiayaan SiLPA akan menaikan alokasi belanja modal
tahun berikutnya.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Martini dan Dwirandra
(2015) yang menyatakan bahwa rasio tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu
namun sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang
menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal pada α = 1 %.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan SiLPA
berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. hal
ini dapat menunjukkan kemungkinan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara mengalokasikan SiLPA daerahnya untuk mendanai pelaksanaan
kegiatan yang bertujuan untuk pelayanan publik yang ditampung dalam kegiatan
belanja modal, hal ini sesuai dengan tujuan SiLPA berdasarkan penjelasan
Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
6.4.5 DAK sebagai variabel moderating
Hasil uji residual menunjukkan nilai koefisien adalah -0,086 dan signifikansi
sebesar 0,141 lebih dari α = 0,05 sehigga DAK tidak mampu memoderasi hubungan
antara kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal atau dapat dikatakan
bahwa variabel DAK bukanlah variabel pemoderasi.
DAK bersifat special grant, dimana peruntukanya untuk pembangunan yang
sudah ditentukan dari pusat, yang lebih diprioritaskan untuk belanja modal
(Verawaty, Meriana dan Sari, 2015). Besaran DAK ditentukan oleh pemerintah pusat
melalui kajian menteri teknis berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, bila usulan pembiayaan daerah diterima menteri teknis dan
anggarannya ditampung dalam DAK maka daerah akan mempunyai sumber
pembiayaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang ditampung
dalam belanja modal namun jika besaran DAK yang diusulkan pemerintah daearah
maka pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan lain untuk menutupi
belanja modal yang pendanaanya berasal dari DAK.
Berdasarkan deskripsi dan evaluasi APBD 2014 yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014),
menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang disampaikan pemerintah daerah
dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya informasi alokasi dana transfer ke
daerah yang ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Keterlambatan informasi
alokasi dana transfer yang mencakup DAK, DBH dan DAU ke daerah
mempengaruhi proses penganggaran APBD termasuk penganggaran untuk belanja
modal. Jadi, kemungkinan penyebab DAK tidak mampu memoderasi hubungan
antara kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan
daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat
pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal adalah karena ketidakpastian
jumlah alokasi DAK yang diterima pemerintah daerah. Ketidakpastian ini
disebabkan oleh lambatnya informasi alokasi dana transfer ke daerah oleh
Kementerian Keuangan, sehingga seringkali besaran alokasi DAK yang dianggarkan
pemerintah daerah pada APBD tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:
1. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan
daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat
pembiayaan SiLPA secara serempak berpengaruh signifikan terhadap alokasi
belanja modal. Meskipun demikian pengujian secara parsial menunjukan tidak
semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel alokasi belanja
modal. Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan
daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun
berikutnya; rasio efektivitas PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
alokasi belanja modal tahun berikutnya; Rasio tingkat pembiayaan SiLPA
berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun
berikutnya.
2. Variabel DAK tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel kinerja
keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah,
rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio tingkat
pembiayaan SiLPA dengan variabel alokasi belanja modal. Variabel DAK
6.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :
1. Variabel dependen yang digunakan hanya mampu menjelaskan 48,6 %
pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal, kemungkinan masih lebih
banyak variabel lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal dan
pengukuran kinerja keuangan daerah hanya menggunakan 4 rasio keuangan
daerah
2. Penelitian ini hanya meneliti 23 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera
Utara.
6.3 Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang alokasi
belanja modal, supaya menambah variabel independen lainnya seperti DBH,
pinjaman daerah dan lain-lain. Pengukuran kinerja keuangan agar menambah
indikator lain, seperti rasio kontribusi BUMD, Total Revenues/Population
Ratio, Debt Service Coverage Ratio dan lain-lain.
2. Peneliti selanjutnya, agar memperluas atau menambah sampel penelitian di