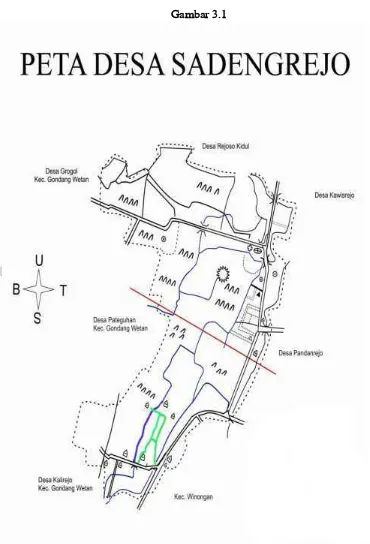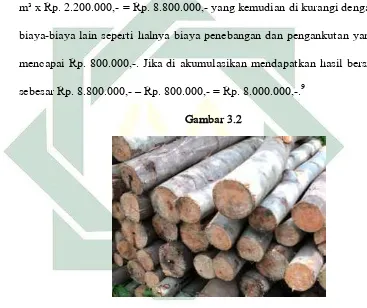WANPRESTASI
PADA BAGI HASIL PENGOLAHAN TANAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)
SKRIPSI
Oleh
Nikmatul Maghfiroh NIM. C02213055
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Surabaya
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Wanprestasi pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan) dengan rumusan masalah (a) bagaimana praktik perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan? (b) bagaimana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan?
Dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan kerangka teori kerjasama muza>ra’ah dalam Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Adapun pengumpulan data menggunakan metode observasi dan metode interview (wawancara), sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif, artinya penulis berusaha menggambarkan pengolahan tanah, sistem bagi hasil dalam pengolahan, yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dalam perspektif Hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah disetujui serta dijalankan oleh kedua belah pihak dan tidak menjadi ketentuan hukum Adat. Dari pembagian hasil yang dilaksanakan menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena dari pihak pengelola minta bagian lebih dari yang dihasilkan sebab merasa berhak dengan alasan pengelola yang mengeluarkan biaya-biaya.
Perjanjian tersebut termasuk dalam jenis perjanjian muza>ra’ah yang sistemnya memang pihak pemilik tanah hanya menyediakan tanah/lahan, sedangkan alat, benih dan pengolahan tanah berasal dari pihak pengelola. Idealnya muza>ra’ah menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi sebaliknya yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak pemilik tanah karena terjadi wanprestasi (ingkar janji) pemberian bagi hasil dari pihak pengelola.
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL DALAM ... i
PERNYATAAN KEASLIAN ... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii
PENGESAHAN ... iv
ABSTRAK ... v
KATA PENGANTAR ... vi
DAFTAR ISI ... viii
DAFTAR GAMBAR ... x
DAFTAR TRANSLITERASI ... xi
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ... 6
C. Rumusan Masalah ... 7
D. Kajian Pustaka ... 7
E. Tujuan Penelitian ... 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian ... 10
G. Definisi Operasional ... 11
H. Metode Penelitian ... 12
I. Sistematika Pembahasan ... 17
BAB II MUZA>RA’AH ... 19
A. Pengertian Muza>ra’ah ... 19
B. Dasar Hukum Muza>ra’ah ... 22
C. Rukun Muza>ra’ah dan Sifat Akadnya ... 23
D. Syarat-Syarat Muza>ra’ah ... 25
E. Macam- Macam Muza>ra’ah ... 29
F. Hukum-Hukum Muza>ra’ah yang S}ahih dan Fa>sid ... 31
BAB III DESKRIPSI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
PENGOLAHAN TANAH di DUSUN DARAH DESA
SADENGREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN ... 38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 38
1. Letak Geografis Desa Sadengrejo Kec. Rejoso ... 38
2. Kecamatan Rejoso ... 40
B. Praktek Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ... 41
1. Latar Belang dan Faktor Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah ... 41
2. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil ... 46
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN TANAH DI DUSUN DARAH DESA SADENGREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN ... 50
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo ... 50
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo ... 57
BAB V PENUTUP ... 65
A. Kesimpulan ... 65
B. Saran ... 66 DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna dan mulia,
yang diberi banyak kelebihan termasuk akal fikiran, jiwa dan jasmani.
Manusia diciptakan tidak hanya sebagai makhluk individu melainkan juga
sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas
dari manusia yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka
ragam, manusia tidak akan pernah bisa memenuhinya sendiri. Adanya orang
lain sangat dibutuhkan dalam pemenuhan dan kelangsungan hidupnya.
Kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja
melainkan manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperti makan,
minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi
kebutuhan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam
sekitarnya. Dan hal tersebut tidak terlepas dari aturan-aturan, baik aturan
yang ada di agama hingga aturan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya aturan
tersebut tidak lain adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan mereka sehingga
tercipta kehidupan yang harmonis.
Dalam Islam aturan-aturan yang terkait dengan hubungan manusia
lebih dikenal dengan istilah fiqh mu’a>malah. Yang mana dalam arti luas
2
sosial kemasyarakatan.1 Pengertian lain dari fiqh mu’a>malah yakni
hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang
terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal
ekonomi, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama
dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan rampasan
perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan,
dan pesanan.2
Jenis-jenis transaksi dalam praktek mu’a>malah pada dasarnya adalah
boleh sampai ditemukan dalil-dalil yang melarangnya.3 Sebagai seorang
muslim kegiatan mu’a>malah yang dilakukan harus dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah SWT serta tidak keluar dari nilai-nilai
kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam melakukan interaksi diperlukan adanya
pengetahuan mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga salah
satu pihak tidak merasa dirugikan dan kedua belah pihak saling ri>da.
Dengan demikian mu’a>malah bagi muslim dapat diartikan sebagai
pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya
kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian,
disamping dituntut untuk selalu melakukan habl-min-Alla>h (ibadah) sebagai
aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga dituntut untuk selalu
melakukan habl-min-al-na>s (hubungan sosial kemasyarakatan dengan
1 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,
2012), 11.
3
lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak bisa
dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.4
Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan
tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal
jelas penyaluran dan pemanfaatannya sebagaimana firman Allah SWT dalam
surat Al-Jumu’ah ayat 10:
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.5
Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk tetap menunaikan ibadah
baik secara z}ahir/jasmani maupun bat}in/rohani di muka bumi ini, dengan
memanfaatkan bumi sebagai tempat untuk mencari rizki yang halal. Cara
pemanfaatan bumi bisa dibuat dengan dijadikannya tanah pertanian.
Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus
memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Dalam Agama Islam
tidak diperkenankan membiarkan tanah pertanian itu dalam keadaan kosong
jika masih memberikan manfaat, sebab hal tersebut berarti menghilangkan
nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah Saw melarang keras
untuk menyia-nyiakan harta miliknya. Pemilik tanah ini dapat
4 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2008), 291.
4
memanfaatkannya dengan berbagai cara. Baik ditanami sendiri atau pun
bekerjasama dengan pihak lain.
Di dalam mu’a>malah terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang
pertanian, salah satu diantaranya adalah muza>ra’ah, didalam muza>ra’ah
terdapat 2 pihak yaitu pemilik tanah dan pengelola. Hasil panen yang
diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya, misalnya: ½, ⅓ atau kurang
atau lebih menurut persetujuan bersama. Boleh juga si pemilik tanah itu
membantu kepada yang hendak menanaminya berupa bibit, alat atau hewan.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Muttafaq
’Alaih diterangkan, bahwa Rasulullah Saw menyewakan tanah kepada
penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah.
Hadist ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, diantaranya: Ibnu
Umar, Nafi’ dan Ubaidillah.
اَنَ ثَدَح
َحْسِإ
ق
نْب
رْو صْنَم
اَنْرَ بْخَأ،
ََََْ
ْب
، دْيِعَس ن
َنَأ َرَم ع ِنْبا ْنَع ٌعِفاَن َِِرَ بْخَأ ِهَللا ِدْيَ ب ع ْنَع
ْرَز ْوَأ رَََ ْنِم اَهْ نِم ج رََْ اَم ِرْطَشِب َرَ بْيَخ َلَْأ َلَماَع َمَلَسَو ِهْيَلَع هَللا ىَلَص ِهَللا َلو سَر
ع
.
“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam.”6 (HR. Ibnu Majjah, Muttafaq ’Alaih)
Jadi muza>ra’ah adalah diperbolehkan dengan dalil-dalil yang ada dan
diamalkan oleh salafush shalih. Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik
tanah, dan boleh benih berasal dari pengelola.
6 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemah Shahih Sunan At-Tirmidzi 2 (Jakarta: Pustaka
5
Praktek muza>ra’ah yang terjadi di lingkungan Dusun Darah Desa
Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan hampir sama seperti yang dilakukan
ketika masa Nabi Muhammad dan para sahabat, yaitu antara pemilik tanah
dengan luas 7000 m2 (tepatnya 7.012 m2) yang telah melakukan perjanjian
pengolahan tanah penanaman pohon sengon dengan bibit dari seorang petani
(pengelola) dengan kesepakatan bagi hasil 100%:2 dalam jangka waktu 5
tahun. Akan tetapi pihak pengelola tidak menanam pohon sengon melainkan
menanam pohon jati, sehingga dalam hal ini telah terjadi ketidaksamaan
dengan perjanjian yang telah dilakukan.
Setelah terjadinya kesepakatan mulailah pengelola melakukan
tugasnya yaitu menanami tanah dan merawatnya hingga tiba masa
berahirnya kesepakatan. Adapun pemilik tanah hanya mensurvei atau
melihat keadaan lahan dan perkembangan tanamannya. Hingga tiba batas
waktu yang telah disepakati pohon jati belum juga ditebang, dikarenakan
usianya masih terlalu muda dan tidak laku. Dengan berjalannya waktu
pemilik tanah merasa dirugikan akibat keterlambatan penebangan selama 2
tahun. 7
Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan
pengelola tersebut hanya secara lisan saja dengan menghadirkan seorang
saksi.8 Sehingga dapat memicu terjadinya perselisihan, terutama pada waktu
melakukan bagi hasil. Dari pembagian hasil yang diberikan, pihak pengelola
tidak memenuhi kesepakatan awal yang seharusnya pembagian hasil dengan
6
persentase 50:50 menjadi 44:56. Perbedaan pembagian hasil tersebut terjadi
karena pihak pengelola mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Jika
sudah terjadi perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati
bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.
Dari pemaparan diatas penulis tertarik dan berkeinginan untuk
menulis dan meneliti bagaimana praktek pengolahan tanah, yang lebih
khususnya terkait wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah untuk
dituangkan sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul
“Wanprestasi Pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.
Pasuruan)”.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis
mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari perjanjian bagi hasil
pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.
Pasuruan yakni sebagai berikut:
1. Praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan pengelola.
2. Mekanisme bagi hasil antara pemilik tanah dengan pengelola.
3. Wanprestasi pada bagi hasil pengolahan tanah.
7
Dari beberapa identifikasi masalah diatas, untuk menghasilkan
penelitian yang lebih fokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni
sebagai berikut:
1. Praktek penjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa
Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
2. Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi hasil
pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.
Pasuruan.
C. Rumusan Masalah
Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, agar lebih
memberikan kejelasan terhadap masalah yang diangkat maka permasalahanya
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek penjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi
hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso
Kab. Pasuruan?
D. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga
8
pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan
deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.9
Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri,
penulis menemukan beberapa kajian seputar perjanjian bagi hasil pengelolaan
tanah, di antaranya adalah:
1. Skripsi yang terbit pada tahun 2012, yakni berjudul “Studi Komparasi
Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ladang Pesanggem Antara Desa
Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu
Kabupaten Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh
Fahrizal Bahari. Skripsi ini menjelaskan bagaima pengelolaan ladang
pesanggem boleh menurut Islam, akad yang dilakukan di Desa
Sugihwaras boleh dilihat dari analisis akad, syarat dan rukun yang ada,
akan tetapi di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong ada sebuah syarat
yang tidak dipenuhi, yaitu syarat tentang tanah yang subur dan
menghasilkan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw tentang tidak
diperbolehkan memberikan tanah yang tidak subur sebagai objek akad,
dikarenakan menjadikan akad ini merugikan, sehingga akad yang terjadi
di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong menjadi tidak boleh.10
2. Skripsi yang ditulis oleh Epy Yuliana pada tahun 2008 dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet
9Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya,
2016), 8.
10Fahrizal Bahari, “Studi komparasi Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ladang Pesanggem
9
Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”.
Penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Desa
Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tidak
bertentangan dengan hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam
bidang musaqah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga
dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.11
3. Skripsi yang ditulis oleh Anisatur Rohmatin pada tahun 2008 dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil
Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa
Kab. Pati)” disini penulis menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil
pengelolaan lahan tambak yang dilakukan di Desa Tluwuk Kec.
Wedarijaksa Kab. Pati ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasilnya
sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama
dan turun temurun, sehingga bagi hasil yang telah dipraktekkan oleh para
petani di desa tersebut sudah dikategorikan menjadi hukum adat dan tidak
bertentangan dengan syariat Islam.12
Dari ketiga kajian pustaka diatas, bahwa jelas terdapat perbedaan
dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni dengan judul “Wanprestasi
Pada Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.
11 Epy Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa
Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2008).
12 Anisatur Rohmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan
10
Pasuruan)”. Perbedaanya terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian
ini, penulis ingin memfokuskan pada wanprestasi praktek perjanjian bagi
hasil pengolahan tanah dan bagaimana analisis hukum Islamnya.
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan
penelitian ini penulis memiliki tujuan:
1. Mengetahui praktek perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
2. Memahami analisis hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian bagi
hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso
Kab. Pasuruan.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari penelitian yang berjudul “Wanprestasi Pada Perjanjian Bagi
Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”, diharapkan
dapat memberikan manfaat serta dapat dipergunakan untuk:
1. Dari aspek teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas
wawasan serta ilmu pengetahuan terkait perjanjian pengolahan tanah dan
dapat dijadikan sumber pengetahuan baik dalam ranah formal maupun
11
khazanah keilmuan bagi peneliti-peneliti, khususnya mahasiswa jurusan
muamalah yang ingin mendalami masalah yang terkait dengan perjanjian
pengolahan tanah.
2. Dari aspek praktis
Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang terlibat dalam
praktek perjanjian pengolahan tanah untuk kemudian bisa diterapkan
sesuai dengan akad yang diperbolehkan dalam fiqh mu’a>malah. Di sisi
lain, diperuntukkan bagi peneliti berikutnya sebagai perbandingan untuk
membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
G. Definisi Operasional
Untuk lebih memahami penelitian yang berjudul “Wanprestasi Pada
Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”,
maka penulis perlu memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang ada di
dalam judul penelitian yakni sebagai berikut:
1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan
berdasarkan al-Qur’an, Hadist dan pendapat ulama’.13 Yang dalam hal ini
adalah muza>ra’ah.
2. Wanprestasi : Kelalaian; kealpaan.14 Dalam skripsi ini yaitu suatu
pelanggaran dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian bagi hasil
pengolahan tanah.
12
3. Perjanjian Bagi Hasil : Kontrak kerja sama antara dua pihak dimana
setiap pihak membagi keuntungan secara sama atau sesuai kesepakatan.
Dalam hal ini adalah perjanjian pengolahan tanah yang terjadi di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang dilakukan antara
pemilik tanah dengan pengelola berdasarkan kesepakatan pembagian hasil
di antara kedua belah pihak.
H. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah field research (lapangan) dapat langsung
memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menghubungkan peneliti
dengan responden secara langsung.
Untuk menghasilkan gamabaran yang maksimal terkait “Wanprestasi
Pada Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”,
dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langka-langka tersebut
terdiri atas:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Data tentang perjanjian bagi hasil pengolahan tanah di Dusun Darah
Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
13
b. Data tentang proses pengolahan tanah yang dilakukan di Dusun Darah
Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
c. Data tentang mekanisme pembagian bagi hasil.
2. Sumber data
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sekunder:
a. Sumber Data Primer
Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan
objek penelitian.15 Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu
melalui wawancara dengan pemilik tanah dan pengelola di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau
melengkapi dari sumber primer16 yang di dapat melalui wawancara
dengan aparat/pemuka desa. Selain itu sumber bisa berupa dokumen,
buku, dan karya ilmiah yang mendukung sumber primer. Diantara
sumber buku yang penulis jadikan rujukan diantaranya yakni:
1) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 6 (Jakarta:
Gema Insani, 2011).
2) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) (Jakarta:
Kencana, 2013).
15 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),
31.
14
3) Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i (Muamalat, Munakahat,
Jinayat) buku 2 (Bandung: Cv Setia Pustaka, 2007).
4) Abdul Rahman Ghazaly, et.al. Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana,
2010).
5) Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010).
6) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2000).
7) Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi,
Matan Al-Bukhari Mashkul Bih}a>thiayah As-Sindi, Juz 2
(Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Mah}ramayn, t.t.).
3. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara
lain:
a. Observasi
Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang
fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan
pencatatan.17 Penulis mengamati bagaimana praktek pengolahan tanah
di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
b. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara
15
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.18
Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan
tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti, yaitu pemilik tanah dan pengelola di Dusun Darah Desa
Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupaka pengumpulan data yang diperoleh
melalui dokumen-dokumen.19 Dalam hal ini dokumen yang terkumpul
adalah data perjanjian pengolahan tanah, gambaran umum Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan serta
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan bahasan penelitian.
4. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.20
Dalam hal ini data penelitian di peroleh dari buku, kitab, internet dal
lainnya. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah
mengolah data melalui metode:
a. Editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah
dikumpulkan. Sanapah Faisal mengartikan “mengedit data” dengan
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),
186.
19 Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi
Askara, 1996), 73.
16
kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari segi kesempurnaannya,
kelengkapan jawaban yang diterima, kebenaran cara pengisiannya,
kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi relevasinya bagi
penelitian, maupun keragaman data yang diterima peneliti.21 Yaitu
dengan memeriksa data-data tentang perjanjian bagi hasil di Dusun
Darah Desa Sadengrejo Kec. rejoso Kab. Pasuruan.
b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan
sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang
relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.
c. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait hukum Islam
terhadap wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah.
5. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis
menggunakan analisis secara deskriptif analisis, yaitu bertujuan
mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan
data-data tentang perjanjian bagi hasil pengolahan tanah yang didapat
dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Kemudian
dikembangkan dengan pola pikir induktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta
yang bersifat khusus dari hasil riset dan terahir diambil kesimpulan yang
bersifat umum.
17
I. Sistematika Pembahasan
Terdapat lima bab pembahasan dalam sistematika pembahasan
penelitian ini yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami.
Berikut lima bab yang tersusun:
Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang
permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian serta sitematika pembahasan.
Bab kedua membahas mengenai landasan teori tentang muza>ra’ah,
meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam
dalam akad muza>ra’ah.
Bab ketiga yaitu membahas tentang hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis tentang wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan
tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang
meliputi: gambaran umum Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.
Pasuruan meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri atas keadaan
geografis, keadaan sosial dan keagamaan, pendidikan dan keadaan ekonomi.
Mendeskripsikan tentang bagaimana terjadinya perjanjian pengolahan tanah
tersebut, wanprestasi pada perjanjian bagi hasil, alasan-alasan terjadinya
wanprestasi perjanjian bagi hasil pengolahan tanah.
Bab keempat merupakan analisis, yakni analisis praktek perjanjian
18
hasil pengolahan tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo kec. Rejoso Kab.
pasuruan.
Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran
BAB II
MUZA>RA’AH
A. Pengertian Muza>ra’ah
Secara etimologis muza>ra’ah adalah kerjasama dibidang pertanian
antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari
pemilik tanah.1 Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, muza>ra’ah adalah
kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap,
dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap
untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil
panen. Dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai “paruhan”.2
Kata muza>ra’ah dalam arti bahasa berasal dari wazn maufa’alah dari
akar kata zara’a yang sinonimnya: anbata, seperti dalam kalimat:
ُاََََو َُتَبْ نَأ : َعْرَزلا ُّللا َعَرَز
“Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan : artinya Allah
menumbuhkannya dan mengembangkannya”.3
Sedangkan pengertian muza>ra’ah secara iatilah diartikan sebagai
berikut:
ْلا ِِ ِعِراَزلاَو ِكِلاَمْلا ِكاَِِْشاِب ِةَيِعاَرِزلا يِضاَرَْْا ِلَاْغِتْسِا ٌةَقْ يِرَط : ُةَعَراَزُمْلَا
, ِل َاْغِتْس
ُمَسْقَ يَو
.ُفْرُعْلا ِوأ ُدْقَعْلا اَهُ ِ يَعُ ي ِةَبْسِِب اَمُهَ ْ يَ ب ُجِتاَلا
“Muza>ra’ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi antara mereka
1 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 275.
2 Muhmmad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (dari teori ke praktik) (Jakarta: Gema Insani, 2001),
99.
3 Ahmad Shalaby, Kamus Lengkap 3 Bahasa (Arab-Inggris-Indonesia) (Surabaya: Giri Utama,
20
berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjnjian atau berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan)”.4
Terdapat beberapa definisi muza>ra’ah yang dikemukakan oleh para
ulama fiqh sebagai berikut:
1. Ulama Hanafiyah5 memberikan definisi muza>ra’ah sebagai berikut:
ِةَعَراَزُمْلا ىَلَع ِدْقَعْلا ِنَع ٌةَراَبِع : ٍعْرَش ِفْرُع َِِْو
َُل ِةَعْوُضْرَمْلا ِِطِئاَرَشِب ِجِراَْْا ِضْعَ بِب
اًعْرَش
“Dalam istilah syara’ muza>ra’ah adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama pengolahan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara’”.
2. Ulama Malikiyah6 mendefinisikan muza>ra’ah sebagai berikut:
ِعْرَزلا ِِ ُةَكْرِشلا اَهَ نَأِب
“Sesungguhnya muza>ra’ah itu adalah syirkah (kerja sama) didalam menanam tanaman (mengelola tanah)”.
3. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan muza>ra’ah sebagai berikut:
ُةَعَراَزُمْلَا
َنِم ُرْذَبءلا َنْوُكَي ْنَأ ىَلَع اَهْ ِم ُجُرََْ اَم ِضْعَ بِب ِضْرَْْا ِِ ِلِماَعْلا ُةَلَماَعُم َيِ
ِكِلاَمْلا
“Muza>ra’ah adalah transaksi antara pengelola dengan pemilik tanah untuk mengolah tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah”. 7
َنِم ُرْذَبْلاَو اَهْ ِم ُجُرََْ اَم ِضْعَ بِب ِضْرَْْا ُلَمَع
ِلِماَعْلا
“Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”.8
4 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 391. 5 Ibid., 392.
6 Ibid. 7 Ibid., 393.
21
4. Ulama Hanabilah9 memberikan definisi muza>ra’ah sebagai berikut:
ِضْر ْْا ُبِحاَص َعَفْدَي ْنأ َيِ ُةَعراَزُمْلا
اَهِعْرَزِب ُمْوُقي يِذَلا ِلِماَعْلِل َُضْرأ ِةَعاَرِزِل ِةَِِاَصلا
ِلْوُصْحَمْلا ِِ ٌمْوُلْعَم ٌعاَشَم ٌءْزُج َُل َنْوُكَي ْنأ ىَلَع اًضْيأ ُُرُذْبَ ي يِذَلا َبَِْا َُل ُعَفْدَيَو
. ِثُل ثلا ِوأ ِفْصِلاَك
“Muza>ra’ah adalah menyerahkan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada pengelola yang akan menanaminya, dengan menyerahkan bibit yang akan ditanaminya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (separuh) atau sepertiga”.
Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah, salah seorang ulama
Hanabilah, memberikan definisi muza>ra’ah sebagai berikut:
ُعْرَزلاَو اَهْ يَلَع ُلَمْعَ ي ْوأ اَهُعَرْزَ ي ْنَم ََإ ِضْر ْْا ُعْفَد ِةَعَراَزُمْلا ََْعَم
اَهَ ْ يَ ب
“Arti muza>ra’ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau akan mengolahnya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua (pemilik dan pengelola)”.
Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab
tersebut dapat diambil intisari bahwa muza>ra’ah adalah suatu akad kerja
sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan pengelola, dimana
pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si pengelola untuk
ditanami dan dipelihara10 dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya
menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit yang akan ditanam boleh
dari pemilik tanah dan boleh berasal dari pengelola. Dan dalam kebiasaan
Indonesia disebut sebagai “paruhan”.11
9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 393.
10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), 99.
22
B. Dasar Hukum Muza>ra’ah
1. Al-Qur’an
Kerjasama dalam bentuk muza>ra’ah menurut kebanyakan ulama
fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya itu, disamping dapat
dipahami dari keumuman firma Allah SWT yang menyuruh saling tolong
menolong dalam surat Al- Maidah ayat 2:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah”.12
2. Hadis
Juga secara khusus hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari
dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah
tanahnya secara muza>ra’ah dengan rasio bagi hasil : , ¼:¾, ½:½, maka
Rasulullah Saw pun bersabda:
ُلوُسَر َلاَق
ْنِإَف ُاَخَأ اَهْحَْمَيِل ْوَأ اَهْعَرْزَ يْلَ ف ٌضْرَأ َُل ْتَناَك ْنَم َمَلَسَو ِْيَلَع َُللا ىَلَص َِللا
( .َُضْرَأ ْكِسْمُيْلَ ف َََأ
)ىراخبلا اور
“Barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk dikelola. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”.13 (HR. Bukhari)
3. Ijma’
Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada
satupun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), 106. 13 Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi, Matan Al-Bukhari Mashkul
23
muza>ra’ah dengan pembagian hasil , dan ¼”. Hal ini telah dilakukan
oleh Sayyidina Ali, Sa’ad bin Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul
Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.14
C. Rukun Muza>ra’ah dan Sifat Akadnya
Jumhur ulama yang membolehkan akad muza>ra’ah mengemukakan
rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun
muza>ra’ah menurut mereka adalah sebagai berikut:
1. Pemilik tanah.
2. Petani penggarap (pengelola).
3. Objek akad (tanah yang di kelola) memiliki dua kemungkinan, yaitu
manfaat tanah atau pekerjaan pengelola. Yang pertama berarti pihak
pengelola menyewa tanah, sedangkan yang kedua berarti pihak pemilik
tanah mempekerjakan atau mengupahnya untuk mengolah lahannya.
Kedua hal ini dalam fiqh disebut akad ija>rah. Menurut ulama Hanafiyah,
akad muza>ra’ah pada awalnya adalah bentuk akad ija>rah, sedangkan
pada akhirnya berupa shirkah (kerja sama, patungan, joinan). Apabila
benihnya dari pihak pengelola, maka objek akadnya berarti kemanfaatan
tanah. Sedangkan jika benihnya dari pemilik lahan, maka objek akadnya
berarti kemanfaatan pekerja atau pengelola.
4. Ijab dan kabul. Yaitu pemilik tanah berkata kepada pihak pengelola,
“Saya serahkan tanah pertanin saya ini kepada engkau untuk dikelola
24
dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Lalu pihak pengelola menjawab,
“Saya terima atau saya setuju tanah pertanian ini untuk dikelola dengan
imbalan hasilnya dibagi dua”. Namun ulama Hanabilah mengatakan
bahwa penerimaan (kabul) akad muza>ra’ah tidak perlu dengan
ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung
mengelola tanah tersebut.15
Adapun sifat akad muza>ra’ah menurut para ulama fiqh sebagai
berikut:
1. Menurut ulama Hanafiyah adalah sama seperti akad-akad syirkah yang
lain, yaitu statusnya adalah ghairu la>zim (tidak berlaku mengikat).
2. Sementara itu ulama Malikiyah mengatakan bahwa akad muza>ra’ah
statusnya sudah menjadi la>zim (berlaku mengikat) jika benih telah
ditaburkan atau telah ditanam.
3. Pendapat yang mu’tamad menurut ulama Malikiyah adalah, bahwa
bentuk akad syirkah (kerjasama, joinan) dalam hal harta statusnya sudah
menjadi la>zim (mengikat) jika telah ada ijab qabul.
4. Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa akad muza>ra’ah
statusnya ghairu la>zim (tidak berlaku mengikat), sehingga salah satu
pihak bisa membatalkan dan akad menjadi batal dengan meninggalnya
salah satu pihak.
15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jaminan (Kafa>lah), Pengalihan Utang
25
D. Syarat-Syarat Muza>ra’ah
1. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad
Syarat-syarat muza>ra’ah ada beberapa bagian yaitu, ada syarat
untuk pihak yang melakukan akad, syarat untuk benih yang ditanam,
syarat untuk tanah pertanian, syarat untuk hasil panen, syarat untuk objek
akad, syarat untuk alat pertanian yang digunakan, dan syarat masa
penanaman.
a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah
baligh dan berakal. Karena akal adalah syarat kelayakan dan
kepatutan di dalam melakukan ketasharufan (tindakan).16
b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas,
sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan menghasilkan.
c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian yaitu sebagai berikut:
1) Menurut adat dan kalangan petani, tanah itu boleh dikelola dan
menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga
tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad
muza>ra’ah tidak sah.
2) Batas-batas tanah itu jelas.
3) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengelola untuk
dikelola. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah
tanah pertanian itu maka akad muza>ra’ah tidak sah.
d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
26
1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa
boleh ada pengkhususan.
3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: ½, , atau ¼, sejak dari
awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan
penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara
mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung,
karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau
dapat juga jauh melampaui jumlah itu. 17
e. Syarat yang menyangkut objek akad muza>ra’ah yaitu harus sesuai
dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut shara’ maupun
‘urf (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu
mengambil manfaat tenaga pengelola dimana pemilik tanah
mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah dimana
pengelola yang mengeluarkan bibitnya.
f. Syarat yang menyangkut alat pertanian yang digunakan untuk
bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern
haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat
tersebut dijadikan tujuan, maka akad muza>ra’ah menjadi fa>sid (rusak).
18
g. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam
akad sejak semula, karena akad muza>ra’ah mengandung makna akad
27
ija>rah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian
hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk
penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat
setempat.19
2. Menurut Ulama Malikiyah
Ulama Malikiyah mensyaratkan tiga hal untuk akad muza>ra’ah,
yaitu:
a. Harus menyewakan lahannya dengan ongkos sewa berupa emas,
perak, atau binatang. Juga bibitnya harus dari kedua belah pihak,
yaitu pihak pemilik tanah dan pihak pengelola. Jika benihnya dari
salah satu pihak saja sedangkan tanahnya milik pihak yang lain, maka
akad muza>ra’ah rusak atau tidah sah.
b. Modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak selain benih harus
sepadan. Dan keuntungan yang di peroleh masing-masing sesuai
dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
c. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis, seperti gandum, kacang
dan lain sebagainya. Apabila benih yang dikeluarkan oleh kedua
belah pihak berbeda jenisnya, maka akad muza>ra’ah tidak sah dan
masing-masing dari kedua belah pihak mendapatkan sesuai dengan
apa yang dihasilkan oleh benihya.
Kesimpulannya adalah bahwa ulama Malikiyah mensyaratkan
benihnya harus dari kedua belah pihak, benih mereka berdua harus
28
sejenis, keuntungan dan modal yang dikeluarkan kedua belah pihak
(selain benih) harus sepadan, muza>ra’ah tidak boleh dengan biaya yang
diambil dari sebagian hasil panen yang didapatkan, akan tetapi harus
dengan harta lain selain hasil panen. Jika diperhatikan syarat ini sangat
ketat dan sulit untuk diterapkan pada realita muza>ra’ah yang berlaku. 20
3. Menurut Ulama Syafi’iyah
Adapun ulama Syafi’iyah tidak mensyaratkan dalam muza>ra’ah
hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola. Menurut mereka
muza>ra’ah adalah pengolahan tanah dengan imbalan hasil yang keluar
dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.21
4. Menurut Ulama Hanabilah
Ulama Hanabilah membolehkan muza>ra’ah dengan upah sebagian
dari hasil panen tanah yang dikelola. Mereka juga tidak mensyaratkan
bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapatkan harus sama.
Sebagaimana ulama Syafi’iyah, mereka mensyaratkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Benihnya harus dari pihak pemilik tanah menurut pendapat madzhab
Hanbali. Namun ada revisi riwayat dari Imam Ahmad yang
menunjukkan bahwa boleh saja benihnya dari pihak pengelola.
b. Mereka mensyaratkan bagian masing-masing harus diketahui dan
ditentukan secara jelas, jika tidak maka akad muza>ra’ah menjadi
tidak sah.
29
c. Mereka juga mensyaratkan jenis dan kadar benih harus diketahui.
Sebab muza>ra’ah adalah suatu kesepakatan atas suatu pekerjaan, oleh
karena itu tidak boleh jika tidak diketahui jenis dan kadarnya.22
E. Macam-Macam Muza>ra’ah
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani
menyatakan bahwa , muza>ra’ah ada empat macam, tiga diantaranya adalah
sah, sedangkan yang satunya lagi tidak sah. Bentuk-bentuk tersebut adalah
sebagai berkut:
1. Apabila tanah dan benih berasal dari salah satu pihak (pemilik tanah),
sedangkan pekerjaan pengolahan tanah dan alat-alat untuk mengolah
tanah dari pihak yang lain (pengelola).23
Bentuk muza>ra’ah ini adalah boleh, sehingga disini pemilik tanah
dan benih statusnya berarti mempekerjakan pihak pengelola, sedangkan
binatang yang digunakan untuk membajak itu memeng menjadi
tanggungan pihak pengelola sebagai konsekuensi dirinya dipekerjakan
untuk mengolah tanah, sebab binatang tersebut adalah alat untuk
melakukan pekerjaannya.
2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan alat, benih
dan pengolahan tanah berasal dari pengelola.
30
Bentuk muza>ra’ah ini juga boleh, dan status pihak pengelola disini
adalah menyewa tanah dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen
tanah yang dikelola.24
3. Apabila tanah, alat dan benih dari salah satu pihak, sedangkan
pengolahan tanah dari pihak yang lain.
Bentun muza>ra’ah ini juga boleh, dan status pemilik tanah disini
adalah mempekerjakan pihak pengelola dengan upah sebagian dari hasil
panen tanah yang dikelola.25
4. Apabila tanah dan alat dari salah satu pihak, sedangkan modal benih dan
pengolahan tanah dari pihak yang lain.
Yang terakhir adalah bentuk muza>ra’ah yang tidak sah menurut
zahir riwayat. Karena seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut
adalah penyewaan tanah, maka persyaratan alat yang dibutuhkan untuk
membajak dan mengolah tanah menjadi tanggungan pihak pemilik tanah,
adalah merusak akad sewa tersebut dan menjadikannya tidak sah. Karena
tidak mungkin menjadikan posisi alat tersebut mengikuti lahan, atau
dengan kata lain tidak mungkin menjadikan penyediaan fasilitas berupa
alat pembajak sebagai konsekuensi atau prasyarat di dalam menyewakan
suatu lahan, karena perbedaan fungsi dan kegunaan antara lahan dan alat.
Sedangkan fungsi dan kegunaan lahan adalah untuk menumbuhkan,
sementara alat fungsi dan kegunaannya adalah untuk bekerja dan
membajak tanah.
24 Ibid., 279.
31
Seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut adalah akad
mempekerjakan pihak pengelola, maka adanya ketentuan modal benih
menjadi tanggungannya adalah merusak akad. Karena tidak
dimungkinkannya mejadikan penyediaan benih oleh pihak yang
dipekerjakan untuk mengolah tanah sebagai konsekuensi dirinya
dipekerjakan.
Berdasarkan hal ini, maka suatu akad muza>ra’ah tidak sah jika ada
ketentuan fasilitas peralatan atau alat pembajak, atau pekerjaan
mengolah tanah menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Begitu juga
muza>ra’ah tidak sah jika ada ketentuan bahwa semua hasil panennya
adalah untuk salah satu pihak saja, atau ada ketentuan bahwa pemanenan
atau penebangan, mengangkut, merawat dan menjaga hasil panen adalah
menjadi tanggungjawab pihak pengelola. Karena semua itu tidak
memiliki kaitan dengan kepentingan tanaman atau dengan kata lain tidak
termasuk hal-hal yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah.26
F. Hukum-Hukum Muza>ra’ah yang S}ahih dan Fa>sid
1. Hukum muza>ra’ah yang s}ahih
Muza>ra’ah yang s}ahih menurut ulama Hanafiyah memiliki
sejumlah konsekuensi hukum sebagai berikut:
32
a. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah seperti
biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan adalah menjadi
beban pihak pengelola.
b. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan tanaman seperti pupuk,
membersihkan rumput liar, pemanenan dan pengangkutan adalah
menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar
bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing dari hasil tanaman
tersebut.
c. Hasil tanaman yang diperoleh dibagi anrata kedua belah pihak sesuai
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati.27 Hal ini
sesuai dengan Hadis Nabi Saw:
ْنَعَو
ُّللا َلْوُسَر َنأ َُْع ُّللا َيِضَر َِِزُمْلا ٍفْوَع ُنْب وُرْمَع
َمَلَسَو ِْيَلَع َُللا ىَلَص
: َلاَق
ىَلَع َنْوُمِلْسُمْلاَو ,اًماَرَح َلَحأ ْوأ ًا َاَح َمَرَح اًحْلُص َاإ َِْْمِلْسُمْلا ََْْ ب ٌزِئاَج ُحْلصلا
ْرَش َاإ ْمِهِطْوُرُش
.اًماَرَح َلَحأ ْوأ ًا َاَح َمَرَح اًط
“Dari Amr bin Auf Al-Muzani Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian dibolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam boleh berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.28 (HR. At- Tirmidzi)
d. Akad muza>ra’ah menurut ulama Hanabilah tidak mengikat (ghairu
la>zim), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat
(la>zim) apabila bibit telah disemaikan (ditanam). Menurut ulama
Hanafiyah dilihat dari sisi pemilik benih, akad muza>ra’ah termasuk
27 Ibid., 572.
28 Tirmidzi, Kitab Hukum-hukum, Bab Perdamaian antara, Hadis No. 1272, Lidwa Pustaka
33
ghairu la>zim, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk la>zim.
Dengan demikian, dengan demikian akad muza>ra’ah tidak boleh
dibatalkan kecuali karena uz}ur (alasan).
e. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk
dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi,
apabila tidak ada kesepakatan maka pengelola lah yang paling
bertanggungjawab untuk menyiram dan memelihara tanaman
tersebut. 29
f. Dibolehkan menanbah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan
dalam akad.30
g. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum mencapai masa
panen, maka tetap dibiarkan berlaku sampai masa panen dan tidak
ada kewajiban apa-apa atas pihak pengelola, karena disini akad ija>rah
masih berlaku karena masanya masih tersisa.31
Muza>ra’ah yang s}ahih menurut ulama Syafi’iyah sebagaimana
telah dikemukakan dimuka tidak membolehkan muza>ra’ah kecuali ikut
kepada musa>qa>h. Apabila muza>ra’ah dilakukan tersendiri maka hasilnya
untuk pemilik tanah, sedangkan pengelola memperoleh upah yang
sepadan atas pekerjaanya dan alat-alatnya.32
29 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 402.
30 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalat (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2001), 211. 31 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ..., 575.
34
2. Hukum Muza>ra’ah yang Fa>sid
Muza>ra’ah yang fa>sid menurut ulama Hanafiyah ada beberapa
ketentuan, yaitu sebagai berikut:
a. Tidak ada kewajiban apapun bagi pengelola dari pekerjaan muza>ra’ah
karena akadnya tidak sah.
b. Hasil yng diperoleh dari pengolahan tanah semuanya untuk pemilik
benih, baik pemilik tanah maupun pengelola. Dalam masalah ini
ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah sepakat dengan ulama
Hanafiyah, yaitu bahwa apabila akadnya fa>sid, maka hasil tanaman
untuk pemilik benih.
c. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola
memperoleh upah atas pekerjaannya, karena fa>sid-nya akad
muza>ra’ah tersebut. Apabila benihnya berasal dari pengelola maka
pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam
dua kasus ini satu akadnya menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus
yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik
tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam
kasus yang ke dua, tidak semua hasi pengolahan tanah untuk
pengelola, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkan
dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan sisanya
disedekahkan oleh pengelola.
d. Dalam muza>ra’ah yang fa>sid, apabila pengelola telah mengolah tanah
35
meskipun tanah yang dikelola tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini
karena muza>ra’ah statusnya sebagai akad ija>rah (sewa-menyewa).
Adapun dalam muza>ra’ah yang s}ahih, apabila pengolahan tanah
tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka pengelola dan pemilik
tanah sama sekali tidak mendapatka apa-apa.
e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan
(ujratul mithli) dalam muza>ra’ah yang fa>sid harus ditetapkan dengan
jumlah yang disebutkan, sesuai persetujuan kedua belah pihak.
Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan
(ujratul mithli) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran
harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh pengelola. 33
G. Berakhirnya Akad Muza>ra’ah
Muza>ra’ah ada kalanya berakhir secara normal, yaitu setelah tercapai
maksud dan tujuan dari muza>ra’ah yang dilakukan. Atau ada kalanya
berakhir secara tidak normal, yaitu dengan mengakhiri dan membatalkannya
sebelum maksud dan tujuan dari muza>ra’ah yang dilakukan terwujud.
Keterangan berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:
1. Berakhirnya masa atau jangka waktu muza>ra’ah yang ditetepkan. Jika
jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya.
2. Salah satu pihak meninggal dunia, sebagaimana akad ija>rah juga berakhir
dan menjadi batal karena salah satu pihak meninggal dunia. Baik
36
meninggalnya itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya,
baik tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Ini adalah
pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama
Malikiyah dan ulama Syafi’iyah mengatakan, akad muza>ra’ah
sebagaimana akad ija>rah, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu
pihak.
3. Menfasakh (membatalkan) akad muza>ra’ah karena ada suatu uz}ur. Jika
terjadi suatu pembatalan akad sebelum akad itu berlaku mengikat, maka
muza>ra’ah yang ada berakhir. 34Diantara uz}ur atau alasan tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga
tanah yang dikelola harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta
yang lain selain tanah tersebut.
b. Timbunya uz}ur (alasan) dari pihak pengelola, misalnya sakit atau
bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fi> sabi>lilla>h, sehingga ia
tidak bisa mengelola tanah tersebut.35
BAB III
DEKRIPSI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN
TANAH di DUSUN DARAH DESA SADENGREJO KEC. REJOSO KAB.
PASURUAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis Desa Sadengrejo Kec. Rejoso
Pada umumnya keadaan wilayah suatu daerah sangat
menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi
semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu
wilayah satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang menentukan
berbedaan kondisi masyarakat tersebut yaitu faktor geografis,
begitupula yang terjadi di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan
yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Dilihat dari letak geografis
Desa Sadengrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa timur, adapun
jarak Desa Sadengrejo ke Ibu Kota Kecamatan 2 Km (arah selatan)
dengan jarak tempuh 15 menit, dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 5 km
(arah timur) dengan jarak tempuh 30 menit,jarak dengan luas wilayah
200,45 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa Sadengrejo yaitu sebagai
berikut:
- Sebelah Utara : Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso
- Sebelah Selatan : Desa Tenggilisrejo Kecamatan Gondangwetan
39
- Sebelah Timur : Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso1
Gambar 3.1
1 Buku Rencana Pembagunan Jangka Menengah (RPJM-Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso
[image:47.595.141.511.134.678.2]
40
Desa Sadengrejo merupakan dataran rendah dengan suhu 30ºC
yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan
pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga
dengan desa Sadengrejo yang terdiri dari dua musim, yaitu musim
kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September,
dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret.
2. Kecamatan Rejoso
Secara Astronomis Kecamatan Rejoso terletak antara :
a. 112 33’ 55” - 113 30’ 37” Bujur Timur
b. 70 32’ 34” - 80 30’ 20” Lintang Selatan
Secara Geografis atau secara administrative (kewilayahan) Kecamatan Rejoso berbatasan dengan berbagai wilayah, antara lain sebagai berikut:2
Batas Wilayah Kecamatan
Sebelah Barat Kecamatan Bugul Kidul Kota
Pasuruan
Sebelah Selatan Gondangwetan dan Winongan
Sebelah Timur Kecamatan Lekok dan Grati
Sebelah Utara Selat Madura dan Kecamatan
Lekok
41
B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa
Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan
1. Latar Belakang dan Faktor Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan
Tanah
Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan
mengenai perjanjian pengolahan tanah di Dusun Dara Desa Sadengrejo
Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, seperti yang dijelaskan di atas bahwa Desa
Sadengrejo secara geografis mempunyai lahan pertanian yang cukup luas
dan mempunyai struktur tanah yang subur, termasuk dusun Darah
sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai
petani. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan bisa bekerja pada petani
pemilik lahan atau melakukan perjanjian pengolahan tanah untuk
mendapatkan upah, imbalan ataupun bagi hasilnya.
Dalam hukum Islam perjanjian pengolahan tanah bukan hanya
peristiwa yang penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka
yang ingin menyambung hidup, tetapi perjanjian pengolahan tanah
dengan sistem bagi hasil merupakan perjanjian yang sangat berarti yang
disebabkan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani.
Tanah adalah sumber daya yang perlu dipertahankan kesuburanya,
agar tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Pemakaian tanah untuk
pertanian secara terus-menerus dapat membuat para petani mendapatkan
42
matapencaharian mayoritas penduduk Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.
Pasuruan.
Untuk seorang petani desa memanfaatkan tanah sebagai
lingkungan tempat tinggal dan sebagai sumber penghidupan, karena
dengan demikian petani tersebut dapat memungut hasilnya sebagai
bahan untuk berdagang. Hasil ini bisa dimanfaatkan sendiri sebagai pola
hidup dan di jual untuk memenuhi kepentingan yang lain. Kegiatan
pengolahan tanah akan sangat mempengaruhi proses budi daya
selanjutnya di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
Biasanya warga Dusun Darah Desa Sadengrejo dalam mengelola
tanah dilakukan secara mekanis, terutama pada lahan yang
memungkinkan. Tujuannyauntuk menciptakan kondisi tanah menjadi
lebih baik, kemudian membunuh gulma dan tanaman yang tidak
diinginkan untuk memperlancar kegiatan bertani.
Selain itu dalam usaha pertanian atau bercocok tanam tidak hanya
dilakukan sendiri, melainkan ada beberapa pihak yang turut ikut serta.
Mereka melakukan kerjasama dengan kesepakatan yang tidak merugikan
kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, mereka yang memiliki
tanah/lahan minta pertolongan kepada pihak yang membutuhkan
pekerjaan untuk menggarap/mengelola tanah pertaniannya dengan
imbalan bagi hasil.
Kondisi seperti ini pada umumnya terlihat pada masyarakat Dusun
43
dilakukan kebanyakan penduduk Dusun Dara Desa Sadengrejo adalah
bertani. Pada dasarnya tidak semua penduduk melakukan akad kerjasama
pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil.
Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian
pengolahan tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola yang
dituturkan oleh pihak ketiga (saksi) : “Saya datang bersama pihak kedua
(pengelola) kepada pemilik tanah karena melihat lahan kosong sudah
terlalu lama dan menawarkan untuk melakukan kerja sama penanaman
pohon kayu seperti pohon sengon, jati, jabon, dll dengan sistem bagi
hasil”3 di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.Pesuruan.
Dalam kerjasama perjanjian pengolahan tanah di Dusun Darah
pada awalnya membuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam
kerjasama tersebut para pihak menggunakan akad secara lisan tanpa
adanya bukti tertulis, karena para pihak mengandalkan rasa saling
percaya antara satu dengan yang lainnya dan rasa kekeluargaan di Dusun
Darah masih dijunjung tinggi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa semua aspek dalam kehidupan kita
erat kaitannya dengan perjanjian. Dalam kegiatan sehari-hari selalu
berhubungan dengan perjanjian, kesepakatan dan kesepahaman baik yang
berbentuk lisan maupun tertulis.
Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak lepas dari peran
serta orang lain atas kehidupannya. Seperti perjanjian yang telah terjadi
44
di Dusun Darah Desa Sadengrejo. Hal tersebut adalah peran serta atas
tumbuh kembangnya kehidupan, yang mana bisa dalam bentuk perbuatan
sosial maupun perbuatan ekonomi orang lain. Peran serta sosial adalah
perbuatan yang mana antar sesama manusia harus bisa saling
tolong-menolong tanpa pamrih untuk membentuk kehidupan sosial yang
berkualitas, sementara peran serta dalam bentuk perbuatan ekonomi
adalah suatu perbuatan berpamrih atau menuntut suatu pemenuhan
prestasi.
Agar terjaga dan terpenuhinya suatu prestasi dibuatlah suatu
perjanjian yang mengikat dua atau lebih para pihak, bisa dalam bentuk
tertulis maupun lisan. Biasanya perjanjian dalam bentuk lisan ini
dilakukan karena para pihak sudah saling percaya. Begitu pula perjanjian
pengolahan tanah yang dilakukan di Dusun darah Desa sadengrejo Rejoso
pasuruan yang menurut pihak pertama yaitu pihak pemilik tanah, yang
memberikan keterangan dari awal mula terjadinya kesepakatan perjanjian
pengolahan tanah penanaman pohon jati yang terlah terjadi yaitu: dari
pihak pengelola datang kepada pemilik tanah bersama satu orang yang
bernama Basari untuk menawarkan perjanjian pengolahan tanah
penanaman pohon sengon dengan imbalan separuh dari hasil perkebunan
dengan batas waktu pengolahan tanah hingga 5 tahun. Akan tetapi
pengelola melakukan wanprestasi di awal melaksanakan perjanjian, yang
seharusnya menanam pohon sengon menjadi pohon jati. 4
45
Bapak Suroso adalah seorang buruh tani di Dusun Darah Desa
Sadengrejo yang memiliki kemampuan dan keahlian penggarapan tanah
pertanian maupun perkebunan. Dia juga turut andil dalam proses
perawatan tanaman mulai dari penanaman, pengairan, dll. Beliau juga
berkata bahwa memang benar dari pihak kedua (pengelola) memberikan
bibit tanaman pohon jati untuk ditanam.5
Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak
telah memenuhi prestasinya masing-masing, seperti yang telah
diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya
perjanjian tersebut tidak terlaksana d