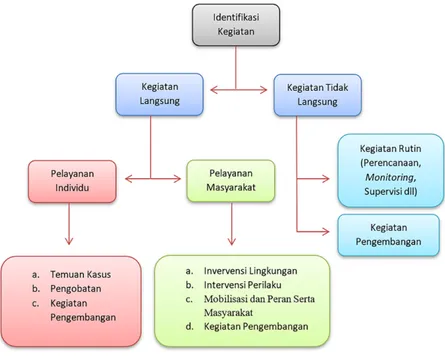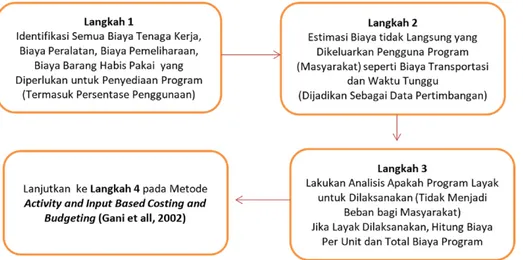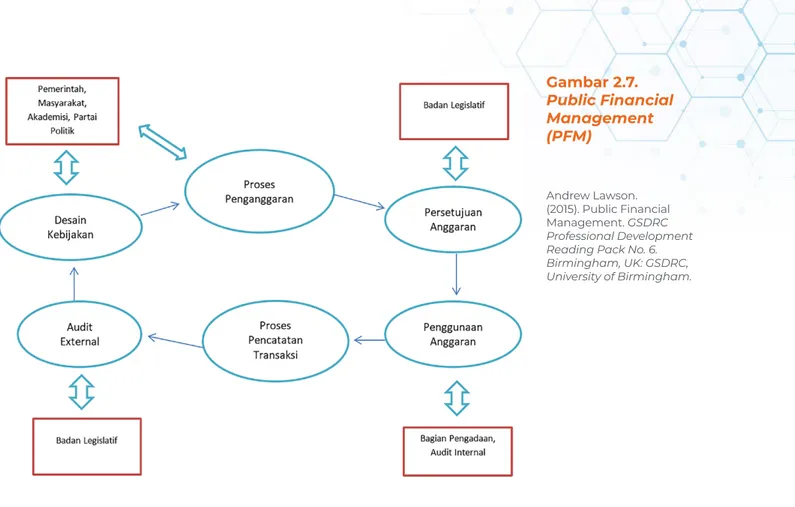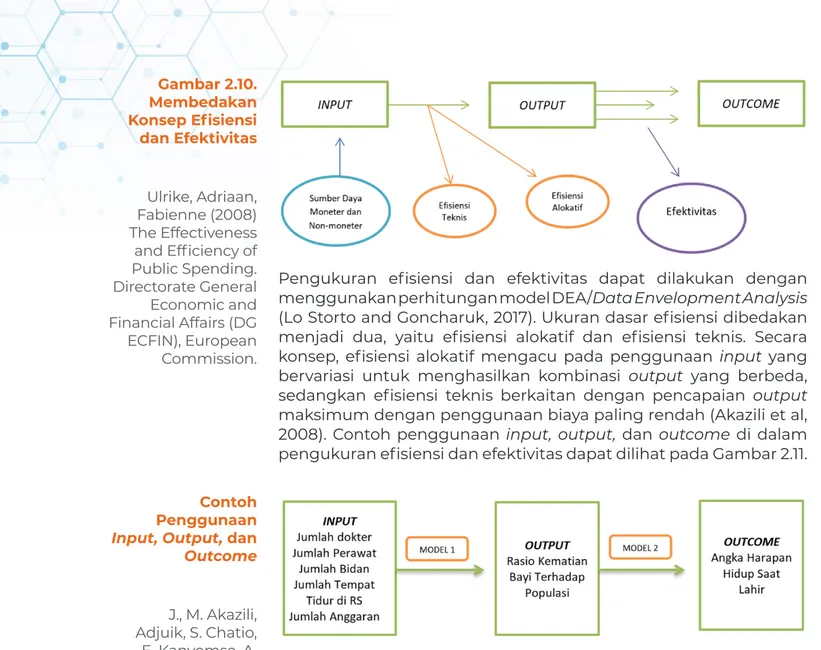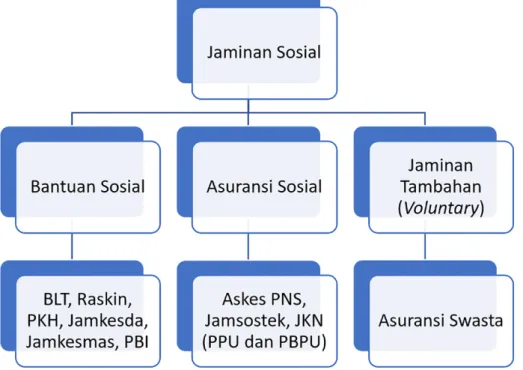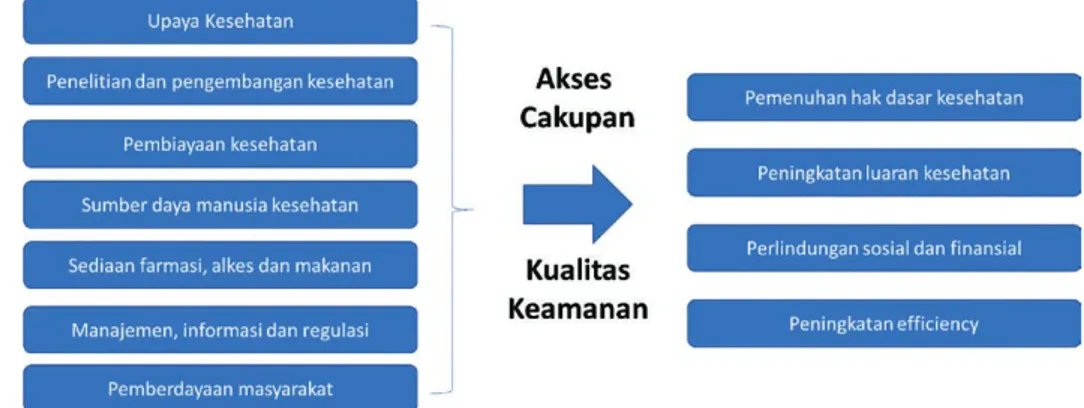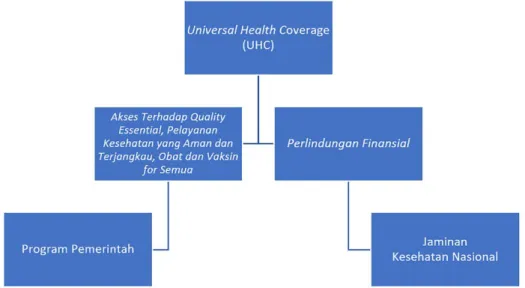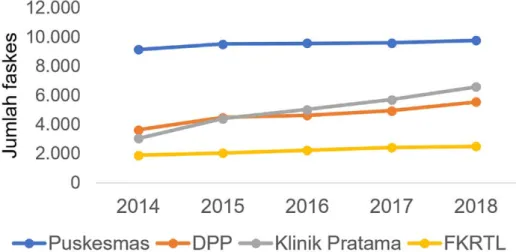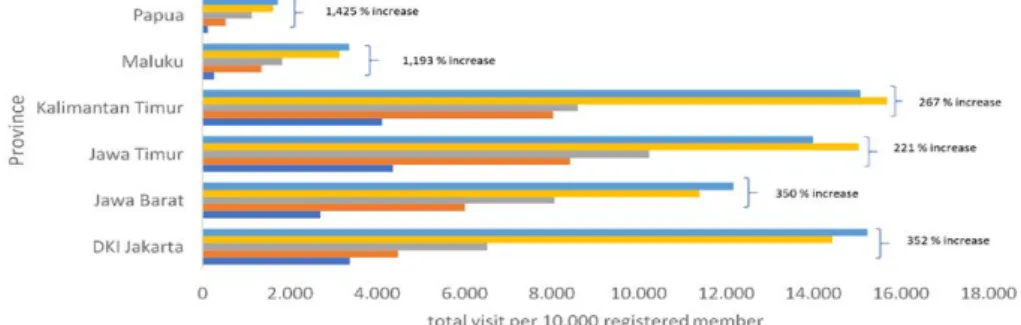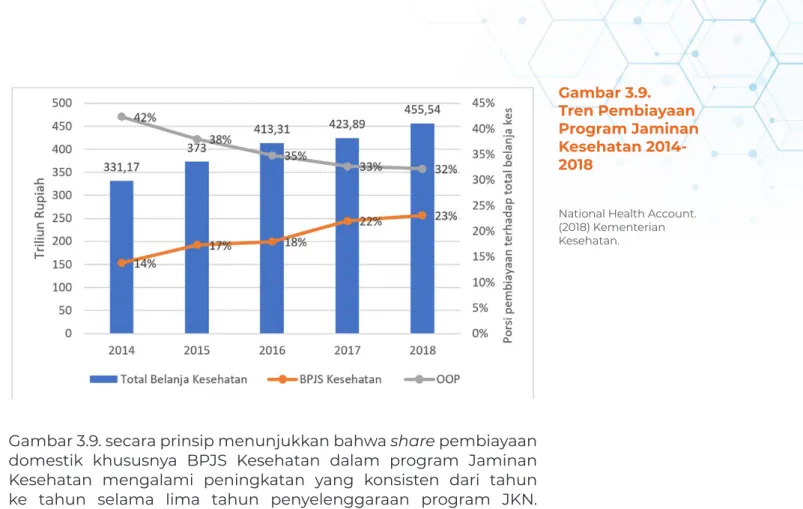KONSEP DAN BEST PRACTICES DI INDONESIA
PEMBIAYAAN KESEHATAN
SERI EK ONOMI KESEHA TAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN
KONSEP DAN BEST PRACTICES DI INDONESIA
SERI EKONOMI KESEHATAN BUKU II
Ery Setiawan Estro Dariatno Sihaloho
Fitriana Yuliawati Giovanni van Empel
Haerawati Idris Adiatma YM Siregar
Penulis
PEMBIAYAAN KESEHATAN
KONSEP DAN BEST PRACTICES DI INDONESIA
SERI EKONOMI KESEHATAN BUKU II
Ery Setiawan Estro Dariatno Sihaloho
Fitriana Yuliawati Giovanni van Empel
Haerawati Idris Adiatma YM Siregar
Seri Ekonomi Kesehatan II
Pembiayaan Kesehatan: Konsep dan Best Pratices
©2021 PPJK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Penulisan buku ini dimungkinkan atas dukungan rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID) yang diproduksi melalui kontrak Health Financing Activity USAID No. 72049719C00002.
Materi yang disampaikan, baik berupa informasi narasi dan visualisasi infografik sepenuhnya menjadi tanggung jawab ThinkWell, dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.
Buku ini dapat diakses dari https://thinkwell.global/ dan http://ppjk.kemkes.go.id/ dan dapat disebarluaskan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang membutuhkannya. PPJK Kementerian Kesehatan RI, United States Agency for International Development (USAID) (2021). Pembiayaan Kesehatan: Konsep dan Best Practices di Indonesia.
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Pengarah : dr. Kalsum Komaryani MPPM
(Kepala PPJK Kementerian Kesehatan RI) Koordinator : Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH
Chief of Party for the Indonesia Health Financing Activity (HFA) Manager Program & : Ryan R. Nugraha
PJ Penerbitan Buku
Penyelia Buku : Adiatma YM Siregar
Penulis : Ery Setiawan, Estro Dariatno Sihaloho, Fitriana Yuliawati, Giovanni van Empel, Haerawati Idris
Penyelaras Akhir : Sonta Frisca Manalu Diterbitkan oleh:
PPJK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cetakan I, September 2021
Ukuran Buku : 21 x 29,6 cm Tebal Buku : xvi, 83 hlm
Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 368.42
Ind Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat p Jenderal
Pembiayaan Kesehatan Concept and Best Practice : Seri ekonomi kesehatan Il.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2021
ISBN 978-623-301-246-1
1. Judul I. HEALTH CARE ECONOMICS AND ORGANIZATIONS II. HEALTHCARE FINANCING
III. INSURANCE, HEALTH IV. HEALTH POLICY
V. GOVERNMENT PROGRAMS
PPJK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-9 Jakarta 12950 Indonesia Phone: (62-21) 5201587, 5201591 Email: kontak@depkes.go.id Website: http://www.depkes.go.id
Cetakan I, Februari 2022
Tim Penyusun
Pengarah : dr. Kalsum Komaryani MPPM
(Kepala PPJK Kementerian Kesehatan RI) Koordinator : Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH
Chief of Party for the Indonesia Health Financing Activity (HFA) Manager Program & : dr. Ryan R. Nugraha, M.P.H.
PJ Penerbitan Buku
Anggota :
Penyelia Buku : Dr. Adiatma Y.M Siregar, S.E., M. Econ. St.
Penulis : Ery Setiawan, S.K.M., M.E., A.A.A.K.
Estro Dariatno Sihaloho, S.E., M.Si.
Fitriana Yuliawati, S.K.M., M.Kes.
dr. Giovanni van Empel, M.Sc.
Dr. Haerawati Idris, S.K.M., M.Kes.
Penyelaras Akhir : Sonta Frisca Manalu dr. Yuli Farianti, M.Epid dr. Ackhmad Afflazir, M.K.M.
Nana Tristiana Indriasari, SE, Ak., M.M.
Amalia Zulfah DHW, S.K.M., M.K.M.
Andhika Nurwin Maulana, S.E., M.S.E.
Mutia Astrini Pratiwi, M.P.A
Kata Pengantar
P
usat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan telah berkomitmen untuk membangun ekosistem pembiayaan dan jaminan kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk inisiatif PPJK untuk secara ekstensif meningkatkan kapasitas akademisi dan praktisi kesehatan dalam bidang pembiayaan kesehatan.Beberapa upaya peningkatan kapasitas yang telah dilakukan, antara lain bimbingan rekapituliasi biaya program Kesehatan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi SISCOBIKES, peningkatan kapasitas Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK), dan tata kelola Casemix Based Groups (CBGs) kepada rumah sakit di seluruh Indonesia.
PPJK menyadari bahwa upaya peningkatan kapasitas dalam bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan tersebut membutuhkan dukungan referensi dan sumber daya pengetahuan yang kuat, baik yang bersumber dari disiplin ilmu maupun praktik kebijakan ekonomi kesehatan. Pengetahuan ini berguna baik sebagai sumber inspirasi panduan dalam pengambilan kebijakan jaminan dan pembiayaan kesehatan.
Karena itulah PPJK menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap USAID- ThinkWell LLC yang telah memprakarsai Health Financing Activity (HFA). Melalui program Young Health Economists (YHE), HFA telah menghimpun tenaga-tenaga ahli muda dalam bidang ekonomi kesehatan dan mendorong mereka untuk memberikan kontribusi keilmuan dan pemikiran bagi peningkatan kualitas pembiayaan dan jaminan kesehatan. Saya berharap YHE dapat menjadi sebuah komunitas praktisi (community of practice) ekonomi kesehatan yang di masa depan dapat menjadi motor penggerak sistem kesehatan, serta hub bagi para ahli dalam mengembangkan tatanan sistem pembiayaan kesehatan.
Seri Ekonomi Kesehatan ini adalah salah satu produk penting YHE. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan para tenaga ahli muda mencurahkan ilmu dan pengalaman mereka dalam buku ini; juga para koordinator penulisan yang telah membantu memastikan kualitas dan kesesuaian buku dengan konteks perkembangan sistem kesehatan Indonesia. Melalui berbagai telaah, analisis kasus, dan refleksi terhadap praktik- praktik pembiayaan kesehatan yang mereka bahas tuntas dalam buku ini, saya berharap buku dapat menjadi katalisator untuk mempercepat proses perbaikan jaminan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Penghargaan serupa juga saya sampaikan kepada Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, organisasi non-pemerintah seperti the World Bank, para akademisi, praktisi kebijakan ekonomi kesehatan baik di rumah sakit, Dinas Kesehatan dan pihak-pihak lain yang telah memberikan berbagai masukan bagi penyempurnaan buku ini. Saya berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut sehingga mampu menghasilkan produk-produk pengetahuan yang berguna bagi peningkatan kualitas kebijakan, pelayanan, jaminan, dan pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Jakarta, 2 Juni 2021
dr. Kalsum Komaryani MPPM.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Kata Pengantar
D
i Indonesia dan negara-negara mitra lainnya di seluruh dunia, United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat bekerja untuk memobilisasi pendekatan seluruh masyarakat dalam mengoptimalkan sistem kesehatan untuk mencapai potensi penuhnya. Kami menyadari perlunya visi bersama untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam lingkungan yang terus berkembang dan berubah. Dengan bekerja sama, kita dapat mempercepat kemajuan menuju sistem kesehatan yang lebih tangguh dan lebih mampu memajukan perawatan preventif, promotif, dan kuratif. Untuk mencapai tujuan yang ambisius tetapi realistis ini, USAID tetap berkomitmen untuk membantu Pemerintah Indonesia membangun dan memperkuat sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan—khususnya dalam program prioritas seperti HIV, TB, dan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.Melalui USAID, Pemerintah Amerika Serikat berinvestasi untuk mengembangkan kekayaan sumber daya manusia Indonesia—termasuk pelajar dan profesional—agar lebih banyak lagi penduduk Indonesia yang dapat menikmati kesehatan yang lebih baik. Health Financing Activity (HFA) USAID memperkuat kemampuan para profesional Indonesia, termasuk pejabat pemerintah, untuk menggunakan fakta dan data dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi pembiayaan dan pengeluaran domestik untuk kesehatan, meningkatkan mekanisme dan kapasitas belanja kesehatan strategis, serta mengoptimalkan manajemen tenaga kesehatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas manajemen pembiayaan kesehatan masyarakat.
Elemen kunci dari kemitraan penting ini adalah program fellowship HFA USAID, yang dirancang untuk memperdalam kemampuan Young Health Economists (YHE) atau ekonom kesehatan muda generasi berikutnya di Indonesia melalui aktivitas akademis yang ketat. Program YHE membekali akademisi, praktisi, dan ekonom kesehatan yang sedang berkembang agar dapat menerapkan prinsip-prinsip kebijakan berbasis bukti dalam merencanakan, menganalisis, dan merancang kebijakan pembiayaan kesehatan dalam sistem kesehatan yang kompleks. Sejauh ini, 30 orang ekonom kesehatan muda yang luar biasa telah lulus dari program ini dan telah diterima di Indonesian Health Economics Association (InaHEA) atau Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia yang bergengsi.
Untuk mempertahankan dan melembagakan pertukaran pengetahuan dan pembelajaran yang difasilitasi oleh fellowship ini, HFA USAID dan 30 ekonom kesehatan muda tersebut mengembangkan enam buku referensi ekonomi kesehatan ini untuk mendefinisikan konsep ekonomi dan mengembangkan ide-ide transformatif untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Setiap buku membahas secara mendalam berbagai aspek ekonomi kesehatan yang berbeda, termasuk belanja kesehatan strategis, pembiayaan kesehatan, national health account, dan banyak lagi. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang merupakan mitra USAID, dan tersedia bagi siapa saja yang membutuhkannya. Saya berharap buku-buku ini akan memberikan akses ke informasi yang komprehensif dan relevan tentang ekonomi kesehatan yang dibutuhkan oleh para pemimpin sistem kesehatan di Indonesia untuk terus memajukan dan memperkuat sistem kesehatan Indonesia. USAID berharap dapat melihat bagaimana informasi yang terkandung dalam buku-buku ini dapat meningkatkan pendanaan kesehatan dan kebijakan berbasis bukti.
Sebagai penutup, izinkan saya mewakili USAID untuk mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, para ekonom kesehatan muda, Bappenas, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan tim HFA USAID. Terima kasih atas kontribusi Anda dalam penerbitan buku-buku yang informatif dan inspiratif ini. Kami berharap kolaborasi dan publikasi ini dapat membawa perubahan nyata: kesehatan yang lebih baik untuk lebih banyak orang Indonesia.
Pamela Foster
Director, Office of Health USAID/Indonesia
Prakata
K
emajuan teknologi kesehatan, kompleksitas layanan kesehatan, serta tuntutan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk mengharuskan adanya sinergi antara teknologi kedokteran dan kesehatan serta ketersediaan sumber daya di berbagai negara. Kondisi ini mendorong berkembangnya ilmu ekonomi kesehatan dalam tiga dekade terakhir dan telah mendapat tempat yang luas di berbagai negara. Namun di Indonesia, ilmu ekonomi kesehatan berjalan relatif stagnan.USAID melalui Health Financing Activity (HFA) bekerja sama dengan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) membantu Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan proses sustainable health financing melalui projek-projek pembiayaan kesehatan di tahun 2019-2024. Projek USAID mengidentifikasi kendala dalam sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia yaitu terbatasnya kapasitas dan jumlah orang yang memahami tentang ekonomi kesehatan.
Didorong oleh alasan tersebut, projek HFA dengan senang hati berterima kasih para penulis Young Health Economists (YHE), yaitu anak-anak muda yang disupervisi oleh health economists senior, yang telah menyelesaikan 6 buku ekonomi kesehatan.
Salah satu tema yang dibahas dalam buku ekonomi kesehatan tersebut adalah pembiayaan kesehatan. Tema ini dibahas karena, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, Pembiayaan Kesehatan merupakan fondasi penting dalam mencapai tatanan sistem kesehatan yang baik, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan. Tema ini membahas secara mendalam konsep serta aplikasi pembiayaan kesehatan, metode serta siklus pembiayaan dan peruntukannya, serta kesetaraan dalam layanan kesehatan sebagai bagian dari capaian pembiayaan kesehatan dengan fokus pembahasan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin mengembangkan dan memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia melalui disiplin ilmu ekonomi kesehatan.
Kami berharap buku ini bermanfaat bagi perguruan tinggi, pemangku kebijakan dalam bidang kesehatan, dan berbagai pihak lain yang mempunyai interest dan kemauan mendalami ilmu ekonomi kesehatan.
Salam,
Hasbullah Thabrany
Chief of Party for the Indonesia Health Financing Activity
Daftar Singkatan
ABC : Activity Based Costing
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara Askes : Asuransi Kesehatan
BLT : Bantuan Langsung Tunai BOK : Bantuan Operasional Kesehatan BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS-K : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan CBGs : Case Based Groups
CDC : Centers for Disease Control and Prevention DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum DBD : Demam Berdarah Dengue DEA : Data Envelopment Analysis DHA : District Health Account DJS : Dana Jaminan Sosial DPP : Dokter Praktik Perorangan DRGs : Diagnosis Related Groups DTD : Dana Transfer Daerah
Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat EPF : Employee Provident Fund
FKRTL : Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut FKTP : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama HMO : Health Maintenance Organization
GFATM : Global Fund for AIDS, Tuberculosis, and Malaria IDHS : Indonesian Demographic and Health Surveys IFLS : Indonesian Family Life Survey
INA-CBGs : Indonesian Case Base Groups
INA-DRGs : Indonesian Diagnosis Related Groups Jamkesda : Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas : Jaminan Sosial Masyarakat Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja JKN : Jaminan Kesehatan Nasional K/L : Kementerian/Lembaga KDK : Kebutuhan Dasar Kesehatan Kesling : Kesehatan Lingkungan KLB : Kejadian Luar Biasa
MTEF : Medium Term Expenditure Framework NHI : National Health Insurance
NHSO : National Health Security Office
OASDI : Old-Age, Survivors, and Disability Insurance
OASDHI : Old-age, Survivors, Disability, and Health Insurance
OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development OOP : Out of Pocket
OOPPS : Out of Pocket Payments PAD : Pendapatan Asli Daerah PBI : Penerima Bantuan Iuran PBPU : Pekerja Bukan Penerima Upah PCU : Primary Care Unit
PDB : Produk Domestik Bruto PEN : Pemulihan Ekonomi Nasional Permenkes : Peraturan Menteri Kesehatan
PFABC : Performance-Focused Activity Based Costing PFM : Public Financial Management
PKH : Program Keluarga Harapan PNS : Pegawai Negeri Sipil Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
PPACC : Patient Protection Affordable Care Act PPU : Pekerja Penerima Upah
Promkes : Promosi Kesehatan
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat Raskin : Beras Miskin
RCCs : Ratio of Cost to Charges Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional SDGs : Sustainable Development Goals
SDM : Sumber Daya Manusia
SIMK : Sistem Informasi Manajemen Kesehatan SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKN : Sistem Kesehatan Nasional SOSCO : Social Security Organization SPM : Standar Pelayanan Minimal Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
TA : Tahun Anggaran
TDABC : Time Driven Activity Based Costing TKDD : Transfer ke Daerah dan Dana Desa UC : Unit Cost
UHC : Universal Health Coverage/Cakupan Kesehatan Semesta UKM : Usaha Kesehatan Masyarakat
UKP : Usaha Kesehatan Perorangan US-FDA : US Food and Drug Administration WHO : World Health Organization
Daftar Isi
Kata Pengantar Kementerian Kesehatan RI v
Kata Pengantar USAID vii
Prakata Health Finance Activity ix
Daftar Singkatan xi
Daftar Isi xiii
Prolog xv
BAB 1 KONSEP PEMBIAYAAN KESEHATAN 1
1.1. Pengantar 1
1.2. Biaya Kesehatan 1
1.3. Pembiayaan Kesehatan 4
1.4. Mekanisme Pembiayaan Kesehatan di Indonesia 10
1.5. Penutup 13
Daftar Pustaka 13
BAB 2 PROSES PEMBIAYAAN KESEHATAN 17
2.1. Pengantar 17
2.2. Perencanaan (Planning) 18
2.3. Perhitungan Kebutuhan Biaya (Costing) 21
2.4. Penganggaran (Budgeting) 23
2.5. Penutup 32
Daftar Pustaka 32
BAB 3 KONSEP ASURANSI SEBAGAI BAGIAN PEMBIAYAAN KESEHATAN 35
3.1. Pengantar 35
3.2. Peran dan Posisi Skema Jaminan Kesehatan dalam Sistem Kesehatan 41
3.3. Penutup 47
Daftar Pustaka 48
BAB 4 EKUITAS DALAM KESEHATAN 49
4.1. Pengantar 49
4.2. Latar Belakang 50
4.3. Konsep Ekuitas 51
4.4. Bukti Empiris 58
4.5. Penutup 61
Daftar Pustaka 62
BAB 5 KEBIJAKAN DAN POTRET PEMBIAYAAN KESEHATAN 65
5.1. Pengantar 65
5.2. Pembiayaan Kesehatan di Negara-Negara Lain 66
5.3. Pembiayaan Kesehatan di Indonesia 70
5.4. Pembiayaan Kesehatan Saat Pandemi COVID-19 76
5.5. Penutup 78
Daftar Pustaka 78
Glosarium 81
Tentang Penulis 83
Health Finance Activity dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
Lanskap pembiayaan kesehatan Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak dilaksanakannya Program Jaminan Kesehatan Nasional pada 2014, dari supply side financing menjadi demand side financing. Perubahan ini telah melahirkan perkembangan dan inovasi ekonomi kesehatan yang cukup pesat.
JKN telah memudahkan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan tanpa harus takut dengan biaya yang mahal, atau dengan kata lain melindungi rumah tangga dari pengeluaran kesehatan besar yang dapat memiskinkan rumah tangga akibat penyakit katastropik. Berbagai instrumen pembiayaan kesehatan publik telah dikembangkan, termasuk alokasi sistem monitoring serta efisiensi pembiayaan kesehatan demi peningkatan layanan kesehatan berkelanjutan.
Kecepatan perubahan, inovasi, dan reformasi sistem kesehatan tersebut membutuhkan kapasitas yang mumpuni dari seluruh sumber daya kesehatan, terutama para tenaga kesehatan dan akademisi kesehatan, untuk terus-menerus mendorong dan mengembangkan perbaikan kebijakan pelayanan kesehatan.
Kapasitas kunci yang diperlukan antara lain melakukan advokasi pembiayaan, mendorong pemerintah daerah untuk mengaplikasikan sistem perencanaan dan penganggaran kesehatan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kualitas program kesehatan masyarakat. Akademisi kesehatan yang ada di setiap perguruan tinggi sudah semestinya terlibat dalam proses advokasi perubahan ini dengan menjadikan dirinya sebagai pusat rujukan dalam teori serta praktik ekonomi kesehatan bagi pemerintah daerah.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan itulah Program Health Finance Activity dirancang. Program ini merupakan kolaborasi United States Agency for International Development (USAID) dan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini akan berlangsung selama lima tahun dengan tujuan spesifik mengembangkan analisis atas evidence data dan fakta kesehatan untuk menyokong pembiayaan kesehatan yang tepat guna dan berkelanjutan.
Implementasi program ini digarap oleh ThinkWell sebagai lembaga pelaksana kegiatan, bekerja sama dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, Results for Development (R4D), serta mitra pemerintah lainnya seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Berbagai upaya peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan USAID HFA dan PPJK
PROLOG
pelatihan tentang berbagai topik ekonomi kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan dan akademisi kesehatan bagi dari lingkungan pemerintah dan nonpemerintah.
Beberapa contoh kegiatan yang bisa disebut misalnya “Pelatihan “Pelatihan Jurnalistik bidang Ekonomi Kesehatan” dan “Pelatihan Analisis Sosioekonomi dan Kesehatan”.
Seri Ekonomi Kesehatan untuk Akademisi Muda
Salah satu perhatian HFA adalah konsolidasi dan peningkatan kapasitas ilmu ekonomi kesehatan di kalangan ahli dan akademisi muda. Untuk tujuan ini, HFA dan PPJK telah melaksanakan program The Young Health Economists, yang menghasilkan seri buku didaktik di bidang ekonomi kesehatan.
Seri Ekonomi Kesehatan terdiri dari enam buku, yaitu (1) Pengantar Ekonomi Kesehatan;
(2) Pembiayaan Kesehatan: Konsep dan Praktik Terbaik di Indonesia; (3) Belanja Strategis Kesehatan: Konsep dan Praktik Terbaik di Indonesia; (4) Evaluasi Ekonomi dan Penilaian Teknologi Kesehatan: Konsep dan Praktik Terbaik di Indonesia; (5) Akun Kesehatan Nasional; dan (6) Manajemen Keuangan dan Akuntansi dalam Ekonomi Kesehatan.
Buku seri ini ditulis dengan niat besar mendorong dan memperkenalkan ilmu ekonomi kesehatan sebagai insight dan jalan keluar bagi pengembangan sistem kesehatan di Indonesia. Ekonomi kesehatan, yang pertama kali digaungkan oleh ekonom Kenneth Arrow pada 1963, pada akarnya mengobservasi interaksi antar-faktor determinan kesehatan dan fungsi sistem layanan kesehatan demi menghasilkan derajat kesehatan terbaik.
Buku seri ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar dan referensi bagi akademisi dan praktisi kesehatan, serta para perencana kebijakan kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama mereka yang ingin melakukan penelitian atau mendesain program-program pelayanan kesehatan secara efisien dan tepat sasaran.
Metode Penyusunan Seri Ekonomi Kesehatan
Proses penyusunan Seri Ekonomi Kesehatan ini menempuh jalan panjang. Serial modul ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan diskusi intensif banyak pihak yang diselenggarakan oleh Program HFA.
Seri EKonomi Kesehatan ditulis secara kolaboratif oleh para ekonom muda yang menjadi peserta kegiatan peningkatan kapasitas dengan latar belakang profesi yang beragam. Di dalam modul yang ditulisnya kita akan melihat bagaimana mereka memandang ekonomi kesehatan dari perspektif dan kepakarannya masing-masing.
Para penulis mengembangkan buku ini dengan bimbingan seorang penyelia pada setiap topik. Dalam waktu yang cukup lama, penulis dan penyelia ini bersama-sama mendalami dan mengembangkan setiap topik sehingga menghasilkan buku yang komplet seperti sekarang. Materi buku juga telah melewati proses review yang melibatkan beragam pemangku kebijakan di sektor kesehatan. Merekalah yang memberikan masukan terhadap konten buku dari sisi praktikal terhadap setiap topik pembahasan. Melalui proses ini, HFA USAID dan PPJK Kemenkes RI berharap buku ini memiliki kedalaman konten yang memadai, baik dari sisi teoretis maupun praktik pengelolaan pembiayaan kesehatan.
Buku Seri II yang tengah Anda baca ini berjudul Pembiayaan Kesehatan: Konsep dan Praktik Terbaik di Indonesia. Buku akan mengantarkan Anda untuk mendalami Konsep Pembiayaan Kesehatan, Proses Pembiayaan Kesehatan, Konsep Asuransi Sebagai Bagian Pembiayaan Kesehatan, Ekuitas dalam Kesehatan, dan Kebijakan dan Potret Pembiayaan Kesehatan.
BAB 1
Konsep
Pembiayaan Kesehatan
Haerawati Idris, Adiatma YM Siregar
Pembiayaan kesehatan
merupakan salah satu komponen dalam suatu sistem kesehatan.
1.1. Pengantar
Bab ini membahas mengenai konsep dasar pembiayaan kesehatan.
Kami akan mengawali dengan pengantar dan kemudian membahas mengenai biaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan diakhiri dengan penutup. Semua konsep dasar yang disajikan bertujuan membantu para pembaca memahami sistem pembiayaan kesehatan dan penerapannya di Indonesia. Hal ini diharapkan berguna bagi praktisi di lapangan dalam mengambil keputusan terkait pembiayaan kesehatan.
1.2. Biaya Kesehatan
Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata “biaya kesehatan”?
Mungkin sebagian orang menganggap biaya kesehatan adalah dana yang digunakan untuk masalah kesehatan, misalnya biaya yang dikeluarkan ketika sakit, membeli obat, atau membeli alat kesehatan. Jawaban tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi sesungguhnya hanya mencakup sebagian kecil biaya kesehatan.
Ketika berbicara tentang biaya kesehatan, kita perlu melihat biaya dan pembiayaan kesehatan dalam perspektif suatu sistem.
Pembiayaan kesehatan merupakan salah satu komponen dalam suatu sistem kesehatan.
Biaya kesehatan merupakan sejumlah dana yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan dibagi menjadi dua perspektif (Azwar, 1996): perspektif penyedia layanan kesehatan dan perspektif pengguna jasa.
Dari perspektif penyedia layanan kesehatan, biaya kesehatan merupakan sejumlah uang yang harus disiapkan dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Layanan kesehatan bisa dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan swasta. Adapun dana yang disiapkan oleh penyedia layanan kesehatan berupa biaya investasi (investment cost) dan biaya operasional (operasional cost). Dana tersebut digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
Dari perspektif pengguna jasa, biaya kesehatan merupakan sejumlah dana yang harus disiapkan ketika menggunakan layanan kesehatan. Besaran dana yang digunakan oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan berasal dari kantong pribadi individu (out of pocket).
Biaya kesehatan memiliki beragam jenis dan peruntukan. Hal ini disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan. Secara umum, terdapat dua jenis biaya kesehatan (Azwar, 1996): biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya pelayanan kedokteran adalah dana yang dikeluarkan untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien, sedangkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat dibutuhkan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya ini bertujuan mencegah penyakit, memelihara, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Pengumpulan, penyediaan, dan pembelanjaan keuangan digunakan untuk pembiayaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP). Hal ini dilakukan dengan memobilisasi dana dari masyarakat, pemerintah, dan public-private mix. Pembiayaan bagi masyarakat miskin umumnya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan pembiayaan untuk masyarakat mampu bersumber dari masyarakat itu sendiri melalui mekanisme jaminan kesehatan, baik secara wajib maupun sukarela (Gotama, 2010).
Biaya kesehatan dianggap baik jika memenuhi empat komponen:
pertama, biaya kesehatan tersedia dalam jumlah yang cukup dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan dengan mudah. Kedua, penyebaran dana harus sesuai dengan kebutuhan.
Ketiga, pemanfaatan dana harus diatur secara saksama. Keempat, pengelolaan biaya kesehatan hendaklah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, pelaksanaan di lapangan tidaklah demikian.
Masalah yang kontradiktif masih sering terjadi, dari jumlah dana yang masih terbatas, penyebaran atau alokasi dana yang tidak Secara umum,
terdapat dua jenis biaya kesehatan:
biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat.
sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum baik, hingga biaya kesehatan yang terus meningkat.
Menurut Azwar (1996), masalah pembiayaan dapat diatasi dengan meningkatkan jumlah dana, memperbaiki alokasi dana, manajemen dana, dan mengendalikan biaya kesehatan. Masalah peningkatan biaya kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat inflasi, tingkat permintaan, kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan pola penyakit, perubahan pola pelayanan kesehatan, perubahan pola hubungan dokter dengan pasien, mekanisme pengendalian biaya yang lemah, dan penyalahgunaan asuransi kesehatan (Setyawan, 2018).
Sistem kesehatan membutuhkan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Biaya utama sebagian besar sistem pelayanan kesehatan diserap oleh kebutuhan biaya sumber daya manusia, perawatan di rumah sakit, dan penyediaan obat- obatan. Di sebagian besar negara tropis, pelayanan kesehatan dibiayai oleh pengeluaran pemerintah, swasta (didominasi out of pocket), dan bantuan eksternal. Pembiayaan pelayanan kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadi tantangan yang signifikan. Banyak negara berpenghasilan menengah ke atas di seluruh Amerika Latin, Afrika, dan Asia telah mampu menyediakan perlidungan kesehatan untuk sebagian besar dari populasi mereka. Mekanisme pembiayaan yang digunakan diharapkan mampu memastikan akses ke pelayanan kesehatan dan melindungi individu dari bencana utang ketika mengakses pelayanan kesehatan (Rhatigan Jr, 2020).
Menurut Azwar (1996), secara umum sumber biaya kesehatan dikelompokkan menjadi dua, yakni pertama, seluruh pembiayaan bersumber dari anggaran pemerintah. Negara yang menggunakan model ini menyediakan biaya kesehatan untuk masyarakat sepenuhnya. Pelayanan kesehatan diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma. Tidak ada campur tangan dari pelayanan kesehatan swasta.
Kedua, sebagian pembiayaan ditanggung oleh masyarakat.
Beberapa negara mengajak peran serta masyarakat untuk ikut andil dalam pelayanan kesehatan, baik dalam penyelenggaraan upaya kesehatan maupun pemanfaatan layanan kesehatan. Pada kondisi ini, swasta pun ikut berperan dalam penyediaan layanan kesehatan sehingga masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan dengan mengeluarkan dana sendiri.
Berikut empat sumber utama pembiayaan untuk sektor kesehatan (Kutzin, 2008; Mills & Gilson, 1988).
1. Pembiayaan pemerintah untuk pelayanan kesehatan meliputi pengeluaran kesehatan di semua tingkat pemerintah (pusat dan daerah), termasuk pengeluaran perusahaan publik.
Sistem kesehatan membutuhkan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan.
2. Pembiayaan swasta, dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pembayaran langsung merupakan pembayaran pribadi yang dilakukan langsung kepada berbagai penyedia, termasuk praktik swasta, tabib tradisional, dan apoteker. Biaya pengguna untuk layanan yang disediakan pemerintah atau pelayanan kesehatan swasta yang berasal dari kantong sendiri dianggap sebagai pembiayaan kesehatan dari sumber swasta.
Biaya yang sama, kontribusi, atau pra-pembayaran oleh anggota dalam skema pembiayaan masyarakat juga dianggap berasal dari sumber non-pemerintah.
Pembayaran tidak langsung merupakan pembayaran layanan kesehatan oleh pengusaha sebagai cakupan dan pembiayaan kesehatan oleh badan non-pemerintah lainnya, seperti pengumpulan dana amal.
3. Pembiayaan asuransi kesehatan. Ada tiga jenis asuransi utama, yaitu asuransi pemerintah atau sosial, asuransi swasta, dan asuransi berbasis pengusaha atau pekerja.
4. Pembiayaan sumber eksternal. Pembiayaan ini bersumber dari bantuan organisasi luar dalam membantu program kesehatan, seperti dari WHO, World bank, dan organisasi lain dalam membiayai program prioritas kesehatan suatu negara, seperti HIV, TB, Malaria, dan imunisasi. Selama lima belas tahun terakhir, pendanaan eksternal meningkat secara signifikan untuk kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah dengan beban penyakit yang tinggi. Bantuan pembangunan untuk kesehatan, biasa disebut bantuan asing, merupakan porsi yang signifikan dari pengeluaran kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah, rata-rata 40% dari total pengeluaran perawatan kesehatan (J. L. Dieleman et al., 2016).
1.3. Pembiayaan Kesehatan
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (2000), pembiayaan kesehatan mengacu pada fungsi sistem kesehatan yang berkaitan dengan pengumpulan, alokasi, dan mobilisasi dana untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, secara individu dan kolektif. Dalam sistem kesehatan, tujuan pembiayaan kesehatan adalah menyediakan pendanaan dan menetapkan insentif atau pembiayaan bagi penyedia layanan, serta memastikan semua individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif. Lebih lanjut lagi, WHO menjelaskan bahwa pembiayaan kesehatan mengacu pada bagaimana menggunakan sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan setiap orang secara kolektif & memadai (Organization, 2010).
Pembiayaan kesehatan menjadi suatu bagian yang sangat mendasar dari sistem kesehatan. Dengan dukungan pembiayaan kesehatan, sistem kesehatan akan mampu memelihara dan Dalam sistem
kesehatan, tujuan pembiayaan kesehatan adalah menyediakan pendanaan dan menetapkan insentif atau pembiayaan bagi penyedia layanan, serta memastikan semua individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif.
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Pada kondisi yang sangat ekstrem, ketidaktersediaan pendanaan kesehatan akan menyulitkan layanan kesehatan, pengobatan, pelaksanaan program, pencegahan, dan promosi kesehatan. Pembiayaan bukan hanya sekadar menghasilkan pendanaan, melainkan negara mampu memantau dan mengevaluasi pembiayaan untuk sistem kesehatan dengan menggunakan berbagai indikator. Pembiayaan kesehatan bukan hanya membahas cara meningkatkan dana pelayanan kesehatan, melainkan juga mencakup alokasi pendanaan yang ada.
Sumber pembiayaan kesehatan suatu negara dapat berasal dari pemerintah dan non-pemerintah yang akan digunakan secara luas untuk membiayai upaya kesehatan. Namun, sering kali terjadi persaingan alokasi pendanaan dalam suatu sistem. Cara pengalokasian dana tidak hanya dipengaruhi oleh cara layanan, tetapi juga penetapan prioritas dalam hukum ekonomi kesehatan (Tulchinsky & Varavikova, 2014). Pembiayaan kesehatan diharapkan mampu menyediakan sumber daya dan insentif untuk pelaksanaan sistem kesehatan. Selain itu, pembiayaan kesehatan menjadi penentu utama kinerja sistem kesehatan dalam hal pemerataan, efisiensi, dan outcome kesehatan (Schieber, Baeza, Kress, & Maier, 2006).
Berikut beberapa macam model pembiayaan kesehatan yang dapat diadopsi oleh beberapa negara (Setyawan, 2018):
1. Pembiayaan secara langsung (direct payments by patients) Setiap individu mengeluarkan biaya secara langsung berdasarkan
tingkat penggunaan layanan kesehatan yang diterima. Model pembiayaan ini dapat mendorong penggunaan layanan kesehatan secara lebih hati-hati. Kondisi ini melahirkan kompetisi antara penyedia layanan kesehatan dalam menarik perhatian konsumen (free market). Walaupun hal ini tampak sehat, transaksi kesehatan menjadi tidak seimbang. Konsumen tidak mampu memahami dengan baik akan kebutuhan kesehatan dan masalah kesehatan yang dimiliki. Seluruhnya dikontrol oleh penyedia layanan kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan inefisiensi dan pemakaian terapi secara berlebihan.
2. Pembayaran oleh pengguna (user payments)
Pasien membayar layanan kesehatan secara langsung, baik kepada pemerintah maupun swasta. Besaran dan mekanisme pembayaran telah diatur secara formal oleh penyedia layanan kesehatan dan pemerintah. Pada kondisi yang lebih kompleks, besaran biaya setiap kunjungan dapat berbeda-beda sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan (misalnya untuk pelayanan kesehatan di fasilitas swasta). Besaran biaya per episode ketika sakit bersifat tetap atau flat rate.
3. Pembiayaan berbasis tabungan (saving-based)
Pengeluaran biaya kesehatan individu didasarkan pada tingkat penggunaannya. Individu memperoleh bantuan dalam
Sumber pembiayaan kesehatan suatu negara dapat berasal dari pemerintah dan non-pemerintah yang akan
digunakan
secara luas untuk membiayai upaya kesehatan.
pengumpulan dana dalam bentuk tabungan. Ketika dibutuhkan, individu tersebut dapat memakai dana tersebut. Model ini dapat meng-cover biaya pelayanan kesehatan yang bersifat primer dan lanjutan, tetapi individu akan mengalami kesulitan membiayai pelayanan yang bersifat kronis dan kompleks. Oleh sebab itu, perlu model pembiayaan lain untuk mendukung model ini dalam menanggung biaya kesehatan yang kompleks dan populasi yang lebih luas.
4. Pembiayaan informal
Model ini tidak mengatur besaran, jenis, dan mekanisme pembayaran. Besaran biaya disesuaikan dengan kesepakatan antara penyedia dan pengguna layanan kesehatan. Umumnya penyedia layanan kesehatan lebih dominan dalam pengaturannya.
Selain uang, barang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, misalnya dari penyedia layanan kesehatan mantri atau pengobatan tradisional. Model ini biasanya diadopsi oleh negara-negara berkembang yang belum memiliki sistem kesehatan yang mampu melindungi seluruh masyarakatnya.
5. Pembiayaan berbasis-asuransi (insurance-based)
Dalam model ini individu tidak membiayai pelayanan kesehatan secara langsung, tetapi terjadi pengalihan risiko kesakitan seseorang menjadi risiko kelompok. Selain itu, terjadi pembagian risiko biaya secara adil. Biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan perhitungan dan akan ditanggung dari dana yang telah dikumpulkan bersama. Individu membayar premi dengan mekanisme pembayaran yang diatur oleh organisasi pengelola dana asuransi.
Selain kelima model tersebut, model pembiayaan kesehatan lainnya adalah model Out of Pocket (Pengeluaran dari Kantong Sendiri). Pengeluaran pada model ini berasal dari individu ketika ingin mengakses pelayanan kesehatan dan tidak didanai oleh program asuransi. Model pembiayaan ini diterapkan di sebagian besar negara yang berpenghasilan rendah (J. Dieleman, Campbell,
& Chapin, 2017).
Hal ini akan memberatkan banyak segmen dari populasi yang tidak memiliki sumber pendapatan tunai dan memiliki sedikit tabungan.
Biaya yang bersumber dari kantong sendiri sering menyebabkan keluarga jatuh miskin. Hal ini menjadi penghalang yang sulit diatasi untuk mengakses layanan perawatan kesehatan yang diperlukan.
Negara-negara berpenghasilan tinggi cenderung lebih sedikit mengeluarkan biaya kesehatan dari kantong sendiri karena lebih banyak penduduk yang dilindungi oleh skema asuransi kesehatan prabayar (Rhatigan Jr, 2020).
Model pembiayaan kesehatan antar-negara berbeda. Penggunaan model pembiayaan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Model yang diadopsi diharapkan mampu Model
pembiayaan kesehatan antar-
negara berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
menciptakan akses, keadilan, dan efisiensi pelayanan kesehatan.
Pembiayaan pelayanan kesehatan di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dan tinggi umumnya disediakan melalui asuransi kesehatan (sering kali berbasis lapangan pekerjaan atau serikat pekerja) atau pembiayaan pemerintah yang didanai oleh perpajakan umum.
Pendanaan pemerintah sangat terbatas di negara berpenghasilan rendah karena kurangnya basis pajak yang signifikan. Asuransi kesehatan sulit diterapkan di negara tersebut karena beban penyakit yang tinggi, pendapatan penduduk yang kurang, dan kesulitan menciptakan kumpulan risiko yang besar dan beragam (Mills, 2014). Hampir semua skema asuransi kesehatan yang diterapkan di negara ini memerlukan subsidi dari permerintah untuk menopang sistem mereka (Sachs, 2012).
Interaksi fungsi-fungsi pembiayaan kesehatan ditunjukkan pada Gambar 1.1. Pembiayaan kesehatan meliputi fungsi dasar pengumpulan pendapatan (revenue collection), pengumpulan sumber daya (pooling resources), dan pembayaran intervensi (purchase of interventions). (Gottret & Schieber, 2006; Rannan-Eliya, 2009):
1. Pengumpulan pendapatan adalah bagaimana sistem kesehatan mengumpulkan uang dari rumah tangga, bisnis, dan sumber eksternal.
2. Pengumpulan berkaitan dengan akumulasi dan pengelolaan pendapatan sehingga anggota kelompok berbagi risiko kesehatan secara kolektif. Hal ini akan melindungi anggota kelompok individu dari pengeluaran kesehatan yang besar dan tidak dapat diprediksi. Pembayaran di muka memungkinkan anggota untuk membayar biaya rata-rata di muka, membebaskan mereka dari ketidakpastian, dan memastikan kompensasi jika terjadi kerugian.
Pengumpulan ini memungkinkan pembentukan asuransi dan redistribusi pengeluaran kesehatan antara individu berisiko (tinggi dan rendah) dan individu berpenghasilan (tinggi dan rendah).
3. Pembelian mengacu pada mekanisme yang digunakan untuk membeli layanan dari penyedia publik dan swasta.
Hampir semua skema asuransi kesehatan yang diterapkan di negara ini memerlukan subsidi dari permerintah untuk menopang sistem mereka.
Gambar 1.1.
Hubungan Fungsi-Fungsi Pembiayaan Kesehatan
Diadopsi dari G. Schieber, Baeza, C., Kress, D., &
Maier, M. (2006). Financing Health Systems in the 21st Century. Disease Control Priorities in Developing Countries, 225, 224.
Fungsi pembiayaan kesehatan di atas memiliki implikasi yang penting untuk mendukung kerja sistem kesehatan berupa:
1. Jumlah dana yang tersedia (saat ini dan di masa depan) dan tingkat layanan esensial dan perlindungan keuangan bagi populasi.
2. Keadilan (ekuitas).
3. Efisiensi ekonomi dari upaya peningkatan pendapatan.
4. Tingkat pooling (subsidi risiko, asuransi) dan pembayaran di muka (ekuitas subsidi)
5. Jumlah dan jenis layanan yang dibeli dan dikomsumsi terhadap dampak kesehatan dan biaya kesehatan (efektivitas biaya dan efisiensi alokasi layanan)
6. Efisiensi teknis dari produksi layanan (tujuannya adalah untuk menghasilkan setiap layanan dengan biaya rata-rata minimum) 7. Akses fisik dan finansial dan ke layanan oleh populasi (termasuk
ekuitas akses dan manfaat)
Dalam hal kebijakan kesehatan di tingkat negara, ketujuh fungsi pembiayaan kesehatan di atas berguna untuk, pertama pengumpulan dana yang dapat meningkatkan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan dengan cara yang adil dan efisien.
Hal ini dilakukan dengan menyediakan kebutuhan individu akan paket dasar layanan esensial dan perlindungan keuangan terhadap bencana keuangan yang terjadi ketika individu sakit.
Kedua, penggabungan risiko untuk mengelola pendapatan yang dikumpulkan dan menyatukan risiko kesehatan secara adil dan efisien. Ketiga, pembelian dapat memastikan pembelian layanan kesehatan secara efisien, baik alokasi maupun teknis.
Fungsi pembiayaan di atas diwujudkan dalam tiga model pembiayaan kesehatan sebagai berikut (Gottret & Schieber, 2006;
Jaworzyľska, 2016):
1. National Health Service (NHS)
Model Layanan Kesehatan Nasional juga sering disebut dengan Model Beveridge. NHS dikenal pertama kali di Inggris pada 5 juli 1948. Model ini diperkenalkan oleh William Beveridge. Model ini ditandai dengan cakupan universal yang bersifat wajib dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan umum nasional dan kepemilikan nasional. Dalam sistem ini, perawatan kesehatan disediakan dan dibiayai oleh pemerintah melalui pembayaran pajak. Model ini menawarkan pelayanan gratis bagi seluruh populasi. Negara-negara yang menggunakan model Beveridge atau variasi di dalamnya di antara Inggris Raya, Spanyol, sebagian besar Skandinavia, dan Selandia Baru.
2. Asuransi sosial
Model pembiayaan ini sering disebut dengan model Bismarck.
Model ini diperkenalkan oleh Kanselir Prusia Otto Von Bismarck.
Fungsi pembiayaan kesehatan berguna untuk pengumpulan dana yang dapat meningkatkan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan dengan cara yang adil dan efisien.
Cakupan universal wajib berada di bawah sistem jaminan sosial.
Kontribusi asuransi ini bersumber dari karyawan dan pemberi kerja. Model Bismarck meliputi struktur, pembiayaan, dan pemberian pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, model Bismarck mewakili layanan yang tersedia bagi karyawan melalui cakupan asuransi kesehatan yang disponsori oleh majikan. Model Bismarck diadopsi oleh Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, Jepang, Swiss, dan beberapa bagian di Amerika Latin.
3. Asuransi swasta
Pembelian asuransi kesehatan swasta ini berbasis pada perusahaan atau perorangan. Model asuransi kesehatan swasta dengan akses manfaat yang dikondisikan berdasarkan polis asuransi swasta. Dana yang dialokasikan untuk membiayai manfaat layanan kesehatan berasal dari premi asuransi swasta.
Produsen layanan kesehatan adalah entitas swasta. Negara- negara Anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat membangun sistem pembiayaan mereka berdasarkan model ini.
Bagaimana dengan mekanisme pembiayaan kesehatan? Menurut WHO, skema pembiayaan pelayanan kesehatan adalah komponen struktural dari sistem pembiayaan pelayanan kesehatan, yakni pengaturan pembiayaan sehingga seseorang mampu memperoleh pelayanan kesehatan. Skema pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk pembayaran langsung oleh rumah tangga untuk layanan dan barang serta pengaturan pembiayaan oleh pihak ketiga (Organization, 2017a). Manfaat atau cakupan dibagi ke dalam cakupan luas dan cakupan ruang lingkup. Cakupan luas berarti kelompok populasi yang dicakup oleh bentuk sistem prapembayaran atau perlindungan sosial apa pun, sedangkan cakupan ruang lingkup mengacu pada jenis layanan kesehatan yang disediakan pada skema sistem prapembayaran atau skema perlindungan sosial. Hal tersebut secara detail dideskripsikan pada Tabel 1.1.
1.4. Mekanisme Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
Berikut mekanisme pembiayaan kesehatan yang diterapkan di Indonesia (Myint et al., 2019): sumber utama pendapatan berasal dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan out of pocket (OOP).
Metode pengumpulan pendapatan menggunakan sistem single pool. Jenis penyedia layanan kesehatan berasal dari penyedia publik dan swasta. Dalam hal pembelian, penyedia layanan untuk pelayanan kesehatan mengandalkan campuran penyedia publik dan swasta.
Cakupan pelayanan berupa layanan kesehatan esensial dan berbiaya tinggi atau pelayanan tersier. Luas cakupan mencakup sekitar 63%
masyarakat melalui subsidi pemerintah dan/atau pembayaran di muka dan/atau skema pengelompokan risiko. Cakupan ini belum mencapai tingkat yang direkomendasikan WHO, yaitu lebih dari 90%. Paket layanan bersifat komprehensif, tetapi tergantung pada jenis asuransi yang dipilih oleh individu (perawatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga)(Marzoeki, Tandon, Bi, & Pambudi, 2014).
Penyedia layanan di Indonesia membutuhkan akreditasi. Metode pembayaran penyedia menggunakan sistem kapitasi dan Diagnostic Related Group (DRG). Dana dikumpulkan ke satu tempat yang disebut asuransi kesehatan nasional (single pool).
Meskipun pendapatan dimasukkan ke kumpulan tunggal, tarif
C. Y. Myint, Pavlova, M., Thein, K.-N.-N., & Groot, W.
(2019). A Systematic Review of The Health-Financing Mechanisms in The Association of Southeast Asian Nations Countries and The People’s Republic of China: Lessons for The Move Towards Universal Health Coverage. PLoS One, 14(6), e0217278.
Tabel 1.1. Indikator untuk Menilai Mekanisme Pembiayaan Kesehatan Menurut Framework McIntyre dan Kutzin (2016)
Sejak 2004, anggaran
pemerintah untuk kesehatan telah meningkat secara signifikan.
premium bervariasi berdasarkan status pekerjaan di Indonesia.
Sumber pendapatan asuransi kesehatan nasional terdiri dari kontribusi sosial dan subsidi pemerintah untuk orang miskin dan target spesifik (Myint et al., 2019).
Standar anggaran minimal suatu negara yang ditetapkan oleh WHO adalah sekitar 5%-6% dari total APBN. Tujuannya adalah agar mampu meningkatkan derajat kesehatan dengan dukungan pembiayaan kesehatan yang kuat. Idealnya suatu negara menganggarkan 15-20%
dari APBN. Anggaran yang besar diharapkan mampu membiayai kebutuhan pelayanan kesehatan yang cukup mahal. Kesehatan menjadi investasi suatu negara untuk meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakatnya (Organization, 2014).
Sejak 2004, anggaran pemerintah untuk kesehatan telah meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena kebijakan pembiayaan kesehatan pemerintah yang lebih fokus untuk mengurangi risiko keuangan dari pengeluaran perawatan kesehatan, khususnya untuk kelompok miskin. Peningkatan anggaran ini juga diamanatkan oleh UU Kesehatan, yang menetapkan bahwa alokasi anggaran pemerintah secara nasional setidaknya harus berjumlah 5% dari total anggaran pemerintah pusat (APBN); sementara untuk anggaran daerah (APBD) alokasi untuk kesehatan minimal berjumlah 10%.
Berdasarkan persyaratan hukum itu, pemerintah telah menambah alokasi anggaran untuk perawatan kesehatan secara nasional hingga 5% dari total pemerintah anggaran pada 2016. Jumlahnya diperkirakan sekitar 109 Triliun Rupiah (Mahendradhata et al., 2017).
Sumber pendanaan kesehatan di Indonesia berasal dari APBN, APBD, dana swasta, out of pocket, hibah, dan donor dari perusahaan ataupun luar negeri. Sumber dana tersebut dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang kesehatan, baik bersifat fisik maupun nonfisik.
Gambar 1.2. merangkum aliran pembiayaan yang terjadi dalam sistem kesehatan Indonesia. Aliran dana pemerintah termasuk proses pengumpulan pendapatan dari rumah tangga, perusahaan swasta, dan sumber eksternal dan transfer ke daerah pemerintah dan fasilitas kesehatan. BPJS kesehatan merupakan administrator dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengumpulkan kontribusi dari pemerintah, perusahaan swasta, dan rumah tangga menjadi satu kumpulan nasional dan membeli layanan kesehatan dari penyedia publik dan swasta. Aliran dana pribadi meliputi pengeluaran Out of Pocket (OOP) dari rumah tangga, perusahaan di fasilitas publik dan swasta. Sejak lima tahun yang lalu, hanya sekitar satu persen dari total pengeluaran kesehatan berasal sumber eksternal (Pinto, Masaki, & Harimurti, 2016).
Dalam 20 tahun terakhir, reformasi di bidang pembiayaan kesehatan di Indonesia bergerak sangat dinamis, dari penargetan berbagai program menuju UHC. Upaya reformasi pembiayaan yang dilaksanakan pada akhir 1990-an bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat miskin sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang melanda Asia pada akhir 1998. Pada 2004 dibentuk skema asuransi kesehatan sosial. Pada 2008, skema tersebut ditingkatkan dan diperluas lebih jauh. Kemudian pada tahun 2011, skema perlindungan keuangan lainnya diperkenalkan secara khusus untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Akhirnya, sebuah langkah menuju Universal Health Coverage (UHC) dimulai pada tahun 2014 dengan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (Mahendradhata et al., 2017).
JKN adalah reformasi pembiayaan kesehatan yang berupaya mengatasi tiga pilar pembiayaan kesehatan, yakni pengumpulan pendapatan, penggabungan, dan pembelian. JKN berpotensi menciptakan momentum untuk bergerak menuju kebijakan dan strategi yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). JKN telah berupaya menciptakan distribusi yang adil dari beban sistem pendanaan. Negara perlu melanjutkan dan membuat penyesuaian yang diperlukan sehingga sistem kesehatan dapat berfungsi secara berkualitas, efisien dan adil. Pada saat yang sama menyediakan perlindungan finansial berkelanjutan kepada rakyat (Mahendradhata et al., 2017).
Sistem UHC berkembang pesat di Indonesia dan mencakup 203 juta orang. Kini Indonesia dikenal sebagai pengguna skema pembayar tunggal terbesar di dunia dan telah meningkatkan pemerataan kesehatan dan akses layanan. Kesuksesan di awal Gambar 1.2.
Aliran Pembiayaan Kesehatan
Diadopsi dari Pinto, R., Masaki, E., & Harimurti, P. (2016). Indonesia Health Financing System Assessment: Spend More, Spend Right, Spend Better:
World Bank.
memberikan tantangan lain, seperti munculnya kelompok “missing middle”. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan sejumlah kecil orang yang terdaftar di UHC dengan kuintil kekayaan Q2-Q3 dibandingkan orang di kuintil lainnya, dan rendahnya cakupan UHC pada anak sejak lahir sampai usia 4 tahun (Agustina et al., 2018).
Pembiayaan publik sangat penting untuk membuat kemajuan menuju UHC. Komitmen kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) PBB menekankan bahwa setiap orang harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan penggunaan layanan ini mampu melindungi keuangan individu (Organization, 2017b). Dampak pada pengeluaran publik untuk kesehatan akan bergantung pada sejauh mana kebijakan fiskal dan prioritas kesehatan terjadi. Selama periode ini sangat penting untuk memastikan tingkat pembiayaan publik untuk mempertahankan cakupan layanan yang efektif dan perlindungan risiko keuangan terhadap UHC (Tandon, Cain, Kurowski, Dozol, & Postolovska, 2020).
1.5. Penutup
Secara luas, pembiayaan kesehatan dipandang mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara.
Pembiayaan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan pembiayaan kesehatan yang memadai akan membantu negara dalam memobilisasi sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional, dan menggunakannya secara efektif serta efisien. Untuk mendorong tercapainya akses yang universal dibutuhkan kebijakan pembiayaan yang memperhatikan pemerataan dan membantu penduduk miskin.
Daftar Pustaka
Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K., Achadi, E., Taher, A., . . . Shankar, A. (2018). Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress, and Challenges. Lancet (London, England).
Azwar, A. (1996). Pengantar Administrasi Kesehatan, Sistem Kesehatan. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Binarupa Aksara.
Dieleman, J., Campbell, M., & Chapin, A. (2017). And the Global Burden of Disease Health Financing Collaborator Network.
Evolution and Patterns of Global Health Financing 1995- 2014: Development Assistance for Health, and Government, Prepaid Private, and Out-Of-Pocket Health Spending in 184 Countries. The Lancet, 389(10083), 1981-2004.
Untuk mendorong tercapainya akses yang universal dibutuhkan kebijakan
pembiayaan yang memperhatikan pemerataan dan membantu penduduk miskin.
Dieleman, J. L., Schneider, M. T., Haakenstad, A., Singh, L., Sadat, N., Birger, M., . . . Chapin, A. (2016). Development Assistance for Health: Past Trends, Associations, and the Future of International Financial Flows for Health. The Lancet, 387(10037), 2536-2544.
Gotama, D. P. I. (2010). Reformasi Jaminan Sosial Kesehatan (Isu- Isu Kesehatan & Jaminan Kesehatan). Jakarta: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes RI.
Gottret, P., & Schieber, G. (2006). Health Financing Revisited: A Practitioner’s Guide. The World Bank.
Jaworzyľska, M. (2016). A Comparative Analysis of the Health System Financing in Poland and Selected Countries. Economics and Sociology, 9(3), 41-51.
Kutzin, J. (2008). Health Financing Policy: A Guide for Decision- Makers. Health Financing Policy Paper. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 24.
Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., Marthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. (2017). The Republic of Indonesia Health System Review.
Marzoeki, P., Tandon, A., Bi, X., & Pambudi, E. S. (2014). Universal Health Coverage for Inclusive and Sustainable
Development: Country Summary Report for Indonesia.
Mills, A. (2014). Health Care Systems in Low-And Middle-Income Countries. New England Journal of Medicine, 370(6), 552- 557.
Mills, A., & Gilson, L. (1988). Health Economics for Developing Countries: A Survival Kit.
Myint, C.-Y., Pavlova, M., Thein, K.-N.-N., & Groot, W. (2019). A
Systematic Review of The Health-Financing Mechanisms in The Association of Southeast Asian Nations Countries and The People’s Republic of China: Lessons for The Move Towards Universal Health Coverage. PLoS One, 14(6), e0217278.
Organization, W. H. (2000). The World Health Report 2000:
Health Systems: Improving Performance. World Health Organization.
Organization, W. H. (2010). Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies. World Health Organization.
Organization, W. H. (2014). WHO Global Health Expenditure Atlas.
September 2014. WHO Global Health Expenditure Atlas.
Switzerland2014.
Organization, W. H. (2017a). A System of Health Accounts 2011 Revised edition: OECD Publishing.
Organization, W. H. (2017b). World Bank. Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report. World Health Organization.
Pinto, R., Masaki, E., & Harimurti, P. (2016). Indonesia Health Financing System Assessment: Spend More, Spend Right, Spend Better:
World Bank.
Rannan-Eliya, R. P. (2009). Strengthening Health Financing in Partner Developing Countries. Task Force on Global Action for Health System Strengthening, Editor (2009) Global Action For Health System Strengthening. Tokyo: Japan Center for International Exchange, 59-90.
Rhatigan Jr, J. J. (2020). Health Systems and Health Care Delivery Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases (pp. 214-218): Elsevier.
Sachs, J. D. (2012). Achieving Universal Health Coverage in Low- Income Settings. The Lancet, 380(9845), 944-947.
Schieber, G., Baeza, C., Kress, D., & Maier, M. (2006). Financing Health Systems in the 21st Century. Disease Control Priorities in Developing Countries, 225, 224.
Setyawan, F. E. B. (2018). Sistem Pembiayaan Kesehatan. Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan, 2(4).
Tandon, A., Cain, J., Kurowski, C., Dozol, A., & Postolovska, I. (2020).
From Slippery Slopes to Steep Hills: Contrasting Landscapes of Economic Growth and Public Spending For Health. Social Science & medicine, 259, 113171.
Tulchinsky, T., & Varavikova, E. (2014). Chapter 11-Measuring costs: The Economics of Health. The New Public Health, 575-611.
BAB 2
Proses
Pembiayaan Kesehatan
Estro Dariatno Sihaloho, Adiatma YM Siregar
Konsensus umum menyatakan bahwa proses pembiayaan kesehatan tidak hanya bertujuan mencari dan mengumpulkan dana yang cukup, melainkan juga meliputi proses penganggaran dengan tepat.
2.1. Pengantar
Proses pembiayaan kesehatan merupakan hal yang mendasar untuk mencapai target indikator kesehatan dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional. Proses pembiayaan yang tidak tepat menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut meminimalkan tenaga kesehatan yang akan diperkerjakan, obat- obatan yang tersedia, dan mengurangi promosi kesehatan (World Health Organization, 2008).
WHO menekankan bahwa proses pembiayaan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun konsensus umum menyatakan bahwa proses pembiayaan kesehatan tidak hanya bertujuan mencari dan mengumpulkan dana yang cukup, melainkan juga meliputi proses penganggaran dengan tepat.
Banyak pengambil kebijakan yang masih belum memahami proses pembiayaan kesehatan sehingga pembuatan kebijakan kesehatan, perencanaan, penetapan biaya hingga penganggaran dilaksanakan secara terpisah. Hal tersebut menyebakan ketidakselarasan (Rajan, et al., 2016).
Adapun proses pembiayaan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perencanaan, perhitungan kebutuhan biaya, dan penganggaran (Gani 2002; Rajan et al, 2016) yang akan dibahas secara mendetail dalam bab ini.
Deskripsi masalah kesehatan diidentifikasi dengan prinsip dan metode epidemiologi yang menghasilkan besaran masalah kesehatan, distribusi kelompok
masalah kesehatan, dan kemungkinan sumber masalah kesehatan.
2.2. Perencanaan (Planning)
Perencanaan merupakan awal proses pembiayaan kesehatan.
Perencanaan yang baik dapat mengidentifikasi kegiatan yang akan dibiayai. Gani, et al. (2002) membagi perencanaan menjadi empat bagian, yaitu analisis situasi, penetapan tujuan, identifikasi kegiatan, dan penyusunan rencana operasional.
2.2.1 Analisis Situasi
Dari analisis situasi akan diperoleh deskripsi masalah kesehatan yang terjadi di dalam masyarakat, kinerja sistem pelayanan atau kesehatan hingga saat ini, faktor risiko lingkungan, dan faktor risiko perilaku (Gani, et al., 2002). Deskripsi masalah kesehatan diidentifikasi dengan prinsip dan metode epidemiologi yang menghasilkan besaran masalah kesehatan, distribusi kelompok masalah kesehatan, dan kemungkinan sumber masalah kesehatan.
Untuk melakukan deskripsi masalah, pengambil kebijakan dapat menganalisis data primer yang dikumpulkan dengan survei atau data sekunder yang dikumpulkan dari laporan puskemas, laporan rumah sakit, laporan program, survei demografi dan kesehatan Indonesia, Survei Sosial Ekonomi Sosial (Susenas), dan lain-lain.
Kinerja atau sistem pelayanan dan program kesehatan disusun berupa tren output layanan kesehatan apakah sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya. Dalam menyusun kinerja pelayanan dan program kesehatan dapat juga dicari masalah dan tantangan yang ditemukan di lapangan. Hasil kinerja pelayanan saat ini akan menjadi sangat penting untuk merumuskan tujuan atau target output dalam proses perencanaan.
Analisis faktor risiko lingkungan bertujuan untuk mengetahui faktor lain yang meningkatkan masalah kesehatan, tetapi tidak berkaitan langsung dengan kejadian penyakit. Contohnya adalah nyamuk Aedes Aegypti merupakan sumber penyakit (yang berkaitan langsung dengan kejadian DBD), sedangkan curah hujan merupakan faktor yang secara tidak langsung berkaitan dengan kejadian DBD (Kosnayani and Hidayat, 2018). Analisis faktor risiko lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan hasil surveilans, laporan puskesmas, data yang diperoleh dari pemerintah daerah, survei khusus atau pengamatan staf Dinas Kesehatan (Dinkes) dan laporan masyarakat.
Analisis faktor risiko perilaku bertujuan untuk menganalisis faktor perilaku yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan. Salah satu contoh adalah perilaku buang air besar sembarangan yang menimbulkan masalah kesehatan (Anggoro, 2017). Analisis faktor risiko perilaku dapat dilakukan menggunakan data Susenas, hasil survei khusus atau pengamatan staf, laporan masyarakat, dan laporan puskesmas.
Gambar 2.1.
Pelaksanaan Program Kesehatan
Gani, et al. (2002). Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT).
Jakarta: PT.Nisarindo Jaya Abadi.
Gani, et al. (2002) mendefinisikan penetapan tujuan program dibagi menjadi dua bagian, yaitu outcome atau hasil yang berkaitan dengan tujuan umum dan output atau target yang berkaitan dengan tujuan khusus. Tujuan umum berkaitan dengan perbaikan derajat kesehatan, sedangkan tujuan khusus merupakan pencapaian output yang berkaitan dengan perbaikan kinerja program. Contoh dari tujuan umum adalah KLB Polio tidak terjadi, sedangkan contoh dari tujuan khusus adalah jumlah balita yang berhasil diimunisasi sebesar 80%. Gambar 2.1 menggambarkan pelaksanaan suatu program kesehatan yang terdiri dari kegiatan, input, output, target, dan outcome.
Dalam menentukan tujuan program harus dipertimbangkan target atau tujuan yang menjadi komitmen nasional dan komitmen global.
Contohnya Kementerian PPN/Bappenas menetapkan seluruh isu kesehatan dalam SDGs dalam satu outcome, yakni jaminan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Output yang diusung untuk mewujudkan tujuan SDGs dibagi menjadi tiga pilar, yaitu paradigma sehat, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional (Kementerian PPN/Bappenas n.d.). Output paradigma sehat dilakukan dengan mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan serta menempatkan kesehatan sebagai input penting dari proses pembangunan. Output pelayanan kesehatan lebih ditekankan pada peningkatan akses dan mutu layanan. Output jaminan kesehatan nasional diperoleh dengan meningkatkan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Sementara itu, penentuan tujuan (target) khusus harus memiliki rumusan kuantitatif yang spesifik, sasaran penduduk yang jelas, sasaran lokasi yang jelas, dan waktu pencapaian yang jelas.