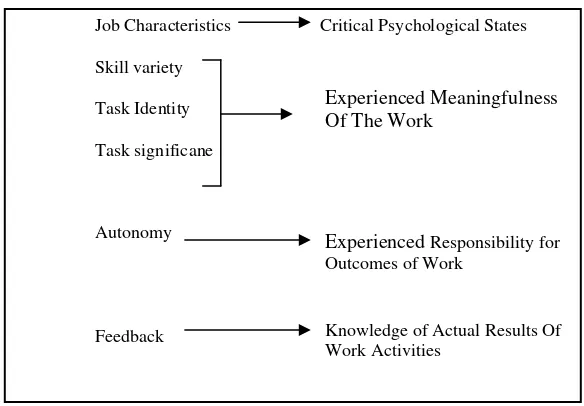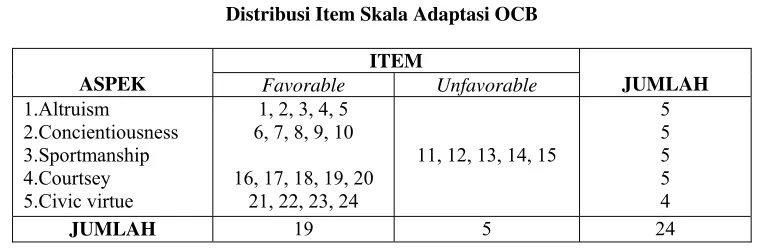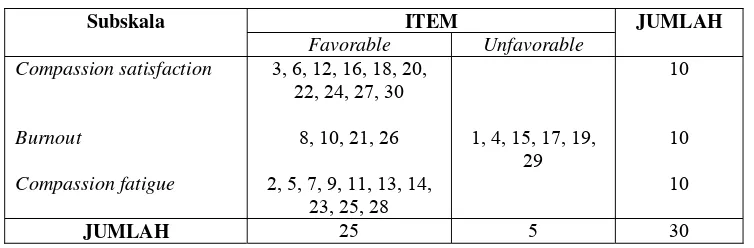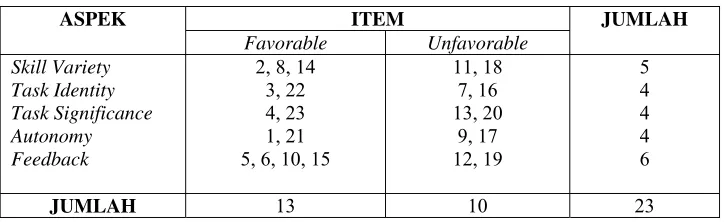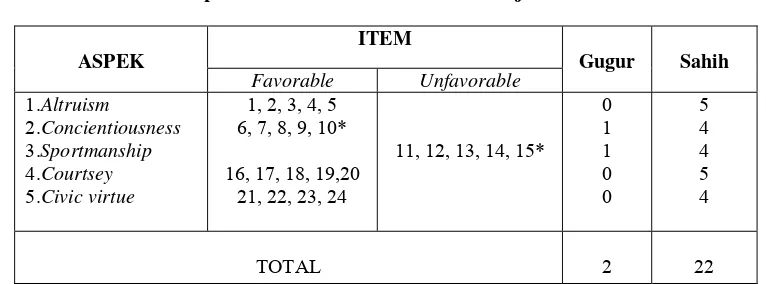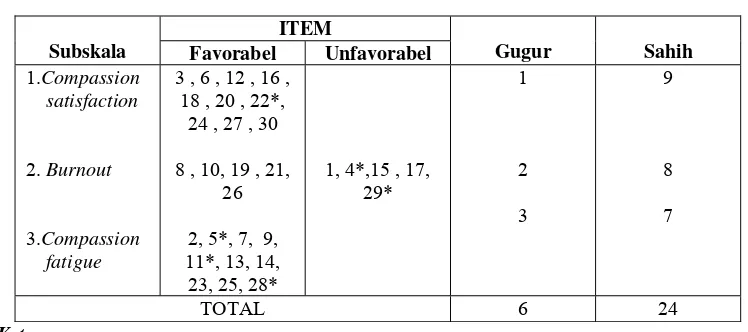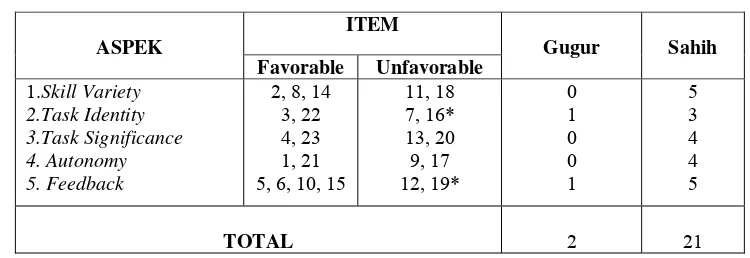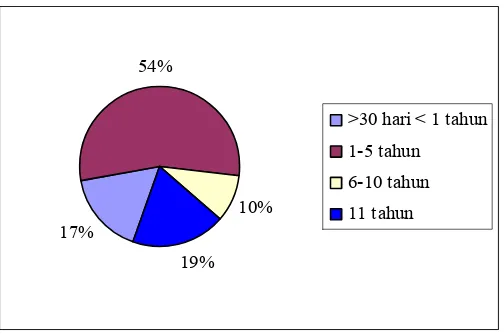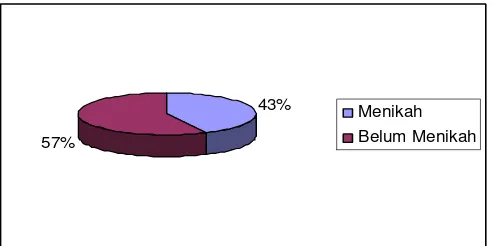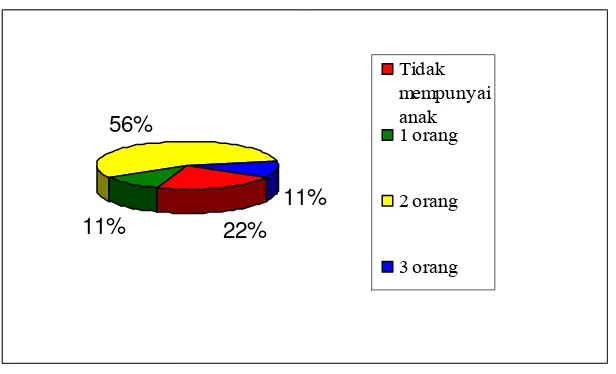PADA PEGAWAI PT.BRI CABANG KATAMSO DI YOGYAKARTA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi
Oleh :
Angelia Prasastha Widhi Nugraheni NIM : 059114012
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2010
berbeda dari cara memanfaatkan sejuta bahkan ribuan pilihan atau keputusan dalam kesempatan yang ada. Bagaimanapun semuanya tidak terlepas dari karunia Nya, bila semuanya telah tertulis, … Just Written.
By : Angelia Prasastha W. N
Memaafkan orang lain sama hal nya dengan membebaskan tawanan.
Betapa sulitnya … karena tawanan itu adalah Anda sendiri
By : Wanita Bijak (Book)
“ Let ’ s sing a song. . Oh ..Happy Day!” karena Yesus memberikan kasih dan karunia ket ika meraj ut hari-hari kit a dalam t iap harinya yang demikian,
SADday (hari yang menyedihkan) MOANday (hari mengerang)
TEARSday (hari penuh air mat a) WASTEday (hari yang t erbuang sia-sia) THRISTday (hari ‘ kehausan’ )
FIGHTday (hari penuh pergumul an) SHATTERday (hari yang berant akan)
(humor yang dikut ip dari buku Johny The)
I
Yesus, sumber segala anugerah & hidup
K
I
Almarhum Opa tercinta,
T
. Sastra Atmadja &
N
iti Soedarmo
K
I
P
api &
M
ami , atas doa & dukungan kelancaran karya kecil
K
I
My sisters & Brother:
A
jeng galih, P.S.,SS,
N
aning &
J
alu
K
I
Yg tercinta,
K
ristofer Adi, atas pengorbanan & kasih yg tulus
K
I
Semua peri-peri kecil yang hidup di kejamnya jalanan
K
Terimakasih yang tak terhingga untuk :
I
M
om A, Yg berikan ketegaran dan semangat hidup
K
I
Keluarga besar Ir.
W
idayat, M.T
K
I
Keluarga drg.
D
idit Istadi, Sp.BM.
K
I
dr.
B
enedictus Nugraha & dr.
M
andiri Nindia Sari, Sp.M.
K
Terima kasih atas segenap
dukungan dan doa sehingga karya kecil ini tercipta
YOGYAKARTA
Angelia Prasastha Widhi Nugraheni
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan professional quality of life (ProQOL) dan organizational citizenship behavior (OCB) dengan karakteristik pekerjaan sebagai variabel moderator. Hipotesis yang diajukan yaitu karakteristik pekerjaan signifikan sebagai variabel moderator terhadap hubungan antara ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) dengan OCB (altruism, concientiousness, sportmanship, courtesy, civic virtue). Subyek penelitian adalah pegawai di kantor cabang PT. BRI Katamso di Yogyakarta yang berjumlah 42 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran skala OCB, skala Karakteristik Pekerjaan, dan skala ProQOL. Setelah uji coba, skala OCB menghasilkan koefisien reliabilitas yaitu: altruism = 0.838; concientiousness = 0.829; sportsmanship = 0.854 ; courtesy = 0.830; civic virtue = 0.827. Berikutnya skala ProQOL menghasilkan koefisien reliabilitas yaitu : compassion satisfaction = 0.738 ; burnout = 0.705 ; compassion fatigue = 0.717. Sedangkan skala Karakteristik Pekerjaan memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0.856. Penelitian ini menggunakan teknik moderated regression analysis (MRA). Hasil analisis data menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan tidak signifikan sebagai variabel moderator terhadap hubungan antara professional quality of life / ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) dan organizational citizenship behavior / OCB (altruism, concientiousness, sportsmanship, courtesy, civic virtue). Hal ini ditunjukkan melalui hasil koefisien regresi pada signifikansi ≥ 0.05.
Kata kunci : karakteristik pekerjaan, professional quality of life (ProQOL), organizational citizenship behavior (OCB)
Angelia Prasastha Widhi Nugraheni ABSTRACT
This research is aimed to find out about the relation of professional quality of life (ProQOL) and organizational citizenship behavior (OCB) with job characteristic as a moderator variable. The Hypothesis is that significance of job characteristic as a moderator variable toward the relation of professional quality of life / ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) and organizational citizenship behavior /OCB (altruism, concientiousness, sportmanship, courtesy, civic virtue). The subject of this research were the employees in office of PT. BRI Katamso branch in Yogyakarta amount 42 people. The data collecting by giving OCB’s scale, ProQOL’s scale and also Job Characteristic’s scale. The realibility coeficient scale of OCB after the try out were shown : altruism = 0.838 ; concientiousness = 0.829; sportsmanship = 0.854 ; courtesy = 0.830; civic virtue = 0.827. And then coeficient reliability of compassion satisfaction = 0.738 ; burnout = 0.705 ; compassion fatigue = 0.717. While the coeficient reliability of job characteristic was 0.856. Moderated Regression Analysis (MRA) technique was used to measure the relation of professional quality of life (ProQOL) and organizational citizenship behavior (OCB) with job characteristic as a moderator. The result shows the job characteristic is not significant as a moderator variable toward the relation of professional quality of life / ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) and organizational citizenship behavior /OCB (altruism, concientiousness, sportsmanship, courtesy, civic virtue). This shown by the result of coefficient regression of p ≥ 0.05.
Keywords : job characteristic, professional quality of life (ProQOL), organizational citizenship behavior (OCB)
Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator Pada Pegawai Di Kantor Cabang PT. BRI Katamso Di Yogyakarta dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana psikologi.
Penulis banyak melibatkan banyak pihak untuk membantu penulisan karya ini. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :
1. Ibu Dr.Christina Siwi Handayani, selaku Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
2. Ibu Kristiana Dewayani, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik, yang banyak memberikan masukan dan kritikan pada penulis.
3. Bapak Eddy Suhartanto,M.Si, selaku dosen penguji, yang bersedia dengan sabar memberikan masukan pada penulisan skripsi ini.
4. Bapak Minta Istono, M.Si., selaku dosen penguji, atas masukan penulisan skripsi ini.
5. Mbak Siegfrieda Alberti dan mbak Ajeng Galih P.S atas bantuan dan dukungannya sebagai ahli alih penerjemah skala penelitian
6. Romo A. Priyono Marwan, atas masukan dan nasehatnya bagi penulisan skripsi ini.
7. Direktur utama kantor PT.BRI Pusat di Yogyakarta, bapak Sofyan Baasir, atas ijin tempat serta dukungan penelitiannya.
8. Pemimpin wilayah PT.BRI di Yogyakarta, bapak Tentendjaka Triana, atas dukungan penelitiannya.
9. Pemimpin cabang PT.BRI Katamso, bapak Bambang Wijanarko, atas dukungan penelitiannya.
11. Seluruh pimpinan unit PT. BRI cabang Katamso beserta segenap pegawai PT.BRI cabang Katamso, atas dukungan serta kesediaannya tehadap penelitian ini.
12. Segenap dosen Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi saya.
13. Segenap karyawan Universitas Sanata Dharma. Ntoek Gandung, Ibu Nanik, Pak Gie dan mas Doni, atas keramahannya. Ntoek mas Muji, atas perhatian, bantuan dan dukungannya selama ini. Ntoek mas Boni, mas Joko, mas Supri atas keramahannya.
14. Semua kakak di KomNak serta segenap karyawan LPM Marga Husada yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk atas persaudaraan serta bantuan dan dukungannya terhadap penelitian ini.
15. Untuk sahabat mami, Om Johny The, tante Yanti dan tante Lieng-Lieng, atas perhatian, semangat baru dan peneguhan iman dari buku karya Om.
16. Ntoek mas Yerry, totok, cista, mas yongki, mbak ajeng atas kesediaannya mendukung kelancaran selama di bangku kuliah.
17. Semua teman-teman psikologi angkatan 05’ yang tidak dapat disebutkan satu per satu, untuk pertemanan yang berkesan.
18. Ntoek mbak Bertha Devi, mbak Nina, Cik Pan, Cha2 atas nasehat dan dukungannya. Beatrik, Momo, Ditha, Dyah. Thank’s untuk pertemanan yang berkesan.
19. Semua orang yang t’lah mengisi, datang dan pergi dalam hidup ku..., atas semua warna-warni yang ikut terlukis dan memberikan bingkai hidupku.
penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca sekalian.
Yogyakarta, 27 Maret 2010 Angelia Prasastha W.N
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……… ii
HALAMAN PENGESAHAN……….. iii
HALAMAN MOTTO ………. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN……….. v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA……… vi
ABSTRAK……….. vii
ABSTRACT………... viii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH…… ix
KATA PENGANTAR……… x
DAFTAR ISI………. xiii
DAFTAR TABEL……….. xvii
DAFTAR GAMBAR………. xix
BAB I PENDAHULUAN…………... 1
A. Latar Belakang Masalah……… 1
B. Rumusan Masalah……… 5
C. Tujuan Penelitian……….. 5
D. Manfaat Penelitian………. 6
BAB II LANDASAN TEORI……… 7
A. Definisi Organizational Citizenship Behavior (OCB)………… 7
1. Pengertian OCB………... 7
2. Dimensi-Dimensi OCB……… 8
3. Faktor Yang Mempengaruhi OCB……… 10
B. Definisi Professional Qualtiy Of Life (ProQOL)……… 12
1. Pengertian ProQOL……… 12
2. Subskala ProQOL………. 13
a. Compassion Satisfaction……… 13
b. Burnout………... 13
c. Compassion Fatigue………... 17
2. Dimensi-Dimensi Karakteristik Pekerjaan……… 21
3. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan……... 22
D. Dinamika Antar Variabel……….. 24
E. Hipotesis Penelitian………. 26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN………. 27
A. Jenis Penelitian……….. 27
B. Identifikasi Variabel Penelitian………. 27
C. Definisi Operasional………... 28
D. Lokasi dan Subyek Penelitian……….. 32
1. Lokasi Penelitian………. 32
2. Subyek Penelitian……… 32
E. Prosedur Penelitian……….... 32
F. Metode dan Alat Pengumpulan Data……… 34
G. Validitas, Reliabilitas Alat Ukur……… ……….. 38
1. Validitas……….. 38
2. Reliabilitas……….. 39
H. Subyek dan Uji Coba Alat Penelitian……… 40
1. Subyek Uji Coba Alat Penelitian………... 40
2. Uji Coba Alat Penelitian………. 40
3. Uji Coba Validitas dan Reliabilitas Alat Penelitian……… 41
I. Metode dan Teknik Analisis Data ……… 44
J. Uji Hipotesa……….. 44
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………... 45
A. Sekilas Tentang PT. BRI……….. 45
B. Pelaksanaan Penelitian………. 47
C. Deskripsi Subyek Penelitian………. 48
D. Uji Item dan Alat Ukur ……… 50
E. Analisis Data dan Hasil Penelitian………... 53
xv
B. Saran………. 97
DAFTAR PUSTAKA………. 99
Tabel 2 : Distribusi Item Subskala ProQOL……….. 36
Tabel 3 : Distribusi Item Skala Karakteristik Kerja………… ……… 38
Tabel 4 : Spesifikasi Item Skala OCB Setelah Uji Coba……… 41
Tabel 5 : Spesifikasi Item ProQOL Setelah Uji Coba ……….. 42
Tabel 6 : Spesifikasi Item Karakteristik Kerja Setelah Uji Coba ….. ….. 43
Tabel 7 : Spesifikasi Item Skala OCB Penelitian……… 51
Tabel 8 : Spesifikasi Item Subskala ProQOL Penelitian ……… 52
Tabel 9 : Spesifikasi Item Karakteristik Pekerjaan Penelitian ………… 52
Tabel 10 :Hubungan Antara Compassion Satisfaction
dan Altruism dengan Karakteristik Pekerjaan
Sebagai Variabel Moderator……….. 60
Tabel 11 :Hubungan Antara Burnout dan Altruism dengan
Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator………… 62
Tabel 12 :Hubungan Antara Compassion Fatigue dan Altruism
dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator... 63
Tabel 13 :Hubungan Antara Compassion Satisfaction dan
Concientiousness dengan Karakteristik Pekerjaan
Sebagai Variabel Moderator………. 66
Tabel 14 :Hubungan AntaraBurnout dan Concientiousness
dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator… 67
Tabel 15 :Hubungan Antara Compassion Fatigue
dan Concientiousnes dengan Karakteristik Pekerjaan
Sebagai Variabel Moderator……… 69
Tabel 16 :Hubungan Antara Compassion Satisfaction
dan Sportsmanship dengan Karakteristik Pekerjaan
Sebagai Variabel Moderator……….. 72
Tabel 17 :Hubungan Antara Burnout dan Sportsmanship dengan
Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……….. 73
dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator … 78
Tabel 20 :Hubungan AntaraBurnout dan Courtsey dengan
Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……….. 79
Tabel 21 :Hubungan AntaraCompassion Fatigue dan Courtsey
dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…. 81
Tabel 22 :Hubungan AntaraCompassion Satisfaction dan Civic Virtue
dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……. 22
Tabel 23 :Hubungan AntaraBurnout dan Civic Virtue dengan
Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……… 85
Tabel 24 :Hubungan AntaraCompassion Fatigue dan Civic Virtue
dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…… 87
Gambar 2: Deskripsi Subyek Penelitian Berdasarkan Lama Kerja……… 48
Gambar 3: Deskripsi Subyek Penelitian Berdasarkan Status Pernikahan……… 49
Gambar 4: Deskripsi Subyek Penelitian Berdasarkan Jumlah Anak
Dalam Keluarga………. 49
Gambar 5: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Altruism
Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator……… 50
Gambar 6: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Concientiousness
Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator.... …. 59
Gambar 7: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Sportmanship
Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…….. 65
Gambar 8: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Courtsey
Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…….. 71
Gambar 9: Uji Interaksi Hubungan Antara ProQOL dan Civic Virtue
Dengan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Variabel Moderator…….. 77
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, manusia memenuhinya dengan berbagai cara, diantaranya, bekerja
melalui berbagai jenis pekerjaan. Salah satunya yaitu menjadi bagian dari organisasi,
dalam hal ini, perusahaan atau perkantoran tempatnya bekerja.
Manusia dan organisasi tidak dapat dipisahkan. Hal ini diungkapkan oleh
Cascio dan Wayne (1994) bahwa sumber daya manusia dan organisasi saling
membutukan satu sama lain. Tanpa sumber daya manusia organisasi tidaklah
berfungsi. Sedangkan manusia tidak dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya
serta melanjutkan fungsi-fungsinya apabila tidak terlibat dalam organisasi.
Dewasa ini organisasi dihadapkan pada arus globalisasi. Rothenberg (2002)
mendefinisikan globalisasi sebagai akselerasi, interaksi yang intensif dan integrasi
antar manusia, perusahaan dan pemerintahan dari berbagai negara. Era globalisasi
ditandai oleh perubahan yang pesat. Menurut Widawati (Prasetyo & Handoyo, 2002)
perubahan tersebut antara lain perubahan pasar, persaingan global, daur hidup
inovasi teknologi yang singkat, perubahan budaya, sosial dan politik. Perubahan
yang pesat menuntut adaptasi atau tuntutan kerja yang semakin meningkat. Oleh
karena itu, dibutuhkan keunggulan yang kompetitif untuk menghadapi arus
globalisasi.
Sikap dan perilaku sumber daya manusia di tempat kerja menentukan
kelangsungan organisasi (Handi & Suhariadi, 2003). Hal ini ditegaskan oleh Fisher,
Schoenfeldt dan Shaw (Saragih & Margareta, 2008) yang mengungkapkan bahwa
faktor paling potensial dalam penyediaan keunggulan kompetitif bagi organisasi
adalah sumber daya manusia. Hal ini karena organisasi tidak hanya bergantung pada
teknologi saja melainkan juga faktor sumber daya manusia yang berperan sebagai
kontrol di dalamnya. Oleh karena itu, Wuryanano (2008) menegaskan pentingnya
meningkatkan faktor sumber daya manusia. Almigo (2004) juga menekankan bahwa
sumber daya manusia memiliki sumbangan terbesar dalam pencapaian keberhasilan
organisasi.
Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi hendaknya memiliki
kualitas kehidupan yang profesional dan memiliki peran ekstra di tempat kerja.
Kualitas kehidupan yang profesional (Professional Quality Of Life / ProQOL)
diungkapkan oleh Stamm (2005) mengenai pengalaman positif yaitu compassion
satisfaction dan pengalaman negatif yaitu burnout dan compassion fatigue.
Compassion satisfaction adalah kepuasan yang diarahkan pada pekerjaan yang
dilakukan dengan baik. Sedangkan burnout adalah keputusasaan yang berkelanjutan
karena apa yang diharapkan tidak tercapai serta adanya kesulitan untuk melakukan
pekerjaan dengan efektif. Selanjutnya compassion fatigue adalah trauma sekunder
atau trauma yang dialami tidak langsung oleh seseorang. Kualitas kehidupan yang
profesional tersebut berperan menggambarkan kualitas kehidupan karyawan di
organisasi yang meliputi compassion satisfaction, burnout dan compassion fatigue.
Sedangkan perilaku ekstra peran atau Organizational Citizenship (OCB) adalah
perilaku bebas atau spontan yang ditentukan individu, tidak secara langsung atau
meningkatkan keefektifan organisasi (Organ, Podsakoff, Mackenzie, 2006). OCB
terbukti secara empiris meningkatkan keefektifan organisasi (Organ, Podsakoff,
Mackenzie, 2006). Melalui OCB kontribusi positif karyawan tidak terbatas pada
kewajiban formal namun melebihi standar kewajiban formal. Motowidlo (Saragih &
Margaretha, 2008) mengungkapkan pentingnya OCB di tempat-tempat kerja dewasa
ini dengan beberapa alasan antara lain: 1) Pekerja membutuhkan usaha-usaha yang
lebih atau ekstra dalam menghadapi kompetisi global ; 2) Bekerja secara
berkelompok merupakan hal yang lazim daripada bekerja secara sendiri. Hal ini
karena perilaku OCB yang dilakukan oleh sebagian besar karyawan memiliki
dampak yang berarti bagi organisasi daripada hanya dilakukan oleh seorang
karyawan dalam organisasi ; 3) Membutuhkan kemampuan adaptasi; 4) Pentingnya
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya Jahangir, Akbar dan Haq
(2004) menambahkan bahwa organisasi yang sukses mempunyai karyawan yang
bertanggung jawab terhadap peran-peran yang melebihi tanggung jawab peran
formalnya.
Kualitas kehidupan yang profesional dan perilaku ekstra peran, keduanya,
dapat terwujud ketika seseorang bekerja yaitu melalui sikap dan perilaku- perilaku di
tempat kerja. Hal ini berarti bahwa kualitas kehidupan yang profesional dan perilaku
ekstra peran tidak dapat dipisahkan, salah satunya, dari karakteristik pekerjaan.
Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti atau ciri kesamaan dari
berbagai jenis pekerjaan yang mempunyai sifat berbeda-beda (Suhartanto, 2006).
Karakteristik pekerjaan dapat mempengaruhi kondisi psikologis yang dibutuhkan
pengalaman bertanggungjawab terhadap pekerjaan , pengalaman atas pengetahuan
hasil pekerjaan. Hal ini tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang
melalui potensi motivasi (Landy 1989).
Hackman dan Oldham (Roger & Tremblay, 1998) mengungkapkan bahwa
kondisi psikologis dari karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap sikap dan
perilaku di tempat kerja. Karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap motivasi,
kepuasan, performansi, kehadiran dan kualitas kerja. Hal ini juga didukung oleh
penelitian empiris yang menunjukkan bahwa potensi motivasi dalam karakteristik
pekerjaan meningkatkan kepuasan kerja, performansi, usaha-usaha yang dilakukan
karyawan, tingkat kehadiran dan menurunkan tingkat karyawan untuk mengundurkan
diri dari pekerjaan. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penelitian
oleh Smith (Organ, Podsakoff, MacKenzie, 2006) yang mengungkapkan bahwa
karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap sikap karyawan di tempat kerja,
dalam hal ini yaitu, perilaku ekstra peran pada subyek karyawan bank.
Berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh adanya ketidakkonsistenan hasil
penelitian mengenai pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap sikap dan
perilaku-perilaku di tempat kerja. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan
penelitian yaitu mengenai karakteristik pekerjaan sebagai moderator terhadap
hubungan antara kualitas kehidupan yang profesional (professional quality of life)
dengan organizational citizenship behavior (OCB). Selain itu, penelitian ini juga
masih jarang dilakukan, terutama di sektor perbankan. Oleh karena itu, peneliti
memilih subyek penelitian karyawan bank yaitu karyawan di kantor cabang PT. BRI
Adapun beberapa pertimbangan peneliti memilih karyawan di kantor cabang
PT. BRI Katamso di Yogyakarta sebagai subyek penelitian yaitu: 1) PT. BRI
merupakan bank tertua di Indonesia (bri.co.id) ; 2) eksistensinya di era krisis moneter
justru mengalami surplus atau meningkatnya nilai tabungan (dalam
www.indonesiaindonesia.com) ; 3) Tugas-tugas operasional di era globalisasi yang
harus dilakukan oleh karyawan PT. BRI Katamso seperti mencari nasabah dan
melaksanakan arahan dari kantor Pusat PT.BRI di Yogyakarta sebagaimana
tercantum dalam buku pedoman operasional PT.BRI (Buku Pedoman Operasional
Kanca/Kancapem/BRI Unit Brinets, 2007).
B. Rumusan Masalah
Apakah ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan
Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan karakteristik pekerjaan yang
signifikan sebagai variabel moderator ?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Professional
Quality Of Life (ProQOL) dan Organizational Citizenship Behavior (OCB)
D. Manfaat Penelitian
• Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan
pemikiran dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perluasan penelitian
selanjutnya bagi dunia industri dan ilmu psikologi, terutama yang
berhubungan dengan karakteristik pekerjaan, Professional Quality Of Life
(ProQOL)dan Organizational Citizenship Behavior (OCB).
• Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau dapat memberikan
masukkan yang berarti di bidang industri pada umumnya, dan perbankan,
dalam hal ini yaitu kantor cabang PT. BRI Katamso di Yogyakarta pada
khususnya, serta pembaca ataupun penelitian di bidang serupa, sehubungan
dengan karakteristik pekerjaan dalam menentukan sikap atau perilaku di
tempat kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan untuk
A. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 1. Pengertian OCB
Perilaku sumber daya manusia merupakan aspek penting bagi kelangsungan
organisasi. Katz dan Khan (Novliadi, 2008) menggolongkan perilaku di tempat kerja
menjadi dua yaitu in-role behavior dan extra role behavior. In-role behavior
merupakan perilaku peran formal yang ditetapkan oleh organisasi yang tercantum
dalam uraian jabatan. Lebih lanjut, perilaku ini secara langsung berkaitan dengan
sistem reward formal organisasi ataupun sanksi. Sedangkan extra role behavior,
yaitu istilah lain dari OCB, merupakan perilaku yang memberikan kontribusi positif
yang melebihi peran formal atau yang tidak tercantum dalam uraian jabatan. Perilaku
ekstra peran tidak berkaitan dengan reward dari sistem formal yang akan diterima.
Melalui perilaku ekstra peran penyelesaian tugas-tugas akan lebih efektif karena
perilaku karyawan melebihi yang diharapkan oleh organisasi. Dalam penelitian ini,
OCB merupakan perilaku ekstra peran.
Beberapa tokoh mengemukakan definisi Organizational Citizenship Behavior
(OCB). Organ (Organ, Podsakoff, Mackenzie, 2006) mendefinisikan OCB sebagai
perilaku bebas atau spontan yang ditentukan individu, tidak secara langsung atau
eksplisit mendapat imbalan dari sistem formal dan secara keseluruhannya
meningkatkan keefektifan organisasi. Lebih lanjut, OCB berdampak bagi keefektifan
dalam kelompok kerja kemudian mengkontribusikannya bagi organisasi (Wikipedia,
2008). Sedangkan Jhons, Shnake dan Morrison (Franches, Tjahoanggoro, Atmadji,
2001) mendefinisikan OCB sebagai perilaku sukarela bersifat informal sehingga sulit
untuk memberikan imbal balik yang bersifat formal namun memberikan keuntungan
karena menciptakan keefektifan organisasi.
Berdasarkan beberapa definisi OCB tersebut di atas maka berikut ini dapat
disimpulkan beberapa pokok pengertian OCB antara lain :
a.Tindakan bebas, bersifat sukarela, spontan. Artinya bahwa perilaku tersebut bukan
berdasarkan saran ataupun perintah orang lain.
b.Tindakan yang informal atau tidak tercantum dalam uraian jabatan sehingga sulit
untuk diberi imbal balik ataupun penghargaan yang formal secara tegas.
c.Tindakan yang efisien karena melebihi persyaratan formal sehingga mampu
menciptakan keefektifan organisasi.
Dari pokok-pokok pengertian OCB di atas dapat disimpulkan bahwa
pengertian OCB adalah perilaku yang tidak didasarkan oleh saran ataupun perintah
orang lain, bersifat informal namun efisien sehingga menguntungkan organisasi
walaupun tidak dapat secara tegas untuk diberikan reward formal.
2. Dimensi-Dimensi OCB
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dimensi-dimensi OCB yang
diungkapkan oleh Podsakoff, Mackenzie, Moorman, Fetter, yang didasarkan pada
konseptual OCB menurut Organ (Organ, Podsakoff, Mackenzie, 2006 ; periksa juga
Altruism adalah perilaku membantu, yang bersifat bebas, yang berkaitan
dengan masalah-masalah organisasi ataupun masalah pribadi orang lain.
Dimensi ini mengacu pada pemberian pertolongan yang bukan kewajiban
yang ditanggung atau peran formalnya.
Conscientiousness adalah perilaku kinerja dari prasyarat formal yang bersifat
bebas namun melebihi standar minimum persyaratan peran di organisasi yang
meliputi kehadiran, kepatuhan terhadap kewajiban dan peraturan, istirahat
kerja, dan sebagainya. Dimensi ini mengarah pada perilaku yang jauh
menjangkau di atas peran formal.
Sportsmanship adalah kesediaan untuk bertoleransi tanpa komplain terhadap
keadaan yang jauh dari harapan ideal. Dimensi ini mengarah pada toleransi
yang tinggi terhadap organisasi meliputi perilaku positif yaitu menghindari
keluhan yang tidak perlu ataupun tanpa mengeluh.
Courtesy adalah perilaku yang bersifat bebas yang bertujuan untuk mencegah
timbulnya permasalahan dengan orang lain di tempat kerja ataupun mencegah
permasalahan dengan pihak di luar relasi kerja.
Civic virtue adalah perilaku yang menunjukkan partisipasi untuk bertanggung
jawab terlibat dalam organisasi termasuk mempedulikan kelangsungan
organisasi. Dimensi ini mengarah pada tanggung jawab kelangsungan
organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas bidang yang sedang
3. Faktor Yang Mempengaruhi OCB
Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi OCB menurut
beberapa tokoh antara lain :
a. Budaya dan iklim organisasi
Organ dan Sloat (Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa iklim dan budaya
organisasi berpengaruh terhadap OCB. Iklim organisasi yang positif berarti mampu
menciptakan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya, adanya perilaku sportif dan
perhatian dari pengawas dan kepercayaan terhadap adanya perlakuan yang adil di
organisasi. Hal tersebut dapat mendorong karyawan untuk melakukan tindakan
melebihi uraian pekerjaannya
b. Kepribadian
Kepribadian dan suasana hati berpengaruh terhadap munculnya OCB secara
individual maupun kelompok. Purba dan Seniati (2004), dalam penelitiannya,
menunjukkan bahwa kepribadian berpengaruh signifikan terhadap OCB.
c. Suasana hati (mood)
Menurut George dan Brief (Novliadi, 2008) kemauan membantu orang lain
dipengaruhi oleh suasana hati. Hal ini karena suasana hati merupakan karakteristik
yang sifatnya berubah-ubah sehingga suasana hati yang positif dapat mendorong
seseorang membantu orang lain.
c. Persepsi terhadap dukungan sosial
Shore dan Wayne (Novliadi, 2008), dalam studinya, memperoleh hasil bahwa
persepsi dukungan organisasional (Perceived Organizational Support / POS)
merasa didukung oleh organisasi akan memberikan timbal balik serta meminimalkan
ketidakseimbangan hubungan melalui perilaku organizational citizenship
d. Persepsi terhadap Kualitas Interaksi Atasan-bawahan
Riggio (Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa interaksi yang berkualitas
tinggi tersebut bisa mengakibatkan persepsi positif karyawan. Interaksi yang
dimaksud seperti adanya pemberian motivasi dan dukungan dari atasan. Sejalan
dengan itu rasa percaya dan hormat akan memotivasi karyawan melakukan tindakan
melebihi harapan organisasi.
e. Masa Kerja
Greenberg dan Baron (Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa masa kerja
mempengaruhi OCB. Hal ini karena OCB merupakan “pengukuran investasi”
karyawan di organisasi. Artinya, semakin lama masa kerja seseorang, semakin tinggi
persepsi bahwa mereka memiliki “investasi” dalam organisasi
f. Jenis Kelamin
Konrad, Gabriel, Garder, Morrison dan Dienfendorff (Novliadi, 2008)
mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap OCB berdasarkan
jenis kelamin. Konrad (Novliadi, 2008) menyebutkan bahwa wanita lebih menonjol
dalam perilaku menolong orang lain daripada pria. Selanjutnya Gabriel dan Garder
(Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa wanita cenderung mengutamakan
pembentukan relasi (relational identities). Bridges dan George (Novliadi, 2008)
menambahkan bahwa wanita lebih menujukkan perilaku menolong daripada pria di
tempat kerja. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Morrison (Novliadi, 2008) juga
Lebih lanjut, Dienfendorff (Novliadi, 2008) mengungkapkan bahwa dibandingkan
dengan pria, wanita lebih menganggap bahwa OCB adalah bagian dari perilaku
in-role. Hal ini membuktikan bahwa wanita cenderung melakukan internalisasi terhadap
harapan kelompok, rasa kebersamaan dan tindakan menolong sebagai bagian dari
pekerjaan.
g. Karakteristik pekerjaan
Johari dan Yahya (2009) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku organizational
citizenship. Hasil tersebut juga serupa dengan studi oleh Pearce dan Gregersen serta
Van Dyne (Organ, Podsakoff & Mackenzie, 2006) yang hasil penelitiannya
mengungkapkan adanya pengaruh motivating potential scores (MPS) terhadap OCB.
B. Professional Quality Of Life (ProQOL) 1. Pengertian ProQOL
Professsional Quality Of Life (ProQOL) adalah pengalaman positif yaitu
compassion satisfaction dan pengalaman negatif yaitu burnout dan compassion
fatigue.
Professsional Quality Of Life (ProQOL) merupakan versi nama terbaru dari
skala CFST (Compassion Fatigue Secondary Trauma). Ada dua alasan untuk perubahan nama skala tersebut. Pertama, skala CFST memiliki kesalahan pada
psikometri skalanya. Kedua, penggantian nama tersebut didasarkan atas alasan
bahwa item-item yang disajikan berfokus ke arah kehidupan yang profesional yaitu
Of Life mampu memperbaiki hal-hal yang negatif dari rasa kepedulian serta
menunjang pengaruh positif terhadap rasa kepedulian(Stamm, 2005).
2. Subskala ProQOL
Professional Quality Of Life (ProQOL) terdiri dari tiga skala terpisah yang
belum memiliki skor gabungan ataupun kombinasi. Hal ini karena penelitian Stamm
(2005) belum menemukan adanya kombinasi skor tinggi compassion satisfaction
sekaligus skor tinggi pada burnout ataupun compassion fatigue dalam diri seseorang.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap subskala ProQOL memiliki keunikan
psikometri masing-masing. Berikut ini subskala dari professional quality of life :
a. Compassion Satisfaction
a. 1. Pengertian Compassion Satisfaction
Compassion satisfaction adalah kepuasan yang diarahkan pada kemampuan
melakukan pekerjaan dengan baik (Stamm, 2005). Compassion memiliki pengertian
yang lebih dari sekadar empati (Wikipedia, tanpa tahun). Akan tetapi, belum ada
literatur yang mengungkapkan anteseden compassion satisfaction.
b. Burnout
b.1. Pengertian Burnout
Burnout adalah perasaan putus asa berkelanjutan yang diasosiasikan dengan
beban kerja yang berlebih namun tidak ada perubahan yang berarti melalui
karena kurang adanya dukungan (Stamm, 2005). Stamm mengungkapkan bahwa burnout
juga merepresentasikan mood (suasana hati) yang negatif. Tokoh Freundenburger (Mitra
riset, 2008) memberikan istilah burnout untuk pertama kalinya dan mendefinisikannya sebagai kelelahan atau frustasi karena yang diharapkan tidak tercapai atau sekuat tenaga mencapai tujuan namun mengalami kesulitan untuk mencapainya atau jauh dari kenyataan. Selanjutnya Frith dan Britton (Mitra riset, 2008) mendefinisikan burnout sebagai keadaan internal negatif meliputi pengalaman psikologis yang menunjukkan kelelahan atau kehabisan tenaga serta turunnya motivasi bekerja. Pines dan Aronson (Mitra riset, 2008) menambahkan bahwa burnout merupakan keadaan lelah secara fisik, emosi dan mental. Konsep burnout hanya dipergunakan dalam kaitannya dengan pekerjaan (Mitra riset, 2008).
Pada penelitian ini peneliti memilih konseptual burnout dari Stamm yang dalam
penjelasannya burnout tidak diklasifikasikan ke dalam dimensi-dimensi.
b.2. Faktor Yang Mempengaruhi Burnout • Gender
Gibson, Ivancevich dan Donnely serta Schultz (Sihotang, 2004) mengungkapkan hal yang berlainan terhadap burnout berdasarkan gender. Gibson, Ivancevich dan Donnely (Sihotang, 2004) mengungkapkan bahwa secara umum wanita tidak mudah mengalami burnout daripada pria. Hal ini disebabkan adanya tekanan sosial terhadap peran gender. Bagi pria, ‘bekerja’ adalah suatu hal yang mutlak untuk menghidupi keluarga. Sedangkan bagi wanita, boleh ataupun tidak boleh bekerja, bukan merupakan keharusan. Di sisi lain, Schultz (Sihotang, 2004) menyimpulkan bahwa wanita memiliki resiko lebih besar mengalami burnout daripada pria karena wanita lebih sering merasakan kelelahan emosional. Perbedaan fisik, sosial dan psikologis serta cara menghadapi masalah antara pria dan wanita juga menjadi dasar pertimbangannya.
• Kepercayaan Diri (self-confidence)
Gil Monte mengungkapkan bahwa kepercayaaan diri (Peiró & Gil-Monte, 1998) merupakan anteseden
burnout. Kepercayaan diri yang dimaksud yaitu kepercayaan individu untuk memiliki kepastian terhadap
kesuksesan karena kemampuannya. Seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri memiliki kesulitan
• Lingkungan fisik
Caputo (Sedjo, 2005) menngungkapkan bahwa lingkungan fisik berpengaruh terhadap
burnout. Lingkungan fisik yang dimaksud tersebut yaitu : ¾ Kurangnya otonomi profesional
Perasaan kurang mampu melakukan kontrol dalam pekerjaan dapat menyebabkan
burnout.
¾ Berhadapan dengan publik
Pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan orang dapat menyebabkan burnout. Interaksi
dengan publik menuntut kesabaran sehingga mampu menunjukkan keterampilan sosial bahkan tanpa
menghiraukan perasaannya sendiri.
¾ Konflik peran
Ada dua jenis konflik peran yang menyebabkan terjadinya burnout. Pertama, yaitu konflik
peran mengenai ketidakcocokan individu dengan pekerjaannya. Kedua, yaitu pertentangan antara
nilai-nilai yang dimiliki individu dengan kecenderungan dari pekerjaan.
¾ Peran ambigu
Peran ambigu adalah kekaburan tanggung jawab dalam pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat
ketidakjelasan parameter dan ruang lingkup pekerjaan sehingga tujuan organisasi dan individu
mengalami kekaburan.
¾ Beban kerja berlebihan yang terus menerus
Lamanya jam kerja dan banyaknya tanggung jawab atau tuntutan pekerjaan yang
berulang-ulang diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya burnout.
¾ Stressor Lingkungan fisik
Ketiadaan atau kurangnya fasilitas yang mendukung kinerja dalam organisasi dapat
menyebabkan burnout.
• Personal
Caputo (Sedjo, 2005) juga mengungkapkan bahwa faktor personal berpengaruh terhadap
burnout. Faktor personal tersebut yaitu :
Berdasarkan penelitian bahwa burnout banyak ditemukan pada orang yang memiliki
idealisme dan antusiasme tinggi.
¾ Perfeksionis
Orang dengan sifat perfeksionis selalu mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Namun
kebutuhan untuk selalu sempurna dapat menyebabkan frustasi yang berakhir dengan burnout.
¾ Berkomitmen terlalu tinggi (Overcommitment)
Rasa sulit untuk mengatakan ‘tidak’ pada pekerjaan serta kompetisi yang tinggi dapat
menyebabkan terjadinya burnout.
¾ Pekerjaan sebagai yang sangat bernilai dan berharga (Single mindedness)
Seseorang yang menganggap pekerjaan adalah suatu yang berharga, bernilai sehingga sangat
penting bagi hidupnya akan berusaha mencapai kesuksesan. Namun jika karena sesuatu hal kesuksesan
menurun maka dapat menyebabkan terjadinya burnout.
¾ Kurangnya dukungan
Kurangnya dukungan sosial di tempat kerja yaitu dari rekan kerja, supervisor, atasan,
keluarga, teman-teman, dll. dapat menimbulkan burnout.
c. Compassion Fatigue
c.1. Pengertian Compassion Fatigue
Compassion Fatigue (CF) adalah trauma yang tidak secara langsung dialami
oleh seseorang (Stamm, 2005). Compassion Fatigue (CF) disebut juga sebagai
Secondary Traumatic Stress (STS) ataupun Vicarious Trauma (VT). Istilah awalnya
dicetuskan oleh Figley (Huggard, Peter. & Huggard, Jayne., 2008) yaitu secondary
victimization.Figley (1995) mengungkapkan bahwa compassion fatigue adalah stress
yang dihasilkan dari usaha memberikan pertolongan bagi orang – orang yang
mengalami trauma Hal ini menegaskan pengertian compassion fatigue sebagai
“harga yang harus dibayar” untuk penderitaan secara emosional ataupun fisik dari
c.2. Faktor Yang Mempengaruhi Compassion Fatigue
Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Compassion
Fatigue :
• Riwayat Hidup
Peneliti menemukan bahwa riwayat hidup seseorang dapat
mengkontribusikan compassion fatigue (Meyers & Cornille, 2002 ; periksa juga
Mathieu, 2007). Miller (Huggard, 2003) mengungkapkan bahwa compassion fatigue
merupakan konsekuensi dari ‘terkurasnya’ sumber emosi internal seseorang.
Konsekuensi ini dapat dialami oleh seseorang yang melibatkan dirinya pada
kepedulian terhadap orang lain, khususnya dalam peristiwa yang sifatnya darurat.
Schawm (Huggard, Peter. & Huggard, Jayne., 2008) menambahkan bahwa compassion
fatigue tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang yang secara profesional
membantu orang lain (professional helpers) dan para pemerhati (carers) melainkan
juga para sukarelawan (volunteers). Hal ini karena keterlibatan tersebut dapat memunculkan
trauma sekunder atau trauma yang dialami secara tidak langsung oleh seseorang. Picket (Figgley,
1995) mengungkapkan ratusan penelitian yang menyatakan bahwa individu yang
mengalami trauma bukan hanya korban trauma melainkan juga yang tidak secara
langsung terlibat trauma. Stamm (2005) menambahkan bahwa hanya mendengar
peristiwa traumatik dapat berpotensi trauma pada diri seseorang. Di sisi lain, Peter
Huggard dan Jayne Huggrard (2008) menambahkan bahwa compassion fatigue dapat
terjadi pada siapapun termasuk mereka yang bukan bekerja di kalangan profesional
• Strategi coping
Stamm (2002) mengungkapkan bahwa tidak semua orang yang memberikan
perhatian terhadap orang lain terpengaruh hanya oleh hal-hal yang negatif saja.
Dalam hal ini, strategi coping menjadi penting sebagai penentu kontribusi
compassion fatigue seseorang. Seseorang yang puas karena telah mengkontribusikan
kemampuannya pada orang yang membutuhkan pertolongan akan lebih kecil
kemungkinan terkena resiko compassion fatigue.
• Mempedulikan diri sendiri (self care)
Menurut Stamm (2002) seseorang yang tidak cukup mempedulikan atau
memperhatikan dirinya sendiri, dalam hal ini kebutuhan ataupun kepentingannya,
ketika berbelas kasih meringankan beban orang lain dapat berpotensi compassion
fatigue.
3. Peran Professsional Quality Of Life (ProQOL)
Di era globalisasi keunggulan yang kompetitif sangat dibutuhkan. Hal ini
ditentukan oleh sumber daya manusia yang unggul untuk mempertahankan eksistensi
organisasi menghadapi era globalisasi. Keunggulan yang dimiliki terkait dengan
kualitas organisasi. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan profesional.
Organisasi yang berkualitas berarti harus profesional dalam kinerjanya. Oleh
karena itu, melalui skala Profesional Quality Of Life (ProQOL) dapat diketahui
kualitas kehidupan karyawan yang profesional di tempat kerja. Hal ini karena
yang mendukung perubahan positif (Stamm, 2005). Stamm (2005) mengungkapkan
bahwa melalui skala ProQOL dapat diketahui gambaran compassion satisfaction,
burnout, dan compassion fatigue yang dimiliki karyawan di tempat kerja. ProQOL
dapat menjadi pedoman bagi karyawan ataupun keseimbangan organisasi, dalam hal
ini meliputi pengalaman positif yaitu compassion satisfaction ataupun negatif yaitu
burnout dan compassion fatigue di organisasi.
Stamm (2005) mengungkapkan bahwa ProQOL berperan untuk mengetahui
keseimbangan dalam organisasi serta dapat memberikan pertimbangan bagi
kehidupan karyawan di organisasi. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai kombinasi
skor ProQOL. Apabila skor compassion satisfaction lebih tinggi dibandingkan skor
burnout dan compassion fatigue ataupun jika diperoleh lebih tingginya skor
compassion fatigue dibandingkan skor compassion satisfaction dan burnout , atau
berbagai kombinasi skor lainnya. Hal ini dapat memberikan masukan yang berarti
bagi organisasi untuk meningkatkan atau lebih memperhatikan kehidupan
profesionalisme karyawannya.
C. Karakteristik Pekerjaan
1. Pengertian Karakteristik Pekerjaan
Karakteristik pekerjaan adalah dimensi inti atau persamaan sifat dari berbagai
pekerjaan (Suhartanto, 2006). Heads (Stevens, 2006) mengungkapkan bahwa
karakteristik pekerjaan merupakan pemenuhan kondisi psikologis seseorang ketika
meaningfulness), pengalaman bertanggung jawab dalam kerja (experienced
responsibility), pengetahuan atas hasil pekerjaan (knowledge of Results).
Oldham (Nogradi, Yardley, Kanters, 1993) mengungkapkan bahwa karakteristik
pekerjaan berinteraksi atau mempengaruhi beberapa variabel perbedaan-perbedaan individu dalam
menentukan hasil-hasil kerja yang efektif melalui potensi motivasi pekerjaan.
2. Dimensi-Dimensi Karakteristik Pekerjaan
Hackman dan Oldham (Buys, Olckers, Schaap, 2007) mengembangkan
dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan yang sebelumnya diteliti oleh Turner dan
Lawrence. Dimensi-dimensi tersebut yaitu:
a. Keragaman keterampilan (Skill Variety) adalah penyelesaian pekerjaan yang
melibatkan berbagai aktivitas yang berbeda-beda. Artinya, pekerjaan dengan
keragaman tinggi menuntut berbagai kemampuan dan keterampilan untuk
menyelesaikannya.
b. Identitas tugas (Task Identity) adalah penyelesaian keseluruhan pekerjaan
yang hasilnya dapat diidentifikasi per bagian pekerjaan dari awal hingga
akhir. Artinya, bahwa pekerjaan memiliki kejelasan penyelesaian
tugas-tugasnya secara menyeluruh sehingga hasilnya dapat diidentifikasi.
c. Signifikansi tugas (Task Significance) adalah tingkat dimana pekerjaan
berdampak penting bagi di tempat kerja ataupun di luar lingkungan kerja.
Artinya bahwa pekerjaan tersebut memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan
pekerjaan seseorang.
d. Otonomi (Autonomy) adalah tingkat kebebasan dalam pekerjaan meliputi
prosedur-prosedur yang akan digunakan dalam pekerjaan. Artinya bahwa
pekerjaan menyediakan keleluasaan dimana seseorang mampu merancang
atau memprogram strategi menurut kebijaksananya secara mutlak dalam
menyelesaikan pekerjaan.
e. Umpan balik (feedback) adalah penerimaan informasi yang jelas mengenai
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan performansinya. Artinya,
seseorang menerima kejelasan mengenai pengetahuan terhadap
performansinya bekerja.
3. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan
Di era globalisasi organisasi membutuhkan desain pekerjaan yang berkualitas
baik sehingga dapat meningkatkan performasi karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan
karakteristik kerja yang baik. Hal ini karena karakteristik pekerjaan merupakan
bagian dari desain pekerjaan. Karakteristik pekerjaan yang baik mampu memotivasi
karyawannya melalui potensi motivasi.
Idaszak dan Drasgrow (Buys, Olckers, Schaap, 2007) mengungkapkan bahwa
karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap desain pekerjaan. Lebih lanjut Stevens
(2006) mengungkapkan bahwa karakteristik pekerjaan bermanfaat untuk
mengindentifikasi perbedaan dan persamaan antara pekerjaan dan untuk memutuskan
motivasi internal dalam mendesain atau mendesain ulang pekerjaan. Informasi
tersebut berpengaruh bagi manager untuk dapat memutuskan area umum mana yang
Adapun pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap pemenuhan kondisi
psikologis yang dibutuhkan oleh karyawan dalam bekerja seperti gambar berikut ini:
Gambar 1
Karakteristik Pekerjaan Mempengaruhi Kondisi Psikologis
Job Characteristics Critical Psychological States
Skill variety
Task Identity
Task significane
Experienced Meaningfulness Of The Work
Autonomy
Experienced Responsibility for Outcomes of Work
Feedback Knowledge of Actual Results Of Work Activities
Berdasarkan gambar di atas Stevens (2006) mengungkapkan bahwa dimensi
karakteristik pekerjaan yaitu keragaman keterampilan (skill variety), identitas tugas
(task Identity) dan signifikansi tugas (task significance) akan berpengaruh terhadap
pengalaman yang berarti (experienced meaningfulness). Sedangkan dimensi lainnya
yaitu otonomi (autonomy) akan mempengaruhi pengalaman bertanggung jawab
dalam kerja (experienced responsibility). Berikutnya umpan balik (feedback) akan
mempengaruhi pengetahuan atas hasil pekerjaan (knowledge of Results).
Ketiga kondisi psikologis tersebut merupakan tuntutan pemenuhan psikologis
ketika seseorang bekerja yang kemudian akan memotivasi karyawan melalui
pekerjaan.
Meskipun secara empiris dinamika variabel antara karakteristik pekerjaan,
kualitas kehidupan yang perofesional dengan perilaku ekstra peran masih jarang
ditemukan, namun penelitian sebelumnya dan penjelasan teoritis dari beberapa ahli
dapat mengungkapkan dinamika antar variabel pada penelitian ini.
Karakteristik pekerjaan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat
dipisahkan ketika seseorang bekerja. Steven (2006) mengungkapkan bahwa
karakteristik pekerjaan, dalam hal ini meliputi potensi motivasi, berpengaruh
terhadap kondisi psikologis karyawan meliputi pengalaman berarti dalam pekerjaan
(experienced meaningfulness), pengalaman bertanggung jawab dalam pekerjaan
(experienced responsibility), pengalaman terhadap pengetahuan atas hasil pekerjaan
(knowledge of Results). Lebih lanjut, Hackman dan Oldham (Roger & Tremblay,
1998) mengungkapkan bahwa kondisi psikologis dari karakteristik pekerjaan
berpengaruh terhadap sikap dan perilaku di tempat kerja.. Hal ini didukung oleh
penelitian empiris yang juga menunjukkan bahwa potensi motivasi dalam
karakteristik pekerjaan meningkatkan kepuasan kerja, performansi, usaha-usaha yang
dilakukan karyawan, tingkat kehadiran dan menurunkan tingkat karyawan untuk
mengundurkan diri dari pekerjaan. Johari dan Yahya (2009) dalam penelitiannya
mengungkapkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap
perilaku organizational citizenship. Hasil tersebut juga serupa dengan studi oleh
Pearce dan Gregersen serta Van Dyne (Organ, Podsakoff, Mackenzie, 2006) yang
hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa potensi motivasi berpengaruh terhadap
OCB. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penelitian oleh Smith
pekerjaan tidak berpengaruh terhadap sikap karyawan di tempat kerja, dalam hal ini
yaitu, perilaku ekstra peran pada subyek karyawan bank
Stamm (2005) mengungkapkan bahwa profesional quality of life (ProQOL)
sebagai pengertian dari item-item pada skala ProQOL nya, yang berisi pengalaman
positif (compassion satisfaction) ataupun negatif (burnout dan compassion fatigue)
yang berkaitan dengan kualitas kehidupan yang profesional. Hal ini sejalan atau
memiliki implikasi dengan pengertian perilaku ekstra peran dari Organ (Organ,
Podsakoff, Mackenzie, 2006) yang merupakan perilaku bebas, sukarela, informal,
melebihi standar uraian jabatan, tidak secara langsung berkaitan dengan reward
formal namun keseluruhannya mewujudkan keefektifan organisasi. Penelitian oleh
Schepman dan Zarate (2008) menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara
burnout dan OCB. Akan tetapi, pada penelitian oleh Emmerik, Jawahar dan Stone
(2005) diperoleh bahwa dimensi burnout yaitu reduced personal accomplishment berkorelasi
signifikan pada altruism, sedangkan dimensi burnout yaitu emotional exhaution dan
depersonalization diasosiasikan negatif dengan OCB.
E. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memiliki hipotesis sebagai
berikut :
1. Hipotesis Mayor :
Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan
Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan karakteristik pekerjaan yang
2. Hipotesis Minor :
H1 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan altruism
dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai variabel
moderator.
H2 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan
concientiousness dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai
variabel moderator.
H3 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan
sportsmanship dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai
variabel moderator.
H4 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan courtesy
dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai variabel moderator.
H5 : Ada hubungan antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan civic
virtue dengan karakteristik pekerjaan yang signifikan sebagai variabel
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen dan dependen dengan variabel moderator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
Professional Quality Of Life / ProQOL (compassion satisfaction, burnout, compassion fatigue) dan organizational citizenship behavior / OCB (altruism, concientiousness, sportmanship, courtesy, civic virtue) dengan karakteristik pekerjaan sebagai moderator.
B. Identifikasi Variabel Penelitian
1. Variabel bebas : Karakteristik pekerjaan, Professional Quality Of Life /ProQOL (Compassion Satisfaction, Burnout, Compassion Fatigue),
2. Variabel tergantung :Organizational Citizenship Behavior /OCB (Altruism, Concientiousness, Sportmanship, Courtesy, Civic Virtue)
3. Variabel moderator : interaksi antara ProQOL dengan Karakteristik Pekerjaan
C. Definisi Operasional
1. Organizational Citizenship Behavior (OCB)
OCB adalah perilaku bebas, sukarela, informal, melebihi standar uraian jabatan, tidak secara langsung berkaitan dengan reward formal namun keseluruhannya mewujudkan keefektifan organisasi. Adapun dimensi-dimensi OCB sebagai berikut :
• Altruism yaitu perilaku yang bersedia, sukarela, sepenuh hati untuk
membantu pekerjaan ataupun masalah orang lain.
• Concientiousness yaitu perilaku di atas standar peraturan formal yang
berkaitan dengan kehadiran, waktu istirahat, pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan kepatuhan terhadap peraturan.
• Sportmanship yaitu perilaku yang tidak mengeluhkan hal sepele, selalu
berfokus pada sisi positif, tidak melebih-lebihkan masalah dan tidak mencari-cari kesalahan ataupun kekurangan.
• Courtesy yaitu perilaku yang mencegah ataupun menghindari permasalahan
dengan orang lain, tidak menyalahgunakan hak-hak orang lain dan mempertimbangkan dampak perilaku yang dilakukan terhadap orang lain. • Civic Virtue yaitu perilaku menghadiri pertemuan yang tidak diwajibkan,
OCB diukur menggunakan skala adaptasi dari Podsakoff, MacKenzie, Moorman dan Fetter dengan dimensi-dimensinya yaitu altruism, conscientiousness, sportmanship, courtsey, dan civic virtue. Skor jawaban subyek bergerak dari 0 sampai 4 untuk item favorabel dan 4 sampai 0 untuk item unfavorable.
2. Professional Quality Of Life (ProQOL)
ProQOL adalah pengalaman positif atau negatif di tempat kerja meliputi trauma sekunder, rasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan putus asa yang berkelanjutan atau kesulitan melakukan pekerjaan dengan efektif. Hal ini diuraikan melalui dimensi-dimensinya sebagai berikut :
a. Compassion satisfaction
Compassion satisfaction dikarakteristikkan dengan perasaan puas, senang dan berpikiran positif ketika menolong orang lain serta merasa bersemangat setelahnya, merasa senang dan puas dengan pekerjaan, merasa senang karena bisa mengikuti prosedur ataupun mekanisme organisasi, bangga terhadap apapun yang dapat dilakukan dan merasa berhasil dalam pekerjaan.
b. Burnout
Burnout adalah perasaan tidak senang ketika bekerja, merasa lelah dengan pekerjaan ataupun beban tugas, merasa terperangkap terhadap pekerjaan, merasa tidak dapat berkembang karena sistem organisasi, tidak dapat menjadi seseorang yang diinginkan, tidak memiliki pedoman yang menguatkan diri sendiri, mengalami gangguan tidur setelah peristiwa yang tidak menyenangkan.
Burnout diukur menggunakan skala adaptasi dari Beth Hudnall Stamm yaitu skala Burnout. Skala Burnout memiliki skor yang bergerak dari 1 sampai 6 untuk item favorabel dan bergerak dari 6 sampai 1 untuk item unfavorabel.
c. Compassion fatigue
Compassion fatigue adalah perasaan khawatir apabila tergantung dengan orang lain, sulit memisahkan antara kehidupan pribadi dan kerja, merasa terpengaruh dengan orang lain yang mengalami stress berat, merasa tertekan dengan pekerjaan, merasakan apa yang dialami orang lain, menghindari melakukan kegiatan ataupun situasi tertentu yang mengingatkan kembali pada suatu peristiwa yang tidak menyenangkan dan berpikir yang ‘tidak-tidak’ setelah membantu orang lain.
3. Karakteristik Pekerjaan
Karakteristik pekerjaan adalah dimensi inti dari berbagai jenis dan sifat pekerjaan, bagian dari desain pekerjaan, yang meliputi keragaman keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas otonomi dan umpan balik. Adapun dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan sebagai berikut :
• Keragaman keterampilan (Skill Variety) meliputi kesempatan melakukan
beberapa tugas dengan berbagai kemampuan, kemampuan untuk berbagai keahlian, tugas pekerjaan yang kompleks dan bervariasi.
• Identitas tugas (Task Identity) meliputi penyelesaian tugas dari awal hingga akhir, hasil
pekerjaan dapat diidentifikasi langsung, kontribusi berkaitan dengan hasil akhir pekerjaan dan pelayanan, adanya kesempatan menyelesaikan pekerjaan lain.
• Signifikansi tugas (Task Significance) meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan
mempengaruhi pekerjaan orang lain, pekerjaan mempengaruhi orang lain dan pekerjaan bermanfaat di tempat kerja.
• Otonomi (Autonomy) meliputi kebebasan dalam bekerja, bertanggung jawab
mengenai cara dan tenggat waktu penyelesaian pekerjaan dan berkesempatan untuk melakukan pekerjaan.
• Umpan balik (feedback) yaitu masukan kinerja dari atasan, supervisor ataupun
Skor skala karakteristik pekerjaan bergerak dari 1 sampai 5 untuk item favorabel dan 5 sampai 1 untuk item unfavorabel.
D. Lokasi dan Subyek Penelitian 1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kantor cabang PT. BRI Katamso di Yogyakarta.
2. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan cabang PT. BRI Katamso di Yogyakarta sejumlah 42 orang dengan kriteria sebagai berikut :
Karyawan tetap
Jenis kelamin : Pria dan wanita Masa kerja : lebih dari 30 hari
Adapun alasan peneliti menetapkan kriteria masa kerja lebih dari 30 hari karena hal tersebut disesuaikan dengan skala adaptasi ProQOL oleh Stamm (2005).
E. Prosedur Penelitian
Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :
2. Skala-skala penelitian ini diuji cobakan pada subyek yang memiliki kriteria yang sama.
3. Melakukan kesahihan item dan reliabilitas item setelah try out pertama yang selanjutnya dilakukan try out kedua untuk skala adaptasi karakteristik pekerjaan dan ProQOL. Sedangkan skala OCB hanya dilakukan satu kali try out karena diperoleh reliabilitas yang cukup tinggi sehingga peneliti memberanikan diri untuk tidak melakukan try out untuk yang kedua kali, setelah sebelumnya menggunakan skala adaptasi yang lain namun diperoleh reliabilitas yang kurang memuaskan. Sedangkan skala adaptasi ProQOL dan karakteristik pekerjaan dilakukan sebanyak dua kali try out dengan pertimbangan bahwa skala tersebut membutuhkan perbaikan pada perluasan alternatif jawaban sehingga peneliti melakukan try out sebanyak dua kali. 4. Data yang diperoleh kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan hasil data sekunder karakteristik pekerjaan dipungut dari skripsi Kristofer Adi dengan judul Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Terhadap Hubungan Antara Professional Quality Of Life (ProQOL) dan Counterproductive Work Behavior (CWB).
F. Metode dan Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpul data berupa skala Likert dengan menggunakan metode
summated ratings. Peneliti menggunakan alat ukur adaptasi dari Eropa dengan tujuan apakah alat ukur tersebut juga berlaku di Indonesia. Adapun uraian mengenai skala adaptasi yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Skala Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Skala OCB bertujuan untuk mengetahui extra behavior karyawan di tempat kerja melalui skor yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala adaptasi organizational citizenship behavior dari Podsakoff, MacKenzie, Moorman dan Fetter (Organ, Podsakoff, MacKenzie, 2006), yang dalam penelitiannya, menghasilkan koefisien reliabilitas altruism = .85 ; courtesy = .85 ; sportsmanship = .85 ; concientiousness = .82, dan civic virtue =.70. Skala ini menggunakan metode
Likert yang bertujuan untuk mengetahui perilaku ekstra karyawan di tempat kerja. Adapun distribusi atau penyebaran item pada skala tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1
Distribusi Item Skala Adaptasi OCB
ITEM
ASPEK Favorable Unfavorable JUMLAH
1.Altruism
2.Concientiousness 3.Sportmanship 4.Courtsey 5.Civic virtue
1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10
16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24
11, 12, 13, 14, 15
5 5 5 5 4
JUMLAH 19 5 24
0 sampai 4 dengan alternatif jawaban yaitu, sangat tidak sesuai, tidak sesuai, ragu-ragu, sesuai, sangat sesuai. Pada penelitian ini pemberian skor subyek adalah sebagai berikut : untuk item favorable, jawaban sangat sesuai skornya adalah 4, sesuai = 3, ragu-ragu = 2, tidak sesuai = 1, sangat tidak sesuai = 0. Sedangkan untuk item
favorable pemberian skor jawaban sebagai berikut : jawaban sangat sesuai skornya adalah 0, sesuai = 1, ragu-ragu = 2, tidak sesuai = 3, sangat tidak sesuai = 4.
2. Skala Professional Quality Of Life (ProQOL)
Peneliti menggunakan skala adaptasi Professional Quality Of Life (ProQOL) dari Stamm (2005) yang terdiri dari subskala yaitu compassion satisfaction, burnout
dan compassion fatigue. Skor masing-masing subskala ProQOL tidak bisa digabungkan karena masing-masing skala tersebut memiliki keunikan psikometri. Skala ini bertujuan untuk mengetahui compassion satisfaction, burnout dan
compassion fatigue pada karyawan di tempat kerja selama 30 hari terakhir
Tabel 2
Distribusi Item Subskala ProQol
ITEM Subskala
Favorable Unfavorable
JUMLAH
Compassion satisfaction
Burnout
Compassion fatigue
3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30
8, 10, 21, 26
2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25, 28
1, 4, 15, 17, 19, 29
10
10
10
JUMLAH 25 5 30
Skala ini terdiri dari 30 item yang meliputi tiga aspek yaitu compassion satisfaction, burnout dan compassion fatigue. Skor bergerak dari angka 0 sampai 5, dengan alternatif pilihan jawaban tidak pernah (0%), jarang (0%-20%), sesekali (21%-40%), kadang-kadang (41%-60%), sering (61%-80%), sangat sering (81%-100%). Pada penelitian ini pemberian skor untuk item favorable sebagai berikut : jawaban sangat sering = 5, sering = 4, kadang-kadang = 3, sesekali = 2, jarang = 1, tidak pernah = 0. Menurut Stamm (2005) khusus untuk pemberian skor item unfavorabel pada skala ini yaitu 0 = 0, 1 = 5, 2 = 4 , 3 = 3, 4 = 2, 5 =1.
3. Skala Karakteristik Pekerjaan
Adapun penjelasan mengenai perhitungan skor karakteristik pekerjaan sebagai berikut :
a. Melakukan perhitungan skor karakteristik pekerjaan yang diperoleh melalui pembagian item-item dari kelima dimensi karakteristik pekerjaan terhadap jumlah masing-masing item untuk setiap dimensi.
b. Melakukan perhitungan skor dengan menggunakan rumus Motivating Potential Score (MPS) sebagai berikut :
SV + TI + TS
Motivating Potential Score (MPS) = X AU X FB
3
Keterangan :
SV : Skill Variety FB : Feedback TI : Task Identity AU : Autonomy TS : Task Significance
Landy, F.J (1989) menguraikan bahwa skill variety, task Identity dan task significance memiliki hubungan additive atau skor yang lebih dari salah satunya akan melengkapi skor yang lain. Namun, hal ini tidak sejalan dengan skor untuk autonomy
dan feedback. Apabila skor keduanya menunjukkan 0 maka MPS pun 0.
Tabel 3
Distribusi Item Skala Karakteristik Pekerjaan
ITEM ASPEK
Favorable Unfavorable
JUMLAH
Skill Variety Task Identity Task Significance Autonomy Feedback
2, 8, 14 3, 22 4, 23 1, 21 5, 6, 10, 15
11, 18 7, 16 13, 20
9, 17 12, 19
5 4 4 4 6
JUMLAH 13 10 23
Skala ini memiliki alternatif pilihan jawaban dan pemberian skor untuk item favorabel yaitu sangat tidak menggambarkan = 1, kurang menggambarkan = 2, kadang-kadang menggambarkan = 3, sebagian besar menggambarkan = 4, sangat menggambarkan = 5. Sedangkan untuk item favorabel pemberian skor adalah sebagai berikut: sangat tidak menggambarkan = 5, kurang menggambarkan = 4, kadang-kadang menggambarkan = 3, sebagian besar menggambarkan = 2, sangat menggambarkan = 1.
G. Validitas , Reliabilitas Alat Ukur
Alat ukur penelitian perlu diujicobakan dengan tujuan memperoleh validitas dan reliabilitas yang baik sehingga alat ukur sahih dan dapat diandalkan (Azwar, 1999).
1. Validitas
isi diselidiki melalui estimasi analisis rasional oleh professional judgment terhadap isi tes. Estimasi yang dilakukan tergantung pada penilaian subyektif sehingga tidak melibatkan perhitungan statistik. Untuk menghindari subyektivitas peneliti maka dalam validitas alat ukur maka analisis rasional juga dilakukan oleh dosen pembimbing.
Selanjutnya peneliti melakukan seleksi item berdasarkan korelasi item total. Azwar (Lababa, 2008) mengungkapkan bahwa batas item yang dianggap sahih apabila korelasi totalnya menunjukkan ≥ 0,3 dengan alasan memiliki daya diskriminasi yang tinggi. Sedangkan item dengan korelasi total < 0,3 dianggap gugur karena daya diskriminasinya rendah.
2. Reliabilitas
Reliabilitas adalah keandalan yang mengacu pada stabilitas dan kejituan alat ukur sehingga diperoleh kepercayaaan terhadap hasil pengukuran (Kerlinger, 1986). Teknik Cronbach menggunakan program komputer SPSS for Windows 17.0. Nilai reliabilitas (rxx1) berkisar antara 0 sampai dengan 1,00. Nilai reliabilitas dianggap memuaskan apabila rxx1 = 0,9 (Azwar, 1999). Dalam prakteknya rxx1 = 1,00 tidak pernah dijumpai. Teknik konsistensi internal estimasi reliabiltas menggunakan
H. Subyek dan Uji Coba Alat Penelitian 1. Subyek Uji Coba Alat Penelitian
Peneliti melakukan uji coba alat ukur sebanyak dua kali kepada subyek yang memiliki kriteria yang sama pada penelitian yang hendak dilakukan. Pada skala ProQol dan Karakteristik Pekerjaan, uji coba yang pertama diujikan pada sampel di unit cabang BRI katamso, yaitu unit BRI Pandeyan, Katamso, Timoho, Terban, Pugeran, Kusumanegara, Poncowinatan, Pasar kembang, Gejayan, Wirobrajan dengan total jumlah subyek sebanyak 53 orang. Sedangkan uji coba yang kedua pada skala adaptasi ProQol dan Karakteristik Pekerjaan, yang merupakan uji coba yang pertama bagi skala adaptasi OCB, diuji cobakan di bagian keuangan di LSM Marga Husada, PT. Garuda Indonesia, UKDW, Yayasan Akper Bethesda dan Bussan Auto Finance (BAF) Yamaha Motor sejumlah 62 orang.
2. Uji Coba Alat Peneliti