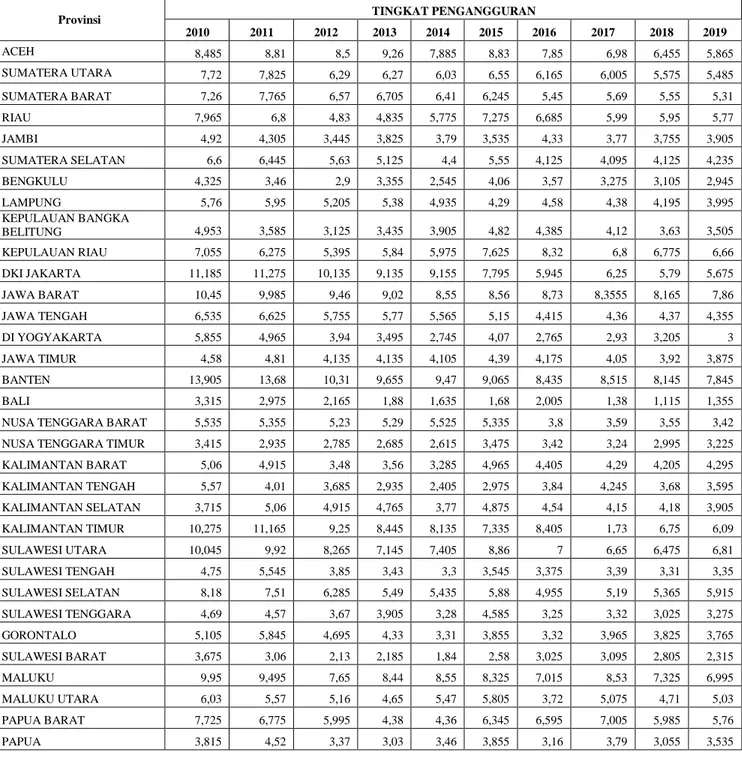ANALISIS PENGARUH ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA
(Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia Periode 2010 – 2019)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
DISUSUN OLEH :
Rangga Dwi Putera 11160840000091
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
ANALISIS PENGARUH ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA
(Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia Periode 2010 – 2019)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Rangga Dwi Putera NIM: 11160840000091
Di bawah Bimbingan:
Pembimbing I
Najwa Khairina, S.E., M.A. NIP: 198711132018012001
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini, Jumat, 15 Mei 2020, telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama: Nama : Rangga Dwi PuteraNIM : 11160840000091 Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia Periode 2010 – 2019)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 27 Oktober 2020
1. Arisman, M.Si.
NIP: 197305102014111003
2. Dr. Pheni Chalid, M.A. ( )
NIP: 195605052000121001 Penguji II
( )
LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Rangga Dwi Putera NIM : 11160840000091 Jurusan : Ekonomi Pembangunan Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini. Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Hari ini, Rabu 23 Desember 2020 telah dilakukan Ujian Skripsi atas Mahasiswa:
Nama : Rangga Dwi Putera NIM : 11160840000091 Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia Periode 2010 – 2019)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan “Lulus” dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 23 Desember 2020
1. Dr. M. Hartana I Putra, M.Si (___________)
NIP: 196806052008011023 Ketua
2. Najwa Khairina, S.E., M.A. (___________)
NIP: 198711132018012001 Pembimbing I
3. Djaka Badranaya, S.Ag., M.E. (___________)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Identitas Pribadi
Nama : Rangga Dwi Putera
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Tinggi/Berat : 171 cm/ 58 Kg
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cipulir 1 No. 30, RT 013 RW 004, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No. HP : 081584852536 E-mail : ranggadwiputera582@gmail.com Pendidikan Formal 2004-2010 : SDN Cipulir 05 Pagi 2010-2013 : SMPN 48 Jakarta 2013-2016 : SMKN 6 Jakarta
2016-2020 : Program Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Pengalaman Organisasi
1. Anggota Departemen Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Periode 2016-2017.
2. Sekretaris Koordinator Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Periode 2017-2018
3. Kepala Bidang I Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Periode 2018-2019.
4. Biro LSO Kajian dan Keilmuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Masa Khidmat 2017-2018.
Latar Belakang Keluarga
Ayah : Desrizon
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 15 Desember 1968
Ibu : Renita
Tempat, Tanggal Lahir : Riau, 09 September 1969
Alamat : Jl. Cipulir 1 No. 30, RT 013 RW 004, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
ABSTRACT
The problem of poverty can be triggered because of the still low quality of human life, minimum wages that are not in line with the cost of living, and the number of poor people that is increasing every year. In addition, with the low old school expectancy, the number of poor people is high. The problem of wages is of course also a crucial problem in poverty, the low wages received by the community will affect the low income received by an area so that the income cannot be used to meet the needs of daily life. Another factor that influences the poverty rate is unemployment, where the greater the unemployment rate, the greater the poverty rate in a region.
The purpose of this study was to analyze the influence of school long- term expectancy, provincial minimum wage, and unemployment on poverty in Indonesia using a case study of 34 provinces in Indonesia. This research uses secondary data. The analytical method used in general to analyze the influence of School Old Expectation Rates, Provincial Minimum Wages, Unemployment and Poverty Rate in Indonesia is a quantitative method.
Keywords : Poverty, Old School Expectation Rate, Provincial Minimum Wage, Unemployment
ABSTRAK
Persoalan kemiskinan dapat dipicu karena masih rendahnya kualitas hidup manusia, upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, dan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Masalah pengupahan tentunya juga menjadi masalah yang krusial dalam kemiskinan, adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran, dimana semakin besar tingkat pengangguran, maka semakin besar pula tingkat kemiskinan di suatu wilayah.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh angka harapan lama sekolah, upah minimum provinsi, serta pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan studi kasus 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Peneitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan secara umum untuk menganalisis tentang pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia adalah metode kuantitatif.
Kata Kunci : Kemiskinan, Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Pengangguran
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr, Wb ..
Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Adapun judul Skripsi ini adalah “Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia Periode 2010 – 2019)”. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.
Proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan, dukungan dan motivasi dari orang-orang yang terbaik yang ada di sekeliling penulis. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan penulis rezeki untuk dapat kuliah di Universitas ini dan segala nikmat yang telah Allah berikan yang harus patut disyukuri dan dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ridho dan berkah-Mu semua ini sulit terjadi.
2. Keluarga tercinta dan terhebat penulis, Bapak Desrizon dan Ibu Renita, abang Adi Fenico Pratama, adik Arjuna Leomas Tri Mulya, adik Rayhan Defranc Sako, adik Shalda Puteri Hawari, dan adik Noura Vio Satika yang menjadi motivator,
dengan penuh rasa kasih sayang.
3. Bapak Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta
jajaran.
4. Bapak M. Hartana Iswandi Putra, M.Si. dan Bapak Deni Pandu, M.Sc. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat bagi penulis dari awal perkuliahan hingga di tahap penulisan skripsi ini.
5. Ibu Najwa Khairina, S.E., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk selalu membimbing, memberikan pengarahan serta memberikan ilmu yang bermanfaat untuk memotivasi penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi. Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan Ibu. 6. Bapak Drs. Rusdianto, M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada saya di setiap semesternya sampai saya berada di tahap penulisan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis. Serta jajaran karyawan dan staf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melayani dan membantu penulis selama perkuliahan. Semoga Allah selalu memberikan pahala yang sebesar- besarnya atas kebaikan bapak ibu semua.
8. Teman – teman “FGD”: Miftahur Royyan, Nabila Rahma Sari, Tiffani Dyahnisa yang telah menunjukkan kepada saya betapa sahabat memang nyata adanya. Terima kasih karena dalam peliknya kehidupan kampus yang kita jalani, kalian membuktikkan bahwa kita bisa, dengan menguatkan satu sama lain, selalu menjadi mata, telinga dan pundak hanya agar kita tak merasa sendiri dan bisa bangkit untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Terima kasih atas kenangan yang tentu akan selalu saya ingat sampai kapanpun. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.
9. Teman-Teman “Berubah Lu”: Chandra Halim, Handika Rahmat Dwi Putro, Reza Eka Putra, Medina Shafira, Sandra Septiyarini, Fitriani Hasan, dan Rayhan Arya Wicaksono yang menjadi kawan setia sedari maba hingga saat ini. Banyak
cerita dan kenangan yang telah kita lalui, menciptakan memori indah selama saya menjalani perkuliahan bersama kalian, berbagi rasa dan asa, canda dan tawa sampai tangis yang sudah kita lewati bersama. Semoga semesta selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Sukses selalu untuk kalian, kawan. 10. Adik Arbi Wijaya dan Adik Amelia Wardhani. Dua sosok adik saya di kampus yang telah membuka mata saya dengan berbagai macam perspektif yang mereka punya. Terima kasih karena selalu memberi dukungan kepada saya. Banyak pelajaran juga kenangan berharga yang saya dapat dari kalian. Senang bisa mengenal dan menjadi bagian dari kalian. Sukses selalu untuk perkuliahannya. Saya tunggu kabar baik dari kalian.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Ekonomi Pembangunan yang telah memberi kehangatan dan arti dari keluarga di bangku perkuliahan. Sukses selalu untuk kita semua.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, baik kritik membangun dari berbagai pihak. Selain itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak.
Wassalamualaikum Wr, Wb.
DAFTAR ISI
COVER
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ... i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ... ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ... iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ...iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... v
ABSTRACT ... vii
ABSTRAK ... viii
KATA PENGANTAR ...ix
DAFTAR ISI ... xii
DAFTAR TABEL... xv
DAFTAR GAMBAR ... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ... xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Rumusan Masalah ... 8
C. Tujuan Penelitian ... 9
D. Manfaat Penelitian ... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori ... 11
1. Kemiskinan ... 11
2. Angka Harapan Lama Sekolah ... 33
4. Pengangguran ... 45
B. Keterkaitan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terkait ... 50
1. Hubungan Antara Angka HLS terhadap Tingkat Kemiskinan ... 50
2. Hubungan Antara UMP terhadap Tingkat Kemiskinan ... 51
3. Hubungan Antara Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan ... 51
C. Penelitian Terdahulu ... 52
D. Kerangka Pemikiran ... 53
E. Hipotesis ... 54
BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ... 56
B. Metode Penentuan Sampel ... 56
C. Metode Pengumpulan Data ... 57
D. Metode Analisis Data ... 58
E. Tahapan Analisis Data ... 61
F. Pengujian Hipotesis ... 62
G. Operasional Variabel Penelitian ... 64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian ... 65
1. Angka Harapan Lama Sekolah ... 65
2. Perkembangan Upah Minimum Provinsi ... 67
3. Perkembangan Tingkat Pengangguran ... 71
a. Model Penelitian... 76
b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) ... 78
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ... 80
d. Uji Koefisien Determinasi R2 ... 82
3. Interpretasi Hasil Penelitian ... 83
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ... 91
B. Saran-saran ... 93
DAFTAR PUSTAKA ... 94
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1. Sejarah Penerapan US$ PPP ... 19
2. Tabel 2. Nilai Tukar PPP Tahun Dasar 2011 (Indonesia) ... 20
3. Tabel 4.1 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (2010-2019) ... 65
4. Tabel 4.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi (2010-2019) ... 68
5. Tabel 4.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran (2010-2019) ... 70
6. Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model with GLS ... 72
7. Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel Uji Chow ... 73
8. Tabel 4.7 Hasil Regresi Data Panel Uji Hausman ... 74
9. Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikasi Fixed Effect Model with GLS ... 74
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 1. Perbandingan Angka Kemiskinan ... 22 2. Gambar 2. Distribusi Pengeluaran Konsumsi Perkapita ... 22 3. Gambar 3. Kerangka Pemikiran ... 49
DAFTAR LAMPIRAN
1. Lampiran 1. Data Olah ... 93
2. Lampiran 2. Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model ... 104
3. Lampiran 3. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model ... 104
4. Lampiran 4. Hasil Regresi Data Panel Uji Chow ... 105
5. Lampiran 5. Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model ... 105
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kesejahteraan lahir batin merupakan suatu kondisi yang diidamkan oleh
umat manusia. Kondisi yang berlawanan dengan kesejahteraaan adalah
kemiskinan, keadaan yang ingin diatasi dalam setiap proses pembangunan.
Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki- laki
dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk
menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian,
kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi
juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi
seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan
tingkat kemiskinan, permasalahan kemiskinan adalah suatu masalah yang
kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya untuk
pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan komprehensif, mencakup
berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir
dkk.,2008).
Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah
dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, apalagi saat ini kondisi perekonomian
pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang. (Keterangan Pers
Kementrian Keuangan, 2015). Hal ini juga didukung dengan kajian Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2016) yang disajikan bahwa harga
minyak dunia anjlok dengan harga Minyak mentah berjangka Brent turun
US$4,72 atau 9,4 persen ke posisi US$45,27 per barel serta harga minyak mentah
berjangka West Texas Intermediate (WTI) anjlok US$4,62 atau 10,1 persen
menjadi US$41,28 per barel. Harga ini merupakan yang terendah sejak Agustus
2016 lalu .
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian
pemerintah di negara manapun terutama di negara sedang berkembang seperti
Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus yang sangat penting bagi pemerintah
Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang besar,
mayoritas tinggal di daerah perdesaan yang sulit untuk diakses bahkan kota besar
seperti Jakarta juga masih sangat banyak ditemukan masyarakat miskin.
Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya
adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Persoalan kemiskinan juga
dapat dipicu karena masih rendahnya kualitas hidup manusia, upah minimum
yang tidak sesuai dengan biaya hidup, dan jumlah penduduk miskin yang semakin
meningkat setiap tahunnya (Ayu, 2018). Hidup miskin bukan hanya berarti hidup
di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi,
informasi, teknologi, dan modal.
Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara
berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan
dalam distribusi pandapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi
dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau
jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) (Tambunan, 2001).
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat
multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia
mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan
makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar
1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu
memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada
dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi
penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat.
Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh
bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup
orang miskin. Untuk itu, disamping data jumlah dan persentasenya, profil serta
karakteristik penduduk miskin juga dirasakan penting untuk diketahui.
Dalam menganalisa ciri-ciri kemiskinan, ada dua pendekatan yang
digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut,
cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan,
pemukiman, kesehatan, dan pendidikan sedangkan, kemiskinan relatif berkaitan
dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Walaupun sudah
banyak program-program yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan,
namun masalah ini tak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah ini
disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin ternyata
sangat kompleks. Pendekatan dan penyelesaiannya tidak hanya dilakukan dari
segi ekonomi saja namun segi sosialnya harus dipertimbangkan. Faktor utama
penyebab kemiskinan sebagian besar karena faktor alamiah seperti keadaan alam,
iklim dan bencana alam (Tri Wahyu, 2011). Selain itu, tidak terjadinya pemerataan
hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan
(Al Arif, 2010).
Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari beberapa aspek antara
lain aspek demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Secara
demografi, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih banyak
dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Dari aspek pendidikan, kepala
rumah tangga miskin mempunyai rata-rata lama sekolah lebih rendah dibanding
kepala rumah tangga tidak miskin. Sementara itu, dari aspek ketenagakerjaan
sebagian besar kepala rumah tangga miskin bekerja pada sektor pertanian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu data dan
informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur pencapaian
sekolah (HLS) mewakili dimensi pendidikan, dan rata-rata pengeluaran per kapita
disesuaikan yang mewakili dimensi hidup layak. HLS merupakan salah satu
indikator pada dimensi pendidikan yang masih rendah pencapaiannya. Kualitas
sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks
pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan
berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang
rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, yang mengakibatkkan
semakin banyak jumlah penduduk miskin. Sehingga dengan rendahnya Harapan
Lama Sekolah menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.
Masalah pengupahan tentunya juga menjadi masalah yang krusial dalam
kemiskinan, adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan
berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah
sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan
dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah
secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas
sumber daya manusia sering dikaitkan oleh ketrampilan yang tinggi yang dimiliki
oleh masyarakat. Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor
penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya
kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan
yang diterima masyarakat, apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah,
maka masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun
Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah
pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang
tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum
dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran dapat terjadi disebabkan
oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukan bahwa
jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.
(Sukirno,1997).
Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan
lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius
dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah
pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada
tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan
berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang,
angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh ”terbatasnya
permintaan” tenaga kerja, yang selanjutnya semakin diciutkan oleh faktor-faktor
eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya
masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya telah
mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya,
penyedian lapangan kerja (Todaro, 2000).
Pasar tenaga kerja, seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan
tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkannya (Mankiw, 2006:487).
Dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, tenaga kerja
merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi
tersebut. Dengan menelaah hubungan antara produksi barang-barang dan
permintaan tenaga kerja, akan dapat diketahui faktor yang menentukan upah
keseimbangan.
Hal senada juga di sampaikan (Alhudori, 2017), pengangguran bisa
disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya,
sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri
yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti,
semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan tingkat
kemiskinan.
Dalam penelitian ini faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap
kemiskinan diantaranya adalah Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum
Provinsi, dan Tingkat Pengangguran. Berdasarkan latar belakang diatas maka
penulis tertarik untuk membahas mengenai tingkat kemiskinan di 33 Provinsi
Indonesia. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana
pengaruh variabel Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi
(UMP), dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di 33 Provinsi
Indonesia. Oleh karenanya maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Angka
Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran
terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode 2010-2019 (Studi Kasus 33
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah in-konsistensi hubungan antara Angka Harapan Lama
Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat
Kemiskinan di Indonesia, menjadi suatu masalah yang perlu untuk dilakukan
penelitian lebih lanjut. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada variabel Angka
Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran
terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2010 – 2019.
Dari latar belakang yang telah diuraikan, dan dengan asumsi Ceteris
Paribus, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum
Provinsi dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di 33
Provinsi di Indonesia pada Periode 2010 - 2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah Terhadap Tingkat
Kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia pada Periode 2010 - 2019?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan
di 33 Provinsi di Indonesia pada Periode 2010 - 2019?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, dan dengan asumsi Ceteris Paribus,
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis bagaimana pengaruh secara parsial antara variabel Angka
Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran
dengan variabel Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh secara simultan antara variabel Angka
Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran
dengan variabel Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai saran dan implementasi ilmu
pengetahuan bagi perkembangan dunia pendidikan dan perekonomian serta
memberikan pembuktian yang empiris hubungan antara variabel-variabel Angka
Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran
terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
1. Manfaat Bagi Pengambil Kebijakan (Pemerintah)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan
masukan bagi Pemerintah Indonesia mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kemiskinan pada Provinsi tersebut dan merumuskan
kebijakan - kebijakan yang nantinya bisa di canangkan oleh pemerintah
2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini erat hubungannya terhadap bidang ilmu ekonomi, maka
diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan ataupun rujukan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 1. Kemiskinan
a. Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan berarti tidak memiliki cukup harta benda atau
pendapatan untuk kebutuhan seseorang. Kemiskinan dapat mencakup
elemen sosial, ekonomi, dan politik (World Bank, 2010).
Kemiskinan absolut adalah kurangnya sarana yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan dasar pribadi, seperti makanan, pakaian,
dan tempat tinggal. Ambang batas di mana kemiskinan absolut
didefinisikan selalu hampir sama, terlepas dari lokasi atau era permanen
seseorang.
Di sisi lain, kemiskinan relatif terjadi ketika seseorang tidak dapat
memenuhi tingkat standar hidup minimum, dibandingkan dengan orang
lain pada waktu dan tempat yang sama. Oleh karena itu, ambang batas
di mana kemiskinan relatif didefinisikan bervariasi dari satu negara ke
negara lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Misalnya,
seseorang yang tidak mampu membeli rumah lebih baik daripada tenda
kecil di lapangan terbuka akan dikatakan hidup dalam kemiskinan
relatif jika hampir semua orang di daerah itu tinggal di rumah bata
bidang terbuka (misalnya, dalam suku nomaden).
Pemerintah dan organisasi non-pemerintah berusaha mengurangi
kemiskinan. Menyediakan kebutuhan dasar bagi orang-orang yang tidak
dapat memperoleh penghasilan yang memadai dapat terhambat oleh
kendala pada kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan,
seperti korupsi, penghindaran pajak, persyaratan hutang dan pinjaman
dan oleh aliran otak para profesional kesehatan dan pendidikan. Strategi
meningkatkan pendapatan untuk membuat kebutuhan dasar lebih
terjangkau biasanya mencakup kesejahteraan, kebebasan ekonomi dan
menyediakan layanan keuangan.
Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Timur, Indonesia –
kepulauan yang mencakup lebih dari 300 suku – telah memperlihatkan
pertumbuhan ekonomi yang sangat baik sejak krisis finansial Asia di
akhir 1990an. PDB nasional Indonesia nasional terus meningkat, dari
$823 pada tahun 2000 menjadi $3.932 pada 2018.
Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar
keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan
paritas daya beli, dan merupakan anggota G-20. Indonesia telah berhasil
mengurangi kemiskinan lebih dari setengah sejak tahun 1999, menjadi
9,4% pada tahun 2019.
Meski tengah berlangsung ketidakpastian global, proyeksi ekonomi
kuat, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kokoh, pertumbuhan
ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 5,2% pada tahun 2019.
Rencana ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan
jangka panjang untuk tahun 2005-2025. Rencana ini dibagi dalam
periode lima tahun, masing-masing dengan prioritas pembangunan yang
berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah saat ini – yang
merupakan tahap ketiga dari rencana jangka panjang – terentang antara
tahun 2010-2020, berfokus antara lain pada pembangunan infrastruktur
dan peningkatan program bantuan sosial untuk pendidikan dan
pemeliharaan kesehatan. Pengalihan anggaran belanja negara tersebut
bisa dilakukan setelah pemerintah mereformasi kebijakan subsidi energi
yang telah berlangsung lama. Kini pemerintah bisa berinvestasi lebih
besar pada program-program yang memberi dampak langsung pada
masyarakat miskin dan hampir miskin. Namun masih ada berbagai
tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia.
Dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia, masih ada sekitar 25,9
juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data
Maret 2018, sekitar 20.19% dari seluruh penduduk masih rentan jatuh
miskin karena pendapatan mereka hanya sedikit di atas garis
kemiskinan.
Kemitraan antara Indonesia dan Kelompok Bank Dunia telah
berlangsung selama enam dekade dan menjadi salah satu model
layanan pengetahuan dan dukungan implementasi. Sejak tahun 2004,
dukungan Bank Dunia bersandar pada agenda kebijakan pemerintah
Indonesia, sesuai dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan
menengah.
Pada Desember 2010, setelah melakukan konsultasi dengan
berbagai pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan
sektor swasta, Dewan Direksi Bank Dunia menyetujui Kerangka
Kemitraan Negara (Country Partnership Framework/CPF) untuk
Indonesia, yang mengikuti prioritas Indonesia dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Tujuan utama CPF adalah mendukung pemerintah Indonesia untuk:
memberantas kemiskinan ekstrem, membangun kesejahteraan, serta
menurunkan tingkat ketimpangan. Strategi dibagi menjadi enam sektor
yang didukung oleh dua pilar.
Enam sektor:
1) Infastruktur
2) Energi yang berkelanjutan dan akses universal
3) Ekonomi dan perhubungan maritime
4) Pemberian layanan umum
5) Lanskap berkelanjutan
6) Mengumpulkan lebih banyak dan melakukan belanja dengan
Pilar pendukung:
1) Pihak swasta
2) Pemerataan kesejahteraan, kesetaraan, dan inklusi.
Pada tahun 2011, Bank Dunia mendukung pengembangan dua
lapangan panas bumi: Ulubelu di Lampung di bagian selatan Pulau
Sumatera (kapasitas 110 MW), dan Lahendong di Sulawesi Utara
(kapasitas 40 MW). Baru-baru ini, pada tahun 2017, Bank Dunia
memberikan hibah untuk mendukung Geothermal Energy Upstream
Development Project, untuk mendukung pengeboran eksplorasi yang
disponsori pemerintah dan memfasilitasi investasi dalam pembangkit
listrik geotermal. Pemerintah Indonesia sedang merencanakan
Geothermal Resource Risk Mitigation Facility yang baru, agar
membuka investasi melalui mitigasi risiko untuk eksplorasi dan
pengeboran produksi awal dengan menyediakan dana eksplorasi untuk
para pengembang panas bumi. Ini akan memungkinkan investor untuk
membuktikan sumberdaya yang cukup untuk menarik keuangan
komersial untuk pengembangan skala besar. Diharapkan fasilitas ini
akan mengarah pada pengembangan lebih dari 600 MW kapasitas panas
bumi baru.
Meningkatkan modal manusia adalah agenda penting bagi
Indonesia, dan Bank Dunia membantu meningkatkan kualitas
pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil. Program KIAT Guru
tunjangan untuk meningkatkan kinerja guru. Program ini telah
dilaksanakan di lebih dari 200 sekolah dan kepuasan masyarakat
terhadap kehadiran guru telah meningkat dari 68% pada tahun 2016
menjadi 90%, dan kinerja layanan guru dari 55% menjadi 91%.
Mengakui pentingnya membantu mereka yang membutuhkan untuk
membantu diri mereka sendiri, Bank Dunia mendukung Program
Keluarga Harapan pemerintah, yang berusaha mengakhiri rantai
kemiskinan di antara penduduk termiskin di Indonesia.
Sesi pengembangan keluarga dan bahan belajar yang
dikembangkan bersama Bank Dunia dimasukkan dalam program ini,
untuk membantu para ibu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
kesehatan dan gizi, praktik pengasuhan yang baik, perlindungan anak
dan manajemen keuangan. Program ini saat ini membantu 3,5 juta
keluarga meningkatkan hasil pendidikan dan kesehatan anak-anak
mereka, dan pemerintah berencana untuk memperluas program tersebut
Program-program Bank Dunia berupaya menjawab berbagai
tantangan yang Indonesia hadapi. Program Generasi menyediakan hibah
berbasis insentif bagi masyarakat untuk mengatasi tiga sasaran MDG
yang masih tertinggal: kesehatan ibu, kesehatan anak dan pendidikan
universal. Generasi aktif di lebih dari 5,000 desa di 11 provinsi, dan
membantu hampir lima juta orang. Beberapa program yang dihasilkan
telah membantu ratusan ribu anak menerima imunisasi, memberi solusi
malnutrisi dan memastikan hampir 1 juta ibu hamil mendapat asupan
zat besi tambahan.
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 500 pemerintahan lokal
yang punya potensi untuk mempercepat pertumbuhan di wilayahnya.
Local Government Decentralized Project bekerja dengan pemerintahan
kabupaten/kota dalam memastikan alokasi anggaran dari pemerintah
pusat untuk investasi infrastruktur digunakan sepenuhnya, sambil terus
berupaya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Dukungan
pemerintah terus menguat dengan pendekatan hasil berbasis verifikasi
yang sedang dikembangkan untuk 30 provinsi, dengan target mencapai
450 kabupaten/kota pada 2018.
Kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh
seseorang atau sekelompok orang di luar keinginan yang bersangkutan
sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan dan
kemampuan yang dimilikinya yang disebabkan oleh berbagai faktor
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2000).
Kemiskinan adalah jumlah keluarga miskin prasejahtera yang
tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya; tidak mampu
makan 2 kali sehari; tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah,
bekerja dan bepergian; bagian tertentu dari rumah berlantai tanah; dan
tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan (Badan
Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2002).
Kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok
orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak- hak
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air
bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman
dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan
maupun laki- laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat
miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara
lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan
pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human
capability approach) dan pendekatan objektif dan subjektif (Badan
sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang
yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat
memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. (PP No.
42 Tahun 1981). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per
kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh
52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan
susu, sayuran, kacang-kacangan, buah- buahan, minyak dan lemak, dll).
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum
untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (Badan Pusat
Statistik, 2010).
Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51
jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Dalam
mengukur kemiskinan ini, BPS menggunakan pendekatan kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dimaknai
sebagai “kurangnya kesejahteraan” dan “kesejahteraan sebagai
menurunnya kesejahteraan. Keduanya saling terkait dan memandang
masalah yang sama dari dua dimensi yang berbeda. Definisi yang luas
dari kemiskinan ini adalah “kurangnya kesejahteraan”, dimana ada
saling tukar dalam konsep ini. Misalnya apabila masyarakat sangat
kurang sejahtera, berarti masyarakat miskin (Gonner, 2007). Disisi lain,
apabila mereka berada dalam kondisi yang sangat sejahtera, maka
hidupnya ditandai dengan kemakmuran, kebahagiaan dan kepuasan
(Albornoz, 2007).
b. Pengukuran Angka Kemiskinan menurut TNP2K Garis Kemiskinan Internasional
Definisi kemiskinan ekstrem (extreme poverty) melalui acuan
tahun dasar 2011 adalah mereka yang hidup di bawah $1,9 PPP per
hari. Sejarah awal dari penggunaan dolar PPP bermula dari publikasi
Bank Dunia tahun 1990, World Development Report. Pendekatan garis
kemiskinan internasional di dalam menentukan garis kemiskinan suatu
negara merupakan suatu cara tidak langsung di dalam mengukur tingkat
kemiskinan. Perkiraan semacam ini terutama sekali dilakukan untuk
studi perbandingan antar negara di samping memperkirakan tingkat
kemiskinan global. Namun tidak jarang pula hal ini dilakukan untuk
memperkirakan tingkat kemiskinan suatu negara tertentu (Edi Santosa,
internasional, Bank Dunia pada 1990 menggunakan sampel GK
nasional dari 33 negara. Selanjutnya, terdapat 8 negara termiskin yang
menjadi dasar GK internasional $1 PPP per hari (Kenya, Nepal,
Tanzania, Bangladesh, Indonesia, Moroko, Filipina, Pakistan).
1) Konsep Purchasing Power Parity (PPP)
Analisis kemiskinan global membutuhkan suatu ukuran tingkat harga
barang dan jasa yang dapat dibandingkan antar-negara. PPP merupakan
indeks harga antar-negara yang merupakan ukuran sejumlah uang yang
diperlukan untuk membeli barang dalam jumlah yang sama secara riil
relatif terhadap negara pembanding, dimana umumnya menggunakan
perbandingan dengan Amerika Serikat (Deaton & Aten, 2017). Konsep
PPP terkait erat dengan definisitingkat harga ditiap negara yang
merupakan harga rata-rata tertimbang dari sejumlah barang
menggunakan jenis barang dan bobot yang sama di antara
negara-negara tersebut (Feenstra & Taylor, 2017).
Selanjutnya, diasumsikan bahwa PPP akan berlaku sepanjang tingkat
harga di beberapa negara tersebut terbanding dalam satuan unit nilai
tukar yang sama. Gambaran sederhana terkait konsep PPP adalah apabila
harga satu buah pisang di Amerika Serikat adalah US$ 1, sedangkan
harga pisang yang sejenis di Indonesia adalah Rp500, maka PPP adalah
US$ 0,002/Rupiah. Sumber informasi untuk nilai tukar PPP untuk GK
internasional adalah International Comparison Program (ICP), yang
negara dalam ICP yang terkini, tahun 2011, terdiri dari 199 negara atau
setara dengan 97 persen jumlah penduduk dunia atau sekitar 99 persen
produk domestik bruto dunia (World Bank, 2010).
Penggunaan nilai tukar mata uang dalam PPP berbeda dengan
pemahaman kurs mata uang secara nominal. Pada laporan ICP tahun
dasar 2011, kurs nilai tukar Rupiah per dolar Amerika secara nominal
adalah Rp8.770. Apabila GK internasional tahun dasar 2011 senilai
$1,9 PPP per hari, maka konversi GK internasional ke nilai rupiah tidak
bersandar pada kurs nominal Rp8.770 per dolar Amerika tersebut.
Namun, konversi ke nilai tukar menggunakan kolom konversi kurs nilai
tukar PPP pada tabel pengeluaran individu konsumsi rumah tangga di
Penghitungan angka kemiskinan untuk Indonesia melalui GK
internasional lebih spesifik, karena terdiri dari dua garis menurut
wilayah untuk mempertimbangkan penyesuaian bias wilayah perkotaan
dan perdesaan (Chen & Ravallion, 2010). Rasio GK internasional
wilayah perkotaan dan perdesaan sama dengan rasio GK perkotaan dan
perdesaan sebagaimana GK nasional yang dihitung oleh BPS, yakni
sebesar 1,19. Besarnya nilai tukar $1 PPP per hari pada tahun dasar 2011
ditampilkan pada Tabel 1 (Ferreira, et al., 2010).
2) Penghitungan Garis Kemiskinan Nasional Indonesia
Pendekatan cost of basic need (CBN) adalah metode pengukuran
kemiskinan yang secara resmi dirilis oleh BPS. Pendekatan ini
menghitung biaya pada komponen pengeluaran konsumsi makanan
untuk mendapatkan kebutuhan gizi minimum yang setara dengan 2.100
kalori per orang per hari (Haughton & Khandker, 2010). Kemudian,
biaya pada sejumlah pengeluaran non-makanan esensial dilibatkan
dalam penghitungan keseluruhan (total) untuk melengkapi biaya
konsumsi makanan (BPS, 2016). Nilai kebutuhan minimum kelompok
non-makanan terhadap total pengeluaran yang diperoleh dari hasil
survei paket komoditi kebutuhan dasar (SPKKD). Sumber data dalam
penghitungan GK nasional adalah modul konsumsi yang terdapat pada
survei sosial ekonomi nasional (Susenas). Penghitungan pengeluaran
konsumsi makanan dalam GK nasional melibatkan 52 komoditi,
sedangkan item pengeluaran non-makanan yang menjadi bagian
penghitungan GK nasional mencakup 51 jenis untuk di wilayah
perkotaan dan 47 jenis untuk di wilayah perdesaan (BPS, 2016).
3) Angka Kemiskinan Berdasarkan Dua Pendekatan Penghitungan Garis Kemiskinan
Perkembangan angka kemiskinan antar-tahun berdasarkan dua jenis
GK dapat dilihat pada Gambar 1. Sebelum tahun 2012, angka
kemiskinan yang dihitung menggunakan GK nasional yang dirilis oleh
BPS lebih rendah daripada tingkat kemiskinan yang dihitung dengan
GK internasional ($1,9 PPP per hari). Kemudian, sejak tahun 2012
terlihat bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan GK Nasional lebih
tinggi. Berdasarkan fakta ini, artinya GK nasional memiliki nilai yang
Ilustrasi distribusi pengeluaran per kapita secara spesifik pada
tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2. Distribusi pengeluaran
konsumsi per kapita di Indonesia cenderung right-skewed. Data yang
digunakan adalah Susenas Maret 2019. Rata-rata pengeluaran konsumsi
per bulan secara nasional adalah Rp1.165.241 per kapita (BPS, 2019).
Melalui ilustrasi ini, maka dapat dilihat tingginya jumlah penduduk
dengan pengeluaran konsumsi per kapita yang berada di bawah rata-rata
GK nasional yang dihitung BPS lebih tinggi daripada GK
internasional $1.9 PPP per hari tahun dasar 2011. Angka kemiskinan
berdasarkan GK nasional tahun 2019 adalah 9,41 persen (BPS, 2019).
Dengan menggunakan acuan tingkat inflasi IHK dan GK internasional
$1,9 PPP per hari tahun dasar 2011, estimasi angka kemiskinan
menggunakan GK internasional $1,9 PPP per hari adalah 3,5 persen.
Besarnya nilai GK nasional BPS adalah Rp 425.250 per bulan per
kapita atau ekuivalen dengan GK Internasional $2,5 PPP per hari.
Standar GK yang dapat dipergunakan untuk mengukur angka
kemiskinan kerap dipertanyakan, mengingat keberadaan dua jenis GK
yang tersedia untuk Indonesia. Pertama, GK nasional yang dirilis oleh
BPS, kemudian yang kedua adalah GK internasional yang dikeluarkan
oleh Bank Dunia. Kedua jenis GK ini disusun menurut tujuan yang
berbeda. GK nasional merupakan acuan penghitungan angka
kemiskinan untuk memantau perkembangan pencapaian pembangunan
terkait indikator kemiskinan dengan batas biaya hidup minimum.
Tindak lanjut dari hasil estimasi angka ini kemudian diterjemahkan
dalam sejumlah program untuk penanggulangan kemiskinan. Sementara
itu, GK internasional disusun sebagai bagian dari perangkat analisis
kemiskinan antar- negara, dimana dibutuhkan keterbandingan pilihan
komoditi dan harga melalui penghitungan PPP.
AS.Namun, perlu menggunakan nilai tukar PPP yang merujuk pada
publikasi ICP sesuai tahun dasar yang ditetapkan dengan menerapkan
tingkat inflasi IHK, misalkan pada tahun 2011.
Wacana yang terus berkembang adalah pilihan GK nasional yang
dipakai untuk menghitung angka kemiskinan lebih rendah daripada GK
internasional. Faktanya, secara gradual tingkat kemiskinan yang
dihitung menurut GK internasional menurun lebih cepat dari tahun ke
tahun daripada angka kemiskinan yang menggunakan GK nasional.
Bahkan, mulai dari tahun 2012, angka kemiskinan berdasarkan GK
internasional lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka
kemiskinan yang menggunakan GK nasional. Sehingga, besaran nilai
GK nasional Indonesia yang dihitung oleh BPS sejak tahun 2012 masih
lebih tinggi dibandingkan dengan GK internasional.
c. Jenis-jenis Kemiskinan
1) Kemiskinan Subjektif
Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang terjadi karena setiap
orang mendasarkan pemikiranya sendiri dengan menyatakan bahwa
kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun sebenarnya
tidak terlalu miskin.
2) Kemiskinan Absolut
Kemiskinan Absolut adalah seseorang (keluarga) yang memiliki
untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan
pendidikan mereka.
3) Kemiskinan Relatif
Kemiskinan Relatif adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena
adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau
seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya
ketimpangan pendaptan atau ketimpangan standar kesejahteraan.
4) Kemiskinan Alamiah
Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena keadaan
alam yang miskin atau langka sumber daya alam (SDA), sehingga
produktivitas masyarakat menjadi rendah.
5) Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena sikap dan
kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari
budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki
taraf hidup dengan tata cara modern.
6) Kemiskinan Struktural
Kemiskinan yang terjadi karena ketidak mampuan sistem atau
struktur sosial menghubungkan seseorang dengan sumber daya yang
d. Ukuran Kemiskinan
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur
kemiskinan berdasarkan dua kriteria yaitu (Suryawati, 2005):
1. Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga yang
tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama
dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari
satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih
dari 80% dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
2. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1), yaitu keluarga yang tidak
berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik,
minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli
pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per
segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10
sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5
sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga
mempunyai penghasilan rutinatau tetap, dan tidak ada yang sakit
selama tiga bulan.
e. Penyebab Kemiskinan
Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut
Hartomo dan Aziz (Dadan Hudyana, 2010) yaitu :
rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan
tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan
atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan
kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja
Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib)
menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah
untuk bekerja.
3. Keterbatasan Sumber Alam
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya
tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini
sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya
miskin.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan
bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan
lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil
kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan
keterampilan.
5. Keterbatasan Modal
penghasilan.
6. Beban Keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak
diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan
kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin
meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi, juga
mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh
kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran
ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya
penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.
Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya
(Suryadiningrat Dadan Hudayana, 2010) :
1. Keengganan bekerja dan berusaha,
2. Kebodohan,
3. Motivasi rendah,
4. Tidak memiliki rencana jangka panjang,
5. Budaya kemiskinan, dan
6. Pemahaman keliru terhadap kemiskinan
Penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang
belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk
miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi
dari penduduk miskin di daerah perkotaan (Rencana Kerja Pemerintah
berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong
penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga
miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu
menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan,
air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di
lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai.
Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada
masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan
yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih
2. Angka Harapan Lama Sekolah
a. Pengertian Angka Harapan Lama Sekolah
Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai pendidikan
formal yang digunakan penduduk dalam jumlah tahun. Cakupan penduduk
yang dihitung adalah usia 25 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah
didefinisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama
sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Dimensi pendidikan
ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan
yang merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (Badan Pusat
Statistik , 2010).
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang
dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di
Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang
penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat
didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS
merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun)
yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Angka ini diperoleh dengan 34 cara membagi banyaknya
partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah
penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t. Sebagai catatan
indikator ini dianggap peka dalam menggambarkan variasi antar provinsi.
kemiskinan. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar.
Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk
kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk
mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan
yang berkelanjutan. (Todaro dan Smith, 2006). Pendidikan mempunyai
pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel
pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi
(Hermanto dan Dwi, 2007).
Beberapa hal yang menjadi penyebab belum meratanya pendidikan
di Indonesia diantaranya adalah (Darisandi, 2005) :
1) Perbedaan tingkat sosial. Pernyataan World Development Report bahwa
pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap, dan
menyebarluaskan pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak
tersebar secara merata dan golongan miskin paling sedikit mendapat
bagian. Kasus ini dapat ditemukan di Indonesia yang pendidikannya belum
merata antara masyarakat miskin dan golongan masyarakat menengah ke
atas.
2) Keadaan geografis. Secara geografis, wilayah Indonesia yang cukup luas
sebagai negara kepulauan ternyata menjadi salah satu penghambat
pemerataan pembangunan pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa
pembangunan pendidikan tidak dapat terlaksana dengan optimal
sekali, baik secara fisik maupun non fisik.
3) Sebaran sekolah tidak merata. Sebagian besar pendirian lembaga
pendidikan masih berada dan berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan
minat untuk membangun lembaga pendidikan di daerah pedesaan masih
sangat kurang. Kemudian pembangunan sekolah yang hanya terpusat di
Wilayah Barat khususnya Pulau Jawa membuat sebaran sekolah menjadi
tidak merata. Padahal dengan kebutuhan pendidikan yang sangat besar di
Indonesia Timur seharusnya di prioritaskan pembangunan yang cukup besar
pula.
Angka Harapan Lama Sekolah mengindikasikan makin tingginya
pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi
angka harapan lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan
yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang,
baik pola pikir maupun pola tindakannya. (Hastarini, 2005),
mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih
tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki
pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang 36
pendidikannya lebih rendah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata
jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke
atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Batas maksimum 15 tahun
mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah
setara Sekolah Menengah Atas (SMA).
b. Hubungan Angka Harapan Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan
Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam
mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak
langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum,
maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan
ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka
dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincolin,
1999).
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan
dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong
peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil
yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan
produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia
memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada
akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan
3. Upah Minimum Provinsi
a. Pengertian Upah Minimum Provinsi
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7
tahun 2013 upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas
upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur
sebagai jaringan pengaman. Sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu
provinsi.
Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang
telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa
dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi
pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak
menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai
alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja
(Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2010:1). Di Indonesia, pemerintah
mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Upah
minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada Kebutuhan Fisik
Hidup Layak berupa kebutuhan akan pangan sebesar . Dalam Pasal 1 Ayat
1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum
didefinisikan sebagai ” Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok
(Studi Waisgrais, 2003) menemukan bahwa kebijakan upah
minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan
upah yang terjadi pasar tenaga kerja. Studi Askenazy (2003) juga
menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia. Implikasi upah
minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang
kompetitif. Fakta menunjukkan bahwa nilai IPM Indonesia masih lebih
rendah dibandingkan dengan nilai IPM negara- negara ASEAN lainnya
kecuali Laos, Kamboja, dan Myanmar. Capaian prestasi pembangunan
manusia Indonesia sudah tertinggal jauh dibanding negara-negara
tetangga, yaitu di bawah Singapura, Brunei, dan Malaysia yang sudah
masuk pada kategori High Human Developtment, sementara Indonesia
masih pada kategori Medium Human developtment. Kondisi ini secara
langsung juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di
Indonesia masih relatif rendah.
Tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya
tidak pernah fleksibel dan cenderung terus- menerus turun karena lebih
sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan
institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh (Todaro,
2000;327). Kemerosotan ekonomi selama dekade 1980-an yang melanda
formal meskipun mereka tahu gajinya semakin lama semakin tidak
memadai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Tingkat
pengangguran (terutama pengangguran terselubung) sangat parah dan
bertambah buruk Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam
2 pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari
diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja
profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan.
Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai
pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-
pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan
lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran
keatas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja
kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan
antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai
tidak tetap. (Sukirno, 2008:350- 351).
“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada
pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk
tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan" (Undang-Undang Tenaga
Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30). Pemberian upah kepada
imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya
yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan
tergantung pada:
1) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;
2) Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum
pekerja;
3) Produktivitas marginal tenaga kerja;
4) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat
pengusaha;
5)
Perbedaan jenis pekerjaan.Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap
sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan
produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat
dibedakan dua macam yaitu:
1) Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;
2) Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari
Undang Repubik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai ”Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap…”. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang
diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut (Volume 8, 2012 201). Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar
kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan selanjutnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Fisik Minimum. Peraturan perundangan terbaru, UU No. 13/2003, menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada