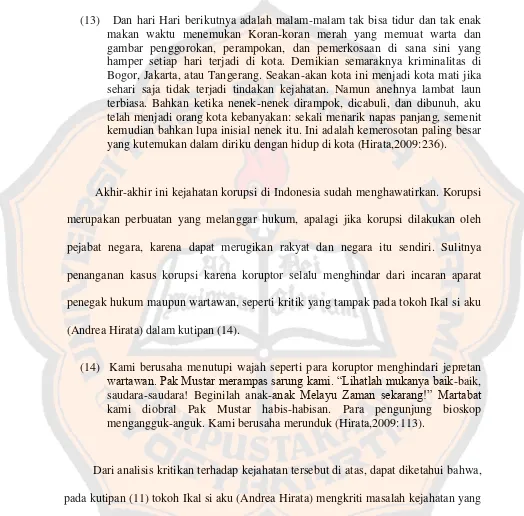KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL SANG PEMIMPI KARYA ANDREA HIRATA
Tugas Akhir
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia
Program Studi Sastra Indonesia
Oleh
Hendrikus Triantoro NIM: 034114012
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
JURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMA
KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL SANG PEMIMPI KARYA ANDREA HIRATA
Tugas Akhir
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia
Program Studi Sastra Indonesia
Oleh
Hendrikus Triantoro NIM: 034114012
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
JURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul Kritik Soial dalam novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata dengan pendekatan sosiologi sastra ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna dan masih mempunyai kekurangan karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membanggun guna perbaikan dan penyempurnaan tugas akhir ini.
Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, masukan, saran, serta dorongan semangat yang bermanfaat dan mendukung penulis dalam menyelesaian tugas akhir ini. Pada lembar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu Dra. Fransica Tjandrasih Adji, M. Hum. Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, perhatian dan bimbingan dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Drs.A. Hery Antono, M. Hum. Selaku dosen pembimbing akademik angkatan 2003 yang dengan perhatiannya selalu menanyakan dan mendorong mahasiswanya untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya. 4. Seluruh dosen Fakultas Sastra, terutama Fakultas Sastra Indonesia yang telah
memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup ini. Terima kasih, penulis haturkan kepada Bapak B Rahmanto, Bapak Yoseph Yapi Taum, Bapak I. Praptomo Baryadi, Bapak Ari Subagyo, dan Bapak F.X Santoso. 5. Segenap keluarga besar Program Studi Sastra Indonesia.
6. Segenap karyawan perpustakaan USD dan staf sekretariat Fakultas Sastra atas pelayanannya selama ini.
7. Bapakku Yoseph Djemu Istanto, Ibuku Alberta Paulina Anot, kakakku Florentina Endang Srilestari, Adrianus Lilik Purwoko, dan adikku Patresia Patmawati. Terimakasih buat doa, cinta, dan dorongan semangatnya.
8. Meilani Adrianingsih. Terimakasih untuk pengertian dan kasih sayangnya selama ini.
9. Teman-teman kosku Pringondani 12A, Ricky, Briyan, Very, Budi, Hendrik, Anggoro, Rahmad, Dody, dan teman-teman futsal yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu terimakasih untuk pertualangannya, pengertian dan persahabatannya.
HALAMAN PERSEMBAHAN
Manusia tak selamanya benar dan tak
selamanya salah, kecuali ia yang
selalu mengoreksi diri dan membenarkan
kebenaran orang lain atas kekeliruan
diri sendiri.
(Frista fantasia 2011)
Hari-hari yang terindah dan termanis
Tidak harus hari-hari dimana segalanya
Serba spektakuler atau
Memberi kejadian menyenangkan
Yang mengagumkan, melainkan
Hari-hari yang membawa
ABSTRAK
Triantoro, Hendrikus. 2011. Kritik Sosial dalam Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata: Pendekatan Sosiologi Sastra. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.
Skripsi ini membahas kritik sosial dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Karena kritik sosial dalam novel ini disampaikan melalui para tokoh maka, penelitian ini memiliki dua tujuan yakni (1) mendekripsikan tokoh dan penokohan dalam novel Sang Pemimpi, (2) mendeskripsikan kritik sosial yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi.
Judul ini dipilih karena kritik sosial yang ada dalam novel Sang Pemimpi disampaikan melalui tokoh-tokohnya. Kritik sosial tersebut muncul karena kondisi dan masalah sosial yang dialami para tokohnya, seperti kemiskinan, kejahatan, masalah birokrasi dan masalah lingkungan hidup Pulau Belitong yang hutannya telah rusak akibat penambangan timah.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra yaitu, studi yang melihat hubungan karya sastra dengan masyarakat dengan segala permasalahannya yang terdapat dalam karya sastra dan bagaimana pengarang mengungkapkan permasalahan yang ada dalam masyarakat sebagai kritik terhadap permasalahan itu sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka ini betujuan untuk mencarai data-data dan sumber-sumber tertulis yang digunakan dan dipilih sesuai dengan masalah yang terdapat dalam tujuan penelitian. Data-data tersebut berupa sebuah novel Sang Pemimpi. Adapun data lain yang mendukung penulis, berupa data dari Internet, buku, dan hasil penelitian akademis (skripsi). Selain teknik studi pustaka, penulis juga menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak digunakan untuk menyimak teks sastra yaitu novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Sedangkan teknik catat digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap sesuai dan mendukung penulis dalam memecahkan masalah.
Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi yaitu, metode yang digunakan untuk mengkaji isi suatu hal. Dalam hal ini, isi yang akan dikaji adalah sebuah karya sastra berupa novel Sang Pemimpi. Dasar dari metode ini adalah penafsiran. Dasar penafsiran analisis isi adalah isi dan pesan.
Dalam penyajian data, digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan analisis. Fakta-fakta atau data-data yang telah dikumpulkan dari novel Sang Pemimpi, berupa tokoh dan penokohan dan kritik sosial diklasifikasikan, kemudian dari fakta-fakta tersebut diberikan penjelasan secukupnya.
Tokoh utama adalah Ikal, Arai, dan Jimbron. Tokoh tambahan adalah Pendeta Geovanny, Pak Mustar M. Djai’din. BA, Drs. Julian Ichsan Balia, Nurmala, Laksmi, Capo Lam Nyet Pho, Taikong Hamim, Bang Zaitun, A Kiun, Nurmi, Pak Cik Basman, A Siong, Deborah Wong, Mei-Mei, Odji Dahrodji, Minar, Cong Cin Kiong, Mahader, dan A Put.
Dari analisis terhadap kritik sosial dalam Novel Sang Pemimpi diperoleh yaitu, kritik terhadap masalah kemiskinan disampaikan melalui tokoh Mak Cik Maryamah, Ikal, Arai, Jimbron, dan Capo. Kritik terhadap masalah kejahatan disampaikan melalui tokoh Ikal dan Minar. Kritik terhadap pelanggaran norma-norma di masyarakat disampaikan melalui tokoh Ikal si aku (Andrea Hirata) dan Pak Mustar. Kritik terhadap masalah lingkungan hidup disampaikan melalui tokoh Ikal dan Arai.
ABSTRACT
Triantoro, Hendrikus. 2011. A Social Critique of Andrea Hirata’s Novel Sang Pemimpi: Literary Sociology Approach. A Thesis. Yogyakarta: Indonesian Literature Study program, Literature Department, Sanata Dharma University.
This thesis discusses the social critique of Andrea Hirata’s novel, Sang Pemimpi. Since the social critique was conveyed through the characters, this research has two aims. They are (1) describing the characters and the characterization in Sang pemimpi, (2) describing the social critique in Sang Pemimpi.
The title was chosen because the social critique in Sang Pemimpi was conveyed through the characters. The social critique arose because of the social condition and problems experienced by the characters such as poverty, crime, bureaucracy, and environment problems in Belitong Island where the forests destroyed because of tin mining.
The approach used in this research was literary sociology approach. It was a study that observed the relationship between a literature with the society whose problems in the literature, and how the author depicted the problems in the society as the critique of the problems. The data was collected using the library study. This library study tried to find the data and written resources used and selected in the line with the problems in the research’s goals. The data was in the form of a novel, Sang Pemimpi. The other supporting data was from internet, books, and other researches. Besides using the library study, the researcher used other techniques: reading and taking a note. The literature texts in Andrea Hirata’s Sang pemimpi were read. Anything supporting the researcher to solve problems was written.
The data analysis was conducted using content analysis method. It was to examine the content of something. In this case, the content examined was a literature, Sang Pemimpi. This method was basically an interpretation. The content analysis interpretation basically consisted of content and message.
The data was presented using descriptive analytic method. It was done by describing the facts followed by an analysis. The facts or data collected from the novel Sang Pemimpi, the characters and characterization and social critique, were classified. Then, there was an explanation for those facts.
The result of this research was the classification of the characters based on the roles or the level of importance of the characters, the main characters and the supporting characters.
Laksmi, Capo Lam Nyet Pho, Taikong Hamim, Bang Zaitun, A Kiun, Nurmi, Pak Cik Basman, A Siong, Deborah Wong, Mei-Mei, Odji Dahrodji, Minar, Cong Cin Kiong, Mahader, and A Put.
From the social critique analysis, the critique of poverty was formed through the characters of Mak Cik Maryamah, Ikal, Arai, Jimbron, and Capo, The critique of crime was formed through the characters of Ikal and Minar, The critique of broken society norms was formed through the characters of me Ikal (Andrea Hirata) and Mr. Mustar, The critique of environment was formed through the characters of Ikal and Arai, a social critique of the bureaucracy was formed through the characters of Mr. Balia, Ikal, Mr. Mustar, and Bang Zaitun. Of the five existing social criticism in the novel The Dreamer, the most dominant social criticism is a social critique of the problems of poverty.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……….. i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING……….. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI………... iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA……… iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ………... v
KATA PENGANTAR ………... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN………. vii
ABSTRAK ………. ix
ABSTRACT ………. xi
DAFTAR ISI ………... xiii
BAB I PENDAHULUAN ……….. 1
1.1 Latar Belakang Masalah ……….. 1
1.2 Rumusan Masalah ……… 5
1.3 Tujuan Penelitian ………. 5
1.4 Manfaat Hasil Penelitian ……….. 5
1.5 Kerangka Teori ……… 6
1.5.1 Tokoh dan Penokohan ………. 6
1.5.1.1 Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan ………... 7
1.5.2 Sosiologi Sastra ………... 8
1.5.2.2 Masalah sosaial sebagai Kritik Sosial dalam Sastra…………. 12
1.6 Metode Penelitian ………... 15
1.6.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data ………. 15
1.6.2 Metode dan Teknik Analisis Data ……….. 16
1.6.3 Metode Penyajian Analisis Data ……… 17
1.7 Sistematika Penyajian ………. 18
BAB II ANALISIS TOKOH DAN PENOKOHAN TOKOH UTAMA DAN TOKOH TAMBAHAN ... 19
2.1 Tokoh dan Penokohan ………. 19
2.1.1 Tokoh Utama ………. 19
2.1.1.1 Tokoh Ikal ……….. 19
2.1.1.2 Tokoh Arai ………. 27
2.1.1.3 Tokoh Jimbron ………... 42
2.2.2 Tokoh Tambahan ………... 50
2.2.2.1 Tokoh Pendeta Geovanny ……….. 50
2.2.2.2 Tokoh Pak Mustar M. Djai’din. BA ……….. 51
2.2.2.3 Tokoh Pak Drs. Julian Ichsan Balia ………... 53
2.2.2.4 Tokoh Zakiah Nurmala binti Berahim Mantarum …………. 56
2.2.2.5 Tokoh Laksmi ……… 57
2.2.2.6 Tokoh Capo Lam Nyet Pho ………... 57
2.2.2.7 Tokoh Taikong Hamim ……….. 60
2.2.2.8 Tokoh Bang Zaitun ……… 61
2.2.2.10 Nurmi ………... 62
2.2.2.11 Pak Cik Basman ………... 63
2.2.2.12 A Siong ………... 64
2.2.2.13 Deborah wong ……….. 65
2.2.2.14 Mei-Mei ………... 65
2.2.2.15 Odji Dahrodji……… 65
2.2.2.16 Minar ……… 66
2.2.2.17 Chong Cin Kiong ………. 66
2.2.2.18 Mahader ………... 66
2.2.2.19 A Put ……… 67
BAB III ANALISIS KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL SANG PEMIMPI………... 68
3.1 Pengantar ……….. 68
3.2 Kritik terhadap Masalah Kemiskinan ……….. 69
3.3 Kritik terhadap Masalah Kejahatan ………. 75
3.4 Kritik terhadap Masalah Pelanggaran Norma-norma di Masyarakat……… 78
3.5 Kritik terhadap Masalah Lingkungan Hidup ………... 83
3.6 Kritik terhadap Masalah Birokrasi ………... 86
BAB IV PENUTUP ……….. 92
4.1 Kesimpulan ……….. 92
4.1.1 Kesimpulan Analisis Tokoh dan Penokohan ……….. 92
4.2 Saran ……… 96 DAFTAR PUSTAKA ………... 97
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sastra memang bukan kenyataan sosial, tetapi ia selalu berdasarkan pada kenyataan sosial. Sastra adalah kenyataan sosial yang mengalami sosial pengolahan pengarangnya. Pengarang melahirkan karya-karyanya karena ingin menunjukan kepincangan-kepincangan sosial dan kesalahan-kesalahan masyarakat, karena memprotes masyarakat dan ingin sekedar menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat dan sebagainya (Sumarjo,1979:30). Dengan kata lain, sastra adalah produk masyarakat. Ia berada di tengah masyarakat karena dibentuk oleh anggota-anggota masyarakat berdasarkan desakan-desakan emosional atau rasional dari masyarakatnya (Sumarjo,1979:12). Seniman tidak semata-mata melukiskan keadaan yang sesungguhnya, tetapi mengubah sedemikian rupa sesuai dengan kualitas kreativitasnya (Ratna,2003:7).
Pada hakikatnya, karya sastra merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Sebagai refleksi karya sastra memang tidak sepenuhnya meniru secara riil kehidupan masyarakat, akan tetapi memberikan pelajaran dan kemungkinan dari sudut pandang estetis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat (Djojosuroto 2006:58). Sebagai dokumen sosial sastra dipakai untuk menguraikan ikhitisar sejarah sosial (Wellek & Warren 1990: 122). Sastra mencerminkan segala persoalan yang ada dalam masyarakatnya dan kalau pengarang memiliki taraf kepekaan yang tinggi, karya sastranya pasti juga mencerminkan kritik sosial yang (barangkali tersembunyi) ada dalam masyarakatnya itu (Damono, 1983:22).
Karya sastra, baik sebagai kreativitas estetis maupun respon terhadap kehidupan sosial, mencoba mengungkapkan prilaku manusia dalam suatu komunitas yang dianggap berarti bagi aspirasi kehidupan seniman, kehidupan manusia pada umumnya. Karena itulah dimensi-dimensi yang dilukiskan bukan hanya entitas tokoh secara fisik, tetapi sikap dan perilaku, dan kejadian-kejadian yang mengacu pada kualitas struktur sosial (Ratna, 2003:34). Dalam novel Sang Pemimpi ini permasalahan-permasalahan dan kritik terhadap kehidupan sosial disampaikan melalui tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang menarik. Sebagai seorang asli putra Belitong, Andrea Hirata menyoroti persoalan-persoalan sosial yang terjadi di di Belitong.
Pengarang besar tentu saja tidak sekedar menggambarkan dunia sosial secara mentah. Ia menggambarkan tugas yang mendesak: memainkan tokoh-tokoh ciptaannya itu dalam suatu situasi rekaan agar mencari “nasib” mereka sendiri, untuk
selanjutnya menemukan nilai dan makna dalam dunia sosial. Sastra karya pengarang besar melukiskan kecemasan, harapan dan aspirasi manusia; oleh karena itu barangkali ia merupakan salah satu barometer sosiologis yang paling efektif untuk mengukur tanggapan-tanggapan manusia terhadap kekuatan-kekuatan sosial, (Damono 1978: 13). Seperti halnya Andrea Hirata, ia menggambarkan dunia sosial melalui tokoh-tokoh yang ada dalam Sang Pemimpi.
dengan tingkat intensitas yang berbeda. Wujud kehidupan sosial yang dikritik dapat bermacam-macam seluas lingkup kehidupan sosial itu sendiri (Nurgiyantoro, 1995: 331).
Adapun novel-novel yang telah ditulis Andrea Hirata di antaranya, yang pertama Laskar Pelangi, novel keduanya, Sang Pemimpi. Novel Edensor adalah novel ketiga dari tertalogi Laskar Pelangi. Novel keempat atau terakhir dalam rangkaian empat karya tetralogi Laskar Pelangi, adalah Maryamah Karpov.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan sosiologis sastra yang menelaah secara objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu, (Ratna, 2004:45). Dari permasalahan tersebut di atas dapat diperoleh gambaran tentang cara manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang menempatkan anggota masyarakat di tempat masing-masing, (Damono, 1978:7).
sebagai kritik social dalam sastra, penulis melakukan penyelidikan atas dasar pengarang sebagai bagian dari masyarakat dan karya yang dihasilan mencerminkan kondisi masyrakat, sehingga dengan membaca karyanya yaitu novel Sang pemimpi penulis dapat menemukan dan memecahkan permasalahan yaitu kritik sosial untuk kemudian dianalisis dan diberi pemahaman secukupnya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belaang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini rumusan permasalahan antara lain sebagai beriut:
2.1 Bagaimanakah tokoh dan penokohan dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata?
2.2 Kritik sosial apa sajakah yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
3.1 Mendeskripsikan tokoh dan penokohan dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1.4 Manfaat Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, baik bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu sastra dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya penggunaan teori-teori sastra terhadap karya sastra.
Sedangkan manfaat praktis bagi pengarang penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk dapat menciptakan karya sastra. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah minat baca dalam mengapresiasikan karya sastra. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan sastra dan menambah khazanah penelitian sastra Indonesia.
1.5 Kerangka Teori
1.5.1 Tokoh dan Penokohan
Menurut Nurgiantoro (1995:165), istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai jawaban atas pertanyaan: “siapakah tokoh utama novel
itu?” , atau “ada berapa orang jumlah pelaku novel itu?”. Watak, perwatakan, dan
penokohan dan karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan-menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Atau seperti dikatakan oleh Jones dalam (Nurgiantoro,1995:165) penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam cerita. Melalui penokohan kita dapat menyimpulkan karakter tokoh yang dipaparkan, mulai dari; kebiasaan hidup, cara pandang, ideologi, dan prinsip hidup. Penokohan sendiri menjelaskan „pelaku cerita‟ dan berarti pula „perwatakan‟.
Penggunaan istilah “karakter” sendiri dalam berbagai literatur bahasa Inggris menyaran pada dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut Stanton dalam Nurgiantoro (1995:156). Dengan demkian character dapat berarti pelaku cerita dan dapat pula berarti perwatakan. Antara seorang tokoh dengan perwatakan yang dimilikinya, memang merupakan suatu kepaduan yang utuh.
1.5.1.1 Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan
Membaca sebuah novel, biasanya kita akan dihadapkan pada sejumlah tokoh yang dihadirkan di dalamnya. Namun dalam kaitannya dengan keseluruhan cerita, peranan masing-masing tokoh tersebut tak sama. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah cerita, ada tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus-menerus sehingga terasa mendominasi sebagian besar cerita, dan ada sebaliknya, ada tokoh-tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita, dan itu pun mungkin dalam porsi penceritaan yang relatif pendek. Tokoh yang disebut pertama adalah tokoh utama cerita ( Central Character, main character), sedangkan yang kedua adalah tokoh tambahan (peripheral character).
Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh tambaan adalah tokoh yang tidak diutamakan penceritaannya, namun ia membantu memunculkan karakter dari tokoh utama (Nurgyantoro,1995:176).
1.5.2 Sosiologi Sastra
Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan tersebut disebut pendekatan sosiologi sastra (Damono, 1978:2). Menurut Damono ada dua cara kecendrunagan utama dalam sosiologi sastra, pertama pendekatan yang berdasarkan anggapan bahwa sastra merupakan cerminan proses sosial belaka. Pendekatan ini bergerak dari faktor-faktor di luar sastra, untuk membicarakan sastra. Sastra hanya berharga dalam hubungan dengan faktor-faktor di luar sastra itu sendiri. Jelas dalam hal ini teks sastra tidak dianggap sebagai yang utama. Kedua, pendekatan yang mengutamakan teks sastra sebagai bahan penelaahan. Metode yang digunakan dalam sosiologi ini adalah teks sastra untuk mengetahui strukturnya, kemudian dipergunakan untuk memahami gejala sosia budaya yang ada, (Damono, 1978:2).
Kendati sosiologi dan sastra mempunyai perbedaan tertentu, namun sebenarnya dapat memberikan penjelasan terhadap makna teks sastra. Laurenson dan Swingewood dalam (Endraswara, 2003:78). Hal ini dapat dipahami, karena sosiologi obyek studinya tentang manusia, dan sastra pun demikian. Sastra adalah ekspresi kehidupan manusia yang tak terlepas dari akar masyarakatnya. Dengan demikian meskipun sosilogi dan sastra adalah dua hal yang berbeda namun saling dapat melengkapi. Dalam kaitan ini, sastra merupakan sebuah refleksi lingkungan sosial budaya yang merupakan suatu teks dialektika antara pengarang dengan situasi sosial yang membentuknya atau merupakan penjelasan suatu sejarah dialektika yang dikembangkan dalam karya sastra, (Endraswara, 2003: 78).
Keadaan masyarakat di salah satu tempat pada suatu saat penciptaan karya sastra, secara ilustratif akan tercermin di dalam sebuah karya sastra. Karya sastra biasanya berisi lukisan yang jelas tentang suatu tempat dalam suatu masa dengan berbagai tindakan manusia. Manusia dengan berbagai tindakannya di dalam masyarakat merupakan objek kajian sosiologi. Seperti yang dikatakan Marx dalam (Faruk,1999:6), struktur sosial sustu masyarakat, juga struktur lembaga-lembaganya, moralitasnya, agamanya, dan kesusastraannya, terutama sekali ditentukan oleh kondisi-kondisi kehidupan, khususnya kondisi-kondisi produktif kehidupan masyarakat itu.
kekuatan sosial suatu periode tertentu. Dalam hal ini teks sastar dilihat sebagai pantulan zaman, karena itu “ia” menjadi saksi zaman, (Endraswara, 2003:78).
1.5.2.1 Kritik Sosial
Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dalam konteks inilah kritik sosial merupakan salah satu variabel penting dalam memelihara sistem sosial. Berbagai tindakan sosial ataupun individual yang menyimpang dari orde sosial maupun orde nilai moral dalam masyarakat dapat dicegah dengan memfungsikan kritik sosial (Mas‟oed,1997:47).
Kata „kritik‟ yang lazim kita pergunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani krinein yang berarti „mengamati‟, membandingkan dan menimbang‟. Dan kritik itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pengamatan yang diteliti, perbandingan yang adil terhadap baik-buruknya kualitas nilai sesuatu dan kebenaran sesuatu (Tarigan,1985:187-188), sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kritik adalah kecaman atau tanggapan yang sering disertai argumen yang baik maupun buruk tentang suatu karya, pendapat, situasi, dan tindakan seseorang atau kelompok, (Pusat Bahasa, 2002:761).
Kata sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2002:1085), adalah berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum. Dari defenisi „kritik‟ dan „sosial‟ dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kritik
atau kepentingan umum yang disertai uraian-uraian dan perbandingan tentang baikik buruk karya sastra tersebut.
Pengarang dalam menciptakan karya sastra mempunyai hak penuh untuk mengharapkan rasa tanggung jawab sosial dari pengarang (Damono,1978:54). Rasa tanggung jawab sosial ini berupa rasa kritik atau protes, tidak untuk membuat ilusi tetapi untuk menghancurkannya. “Bagaimanapun sastra, secara tersurat maupun
tersirat merupakan penilaian kritik terhadap jamannya” (Damono,1978:54).
Berpijak dari beberapa pemahaman tentang masalah sosial sebagai kritik sosial tersebut di atas maka, penelitian ini akan melihat kritik sosial apa sajakah yang diungkapkan oleh Andrea Hirata dalam novel Sang Pemimpi.
1.5.2.2 Masalah Sosial sebagai Kritik Sosial dalam Karya Sastra
Sastra bukanlah sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang terikat erat dengan situasi dan kondisi tempat karya itu dilahirkan (Jobrim,2001:167). Seorang pengarang senantiasa dan niscaya hidup dalam ruang dan waktu tertentu. Ia senantiasa akan terlibat dengan beranekaragam permasalahan. Dalam bentuknya yang paling nyata ruang dan waktu itu adalah masyarakat atau sebuah kondisi sosial, tempat berbagai pranata nilai di dalamnya berinteraksi. Pernyataan di atas senada dengan apa yang diungkapkan Tirtawirya (1982:83) bahwa renungan atas kehidupan merupakan suatu ciri khas yang senantiasa terdapat dalam karya sastra. Dengan demikian keadaan masyarakat disekitar pengarang akan berpengaruh terhadap kreatifitas pengarang dalam menghasilkan karya sastra.
(1995:331), sastra yang mengandung pesan kritik atau disebut sastra kritik, lahir ditengah-tengah masyarakat jika terjadi hal-hal yang kurang beres dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Banyak karya sastra yang memperjuangkan nasip rakyat kecil yang menderita, nasip rakyat kecil yang perlu dibela, rakyat kecil yang dipermainkan oleh tangan-tangan kekuasaan. Berbagai penderitaan rakyat itu dapat berupa korban kesewenangan, penggusuran, penipuan atau selalu dipandang, diperlakukan atau diputuskan sebagai pihak yang selalu di bawah, kalah dan salah. Semua itu adalah hasil imajinasi pengarang yang telah merasa terlibat dan ingin memperjuangkan hal-hal yang diyakini kebenaranya lewat karya-karya yang dihasilkannya.
Dengan adanya pengaruh lingkungan masyarakat terhadap hasil karya seorang pengarang, kebanyakan akan memunculkan kritik sosial terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Nurgiyantoro (1995:331) mengatakan sastra yang mengandung pesan kritik dapat disebut kritik, biasanya akan lahir di tengah masyarakat jika terjadi hal-hal yang kurang beres dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Pengarang umumnya tampil sebagai pembela kebenaran dan keadilan ataupun sifat-sifat luhur kemanusiaan yang lain.
yang berdasarkan atas studi. Mereka mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.
Soekanto (2002:365-394) mengemukakan kepincangan-kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat, tergantung dari sistem nilai-nilai sosial masyarakat tersebut, akan tetapi ada beberapa persoaalan yang sama yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, misalnya:
a) Kemiskinan
Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memilihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut Soekanto (2002:365-394).
b) Kejahatan
Kejahatan diartikan sebagai perilaku dengan kecendrungan untuk melawan norma-norma hukum yang ada. Kejahatan yang perlu mendapat perhatian pada saat ini adalah apa yang disebut white collour crime, yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha atau pejabat dalam menjalankan peran dan fungsinya Soekanto (2002:365-394).
c) Pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat
d) Masalah lingkungan hidup
Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan hal-hal disekitar manusia baik sebagai individu maupun dalam pergaulan hidup. Masalah lingkungan hidup dibedakan menjadi dua pertama, lingkungan fisik yaitu segala benda-benda mati yang berada di sekitar manusia, yang kedua lingkungan biologis yaitu segala sesuatu yang ada disekeliling manusia yang berupa organisme dan lingkungan sosial yang terdiri dari orang-orang secara individual maupun kelompok yang berada di sekitarnya Soekanto (2002:365-394).
e) Masalah birokrasi
Pengertian birokrasi adalah organisasi yang bersifat hirarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif Soekanto (2002:365-394).
1.6 Metode Penelitian
Metode adalah cara yang dipilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan bentuk, isi, dan sifat sastra sebagai subyek kajian (Endraswara,2003:8).
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, dan metode penyajian analisis data. Tahap-tahap penelitiann akan diuraikan sebagai berikut.
1.6.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
sumber-sumber tertulis yang digunakan dan dipilih sesuai dengan masalah yang terdapat dalam tujuan penelitian, (Ratna,2004:39). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebuah novel berjudul Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Adapun data lain yang juga mendukung penulis dalam memecahkan masalah berupa buku ataupun hasil penelitian akademis (skripsi).
Selain studi pustaka, penulis juga menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak digunakan untuk menyimak teks sastra yaitu novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Sedangkan teknik catat digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap sesuai dan mendukung penulis dalam memecahkan masalah. Teknik catat tersebut merupakan tindak lanjutan dari teknik simak.
1.6.2 Metode dan Teknik Analisis Data
Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode analisis isi. Metode ini bertujuan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk mengkaji isi dari suatu hal. Isi dari suatu hal tersebut yang akan menjadi fokus analisis, misalnya karya sastra berupa novel, maka yang akan diteliti adalah isi dari novel tersebut. Dasar dari metode analisis isi adalah penafsiran. Dasar penafsiran dalam analisis isi adalah menitikberatkan pada isi dan pesan. Oleh karena itu metode ini sering diterapkan pada dokumen-dokumen yang padat isi (Ratna, 2004: 49).
sebagai akibat dari komunikasi yang terjadi. Isi laten adalah isi sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis, sedangkan isi komunikasi adalah isi sebagaimana yang terwujud dalam hubungan naskah dengan konsumen. Analisis isi laten akan menghadirkan arti, sedangkan analisis isi komunikasi akan melahirkan makna.
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis isi yang akan menganalisis isi laten dari sebuah naskah. Dengan demikian peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada isi yang terkandung dalam teks sastra tanpa melihat isi komunikasi dari naskah tersebut. Dari data-data yang telah diperoleh akan dilakukan analisis dengan tujuan untuk memaparkan secara tepat tentang tokoh dan penokohan serta kritik sosial dalam novel Sang Pemimpi.
Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan penulis diantaranya, menganalisis tokoh dan penokohan yang ada dalam novel Sang Pemimpi yang berdasarkan pada segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kritik sosial yang ada dalam novel Sang Pemimpi.
1.6.3 Metode Penyajian Analisis Data
Data-data yang berupa tokoh-tokoh, kutipan percakapan yang berkaitan dengan tokoh dan penokohan, serta kritik sosial dianalisis, disusun secara cermat, dan disajikan secara sistematis sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Dengan demikian akan diperoleh suatu analisis terhadap tokoh dan penokohan dan kritik sosial yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1.7 Sistematika Penyajian
Untuk mempermudah pemahaman terhadap proses dan hasil penelitian ini dibutuhkan suatu sistematika yang jelas. Sistematika penyajian dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut;
Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, metode penyajian hasil analisis data, dan sisematika penyajian.
Bab II meliputi uraian pembahasan mengenai tokoh dan penokohan dalam novel Sang Pemimpi. Karya Andrea Hirata.
Bab III meliputi uraian pembahasan mengenai kritik sosial dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
BAB II
ANALISIS TOKOH DAN PENOKOHAN TOKOH UTAMA DAN TOKOH TAMBAHAN
2.1 Tokoh dan Penokohan
2.1.1 Tokoh Utama
Dalam novel Sang Pemimpi diketahui tokoh utama terdiri dari tiga orang tokoh yaitu, Ikal, Arai, dan Jimbron. Ketiganya dikatakan sebagai tokoh utama karena ketiga tokoh ini berperan besar dalam keseluruhan cerita, mempunyai pengaruh yang besar dalam kseseluruhan ide cerita, dan eksistensi ketiga tokoh ini mendominasi sebagian besar isi cerita karena novel ini menceritakan tentang persahabatan mereka dalam menghadapi kenyataan hidup membiayai sekolah dengan bekerja sebagai kuli panggul di pasar ikan sampai mereka dewasa, merantau ke Jawa dan bersekolah di perguruan tinggi. Cerita tentang persahabatan mereka, perjuangan hidup mereka dalam novel Sang Pemimpi ditampilkan secara terus menerus.
2.1.1.1 Tokoh Ikal
Ikal dalam novel ini adalah tokoh pencerita, si aku dalam cerita. Pada saat Ikal terlambat masuk sekolah, di depan sekolahnya, Ikal beraksi bersama Jimbron temannya. Aksi mereka bertujuan untuk mencari perhatian dari siswi-siswi SMA-nya:
rambutku ke belakang, selalu dengan tangan dan tenaga penuh menariknya kembali. Maka muncullah bongkahan jambul terbinar-binar. Dan inilah puncak muslihat anak Melayu kampung; di dekat para siswi tadi, aku berpura-pura menunduk untuk membetulkan tali sepatu, yang sebenarnya tidak apa-apa, sehingga ketika bangkit aku mendapat kesempatan menyibakkan jambilku seperti gaya pembantu membilas cucian. Ah, elegan, elegan sekali. Sangat Melayu! Sayangnya, gadis-gadis kecil itu rupanya telah dikaruniai Sang Maha Pencipta semacam penglihatan yang mampu menembus tulang-benulang, sehingga bagi mereka tubuhku transparan. Aku ada disana, hilir-mudik pasang aksi seperti bebek, tapi mereka tak melihatku, sebab tak seorang pun ingin memedulikan laki-laki yang berbau ikan pari menyeringai kejam. Aku menjejalkan pijakan langkahu untuk melompat tapi terlambat. Pak Mustar merengut kerah bajuku, menyentak dengan keras hingga seluruh kancing bajuku putus. Kancing-kancing itu berhamburan ke udara, berjatuhan gemerincing. Aku meronta-ronta dalam gengamannya, menggelinjang, dan terlepas! Lalu wuuttthhh!! Hanya seinci dari telingaku, Pak Mustar menampar angin sebab aku merunduk. Aku berbalik mencuri momentum dengan mengumpulkan seluruh tenaga pada tunjangan kaki kanan dan sedetik kemudian melesat kabur (Hirata,2009:12-13).
Ikal terus berlari saat di kejar Pak Mustar, ia menampilkan kebolehannya berlari ketika di kejar Pak Mustar gurunya dan dua orang penjaga sekolah. Ia di kejar Pak mustar karena terlambat masuk sekolah. Kebolehan Ikal berlari dapat dilihat pada kutipan berikut:
kini gadis-gadis manis Melayu itu, yang tadi tak sedikit pun mengacuhkan aku melolong-lolong mendukungku (Hirata,2009:13).
Ikal terlibat perdebatan dengan Arai karena Arai menggunakan uang tabungannya. Ikal tidak mau rugi sedikitpun jika uang yang dimilikinya di ambil orang lain untuk tujuan yang tidak ia ketahui. Ikal tidak rela memberikan uangnya kepada orang lain termasuk Arai, ia merasa telah bersusah payah menabung. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada saat Ikal berdebat dengan Arai, karena Arai menggunakan uang tabungannya untuk membeli terigu, yang kelak akan diberikannya kepada Mak Cik Maryamah:
(4) “ Nyah…,” seru Arai pada Nyonya Deborah. Santun dan berwibawa, seolah
ia akan memborong seluruh isi toko dengan koin-koin itu. “Terigu 10 kilo,
gandum 10 kilo, gula….”Aku terkejut tak kepalang. “Rai! Apa-apaan ini?!”
“Untuk apa segala terigu….” Tangkas, Arai menekan jarinya di atas mulutku.
“Sstttt!! Diam, “Nyah, jangan lupa minyak….” Kutepis tangannya dengan marah, Arai tersentak. “Diamlah, Ikal. Lihat saja….” Langsung kupotong,” Ke mana pikiranmu, Rai!! Sudah setahun lebih kita menabung!!” “Tong! Tong! Tong!! Tong! Tong!!” Sang ibu mertua Nyonya Deborah menampar-namparkan piring kalang tempat makanan kucing, menyuruh kami diam.
“Sabar, Kal. Nan ….” “Tak ada sabar!!” “Ini penting, Kal. Bahan-bahan ini
akan ….” “Tak ada penting!! Lupakah kau untuk apa kita susah payah menabung??!!” (Hirata,2009:44-45).
Ikal bersama kedua sahabatnya yaitu Arai dan Jimbron mereka harus membanting tulang untuk membiayai hidup serta membiayai sekolah. Dari kuli ngambat, penyelam di padang golf, office boy, dan menjadi tukang pikul di pelabuhan:
keruk di tengah padang golf itu. Penjaga padang golf akan membayar untuk setiap bola golf yang dapat diambil pada kedalaman hamper tujuh meter di dasar danau (Hirata,2009:68-69).
(6) ….lalu kami beralih menjadi part time office boy di komplek kantor
pemerintah. Mantap sekali judul jabatan kami itu dan hebat sekali job descriptionnya: masuk kerja subuh-subuh dan menyiapkan ratusan gelas the dan kopi untuk para abdi negara. Persoalannya lebih sadis dari ancaman reptile cretaceus itu, yaitu berbulan-bulan tak digajih (Hirata,2009:69). (7) Setiap pukul dua pagi, berbekal sebatang bambu, kami sempoyongan
memikul berbagai jenis makhluk laut yang sudah harus tersaji di meja pualam stanplat pada pukul lima, sehingga pukul enam sudah bias diserbu ibu-ibu. Artinya, setelah itu kami leluasa untuk sekolah. Setiap pagi kami selalu seperti semut kebakaran. Menjelang pukul tujuh, dengan membersihkan diri seadanya karena itu kami selalu berbau seperti ikan pari kami tergopoh-gopoh pergi ke sekolah (Hirata,2009:70).
Ikal selalu tidak terima atas segala hukuman yang menimpanya, termasuk hukuman yang diberikan Pak Mustar kepadanya dan kedua temannnya Arai dan Jimbron. Mereka dihukum karena kedapatan menonton film porno di bioskop milik Capo. Ikal, Arai, dan Jimbron disuruh meniru adegan film yang mereka tonton di bioskop serta membersihkan WC sekolah, seperti pada kutipan berikut:
(8) Akhirnya, aku jengkel pada Pak Mustar yang tak punya perasaan. Maka aku bertekad menghayati peranku. Aku melengak-lengok dengan gaya yang seksi seperti sang pembantu yang semlohai di film murahan itu. Ekspresiku, gerak-geriku, suaraku, semuanya meniru seorang wanita. Dan tahukah, kawan, hal ini justru menimbulkan kehebohan yang luar biasa di lapangan sekolah kami. Para penonton tertawa melihatku sampai keluar air mata (Hirata,2009:123). (9) Setiap menunduk untuk menyikat lantai WC aku menahan nafas. Hebatnya
Pada saat menjalani hukuman dari Pak Mustar, Ikal marah saat Jimbron terus menerus bercerita tentang kuda. Menurutnya, Jimbron telah terpengaruh dan terobsesi oleh kuda, lebih daripada itu kuda menurutnya telah membuat pertengkaran terjadi di antaranya dan Jimbron, seperti yang terlihat pada kutipan berikut:
(10) “Diaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmm!!!!” Aku bangkit, berteriak sekuat tenaga membentak Jimbron saling membanting sikat gigi, lap, dan pahat. Brughh!! Arai yang tengah mengumpulkan kotor-kotoran kelelawar terperanjat. Jika tidak mengikatkan dirinya pada balok plafon, dia sudah terhempas ke lantai. Kotoran kelelawar dari tas Arai tumpah seperti hujan bubuk belerang memaafkan Jimbron yang telah ia marahi karena terus-terusan bercerita tentang kuda. Berikut adalah kutipan ketika Ikal meminta maaf atas sikapnya yang kasar terhadap Jimbron:
(12) Aku menghampirinya. Melepaskan slang yang melingkar lehernya dan membimbingnya keluar. Tubuhnya masih bergetar. Sambil kuelus-elus punggungnya, kubimbing ia berjalan menuju kantin sekolah yang telah sepi. Jimbron tersedu sedan tanpa air mata. Dadaku sesak dibuatnya. Kupesankan teh manis kesenangannya dengan cangkir terbesar yang ada. Jimbron masih shock. Ia benar-benar terpukul. “Maafkan aku, Bron…,” kataku lembut.”
Tetapi memang sudah saatnya kau berhenti memikirkan kuda….” Jimbron
memalingkan wajahnya, jauh memandang padang rumput sekolah. Ia seperti berkontemplasi, merenungkan ketidaknormalannya selama ini (Hirata,2009:135).
Sebagai seorang sahabat, Ikal memberikan nasehat pada Jimbron agar melupakan obsesinya akan kuda, ia sangat perhatian pada Jimbron, ia tidak ingin temannya itu terus-terusan terpengaruh oleh kegilaanya akan kuda, seperti yang terdapat pada kutipan berikut:
(14) “Kisah kuda ini sudah keterlaluan, kawan….Tidak kah kau ingat, sejak kita SD diajar mengaji oleh Taikong Hamim, sejak itu tak ada hal lain yang kau pedulikan selain kuda? Sekarang kita sudah tidak SD lagi Bron. Sebentar lagi kita dewasa. Kau tahu‟kan arti menjadi dewasa, Bron? Akil balik menurut
ketentuan agama?” (Hirata,2009:136).
(15) ….”Sahabatku, banyak hal lain yang lebih positif di dunia ini. Banyak hal lain yang amat menarik untuk dibicarakan, misalnya tentang…mengapa kita orang Melayu, yang hidup di atas tanah timah kaya raya tapi kita semakin miskin hari demi hari, atau tentang…bupati kita baru itu, apakah ia seorang laki-laki sejati atau tidak lebih dari seorang maling seperti yang sudah-sudah, atau tentang cita-cita kita merantau ke Jawa, naik perahu barang dan tentang rencana kita sekolah ke Prancis!! (Hirata,2009:137).
Saat diminta Pak Balia untuk mengucapkan salah satu motto dari tokoh-tokoh kenamaan, Ikal gugup dan gemetar karena dia belum siap:
(16) Semua mata memandangku melecehkan. Tak pernah Pak Balia harus meminta dua kali. Memalukan! Aku gemetar karena tak siap. Tapi aku harus berdiri. Tak mungkin menghianati euphoria kelas ini. Dan pada detik menentukan, aku senang sekali, eureka!! Sebab aku teringat akan ucapan seniman besar favoritku. Akan kukutip salah satu syair lagunya. Aku berdiri tegak-tegak, berteriak “Masa muda, masa yang berapi-api!! Haji Rhoma Irama!” (Hirata,2009:77).
(17) Maka di los kontrakan kami sekarang terpajang tiga tokoh idola kami: Jim Morrison favorit Arai, Laksmi cinta Jimbron, dan Kak Rhoma Irama, seniman kesayanganku (Andrea Hirata,2009:184)
Pada suatu siang, saat Ikal berlari pulang dari sekolah, di sebuah restoran ia melihat bayangan masa depannya beserta kedua temannya Arai dan Jimbron menjadi pelayan di restoran, menjadi kernet bus, dan menjadi pedagang kweni. Ia takut apa yang dilihatnya akan menjadi kenyataan. Ketakutan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut ini:
(19) Aku selalu berlari pulang sekolah tapi siang ini, di depan restoran mi rebus, langkahku terhenti. Aku terkejut melihat tiga orang di dalam restoran: Aku, Arai, dan Jimbron tengah membereskan puluhan piring kotor yang berserakan di atas meja. Aku berlari lagi memandangi tiga orang yang kukenal itu sampai jauh (Hirata,2009:124).
(20) Aku kembali terhenti melihat tiga mobil omprengan reyot di depan kantor syahbandar. Tiga orang kernetnya- Arai, Jimbron, dan Aku sendiri-termangu-mangu menunggu penumpang ke Tanjong Pandan. Aku ketakutan menyaksikan orang lain telah menjelma menjadi diriku. Aku kabur pontang-panting. Sampai di los kontrakan aku kehabisan napas. Dan nun di sana, di Semenanjung Ayah, aku merinding melihat Arai, Jimbron dan aku sendiri berpakaian compang-camping, memikul karung buah kweni (Hirata,2009:142).
Ketakutan tokoh Ikal akan masa depannya yang buruk berakibat bagi pribadinya. Semenjak ia menyaksikan bayangan masa depannya bersama Arai dan Jimbron sebagai pelayan di restoran, kernet, dan pedagang kweni, kini kia menjadi tokoh yang pesimis terhadap masa depannya. Hal ini terlihat pada kutipan berikut:
(21) Aku sendiri, Jimbron, dan Arai yang kusaksikan membersihkan meja di restoran, menjadi kernet, dan pedagan kweni tak lain adalah manifrestasi dari sikapku yang telah bisa realistis; karena usiaku telah menginjak delapan belas tahun. Kini aku sadar setelah menamatkan SMA nasipku akan sama saja dengan nasib kedua sahabatku waktu SMP: Lintang dan Mahar. Lintang yang cerdas malah tak sempat menyelesaikan SMP. Sungguh tak adil dunia ini; seorang siswa garda depan sekaligus pelari gesit berambut ikal mayang akan berakhir sebagai tukang cuci piring di restoran mi rebus (Hirata,2009:143). (22) Dan sampai di los kontrakan , aku melongok ke dalam kaleng celenganku
perlahan padam. Aku sangat maklum, bahwa tabungan ku itu tak akan pernah mampu membawaku keluar dari pulau kecil Belitong yang bau karat ini. Bagi kami, harapan sekolah ke Prancis tak ubahnya pungguk merindukan dipeluk purnama, serupa kodok ingin dicium putri agar berubah menjadi pangeran. Altar suci almamater Sorbonne, menjelajah Eropa sampai ke Afrika, hanyalah muslihat untuk menipu tubuh yang kelelahan agar tak terbangun pukul dua pagi untuk memikul ikan. Kami tak lebih dari orang yang menggadaikan seluruh kesenangan masa muda pada kehidupan dermaga yang keras, hidup tanpa pilihan dan belas kasihan (Hirata,2009:144).
(23) Kini aku telah menjadi pribadi yang pesimistis. Malas belajar, berangkat dan pulang sekolah lariku tak lagi deras. Hawa positif dalam tubuhku menguap dibawa hasutan-hasutan pragmatis. Untuk apa aku memecahkan kepalaku mempelajari teorema binomial untuk mengukur bilangan tak terhingga jika yang tak terhingga bagiku adalah kemungkinan tak mampu melanjutkan sekolah setelah SMA, jika yang akan ku ukur nanti hanya jumlah ikan yang telah kupikul agar mendapat beberapa perak uang receh dari nahkoda. Buat apa aku bersitegang urat leher berdebat di kelas soal geometri ruang Euclidian yang rumit, jika yang tersisa untukku hanya sebuah ruang los sempit 2x2 meter di dermaga. Pepatahku sekarang adalah pepatah konyol kuli-kuli Meksiko yang patah arang karena nasib: ceritakan mimpimu agar tuhan bias tertawa (Hirata,2009:145).
Dari analisis penokohan tokoh Ikal di atas, dapat diketahui bahwa tokoh Ikal adalah tokoh yang kreatif dan suka mencari perhatian dari siswi-siswi SMA-nya (1). Tokoh Ikal juga digambarkan sebagai siswa yang nakal, ia dikejar Oleh Pak Mustar gurunya karena terlambat masuk sekolah (2). Ikal juga jago berlari kencang karena ia adalah sprinter di SMA-nya, kebolehannya ini ditunjukkannya pada saat ia dikejar oleh Pak Mustar (3). Ikal merupakan tokoh yang suka menabung, oleh karena itu ia tidak mau uangnya digunakan oleh Arai untuk keperluan yang belum ia ketahui (4). Demi menyambung hidup, membiayai sekolah, dan membantu orang tua, Ikal bekerja sebagai kuli ngambat, penjual buah kuwni, dan penyelam di padang golf. Ikal adalah sosok pekerja keras (5),(6), dan (7).
benci pada Pak Mustar (8),(9). Ikal sangat benci dengan cerita kuda, ia bosan dengan cerita kuda Jimbron (10), (11). Setelah pertengkarannya dengan Jimbron karena kebenciannya akan cerita kuda, Ikal berjiwa besar dan mau meminta maaf atas tindakannya memarahi Jimbron (12), (13). Ikal selalu peduli dan mau menasehati temannya, seperti ia menasehati Jimbron yang terobsesi dengan kuda (14), (15). Ikal adalah pengemar seniman Rhoma Irama. Mendengar nama Rhoma Irama ia selalu bersemangat (16),(17),(18). Tokoh Ikal menjadi tokoh penakut (paranoid) karena halusinasi masa depannya yang buruk (19),(20). Karena dihantui oleh ketakutan masa depannya yang buruk, tokoh Ikal menjadi pribadi yang pesimis dan mudah putus asa (21),(22), dan (23).
2.1.1.2 Tokoh Arai
Tokoh Arai memberi saran kepada Ikal untuk bersembunyi di balik para-para tempat penjemuran daun cincau saat mereka dikejar oleh Pak Mustar karena terlambat masuk sekolah:
(24) Kami mengendap. Tersengal Arai memberi saran seperti biasa, pasti saran yang menjengkelkan.“Ikal…aku tak kuat lagihh…Habis sudah
napasku….Kalian lihat para-para itu…?” ….”Lompati para-para itu,
menyelinap ke warung A Lung, dan membaur di antara para pembeli tahu,
aman…” Aku meliriknya kejam. Mendengar ocehannya, ingin rasanya aku
mencongkel gembok peti es untuk melempar kepalanya. “Hebat sekali teorimu Rai! Tak masuk akal sama sekali! Jimbron mau kau apakan??!!
Jimbron yang penakut memohon putus asa “ Aku tak bias melompat Kal…”
(Hirata,2009:2-3).
(25) Semuanya gara-gara Arai. Kureka perbendaharaan kata kasar orang Melayu untuk melabraknya. Tapi lambat-lambat berderak mendekat suara sepatu pantofel. Aku mundur, tegang dan hening, keheningan beraroma mara bahaya. Arai menampakan gejala yang selalu ia alami jika ketakutan: tubuhnya menggigil, giginya gemeletuk dan napasnya mendengus satu-satu. Bayangan tiga orang pria berkelebat, memutus sinar stainless tadi dan sekarang pemisah kami dengan nasip buruk hanya beberapa keping papan tipis. Ketiga bayangan itu merapat ke dinding, dekat sekali sehingga tercium olehku bau keringat seorang pria kurus tinggi bersafari abu-abu. Ketika ia berbalik, aku membaca nama pada emblem hitam murahan yang tersemat di dadanya: Mustar M. Djai‟Din, B.A. (Hirata,2009:4-5).
Saat masih dalam pengejaran Pak Mustar, di tengah kepanikannya, Arai kembali memberikan ide kepada Ikal dan Jimbron. Ia mengajak kedua temannya masuk dan bersembunyi di dalam peti es tempat penyimpanan ikan, seperti pada kutipan berikut:
(26) “Ikal bisiknya sambil melirik peti es. Aku paham maksudnya! Luar biasa dan
sinting!! Itulah aria dengan otaknya yang ganjil. Aku suspense. Otakku berputar cepat mengurai satu per satu perasaan cemas, ide yang memacu adrenalin, dan waktu yang sempit. Arai mencongkel gembok dan menyingkap tutup peti. Wajah kami seketika memerah saat bau amis yang mengendap lama menyeruak. Isi peti mirip remah-remah pembantaian makhluk bawah laut. Sempat terpikir olehku untuk mengurungkan rencana gila itu, kami tak punya pilihan lain (Hirata,2009:18).
Arai memerintahkan Ikal untuk masuk ke dalam peti es tempat penyimpanan sikan. Ikal memprotes perintah Arai karena menurutnya yang memimpin pelarian ini adalah dirinya, hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:
(27) “Ikal! Masuk duluan!” perintah Arai sok kuasa. Tatapanku berkilat
“Tak Bisa Rai! Bisa kudisan aku kena umpan busuk itu…” Arai menyeringai seperti jin kurang sajen. Habis sudah kesabarannya dan meledaklah serapahnya yang legendaries. “Kudisan?!! Kudisan katamu? Kau tak punya wewenang ilmiah untuk menentukan penyakit!!” “Masuk!!” ( Hirata,2009:18-19).
Walaupun dalam keadaan terjepit karena di kejar-kejar oleh Pak Mustar, Arai selalu Menganggap pelariannya sebagai sebuah petualangan yang menyenangkan, seperti pada kutipan berikut:
(28) Berbeda dengan Arai. Waktu peti melewati para pengamen ia menjentikan jemarinya mengikuti kerincing tamborin. Dan ia tersenyum. Aku mengerti bahwa baginya apa yang kami alami adalah sebuah petualangan yang asyik. Ia meliriku yang terjepit tak berdaya, senyumnya semakin girang. “Fantastik bukan?” pasti itu maksudnya. Aku merasa takjub dengan kepribadian Arai. Tatapanku menghujam bola matanya, menyusupi lensa selaput jala, dan iris pupilnya, lalu tembus ke dalam lubuk hatinya, inginku lihat dunia dari dalam jiwanya (Hirata,2009:20-210).
Arai adalah seorang anak berbadan pendek. Terlahir dari keluarga yang miskin, ia melakukan cara apa pun demi mendapatkan uang. Seperser pun uang sangat berarti baginya, seperti yang terlihat pada kutipan berikut:
(29) Arai adalah orang kebanyakan. Laki-laki seperti ini selalu bertengkar dengan tukang parkir sepeda, meributkan uang duaratus perak. Orang seperti ini sering duduk di bangku panjang kantor pengadaian menunggu barangnya di taksir. Barangnyai itu dulang tembaga busuk kehijau-hijauan peninggalan neneknya. Kalau polisi menciduk gerombolan bromocorah pencuri kabel telepon, maka orang berwajah serupa Arai di naikan ke bak pick up, dibopong karena tulang keringnya dicuncung sepatu jatah kopral. Dan jika menonton TVRI, kita bias melihat orang seperti Arai meloncat- loncat di belakang presiden agar tampak oleh kamera (Hirata,2009:23).
(30) Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa baru seni kriya yang baru pertama kali menjamah tanah liat, pencet sana melendung sini. Lebih tepatnya, perabotan di wajahnya seperti hasil suntikan selikon dan mulai meleleh. Suaranya kering, serak, dan nyaring persis vokalis mengambil nada falsetto, mungkin karena kebanyakan menangis waktu kecil. Gerak-geriknya canggung serupa belalang sembah. Tapi matanya istimewa. Di situlah pusat gravitasi pesona Arai. Kedua bola matanya itu, sang jendela hati, adalah layar yang mempertontonkan jiwanya yang tak pernah kosong (Hirata,2009:24).
Semenjak ditinggal kedua orang tuanya, Arai hidup sebatang kara namun ia tidak pernah bersedih. Ibunya wafat saat melahirkan adiknya dan waktu itu Arai kelas satu SD, sedangkan ayahnya juga meninggal setelah Arai beranjak kelas tiga SD, nasip yang menimpa tokoh Arai dapat dilihat pada kutipan berikut:
(31) Sesungguhnya, aku dan Arai masih bertalian darah. Neneknya adalah adik kandung kakekku dari pihak ibu. Namun sungguh malang nasipnya, waktu ia kelas satu SD, ibunya wafat saat melahirkan adiknya. Arai, baru enam tahun ketika itu, dan ayahnya memeluk erat bayi merah bersimbah darah. Anak- beranak itu meninggal bersamaan. Lalu Arai tinggal berduaan bersama ayahnya. Kepedihan belum mau menjauhi Arai. Arai menginjak kelas tiga SD, ayahnya juga wafat. Arai menjadi yatim piatu, sebatang kara. Ia kemudian di pungut keluarga kami (Hirata,2009:24).
Setelah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya, Arai hidup dan menjadi saudara angkat Ikal. Mereka selalu bermain bersama dalam setiap kesempatan, seperti yang terlihat pada kutipan berikut:
(33) Aku dan Arai ditakdirkan seperti sebatang jarum di atas meja dan magnet di bawahnya. Sejak kecil kami melekat kesana kemari. Aku semakin dekat dengannya karena jarak aku dengan abang pangkuanku, abang langsung, sangat jauh. Arai adalah saudara sekaligus sahabat terbaikku. Dan meskipun kami seusia, ia lebih abang dari abang mana pun. Ia selalu melindungku. Sikap itu tercermin dari paling hal-hal kecil. Jika kami bermain melawan bajak laut, di Selat Malaka dan aku sebagai Hang Tuah, maka ia adalah Hang Lekir. Dalam sandiwara memerangi kaum Quraishi pada acara dibalai desa (Hirata,2009:31).
(34) Jika di kampung anak-anak bermain memperebutkan kapuk yang berterbangan dari pohonnya seperti hujan salju, Arai akan menjulangku di pundaknya, sepanjang sore berputar-putar di lapangan tak kenal lelah, tak pernah mau kugantikan. Ia mengejar layang-layang untukku, memetik buah delima di puncak pohonnya hanya untukku, mengajariku berenang, menyelam, dan menjalin pukat. Sering bangun tidur aku menemukan kuaci, permen gula merah, bahkan mainan kecil dari tanah liat sudah ada di saku bajuku. Arai diam-diam membuatnya untukku (Hirata,2009:32).
Semenjak kedua orang tuannya meninggal, dan diasuh oleh keluarga Ikal, Arai sudah pandai berkerja mencari uang dengan berjualan akar banar. Bahkan ia juga mengajari Ikal cara mencari akar banar, seperti pada kutipan berikut:
(35) Dan kebanyakan anak-anak Melayu miskin di kampung kami yang rata-rata beranjak dewasa mulai mencari uang, Arai-lah yang mengajariku mencari akar banar untuk dijual kepada penjual ikan. Akar ini digunakan penjual ikan untuk menusuk insang ikan agar mudah ditenteng pembeli. Dia juga yang mengajariku mengambil akar purun (perdu yang tumbuh di rawa-rawa) yang kami jual kepada pedagang kelontong untuk mengikat bungkus terasi (Hirata,2009:32).
(36) Setiap habis magrib Arai melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur‟an dibawah temaram lampu minyak dan saat itu seisi rumah kami terdiam. Suaranya kering ranggas yang menusuk-nusuk malam. Ratap rilihnya mengirisku, menyeretku ke sebuah gubuk di tengah lading tebu. Setiap lekukan tajwid yang dilantunkan hati muda itu adalah sayat kerinduan yang tak tertanggungkan pada ayah-ibunya (Hirata,2009:33).
Suatu hari Arai menyuruh Ikal mengubah gaya penempilannya, terutama sisiran rambutnya. Arai menganjurkan kepada Ikal untuk mengikuti gaya rambut musisi Toni Koeswoyo:
(37) “Oh, amboi, Ikal….tengoklah ini! Model rambut paling mutakhir!
Aiiihh…Toni Koeswoyo, rambut belah tengahnya itu! Elok bukan buatan! Lihatlah, Kal, semua pemain Koes Plus rambutnya belah tengah!” Demikianlah hasutan Arai sambil mengagumi foto Koes Plus di sampul buku PKK-nya. Ia telah menerapkan belah tengah seminggu sebelumnya dan tak sedikit pun nilai tambah pada wajahnya. Tapi karena Arai memang diberkahi dengan bakat menghasut, maka aku termakan juga (Hirata,2009:34).
Namun karena ide Arai itu, Ikal malah mendapat ejekan dari orang-orang yang menertawakan penampilannya, sehingga Ikal malu untuk keluar rumah. Arai menuntun Ikal melewati ruang tengah rumah menuju ke luar rumah:
(38) Arai menggengam tanganku erat-erat dan menuntunku gagah berani melewati ruang tengah rumah. Dalam dukungan Arai, aku tak sedikit pun gentar menghadapi badai cemoohan. Papan-papan panjang lantai rumah berderak-derak ketika kami berdua melangkah penuh gaya (Hirata,2009:35).
Suatu hari, Arai prihatin dan sedih melihat kondisi Mak Cik Maryamah dan anaknya yang tengah menenteng setengah karung beras. Beras itu adalah pemberian dari ibu Ikal, sekaligus Ibu angkat Arai:
Kulihat ketidakpuasan, ada juga keliatan kemarahan. Lebih dari itu, kulihat sebuah rencana yang aneh. Instingku mengabari bahwa sesuatu yang dramatis pasti sedang berkecamuk dalam kepala manusia nyentrik ini (Hirata,2009:40).
Arai mengajak Ikal ke gudang peregasan, disanalah Arai dan Ikal menyimpan uang tabungan hasil jerih payahnya berkerja. Arai mengajak Ikal memecahkan celengannya, seperti yang terlihat pada kutipan berikut:
(40) Benar saja, tiba-tiba Arai membanting telpon kaleng botan dan menyeretku ke gudang peregasan. Aku terbengong-bengong melihat tingkah Arai. Ibuku sibuk menggulung kabel telepon yang kami campakkan. Aku semakin tak mengerti waktu Arai bergegas membuka tutup peregasan, mengambil celengan ayam jagonya, dan tanpa ragu menghempaskannya. Uang logam berserakan di lantai. Napasnya memburu dan matanya nanar menatapku saat ia mengumpulkan uang koin. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun dan pada detik itu aku langsung terperangkap dalam undangan ganjil sorot matanya. Seperti tersihir aku tergoda pada berbagai kemungkinan yang ditawarkan kelakuan sintingnya. Tanpa piker panjang aku menjangkau celenganku di dasar peregasan dan melemparnya ke dinding (Hirata,2009:41).
(41) Aku tak tahu apa yang telah merasukiku. Aku juga tak tahu secuil pun rencana Arai. Yang kutahu adalah Allah telah menghadiahkan karisma yang begitu kuat pada sang Simpai Keramat ini, mungkin sebagai kompensasi kepedihan masa kecilnya. Hanya dengan menatap, ia mampu menguasaiku. Atau mungkin juga aku bertindak tolol karena persekongkolan kami sudah mendarah daging (Hirata,2009:41).
(42) Tetapi seperti biasannya, Arai selalu meyakinkan, lihatlah ekspresi dan gayanya berjalan. Aku terhipnotis oleh kekuatan kepercayaan dirinya. Aku seperti kerbau di cucuk hidung, di giring ke penjagalan pun manut saja. Bahkan hanya untuk sekedar bertannya mulutku terlanjur kelu (Hirata,2009:43).
(43) “Nyah…,” seru Arai pada Nyonya Deborah. Santun dan berwibawa, seolah ia akan memborong seluruh isi toko dengan koin-koin itu. “terigu 10 kilo,
gandum 10 kilo, gula….” Aku terkejut tak kepalang. “Rai! Apa-apaan ini?!”
“Untuk apa segala terigu….” Tangkas, Arai menekan jarinya di atas mulutku.
“Sssttt!! Diam Kal, ” (Andrea Hirata,2009:44-45)
(44) Nyah, jangan lupa minyak….,” “Arai, kita memerlukan tabungan itu.” “Aku
tak punya banyak waktu, Kal…” “Nanti ku jelaskan. Ikut saja rencanaku,
percayalah….” Aku menatap mata Arai dalam-dalam. Dia memang aneh tapi
aku tahu tak ada bibit culas dalam dirinya (Hirata,2009:50).
Setelah selesai membeli tepung, gula, dan minyak, Arai bergegas menuju rumah Mak Cik Maryamah. Sesampainnya di sana Arai langsung menyerahkan barang belanjaannya kepada Mak Cik Maryamah:
(45) Aku masih tak mengerti apa maksud Arai waktu ia memasuki pekarangan rumah Mak Cik Maryamah. Kami masuk kedalam rumah yang senyap. Dari dalam kamar, sayup terdengar Nurmi sedang mengesek biola. Arai menyerahkan karung-karung tadi pada Mak cik. Beliau terkaget-kaget. Lalu aku tertegun mendengar rencana Arai: dengan bahan-bahan itu dimintannya Mak Cik membuat kue dan kami yang akan menjualnya. “Mulai sekarang, Mak Cik akan punya penghasilan!” seru Arai bersemangat. Mata Mak Cik berkaca-kaca. Seribu terimakasih seolah tak‟kan cukup baginnya (Hirata,2009:51). sering dipraktikan Arai adalah mengucapkan amin dengan sangat tidak
Setiap mengakhiri sesi belajar-mengajar, Pak Balia sesalu meminta muridnya mengucapkan motto sebagai penyemangat agar kelak dapat meniru dan menghayati tiap kata-kata yang mereka ambil dari motto tersebut. Arai selalu antusias, demi mendapat perhatian dan cinta Nurmala, Arai selalu berusaha dengan cara apa pun:
(47) Tiba-tiba tanpa di minta Pak Balia, Arai melompat bangkit, melolong keras sekali, “Tak semua yang dapat di hitung, diperhitungkan, dan tak semua yang diperhitungkan, dapat dihitung!! Albert Einstein! Fisikawan nomor wahid!” Tinggi, runyam, membinggungkan. Matanya melirik-lirik Nurmala. Pak Balia terpana dan berkerut keningnya, tapi memang sudah sifat alamiah beliau menghargai siswanya. “Cerdas sekali Anak Muda, cerdas sekali….” Aku tahu taktik tengik Arai. Ia menggunakan kata-kata langit hanya untuk membuat Nurmala terkesan. Kembang SMA Bukan Main itu telah ditaksirnya habis-habisan sejak melihatnya pertama kali waktu pendaftaran (Hirata,2009:76).
(48) Sejak pertama kali melihatnya waktu pendaftaran di SMA Arai telah jatuh hati pada Nurmala. Cinta pada pandangan pertama. Dan sejak itu ia telah mengirim kembang SMA kami itu berates-ratus kali salam. Tak satu pun ditanggapi (Hirata,2009:187).
(49) Tak terhitung syair gurindam, lirik-lirik tembang semenanjung, bahkan bunga, mulai dari bunga meranti yang amat langka, hanya bersemi tujuh tahun sekali dan harus dipetik di dalam rimba pada ketinggian sehingga seluruh tepian Pulau belitong kelihatan, sampai bunga halus muralis yang rajin tumbuh di gunung kotoran kerbau, semuanya telah Arai coba. Bunga itu diam-diam ia letakan di keranjang sepeda Nurmala beserta sepucuk surat (Hirata,2009:187).
(50) Bukan Arai namanya kalau gampang menyerah. Padahal gitaris professional sekalipun belum tentu membawakan “When I Fall In Love” dengan baik, apalagi sambil menyanyikannya (Hirata,2009:200).
(51) Jari Arai melepuh karena tak bisa memencet senar gitar. Dua minggu pertama ia masih belum bisa memperdengarkan satu pun kunci nada dengan benar tapi tak sedikit pun surut semangatnya (Hirata,2009:201).
Sebagai seorang Anak SMA yang baru beranjak dewasa, rasa ingin tahu selalu ada pada diri Arai. Ia pernah memberikan saran kepada Ikal dan Jimbron untuk menerobos masuk kedalam Bioskop yang akan menayangkan film porno:
(53) Bioskop itu hanya memiliki satu akses, yaitu pintu masuknya. Pak Cik dan A Kiun adalah palang pintunya dan keduannya gagal kami dekati. Kami memutar otak dengan keras. Arai punya rencana gila. “Tengah malam kita bongkar atapnya, masuk, dan dan sembunyi dalam bioskop sampai diputar
film besok malam” (Hirata,2009:102).
Namun malang nasip Arai, Ikal, dan Jimbron, mereka kedapatan Pak Mustar menyelinap masuk ke dalam bioskop. Arailah orang yang paling menyesal atas kejadian itu:
(54) “Menonton bioskop mengandung resiko seperti menelan buah khuldi,
hukumannya diusir. Arai tegang wajahnya. Jelas sekali gurat penyesalan yang dalam. Dan aku tahu, seperti pikiranku, dari tadi dia hanya memikirkan ayahku. “Hanya karena dua di antaranya penghuni garda depan dan sudah kelas tiga, maka kalian tidak kudepak dari SMA ini, paham?!!” (Hirata ,2009:118-119).
Karena kedapatan menonton film di bioskop Arai dan kedua orang temannya mendapatkan hukuman dari Pak Mustar, mereka disuruh meniru semua adegan seperti yang terdapat dalam film yang mereka tonton. Arai disuruh menjadi anjing pudel yang menyalak-nyalak:
(55) Arai menyalak-nyalak, “Affhhh!! Affh!! Afffhh!! Afffhh” Wajah Arai yang jenaka, model rambutnya, suaranya yang kering sangat mirip dengan anjing pudel. Peran sebagai anjing sangat pas untuknya (Hirata,2009:122).