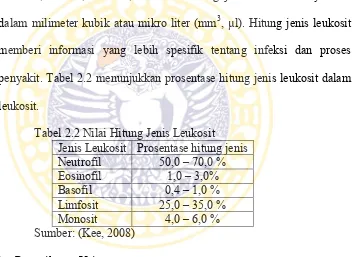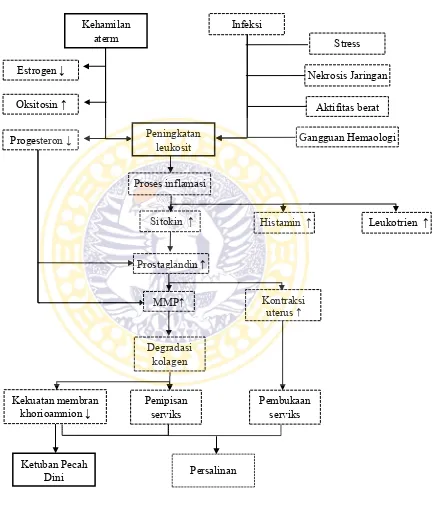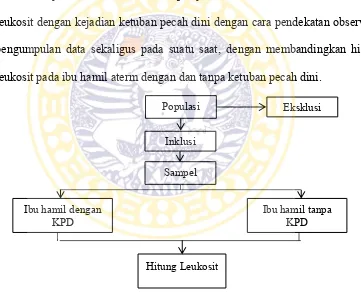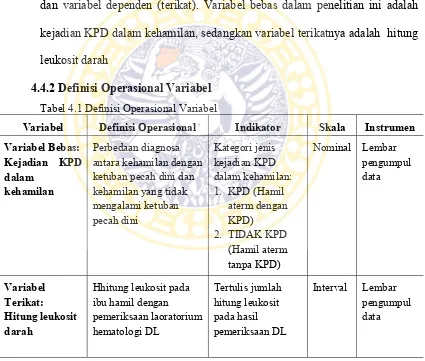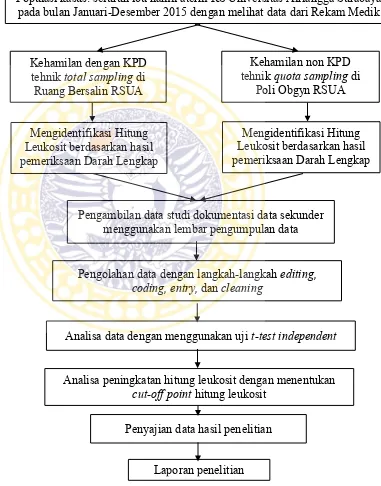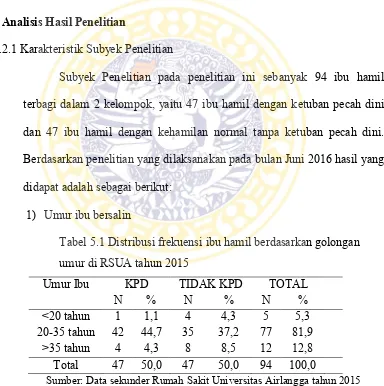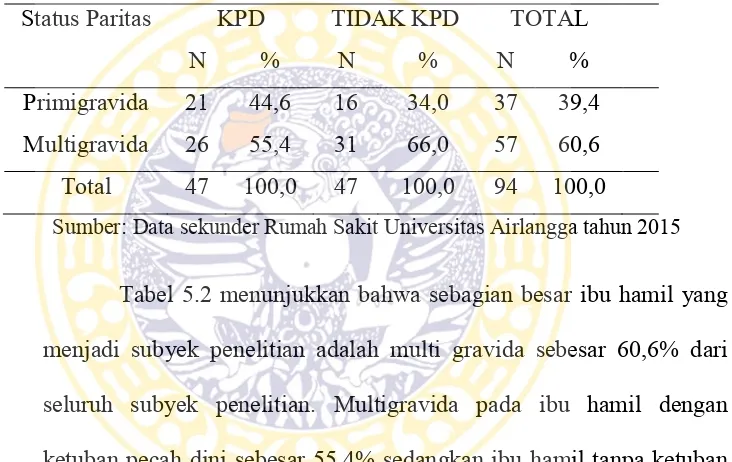SKRIPSI
HITUNG LEUKOSIT PADA KETUBAN PECAH DINI
SEBAGAI INDIKATOR INFLAMASI
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2015
Oleh: Iqsyadina Fikriya
011411223004
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SKRIPSI
HITUNG LEUKOSIT PADA KETUBAN PECAH DINI
SEBAGAI INDIKATOR INFLAMASI
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2015
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kebidanan Dalam Program Studi Pendidikan Bidan Pada Fakultas Kedokteran Unair
Oleh: Iqsyadina Fikriya
011411223004
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SKRIPSI
HITUNG LEUKOSIT PADA KETUBAN PECAH DINI
SEBAGAI INDIKATOR INFLAMASI
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2015
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kebidanan Dalam Program Studi Pendidikan Bidan Pada Fakultas Kedokteran Unair
Oleh: Iqsyadina Fikriya
011411223004
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI
Skripsi dengan judul “Hitung Leukosit pada Ketuban Pecah Dini sebagai Indiktor Inflamasi
di Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun 2015”
Telah diuji tanggal : 2 Agustus 2016
Panitia penguji Skripsi :
Ketua : Eighty Mardiyan Kurniawati, dr., Sp.OG (K)
NIP. 19770814 200501 2 001
Anggota Penguji : 1. Dr. Pudji Lestari, dr., M. Kes NIP. 19700129 199702 2 002
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi dengan judul “Hitung Leukosit pada Ketuban Pecah Dini sebagai Indiktor Inflamasi
di Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun 2015”
Telah diuji tanggal : 2 Agustus 2016
Panitia penguji Skripsi :
Ketua : Eighty Mardiyan Kurniawati, dr., Sp.OG (K)
NIP. 19770814 200501 2 001
Anggota Penguji : 1. Dr. Pudji Lestari, dr., M. Kes NIP. 19700129 199702 2 002
MOTTO
Whoever submit his/her whole self to Allah while he/she is a doer of good- then he/she has
grasped indeed the most trustworthy hand-hold (buhul); And to Allah return all matters for
decision.
Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat
kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) yang kukuh. Hanya
kepada Allah kesudahan segala urusan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat
dan hidayah serta bimbingan-Nya dapat diselesaikannya skripsi dengan judul
“Hitung Leukosit pada Ketuban Pecah Dini sebagai Indikator Inflamasi di Rumah
Sakit Universitas Airlangga Tahun 2015”
Bersama ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya dengan hati yang tulus kepada :
1. Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan
fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
program studi pendidikan bidan.
2. Baksono Winardi, dr., Sp .OG (K) selaku Koordinator Program Studi
Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah
memberikan kesempatan dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan
program studi pendidikan bidan.
3. Ashon Sa’adi, dr., Sp. OG (K) selaku dosen pembimbing I penelitian skripsi
yang telah memberikan bimbingan dan sarannya selama proses pengerjaan
skripsi ini.
4. Dr. Pudji Lestari, dr., M. Kes. selaku dosen pembimbing II penelitian skripsi
yang telah memberikan bimbingan dan sarannya selama proses pengerjaan
skripsi ini.
5. Eighty Mardiyan Kurniawati, dr., Sp.OG (K) selaku dosen penguji yang telah
6. Ketua Komite Etik Rumah Sakit Universitas Airlangga yang telah
menyatakan penelitian ini layak etik
7. Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya yang telah
memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
8. Koordinator serta staf Rekam Medik Rumah Sakit Universitas Airlangga
yang telah membantu dalam pelaksanaan pengambilan sampel penelitian.
9. Dosen serta staf sekretariat Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas
kedokteran Universitas Airlangga yang telah banyak membantu.
10. Bapak Drs. Abd. Syakur, Ibu Binti Mubaiyah, Iqsyahiro Kresna Arsela,
M. Iqsyarifal Fakhri dan segenap keluarga serta calon keluarga yang selalu
memberikan dukungan, semangat dan material dalam proses pengerjaan
penelitian.
11. Teman-teman Program Studi Pendidikan Bidan Alih Jenis dan Reguler yang
juga memberikan semangat, bantuan serta teman berdiskusi.
Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi
kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya
menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Surabaya, Juli 2016
RINGKASAN
Ketuban Pecah Dini (KPD) yang dikenal dengan istilah Premature Rupture of Membrane (PROM) merupakan salah satu komplikasi kehamilan yaitu pecah selaput ketuban secara spontan sebelum awitan persalinan. Sejak akhir kehamilan terjadi aliran sel-sel imunologis ke dalam miometrium sehingga memicu proses inflamasi. Efek ini terjadi akibat dari toleransi ibu terhadap antigen jaringan asing dari janin yang bersifat semialogenik. Mediator proinflamsi menyebabkan terjadinya reaksi peradangan dengan perantara leukosit. Leukosit yang tinggi dapat mengaibatkan serangkaian proses biokimia yang dapat mengakibatkan degradasi kolagen sehingga menurunkan kekuatan selaput ketuban. Pada pemeriksaan rutin, hitung leukosit dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk skrining pada ibu hamil trimester ketiga kaitannya dengan akibat yang timbul karena proses inflamasi yang secara fisiologis terjadi pada akhir kehamilan. Leukosit berperan dalam pengaktifan sitokin yang menyebabkan rangsangan produksi hormon prostaglandin dan matriks metalloproteinase (MMP) dan merangsang kontraksi. Peningkatan MMP dapat menyebabkan peningkatan degenarasi kolagen khorioamnion yang berakibat pecahnya selaput ketuban dan struktur serviks yang berakibat terjadinya KPD
Masalah. KPD merupakan salah satu komplikasi kehamilan dan persalinan yang memerlukan perhatian, karena prevalensinya yang cukup besar. Sekitar 10% perempuan hamil akan mengalami KPD. Di Indonesia, KPD terjadi pada sekitar 6,46-15,6% pada kehamilan aterm. Ketuban pecah dini berkaitan erat dengan peningkatan kadar leukosit kaitannya dalam proses inflamasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan jumlah hitung leukosit melalui hasil pemeriksaan DL pada ibu hamil dengan dan tanpa KPD serta menunjukkan titik potong optimalpeningkatan hitung leukositpada ibu hamil dengan KPD
Metode.dilakukan penelitian observasional potong lintang yang bersifat komparatif dengan pemilihan sampel total pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini selama tahun 2015 di RS Unair. Hitung leukosit dianalisis dengan uji t tidak berpasangan kemudian dilanjutkan dengan uji sensitifitas dan uji spesifisitas. Hasil. Didapatkan hasil bahwa rerata hitung leukosit pada kelompok ibu hamil dengan KPD (rerata 13,19. 103 /µl, SB 3,87) lebih tinggi bermakna dibandingkan dengan kelompok ibu hamil tidak-KPD (rerata 8,30 . 103 /µl, SB
1,45) serta hitung leukosit dengan cut-off point ≥ 9,53 . 103 /µl memiliki
sensitifitas 76,6%, spesifisitas 76,6% dengan ROC 0,88.
Kesimpulan. rerata hitung leukosit pada kelompok ibu hamil dengan KPD lebih tinggi bermakna dibandingkan dengan kelompok ibu hamil tidak-KPD . Hitung leukosit dengan cutt-off point ≥ 9,53 . 103 /µl dapat membedakan
peningktan hitung leukosit pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini dan tidak ketuban pecah dini dengan sensitifitas dan spesifisitas tertinggi (sensitifitas 76,6%, spesifisitas 76,6% dengan ROC 0,88)
ABSTRACT
Background : Premature Rupture of Membrane (PROM) is a complication of pregnancy that spontaneous rupture of the membranes before the onset of labor. PROM is one of the complications of pregnancy and childbirth that require attention, because the prevalence is sizable. Approximately 10% of pregnant women will experience KPD. In Indonesia, KPD occurred at about 6.46 to 15.6% in term pregnancies. Premature rupture of membranes is closely related to increased levels of leukocytes relation to the inflammatory process. Objectives : the objective of this study is to analyze the the difference of Descriptive analysis and bivariate analysis using Independent T-test was done on some specific variables. The limit of significances was p <0.05 with 95% confidence interval. This research analyze the cuf-off point of leukocytes count with the best sensitivity, specificity.
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL DEPAN
SAMPUL DALAM ... i
PRASYARAT GELAR ... ii
SURAT PERNYATAAN... iii
LEMBAR PERSETUJUAN ... iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ... v
LEMBAR PENGESAHAN ... vi
DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG ... xvii
BAB 1 PENDAHULUAN
2.1.3 Pemeriksaan Laboratorium Leukosit ... 8
2.1.4 Masalah Klinis Hasil Penghitungan Leukosit ... 10
2.2 Konsep Kehamilan dengan Ketuban Pecah Dini ... 12
2.3 Peningkatan Leukosit dalam Kehamilan dan Ketuban Pecah Dini 19 2.3.1 Mekanisme Inflamasi dalam Kehamilan ... 19
2.3.2 Perubahan Sistem Hematologi dan Urinaria ... 20
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
4.8.2 Confidentiality (Kerahasiaan) ... 35
4.9 Keterbatasan ... 35
BAB 5 HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 5.1 Hasil Penelitian ... 36
5.2 Analisis Hasil Penelitian ... 37
BAB 6 PEMBAHASAN 6.1 Pembahasan ... 44
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan ... 51
7.2 Saran... ... 51
DAFTAR PUSTAKA ... 53
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Data Normal Nilai Hitung Leukosit ... 9
Tabel 2.2 Nilai Hitung Jenis Leukosit ... 9
Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel ... 29
Tabel 5.1 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan golongan umur ... 37
Tabel 5.2 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan status paritas ... 38
Tabel 5.3 Perbandingan rerata hitung leukosit pada ibu hamil dengan ketuaban pecah dini dan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini ... 39
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Lokasi Potensial Infeksi Bakteri ke dalam Uterus ... 15
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian ... 24
Gambar 4.1 Rancangan Penelitian ... 26
Gambar 4.2 Kerangka Operasional ... 34
Gambar 5.1 Receiver Operating Characteristik Curve ... 40
Gambar 5.2 Kurva sensitifitas dan spesifisitas hitung leukosit ... 40
Gambar 5.3 Diagram peningkatan hitung leukosit di RSUA tahun 2015... 42
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Mahasiswa Prodi Pendidikan Bidan
FK UNAIR Tahun Ajaran 2015/2016 ... 56
Lampiran 2 Berita Acara Perbaikan ... 57
Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Penelitian. ... 61
Lampiran 4 Surat Jawaban Permohonan Ijin Penelitian di RSUA ... 62
Lampiran 5 Surat Keterangan Lolos Kaji Etik RSUA ... 63
Lampiran 6 Lembar Pengolahan Data Penelitian ... 64
Lampiran 7 Pengujian Statistik dengan SPSS ... ... 71
DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG
MMP : Matriks Metalloproteinase P : Probabilitas
PG : Prostaglandin PGE2 : Prostaglandin E2
PGF2α : Prostaglandin F2α
POGI : Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia pPROM : Preterm Prematur Rupture of Membran
PROM : Prematur Rupture of Membran
ROC : Receiver Operating Charakteristik
RS : Rumah Sakit
RSUA : Rumah Sakit Universitas Airlangga
SDKI : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDP : Sel darah Putih
TIMP : Tissue Inhibitor of Metalloproteinases
VCAM : Vascular Cell Adhesion Molecule
WBC : White Blood Cell
WHO : World Health Organization
Daftar Lambang
% : persentase
/ : per
µl : mikro liter
≥ : lebih atau sama dengan dari < : kurang dari
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ketuban pecah dini (KPD) merupakan salah satu komplikasi
kehamilan dan persalinan yang memerlukan perhatian, karena
prevalensinya yang cukup besar. Sekitar 10% perempuan hamil akan
mengalami KPD (Jazayeri, 2015). Di Indonesia, KPD terjadi pada sekitar
6,46-15,6% pada kehamilan aterm (POGI, 2014). Berdasarkan data SDKI
tahun 2012 prevalensi ketuban pecah dini adalah 15% dari jumlah
persalinan. (Badan Pusat Statistik, 2013). Berdasarkan data Dinas
Kesehatan Kota Surabaya tahun 2013 kasus kematian ibu sebanyak 49
kasus akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Rumah Sakit
Universitas Airlangga merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan di kota
Surabaya yang berperan aktif dalam penanganan komplikasi maternal
neonatal dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, termasuk
pemeriksaan hematologi.
Ketuban Pecah Dini yang dikenal dengan istilah Premature
Rupture of Membrane (PROM) merupakan salah satu komplikasi
kehamilan yaitu pecah selaput ketuban secara spontan sebelum awitan
persalinan (Kennedy, 2014). Sejak akhir kehamilan terjadi aliran sel-sel
imunologis ke dalam miometrium sehingga memicu proses inflamasi. Efek
ini terjadi akibat dari toleransi ibu terhadap antigen jaringan asing dari
terjadinya reaksi peradangan dengan perantara leukosit (Cunningham et al,
2014).
Rentang hitung leukosit selama kehamilan secara fisiologis lebih
tinggi bila dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil (Kee, 2008). Di
Korea Selatan penelitian menunjukkan berdasarkan histologis
khorioamnitis semakin rendah usia kehamilan, maka semakin tinggi kadar
serum C-Reactive protein dan leukositnya (Kim, et al., 2016). Leukosit
yang tinggi dapat mengaibatkan serangkaian proses biokimia yang dapat
mengakibatkan degradasi kolagen sehingga menurunkan kekuatan selaput
ketuban. Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan oleh
kontraksi uterus dan peregangan berulang. Kang dan kawan-kawan
meneliti bahwa kepadatan sel selaput ketuban menurun pada ibu dengan
ketuban pecah dini (Kang, et al. 2015).
Pada umumnya hitung leukosit sering digunakan sebagai
indikatator adanya infeksi. Namun dalam pemeriksaan rutin, hitung
leukosit dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk skrining pada ibu
hamil trimester ketiga kaitannya dengan akibat yang timbul karena proses
inflamasi yang secara fisiologis terjadi pada akhir kehamilan. Leukosit
berperan dalam pengaktifan sitokin yang menyebabkan rangsangan
produksi hormon prostaglandin dan matriks metalloproteinase (MMP) dan
merangsang kontraksi.
Menurut penelitian yang dilakukan di China tahun 2015 bahwa
wanita yang mengalami KPD memiliki kadar sitokin lebih tinggi dan
Peningkatan MMP dapat menyebabkan peningkatan degenarasi kolagen
khorioamnion yang berakibat pecahnya selaput ketuban dan struktur
serviks yang berakibat penipisan serviks. Hormon prostaglandin berperan
dalam kontraksi uterus sehingga akan mengakibatkan proses inpartu.
Namun bila pecahnya selaput ketuban tidak diikuti dengan tanda
persalinan maka disebut dengan ketuban pecah dini. Penelitian
sebelumnya tenang ketuban pecah dini dilakukan oleh Lee bahwa
peningkatan hormon prostaglandin dapat menjadi kemungkinan terjadinya
ketuban pecah dini (Lee, et al., 2009).
Berdasarkan penelitian oleh beberapa para ahli ini menunjukkan
bahwa ketuban pecah dini berkaitan erat dengan peningkatan kadar
leukosit kaitannya dalam proses inflamasi. Dengan melihat fenomena
tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan total hitung leukosit
pada darah ibu hamil dengan usia kehamilan yang aterm dengan
pemeriksaan hitung darah lengkap pada kehamilan dengan komplikasi
ketuban pecah dini dibandingkan dengan kehamilan yang tidak mengalami
komplikasi ketuban pecah dini
1.2 RumusanMasalah
“ Adakah perbedaan hitung leukosit darah antara kehamilan aterm
dengan ketuban pecah dini dan kehamilan aterm tanpa ketuban pecah
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Membuktikan adanya perbedaan hitung leukosit dilihat dari
pemeriksaan laboratorium darah lengkap (DL) pada ibu hamil dengan
ketuban pecah dini bila dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak
mengalami ketuban pecah dini.
1.3.2 Tujuan Khusus
1) Menganalisis perbedaan jumlah hitung leukosit melalui hasil pemeriksaan
darah lengkap pada ibu hamil dengan KPD bila dibandingkan dengan ibu
hamil tanpa KPD
2) Menunjukkan titik potong optimal (cut-off point) peningkatan hitung
leukosit pada ibu hamil dengan KPD bila dibandingkan dengan ibu hamil
tanpa KPD
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitiaan ini bermanfaat untuk mengetahui peranan leukosit dan
hubungannya dengan proses inflamasi selama kehamilan dan kejadian
ketuban pecah dini.
1.4.2 Manfaat Praktis
1) Menambah wawasan mahasiswa mengenai proses perubahan
dini dalam kaitannya dengan proses inflamasi selama kehamilan
trimester ketiga.
2) Bagi tenaga medis, dapat dijadikan sebagai informasi tentang
peningkatan leukosit yang dapat beresiko terhadap kejadian ketuban
pecah dini sehingga dapat dijadikan indikator pencegahan kejadian
ketuban pecah dini
3) Bagi pihak rumah sakit, dapat dijadikan bahan evaluasi dalam
memberikan pelayanan optimal, serta meningkatkan mutu pelayanan di
dalam ruang lingkup pelayanan maternal perinatal terkait dengan
BAB 2
KAJIAN PUSTAKA
2.1Konsep Leukosit
2.1.1 Definisi Leukosit
Leukosit atau sel darah putih ( white blood cell, WBC, lekocyte)
merupakan salah satu sel yang membentuk darah. Leukosit merupakan
bagian dari sitem pertahanan tubuh, sel ini memeberikan respon yang
cepat pada benda asing yang masuk dengan cara bergerak ke arah sisi
organ yang mengalami gangguan (Cunningham et al, 2014)
2.1.2 Klasifikasi Leukosit
Leukosit merupakan kelompok dari beberapa jenis sel. Leukosit
dibedakan menjadi: Granulosit (Leukosit granuler/ polimorfonuclear) dan
Agranulosit (Leukosit nongranuler/ mononuclear)
1) Granulosit
Paling banyak terdapat dalam darah, sekitar 75%. Terdapat
butir spesifik yang mengikat zat warna dan sitoplasma.
(1) Sel neutrofil
Jumlahnya paling banyak sekitar 60-70% dari jumlah
seluruh leukosit atau 3000-6000 per mm3 dalam darah normal.
(Subowo, 2009). Neutrofil merupakan garis terdepan pertahanan
tubuh selama infeksi akut karena mempunyai kemampuan
fagositosis. Neutrofil berespon lebih cepat terhadap inflamasi dan
Neutrofil yang belum matang disebut dengan batang dan dapat
bermultiplikasi dengan cepat selama infeksi akut, sedangkan yang
sudah matang disebut segmen (Kee, 2008)
(2) Sel eosinofil
Jumlah sel eosinofil sebanyak 1-3% dari seluruh leukosit
atau 150-450 buah per mm3 darah. Sel eosinofil berkaitan dengan
peristiwa alergi dan sering ditemukan dalam jaringan yang
mengalami reaksi alergi atau radang kronis. Hitung jenis eosinofil
meningkat selama alergi disebabkan oleh parasitik. (Kee, 2008;
Subowo, 2009).
(3) Sel basofil
Jumlah sel basofil sekitar 0,5% sehingga sangat sulit
ditemukan pada sediaan apus. Ukurannya 10-12 µm.
Sitoplasmanya mengandung bahan-bahan diantaranya histamin
yang berperan dalam proses alergi atau anafilaksis (Subowo,
2009). Hitung basofil meningkat pada masa penyembuhan. Pada
peningkatan steroid, hitung basofil akan menurun (Kee, 2008)
2) Agranulosit
(1) Limfosit
Jumlah limfosit sekitar 1000-3000 per mm3 darah atau
20-30% dari seluruh leukosit. Limfosit dapat berperan dalam sistem
imunologik, dikenal dengan nama sel imunokompeten dan
Peningkatan jumlah limfosit (limfositosis) terjadi pada infeksi
krinis dan virus (Kee, 2008).
(2) Monosit
Berjumlah sekitar 3-8% dari seluruh leukosit. Monosit
memiliki diameter terbesar yaitu 12-15µm. Monosit adalah
pertahanan baris kedua terhadap infeksi bakteri dan benda asing.
Sel ini lebih kuat daripada neutrofil dan dapat mengonsumsi
partikel debris yang lebih besar. (Kee, 2008). Monosit mampu
bermigrasi menembus kapiler untuk masuk ke dalam jaringan
pengikat dan monosit berubah menjadi makrofag atau sel-sel lain
yang diklasifikasikan sebagai sel fagositik. Selain berfungsi
sebagai fagositosis sel makrofag dapat berperan menyampaikan
antigen kepada limfosit untuk bekerja sama dalam sistem imun
(Subowo, 2009).
2.1.3 Pemeriksaan Laboratorium Leukosit
Salah satu pemeriksaan yang dapat menunjukkan adanya infeksi dan
inflamasi adalah dengan pemeriksaan darah rutin dan urin rutin, dengan
menghitung jumlah Sel Darah Putih (SDP) atau White Blood Cell (WBC)
(Gomez et al., 2010).
1) Pemeriksaan Darah
Hitung dan hitung jenis leukosit termasuk dalam uji hematologi
atau Hitung Darah Lengkap (Complete Blood Count). Hitung leukosit
cenderung lebih rendah di pagi hari daripada siang hari. Steroid dapat
Tabel 2.1 Data Normal Nilai Hitung leukosit
Sumber: (Kee, 2008; Gomez, 2010)
Hitung jenis leukosit terdiri atas 5 jenis leukosit yaitu neutrofil,
eosinofil, basofil, limfosit, monosit. Hitung jenis leukosit dinyatakan
dalam milimeter kubik atau mikro liter (mm3, µl). Hitung jenis leukosit
memberi informasi yang lebih spesifik tentang infeksi dan proses
penyakit. Tabel 2.2 menunjukkan prosentase hitung jenis leukosit dalam
leukosit.
Tabel 2.2 Nilai Hitung Jenis Leukosit Jenis Leukosit Prosentase hitung jenis
Neutrofil 50,0 – 70,0 %
Jumlah leukosit dalam urin dapat diketahui dengan pemeriksaan
mikroskopik sedimen urin yang merupakan rangkaian dari pemeriksaan
urin atau urinalisis. Adanya leukosit di dalam sedimen urin dapat
ditemukan terdapat dalam urin wanita yang sedang mengalami
jumlah leukosit hanya 0-5 per lapangan penglihatan kecil dan pada
wanita dapat pula karena kontaminasi dari genetalia (Kee, 2008).
2.1.4 Masalah Klinis Hasil Penghitungan Leukosit
Peningkatan leukosit dalam darah disebut dengan leukositosis dan
penurunan leukosit disebut leukopenia (Kee, 2008; Subowo, 2009).
Pada umumnya, leukosit adalah indikator adanya infeksi di dalam
tubuh, sehingga peningkatan kadar leukosit di dalam darah dapat
dijadikan gambaran adanya infeksi (Gomez et al., 2010). Peningkatan
kadar leukosit dapat terjadi secara fisiologis dan patologis.
Kadar leukosit akan meningkat pada keadaan berikut ini:
(1) Infeksi akut
(2) Nekrosis jaringan
(3) Leukemia
(4) Penyakit kolagen
(5) Anemia hemolitik dan sel sabit
(6) Stres (pembedahan/trauma, perdarahan demam, kekacauan
emosional yang berlangsung lama)
(7) Aktifitas fisik berlebihan, kelelahan.
(8) Kehamilan, persalinan dan nifas
(9) Menstruasi
Penurunan kadar leukosit dapat disebabkan oleh beberapa hal
berikut ini
(1) Penyakit hematopoetik
(2) Infeksi virus
(3) Malaria
(4) Agranulositosis
(5) Alkoholisme
(6) Sistem lupus eritematosus
(7) Artritis reumatoid
Terdapat leukosit dalam jumlah banyak di urin desebut piuria.
Keadaan ini sering dijumpai pada kasus infeksi saluran kemih atau
kontaminasi dengan sekret vagina pada penderita dengan flour albus
dan pada ibu KPD dengan tanda-tanda infeksi. Tampilan urin yang
terdapat leukosit biasanya berwarna keruh dan berkabut. Masalah klinis
yang mungkin terjadi adalah infeksi saluran kemih (ISK), demam,
latihan fisik berlebihan, lupus nefritis, penyakit ginjal dan bahkan
tumor. Bila leukosit terdeteksi dalam urin maka harus dilakukan
2.2Konsep Kehamilan dengan Ketuban Pecah Dini
2.2.1 Definisi Kehamilan
Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan
didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum
dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat
fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam
waktu 40 minggu (Saifuddin, 2011).
Status reproduksi merupakan determinan antara yang
menyebabkan terjadinya komplikasi pada maternal maupun perinatal.
Gravida dan umur merupakan bagian dari status reproduksi yang menjadi
determinan antara yang berpengaruh terhadap terjadinya komplikasi ibu
dan anak (Saifuddin, 2009)
1) Umur ibu
Umur atau usia adalah lawan waktu hidup sejak dilahirkan atau
diadakan. Umur ibu merupakan salah satu indikator untuk menentukan
apakah kehamilan ibu dalam faktor resiko kehamilan atau tidak. Umur
yang beresiko untuk melangsungkan kehamilan adalah umur kurang dari
20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Umur sehat untuk reproduksi adalah
umur ibu dari 20 tahun sampai 35 tahun. Umur antara 20-35 tahun
merupakan umur dengan kehamilan dan kelahiran terbaik, artinya di umur
tersebut ibu hamil memiliki risiko yang rendah untuk ibu dan janin
(Affandi,2012).
Kehamilan ibu pada umur kurang dari 20 tahun sangat beresiko
untuk proses kehamilan sehingga dapat menyebabkan terjadinya
komplikasi persalinan yang dapat merugika kesehatan ibu maupun janin
(Manuaba,2012). Umur ibu lebih dari 35 tahun beresiko terhadap
kesehatan ibu dan janin serta pada umur ini kehamilan akan berpotensi
mengalami kegawatdaruratan obstetri atau APGO (Ada Potensi Gawat
Obstetri) (Saifuddin,2009). Kesehatan ibu dengan umur lebih dari 35
tahun tidak seoptimal pada ibu hamil dengan umur 20-35 tahun karena
pada umur lebih dari 35 tahun, kesehatan ibu akan menurun dan mudah
terserang penyakit serta organ reproduksi juga mengalami penuaan
sehingga jalan lahir menjadi kaku dan terjadi perubahan pada jaringan
organ reproduksi dalam (Rochjati, 2011)
2) Status paritas
Penentuan graviditas/paritas yang pertama adalah menggunakan
sistem gravida/para 2-digit, maka gravida menunjukkan berapa kali
seorang wanita pernah hamil. Bila saat ini hamil, kehamilan masuk
hitungan dan menunjukkan jumlah kehamilan yang berakhir dengan
kelahiran janin viabel. Jika seorang wanita hamil kembar, kehamilannya
tetap dihitung sebagai satu kali kehamilan. Jika janil lahir mati namun
sudah melewati usia viabilitas maka hal tersebut masuk hitungan paritas.
Penghitungan paritas klasik menggunakan sistem 4-digit yaitu digi
pertama: jumlah kehamilan cukup bulan yang dilahirkan setelah melewati
usia viabilitas(>37 minggu). Digit kedua: jumlah kelahiran kurang bulan
(<37 minggu). Digit ketiga: jumlah kehamilan yang berakhir dengan
minggu atau BB janin <500gr). Digit keempat: jumlah anak yang saat ini
hidup.
Ada beberapa istilah terkait dalam paritas, antara lain: nulipara adalah
wanita yang belum pernah melahirkan janin viabel, primipara adalah wanita
yang pernah melahirkan satu kali (tanpa mempertimbangkan jumlah janin)
dengan 28 janin viabel, multipara adalah wanita yang perbah melahirkan dua
kali atau lebih (tanpa mempertimbangkan jumlah janin) dengna janin viabel.
Dan grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan sampai lima anak
atau lebih.
2.2.2 Definisi Ketuban Pecah Dini
Ketuban Pecah Dini (KPD) dikenal dengan istilah
Premature/Spontaneus/Early Rupture of Membrane (PROM) adalah pecah
selaput ketuban secara spontan sebelum adanya tanda persalinan atau
dimulainya tanda inpartu pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu
(Kemenkes RI, 2013; Kennedy, 2014; Jazayeri, 2015).
KPD adalah pecahnya ketuban sebelum inpartu, yaitu bila
pembukaan pada primi kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5
cm (Mochtar, 2012). Ketuban yang pecah sebelum terdapat tanda
persalinan, dan setelah ditunggu 1 jam belum ada tanda-tanda persalinan
(Manuaba, 2010).
2.2.3 Etiologi Ketuban Pecah Dini
Pada dasarnya mekanisme yang mengawali ketuban pecah dini
belum diketahui secara pasti, ketuban pecah dini merupakan sindroma
Ketuban pecah dini memiliki hubugan dengan hal-hal berikut :
(1) Hipermortilitas rahim yang telah lama terjadi sebelum ketuban pecah,
biasanya karena penyakit seperti pielonefritis, sistitis, servisitis, dan
vaginitis
(2) Kelainan selaput ketuban (selaput ketuban terlalu tipis)
(3) Solusio plasenta
(4) Kekurangan tembaga dan asam askorbik sebagai komponen kolagen
yang berakibat pertumbuhan struktur abnormal
(5) Infeksi (amnionotis atau khorioamnitis)
(6) Ketuban pecah dini afrisial, dimana dilakukan amniotomi terlalu dini
( Saifuddin, 2011; Jazayeri, 2015)
Gambar 2.1 Lokasi potensial infeksi bakteri ke dalam uterus Sumber: (Jazayer, 2015)
Faktor predisposisi lain yang mempengaruhi seperti:
(1) Multipara
(2) Malposisi (letak sungsang, letak lintang)
(3) Disproporsi sefalopelvik, kesempitan panggul,
(4) Servik inkompeten
2.2.4 Patofisiologi Ketuban Pecah Dini
Secara fisiologis, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan
secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus, peregangan berulang dan
pada daerah tertentu mengalami perubahan biokimia yang menyebabkan
selaput ketuban inferior rapuh. Melemahnya kekuatan selaput ketuban ada
hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim dan gerakan
janin. Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda, ketuban pecah
dini pada kehamilan prematur disebabkan oleh adanya faktor-faktor
eksternal, misalnya infeksi yang menjalar dari vagina (Saifuddin, 2011).
Menurut Manuaba (2010) mekanisme KPD adalah bila selaput
ketuban tidak lagi kuat karena kurangnya jaringan ikat dan vaskularisasi,
dan bila terjadi pembukaan serviks maka selaput ketuban bertambah lemah
dan mudah pecah. Pada kehamilan aterm, perubahan yang terjadi secara
fisiologis dan pengaruh dari kontraksi seringkali menyebabkan
melemahnya kekuatan selaput ketuban sehingga terjadi ketuban pecah dini
(Kennedy, 2014).
Pecanya selaput ketuban berhubungan dengan perubahan proses
biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstra selular amnion,
korion, dan apoptosis membran janin. Perubahan struktur, jumlah, dan
katabolisme kolagen mengakibatkan aktivitas kolagen berubah sehingga
selaput ketuban pecah. Membran janin dan desidua bereaksi terhadap
mediator seperti prostaglandin, sitokin, dan protein hormon yang
merangsang aktivitas “matrix degrading enzym” (Saifuddin, 2011).
Degradasi kolagen dimediasi oleh Matriks Metaloproteinase
(MMP) yang dihambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor
protase. Mendekati waktu persalinan keseimbangan antara MMP dan
TIMP-1 mengarah pada degradasi proteolitik dari matriks ekstraselular
dan membran janin. Aktivitas degradasi proteolitik ini meningkat
menjelang persalinan. Pada penyakit periodontitis dimana terdapat
peningkatan MMP, cenderung terjadi ketuban pecah dini (Saifuddin,
2011). Ketuban pecah dini berpengaruh terhadap kehamilan dan
persalinan. Periode laten atau lag period (LP) adalah jarak antara pecahnya
ketuban dengan permulaan persalinan. Periode laten akan semakin
memanjang pada usia kehamilan yang semakin muda. Sedangkan lamanya
persalinan akan lebih pendek dalam keadaan usia kehamilan yang semakin
muda (Mochtar, 2012)
2.2.5 Pengaruh Ketuban Pecah Dini
Resiko pada ibu dan janin akibat KPD meningkat seiring dengan
durasi atau lamanya waktu sebelum persalinan dan frekuensi periksa
dalam (Kennedy, 2014). Semakin lama periode laten maka semakin besar
resiko morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Komplikasi yang timbul
akibat ketuban pecah dini bergantung pada usia gestasinya. Dapat terjadi
infeksi maternal maupun neonatal persalinan prematur, hipoksia karena
kompresi tali pusat, deformitas janin, meningkatkan insiden seksio
Terbukanya jalan lahir akibat KPD dapat menyebabkan infeksi
ascendens, selain itu juga dapa dijumpai infeksi puerperalis, peritonitis,
septikemia, serta dry-labour (Mochtar, 2012) Resiko terhadap neonatal
dapat berupa
(1) Infeksi neonatus
(2) Placental abrupton
(3) Gawat janin
(4) Fetal restriction deformities
(5) Pulmonary hypoplasia
(6) Kematian janin/ neonatus. (Jazayeri, 2015)
Infeksi intrauterin terjadi bahkan sebelum ibu merasakan tanda
gejala infeksi, sehingga hal ini menigkatkan morbiditas dan mortalitas
perinatal (Mochtar, 2012). Risiko infeksi ibu dan anak meningkat pada
ketuban pecah dini. Pada ibu dapat terjadi korioamnitis, pada bayi dapat
terjadi septikemia, pneumonia, omfalitis. Umumnya korioamnitis terjadi
2.3Peningkatan Leukosit dalam Kehamilan dan Ketuban Pecah Dini
2.3.1 Mekanisme Inflamasi dalam Kehamilan
Dalam bukunya, Chunningham (2014) menyatakan bahwa:
“Pregnancy is thought to be associated with suppression of various
humoral and cell-mediated immunological functions to accommodate the
“foreign” semiallogeneic fetal graft. In reality, pregnancy is both a
proinflammatory and antiinflammatory condition, depending upon the
stage of gestation.”
Kalimat tersebut menjelaskan bahwa kehamilan berhubungan
dengan penekanan berbagai hormon dan dan fungsi imunologis karena
respon ibu hamil dalam menampung jaringan semiallogenik yaitu janin.
Kehamilan mencakup 2 kondisi yaitu proinflamatory dan antiinflamatory
bergantung pada tiap tahapan kehamilan. Mor (2011) membagi fase
imunlogis kehamilan menjadi 3 fase.
1) Awal kehamilan berkaitan dengan proses proinflamasi. Selama proses
implantasi dan pembentukan plasenta, blastokis harus menerobos ke
lapisan rongga epitelium rahim untuk menetap di jaringan
endometrium. Tropoblas menggantikan endotelium untuk otot polos
pada pembuluh darah untuk mempertahankan peredaran darah pada
plasenta. Aktifitas ini mengakibatkan perlunya aktifitas inflamasi
dalam regenerasi sel epitelium rahim.
2) Pertengahan kehamilan berkaitan dengan proses antiinflamasi. Selama
3) Akhir kehamilan dan persalian ditandai dengan aliran sel-sel
imunologis ke dalam miometrium sehingga memicu terjadinya proses
inflamasi (Cunningham et al, 2014)
2.3.2 Perubahan Sistem Hematologi dan Urinaria
Perubahan hematologi pada saat kehamilan adalah meningkatnya
volume darah, rata-rata peningkatan darah pada kehamilan aterm adalah
45-50%. Peningkatan terjadi secara fisiologis untuk mengganti aliran
darah ekstra ke uterus, memenuhi kebutuhan metabolisme fetus, dan
meningkatkan perfusi pada organ lain. Ekstra volume darah juga sebagai
persiapan untuk menkompensaasi kehilangan darah dalam persalinan
(Leveno, 2009; Aprillia, 2010)
Jumlah sel darah putih yang lebih dari 15.000/mm3 merupakan
indikasi adanya infeksi pada wanita hamil (Jazayeri, 2015). Peningkatan
kadar leukosit pada wanita hamil sering terjadi karena adanya infeksi
selama kehamilan sebagai respon terhadap agen infeksius (Sutedjo, 2008).
Selain karena infeksi, secara fisologis wanita hamil mengalami
peningkatan leukosit akibat toleransi ibu terhadap antigen jaringan asing
dari janin yang bersifat semialogenik (Cunningham, 2008).
Hitung leukosit cukup bervariasi selama kehamilan hingga
mendekati 15.000 /mm3. Selama persalinan dan awal masa nifas leukosit
meningkat hingga mencapai 25.000 /mm3 atau bahkan lebih sampai
30.000 /mm3. Namun nilai rata-ratanya 14.000 – 16.000 /mm3. Penyebab
persalinan faktor pembekuan darah meningkatkan kadar beberapa
koagulan seperti fibrinogen (Aprillia, 2010; Cunningham et al, 2014).
Selama kehamilan, masing-masing ginjal memanjang1-1,5 cm dan
ureter berdilatasi sampai tepi atas tulang pelvis. Hal ini menyebabkan
meningkatnya kejadian statis urin yang menyebabkan infeksi dan tes
fungsi renal sulit diinterpretasi (Aprillia, 2010). Sedimen leukosit
dianggap normal bila ditemukan 0-5/ daya penglihatan rendah (Kee, 2008)
2.3.3 Peran Leukosit dalam Kehamilan dan Ketuban Pecah Dini
Respon tubuh terhadap patogen melibatkan berbagai komponen
sistem imun dan sitokin, baik yang bersifat pro inflamsi maupun
antiinflamasi. Pada inflamasi atau jaringan yang meradang, prostaglandin
berperan dalam menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan
permeabilitas vaskular. Mediator inflamsi yang dilepas menyebabkan
terjadinya reaksi peradangan dengan perantara leukosit diantaranya
makrofag, netrofil, dan limfosit.
Molekul aktif seperti prostagalandin (PG) terlibat dalam proses
persalinan. Pada persalinan normal Prostaglandin dihasilkan oleh desisua,
dan konsentrasinya meningkat sejak kehamilan 15 minggu. Prostaglandin
akan menyebabkan kontraksi uterus dan memicu persalinan. Sitokin
tertentu seperti interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6) tumor necrosis
factor alpha (TNF-α) menstimulasi sintesa PG dari plasenta dan
khorioamnion. Pada kehamilan normal, mediator pada intraamnion
meningkat secara fisiologis sampai batas ambang terjadi pada titik
Infeksi menyebabkan proses biomekanik pada selaput ketuban
dalam bentuk proteolitik sehingga memudahkan ketuban pecah. Invasi
bakteri ke dalam koriodesidua akan melepaskan produk-produknya,
seperti: endotoksin dan eksotoksin serta mengaktifkan sistem
monosit-makrofag pada maternal yang kemudian melepaskan sejumlah sitokin
seperti TNF-, IL-1, IL-6, dan IL-8. Respon tubuh setelah invasi mikroba
merupakan hasil interaksi kompleks antara microbial signal, leukosit,
mediator humoral dan endotel vaskuler. Sitokin pada reaksi inflamasi
memberi respon. Proses inflamasi akibat agen infeksius ini akan
mecetuskan mediator-mediaor inflamasi seperti histamin, sitokin,
leukotrien, dan prostaglandin.
Selama demam, pirogen endogen (interleukin-1) dilepaskan dari
leukosit dan bekerja langsung pada pusat termoregulator dalam
hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh. Efek ini berhubungan
dengan peningkatan prostaglandin otak (yang bersifat pirogenik). Reaksi
peradangan/ inflamasi ini terjadi dengan perantara sel darah putih untuk
melakukan proses fagositosis pada bakteri. Sitokin, endotoksin dan
eksotoksin menstimulasi biosintesis PGF2-dan PGE2 di desidua atau
amnion dan melepaskannya. Sitokin dapat berfungsi sebagai endokrin,
parakin, autokrin. Sitokin berperan penting dalam mekanisme sistem imun
dalam pertumbuhan plasenta dan pemeliharaan kehamilan. Puncak dari
sintesis ini adalah pelepasan metaloprotease dan unsur-unsur bioaktif
lainnya. Prostaglandin menstimulasi kontraksi uterus meningkatan matriks
degradasi kolagen yang berakibat pada melemahnya membran kolagen
yang dalam hal ini berakibat pada penurunan kekuatan khorioamnion
sampai dengan pecahnya selaput ketuban dan penurunan kolagen pada
serviks merubah jaringan kolagen pada serviks menjadi lebih lunak
BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian
: Diteliti : Tidak diteliti
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian
Gambar 3.1 menjelaskan bahwa peningkatan leukosit dapat terjadi kerana beberapa hal, diantaranya kehamilan, infeksi, stress, nekrosis jaringan, aktifitas berat, dan ganggua sistem hematologi. Peningkatan Leukosit merupakan merupakan hal yang terjadi secara fisiologis dalam proses kehamilan dan persalinan. Peningkatan leukosit mengakibatkan proses inflamasi atau peningkatan suhu tubuh oleh pusat termoregulasi dalam hipotalamus. Masa akhir kehamilan merupakan fase proinflamsi akibat proses biokimia berbagai hormon dan aktivitas rahim yang mengakibatkan meningkatkan produksi sitokin yang merupakan merupakan salah satu mediator inflamasi.
Sitokin diproduksi oleh sel darah putih, proses inflamasi menyebabkan sitokin menstimulasi biosintesis prostaglandin di desidua dan amnion. Prostaglandin menstimulasi kontraksi dan meningkatkan kadar enzim Matriks Metaloprotase (MMP) pada membran khorioamnion. Peningkatan kadar MMP menyebabkan degradasi kolagen meningkat pada membran khorioamnion dan penipisan jaringan serviks. Degradasi kolagen berakibat pada melemahnya kekuatan khorioamnion sampai dengan pecahnya selaput ketuban. Pecahnya selaput ketuban tanpa diikuti dengan tanda gejala persalinan disebut dengan Ketuban Pecah Dini (KPD).
3.2 Hipotesis Penelitian
BAB 4
METODE PENELITIAN
4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang telah dilaksanakan merupakan penelitian
comparatif yang bersifat analitik observasional, yaitu penelitian yang
menjelaskan adanya hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis
(Notoatmodjo, 2010). Peneliti mempelajari dinamika korelasi antara hitung
leukosit dengan kejadian ketuban pecah dini dengan cara pendekatan observasi/
pengumpulan data sekaligus pada suatu saat, dengan membandingkan hitung
leukosit pada ibu hamil aterm dengan dan tanpa ketuban pecah dini.
Gambar 4.1 Rancangan Penelitian Perbedaan Rerata Hitung Leukosit pada Kehamilan Dengan dan Tanpa Ketuban Pecah Dini
Sampel
Ibu hamil tanpa KPD Ibu hamil dengan
KPD
Inklusi
Populasi Eksklusi
4.2 Populasi dan Sampel
4.2.1 Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil dengan usia
kehamilan aterm yang memeriksakan kehamilannya di Rumah Sakit
Universitas Airlangga yang menjalani pemeriksaan laboratorium hematologi
dan tercatat dalam rekam medik mulai dari bulan Januari – Desember 2015.
4.2.2 Sampel
Dalam penilitian ini terdapat 2 kelompok sampel, yaitu ibu hamil
aterm dengan KPD dan ibu hamil aterm TIDAK KPD yang tercatat dalam
rekam medik pada bulan Januari - Desember 2015 yang memenuhi kriteria
inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini.
Kriteria inklusi Ibu Hamil dengan KPD
1) Ibu hamil usia kehamilan aterm usia kehamilan >37 – 42 minggu dengan
diagnosis ketuban pecah dini
2) Menjalani pemeriksaan laboratirium DL
3) Mendapat persetujuan pihak Rumah Sakit untuk dilakukan pengkajian
pada rekam medis pasien
Kriteria inklusi Ibu Hamil TIDAK KPD
1) Ibu hamil usia kehamilan aterm usia kehamilan >37 – 42 minggu
2) Selaput ketuban utuh
3) Menjalani pemeriksaan laboratirium DL
Kriteria eksklusi KPD dan Tidak KPD
1) Terdapat tanda-tanda infeksi
2) Terdapat tanda gejala inpartu
3) Mengalami komplikasi kehamilan lain seperti obesitas, DM, Hipertensi,
PE dan Gemelli
4) Rekam medis yang tidak lengkap
4.2.3 Besar Sampel
Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sesuai
dengan jumlah ibu hamil dengan KPD dan ibu hamil tanpa KPD di Rumah
Sakit Universitas Airlangga yang tercatat dalam rekam medik mulai dari
bulan Januari - Desember 2015 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
Dari seluruh jumlah kehamilan dengan ketuban pecah dini yang dirawat di
Rumah Sakit Universitas Airlangga sebanyak 87 ibu hamil, dan yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebanyak 47 ibu hamil.
Sedangkan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini sebanyak 47 ibu hamil.
4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian ini memakai dua tehnik pengambilan sampel. Kelompok
sampel ibu hamil dengan KPD diambil dengan menggunakan tehnik total
sampling yaitu seluruh ibu hamil dengan KPD yang memenuhi kriteria
eksklusi dan inklusi di RS Universitas Airlangga sedangkan untuk sampel ibu
hamil tanpa KPD akan digunakan tehnik quota sampling, yang jumlah
4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya
pada bulan April-Juni tahun 2016 dengan menganalisi data rekam medis
pasien pada bulan Januari-Desember tahun 2015
4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional,
4.4.1Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas)
dan variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
kejadian KPD dalam kehamilan, sedangkan variabel terikatnya adalah hitung
leukosit darah
4.4.2Definisi Operasional Variabel Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Instrumen
Karakteristik:
Status Paritas Jumlah kehamilan ibu saat ini yang tercatat di rekam medik
4.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
4.5.1Instrumen
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah format lembar pengumpulan data atau lembar rekam medik pasien,
sekunder pasien ibu hamil dengan ketuban pecah dini dan ibu hamil yang
tidak mengalami ketuban pecah dini dengan melihat rekam medik
4.5.2Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Mengumpulkan data yang berisi jumlah ibu hamil yang mengalami
ketuban pecah dini yaitu dengan melihat catatan register pada Ruang
Bersalin di RSUA pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember
tahun 2015
2) Mengumpulkan data yang berisi jumlah ibu hamil yang mengalami
ketuban pecah dini yaitu dengan melihat catatan register pada Poli
Obstetri dan Ginekologi di RSUA pada bulan Januari sampai dengan
bulan Desember tahun 2015
3) Melakukan pengambilan sampel penelitian menggunakan lembar
rekam medis pada di Ruang Rekam Medis dengan dengan
menyesuaikan dengan kriteria inklusi dan menghindari kriteria ekslusi
4) Mengidentifikasi jenis kehamilan berdasarkan komplikasi yang
dialami ibu, yaitu kehamilan dengan ketuban pecah dini dan
kehamilan yang tidak mengalami ketuban pecah dini.
5) Mengumpulkan data dengan menggunakan lembaran pengumpulan
data dan melakukan pengkodean
6) Mengidentifikasi hasil jumlah hitung leukosit berdasarkan
4.6 Pengolahan dan Analisis Data
4.6.1Pengolahan Data
Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Editing yang dilakukan untuk mengoreksi data atau menyunting data
yang diperoleh atau dikumpulkan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa
terhadap kelengkapan dan penyesuaian data yang diperoleh dengan
kebutuhan penelitian.
2) Coding. Setelah data dikoreksi atau disunting, selanjutnya dilakukan
coding, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi
data angka dengan menentukan code yang digunakan, untuk
membedakan masing-masing subyek penelitian. Pengkodean yang
dilakukan adalah membedakan subyek penelitian kelompok KPD
adalah kelompok ibu hamil dengan komplikasi ketuban pecah dini,
sedangkan kelompok TIDAK KPD adalah ibu hamil tanpa ketuban
pecah dini.
3) Entry. Setelah melakukan editing dan coding, data kemudian
dimasukkan ke dalam master tabel sehingga data mudah dijumlah dan
disusun untuk disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
4) Cleaning. Setelah melakukan entry data, data perlu diperiksa kembali
untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode,
4.6.2 Analisis Data
Pada penelitian ini, data penelitian dianalisis dengan metode analitik
observasional untuk melakukan analisis dinamika kolerasi antara fenomena
atau faktor resiko yang dalam hal ini adalah total hitung leukosit pada ibu
hamil aterm dengan faktor efek yaitu kejadian ketuban pecah dini.
1) Analisis Univariat
Digunakan untuk mendiskripsikan karakteristik subyek penelitian
dengan menghitung distribusi dan persentase. Menjelaskan
karakteristik ibu hamil sebagai subyek penelitian meliputi umur ibu,
status paritas, serta lamanya pecah ketuban subyek penelitian baik ibu
hamil dengan KPD maupun ibu hamil TIDAK KPD.
2) Analsis Bivariat
Analisis data menggunakan komparasi yaitu dengan membandingkan
perbedaan dua kelompok sampel. Data penelitian berdistribusi normal.
Uji hipotesis yang digunakan adalah t-test independent karena variabel
bebas berskala nominal (2 nilai yaitu ibu hamil dengan KPD dan ibu
hamil tanpa KPD) dengan variabel tergantung berskala numerik
(hitung leukosit darah). Interval kepercayaan (Confidence Interval)
sebesar 95% dan p (signifikan < 0,05) Analisis ini menggunakan
bantuan SPSS 23. Hasil analisis dilanjut dengan uji sensitifitas dan uji
spesifisitas dengan metode Receiver Operating Characteristik (ROC)
4.7 Kerangka Operasional
Kerangka kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Populasi
Populasi kasus: seluruh ibu hamil aterm RS Universitas Airlangga Surabaya pada bulan Januari-Desember 2015 dengan melihat data dari Rekam Medik
Pengolahan data dengan langkah-langkah editing, coding, entry, dan cleaning
Pengambilan data studi dokumentasi data sekunder menggunakan lembar pengumpulan data Kehamilan dengan KPD
tehnik total sampling di Ruang Bersalin RSUA
Analisa data dengan menggunakan uji t-test independent
Penyajian data hasil penelitian
Analisa peningkatan hitung leukosit dengan menentukan
4.8 Ethical Clearence
Untuk melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan proposal ke bagian
penelitian dan pengembangan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya
untuk pengajuan sidang etik yang diselenggarakan oleh komite etik RS Unair
untuk mendapatkan izin melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin,
penelitan ini menekankan etika penelitian, antara lain:
4.8.1Anonimity (tanpa nama)
Peneliti tidak akan mencantumkan identitas atau nama pasien pada
lembar pengumpul data. Peneliti hanya akan menggunakan kode untuk
mengklasifikasikan subyek penelitian.
4.8.2 Confidentiality (kerahasiaan)
Kerahasiaan informasi klien dijamin oleh peneliti dan tidak akan
disebarluaskan dikalangan umum. Semua informasi yang telah dikumpulkan,
hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.
4.9 Keterbatasan
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu terbatas dari apa yang
tertulis di rekam medik. Sedangkan apa yang tertulis di rekam medik terkadang
tidak lengkap dan tidak cukup mewakili diagnosis serta untuk melengkapi data
BAB 5
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN
5.1Hasil Penelitian
5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian telah dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas
Airlangga (RSUA) atau biasa disebut Rumah Sakit Unair merupakan salah
satu Rumah Sakit pendidikan di Indonesia di wilayah Jawa Timur yang
memajukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Rumah
Sakit Unair telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
sejak tahun 2013 dan merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Kota
Surabaya yang saat ini masih tergolong dalam Rumah Sakit Tipe C.
Rumah Sakit Unair berlokasi di Kampus C Universitas Airlangga
Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Informasi lengkap
mengenai Rumah Sakit Unair dapat diakses melaui website:
rumahsakit.unair.ac.id, nomer telepon 031-5916287 atau melalui email
5.1.2 Subyek Penelitian
Jumlah pasien bersalin pada bulan Januari – Desember tahun 2015
di Rumah Sakit Unair adalah 829 ibu bersalin dengan berbagai diagnosa
baik dengan persalinan normal maupun komplikasi lain, salah satunya
adalah ketuban pecah dini. Ibu hamil yang mengalami ketuban pecah dini
sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Unair adalah 87 ibu hamil dengan
kehamilan <37 minggu, dan 65 ibu hamil mengalami ketuban pecah dini
pada usia kehamilan aterm atau 37 - 42 minggu.
Karena beberapa alasan seperti rekam medis yang tidak lengkap,
tidak dilakukan pemeriksaan darah sebelum masuk fase inpartu dan ibu
mengalami tanda-tanda infeksi, sehingga harus dijadikan ekslusi sebanyak
18 ibu hamil. Besar sampel pada penelitian ini adalah 47 ibu hamil dengan
ketuban pecah dini dan 47 ibu hamil tanpa ketuban pecah dini.
5.2Analisis Hasil Penelitian
5.2.1 Karakteristik Subyek Penelitian
Subyek Penelitian pada penelitian ini sebanyak 94 ibu hamil
terbagi dalam 2 kelompok, yaitu 47 ibu hamil dengan ketuban pecah dini
dan 47 ibu hamil dengan kehamilan normal tanpa ketuban pecah dini.
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juni 2016 hasil yang
didapat adalah sebagai berikut:
1) Umur ibu bersalin
Tabel 5.1 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan golongan umur di RSUA tahun 2015
Umur Ibu KPD TIDAK KPD TOTAL
Tabel 5.1 Menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil
sebagai subyek penelitian berada pada usia reproduksi sehat yaitu
umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 77 ibu hamil atau sebesar 81,9%
dari seluruh subyek penelitian
2) Status Paritas
Tabel 5.2 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan status paritas di RSUA tahun 2015
Sumber: Data sekunder Rumah Sakit Universitas Airlangga tahun 2015
Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang
menjadi subyek penelitian adalah multi gravida sebesar 60,6% dari
seluruh subyek penelitian. Multigravida pada ibu hamil dengan
ketuban pecah dini sebesar 55,4% sedangkan ibu hamil tanpa ketuban
5.2.2 Hasil Analisis Perbandingan Rerata Hitung Leukosit pada Ibu Hamil
Dengan dan Tanpa Ketuban Pecah Dini
Tabel 5.3 Perbandingan rerata hitung leukosit pada ibu hamil dengan
ketuban pecah dini dan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini
Kejadian Ketuban
Pecah Dini N
Rerata ±
Simpangan Baku
Perbedaan Rerata
(IK95%) p
KPD 47 13,19 ( 3,87) 4,89 (3,68 – 6,09) < 0,001
TIDAK KPD 47 8,30 (1,45)
Uji T tidak berpasangan
Hasil analisis pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa rata-rata
jumlah leukosit ibu hamil dengan KPD lebih tinggi dibandingkan
dengan ibu hamil tanpa KPD dengan perbedaan rerata sebesar 4,89.
.103/µl Nilai Interval Kepercayaan(IK) 95% adalah antara 3,68 sampai
6,09. Hasil uji statistik Independent T-test, didapatkan nilai sig 0,000
karena nilai p lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
secara statistik terdapat perbedaan yang bermakna jumlah hitung
leukosit ibu hamil antara ibu hamil dengan ketuban pecah dini dan ibu
Gambar 5.1 Receiver Operating Charakteristik Curve
Gambar 5.1 merupakan kurva Receiver Operating
Charakteristik (ROC) yang menunjukkan bahwa hitung leukosit
memiliki nilai diagnostik yang baik karena kurva jauh dari garis 50%
dan mendekati 100%. Nilai dari Area Under the Curve (AUC) yang
didapat dari metode ROC adalah sebesar 88,2% (95%IK 81,3% -
95,0%), p < 0,001. Secara statistik nilai AUC sebesar 88,2% tergolong
kuat.
Gambar 5.3 Kurva sensitifitas dan spesifisitas hitung leukosit
T
i
Cut off point/ titik potong optimal berdasarkan kurva
sensitifitas dan spesifisitas berada pada titik ke 45. Bernilai ≥
9,53103/µl
Tabel 5.4 Tabel 2 X 2 Hasil Penelitian Diagnostik
Cut-off point
Total ≥ 9,53 < 9,53
Kejadian
KPD KPD TIDAK 36 11 47
KPD 11 36 47
47 47
Tabel 5.4 menunjukkan terdapat 11 ibu hamil KPD yang memiliki
hitung leukosit lebih rendah dari nilai cut-off point, serta terdapat
11 ibu hamil TIDAK KPD yang memiliki hitung leukosit lebih
tinggi dari nilai cut-off point. Jumlah subyek yang memiliki nilai
hitung leukosit diatas maupun dibawah cut-off point berdasarkan
kejadian KPD sehingga dapat diketahui beberapa parameter
diagnostik diantaranya:
Sensitivitas = a : (a+c) = 36 : 47 = 0,76
Spesifisitas = d : (b+d) = 36 : 47 = 0,76
Nilai Sensitivitas dan spesifisitas dari titik potong ≥ 9,53103/µl
Gambar 5.3 Diagram peningkatan rerata hitung leukosit pada KPD
berdasarkan lamanya pecah ketuban di RSUA tahun 2015
Sumber: Data sekunder Rumah Sakit Universitas Airlangga tahun 2015
Diagram pencar di atas menunjukkan pola pencar data dan
garis regresi dari bagian kiri naik ke arah kanan. Hal ini
menunjukkan ada korelasi positif lemah. Sebagian besar hasil
hitung leukosit ibu hamil dengan KPD berada pada nilai di atas
garis cut-off point. 0 5 10 15 20 25
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
lamanya pecah ketuban (menit)
Σ hitung leukosit Linear (Σ hitung leukosit)
TIDAK KPD
Gambar 5.1 Grafik peningkatan rerata hitung leukosit pada KPD
berdasarkan lamanya pecah ketuban di RSUA tahun 2015
Sumber: Data sekunder Rumah Sakit Universitas Airlangga tahun 2015
Hitung leukosit dilihat dari lamanya pecah ketuban ≥ 12
jam lebih tinggi bila dibandingkan dengan kadar leukosit pada ibu
BAB 6
PEMBAHASAN
Menurut hasil penelitian Di Rumah Sakit Unair bulan Januari-Desember
tahun 2015 prevalensi ketuban pecah dini adalah 10,4%, dan 7,8% diantaranya
adalah KPD pada ibu dengan kehamilan aterm. Persentase ini sesuai bila
dibandingkan dengan prevalensi KPD menurut Jazayeri (2015) bahwa 10%
wanita hamil akan mengalami KPD. Berdasarkan data Perkumpulan Obstetri dan
Ginekologi Indonesia (POGI) tahun 2014 KPD terjadi sekitar 6,46-15,6% pada
kehamilan aterm. Hal ini menunjukkan kejadian KPD masih memerlukan
perhatian karena prevalensinya yang cukup besar.
6.1 Karakteristik Subyek Penelitian
Karakteristik subyek penelitian ini meliputi umur, status paritas
dan lamanya pecah ketuban. Ditribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan
golongan umur di RSUA tahun 2015 pada tabel 5.1 menunjukkan secara
umum persebaran berdasarkan usia ibu hamil adalah sama antara
kehamilan dengan ketuban pecah dini dan kehamilan tanpa ketuban pecah
dini yaitu sebagian besar subyek penelitian berada pada umur 20-35 tahun.
Umur ibu hamil tidak secara langsung berpengaruh pada kejadian ketuban
pecah dini. Namun menurut Affandi (2012) dalam usia reproduksi sehat
yaitu umur 20-35 tahun, ibu dan anak memiliki risiko paling rendah untuk
menunjukkan tidak adanya perbedaan disribusi umur pada ibu hamil dengan
dan tanpa ketuban pecah dini.
Menurut kejadian ketuban pecah dini, 55,4% ibu yang mengalami
ketuban pecah dini adalah multigravida, artinya sebagian besar subyek
penelitian memiliki faktor redisposisi terjadinya ketuban pecah dini.
Multigravida merupakan salah satu faktor predisposisi yang
mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini (Mochtar, 2012). Penelitian
yang dilakukan Aisyah (2012) menunjukkan bahwa 80% ibu bersalin
multipara mengalami ketuban pecah dini. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Pawestri (2010) ada hubungan yang sangat rendah antara
paritas dan usia ibu dengan ketuban pecah dini.
6.2 Perbandingan Rerata Hitung Leukosit pada Ibu Hamil Dengan dan
Tanpa Ketuban Pecah Dini
Tabel 5.4 menunjukkan perbandingan rerata hitung leukosit pada ibu
hamil dengan ketuban pecah dini dan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rerata hitung
leukosit yang bermakna antara kelompok ibu hamil dengan ketuban pecah
dini dan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini. Dimana hitung leukosit ibu
hamil dengan ketuban pecah dini lebih tinggi dari pada ibu hamil tanpa
ketuban pecah dini. Hasil penelitian ini sesuai menurut penelitian yang
dilakukan di China tahun 2016 bahwa wanita yang mengalami ketuban pecah
Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Lee bahwa peningkatan hormon prostagandin yang dalam hal
ini di produksi oleh leukosit dapat menjadi kemungkinan terjadinya ketuban
pecah dini (Lee, et al., 2009). Ditinjau dari fase imunologis dalam kehamilan,
tahap akhir kehamilan dan persalinan merupakan fase dimana ibu hamil akan
mengalami kondisi proinflammatory ditandai dengan aliran-aliran sel
imunologis ke dalam miometrium sehingga memicu terjadinya proses
inflamasi yang dapat dilihat salah satunya dengan pemeriksaan leukosit
(Chunninham, et. al., 2014).
Peningkatan jumlah hitung leukosit merupakan salah satu bukti
adanya proses inflamasi dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan sehingga
pemeriksaan terhadap leukosit dijadikan sebagai variabel inflamasi dan
sebagai pemeriksaan penunjang yang penting dilakukan pada ibu hamil baik
dengan ketuban pecah dini maupun ibu hamil dengan kehamilan normal
untuk mendeteksi terjadinya proses inflamasi akibat proses kehamilan
(Kosim, 2009). Hal ini sesuai oleh penelitian yang dilakukan oleh Kang dan
kawan-kawan di Korea Selatan pada tahun 2015 bahwa kepadatan sel selaput
ketuban menurun pada ibu dengan ketuban pecah dini (Kang, et al, 2015)
Dalam kondisi normal, peningkatan jumlah leukosit bermanfaat untuk
meredam infeksi dan mempertahankan homeostasis organ vital, namun
apabila kondisi reaksi yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya
kerusakan jaringan dalam hal ini adalah membran khorionamnion dan dapat
timbul nekrosis (Kosim, 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh