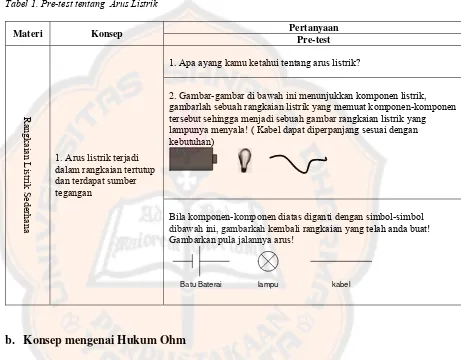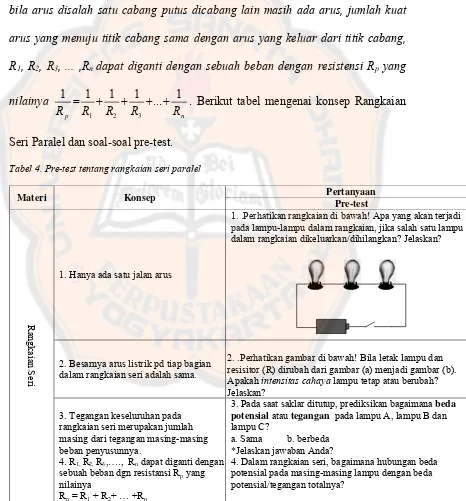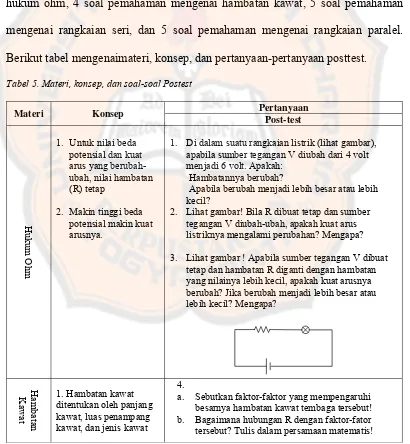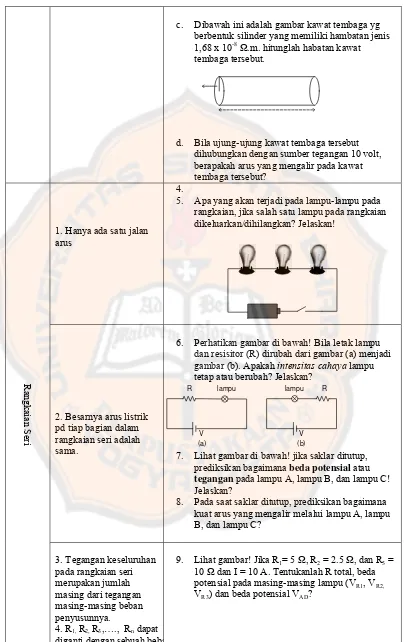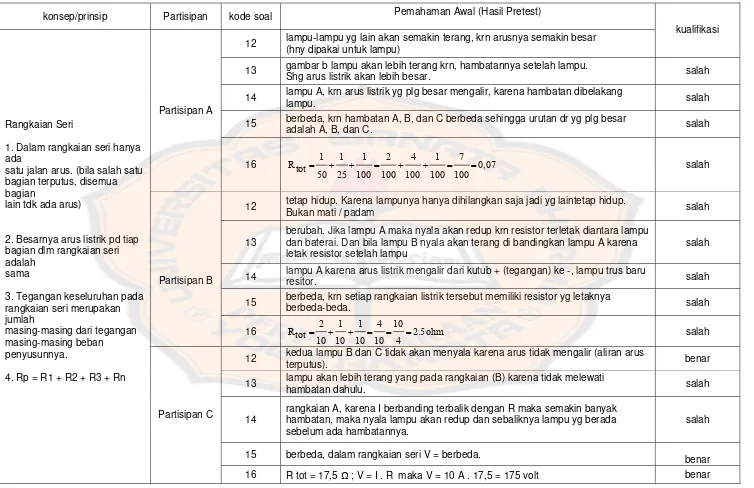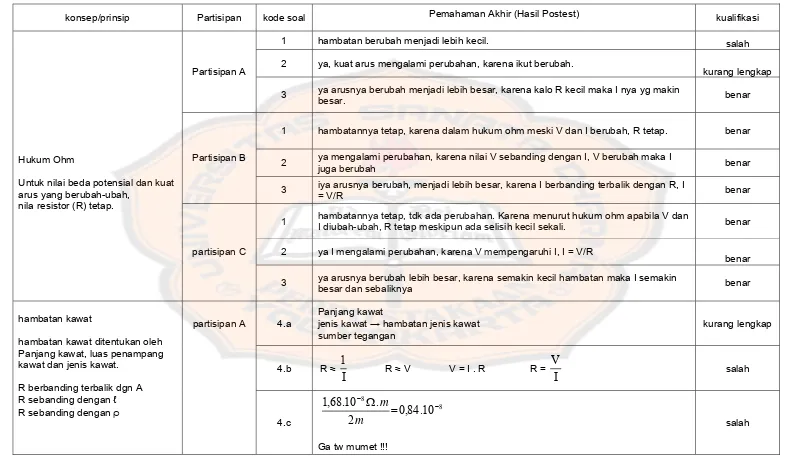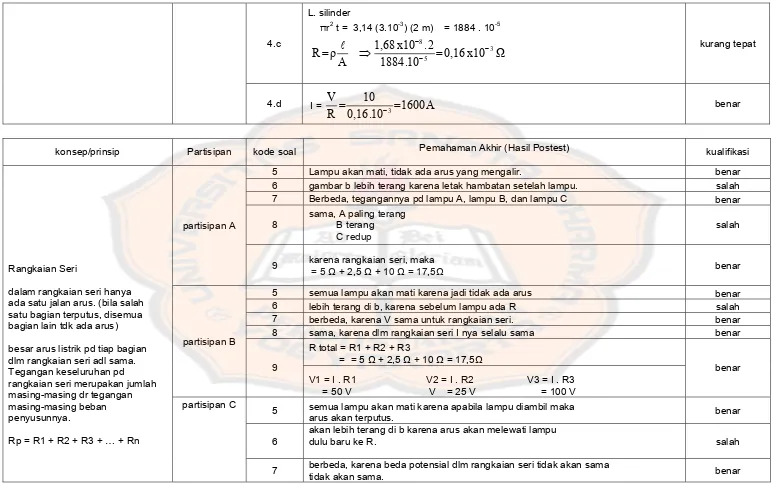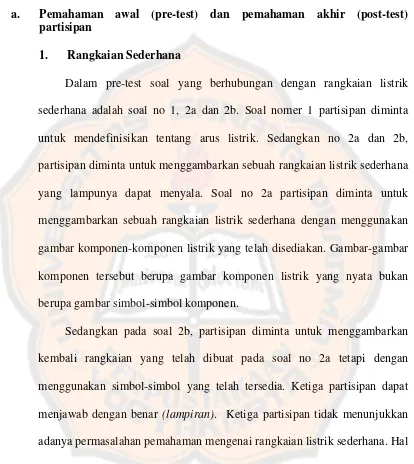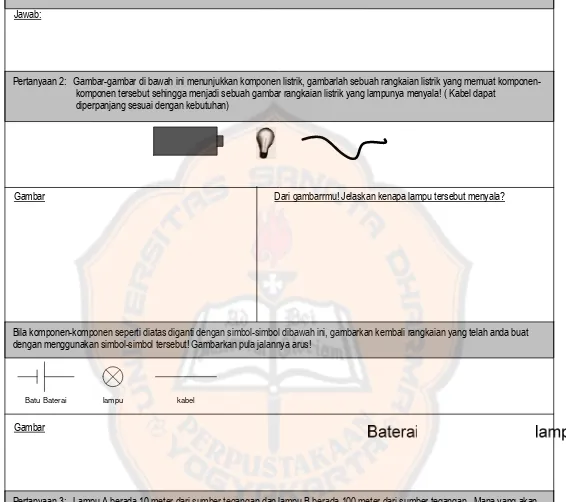Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Eksperimen Terbimbing
(Suatu Studi Kasus Pada Tiga Siswa Kelas X SMA N 2 Bener, Tegalrejo Yogyakarta)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Fisika
Rosa Delima Indriastuti 031424001
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
ii
Pembentukan Konsep Siswa
Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Eksperimen Terbimbing
(Suatu Studi Kasus Pada Tiga Siswa Kelas X SMA N 2 Bener, Tegalrejo Yogyakarta)
Oleh:
Rosa Delima Indriastuti NIM. 031424001
Telah disetujui oleh:
Pembimbing Tanggal………...
iii
Pembentukan Konsep Siswa
Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Eksperimen Terbimbing
(Suatu Studi Kasus Pada Tiga Siswa Kelas X SMA N 2 Bener, Tegalrejo Yogyakarta)
Dipersiapkan dan ditulis oleh: Rosa Delima Indriastuti
NIM. 031424001
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 18 Desember 2007 dan dinyatakan memenuhi syarat
Susunan Panitia Penguji
Nama Lengkap Tanda Tangan
Ketua : Drs. Domi Severinus, M.Si. ... Sekretaris : Dra. Maslichah Asy’ari, M.Pd. ...
Anggota : Drs. Domi Severinus, M.Si. ... Anggota : Drs. FX. Kartika Budi, M.Pd ...
Anggota : Drs. A. Atmadi, M.Si. ...
Yogyakarta, ... Januari 2008 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Dekan,
HALAMAN PERSEMBAHAN
Bila aku dirundung KeCeMaSaN Dengarkanlah suaraku bila aku jatuh
Sudilah menjadi bagiku …
“Penghibur dalam PerjalanaN”
Tempat bernaung diwaktu panas
Tempat berteduh dikala “ H u J a N ”
Tongkat penuntun dalam kelelahan dan penolong dalam “B a H a y A “
(doa para peziarah dalam perjalanan menuju Santiago de Compostela)
Sebagai ungkapan
Syukur
Kupersembahkan karya ini bagi:
Tuhan Yesus Kristus
Bunda Maria
Bapak
&
Ibu ku
yang Terkasih
Suami Tercinta
Heribertus Sugiri
Mas Bayu dan Adikku Oni
v
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.
Yogyakarta, 18 Desember 2007 Penulis,
Rosa Delima Indriastuti. Pembentukan Konsep Siswa Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Eksperimen Terbimbing. Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana konsep awal siswa tentang hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel, (2) Bagaimana perubahan konsep siswa tentang hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel dengan menggunakan metode eksperimen terbimbing , (3) Bagaimana konsep siswa tentang hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel setelah mengalami proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen terbimbing.
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2007 – 27 April 2007 di SMA Negeri 2 Bener, Tegalrejo, Yogyakarta. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-2 yang berjumlah 33 orang. Dari ke 33 siswa dipilih 3 siswa sebagai partisipan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu: pretest, wawancara awal, proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen terbimbing, dan posttest.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ditemukan adanya pemahaman konsep (konsep awal) partisipan yang belum benar mengenai hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel sebelum mengalami proses pembelajaran, (2) Partisipan mengalami perubahan konsep menjadi lebih benar, (3) Setelah mengalami proses pembelajaran, masih ada beberapa pemahaman partisipan mengenai hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel yang belum berhasil diubah.
Misconceptions are a troubling issue for teachers and students in high school science. This is especially true in physics due to its often abstract nature. For example, studying everythings about gases, included Boyle’s Law for gases inside. The purpose of this study was to understand the level of student understanding’s about Boyle’s Law for gases. The understanding developed based on students response to the amount of task relating to Boyle’s Law. The research was also aimed at reveal whether there was misconceptions among students relating to Boyle’s Law. Participants of this study was students of middle class XI science stream state of high school, Sentolo I, Yogyakarta.
This research could be categorized as descriptive qualitative. The instrument employed in this research including problems relating to Boyle’s Law especially and kinetic theory of gas generally for test written importance and than interview. Test written to be used to know level of participant understanding’s. The problems was tried out to a group of students prior to revision in order to discover the extent to which misconception occurred. Interview was employed at participant that probably have misconception see from test written result.
Result of research indicate that as a whole the understanding of participant about Boyle’s Law for gases still less shown by average level of concept insight to reach round 50,84%. It is interesting to note that, for the greater part of participant do not understand the concept of mol, mass and mass of molecules; equation of ideal gases; pressure of a gas in sealed syringe. At this research misconception happened in understand the concept of temperature, volume and mass of a gas in different state of compression; energy kinetic of molecules and rms speed of molecules. Misconceptions often reflect a basic lack of understanding hidden beneath the ability to use equation to solve problems because many of the problems could be solved through memorization of the formulae, rather than through any conceptual understanding of the content.
Puji syukur atas kebesaran kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembentukan Konsep Siswa Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Eksperimen Terbimbing”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dengan jenjang pendidikan strata satu.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak terbantu dengan bimbingan, kesempatan, sarana, fasilitas, dan dukungan spiritual yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bpk Drs. Domi Severinus, M. Si. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan sejak awal penyusunan skripsi, penelitian hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, khususnya Bpk Sunarjo dan Bpk Aloysius Sugeng yang telah mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa JPMIPA Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bpk Drs. Winarso, selaku Guru Mata Pelajaran Fisika Kelas X SMA Negeri I Bener, Tegalrejo atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian terhadap siswa-siswi yang diasuhnya.
4. Bapakku Vincentius Idrus & Ibuku Lucia Sri Lestari, atas doa, dana, nasihat dan dukungan yang tiada henti-hentinya. Terima kasih banyak, ”Maafkan aku telah banyak mengecewakan, aku mencintai dan mengasihimu”.
5. Suamiku terkasih Heribertus Sugiri, engkau telah menemaniku, menguatkanku dan mengisi hari-hariku. Engkau takkan kulupakan dalam
memilihku menjadi ”pendamping hidupmu”, aku mencintaimu dan akan selalu setia padamu.
6. Kakakku Ignatius Bayu Sudibyo dan adikku Emilda Oktaviani atas perhatian, dukungan dan doanya. Tetap semangatttt!!!! Selamat Berjuang! Aku rindu berkumpul, ngobrol dan bernyanyi bersama di dapur kita yang sederhana namun bersih, tenang, damai dan indah sambil diiringi gitar. Kapan lagi ya???
7. Teman-temanku: Mb. Nina, Joe, Lucy, dan semua teman angkatan 2003 atas perjuangan kita bersama di bangku kuliah, melewati hari-hari penuh tantangan, saling memotivasi satu sama lain. Untuk semua itu, meskipun tidak akan pernah terulang, namun tetap akan menjadi kenangan.
Karya ini masih jauh dari sempurna. Menyadari hal itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan sains.
Yogyakarta, Desember 2007
Penulis
JUDUL... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
PENGESAHAN... iii
PERSEMBAHANAN ... iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v
ABSTRAK... vi
ABSTRACT... vii
KATA PENGANTAR ... viii
DAFTAR ISI... xi
DAFTAR LAMPIRAN... xiii
BAB I. PENDAHULUAN... 1
A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Perumusan Masalah ... 4
D. Tujuan Penelitian ... 5
E. Manfaat Penelitian... 5
BAB II. DASAR TEORI ... 7
A. Pembelajaran Fisika ... 7
B. Peranan Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran Fisika... 9
B.1 Peran Guru... 9
B.2 Peranan Siswa... 13
C. Konsep ... 14
C.1 Pengertian Konsep ... 14
C.3 Memahami Konsep ... 19
C.4 Proses Perubahan Konsep... 20
D. Miskonsepsi ... 24
E. Metode Eksperimen Terbimbing ... 26
F. Lembar Kerja Siswa... 28
G. Wawancara... 30
BAB III.METODE PENELITIAN ... 33
A. Jenis Penelitian ... 33
B. Tempat dan Waktu Penelitian... 33
C. Subjek Penelitian ... 33
D. Disain Penelitian ... 34
1. Kegiatan Penelitian... 34
2. Pelaksanaan Pembelajaran... 36
3. Pengumpulan Data Penelitian... 37
E. Instrumen Penelitian ... 38
F. Metode Pengumpulan Data... 39
G. Analisa Data... 40
1. Pre-test ... 41
2. Post-test... 42
3. Lember Kerja Siswa... 42
4. Transkrip rekaman video ... 43
DAN PEMBAHASANNYA ... 44
A. Pelaksanaan Penelitian ... 44
B. Data Penelitian dan Analisis data... 65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 103
A. Kesimpulan ... 103
B. Saran ... 105
DAFTAR PUSTAKA ... 107
LAMPIRAN... 108
LAMPIRAN 1
Hasil Pretest ... 108 LAMPIRAN 2
Hasil Posttest Siswa ... 131 LAMPIRAN 3
Lembar Kerja Siswa... 149 LAMPIRAN 4
Contoh Hasil Wawancara ... 167 LAMPIRAN 5
Foto-Foto ... 181
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Paul, seorang anak kelas X yang cerdas, diminta untuk menjelaskan
mekanisme yang menyebabkan terjadinya musim di bumi dan fase bulan.
Meskipun materi ini telah dipelajari dalam pembelajaran sains (fisika) di kelas
sebelumnya, namun dalam penjelasannya, Paul menunjukkan beberapa konsepsi
yang keliru tentang terjadinya musim di Bumi. Misalnya ia yakin bahwa musim
disebabkan oleh kedekatan bumi pada matahari, musim dingin akan terjadi bila
bumi berada paling dekat dengan matahari dan musim panas akan terjadi bila
bumi terletak paling jauh dari matahari. Untuk fase bulan ia menjelaskan bahwa
bayangan bumi di bulan adalah penyebabnya (Mestre,1994).
Seperti Paul, banyak siswa yang telah mengikuti pembelajaran fisika di
kelas memiliki konsepsi yang keliru tentang meteri yang telah diajarkan, konsepsi
tersebut tidak cocok dengan penjelasan ilmiah. Konsep yang mereka bangun
dalam proses pembelajaran ternyata tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau
pengertian yang diterima oleh pakar dalam bidang fisika. Bila hal ini yang terjadi
tentu saja tujuan belajar, yakni memahami dan mengerti apa yang dipelajari
tidaklah tercapai.
Menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Suparno (2001:112) mengerti
adalah proses adaptasi intelektual dimana pengalaman dan ide baru diinteraksikan
baru. Jika dalam pembelajaran siswa tidak mengerti dengan benar tentang materi
yang diberikan, ini berarti siswa memiliki jaringan konsep yang salah. Jaringan
konsep yang salah ini selanjutnya akan ia gunakan untuk membentuk struktur atau
pengertian baru yang salah pula. Dalam hal ini bagaimanapun konsepsi siswa
yang keliru sangat menghambat pembelajaran. Oleh karena itu siswa yang
mengalami salah konsepsi perlu segera dideteksi, dibantu untuk mengatasi
beberapa konsepsi yang keliru sehingga menghasilkan perubahan konsep.
Menurut Posner dkk sebagaimana dikutip oleh Suparno (2000:16) ada dua macam
perubahan konsep yaitu proses asimilasidan proses akomodasi.
Terjadi proses asimilasi bila dalam perkembangan pengetahuan siswa
hanya menambahkan unsur baru pada konsep lamanya, karena
konsep-konsep yang dimiliki masih sesuai dengan pengalaman baru yang dijumpainya.
Sedangkan proses akomodasi terjadi apabila siswa mengalami ketidaksesuaian
konsep-konsep lama yang dimiliki dengan pengalaman baru yang dijumpai.
Konsep-konsep yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk menjelaskan gejala
atau fenomena yang sedang dihadapi. Dalam proses ini siswa akan mengubah
total konsep-konsep lamanya dan mengganti dengan konsep-konsep yang baru,
disini terjadi perubahan konsep secara drastis atau radikal.
Dalam perubahan konsep ini guru perlu merancang suatu metode
pembelajaran, dimana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan empat kondisi
yang diperlukan agar siswa mengalami perubahan konsep yaitu, 1) siswa harus
menjadi tidak puas dengan konsep-konsep mereka saat itu, 2) konsep yang baru
4) konsep yang baru harus bermanfaat (Waltson, Bruce and Richard
Kopnicek:2005). Dengan kondisi inilah akan terjadi proses akomodasi. Salah satu
metode yang dapat digunakan untuk mengalami perubahan konsep adalah dengan
eksperimen terbimbing yang menyediakan pristiwa anomali diikuti wawancara
diagnosis dan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai penuntunnya. Peristiwa
anomali adalah pristiwa yang bertentangan dengan pemikiran atau gagasan siswa.
Dalam metode ini siswa dirangsang untuk terlibat secara aktif dalam meramalkan,
mengobservasi, melakukan eksperimen, menjelaskan aktivitas mereka, menjawab
pertanyaan-pertanyaan dan mengungkapkan pemikiran atau gagasan-gagasan
mereka yang dituangkan dalam LKS. Guru hanya bertugas dalam mengarahkan
dan menuntun tindakan siswa, menggunakan pertanyaan-pertanyaan lewat
wawancara untuk menggali gagasan-gagasan siswa sehingga dapat berpikir logis
dan ilmiah.
Metode belajar ini adalah merupakan implementasi dari sejumlah
prinsip-prinsip konstruktivisme tentang bagaimana pengetahuan diperoleh.
Pendekatan ini mempunyai pola umum sebagai berikut: - Fase pertama,
mengungkapkan gagasan atau ide atau prapersepsi siswa tentang konsep yang
dipelajari, - Fase kedua, mendiskusikan dan mengevaluasi prakonsepsi, - Fase
ketiga menciptakan konflik antara konsep dan prakonsepsi, dan – Fase keempat,
mendorong dan mengarahkan rekonstruksi konsep (akomodasi) dalam pikiran
Diharapkan data yang dihadapi diartikan dan digunakan untuk mengubah
konsep yang ada, sehingga dapat diterima dalam diri siswa dan pada akhirnya
terbentuk konsep-konsep baru yang sesuai dengan gagasan para ahli.
Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk menyelidiki
bagaimana konsep awal siswa dan pembentukan konsep siswa melalui akomodasi
setelah siswa mengalami pembelajaran dengan menggunakan metode yang telah
dijelaskan di atas. Selain itu peneliti juga mengkaji bagaimana proses berpikir
siswa dalam mengubah (akomodasi) konsep-konsep yang ada hingga membentuk
konsep-konsep baru yang sesuai dengan gagasan para ahli. Untuk itu, maka
penelitian ini diberi judul “Pembentukan Konsep Siswa Tentang Hukum Ohm,
Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Berbantuan Experimen Terbimbing”. (Suatu Studi Kasus Pada Tiga Siswa Kelas I SMA N 2 Bener, Tegalrejo Yogyakarta)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka
permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah:
1) Bagaimana konsep awal siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan
Rangkaian Seri Paralel.
2) Bagaimana perubahan konsep siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat,
dan Rangkaian Seri Paralel dengan menggunakan metode eksperimen
3) Bagaimana konsep siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan
Rangkaian Seri Paralel setelah mengalami proses pembelajaran dengan
menggunakan metode eksperimen terbimbing.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini
bertujuan untuk :
1) Mengetahui bagaimana konsep awal siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan
Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel
2) Mengetahui bagaimana perubahan konsep siswa tentang Hukum Ohm,
Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel dengan menggunakan metode
eksperimen terbimbing.
3) Mengetahui bagaimana konsep siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat,
dan Rangkaian Seri Paralel setelah mengalami proses pembelajaran dengan
menggunakan metode eksperimen terbimbing.
D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Peneliti
Menambah pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh selama
kuliah, serta memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran fisika
2. Bagi Guru/Calon Guru
Hasil penelitian ini secara teoritis dipakai sebagai pertimbangan dalam
mengembangkan pembelajaran fisika, guru/calon guru termotivasi untuk semakin
kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam
pembelajaran.
3. Bagi Universitas Sanata Dharma
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan
referensi bagi perpustakaan sehingga dapat menambah khasanah bacaan ilmiah
BAB II DASAR TEORI
A. Pembelajaran Fisika
Fisika atau sains dapat dipandang sebagai kesatuan dari proses, sikap
dan hasil (Kartika Budi, 1998:162). Sedangkan pembelajaran merupakan suatu
proses memperoleh pengetahuan (Reber dalam Muhibbin Syah, 2003:64). Dalam
pembelajaran, proses merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan dan
aktivitas itu terjadi karena adanya tahap-tahap aktivitas yang sistematis dan
terarah. Dalam pembelajaran fisika aktivitas-aktivitas yang dilakukan diantaranya
melakukan observasi, mengukur, memprediksi, mengklasifikasi, membandingkan,
menyimpulkan, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis
data, membuat laporan penelitian dan mengkomunikasikan hasil penelitian.
Dengan aktivitas-aktivitas tersebut berarti siswa melakukan proses belajar dalam
hal ini belajar fisika.
Menurut kaum konstruktivis, belajar adalah merupakan proses aktif dari
siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan
lingkungannya. Belajar bukan sekedar proses mekanik mengumpulkan
pengetahuan. Siswa dikatakan telah belajar fisika apabila teori fisika dan konsep
fisika yang disajikan menjadi bagian dari struktur kognitif siswa. Kaum
konstruktivis juga mengungkapkan bahwa mengajar fisika bukanlah sekedar
memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu kegiatan yang
apa yang dipelajari, mencari kejelasan mengenai apa yang dipelajarinya, bersikap
kritis dan mengadakan justifikasi. Jadi mengajar dalam pembelajaran fisika adalah
suatu bentuk belajar sendiri (Suparno, 1997:62).
Dalam pembelajaran fisika disamping siswa harus berinteraksi dengan
guru, siswa juga harus diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan
obyek yang akan atau sedang dipelajarinya. Hal ini disebabkan karena bidang
telaah dalam fisika adalah semesta alam. Sehingga dalam pembelajaran fisika
penting untuk memahami dan menjelaskan alam bersama dengan berbagai
fenomena yang terjadi didalamnya. Karena itu, interaksi antara siswa dengan
lingkunagn merupakan ciri pokok dalam pembelajaran fisika. Dalam
pembelajaran fisika kedudukan siswa adalah sebagai subjek belajar yang artinya
dalam setiap proses kegiatan pembelajaran fisika, siswa harus berperan aktif.
Bantuan yang diberikan guru sebagai mediator maupun fasilitator sungguh
dimanfaatkan untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Sehingga hasil belajar
bukan semata-mata bergantung pada apa yang disajikan oleh guru, melainkan
sangat dipengaruhi oleh hasil interaksi antara berbagai informasi yang seharusnya
diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa mengolah berbagai informasi
berdasarkan pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya.
Hasil pembelajaran fisika tidak cukup dengan hanya mengingat apa yang
dipelajari. Namun, yang terpenting adalah perilaku dalam mencari pengertian
konsep melalui kegiatan dalam belajarnya. Siswa perlu dilatih untuk berprilaku
sebagai seorang ilmuwan selama berlangsungnya pembelajaran fisika. Perilaku
pemecah masalah, suka mempertanyakan dan mencari jawaban dengan
mengumpulkan berbagai informasi serta melakukan penelitian dan pengujian.
Perilaku yang tidak kalah penting adalah rasa ingin tahu yang sangat besar. Hal
lain yang menjadi aspek pokok dalam pembelajaran fisika adalah siswa menyadari
keterbatasan pengetahuan mereka. Memiliki rasa ingin tahu untuk menggali
berbagai informasi yang baru, dan akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam
kehidupan mereka (Rohandi, 1998:121). Apabila hal itu diterapkan pada siswa,
niscaya pembelajaran di sekolah akan menampakkan hasil yang tidak
mengecewakan.
B. Peranan Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Fisika B.1 Peran Guru
Dalam pembelajaran fisika seorang guru berperan sebagai mediator dan
fasilitator yang membantu siswa agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan
dengan lancar. Agar peran guru dapat berfungsi secara optimal maka guru dituntut
untuk menguasai materi atau bahan yang diajarkan secara luas dan mendalam
sehingga peran mediator dan fasilitator adalah sebagai berikut (Suparno, 1997:66)
a. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung
jawab dalam membuat rencana, proses, dan penelitian.
b. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang
keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan
gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka. Menyediakan sarana
dan pengalaman yang paling mendukung proses belajar siswa. Guru harus
menyemangati siswa. Guru perlu menyediakan pengalaman konfik.
c. Memonitor, dan mengevaluasi apakah pemikiran siswa berkembang atau
tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa itu
berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Guru membantu
mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan siswa.
Agar peran guru sebagai mediator dan fasilitator dapat dilaksanakan
secara optimal, maka diharapkan seorang guru menguasai beberapa hal berikut
(Suparno, 1997:68-71)
a. Menguasai Materi
Penguasaan materi secara luas dan mendalam memungkinkan seorang
guru menerima pandangan dan gagasan yang berbeda-beda dari siswa dan
menunjukkan apakah gagasan itu benar atau tidak, menyediakan berbagai
pengalaman belajar dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan siswa.
b. Menguasai Strategi Mengajar
Tugas guru adalah membantu siswa agar mampu mengkonstruksi
pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret maka strategi mengajar
hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi siswa. Driver dan Oldham
dalam Suparno (1997:69) menyebutkan beberapa hal yang perlu dikembangkan
dalam strategi pembelajaran sehingga siswa dapat mengkonstruksi
1) Orientasi. Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam
mempelajari suatu topik. Siswa diberi kesempatan untuk mengadakan
observasi terhadap topik yang hendak dipelajari.
2) Elisitasi. Siswa dibantu mengungkapkan idenya secara jelas dengan
berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Siswa diberi kesempatan
untuk mendiskusikan apa yang diobservasikan, dalam wujud tulisan, gambar,
atau poster.
3) Restrukturisasi ide. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan:
a) Klasifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman
lewat diskusi ataupun pengumpulan ide. Berhadapan dengan ide-ide lain,
siswa dapat terangsang untuk merekonstruksi gagasannya kalau tidak
cocok atau sebaliknya, menjadi lebih yakin bila gagasannya cocok.
b) Membangun ide baru. Ini terjadi bila dalam diskusi ide siswa bertentangan
dengan ide siswa yang lain atau ide siswa tidak dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman.
c) Mengevalusi ide barunya dengan experimen. Kalau dimungkinkan, ada
baiknya bila gagasan yang baru dibentuk diuji dengan suatu percobaan
atau persoalan baru.
4) Pengunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah
dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang
dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap dan bahkan
5) Mengkaji ulang bagaimana ide itu berubah. Dapat terjadi dalam aplikasi
pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, seseorang perlu
merevisi gagasannya entah dengan menambahkan suatu keterangan ataupun
mungkin dengan mengubahnya menjadi lebih lengkap.
c. Hubungan Guru dengan Siswa
Hubungan guru dengan siswa yang harmonis yang memungkinkan siswa
bekerja sama dengan guru, menyampaikan ide dan gagasan-gagasannya yang
kemudian mendiskusikannya dengan guru. Siswa berpandangan bahwa guru
adalah mitra mereka dalam membangun pengetahuan.
Dalam kegiatan pembelajaran fisika disamping guru disamping guru
bertanggung jawab atas kelancaran proses pembelajaran, hal yang perlu
ditekankan oleh seorang guru dalam pembelajaran fisika yaitu mengembangkan
perubahan konsep pada siswa yang sedang belajar. Sehingga selain sebagai
mediator dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran fisika, seorang guru fisika
diharapkan bersikap sebagai berikut (Scott, Asoko, Driver, 1991:9-1 dalam
Suparno, 2005:118).
a. Sadar akan gagasan dan pengertian siswa berkaitan dengan bahan yang
dipelajari.
b. Sadar akan jalan konseptual dari topik yang sedang dipelajari.
c. Sensitif pada kemauan belajar siswa.
d. Mampu menciptakan tugas belajar yang mendorong dan memajukan
e. Yakin dengan pengertiannya sendiri sehingga dapat menghargai, menjawab,
dan menerima gagasan yang berbeda.
B.2. Peran Siswa
Peran siswa dalam kegiatan pembelajaran fisika yaitu melibatkan diri
secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bantuan yang diberikan guru sebagai
mediator maupun fasilitator sungguh dimanfaatkan untuk membentuk
pengetahuannya sendiri.
Berbagai pengalaman yang diberikan guru sungguh dimanfaatkan untuk
menemukan berbagai pengertian baru dan memperluas pengetahuan lama yang
telah dimiliki (siswa mengalami perubahan konsep). Pada tahap ini siswa
memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyesuaikan konsep serta ide
baru dengan kerangka berfikir yang telah ada dalam pikiran mereka (Betterncourt,
1989; Shymansky, 1992; Watt dan Pope dalam Suparno, 1997:62). Jika
pengalaman-pengalaman baru yang dihadapi dapat dijelaskan dengan
mengunakan konsep-konsep awal mungkin dengan cara mendefinisikan lebih
spesifik sesuai dengan fenomena-fenomena yang dihadapi maka diperoleh
konsep-konsep yang baru yang lebih luas dengan memperinci berbagai variabel
yang mempengaruhi atau mungkin konsep lama yang telah dimiliki tidak dapat
lagi digunakan untuk menjelaskan pengalaman baru yang dihadapi, untuk itu ia
harus mengubah skema lamanya.
Fasilitas-fasilitas yang diberikan guru hendaknya dimanfaatkan
Berbagai kegiatan belajar yang dilakukan untuk memperoleh pengalaman belajar
antara lain dengan membuat hipotesis, menguji hipotesis, manipulasi objek,
memecahkan persoalan, mencari jawaban, menggambarkan, meneliti, berdialog,
mengadakan refleksi, mengungkapkan pertanyaan, mengekspresikan gagasan, dan
lain-lain (Suparno, 1997:62). Berbagai kegiatan diatas memungkinkan siswa
untuk mengembangkan skema-skema yang dimiliki. Disamping itu, dapat
membantu siswa dalam proses perubahan konsep baik yang memperluas konsep
ataupun membetulkan konsep yang salah.
C. Konsep
C.1. Pengertian konsep
Dalam proses pembelajaran fisika guru dan siswa selalu menghadapi dan
berhubungan dengan sejumlah konsep sesuai dengan pokok bahasan yang sedang
dipelajari. Konsep adalah gambaran mental sesuatu (Kartika Budi, 1987:234).
Gambaran mental itu diperoleh melalui generalisasi dari contoh-contoh, data-data,
dan peristiwa-peristiwa khusus. Dalam pembelajaran fisika konsep dapat berupa
objek (benda), gejala, situasi (kondisi), sifat-sifat, dan atribut dari suatu obyek
(Euwe Van den Berg, 1991:8). Konsep sebagai gambaran mental terbentuk
sebagai hasil aktivitas manusia baik mental maupun fisik. Konsep sendiri
merupakan hasil akhir dari persepsi. Untuk membedakan konsep yang satu dengan
konsep yang lain maka konsep itu harus menggunakan hakekat atau ciri yang
Menurut Kartika Budi (1987:237) dalam pembelajaran fisika kita
berhadapan dengan konsep fisis, baik itu konsep konkrit maupun konsep proses.
Robert B. Sund dalam Kartika Budi (1987:235) menjelaskan bahwa konsep
konkrit adalah konsep yang mengacu pada obyek seperti benda-benda,
besaran-besaran atau atribut dari besaran-besaran misalnya batu baterai, gaya, tegangan, tekanan
dan sebagainya. Sedangkan konsep proses adalah konsep yang mengacu pada
proses dari benda-benda atau besaran-besaran fisis seperti pemuaian, perambatan
panas dan sebagainya. Selain itu dalam pembelajaran fisika kita juga menjumpai
konsep seperti konsep medan magnet, kuat medan magnet, momen putar dan
sebagainya. Untuk membedakan konsep-konsep tersebut dapat ditinjau dari
beberapa dimensi atau sudut padang kita terhadap objek tersebut. Menurut Favell
sebagaimna dikutip oleh Ratna Wilis Dahar (1989:79) menyebutkan bahwa
konsep dapat dibedakan dalam tujuh dimensi antara lain:
a. Atribut. Setiap konsep memiliki atribut yang berbeda-beda baik ditinjau dari
segi fisik maupun fungsinya. Misalnya konsep meja harus memiliki
permukaan yang datar dan sambungan-sambungan yang mengarah ke bawah
yang mengangkat permukaan itu dari lantai.
b. Struktur yaitu cara bagaimana atribut tersebut saling terkait. Ada tiga macam
struktur yaitu (1) struktur konjuktif yaitu konsep dimana terdapat dua atau
lebih sifat sehingga dapat memenuhi syarat sebagai contoh konsep, seperti
percepatan adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu. Dua atribut yaitu
perubahan kecepatan dan selang waktu harus ada agar memenuhi konsep
lebih sifat harus ada, (3) struktur relasional manyatakan hubungan tertentu
antara stribut-stribut konsep seperti superposisi.
c. Keabstrakan. Ada konsep yang begitu konkrit dan abstrak misalnya jarak,
elektron.
d. Keinklusifan. Mengacu pada jumlah contoh yang dapat terlibat dalam
konsep.
e. Generalisasi atau keumuman. Bila diklasifikasikan konsep dapat dibedakan
dalam posisi superordinat atau subordinat, misalnya energi merupakan
superordinat dari energi kinetik.
f. Ketetapan. Menyangkut apakah ada sekumpulan aturan untuk membedakan
contoh-contoh dari noncontoh.
g. Kekuatan. Ditentukan sejauhmana orang setuju bahwa konsep itu penting.
Penjelasan yang kita berikan pada orang lain mengenai suatu konsep
dengan menunjuk salah satu atau lebih dari dimensi-dimensi yang dicakup oleh
konsep yang dimaksud akan memberikan gambaran pada orang tersebut mengenai
konsep yang dimaksud.
Konsep yang sudah dikuasai dengan benar, akan membantu siswa dalam
memecahkan suatu masalah. Sementara itu, tidak tertutup kemungkinan konsep
yang telah dikuasai siswa tidak tepat/salah, karena konsep awal siswa resisten
terhadap perubahan. Hal ini terjadi karena siswa percaya bahwa pengertian awal
mereka telah berjasa dalam memahami dunia ini. Maka dalam proses kegiatan
perubahan konsep sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap
dan benar.
C.2. Pembentukan Konsep (Concept Formation)
Konsep, sebagai gambaran mental, terbentuk sebagai hasil aktivitas
manusia baik mental maupun fisik; merupakan hasil akhir dari proses persepsi.
Persepsi adalah proses pemberian arti pada sederet informasi yang berhasil
ditangkap dan direkam indra. Arti yang ditangkap dari informasi itulah yang
kebanyakan berupa konsep (Moates, 1980 dalam Kartika Budi, 1987).
Secara umum proses persepsi dapat dijelaskan sebagai indra (sensory
register) menangkap dan merekam informasi. Melalui perhatian informasi
diseleksi. Informasi terseleksi dikirim ke otak. Otak mengolahnya. Pengolahan itu
berupa aktivitas mental seperti : mengklasifikasi, analisis-sintesis, proses asimilasi
dan akomodasi, pengujian-pengujian; yang akhirnya terbentuk gambaran mental
yang berupa arti atau interpretasi dari informasi (rangsangan, stimulus) yang
diterimanya. Komplikasi dan kualitas proses mental tersebut bergantung pada
jenis dan level konsep yang dibentuk serta peringkat perkembangan atau
kedewasaan pelaku pembentuk konsep tersebut.
Dua teori dasar pembentukan konsep adalah Teori Abstraksi dan Teori
Hipoteis (Neil Bolton, 1977 dalam Kartika budi, 1987). Menurut teori abstraksi
konsep dibentuk dengan menggeneralisasi fakta-fakta, contoh-contoh atau
pristiwa-prisatiwa khusus dengan mencari ciri-ciri esensial yang ada pada setiap
pada setiap contoh sebagai contoh konsep meja. Konsep kita tentang meja tidak
memuat jumlah kaki, bentuk, tinggi, lebar. Bila kita dihadapi meja dengan
berbagai macam bentuk serta ukuran dan jumlah kaki yang berbeda-beda kita
tetap mengatakan meja karena kita telah menangkap hakekat dari meja dan kita
tahu bahwa bentuk, ukuran dan banyaknya kaki bukanlah ciri esensial. Proses
berpikir seperti itu yaitu yang dimulai dari contoh-contoh khusus kemudian
sampai pada kesimpulan umum, kita kenal sebagai cara berpikir induktif.
Teori hipotesis mengatakan bahwa konsep mula-mula diajukan sebagai
hipotesis. Proses selanjutnya adalah membuktikan kebenaran hipotesis itu. Mecari
kebenaran konsep hipotesis berarti memberi contoh peristiwa-peristiwa yang
memenuhi atau cocok dengan konsep itu, atau mencoba menggunakan konsep itu
untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa alam. Konsep itu akan diterima sebagai
konsep yang benar bila ada peristiwa atau contoh-contoh yang memenuhi, atau
dapat dipakai untuk menjelaskan peristiwa alam. Makin banyak contoh yang
memenuhi dan makin banyak dapat dipergunakan untuk mengungkap misteri
alam, konsep itu akan diterima keberadaannya. Konsep hipotesis ini muncul
karena ketajaman para ilmuwan memandang peristiwa-peristiwa alam serta
tuntutan keinginan memecahkan masalah-masalah yang belum mampu
dipecahkan menggunakan konsep-konsep yang telah ada. Pembentukan konsep
C.3. Memahami Konsep
Salah satu tujuan pembelajaran di sekolah adalah agar siswa memiliki
kemampuan untuk memahami hal yang dipelajari. Guru sebagai mediator dan
fasilitator harus membimbing dan menekankan siswa pada pemahaman tersebut.
Pemahaman menurut Kartika Budi (1987:233) merupakan salah satu aspek
kognitif yang sangat penting pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah .
Aspek ini merupakan aspek yang menonjol atau aspek yang paling ditonjolkan.
Bila diadakan kegiatan pembelajaran, maka pertama-tama yang akan dicapai
adalah memahami atau mengerti apa yang dipelajari.
Untuk memutuskan seseorang memahami suatu konsep maka diperlukan
kriteria atau indikator-indikator. Menurut Kartika Budi (1992:114) kriteria atau
indikator-indikator yang menunjukkan seorang siswa memahami suatu konsep
antara lain (1) dapat menyatakan pengertian konsep dalam bentuk definisi
menggunakan kalimat sendiri, (2) dapat menjelaskan makna dari konsep
bersangkutan kepada orang lain, (3) dapat menganalisis hubungan atntara konsep
dalam suatu hukum, (4) dapat menerapkan konsep untuk (a) menganalisis dan
menjelaskan gejala-gejala alam khusus, (b) untuk memecahkan masalah fisika
baik secara teoritis maupun secara praktis, (c) memprediksi
kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada suatu sistem bila kondisi tertentu dipenuhi,
(5) dapatmempelajari konsep lain yang berkaitan dengan lebih cepat, (6) dapat
membedakan konsep yang satu dengan konsep lain yang saling berkaitan, (7)dapat
membedakan konsepsi yang benar dan konsepsi yang salah. Berdasarkan kriteria
kegiatan pembelajaran fisika apakah mengalami perubahan konsep baik yang
memperluas ataupun yang membetulkan konsep yang salah. Dengan semakin
bertambahnya konsep yang diketahui dan dipahami, dan sekaligus semakin tepat
konsep fisika dimengerti oleh siswa, maka mereka benar-benar menguasai bidang
fisika.
C. 4. Proses Perubahan Konsep
Siswa setiap kali membangun konsep baru melalui proses asimilasi dan
akomodasi skema mereka. Skema dapat dipikirkan sebagai konsep atau kategori.
Skema menurut Suparno (1997:30) merupakan suatu struktur mental seseorang
dimana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Melalui
kontak dengan pengalaman baru, skema dapat dikembangkan dan diubah, yaitu
dengan asimilasi dan akomodasi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih ditekankan
pada proses akomodasi.
Proses akomodasi terjadi jika seseorang tidak dapat lagi menggunakan
skema-skema lamanya yang telah dimiliki. Skema seseorang dibentuk dengan
pengalaman sepanjang waktu. Skema menunjukkan taraf pengertian dan
pengetahuan seseorang tentang dunia sekitarnya. Karena skema merupakan
konstruksi, maka bukan tiruan dari kenyataan dunia yang ada.
Menurut Posner dkk sebagaimana dikutip oleh Suparno (2000:17)
menyebutkan beberapa situasi dan kondisi yang memungkinkan proses perubahan
a. Harus ada ketidakpuasan terhadap konsep yang ada. Siswa mengubah
konsep mereka jika mereka percaya bahwa konsep yang telah mereka miliki
tidak dapat lagi digunakan untuk menghadapi situasi, pengalaman atau
gejala baru. Sumber ketidakpuasan terhadap konsep lama adalah adanya
peristiwa anomali, yaitu peristiwa yang bertentangan dengan yang
dipikirkan siswa bahkan siswa tidak dapat mengasimilasikan
pengetahuannya untuk memahami fenomena baru.
b. Konsep yang baru harus intelligible (dapat dimengerti). Siswa dapat
mengerti bagaimana pengalaman-pengalaman baru dapat didekati dengan
konsep-konsep baru tersebut.
c. Konsep yang baru harus masuk akal, yaitu mempunyai kemampuan untuk
memecahkan persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh para pendahulu,
dan konsisten dengan teori dan pengetahuan lain atau dengan pengalaman
lama.
d. Konsep baru harus beguna, berguna untuk riset dan punya kemampuan
untuk dikembangkan dan membuka penemuan baru.
Proses pembelajaran fisika yang baik dan benar harus mengembangkan
perubahan konsep dan perubahan konsep itu terjadi secara cepat dan efisien.
Perubahan konsep dapat pula dipahami sebagai perubahan dan penataan
pengalaman (pemahaman) siswa menjadi pemahaman konsep yang benar (ilmiah),
mantap dan berdaya guna. Di bawah ini diuraikan secara singkat dua perubahan
konsep dalam pembelajaran fisika, yaitu proses perluasan konsep dan proses
a) Proses Perluasan Konsep
Proses yang pertama adalah proses memperluas konsep yang sudah ada.
Semua model pembelajaran dan pengajaran klasik dengan ceramah, menjelaskan
bab demi bab dari suatu bahan fisika sesuai dengan kurikulum yang direncanakan,
semua itu adalah proses untuk mengembangkan konsep fisika siswa. Beberapa
cara membantu siswa menambah konsep atau pengetahuan mereka tentang bahan
fisika, antara lain:
- Memberikan informasi baru yang belum pernah diketahui oleh siswa.
Pemberian informasi baru atau tambahan konsep-konsep baru dapat
dilakukan antara lain guru menjelaskan konsep yang baru sesuai dengan
urutan kurikulum yang telah direncanakan.
- Siswa diberi bahan baru dan diajak untuk mempelajari sendiri bahan itu
sehingga konsepnya bertambah. Di sisni diperlukan bantuan pengarahan dari
guru.
- Siswa diberi kesempatan untuk mencari bahan-bahan baru yang telah
disediakan baik dari buku maupaun multimedia fisika.
b) Proses Pembetulan Konsep
Proses yang kedua dalam perubahan konsep adalah proses membetulkan
konsep yang salah. Untuk proses ini tidak cukup guru menambah bahan fisika
dalam pembelajaran, tetapi harus memiliki strategi yang tepat untuk membetulkan
miskonsepsi yang dialami siswa. Siswa disadarkan bahwa konsep awal mereka itu
tidak tepat dengan situasi yang ada. Cara penyadaran dapat dengan menyediakan
lamanya yang memang ternyata tidak mencukupi. Maka, ia tertantang untuk
mengubah konsepnya.
Menurut Joan Davis (2001) sebagaimana dikutip oleh Suparno (2005:97)
seorang guru dalam mengajarkan perubahan konsep harus memperhatikan dua hal
pokok yaitu:
1) Membuka konsep awal siswa.
Perubahan konsep hanya mungkin terjadi bila siswa sadar akan konsep awal
mereka, entah benar entah tidak. Dari konsep awal itulah dapat dilihat di mana
miskonsepsi mereka dengan segala alasannya. Maka dalam hal ini diperlukan
kepiawian guru untuk membantu siswa berani mengungkapkan gagasan mereka.
2) Membantu siswa mengubah kerangka berpikir awal.
Dalam langkah ini guru mencari beberapa teknik yang sesuai untuk
menantang agar siswa mengubah gagasan mereka yang tidak benar. Untuk dapat
mengubah kerangka berpikir siswa, seorang guru perlu mengerti ekologi
konseptual siswa, yaitu pengetahuan dan kepercayaan yang dipunyai siswa.
Hal ini meliputi antara lain:
a. Pengetahuan awal atau konsep yang telah ada dalam diri siswa
b. Relasi atara konsep-konsep tersebut dalam pikiran siswa
c. Pengetahuan baru tentang konsep-konsep alternatif yang dipunyai siswa
d. Keyakinan epistemologis siswa, yaitu keyakinan siswa yang membuat siswa
D. Miskonsepsi
Siswa sewaktu memasuki kelas untuk belajar fisika tidak dengan kepala
kosong tetapi kepala siswa sudah mempunyai pengetahuan yang berhubungan
dengan fisika (Euwe Van Den Berg, 1991:1). Misalnya, sebelum siswa mengikuti
pelajaran mekanika, mereka sudah banyak berpengalaman dengan peristiwa
mekanika (gerak, gaya, benda yang jatuh bebas dan sebagainya). Dengan
pengalamannya itu mereka mengembangkan banyak konsepsi mengenai
konsep-konsep fisika. Menurut Euwa Van Den Berg (1991:10) konsep-konsepsi adalah penafsiran
seseorang tentang konsep.
Dalam mempelajari suatu konsep tertentu konsepsi awal siswa tersebut
bisa jadi berbeda dengan konsepsi para fisikawan. Misalnya, inti konsep massa
jenis adalah bahwa utnuk jenis bahan tertentu hasil bagi antara massa dan volume
selalu tetap dan bahwa tetapan itu berbeda untuk setiap unsur/senyawa/campuran,
maka unsur/senyawa dapat dikenal dari massa jenisnya. Tetapi banyak siswa
mempunyai konsep berbeda, maka cenderung berpikir bahwa jika jumlah zat
(massanya) ditambah, maka massa jenisnya juga bertambah. Konsepsi siswa yang
tidak sesuai dengan konsepsi para fisikawan disebut miskonsepsi atau salah
konsepsi.
Suparno (2005:4) mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu konsep
yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para
pakar dalam bidang itu. Bentuknya dapat berupa konsep awal, kesalahan,
hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif, atau
sebagai suatu konsep yang tidak sama bahkan bertentangan dengan konsepsi yang
dibangun oleh para ilmuan yang diterima sebagai konsepsi yang benar.
Namun ada pula konsepsi yang tidak sepenuhnya salah, tetapi
mengakibatkan salah pada konsepsi yang lain. Misalnya, gaya dipandang sebagai
tarikan atau dorongan mempunyai makna berbeda dengan “gaya adalah yang
menyebabkan kecepatan atau momentum berubah”, tetapi keduanya salah.
Konsepsi gaya sebagai “penyebab gerak”’tidak sepenuhnya salah, akan tetapi
dapat menghasilkan salah konsepsi pada konsep yang lain, misalnya gaya selalu
digambarkan searah dengan gerak; pada benda yang bertumbukan, setelah
peristiwa tumbukan berakhir, pada benda tetap dianggap masih mengalami gaya
untuk mempertahankan geraknya, yang bertentangan dengan konsep: “sebagai
hasil interaksi, gaya ada saat ada interaksi, dan gaya tak lagi ada setelah interaksi
berakhir”.
Untuk menyadarkan siswa akan miskonsepsi mereka, ada baiknya bila
seorang guru memberikan pengalaman belajar yang menantang konsep awal siswa
yang kurang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan percobaan, karena percobaan
dapat menantang intuisi siswa apakah benar atau tidak. Dengan mengalami dan
mengamati percobaan yang hasilnya terus-menerus berbeda, maka siswa
tertantang untuk mengubah gagasan atau konsep mereka. Dengan demikian
miskonsepsi dapat diluruskan dan membantu siswa mengembangkan konsep yang
E. Metode Eksperimen Terbimbing
Ada dua bentuk metode eksperimen, yaitu: eksperimen bebas dan
eksperimen terbimbing. Eksperimen bebas adalah suatu metode pembelajaran
dimana seseorang bebas untuk melakukan atau mengembangkan hal-hal yang
berhubungan dengan percobaan. Eksperimen bebas biasa dilakukan oleh para
ilmuwan yang bertujuan untuk membuktikan pemikiran mereka. Bisa terjadi pada
eksperimen bebas ini para ilmuwan tidak dapat membuktikan pemikiran mereka
tetapi justru memperoleh pengetahuan baru, yang pada mulanya tidak mereka
duga sama sekali. Eksperimen bebas ini tidak biasa dilakukan oleh para siswa
dalam pembelajaran.
Eksperimen terbimbing adalah suatu metode pembelajaran dimana siswa
melakukan percobaan peralatan sains dengan bimbingan seorang guru. Dalam hal
ini seorang guru selain bertugas membimbing siswa dalam melakukan setiap
langkah-langkah percobaan, guru juga bertugas mengembangkan dan mengajukan
pertanyaan penyelidikan, menimbulkan tanggapan, mencari penjelasan lebih
lanjut, dan membantu siswa mencapai kesimpulan atas dasar bukti yang mendasar
(Wenning, 2005:5)
Metode eksperimen terbimbing menempatkan guru sebagai fasilitator.
Metode ini lebih cocok untuk sains karena ilmu pengetahuan alam adalah ilmu
yang eksperimental, artinya kebenaran teori IPA selalu diuji dengan percobaan
(Euwe Van den Berg, 1991:1). Metode eksperimen terbimbing berfungsi sebagai
berbuat atau melakukan sesuatu, sehingga aktivitas siswa lebih banyak pada
mempraktekkan sesuatu yang diamati.
Beberapa keunggulan pembelajaran dengan metode eksperimen
terbimbing menurut Moedjiono dan Moh. Dimyanti (1991:78) antara lain:
(1) Siswa secara aktif terlibat mengumpulkan fakta, informasi, atau data yang
diperlukannya melalui percobaan yang dilakukan.
(2) Siswa memperoleh kesempatan untuk mebuktikan kebenaran teoritis secara
empiris melalui eksperimen, sehingga siswa terlatih membuktikan ilmu secara
ilmiah.
(3) Siswa berkesempatan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah dalam
rangka menguji kebenaran hipotesis.
Metode eksperimen terbimbing juga memiliki kelemahan, beberapa
kelemahan pembelajaran dengan metode eksperimen ayaitu sebagai berikut:
(1) Memerlukan peralatan, bahan dan/atau sarana eksperimen bagi setiap siswa
atau sekelompok siswa, hal ini perlu dipenuhi karena akan mengurangi
kesempatan siswa bereksperimen jika tidak tersedia.
(2) Jika eksperimen memerlukan waktu yang lama, akan mengakibatkan
berkurangnya kecepatan laju pembelajaran.
(3) Kurangnya pengalaman para siswa maupun guru dalam melaksanakan
eksperimen akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melakukan
eksperimen.
(4) Kegagalan/kesalahan dalam eksperimen akan mengakibatkan perolehan hasil
Walaupun metode eksperimen terbimbing memiliki kelemahan seorang
guru tidak boleh meninggalkan atau mengesampingkan penggunaan metode
eksperimen bila situasi pembelajaran menuntut digunakan metode eksperimen.
Metode eksperimen terbimbing memiliki prosedur yang sama dengan proses
pembelajaran yang biasanya berlangsung. Ada kegiatan persiapan, pelaksanaan,
dan evaluasi. Dalam kegiatan persiapan guru merancang langkah-langkah
eksperimen yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai dan media sebagai pendukung agar siswa sungguh terlibat aktif.
Siswa melakukan eksperimen terbimbing dengan cara mengikuti
langkah-langkah eksperimen dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sudah
dirancang oleh peneliti agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan sebagai
hasil dari proses pembelajaran. Selama pelaksanaan pembelajaran, guru perlu
menginformasikan apa saja yang perlu dilakukan, diamati dan dicatat selama
eksperimen. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagian besar kegiatan dilakukan
oleh siswa. Setelah pembelajaran berlangsung, guru perlu mengadakan evaluasi
untuk mengetahui sejauh mana siswa mempu mengumpulkan dan mengkonstruksi
pengetahuannya selama eksperimen serta pengalaman apa saja yang mereka
dapatkan. Dalam penelitian ini selain menggunakan Lembar Kerja Siswa, peneliti
juga melakukan wawancara diagnosis.
F. Lembar Kerja Siswa
LKS merupakan lembar kerja siswa yang digunakan agar proses
kegiatan yang releven dalam membangun kompetensi (Fika: 2005). Lembar kerja
siswa merupakan rancangan kegiatan yang khusus dibuat untuk siswa, agar dapat
digunakan oleh siswa pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu
lembar kerja siswa juga merupakan sarana dalam pembelajaran fisika yang dapat
digunakan dalam kegiatan demonstrasi, eksperimen, diskusi, dan dapat juga
digunakan sebagai media dalam tugas kokurikuler. Lembar kerja siswa pada
umumnya berbentuk buku atau lembaran-lembaran yang berisi beberapa
komponen.
Komponen-komponen penting yang terdapat dalam lembar kerja adalah
(1) kompetensi dasar, (2) materi pokok, (3) sub materi pokok, (4) indikator hasil
belajar, (5) petunjuk, dan (6) kegiatan belajar.
Petunjuk dibagi menjadi dua bagian yaitu petunjuk umum dan petunjuk
khusus. Petunjuk berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa dalam
mempelajari suatu materi selama kegiatan pembelajaran.
Kegiatan belajar dibagi dalam beberapa kegiatan. Dalam setiap kegiatan
memuat sub pokok bahasan yang akan diajarkan lengkap dengan tujuan yang
harus dicapai oleh siswa, langkah-langkah percobaan, dasar teori atau materi awal
yang harus dipelajari oleh siswa, soal-soal latijan, penarikan kesimpulan oleh
siswa, dan lembar kerja.
Dalam penyusunan lembar kerja siswa, bila tidak ada keharusan untuk
menggunakan format tertentu maka guru atau sekolah dapat menentukan sendiri
lembar kegiatan siswa tersebut bukan formatnya, melainkan fungsinya yaitu untuk
lebih membelajarkan siswa. Lembar kerja siswa yang paling baik adalah dapat
melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang relevan dan berkesinambungan.
Kegiatan dalam lembar kegiatan siswa antara lain (1) membaca uraian atau
penjelasan, (2) menjawab pertanyaan, (3) mengerjakan tugas, (4) mengerjakan
latihan-latihan, (5) mencatat data dari demonstrasi ke dalam tabel yang telah
disediakan, (6) melakukan eksperimen dan mencatat data dalam tabel yang telah
disediakan, (7) menganalisis data melalui pertanyaan-pertanyaan, (8) menarik
kesimpulan, (9) menguji kesimpulan.
G. Wawancara
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi
semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi
(Nasution1982:131). Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara
verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan,
namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telpon. Peneliti menerima
informasi yang diberikan tanpa mambantah, mengecam, menyetujui atau tidak
menyetujui. Dengan wawancara peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang
dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang
menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang
diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah
Wawancara tida sekedar omong-omong atau percakapan biasa, dalam
wawancara diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan
secara tajam, halus dan tepat, dan kemampuan untuk menangkap buah pikir orang
lain dengan cepat. Wawancara memerlukan keterampilan dan kecepatan berpikir,
ia harus dengan tajam meneliti kesesuaian suatu keterangan dengan keterangan
lain.
Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan
kenyataan, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tetang berbagai aspek.
Melalui tanya jawab kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga kita
peroleh gambaran tentang dunia mereka. Wawancara dapat berbentuk wawancara
bebas (tak berstruktur) dan wawancara terstruktur.
Dalam wawancara bebas (tak-berstruktur) tidak dipersiapkan daftar
pertanyaan sebelumnya, guru atau bebas bertanya kepada siswa dan siswa dapat
dengan bebas menjawab. Ia boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu
dalam situasi wawancara itu. Lama interview juga tidak ditentukan dan diakhiri
menurut keinginan pewawancara. Namun ada baiknya bila pewawancara sebagai
pegangan mencata pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan
tujuan wawancara.
Keuntungan dari wawancara bebas ialah kebebasan yang menjiwainya,
sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin
dikemukakannya. Dengan demikian pewawancara memperoleh gambaran yang
aspek menurut pendirian dan pikiran masing-masing dan dengan demikian dapat
memperkaya pandangan peneliti (Nasution, 1982:137-138).
Sedangkan dalam wawancara terstruktur, semua pertanyaan telah
dirumuskan sebelumnya dengan cermat, dan urutannya pun secara garis besar
sudah disusun, sehingga memudahkan dalam praktiknya (Suparno, 2005:127).
Keuntungan dari wawancara terstruktur antara lain. (1) tujuan wawancara lebih
jelas dan terpusat pada hal-hal yang telah ditentukan lebih dahulu sehingga tidak
ada bahaya bahwa percakapan menyeleweng dan menyimpang dari tujuan. (2)
jawaban-jawaban mudah dicatat dan diberi kode, dan karena itu (3) data lebih
mudah diolah (Nasution,1982:137). Melalui wawancara terstruktur peneliti dapat
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian yang mendalami
suatu kasus pada satu orang atau kelompok tertentu. Hasil penelitian ini hanya
berlaku terbatas pada siswa-siswi yang diteliti saja. Kesimpulan yang diperoleh
peneliti tidak dapat digeneralisasi pada keadaan-keadaan di luar kasus yang
diteliti.
B. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian untuk pemilihan partisipan pada tanggal 28 Maret 2007 dan
pelaksanaan post-test pada tanggal 4 Mei 2007 dilakukan di SMA Negeri 2 Bener,
Tegalrejo, Yogyakarta. Sedangkan pelaksanaan proses pembelajaran pada tanggal
13, 20, dan 27 April 2007 dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar, lantai
II Universitas Sanata Dharma, Paingan.
C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMA Negeri 2 Bener,
Tegalrejo, Yogyakarta yang pernah mendapatkan materi pelajaran tentang
Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel. Dari ke 33 siswa
dipilih sebagai partisipan berjumlah tiga (3) siswa. Partisipan yang dipilih yaitu
kurang lengkap mengenai Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri
Paralel. Penelitian dibatasi hanya berlaku pada partisipan yang bersangkutan dan
bersifat studi kasus.
D. Disain Penelitian 1. Kegiatan Penelitian
Kegiatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
I. Peneliti mengajukan tes kepada siswa berupa pertanyaan-pertanyaan
pemahaman siswa mengenai Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian
Seri Paralel, hal ini bertujuan untuk membuka konsep awal siswa dan menguji
pemahaman siswa. Pertanyaan tersebut berupa soal esai dan harus dijawab
beserta dengan alasan-alasannya.
II. Partisipan yang mengalami salah konsep akan dibimbing untuk melakukan
eksperimen. Sebelumnya partisipan diminta untuk membuat tentang
Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel. Partisipan
diminta untuk meramalkan atau memprediksi tentang fenomena yang akan
terjadi dalam eksperimen melalui permasalahan yang diajukan untuk
masing-masing percobaan. Prediksi yang dibuat harus diserta dengan penjelasan. Hal
ini bertujuan untuk mengungkapkan gagasan atau ide siswa tentang konsep
yang dipelajari.
III.Setelah prediksi dibuat, partisipan diminta untuk melakukan percobaan
permasalahan yang diajukan dan mencatat datanya dalam Lembar Kerja
Siswa.
IV.Selama eksperimen berlangsung, partisipan diajak untuk berdiskusi dengan
peneliti melalui pertanyaan-pertanyaan panduan yang terdapat dalam LKS.
Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi untuk menunjukkan jalan pikiran siswa
serta membantu menuntun siswa dalam membangun konsep yang benar.
V. Setelah kegiatan percobaan (observasi) dilakukan, partisipan diminta untuk
memberikan penjelasan, menganalisis dan menarik kesimpulan atas hasil
observasinya dan kemudian membandingkannya dengan prediksi yang dibuat.
VI.Peneliti mengajukan tes untuk menguji kembali pemahaman partisipan setelah
melakukan eksperimen. Tujuan dari tes ini adalah untuk melihat apakah
2. Pelaksanaan Pembelajaran
Dalam pembelajaran ini digunakan metode eksperimen terbimbing disertai
dengan wawancara diagnosis dan media pembelajarannya berupa lembar kerja
siswa. Langkah-langkah pembelajaran adalah sebagai berikut:
a. Peneliti memberikan informasi kepada partisipan mengenai kegiatan yang
b. Peneliti memberikan lambar kerja siswa kepada partisipan untuk
melakukan serangkaian kegiatan, kemudian peneliti menuntun partisipan untuk
menjawab pertanyaan beserta dengan penjelasan yang terdapat di dalam Lembar
Kerja Siswa.
c. Peneliti membimbing partisipan dalam melakukan eksperimen, sehingga
siswa dapat melaksanakan eksperimen dan memperoleh data dengan lancar dan
terkontrol.
d. Setelah melakukan eksperimen peneliti menuntun partisipan dalam
mengolah dan menganalisis data, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat
dalam LKS disertai juga dengan wawancara diagnosis, dan menarik kesimpulan.
e. Peneliti mengadakan penyelidikan kembali tentang pemahaman konsep
siswa melalui post-test sebagai tes akhir untuk mengetahui pemahaman partisipan
setelah melakukan eksperimen. Tujuan dari tes ini adalah untuk melihat apakah
peroses akomodasi benar-benar telah terjadi.
3. Pengumpulan Data Penelitian
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan empat macam
instrumen, yaitu pre-test , post-test, transkrip rekaman video, dan lembar kerja
siswa dengan metode eksperimen.
a. Data tentang ketidaktepatan atau salah konsep partisipan diperoleh dari
hasil pre-test dan .
b. Data tentang perubahan konsep dan pengetahuan yang dibangun siswa
menggunakan lembar kerja siswa yang diberikan, wawancara dan pengamatan
visual dalam transkrip rekaman video.
c. Data pembentukan konsep partisipan setelah pembelajaran dengan metode
eksperimen terbimbing diperoleh dari hasil post-test, dan wawancara dalam
transkrip rekaman video.
E. Instrumen Penelitian
Ada dua macam instrumen penelitian, yaitu instrumen untuk melakukan
kegiatan pembelajaran dan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen untuk
melakukan kegiatan pembelajaran meliputi lambar kerja siswa, Rancangan
Pembelajaran dan peralatan percobaan. Sedangkan instrumen untuk
mengumpulkan data meliputi: test hasil belajar yang berupa pre-test, post-test, dan
transkrip rekaman video (audio visual).
a. Lembar Kerja Siswa
Lembar kerja siswa akan memuat: topik, subtopik, alat, petunjuk,
penggunaan alat, masalah yang akan disajikan, serta lembar tugas yang diisi oleh
partisipan. Dengan Lembar Kerja Siswa peneliti bisa melihat prediksi serta alasan
atau gagasan yang dibuat partisipan, data atau hasil yang diperoleh pada waktu
observasi, dan dapat melihat penjelasan yang ditulis oleh partisipan.
b. Soal Pre-test dan Post-test
Dengan pre-test peneliti dapat mengetahui konsep awal, dan
ketidaktepatan atau kurang lengkapnya konsep awal yang dimiliki siswa.
dibagun oleh siswa setelah siswa mengalami pembelajaran. Jenis soal untuk
pre-test dan post-pre-test adalah berupa soal-soal esai disertai dengan penjelasan.
c. Transkrip Rekaman Video
Intrumen ini meliputi hasil wawancara (audio) dan pengamatan visual,
bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan pemahaman atau konsep siswa,
prediksi-prediksi siswa, gagasan-gagasan siswa dan proses berpikir siswa yang
diungkapkan melalui wawancara diagnosis selama mengalami proses
pembelajaran. Dengan rekaman video ini peneliti juga dapat melihat secara visual
jalannya tiap-tiap percobaan yang dilakukan siswa.
F. Metode Pengumpulan Data
1) Menguji konsep awal dan pemahaman siswa tentang Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel.
Untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan pemahaman siswa dapat
dilihat dari hasil pre-test, yaitu melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan
konseptual mengenai Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel.
Pertanyaan-pertanyaan berupa soal esai yang harus dijawab berserta dengan
alasan-alasan yang melatarbelakangi jawaban tersebut. Hasil pre-test dan
wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif.
2) Poses perubahan konsep siswa tentang Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel yang dibangun siswa melalui pembelajaran dengan metode eksperimen terbimbing.
Data untuk menganalisis proses perubahan dan pengetahuan yang
dibangun siswa diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan visual dimana
video. Wawancara dilakukan selama berlangsungnya proses percobaan,
wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam.
Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berpedoman pada fenomena percobaan yang diajukan.
Selain dari transkrip rekaman video, peneliti juga menganalisis jawaban
pertanyaan, analisis data, dan kesimpulan yang dikerjakan siswa melalui Lembar
Kerja Siswa, kemudian dilihat apakah konsep tersebut telah sesuai atau tidak,
sehingga dapat dilihat kesalahan-kesalahan yang mungkin masih terjadi dalam
membangun konsep. Semua perolehan data ini dianalisis secara deskriptif
kualitatif.
3) Pembentukan konsep partisipan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan metode eksperimen terbimbing.
Pembentukan pengetahuan siswa tentang Hambatan Kawat, Hukum Ohm,
dan Rangkaian Seri Paralel dapat dianalisis melalui jawaban partisipan atas
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam post-test. Pendeteksian konsep yang
dibangun oleh partisipan dilakukan juga dengan wawancara diagnosis. Hasil
post-test dianalisis secara kualitatif dan diberi pembahasan untuk tiap hasil jawaban
post-test.
G. Analisis Data
Melalui hasil pre-test, post-test, dan transkrip rekaman video dapat
diketahui konsepsi siswa sebelum pembelajaran, konsepsi siswa setelah
pembelajaran, dan perubahan konsepsi siswa selama pembelajaran.. Data-data
yang diperoleh melalui instrumen-instrumen di atas dianalisis untuk
akomodasi dengan metode eksperimen terbimbing dan wawancara. Dari gambaran
pembentukan konsep tersebut kemudian dilakukan pembahasan.
1. Pre-test (Tes Awal)
Pre-test diberikan sebelum kegiatan eksperimen dilakukan. Tujuan dari
tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa, pemahaman siswa, dan
juga untuk mendeteksi ada tidaknya miskonsepsi yang dimiliki siswa tentang
Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel. Soal tes berjumlah
18, masing-masing 2 soal untuk materi Rangkaian listrik sederhana, 3 soal untuk
Hukum Ohm, 4 soal untuk hambatan penghantar, 4 soal untuk Rangkaian seri, dan
5 soal untuk Rangkaian Paralel. Soal tes awal berbentuk esai.
Setiap jawaban dari pre-test akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti
akan menganalisis jawaban setiap soal dengan penjelasan yang diberikan. Dengan
analisis ini peneliti akan melihat bagaimana hubungan jawaban setiap soal dengan
penjelasan yang mendasari jawaban. Penjelasan yang dibuat siswa
menggambarkan bagaimana konsep yang mereka miliki. Analisis ini akan
memberikan informasi bagi peneliti apakah siswa memiliki pemahaman yang
benar, mengalami miskonsepsi (salah konsep) , atau mungkin siswa memiliki
konsep yang kurang lengkap. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 3
siswa yang mengalami miskonsepsi atau juga yang memiliki ketidaklengkapan
konsep. Tiga siswa (partisipan) inilah yang selanjutnya akan dibimbing melalui
2. Post-test (Tes Akhir)
Test akhir digunakan untuk mengetahui pembentukan konsep partisipan
setelah mengalami proses pembelajaran melalui eksperimen terbimbing. Soal-soal
dalam test akhir ini merupakan modifikasi dari soal-soal pre-test. Jumlah soal
dalam test ini berjumlah 17, masing-masing 3 soal untuk Hukum Ohm, 4 soal
untuk hambatan penghantar, 5 soal untuk Rangkaian seri, dan 5 soal untuk
Rangkaian Paralel. Soal test awal berbentuk esai.
Setiap jawaban dari post-test akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti
akan menganalisis jawaban dari setiap soal dengan penjelasan yang diberikan.
Dengan analisis ini peneliti akan melihat bagaimana hubungan jawaban setiap
soal dengan penjelasan yang diberikan, kemudian akan diperoleh informasi
apakah siswa tersebut telah memiliki pemahaman yang benar tentang hukum
Ohm, hambatan kawat, dan rangkaian seri paralel atau malah sebaliknya.
3. Lembar Kerja Siswa (LKS)
Lembar kerja siswa digunakan oleh partisipan selama kegiatan
eksperimen berlangsung. LKS ini dirancang dengan 3 bagian. Pertama bagian
pertanyaan persiapan percobaan, bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk
mendorong siswa merumuskan suatu hipotesis terhadap fenomena yang dihadapi.
Bagian ini berfungsi untuk melihat bagaimana pemahaman siswa sebelum
melakukan eksperimen. Kedua bagian melakukan kegiatan, mencari data, dan
pertanyaan-pertanyaan yang membantu siswa dalam menganalisis data.