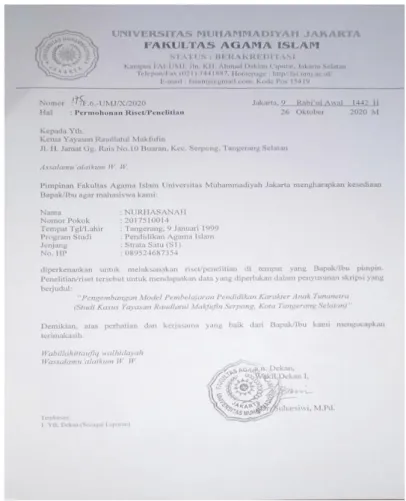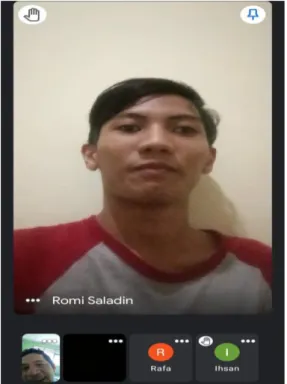TUNANETRA (STUDI KASUS YAYASAN RAUDLATUL MAKFUFIN SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN)
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strara Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam
Disusun oleh :
Nama : NURHASANAH NPM : 2017510014
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 1442 H/ 2021 M
i
LEMBAR PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Nurhasanah
NPM : 2017510014
Program Studi : Pendidikan Agama Islam Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial Dan Komunikasi (OMSK) dalam Membentuk Karakter Anak Tunanetra (Studi Kasus Yayasan Raudlatul Makfufin Serpong Kota Tangerang Selatan)
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.
Jakarta, 22 Jumadil Akhir 1442 4 Februari 2021 M
Yang Menyatakan,
Materai
Nurhasanah
ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi yang berjudul “Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial Dan Komunikasi (OMSK) dalam Membentuk Karakter Anak Tunanetra (Studi Kasus Yayasan Raudlatul Makfufin Serpong Kota Tangerang Selatan)” yang disusun oleh Nurhasanah, Nomor Pokok Mahasiswa: 2017510014 Program Studi Pendidikan Agama Islam disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Jakarta, 4 Februari 2021
Pembimbing
Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc.
iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul”Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi (OMSK) Dalam Membentuk Karakter Anak Tunanetra (Studi Kasus Yayasan Raudlatul Makfufin Serpong Kota Tangerang Selatan)” disusun oleh : Nurhasanah Nomor Pokok Mahasiswa : 2017510014. Telah diujikan pada hari/tanggal : Rabu/10 Februari 2021, telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam.
FAKULTAS AGAMA ISLAM Dekan,
Dr. Sopa, M.Ag
Nama - Tanda Tangan - Tanggal
Dr. Sopa, M.Ag ... ...
Ketua
Dr. Suharsiwi, M.Pd ... ...
Sekretaris
Dr. Rusjdy S. Arifin, M. Sc ... ...
Dosen Pembimbing
Yudi Kristanto, M. Pd 27 Februari 2021 Anggota Penguji I
Mukti Ali, MA ... ...
Anggota Penguji II
iv FAKULTAS AGAMA ISLAM
Program Studi Pendidikan Agama Islam NURHASANAH
2017510014
Skripsi, Januari 2021
Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial Dan Komunikasi (Omsk) Dalam Membentuk Karakter Anak Tunanetra (Studi Kasus Yayasan Raudlatul Makfufin Serpong Kota Tangerang Selatan)
ABSTRAK
Penerapan program OMSK (Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi) yang mana pengembangan kemampuan komunikasi anak tunanetra bertujuan untuk melatih bersikap baik dan benar dalam berkomunikasi lisan, tulisan baik menggunakan alat komunikasi manual (braille) dan elektronik. Melalui pembelajaran ini diharapkan anak tunanetra dapat terbentuk karakternya serta dapat bersikap mandiri dan mengurangi ketergantungannya terhadap orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) karakter anak tunanetra, (2) pengembangan pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (omsk) dalam membentuk karakter anak tunanetra (3) faktor pendukung dan penghambat pengembangan pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan, guru orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK), kepala sekolah Yayasan Raudlatul Makfufin dan siswa sebagai subyek penelitiannya. Hasil penelitian ini yaitu : (1) karakter anak tunanetra diantaranya tidak percaya diri, takut, pemalu, serta ketergantungan yang berlebih (2) pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) dapat meningkatkan kepercayaan diri serta kemandirian pada anak tunanetra (3) faktor pendukung dan penghambat pengembangan pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra adalah : kemampuan motorik anak, guru, motivasi, sarana dan prasarana, orang tua, lingkungan sekolah dan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa guru orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) memiliki peran sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru dalam pengembangan pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra dapat digolongkan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti keluarga ( orang tua) dan faktor eksternal seperti guru, lingkungan sekolah dan masyarakat, serta sarana dan prasarana.
Pengembangan pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra adalah dengan membiasakan anak tunanetra melakukan segala hal dengan sendiri serta menumbuhkan kemandirian dan membentuk
v
karakter yang baik. Saran yang dapat peneliti ajukan antara lain yaitu guru dan kepala sekolah merupakan tombak keberhasilan Pendidikan, agar pelaksanaan pembelajaran berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, kuncinya terletak kesiapan, kemauan dan kemampuan pendidik untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik- baiknya.
Kata Kunci : Karakter, Siswa tunanetra, OMSK, SDLB
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI
1. Konsonan :
ﺀ , ﻁ TH
ﺏ B ﻅ ZH
ﺕ T ﻉ ‘
ﺙ TS ﻍ GH
ﺝ J ﻑ F
ﺡ H ﻕ Q
ﺥ KH ﻙ K
ﺩ D ﻝ L
ﺫ DZ ﻡ M
ﺮ R ﻥ N
ﺰ Z ﻭ W
ﺲ S ﻩ H
ﺵ SY ﻱ Y
ﺹ SH ﺓ H
ﺽ DL
4. Diftong 5. Pembaruan
۔۔۔
ﻭ = au ﻻ = al- …
ﻱ ﺩ۔۔ = ai ﺶ ﻟﺍ = al-sy …
ﻝﺍ ﻭ = wa al- …
2. Vokal Pendek 3. Vokal Panjang
َﺏ A ﺑﺎ ﹶ ȃ
ِﺏ I ﻰ ﺑﹺ î
ُﺏ U ﻭ ﺑﹸ Û
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2021.
Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak- pihak berikut:
1. Dr. Endang Sulastri, M. Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Busahdiar, M.A., Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dr. Rusjdy Sjakyakirti Arifin, M.Sc., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Ade Ismail, S.Pd., Kepala Yayasan Raudlatul Makfufin dan SKh-IT Raudlatul Makfufin dan Agus Sulaiman, S.Pd., selaku guru Orientasi Mobilitas Sosial dan
viii
Komunikasi (OMSK) jenjang SD sampai dengan SMP yang telah membantu memberi izin tempat penelitian dan memberi dukungan data.
6. Siswa-siswi Yayasan Raudlatul Makfufin yang telah menjadi responden penelitian.
Tanpa bantuan mereka mustahil skripsi dapat diselesaikan.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Amad dan Ibu Aminah, serta kakak dan adikku (Arip Budiman dan Nur Kholis Majid) yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
9. Teman-teman Mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta karena telah memberikan motivasi dan dukungan dalam mengikuti perkuliahan.
10. Kepada semua, penulis mengucapkan terima kasih, turut serta do’a semoga budi baik semuanya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Amiin.
Jakarta, 4 Februari 2021
Nurhasanah
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ... iii
ABSTRAK ... iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ... vi
KATA PENGANTAR ... vii
DAFTAR ISI ... ix
DAFTAR TABEL ... xii
DAFTAR LAMPIRAN ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian ... 12
C. Rumusan Masalah ... 12
D. Kegunaan Penelitian ... 13
E. Sistematika Penulisan ... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian ... 16
1. Pengertian Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi ... 16
a. Orientasi ... 16
1) Pengertian ... 16
x
2) Tujuan ... 17
b. Mobilitas ... 19
c. Sosial ... 20
d. Komunikasi ... 21
2. Karakter Anak Tunanetra ... 22
a. Karakter ... 22
1) Pengertian Karakter ... 22
2) Nilai-nilai Karakter ... 26
3) Faktor Pembentukan Karakter ... 30
4) Upaya Pembentukan Karakter ... 31
b. Tunanetra ... 39
1) Pengertian Tunanetra ... 39
2) Faktor Penyebab Ketunanetraan ... 42
3) Ciri-ciri Anak Tunanetra ... 43
4) Klasifikasi Anak Tunanetra ... 44
5) Dampak Ketunanetraan terhadap Penyandangnya ... 46
c. Karakter Anak Tunanetra ... 48
d. Kebutuhan dan Layanan Pendidikan Anak Tunanetra ... 51
B. Hasil Penelitian yang Relevan ... 52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tujuan Penelitian ... 56
B. Tempat dan Waktu Penelitian ... 56
xi
C. Latar Penelitian ... 57
D. Metode dan Prosedur Penelitian ... 57
E. Data dan Sumber Data ... 59
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data ... 60
G. Teknik Analisis Data ... 62
H. Validitas Data ... 63
1. Kredibilitas ... 63
2. Tranferbilitas ... 63
3. Dependabilitas ... 64
4. Konfirmabilitas ... 64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian ... 65
B. Temuan Penelitian ... 76
C. Pembahasan Temuan Penelitian ... 95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 105
B. Saran ... 106 DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Nilai-nilai Karakter ... 26
Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Yayasan Raudlatul Makfufin ... 72
Tabel 4.2 Daftar Nama Guru Yayasan Raudlatul Makfufin ... 74
Tabel 4.3 Keadaan Siswa Yayasan Raudlatul Makfufin ... 76
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman Observasi Lampiran 2 Pedoman Wawancara
Lampiran 3 Pedoman Catatan Hasil Observasi Lampiran 4 Pedoman Catatan Hasil Wawancara
Lampiran 5 Pedoman Dokumentasi Pendukung (Foto dan Dokumen) Lampiran 6 Hasil Analisis Data
xiv
DAFTAR GAMBAR
Peta Letak Geografis Yayasan Raudlatul Makfufin Dokumen Sekolah Relevan
Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
Surat Keterangan Permohonan Riset/ Penelitian Foto Ruang dan Fasilitas Yayasan Raudlatul Makfufin
Foto Wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru OMSK dan Siswa Yayasan Raudlatul Makfufin
1 A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 Dari definisi tersebut terlihat bahwa pendidikan merupakan proses pengubahan sikap atau tingkah laku pada anak melalui proses pembelajaran agar anak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.
Kecerdasan intelektual tanpa diikuti dengan karakter dan akhlak yang mulia maka tidak akan memiliki nilai lebih. Maka dari itu, karakter dan akhlak adalah sesuatu yang sangat mendasar dan saling melengkapi. Karakter atau akhlak mulia harus dibangun, sedangkan membangun akhlak mulia membutuhkan sarana yang salah satunya adalah jalur pendidikan. Pendidikan bisa dilakukan dimana saja, tidak hanya disekolah atau madrasah, akan tetapi juga di rumah (keluarga), maupun di masyarakat.2 Oleh karena itu, pendidikan karakter penting ditanamkan pada anak sejak dini karena untuk membentuk pribadi pada anak agar memiliki nilai-nilai luhur bangsa atau akhlak yang mulia.
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Musrifah, “Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam”, dalam Edukasia Islamika, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 120.
Pengertian Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa dan kepribadian budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, dan watak.
Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa pendidikan karakter merupakan aspek yang sangat penting dalam mengembangkan ranah afektif pada anak untuk membentuk kepribadian budi pekerti serta akhlak mulia.
Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatakan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia pada peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang yang disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan mengaplikasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia dalam perilaku sehari-hari.3
Dengan demikian, pendidikan karakter sangat berperan besar dalam pembentukan karakter pada peserta didik karena melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu menanamkan nilai-nilai karakter dalam perilakunya.
Penanaman pendidikan karakter merupakan suatu kebutuhan untuk tuntutan di dalam memberikan budi pekerti atau moral yang baik. Pendidikan budi pekerti atau karakter sejalan dengan istilah yang diperkenalkan oleh Ernest Renan bahwa nation
3 Putri Rachamadayanti, “Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Sekolah Dasar melalui Kearifan Lokal”, dalam JPSD, Vol. 3, No. 2, 2017, h. 203-204.
and character building merupakan pembangunan karakter dan bangsa. Bangsa adalah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena adanya kesadaran akan pentingnya berkorban dan hidup bersama-sama di tengah perbedaan dan mereka dipersatukan oleh adanya visi bersama.4 Dengan demikian, pendidikan merupakan ceriman karakter bangsa dan orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral yang baik.
Pendidikan islam wajib diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang adanya kesempurnaan fisik. Anak-anak yang memiliki kelainan dan kekurangan fisik atau mental tetap mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan.
Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nur ayat 24: 61,
ٌﺝَﺮَح ِضْيِﺮَمْﻟﺍ ﻰَلَع َﻻَّﻭ ٌﺝَﺮَح ِﺝَﺮْعَ ْﻻﺍ ﻰَلَع َﻻّﻭ ٌﺝﺮَح ﻰ ٰمْع َ ْﻻﺍ ﻰَلَع َﺲْيَﻟ ْمُكِت ْوُيُ ﺑ ْنِم ﺍ ْوُلُك ْأَت ْﻥَﺍ ْمُكِسُفْنَﺍ ﻰٰٰٓلَعَﻻَّﻭ
Artinya:
“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri.”
Ayat tersebut mengandung makna kesetaraan yaitu bahwa tidak ada halangan bagi masyarakat untuk bergabung bersama dengan mereka yang berkebutuhan khusus
4 Abdul Putra Ginda Hasibuan, “Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Kelas VIII SMP Negeri 5 Tambusai”, dalam Pendidikan Rokania, Vol. I, No. 1, 2016, h. 81.
seperti orang buta, pincang, bisu, tuli atau bahkan sakit. Mereka berhak untuk makan bersama berkumpul bersama layaknya masyarakat pada umumnya.
Pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi problem besar, yaitu rendahnya mutu pendidikan dasar dan menengah, salah satunya yaitu degradasi moral di kalangan pelajar. Meskipun sejak tahun 2010 telah diberlakukan pendidikan karakter secara terintegrasi di sekolah, tapi kondisi tersebut menunjukkan proses pendidikan karakter belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal itu terutama yang terjadi di Sekolah Dasar. Karena pada jenjang ini pembentukan sikap menjadi perhatian utama dibandingkan ranah kognitif maupun psikomotorik.
Problematika pendidikan karakter di Indonesia saat ini dikarenakan tiga hal, pertama adalah hilangnya karakter dan kepribadian islami dalam dirinya. Kedua, guru mengajarkan pendidikan karakter namun masih seputar teori dan konsep saja, belum sampai pada ranah tahapan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kurangnya model atau contoh yang tepat dalam penerapan pendidikan karakter di setiap sekolah.5
Berbagai persoalan yang muncul sejumlah kasus di kalangan anak dan pelajar seperti seks bebas, perkelahian pelajar, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, kebocoran dan berbagai kecurangan dalam ujian. Fakta-fakta tersebut menegaskan betapa memprihatinkannya degradasi moral di Indonesia. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum mampu mewujudkan tujuan
5 Niya Yuliana, et.al, “Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter di Sekolah Karakter Indonesia Heritage Foundation”, dalam Pendidikan Dasar, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 17.
pendidikan nasional yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Berbagai fenomena problematis tersebut, terutama mengenai degradasi moral di kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya, hal tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa pendidikan karakter dalam praksis pendidikan nasional, utamanya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menjadi pondasi bagi jenjang pendidikan berikutnya, belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.6
Oleh karena itu, pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah adalah salah satu bentuk pada pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar awal sangat menentukan pembentukan karakter seseorang di masa depan.
Anak-anak tunanetra kehilangan masa belajar dalam hidupnya. Anak tunanetra yang memiliki keterbatasan penglihatan tidak mudah bergerak dalam interaksi dengan lingkungannya dan akan memberikan dampak terhadap perkembangan,
6 Andi Prastowo, “Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pemberdayaan Pikiran Bawah Sadar”, dalam Al-Aulad, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 54-55.
belajar, keterampilan sosial dan perilakunya. Adapun karakteristik pada anak tunanetra diantaranya, karakteristik kognitif, akademik, sosial dan emosional, dan ketunanetraan sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak.
Pertama, karakteristik kognitif, ketunanetraan secara tidak langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal bervariasi. Seorang anak tunanetra lebih mengandalkan indera peraba dan pendengaran untuk membantunya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemampuan bergerak pada anak tunanetra memerlukan pembelajaran yang mengakomodasi indera non visual dalam bergerak secara mandiri, sehingga anak tunanetra harus belajar bagaimana berjalan dengan aman dan efisien dalam lingkungan dengan kemampuan orientasi dan mobilitas. Kedua, karakteristik akademik, ketunanetraan juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akdemisnya, seperti dalam membaca dan menulis, dalam mengatasinya anak tunanetra menggunakan media huruf braille.
Ketiga, karakteristik sosial dan emosianl, karena tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar dan sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Oleh sebab itu, anak tunanetra harus mendapatkan pembelajaran yang langsung dalam melakukan komunikasi serta menggunakan alat bantu. Keempat, ketunanetraan sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak, meskipun demikian hal tersebut berpengaruh pada perilaku sehari-harinya seperti rasa curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, verbalisme pengalaman dan pengetahuan konsep abstrak mengalami
keterbatasan, perasaan rendah diri, adatan atau perilaku stereotip, dan suka berfantasi, berpikir kritis, pemberani, ketergantungan yang berlebihan.7
Maka, karakteristik anak tunanetra yang berupa potensi meliputi sikap pemberani, berpikir kristis dan suka berfantasi. Sikap tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran aktif seperti pada konsep penjumlahan sehingga meminimalisir karakteristik yang berupa kekurangan anak tunanetra. Sedangkan karakteristik yang berupa kekurangan anak tunanetra meliputi sikap mudah curiga, mudah tersinggung, rendah diri, verbalisme, adatan dan ketergantungan yang berlebihan. Sikap tersebut dipandang akan mempengaruhi sosialisasi dan adaptasi di lingkungan tunanetra (rumah, sekolah dan masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa anak tunanetra membutuhkan proses pembelajaran, sosialisasi dan adaptasi dalam mengenal dan memahami kondisi serta situasi lingkungan agar dapat mengurangi kekurangannya.
Adapun sifat rendah diri menjadi penyebab pada rasa tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri yang mengakibatkan anak tunanetra akan menarik diri dari komunitas sosial secara wajar dan mereka akan tertekan dan sering meratapi kejadian yang dialami sebagai suatu persoalan hidupnya yang tak berujung. Tekanan jiwanya ini akan berakibat mereka menjadi pendiam, pemurung, menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain di sekitarnya dan sering emosinya tidak stabil. Dalam
7 Iwan Kurniawan, “Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tunanetra di Sekolah Dasar Inklusi”, dalam Edukasi Islami Pendidikan Islam, Vol. 04, No. 8, 2015, h. 1050-1053.
kondisi demikian anak tunanetra akan semakin terpuruk beban psikologisnya dan tidak memiliki sikap hidup yang positif.
Secara umum dampak psikologis ketunanetraan akan berdampak pada perkembangan bahasa, sosial, penyesuaian dengan lingkungan, perkembangan emosionalnya serta perkembangan intelegensinya. Walaupun tidak berbeda secara kuantitas namun secara kualitas akan menunjukkan perbedaan. Jika dianalisis secara mendalam anak tunanetra juga memiliki sifat keragu-raguan dalam bertindak serta memiliki kecenderungan lebih rendah diri dan selalu curiga dengan orang lain.8
Penyebab karakteristik pada anak tunanetra tersebut disebabkan oleh kebutuhan khusus yang dialami. Selain itu, faktor ekonomi maupun dari orang tuanya sendiri, karena sebagian orang tua memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah dan juga bekerja. Artinya, sebagian kedua orang tua sama-sama bekerja. Hal ini mengakibatkan anak kurang mendapatkan perhatian.9
Lingkungan dapat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, demikian pula terhadap proses belajar anak didik. Pada hakekatnya belajar merupakan suatu proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Lingkungan merupakan suatu tempat dimana terjadi proses interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan diri sendiri pada anak tunanetra, tidak hanya berdampak kepada individu saja, namun juga berdampak pada lingkungan sosialnya baik dalam lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat.
8 Sulthon, “Pola Keberagamaan Kaum Tuna Netra dan Dampak Psikologis terhadap Penerimaan Diri”, dalam Quality, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 55.
9 Agung Riadin, et.al., “Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri (Inklusi) di Kota Palangka Raya”, dalam Anterior, Vol. 17, No. 1, 2017, h.25.
Pertama, faktor dari diri sendiri (anak tunanetra) yaitu memahami kelebihan tentang diri sendiri untuk mengenali kemampuan dan ketidakmampuannya, semakin orang mengenali dirinya semakin mudah pula dalam menerima dirinya, pengharapan yang realistik anak tunanetra mampu mengarahkan sendiri keinginan yang disesuaikan dengan pemahaman dan kemampuannya, jika lingkungan tidak memberikan kesempatan maka anak tunanetra sulit untuk mencapainya.
Kedua, faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat dari anak berkebutuhan khusus (tunanetra). Dukungan dan kasih sayang dari orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak berkebutuhan khusus, mereka memerlukan perhatian yang extra dari kedua orang tuanya sebab anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan dengan karakteristik khusus yang membedakannya dengan anak normal pada umumnya serta memerlukan pendidikan khusus sesuai dengan jenis kelainannya. Sikap penerimaan orangtua terhadap kondisi ketunanetraan yang dialami oleh anaknya merupakan salah satu faktor yang penting bagi penyesuaian diri anak tunanetra.10
Pendidikan luar biasa diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satu layanan Pendidikan khusus adalah keterampilan orientasi dan mobilitas.
Keterampilan orientasi dan mobilitas ini wajib dikuasi oleh penyandang tunanetra.
Orientasi berkaitan dengan kemampuan untuk mengetahui di mana seseorang berada
10 Gangsar Ali Daroni, et.al,, “Impact Of Parent's Divorce On Children's Education For Disability Kids”, dalam IJDS, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 1-2.
oleh dirinya sendiri. Mobilitas berkaitan dengan kemampuan untuk bergerak secara efisien dan selamat dari berbagai bahaya, seperti jatuh, atau tertabrak kendaraan.
Anak yang mengalami kelainan visual pada umumnya mengalami kesulitan dalam melakukan orientasi dan mobilitas. Oleh sebab itu, mereka perlu mendapat latihan untuk dapat bergerak lebih baik di dalam lingkungannya yang dilakukan melalui orientasi dan mobilitas.11
Ketiga, faktor lingkungan sekolah. Penyesuaian diri anak tunanetra di sekolah merupakan cara bereaksi anak tunanetra yang melibatkan respon mental dan perilaku anak tunanetra tersebut dalam usahanya untuk mengatasi tuntutan yang muncul dari dalam diri serta situasi yang ada di sekolah. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak tunanetra tentu dapat mempengaruhi penyesuaian dirinya di sekolah. Bagi anak tunanetra, memasuki sekolah atau lingkungan baru merupakan saat yang kritis.
Perasaan yang muncul dari dalam diri anak tunanetra bahwa dirinya berbeda dengan orang lain tentu akan menimbulkan reaksi-reaksi tertentu, bisa positif atau negatif.
Anak tunanetra yang mentalnya tidak siap dalam memasuki sekolah sering gagal dalam mengembangkan kemampuan sosial. Bila kegagalan tersebut dibiarkan, anak tunanetra akan menunjukkan reaksi-reaksi negatif, seperti menghindari kontak sosial, menarik diri dan apatis.12
Adapun faktor yang keempat, yaitu lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi dalam penerimaan diri pada anak tunanetra. Sikap dari masyarakat
11 Martini Jamaris, Anak Berkebutuhan Khusus, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), Cet. Ke-1, h. 154.
12 Ginanjar Rohmat, “Penyesuaian Diri Anak Tunanetra di Sekolah (Penelitian Studi Kasus di SMP Ekakapti Karangmojo dan SLB Baktiputra Ngawis)”, Skripsi Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. 28-29.
yang menyenangkan. Individu yang diterima dengan baik dapat membuatnya memiliki penerimaan diri yang baik. Harapan realistis dari masyarakat akan membuat individu dapat memahami kekurangan dan kelebihannya. Penerimaan masyarakat dapat ditunjukkan dengan tidak adanya prasangka buruk, adanya penghargaan terhadap kemampuan sosial orang lain, kesediaan individu untuk memiliki kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar.13
Salah satu sekolah luar biasa khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunanetra adalah Yayasan Raudlatul Makfufin. Yayasan Raudlatul Makfufin memberikan perhatian kepada anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan (tunanetra). Anak-anak tunanetra ketika pertama kali masuk ke yayasan ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Adapun karakter anak tunanetra yaitu terkadang tidak sesuai dengan usia anak normal lainnya. Hal ini disebabkan anak tunanetra tidak bisa bergaul dengan anak seusianya. Sehingga menyebabkan anak tunanetra menjadi kurangnya rasa percaya diri, rasa takut, pemalu, dan ketergantungan yang berlebih.
Biasanya para orang tua yang memiliki anak tunanetra akan melarang anaknya dalam melakukan hal apapun secara sendiri, sehingga menyebabkan mereka kurangnya mandiri.
Di Yayasan Raudlatul Makfufin sendiri dalam pembentukan karakter anak tunanetra yaitu yayasan ini memiliki pelajaran khusus untuk membentuk karakter dari anak tunanetra. Adapun pelajaran khususnya yaitu Orientasi Mobilitas Sosial dan
13 Tika Ervina, “Perbedaan Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Netra sejak lahir dan setelah lahir (Penelitian Tindakan pada Siswa Penyandang Disabilitas Netra sejak lahir dan setelah lahir UPT PPSDN Penganthi Temanggung)”, Skripsi Ilmu Pendidikan, (Semarang: Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2019), h. 20.
Komunikasi (OMSK). Pelajaran ini hanya ada di sekolah khusus tunanetra yang bertujuan untuk memperkuat karakter anak tunanetra.14
B. Fokus dan Subfokus Penelitian
Mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh serta keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penelitian ini dibatasi hanya pada Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi (OMSK) dalam Membentuk Karakter Anak Tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin.
Subfokus penelitian ini adalah :
1. Karakter anak tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin.
2. Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin.
3. Faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan subfokus penelitian, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana karakter anak tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin?
14 Ade Ismail, Kepala Yayasan Raudatul Makfufin, Wawancara Pribadi, Serpong, 21 Juni 2020.
2. Bagaimana Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Pembelajaran Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin?
D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi setelah melakukan penelitian. Adapun kegunaan/ manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Kegunaan/ Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu mengenai pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter pada anak tunanetra di lembaga formal, nonformal, maupun informal.
2. Kegunaan/ Manfaat Praktis a) Bagi Peneliti
Dengan penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan yang baru kepada peneliti, serta dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran mengenai pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra kepada peneliti untuk masa yang akan datang.
b) Bagi Lembaga Pendidikan
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tentang pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK) dalam membentuk karakter anak tunanetra.
c) Bagi Peneliti Lain
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian yang dilakukan.
E. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulisan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :
Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang didalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.
BAB I yaitu Pendahuluan, akan dikemukakan mengenai latar belakang, fokus dan subufokus penelitian, rumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II berisi pengembangan pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi (OMSK), karakter anak tunanetra, dan hasil penelitian yang relevan.
BAB III dalam bab ini berisi mengenai jenis-jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, Teknik pengumpulan data.
BAB IV dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap pengembangan pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi dalam membentuk karakter anak tunanetra, yaitu berupa data penelitian, sejarah singkat, struktur organisasi, dan proses serta mekanisme dalam pengembangan pembelajaran orientasi mobilitas sosial dan komunikasi dalam membentuk karakter anak tunanetra yang dilakukan guru OMSK di Yayasan Raudlatul Makfufin.
BAB V merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dan saran.
Kemudian pada akhir penelitian, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.
16
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 1. Pengertian Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi
Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami hambatan baik dari segi fisik maupun mental. Ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus diantaranya tunarungu, tunanetra, tunagrahita, autism, tunalaras dan lain sebagainya. Salah satu jenis anak berkebutuhan khusus adalah anak tunanetra.
Tunanetra merupakan kondisi seseorang yang mengalami gangguan ataupun hambatan pada indera penglihatan. Karena ketidak mampuannya untuk melihat maka pada gerakan berpindah tempat atau yang dinamakan orientasi dan mobilitas. Orientasi merupakan kemampuan dalam mengenali lingkungan dan hubungan dengan dirinya baik itu secara waktu maupun ruang sedangkan mobilitas merupakan kemampuan untuk bergerak ataupun berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai keinginan.15
a. Orientasi 1) Pengertian
15 Ayu Ermayuni dan Fatmawati, “Peranan Teman Sebaya dalam Orientasi dan Mobilitas Lingkungan Sekolah pada Siswa Tunanetra di SMKN 7 Padang”, dalam Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus, Vol.
7, No. 1, 2019, h. 190.
Orientasi adalah proses penggunanaan indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri dalam hubungannya dengan obyek lain di sekitarnya.16
Seorang tunanetra untuk dapat mengorientasikan dirinya dalam lingkungan, maka orang tunanetra tersebut harus lebih faham betul konsep dirinya. Apabila ia dapat dengan baik mengetahui konsep dirinya,
orang tunanetra akan mudah membawa dirinya memasuki lingkungan atau membawa lingkungan kearah dirinya.
Orientasi juga terdapat proses penggunaan indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi dari hubungannya dengan obyek-obyek penting dalam lingkungannya. Proses penggunaan indera yang masih berfungsi diartikan sebagai cara penggunaan indera dalam menyalurkan rangsangan informasi sehingga dapat sampai dan diolah oleh otak menjadi sesuatu informasi yang berguna dalam menetapkan posisi diri. Informasi yang berfungsi artinya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dapat menerangkan tentang posisi seseorang.17
2) Tujuan
Tujuan orientasi mencakup posisi dirinya, posisi tujuannya dan cara mencapai posisi tujuan.
16 Sutriyaningsih, “Meningkatkan Kemampuan Berorientasi dan Mobilitas dengan Peta Timbul bagi Anak Tunanetra Kelas I di SLB ABC Swadaya Kendal Tahun Pelajaran 2009/ 2010”, Skripsi Pendidikan Luar Biasa, (Surakarta: Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 8. t.d.
17 Deni Cahya Padholi, “Peningkatan Kemampuan Orientasi Dan Mobilitas Anak Tunanetra Kelas V di SLB A Yaketunis Yogyakarta Melalui Kegiatan Pramuka”, Skripsi Pendidikan Luar Biasa, (Yogyakarta:
Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 21-22. t.d.
a) Mengetahui posisi diri
Tunanetra yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam berorientasi, ia akan mampu menghubungkan dirinya dengan lingkungannya lebih banyak, mampu memasuki lingkungannya dan mampu menilai lebih realistis terhadap lingkungan. Dengan orientasi orang tunanetra mampu bergerak lebih efektif, yang berarti gerakannya lebih cepat, tepat, sesuai dengan kebutuhan. Gerakan yang didasarkan oleh orientasi adalah gerakan yang bertujuan (tidak coba-coba).
b) Mengetahui posisi diri dan lingkungan
Sering ditemukan seorang tunanetra yang mempunyai kecurigaan yang tinggi bila dibandingkan dengan orang awas. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan posisi dirinya di lingkungan serta ketidak tahuan reaksi lingkungan terhadap dirinya. Misalnya seorang tunanetra yang berkomunikasi dengan orang lain, dia tidak bisa menangkap reaksi yang dilakukan oleh gerakan tubuh seperti gerak wajah (mimik) sewaktu berbicara atau situasi di sekitar kejadian.
c) Mengetahui cara dan teknik mencapai tujuan dan objek
Orientasi memberi arti terhadap perjalanan seorang tunanetra. Sebab di dalam orientasi mengandung proses mencari jawaban tentang posisi diri, posisi tujuan atau objek dan cara untuk sampai ke tujuan atau objek. Dalam mencari jawaban pertanyaan tersebut terdapat proses berfikir (cognitive process). Proses kognitif adalah suatu lingkaran proses yang terangkai dan
di dalamnya terdiri dari lima proses yaitu proses persepsi, proses Analisa, proses seleksi, proses rencana, proses pelaksanaan.
Everett hil & Purvvis Ponder (1979) menjelaskan interaksi kelima langkah proses kognitif tersebut adalah sebagai berikut:
a. Persepsi (perception). Persepsi adalah suatu proses mengasimilasi data dari lingkungan yang diterima melalui indera yang masih berfungsi.
b. Analisa (analysis). Analisa adalah proses mengorganisasi dan memperhitungkan data yang diterima dalam kategori-kategori menurut konsistensinya, ketergantungannya, keterbatasannya, sumbernya jenis inderanya dan intensitasnya.
c. Seleksi (selection). Seleksi adalah proses memilih data yang telah dianalisa dan yang paling memenuhi kebutuhan orientasi dalam situasi lingkungan saat itu.
d. Rencana (planning). Rencana adalah suatu proses menentukan bentuk dan urutan tingkah laku berdasarkan data yang telah dipilih dan yang paling sesuai dengan situasi saat itu.
e. Pelaksanaan (execution). Pelaksanaan adalah proses melaksanakan bentuk dan urutan tingkah laku yang sudah direncanakan.
b. Mobilitas
Mobilitas merupakan suatu kemampuan, kesiapan dan mudahnya bergerak. Bergerak disini tidak hanya diartikan berjalan tetapi lebih luas dari itu. Bergerak bisa dari suatu posisi ke posisi yang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain. Bergerak dari suatu posisi ke posisi lain misalnya
menggerakkan tangan dari posisi mengenggam ke posisi tangan terbuka atau dari posisi badan duduk ke posisi badan berdiri. Bergerak dari suatu tempat ke tempat lain mengandung arti adanya perpindahan. Misalnya seorang berjalan dari ruang tamu ke ruang makan dan sebagainya.
Mobilitas adalah gerakan yang bertujuan yang berarti ada proses mempelajari dan menilai lingkungan. Dari proses mempelajari dan menilai lingkungan akan ditemukan pengetahuan dan pengalaman baru.
Mobilitas merupakan suatu kemampuan untuk bergerak dalam lingkungannya dengan selamat dan semandiri mungkin. Semandiri mungkin artinya tidak terlalu banyak meminta bantuan orang lain dan berusaha untuk mengurangi bantuan orang lain. Dalam melakukan mobilitas orang tunanetra ada yang menggunakan alat bantu ada juga yang tanpa alat bantu.18
c. Sosial
Perkembangan sosial merupakan suatu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat diartikan juga sebagai proses belajar untuk menyesuaian diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi yang kemudian menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama.
Sedangkan pengembangan sosial dalam program OMSK (Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi) diartikan sebagai gambaran interaksi dengan lingkungan sekitar serta perilaku manusia dalam melakukan aktivitas sehari- hari secara mandiri tanpa banyak di bantu orang lain.
18 Yosfan Azwandi dan Jon Efendi, Orientasi dan Mobilitas, (Padang: UNP Padang, 2004), h. 6- 14.
Tujuan dari pengembangan sosial program OMSK (Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi) agar anak tunanetra mampu beradaptasi, berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat luas, serta dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.
d. Komunikasi
Komunikasi pada tunanetra lebih berfokus pada bagaimana anak tunanetra dapat berkomunikasi dengan baik dan benar secara ekspresif kepada orang lain.
Hal ini bukannya anak tunanetra tidak dapat melakukannya, tetapi mereka tidak mendapatkan contoh latihan dari lingkungan karena ketunaannya.
Anak tunanetra mengandalkan indera pendengarannya untuk menyerap informasi dan menambah suku kata tanpa mengetahui keadaannya. Sehingga bimbingan dari orang-orang terdekat sangat di butuhkan guna mengurangi salah penafsiran pada komunikasi anak tunanetra.
Penerapan program OMSK (Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi) yang mana pengembangan kemampuan komunikasi anak tunanetra bertujuan untuk melatih bersikap baik dan benar dalam berkomunikasi lisan, tulisan baik menggunakan alat komunikasi manual (braille) dan elektronik.19
19 Dinda Diah Vitasari, “Program Kekhususan OMSK (Orientasi Mobilitas Sosial Dan Komunikasi) Dalam Mengembangkan Konsep Lingkungan Pada Anak Tunanetra di SDLB Negeri Patrang Jember”, Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam, (Jember: Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), h. 35-41. t.d.
2. Karakter Anak Tunanetra a. Karakter
1) Pengertian Karakter
Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “karasso”, berarti
“cetak biru”, “format dasar”, “sidik” seperti dalam sidik jari. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pengertian mengenai karakter itu sendiri. Secara harfiah Hornby dan Parnwell mengemukakan karakter artinya “kualitas mental atau moral”, kekuatan moral, nama atau reputasi”.20
Orang berkarakter orang yang berkepribadian , berperilaku, bersifat, bertabiat atau berwatak. Makna seperti itu menunjukkan bahwa karakter identik dengan keperibadian atau akhlak.21
Menurut Lickona, mengemukakan bahwa karakter adalah a reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way (Lickona, 1991:
51), yang berarti suatu watak terdalam untuk merespons situasi dengan cara yang menurut moral baik. Selanjutnya, Lickona menambahkan, “Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior”. (Artinya: Karakter tersusun ke dalam tiga bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral, dan berilaku bermoral). Jadi, karakter terdiri atas tiga bagian pokok yang saling
20 Abdul Jalil, “Karakter Pendidikan untuk Membentuk Pendidikan Karakter”, dalam Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, 2012, h. 182.
21 Samrin, “Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai)”, dalam Al-Ta’dib, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 122-123.
berhubungan, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral dan perilaku bermoral.22
Istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, akhlak dan nilai yang berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi “positif”
bukan netral. Oleh karena itu, pendidikan karakter secara lebih luas dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.23
Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat.24
Karakter adalah bawaan lahir dan merupakan fitrah manusia. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak adab atau ciri kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai nilai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak. Seseorang akan
22 Dharma Kesuma, et.al., Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung: PT.
REMAJA ROSDAKARYA, 2013), Cet. Ke- 4, h. 21.
23 Nur Ainiyah, “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam”, dalam Al-Ulum, Vol. 13, No. 1, 2013, h. 27.
24 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama &
Budaya Bangsa, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), Cet. ke- 1, h. 44.
disebut berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.
Kepribadian seseorang, dapat menentukan cara berpikir dan bertindak berdasarkan motivasi terhadap kebaikan dalam menghadapi segala situasi.
Cara berfikir dan bertindak tersebut, telah menjadi identitas diri dalam berbuat dan bersikap sesuai dengan yang menurut moral itu baik, seperti halnya: jujur, bertanggung jawab dan mampu bekerjasama dengan baik.25
Pembentukan karakter dengan nilai agama dan norma bangsa sangat penting karena dalam Islam, antara akhlak dan karakter merupakan satu kesatuan yang kokoh seperti pohon dan menjadi inspirasi keteladanan akhlak dan karakter adalah Nabi Muhammad saw. Pilar-pilar pembentukan karakter Islam bersumber pada hal-hal berikut.
1. Al-Quran. Firman Allah swt. Merupakan pilar penting dalam Islam. Buah
“Pohon” Islam yang berakarkan akidah yang benar terhunjam di hati dan teraplikasi dalam kehidupan nyata dan berdaunkan Syariah yang membudaya dalam ritual ibadah dan sosial bersifat muamalah.
2. Sunnah atau hadis. Seperti sabda Rasulullah saw : “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia” (H.R. Ahmad) dan hadis : “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya” (H.R. Tarmizi).
25 Sofyan Mustoip, et.al., Implementasi Pendidikan Karakter, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h. 38-39.
3. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mahatma Gandi pernah menyatakan: “Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya. Tapi, ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad; serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya”.26
Betapa pentingnya akhlak atau karakter dalam pendidikan sehingga Allah mengabadikannya dalam QS. Al-Qalam: 68: 4.
ٍمْيِظَع ٍقُلُخ ﻰٰلَعَﻟ َكَّنِﺍ َﻭ
Artinya :
“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur”.27
Ayat di atas menjadi kunci betapa Allah swt sangat menekankan kepada umat manusia untuk memiliki akhlak atau karakter dalam berbagai aspek kehidupan, hal ini terbukti dengan diutusnya Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan dalam praktik kehidupan beliau dikenal sebagai berakhlak yang agung dan pantas untuk diteladani.28
Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter adalah bawaan lahir dan fitrah yang ada pada diri seseorang
26 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, loc. cit.
27 Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya Kementrian Agama RI, h. 564.
28 Agus Setiawan, “Prinsip Pendidikan Karakter dalam Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji)”, dalam Dinamika Ilmu, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 4.
berupa watak, kepribadian, akhlak dan etika seperti kejujuran dan sifat-sifat yang ada pada individu itu sendiri.
2) Nilai-nilai Karakter
Karakter itu dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pendidikan nilai.
Pendidikan nilai ini akan membawa kepada pengetahuan nilai, selanjutnya pengetahuan nilai akan membawa ke dalam proses internalisasi nilai tersebut.
Pada proses internaslisasi nilai inilah akan mendorong seseorang mewujudkannya dalam bentuk tingkah laku dan akhirnya terjadi pengulangan yang sama pada tingkah laku tersebut. Hal inilah yang menghasilkan karakter atau watak seseorang.
Pendidikan karakter mempunyai tujuan penanaman nilai dalam diri peserta didik dan pembaharuan dalam tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Hasil pendidikan yang diharapkan, yiatu pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta secara utuh dan terpadu.
Menurut Hasan (2010, 9-10), nilai-nilai karakter yang teridentifikasi dari sumber-sumber pendidikan karakter sebagai berikut.
Tabel 2.1
Nilai deskripsi karakter
No. Nilai Deskripsi
1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran yang dianutnya, toleransi
terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur Perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan.
5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh- sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya.
6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam meyelesaikan tugas- tugasnya.
8. Demokratis Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan
Cara berpikir , bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air
Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat serta mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/
Komunikatif
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan kepada dirinya.
16. Peduli Lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab
Sikap dan tindakan seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya) negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk keberhasilan mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, sekolah perlu mengembangkan dan membudayakannya dengan
melibatkan semua komponen yang ada, termasuk mengintegrasikan dalam setiap mata pelajaran.29
3) Faktor Pembentukan Karakter
Adapun faktor pembentukan karakter pada peserta didik yaitu, pola asuh orang tua, lingkungan sosial, lingkungan belajar dan konsep diri sangat erat berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah.
1. Keluarga (Pola Asuh Orang tua)
Pendidikan pertama anak adalah keluarga, bahkan tanggung jawab orang tua tidak terbatas pada pendidikan formal. Keluarga sebagai pendidikan awal memberikan dasar-dasar karakter dan nilai-nilai luhur yang mampu dibentuk sejak dini. Lingkungan keluarga itu sendiri terdiri atas orang tua (ayah dan ibu) dan anak.
2. Lingkungan Sosial
Perkembangan manusia hidup tidak dapat terlepas dari dimensi sosial.
Lingkungan sekitar berupa pola interaksi terhadap sesama, kelompok maupun kepentingan masyarakat sebagai kepentingan bersama.
Lingkungan tempat manusia hidup, berkembang, dan berinteraksi merupakan lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan sosial itu ada yang diterima secara langsung dan ada yang tidak langsung. Pengaruh secara langsung, seperti pergaulan sehari-hari dengan orang lain, keluarga, teman, kawan sekolah dan sebagainya. Pengaruh tidak langsung, melalui
29 Nurul Hidayah, “Penanaman Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar”, dalam Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 193-197.
radio dan televisi, dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, surat- surat kabar dan sebagainya.
Lingkungan mampu membentuk manusia sebagai proses belajar.
Dalam lingkungan yang buruk seseorang mampu berbuat dan terdorong untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sebaliknya dengan lingkungan pembelajaran yang baik akan mampu memberikan pembelajaran yang baik serta mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan.
3. Lingkungan Belajar
Perkembangan peserta didik dalam belajar sangat dipengaruhi lingkungan sebagai tempat pembelajaran berlangsung. Dalm pendidikan formal, lingkungan belajar peserta didik dapat dilakukan pengondisian dan manipulasi untuk memperoleh hasil belajar yang diinginkan serta mampu menghadirkan kondisi nyata pembelajaran sehingga menghasilkan pengalaman belajar.
4. Konsep Diri (Self Concept)
Konsep diri itu terbentuk karena ada interaksi individu dengan orang- orang disekitarnya. Apa yang dipersepsikan individu lain tentang dirinya tidak terlepas dari struktur, peran dan status sosial yang disandang individu. Oleh karena itu, gambaran sosial dapat terwujud dalam kemampuannya bersosialisasi dan menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya, baik disekolah maupun di masyarakat.30
30 Suparno, “Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Karakter Smart Siswa di Sekolah Islam Terpadu”, dalam Pendidikan Karakter, Vol. 8, No. 1, 2018, h. 65-66.
4) Upaya Pembentukan Karakter
Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Artinya kegagalan institusi keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter anak bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah.
Megawangi menyebutkan, bahwa untuk membentuk karakter anak, ada tiga kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Kelekatan Psikologis dengan Ibunya
Merupakan dasar penting dalam pembentukan karakter anak karena aspek ini berperan dalam pembentukan dasar kepercayaan kepada lain pada anak. Kelekatan ini membuat anak merasa diperhatikan dan menumbuhkan rasa aman dan rasa percaya. Kelekatan diusia awal, yang biasanya terbangun antara ibu dan anak, akan menjadi ikatan emosional yang erat antara ibu dan anak hingga dewasa.
2. Rasa Aman
Yaitu kebutuhan anak akan lingkungan yang stabil dan aman.
Kebutuhan ini sangat penting bagi pembentukan karakter anak karena lingkungan yang berubah-ubah akan membahayakan perkembangan emosi anak. Kekacauan emosi anak yang terjadi karena tidak adanya rasa
aman, misalnya anak berkesulitan makan, hal ini akan tidak kondusif untuk pertumbuhan anak yang optimal.
3. Kebutuhan akan stimulasi fisik dan mental
Merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter anak. Tentu saja hal ini membutuhkan perhatian yang besar dari orang tua dan reaksi timbal balik antara ibu dan anaknya. Dengan demikian, seorang ibu yang sangat perhatian (yang diukur dari seringnya ibu melihat mata anaknya, mengelus, menggendong dan berbicara kepada anaknya) terhadap anaknya yang berusia di bawah enam bulan akan mempengaruhi sikap bayinya sehingga menjadi anak yang gembira, antusias mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya anak yang kreatif.
Bilamana ketiga kebutuhan dasar anak terpenuhi, maka selanjutnya diperlukan adanya pola asuh yang dapat memaksimalkan pembentukan karakter anak. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan (karakter) pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya.
Hurlock Hardy & Heyes menyebutkan ada tiga jenis pola asuh, yaitu :
1. Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh dan tidak boleh bertanya. Ciri- ciri dari pola ini; kekuasaan orang tua yang dominan; anak tidak diakui sebagai pribadi; kontrol pada tingkah laku anka sangat ketat; orang tua menghukum anak jika anak tidak patuh.
2. Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang ia inginkan. Pola ini memiliki ciri; ada kerja sama antara orang tua dan anak; anak diakui sebagai pribadi; ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua; ada kontrol orang tua yang tidak kaku. Pola asuh ini lebih kondusif dalam pendidikan anak.
3. Pola asuh permesif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Ciri pola ini yaitu; dominasi pada anak; sikap longgar atau kebebasan dari orang tua; tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua; kontrol dan perhataian orang tua sangat kurang. Pola asuh ini cenderung memberikan kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak.
Pola asuh dan ciri-ciri diatas, maka dapat dipahami bahwa jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak menentukan keberhasilan pendidikan orang tua.
Karena adanya kekeliruan orang tua dalam mendidik anaknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi pada anak sehingga akan berakibat pada pembentukan karakter buruk pada anak. Bentuk perilaku orang tua seperti ini yaitu:
1. Kurangnya menunjukkan ekspresi kasih sayang.
2. Kurang meluangkan waktu secukupnya pada anaknya.
3. Bersikap kasar secara verbal, misalnya menyindir, mengecilkan anak dan berkata-kata kasar.
4. Bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit dan memberikan hukuman badan lainnya.
5. Terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif sejak dini.
6. Tidak menanamkan “good character” kepada anak.
Dampak atas kesalahan dalam menerapkan pola asuh akan menghasilkan anak-anak yang mempunyai kepribadian bermasalah atau mempunyai kecerdasan emosi rendah. Bentuk perilaku anak yang dapat muncul, yaitu :
1. Anak menjadi acuh tak acuh, tidak butuh orang lain dan tidak dapat menerima persahabatan karena sejak kecil mengalami kemarahan dan gangguan emosi negatif lainnya.
2. Aspek pembentukan anak menjadi tidak responsif, dimana anak yang ditolak akan tidak mampu memberikan cinta kepada orang lain.
3. Berperilaku agresif, anak dengan mudah selalu terdorong untuk menyakiti temannya, baik secara verbal maupun fisik.
4. Anak menjadi minder, merasa tidak berharga dan tidak berguna.
5. Selalu berpandangan negatif pada lingkungan sekitarnya, seperti rasa tidak aman, khawatir, curiga dengan orang lain dan merasa orang lain sedang mengkritiknya.
6. Ketidakstabilan emosional, yiatu tidak toleran atau tidak tahan terhadap stres, mudah tersinggung, dan mudah marah.
7. Hilangnya keseimbangan antara perkembangan emosional dan intelektual, sehingga dapat memicu kenakalan, mudah tawuran.
8. Orang tua yang tidak memberikan rasa aman dan terlalu menekan anak, akan membuat anak merasa tidak dekat.
Aspek lain dalam institusi pendidikan keluaraga yang perlu mendapat perhatian ibu, tentu tak terkecuali peran bapak, khususnya pada usia pra sekolah dalam pembentukan karakter anak, adalah :
1. Membiasakan kejujuran.
2. Membiasakan keadilan.
3. Membiasakan meminta izin.
4. Membiasakan berbicara dengan baik.
5. Membiasakan makan dan minum dengan baik.
6. Membiasakan bergaul dengan baik.
7. Membiasakan kasih sayang.
8. Membiasakan penghargaan.
Muhammad Fauzil Adhim, menyebutkan beberapa hal yang patut dipertimbangkan oleh orang tua dalam membentuk karakter anak, sebgai berikut :
1. Hal usia anak
Ada perilaku anak yang kadang dianggap sebagai kenakalanm tetapi merupakan perilaku yang wajar dilakukan oleh anak, perilaku tersebut merupakan hak usia anak yang perlu diharagai. Justru dengan mengharagai anak dalam bentuk memberikan kasih sayang yang tulus,