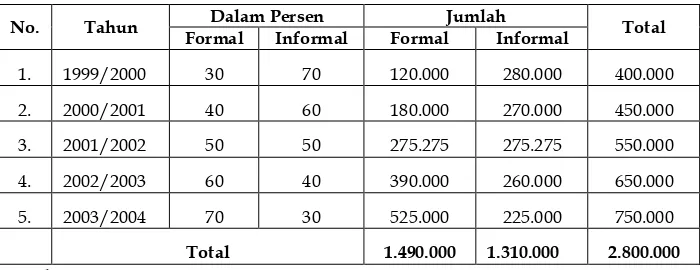DAN PERKEMBANGANNYA
Diterbitkan Oleh
CV. R.A.De.Rozarie
(Anggota Ikatan Penerbit Indonesia)
Hukum Ketenagakerjaan Dan Perkembangannya
© Mei 2014
Eklektikus: Mahdi Bin Achmad Mahfud, S.H., M.Kn. Vinaricha Sucika Wiba, S.H.
Editor: L S Resignata
Master Desain Tata Letak: Eko Puji Sulistyo
Angka Buku Standar Internasional: 9786021447499 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan
Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau
direproduksi dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari CV. R.A.De.Rozarie kecuali dalam hal
penukilan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah dengan
menyebutkan judul dan penerbit buku ini secara lengkap
sebagai sumber referensi.
Terima kasih
i
PRAKATA
Di kalangan ilmuwan hukum, menghasilkan karya tanpa
memposisikan diri sesuai bidang keilmuannya ibarat berjalan
di atas lumpur. Dalam karya ini, kami ingin memberi
pembahasan holistik terkait eksistensi Tenaga Kerja Indonesia
yang berada di negara lain.
Karya yang bersifat pengantar ini setidaknya mampu
melengkapi referensi ilmiah buku hukum ketenagakerjaan
lainnya. Sehingga para masyarakatpun memiliki paradigma
terhadap apa yang berkorelasi dengan hukum ketenagakerjaan.
Apalagi jika kita membaca pasal dramatis yaitu Pasal 27 ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 “Tiap
-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Mengutip pepatah Jerman “
mit einem lachenden und
weinenden auge” –
dengan satu mata yang tertawa dan mata
yang lain menangis. Seperti itulah yang kami rasakan sebagai
penulis. Selamat membaca…
Malang, April 2014
ii
SENARAI ISI
PRAKATA
i
SENARAI ISI
ii
BAB I
Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum
1
BAB II
Filsafat Hukum Perburuhan
12
BAB III
Teori-Teori Hukum Perburuhan
23
BAB IV
Hubungan Kerja
45
BAB V
Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama
57
BAB VI
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
76
BAB VII
Organisasi Buruh
97
BAB VIII
Perlindungan Buruh Migran
109
BAB IX
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
123
BAB X
Dasar-Dasar Dan Kelembagaan Keselamatan Dan Keseha-
tan Kerja
139
1
Bab i
Ilmu hukum dan filsafat hukum
Sebelum kita berangkat ke filsafat hukum perburuhan, terlebih dahulu kita akan mengupas makna dari hukum.
A.Pengertian Hukum
Menurut pakar hukum, Bellefroid mengatakan bahwa
“hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang
ada pada masyarakat tersebut“. Sementara di dalam Ensiklopedia,
“Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat”.1
Menurut pendapat penulis, hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa yang bersifat mengikat dan memaksa, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta ketenteraman.
Ilmu-ilmu yang membantu ilmu hukum yaitu:
N Sejarah hukum, salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antar hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Sejarah hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah hukum erat terkait dengan perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarah sosial.
N Politik hukum, salah satu bidang studi hukum yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.
N Perbandingan hukum, salah satu bidang studi hukum yang mempelajari dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dua atau lebih sistem hukum antar negara maupun dalam negara sendiri.
N Antropologi hukum, salah satu bidang studi hukum yang mempelajari pola-pola sengketa penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana
2
maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.
N Filsafat hukum, salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat dari hukum, objek dari filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam.
N Sosiologi hukum, salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.
N Psikologi hukum, salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia.
Ilmu hukum positif, ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup berlaku pada waktu sekarang. 2
B. Tata Hukum Di Indonesia
Tata hukum di Indonesia meliputi:
1. Sistem Hukum
Macam-macam sistem hukum:
o Sistem hukum Eropa Kontinental, o Sistem hukum Anglo Saxon, o Sistem hukum adat.
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).
Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.3
2 http://pengantarhukum.indonetwork.co.id/.
3
2. Hukum Tata Negara di Indonesia* Hukum perdata Indonesia,
* Hukum pidana Indonesia,
* Hukum tata negara Indonesia,
* Hukum dagang,
* Hukum agraria,
* Hukum pajak,
* Hukum acara pengadilan,
* Hukum administrasi negara,
* Hukum adat,
* Hukum Islam.
C.Klasifikasi Hukum4 1. Berdasarkan Sifatnya
E Utrecht dalam buku fenomenalnya berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” (1953) telah membuat suatu batasan. Utrecht memberikan batasan hukum bahwa hukum itu adalah himpunan peratura-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat itu. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum itu, maka peraturan kemasyarakatan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa.
Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberi sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.
2. Berdasarkan Fungsinya
Fungsi hukum ialah untuk mengatur, sebagai petugas, serta sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban. Yang akan diatur oleh hukum ialah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, adanya sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas, bersifat memaksa, dan peraturan
4
hukum diadakan oleh badan-badan resmi. Hukum yang diciptakan penguasa memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai.
Untuk menjelaskan tujuan ini terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang tujuan hukum yaitu teori etis (tujuan hukum untuk mencapai keadilan), teori utilitas (tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan manusia), teori campuran (tujuan hukum untuk mencapai ketertiban (yang utama) dan keadilan yang berbeda-beda isinya dan ukurannya menurut masyarakat dan zaman. Sedangkan tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”.
Tujuan hukum intinya menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, keadilan, ketertiban, ketenteraman dan kebahagiaan setiap insan manusia, maka dari hal tersebut dapat diketahui apa sebenarnya fungsi dari hukum itu sendiri.
Secara umum fungsi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yaitu:
þ Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
þ Sarana mewujudkan keadilan sosial.
þ Alat penggerak pembangunan nasional. þ Alat kritik.
þ Sarana penyelesaian sengketa atau perselisihan.
3. Berdasarkan Isinya
5
bidang hukum dimana subjek hukum bersangkutan dengan subjek hukum lainnya, yang dimaksud ialah jika seseorang melanggar atau melakukan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman. Hukum publik ialah termasuk hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana.
4. Berdasarkan Waktu Berlakunya
Hukum berdasarkan waktu berlakunya berdasarkan hukum positif atau tata hukum dengan nama asing disebut ius constitutum
sebagai lawan kata dari pada ius constituendum yakni perbuatan hukum yang berdampak positif bagi masyarakat, seperti seseorang memliki keinginan untuk mencuri atau merampok, tetapi seseorang tersebut tidak jadi mencuri atau merampok karena mengetahui adanya hukuman atau sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut sebaliknya ius constituendum yakni hukum negatif ialah seseorang tersebut telah mengerti adanya hukuman atau sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan tersebut tetapi seseorang tersebut seakan tidak mempedulikan hal tersebut, seperti korupsi. Serta hukum antar waktu yakni hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku pada masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.
5. Berdasarkan Bentuknya
Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara:
a. Hukum tertulis
Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan suatu negara, contohnya:
Ω UUD NRI 1945,
Ω Peraturan pemerintah,
Ω Peraturan presiden,
Ω Peraturan daerah.
6
tujuan kodifikasi dari hukum tertulis ialah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, kesatuan hukum. Berikut ialah contoh hukum yang sudah dikodifikasikan:
P Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (1 Mei 1848), P Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848), P Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918).
b. Hukum tidak tertulis
Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan), disebut hukum adat
(adat law).
Perhatian dari luar terhadap hukum adat, bangsa Indonesia tidak lepas dari kontak dengan bengsa-bangsa lain. Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari perkataan Belanda “adatrecht”.
Istilah “adat recht” ini ialah untuk pertama kali dipakai dan merupakan ciptaan Snouck Hurgronje kemudian dipakai oleh pengarang-pengarang lain. Tetapi kesemuanya ini memakainya masih secara sambil lalu dan hanya untuk hukum Indonesia asli, terlepas dan akibat pengaruh-pengaruh dari luar, seperti pengaruh agama.
6. Berdasarkan Waktu Berlakunya
Hukum nasional
Hukum yang berlaku dinegara yang bersangkutan, misalnya hukum nasional Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum positif tertinggi.
Hukum internasional
Hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam, pergaulan internasional.
Hukum asing
Hukum yang berlaku dinegara lain, misalnya bagi bangsa Indonesia adalah hukum yang berlaku di Malaysia, Amerika Serikat, Australia.
Hukum gereja
7
D.Sumber-Sumber Hukum Di Indonesia
Sumber hukum adalah merupakan tempat diketemukannya hukum. Sumber hukum juga dapat diartikan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber hukum dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu segi materiil dan segi formil.5
1. Sumber hukum materiil
Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas:
a Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, a Agama,
a Kebiasaan,
a Politik hukum dari pemerintah.
Sumber hukum materiil yaitu tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.
2. Sumber hukum formil
Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Sumber hukum formil antara lain:
hUndang-undang (statute)
Suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.
hKebiasaan (custom)
Perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum.
hKeputusan hakim (yurisprudensi)
Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda dahulu adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang
8
disingkat A.B. (ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia).
hTraktat (treaty)
Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
hPendapat sarjana hukum (doktrin)
Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.
E. Fungsi Dan Tujuan Hukum
Dimana ada masyarakat di sana ada hukum (ubi societas ibi ius). Hukum ada pada setiap masyarakat, kapan pun, di manapun, dan bagaimanapun keadaan masyarakat tersebut. Artinya eksistensi hukum bersifat sangat universal, terlepas dari keadaan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakatnya (hukum juga memiliki sifat khas, tergantung dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam sebuah komunitas).6
Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum, terdapat 2 (dua) paham mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat:
Pertama, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Maka yang tampak, hukum bertugas mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini dipelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari Jerman yang diintrodusir oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861).
Kedua, menyatakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham ini dipelopori oleh ahli hukum dari Inggris, Jeremy Bentham (1748-1852), untuk kemudian dipopulerkan oleh hakim Amerika Serikat
dengan konsepsi “hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana
9
untuk mengadakan perubahan masyarakat” (law as a tool of social engineering).
Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur ilmu hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 (tiga) teori:7
j Teori etis
Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya ethica dan Rhetorika, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.
Mengenai isi keadilan, Aristoteles membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan yaitu justitia distributive (keadilan distributif) dan justitia commulative (keadilan kumulatif). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing-masing. Makna keadilan bukanlah persamaan melainkan perbandingan secara proporsional. Adapun keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan. Keadilan terwujud ketika setiap orang diperlakukan sama.
j Teori utilitis
Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah
Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the Morals and Legislation”. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.
10
j Teori campuranMenurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.
F. Hubungan Hukum Dengan Filsafat Hukum
Filsafat hukum adalah filsafat yang objeknya khusus hukum. Pokok kajian filsafat hukum terbagi menjadi:
d Ontologi hukum yaitu ilmu tentang segala sesuatu (merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum, seperti konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral).
d Aksiologi hukum yaitu ilmu tentang nilai (merefleksi isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran).
d Ideologi hukum yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang mengangkut cita manusia (merefleksi wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi kaidah hukum, pranata hukum, sistem hukum dan bagian-bagian dari sistem hukum).
d Teleologi hukum yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri (merefleksi makna dan tujuan hukum).
d Epistemologi yaitu ilmu tentang pengetahuan hukum (merefleksi sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia).
d Logika hukum yaitu ilmu tentang berpikir benar atau kebenaran berpikir (merefleksi atran-aturan berpikir yuridik dan argumentasi yuridik, bangunan logikal serta struktur sistem hukum).
11
Pokok kajian yurisprudens yaitu terbagi menjadi:
Logika hukum,
Ontologi hukum (penelitian tentang hakikat dari hukum), Epistemologi hukum (ajaran pengetahuan),
12
BAB II
FILSAFAT HUKUM PERBURUHAN
A.Latar Belakang Filsafat Hukum Perburuhan
Ilmu hukum meliputi tiga bagian,yaitu dogmatis hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Yang termasuk dalam dogmatis hukum adalah hukum tertulis, kaidah-kaidah hukum, pengetahuan tentang hukum, teori hukum adalah membuat jelas apa yang ada di tahapan dogmatis hukum.
Filsafat hukum sendiri adalah induk dari disiplin ilmu yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah yang paling fundamental yang timbul dari hukum. Masalah fundamnetal tersebut itu seperti hakikat hukum, tentang dasar mengikat dari hukum, fungsi hukum, tujuan hukum. Penting halnya kita memahami filsafat dalam membahas hukum perburuhan, karena filsafat hukum akan membantu penyelesaian masalah-masalah hukum yang belum mampu dijawab oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam filsafat hukum untuk mempermudah penerapan dan pemahamannya maka filsafat hukum dibedakan dalam berbagai wilayah bagian, di antara lainnya adalah: 8
æ Aksiologi hukum adalah penetapan isi nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan.
æ Teologi hukum adalah menetukan makna dan tujuan dari hukum.
æ Logika hukum adalah cara berpikir yang benar dalam melakukan penelitian tentang kaidah-kaidah yuridik dan argumentasi yuridik.
Ditinjau dari filsafat hukum, pada hakikatnya permasalahan hukum perburuhan tidak terlepas dari masalah keserasian nilai–nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai itu meliputi menghargai, menghormati, gotong royong, dan sesuatu yang di anggap baik lainnya dalam masyarakat.
Permasalahan hukum ketenagakerjaan berkutat pada lemahnya implementasi perlindungan terhadap posisi buruh yang lemah. Berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pekerja, Suliati
13
Rachmat mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia.9
Frase “segenap bangsa Indonesia” berarti mencakup pula
pekerja. Selanjutnya Suliati Rachmat mengatakan bahwa perlindungan hukum pekerja, baik dengan maupun tanpa bantuan organisasi pekerja, melalui peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah, menempatkan pekerja pada kedudukan yang layak sebagai manusia. Analog dengan hal ini, maka perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan membentuk suatu peraturan yang melindungi hak pekerja.
Filsafat hukum adalah induk dari disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Oleh karena itu orang mengatakan juga bahwa filsafat hukum berkenaan dengan masalah-masalah sedemikian fundamental sehingga bagi manusia tidak terpecahkan, karena masalah-masalah itu akan melampaui kemampuan berpikir manusia. Pelaksanaan hukum ditentukan dari nama dan isi aturan hukum itu sendiri berdasar sudut kefilsafatan.
Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa karena masyarakat akan menerima hukum. Jika masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku mematuhi hukum. Hal itu sekaligus akan membawa akibat bagi para pejabat hukum dimungkinkan untuk melaksanakan dan menegakkannya. Jadi bisa dilihat bahwa hukum membawa hukum itu sendiri dari aspek sistematika. Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.10
Penetapan tujuan filsuf hukum adalah murni teoretikal. Pandangan-pandangan filsuf berkaitan erat dengan nilai-nilai, yang ada pada landasan kaidah hukum. Dilihat dari wilayah Aksiologi hukum adalah penetapan isi nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan dan kebebasan dapat juga digunakan untuk memberikan dasar pembentukan hukum perburuhan, antara lain:
9 Suliati Rachmat, Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Wanita Pekerja di Perusahaan Industri Swasta, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996, hlm 10.
14
+ Kemajuan yang dicapai perusahaan sedapat mungkin harus dinikmati oleh buruh dan pengusaha secara adil. Adil disini adalah diharapkan kemajuan yang dicapai perusahaan dapat dinikmati bersama antara buruh dan pengusaha secara proporsional. Penekanan pada nilai keuntungan dan melupakan pekerja akan memperlihatkan sifat materialistis pengusaha. Hal ini tidak dibenarkan karena menciderai nilai keadilan.
+ Dalam hubungan industrial nilai kebebasan akan mendukung terciptanya keadilan. Dengan adanya kebebasan buruh tidak akan terkekang dan pastinya akan tercipta industrial harmoni di dalam perusahan. Mengutarakan pendapat, kebebasan untuk menentukan pekerjaan itu sanggup dilakukan atau tidak adalah contoh wujud kebebasan dalam ketenagakerjaan.
+ Pelaksanaan hubungan perburuhan harus didasarkan pada nilai persamaan. Maksudnya disini adalah tidak ada diskriminasi. Tidak membeda-bedakan perumpuan dan laki-laki, tua muda, suku, agama. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai titik suatu keadaan dimana tidak ada kemampuan buruh yang tidak terpakai. Demikian pula tidak ada kesempatan yang terisi oleh orang yang sebenarnya tidak mampu. Dalam keadaan demikian, diharapkan hubungan industrial dapat dipertahankan sehingga dapat mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi.
1. Ontologi, Aksiologi, Epistemologi Hukum Perburuhan
Dalam berbagai pemikiran terdapat banyak pengertian
tentang filsafat. Secara etimologis filsafat berasal dari kata “philos”
yang artinya love (cinta) dan sophia artinya wisdom (kebijaksanaan-kearifan). Jadi filsafat dapat diartikan cinta secara mendalam terhadap kebijaksanaan, cinta akan kearifan. Menurut Henderson filsafat dapat berarti sebagai pendirian hidup, sebagai pandangan hidup. Misalnya falsafah Pancasila merupakan pandangan atau pendirian hidup bagi bangsa Indonesia.11
J A Leighton mendefinisikan filsafat sebagai “a world-view, or rasoned conception of the whole cosmos, and a life view, or doctrine of values, meanings, and purpose of human life”. Dari definisi ini pengertian filsafat adalah sistem atau sistematika filsafat yaitu metafisika, etika
15
dan logika yang atinya secara berturut adalah teori tentang kosmologi dan ontologi.
Theodore Brameld dalam bukunya menyatakan salah satu
definisi filsafat adalah “the discipline conserred with the formulation
of procise meaning” dimana menimbulkan kemungkinan salah satu
istilah yang sama diartikan berbeda dan sebaliknya.
Webster mendefinisikan filsafat itu sebagai “love of wisdom”
dan sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki fakta, dan prinsip -prinsip kenyataan hakikat dan kelakuan manusia”.
Definisi filsafat menurut beberapa ilmuwan antara lain:12
/Plato (427 SM-347 SM) seorang filsuf Yunani yang termasyhur murid Socrates dan guru Aristoteles, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).
/Aristoteles (384 SM-322 SM) mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda).
/C Marcus Tullius Cicero (106 SM-43 SM) politikus dan ahli pidato Romawi, merumuskan filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.
/Al-Farabi (meninggal 950 M), filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
/Immanuel Kant (1724-1804), yang sering disebut raksasa pikir barat, mengatakan filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu
”apakah yang dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika)”,
“apakah yang dapat kita kerjakan? (dijawab oleh etika)” hingga
“dimanakah pengharapan kita? (dijawab oleh antropologi)”.
/Fuad Hasan, guru besar psikologi Universitas Indonesia menyimpulkan filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dimasalahkan. Dan dengan jalan penjajakan yang
16
radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal.
/H Hasbullah Bakry merumuskan ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.
2. Filsafat Hukum Menurut para Ahli a. Menurut Soetikno
Soetikno adalah ahli hukum yang memberikan pernyataan hukum yang berkaitan dengan filsafat hukum. Agar lebih jelas sebelum membahas filsafat hukum kita harus tahu filsafat hukum itu sendiri. Filsafat hukum menurut Soetikno adalah mencari hakikat dari hukum, menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003), ada beberapa norma hukum yang tidak sesuai dengan apa yang diingini masyarakat. Misal, adanya pengaturan tentang ”outshourching”. Pasal ini menambah mimpi buruk buruh, karena dalam kenyataannya sampai matipun buruh tidak akan berkembang dengan adanya sistem itu. Pertimbangan-pertimbangan nilai mana yang dipakai, seharusnya buruh mendapatkan perhatian serius. Karena mereka adalah aset negara.
Negara akan maju bila para pekerja atau buruhnya juga maju. Kemajuan dari buruh disini dapat dilihat dari buruh itu memiliki sumber daya manusia yang baik, sehat, memiliki waktu untuk keluarganya, dan memiliki perekonomian yang baik.
17
yang mengatur tentang ketenagakerjaan harus bisa mewujudkan keinginan masyarakat.
Tujuan hukum perundang-undangan menurut Jeremy Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu peraturan perundang-undangan harus berusaha mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:
' to provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup).
' to provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah). ' to provide security (untuk memberikan perlindungan).
' to attain equality (untuk mencapai persamaan).
Jadi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perburuhan harus mampu memberikan kesejahteraan untuk buruh, memberikan perlindungan dan mensejajarkan posisi buruh dan pengusaha. Apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang, tidak lain adalah memberikan sebuah keadilan bagi seluruh buruh dan memberikan kemanfaatan-kemanfaatan dalam bentuk norma dam implementasinya agar tercapai kesejahteraan bagi buruh.
b. Menurut Satjipto Rahardjo
Filsafat hukum menrut Satjipto Rahardjo adalah mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Misal, di dalam hukum perburuhan pancasila adalah sebagai falsafah bangsa, sila mana yang dijadikan acuan hukum perburuhan. Contoh lainnya pertanyaan fundamental tentang hukum perburuhan adalah setiap peraturan harus dibukukan dan diatur terlebih dahulu agar tercipta sebuah kepastian hukum maka hukum ketenagakerjaan harus diatur secara implisit dalam setiap ruang lingkupnya. Atas dasar yang demikian itu maka filsafat hukum bisa menggarap semua bahan hukum.
Menurut penulis berfilsafat hukum sebenarnya merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan secara mendalam dan terus menerus untuk menemukan dan merumuskan hakikat, sifat dan substansi hukum yang ideal.
18
c. Menurut M Van HoeckeFilsafat Hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada gejala-gejala hukum (Wat Is Rechtsteorie, 1982: 83-87). Dalam filsafat dibahas pertanyaan-pertanyaan terdalam berkenaan makna, landasan, struktur, dan sejenisnya dari kenyataan.
Dalam filsafat hukum juga dibedakan berbagai wilayah bagian antara lain:
\ Ontologi hukum: penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral;
\ Aksiologi hukum: penetapan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan;
\ Ideologi hukum: pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat;
\ Epistemologi hukum: penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang “hakikat” hukum dimungkinkan;
\ Teologi hukum: menentukan makna dan tujuan dari hukum;
\ Teori-ilmu dari hukum: filsafat sebagai meta-teori tentang teori hukum dan sebagai meta-teori dari dogmatika hukum;
\ Logika hukum: penelitian tentang kaidah-kaidah berpikir yuridik dan argumentasi yuridik. Bagian ini sering dipandang sebagai suatu bidang studi tersendiri, yang telah melepaskan diri dari filsafat hukum.
Filsafat hukum perburuhan menurut penulis adalah filsafat hukum yang membahas masalah-masalah perburuhan yang paling fundamental yang timbul dalam waktu sekarang atau yang telah lampau, pemikiran secara menyeluruh dan mendalam secara terus menerus sampai menemukan hakikat hukum perburuhan yang sebenarnya sehingga masalah hukum perburuhan bisa terpecahkan. Dan tujuan dari perenungan itu adalah masyarakat khususnya pekerja, pengusaha dan pemerintah akan menerima hukum sebagai acuan bertindak.
3. Korelasi Perburuhan dengan Pancasila sebagai Falsafah Bangsa
19
diselesaikan melalui musyawarah sampai terciptanya sebuah kemufakatan. Selain musyawarah juga ada keadilan, persatuan, dan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat lainnya yang merupakan cerminan kepribadian bangsa.
Untuk mengoperasikan perburuhan pancasila tersebut, telah ditetapkan berbagai sarana untuk mewujudkan industrial harmoni, yaitu:
OPeraturan perundang-undangan terkait perburuhan harus dapat mengakomodasi semua kepentingan pekerja dan pengusaha. Terutama pihak buruh, karena posisi mereka yang lemah sehingga dapat mengurangi terjadinya perselisihan.
OLembaga bipartit, setiap perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah, penyelesaian secara bipartit adalah langkah yang wajib ditempuh pihak yang bersengketa, sebelum lanjut ke penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, arbitrase dan adjudication. Adjudication dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan melalui lembaga bipartit berarti penyelesaian yang dilaksanakan melalui dua pihak, yaitu buruh dan pengusaha.
OPeradilan perburuhan melalui peradilan khusus Mahkamah Agung membuat pengadilan hubungan industrial untuk rakyat pencari keadilan terkait perburuhan. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
OOrganisasi buruh, serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hubungan industrial yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi International Labour Organization
20
(Konvensi No. 87-1948). Dan sampai saat ini pemerintah Indonesia sedang mengadakan evaluasi terhadap UU No. 13-2003.
Undang-undang tersebut nantinya harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat, sehingga bisa terwujud hubungan industrial Pancasila. Dalam perkembangannya hubungan industrial Pancasila belumlah dapat terlaksana dengan baik, karena masih banyak terjadi perselisihan dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh.
4. Hubungan Industrial dalam Islam
Sudah seharusnya buruh diperlakukan secara manusiawi bahkan dianggap seperti anak sendiri. Anak menggantungkan hidupnya pada orang tua dan buruh menggantungkan hidupnya pada pengusaha. korelasi demikian dapat diartikan bahwa anak dan buruh menggantungkan hidupnya pada sesuatu. Oleh karena itu mereka harus diberi hak untuk hidup secara layak. Islam berpandangan bahwa modal tidak dapat menghasilkan laba tanpa adanya seorang buruh.
Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya Islam adalah rahmat bagi sekalian alam juga mengatur tentang hukum perburuhan, misalnya di Surat Al-Baqarah ayat 286 yang mengatur pijakan bagi buruh untuk mendapat hak beristirahat.
Islam mengatur masalah ketenagakerjaan adalah pernyataan Rasulullah SAW tentang bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya, dan masih banyak yang lainnya yang akan diuraikan di bawah.
Hubungan buruh dan pengusaha harus syariah yang didasarkan pada rasa hormat terhadap hak-hak pekerja dan pengusaha. Secara umum, prinsip hubungan industrial dalam Islam harus mengakomodasi kepentingan buruh yang meliputi:
¥ Hak mendapatkan pendidikan dan keterampilan sesuai kompetensinya
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dalam surat al-Mulk ayat 2 Allah SWT berfirman:
21
”Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.
Ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menemukan siapa di antara mereka yang lebih baik perbuatannya. Dalam konteks ekonomi, yang lebih baik perbuatannya adalah yang lebih produktif. Nabi juga pernah menyatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin berarti rugi karena tidak ada nilai tambah.
¥ Hak melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya dengan tetap mendapatkan upah
Semua orang adalah sama tidak peduli kaya miskin, majikan buruh, keturunan raja atau rakyat biasa yang membedakannya adalah derajat keimanan dan ketakwaannya dimata Allah SWT saja. Oleh karena itu hak melaksanakan ibadah tidak boleh dihalang-halangi.
Pelaksanaan ibadah bagi seorang buruh sepertinya sudah dijalankan di seluruh perusahaan di Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim sangat sensitif jika diusik masalah keimanannya dan ketakwaannya terhadap Allah yang esa. Majikan yang baik adalah majikan yang bersedia mengurangi waktu kerja buruh untuk mengerjakan ibadah. Seperti dalam Hadith Nabi:
”Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayananannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya.” (H R Ahmad).
Hadith ini dengan tegas menyatakan bahwa Islam tidak menyamakan tenaga kerja sebagai mesin. Yang menarik dari hadith nabi ini adalah buruh dituntut memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap majikan. Jika hubungan seperti ini dipertahankan terus maka akan tercipta industrial harmoni.
22
23
BAB III
TEORI-TEORI HUKUM PERBURUHAN
Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu oleh para ahli hukum Yunani maupun Romawi dengan membuat berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya.
Sebelum abad ke-19, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika, dan politik. Para ahli pikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik kepada filsafat hukum dari para ahli hukum barulah terjadi pada akhir-akhir ini yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum, sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum dari ahli hukum modern didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri.
A.Teori Hukum Menurut Para Pakar 1. St Thomas Aquinas
Teori hukum ini berkembang pada abad pertengahan. Aquinas berpendapat hukum pada dasarnya merupakan cerminan tatanan Ilahi. Legislasi hanya memiliki fungsi untuk mengklarifikasi dan menjelaskan tatanan Ilahi itu. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan melalui fungsinya menerapkan hukum dalam kaitan dengan pemberlakuan undang-undang.
24
oleh akal manusia.
Teori ini masih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, karena pengaruh ajaran agama yang mereka pahami dan yakini selama ini. Seperti diketahui masyarakat Indonesia sebagian besar penganut-penganut Islam yang fanatik dan sumber hukum mereka yang diyakini kebenarannya, di samping Alquran dan As-Sunnah, juga ijtihad di kalangan para ulama fikih. Hukum yang berasal dari wahyu adalah Alquran dan As-Sunnah, sedangkan hukum yang dijangkau oleh akal manusia adalah ijtihad. Dengan membuka pintu ijtihad, maka dengan sendirinya akan lahir teori-teori hukum baru yang sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri.
2. Hans Kelsen
Teori hukum ini, berkembang pada abad ke-20. Kelsen berpendapat bahwa teori hukum yang murni haruslah bersih dari politik, etika, sosiologi dan sejarah. Menurut Kelsen hukum berurusan dengan bentuk forma, tidak berurusan dengan materia (isi). Sedangkan keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Oleh karena itu gagasan-gagasan mengenai keadilan haruslah menjadi tema di dalam politik, tidak di dalam hukum. Ilmu hukum adalah suatu hirarki mengenai hubungan normatif, bukan suatu hubungan sebab akibat. Demikian pula Kalsen hanya berbicara mengenai hukum sebagai yang ada (law is it is), tidak sebagai yang seharusnya ada (law as ought to be). Objek tunggal hukum adalah menentukan apa yang dapat diketahui secara teoritis tentang tiap jenis hukum pada tiap waktu dan dalam tiap keadaan.
Dari uraian di atas, dapat penulis sebutkan dasar-dasar esensial dari teori Kelsen, sebagai berikut:
Tujuan teori hukum seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
25
Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang ada.
Dari uraian tersebut, Kelsen menganggap bahwa ada perbedaan antara norma hukum dan norma moral, terutama sekali dilihat dari segi sanksinya. Kelsen dianggap sebagai pencetus teori murni tentang hukum, di samping sebagai pencetus dan berjasa mengembangkan teori jenjang yang dicetuskan oleh Adolf Merkl (1836-1896), yaitu teori yang menganggap susunan hukum berbentuk piramida, di mana hukum yang lebih rendah harus sesuai dengan hukum yang lebih tinggi.
3. H L A Hart
Teori hukum ini menyebutkan antara lain adalah” that laws are
commands of human beings” artinya hukum adalah perintah. Juga dikatakan “that there is no necessary connection between law and morals or
law as it is and law as it ought to be”, artinya tidak ada kebutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, dan yang diinginkan. Selanjutnya Hart berpendapat “that a legal system is a closed logical
system in which correct decisions can be deduced from predetermined legal rules by logical means alone”, artinya sistem hukum adalah sistem tertutup yang logis, yang merupakan putusan-putusan yang tepat yang dapat dideduksikan secara logis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.
Sejalan dengan itu teori ini menghendaki, bahwa apapun bunyi pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sebagai contoh, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7-1989), yang mengatur tentang proses syikak, harus diwujudkan dalam kenyataan.
4. John Austin
26
tegas dapat disebut demikian, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya.
Konsep tentang kedaulatan negara mewarnai hampir keseluruhan dari ajaran Austin. Hal mana dapat diikhtisarkan antara lain sebagai berikut:
Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal.
Sifat eksternal dari kedaulatan negara tercermin pada hukum internasional, sedangkan sifat internal kedaulatan negara tercermin pada hukum positif.
5. Jeremy Bentham
Teori hukum ini lahir dari aliran utilistis. Tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Tujuan hukum perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu peraturan perundang-undangan harus berusaha mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:
to provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup).
to provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah). to provide security (untuk memberikan perlindungan).
to attain equality (untuk mencapai persamaan).
Menurut Bentham terdapat 2 (dua) tipe studi ilmu hukum
(jurisprudential study), yaitu:
Expository jurisprudenceialahilmu hukum ekspositor ini tidak lebih dari studi hukum sebagaimana adanya. Objek studi ini adalah menemukan dasar-dasar dari asas-asas hukum melalui penganalisaan sistem hukum sebagaimana yang ada.
Censorial jurisprudence ialah ilmu hukum sensorial ini merupakan studi kritis tentang hukum yang dikenal juga sebagai deontologi untuk meningkatkan efektivitas hukum dan pengoperasiannya.
B. Macam-Macam Teori Hukum Dalam Hukum Perburuhan 1. Teori Kedaulatan Negara
Teori kedaulatan negara ini dipelopori oleh John Austin, yang
27
diikhtiarkan bahwa kedaulatan negara yang digunakan itu, berdasarkan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh pihak yang berkuasa. Dalam ilmu hukum menunjuk pada suatu atribut negara yang bersifat internal dan eksternal. Sehingga prinsip demokratisasi yang didengung-dengungkan oleh Amerika Serikat, kemudian diadopsi Indonesia, lalu untuk memperlihatkan keindonesiaannya, dibingkai dengan istilah ”demokrasi Pancasila” dan itulah yang dianggap terbaik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal yang menjadi ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkannya, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan semboyan retorika yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, dan keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulan-bulanan hukum.
Karena itu, beralasan untuk menegaskan bahwa hukum, bukan sekadar kumpulan peraturan. Hukum adalah norma untuk menjamin dan melindungi hak warga negara.
Warga negara disini adalah segenap bangsa. Berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pekerja, Suliati Rachmat mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban
melindungi segenap bangsa Indonesia. Frase “segenap bangsa Indonesia” berarti mencakup pula pekerja. Selanjutnya Suliati
Rachmat mengatakan bahwa perlindungan hukum pekerja, baik dengan maupun tanpa bantuan organisasi pekerja, melalui peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah, menempatkan pekerja pada kedudukan yang layak sebagai manusia. 13
28
2. Teori Kedaulatan HukumTeori ini menyatakan bahwa hukum itu bersifat mengikat, bukan karena dikehendaki oleh negara, namun lebih dikarenakan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. H Krabbe dalam bukunya ”Die Lehre Rechtssouvernitat” berpendapat bahwa kesadaran hukum berpangkal pada perasaan setiap individu yaitu bagaimana seharusnya hukum itu.
Teori ini dalam tataran praktikal, sedikit mengalami kesulitan, karena tingkat kesadaran hukum, masing-masing orang pasti berbeda dan sangat bergantung pada faktor kepentingan yang ingin dicapai. Salah satu contoh yang nampak di permukaan, bahwa betapa banyak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa tata usaha negara, yang tidak mau dilaksanakan oleh pihak yang kalah, terutama kalau yang dikalahkan adalah pihak penguasa. Mengapa?, karena merasa kebijakannya dirugikan. Yang sangat disayangkan, ketika pihak yang kalah ini, tidak mau menerima kekalahannya, ada pihak-pihak tertentu yang mengompori atau memprovokasi masalah tersebut, akibatnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak dapat dilaksanakan karena adanya perlawanan terhadap putusan pengadilan oleh pihak yang kalah, hal demikian juga terjadi dalam sengketa pengupahan perburuhan, saat dewan pengupahan sudah menetapkan pengupahan, hal ini ditentang oleh banyak pihak, padahal dewan pengupahan dibentuk sudah sangat demokratis, ada unsur dari perwakilan pemerintah, perwakilan pengusaha dan perwakilan buruh, seharusnya semua pihak menghormati keputusan dewan pengupahan.
3. Teori Cita Hukum
29
konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.14
Pandangan Gustav Radbruch tersebut dapat dipahami melalui teks asli sebagai berikut:15
“De rechtsidee niet allen alseen regulatieve maatstaaf fungeert (om het positieve recht op zijn rechtvaardigheid of onrechtvaardigheit to toetsen), maar tegelijk als constitutive grondslag (zonder welke het recht, dat de rechtsidee der gerechtigheit de grondslag vormt van recht, dat met de idee in strijd kan zijn (onrechtvaardigrecht)”.
Dengan demikian, setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang disepakati. Hans Kelsen menyebut cita hukum sebagai grundnorm atau basic norm.16
Cita hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam cita hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan. Dimensi nilai yang dipersoalkan disini bukan saja dijumpai saat peraturan itu hendak diimplementasikan, sebab pada saat pengimplementasiannya itulah dibutuhkan produk kebijaksanaan yang lebih teknis operasional.
Gustav Radbruch mengemukakan, terdapat 3 (tiga) nilai dasar dari hukum17 yang kemudian dikenal dengan cita hukum.
Ketiga nilai tersebut yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam hukum perburuhan kepastian hukum UU No. 13-2003 dan peraturan pelaksananya. Terkait dengan keadilan dalam hukum perburuhan sangat sulit untuk diwujudkan, karena posisi buruh dengan pengusaha yang sesungguhnya memang tidak seimbang, namun dalam UU No. 13-2003, terdapat peran pemerintah sebagai penyeimbang kedudukan buruh dengan pengusaha. Terkait dengan
14 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm 43.
15 Ibid, hlm 44. 16 Ibid, hlm 46.
30
kemanfaatan UU No. 13-2003 hadir untuk memberikan perlindungan bagi pengusaha dan terutama bagi buruh.
Gustav Radbruch juga mengemukakan adanya kesulitan dalam mewujudkan ketiga nilai-nilai dasar hukum ini secara bersamaan. Apabila dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah itu mungkin tercapai. Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dengan yang lainnya berbenturan. Misalnya suatu kasus dimana hakim
menginginkan putusannya ”adil” menurut persepsinya, namun
akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian sebaliknya. Sehingga Radbruch mengajarkan, menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum.18
Berkaitan dengan cita hukum di Indonesia, maka pancasila dikatakan sebagai cita hukum (rechtsidee)19 dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita hukum (rechtsidee)
menurut Rudolf Stammler20 adalah konstruksi berpikir yang
mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu
(leitstern) untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Cita hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.
Hal senada juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif yaitu untuk menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat
18 Chainur Arrasjid, ibid, hlm. 18
19Penjelasan UUD NRI 1945 menerjemahkan kata ”rechtsidee” dengan ”cita-cita hu-kum”, yang semestinya adalah ”cita hukum” karena cita berarti gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita berarti keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di-pikiran atau dihati. Karena itu ”Rechtidee” sebaiknya diterjemahkan dengan cita hu-kum, lihat Hamid S Attamimi, Cita Negara Persatuan Indonesia, Jakarta: BP-7 Pusat, 1996, hlm 133.
31
konstitutif dan menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum positif akan kehilangan maknaya sebagai hukum.21
Menurut M Koesnoe, cita hukum bersumber dari “alam nilai”. Alam nilai itu sendiri merupakan dunia idea-idea tentang apa yang dianggap mulia serta luhur, dan oleh karena itu bersifat harus yang menuntut penghormatan dan ketaatan kepadanya. Dunia nilai-nilai itu kemudian ditangkap, diolah, dan diramu oleh filsafat hidup dari suatu masyarakat hukum.22 Dari filsafat hidup tersebut terbentuklah
rechtsidee. Karena nilai-nilai tersebut memiliki keutamaan dan menjadi cita hukum, maka ia memiliki hakikat imperatif yang mewajibkan. Inilah yang kemudian membentuk konsep hukum yang kategoris.23 Dari unsur-unsur konsep ini, ditarik asas-asas hukum.
Secara spesifik Stammer mengindentifikasikan cita hukum sebagai kemauan yuridis, yaitu suatu kemauan yang mendorong setiap orang untuk membentuk peraturan-peraturan bagi masyarakat dalam hukum positif. Disini terlihat bahwa kemauan yuridis merupakan kemauan dasar dan syarat bagi seluruh hukum positif. Kemauan yuridis ini bersifat transedental yaitu berfungsi sebagai prinsip terakhir dari segala pengertian tentang hukum. Cita hukum mengandung arti pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri.
Cita hukum itu dibentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan dan kenyataan-kenyataan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan keadilan, hasil guna dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberi pedoman, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam pembentukan, penemuan, penerapan dan perilaku hukum. Dengan dirumuskan cita
21 Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyeleng-garaan Pemerintahan Negara: Suatu Sudi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Ber-fungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Jakarta: Univer-sitas Indonesia, 1990, hlm 309.
22 M Koesnoe, Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional, No. 2, 1995, Jakarta: BPHN, 1995, hlm 80.
32
hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Berdasarkan pengertian cita hukum di atas, dapat ditarik pengertian bahwa sebagai suatu ukuran yang berisikan nilai-nilai, maka cita hukum tunduk pada falsafah yang mendasarinya. Dengan demikian setiap cita hukum memiliki rumusan nilai yang berbeda. Rumusan nilai cita hukum Pancasila berbeda dengan cita hukum yang orientasi falsafahnya liberalisme ataupun sosialisme.
Selain sebagai cita hukum, Pancasila juga sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), karena itu sila-sila Pancasila baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum. Dalam kedudukan ini Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian hukum yang dibangun adalah yang berparadigma Pancasila yang berdasarkan pada UUD NRI 1945 yaitu:24
T Mencerminkan religiusitas kebertuhanan segenap warga negara melalui keyakinan segenap bangsa warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa; T Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan
berkeadaban atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
T Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan Indonesia melalui sila persatuan Indonesia;
T Memperkuat nilai-nilai sovereinitas kerakyatan melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
T Melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tiap-tiap sila tidak boleh dilepaskan dari sila yang lain. Sila yang satu meliputi dan menjiwai sila yang lain. Misalnya sila kelima
Pancasila, yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia“,
sila ini diliputi dan dijiwai oleh sila sebelumnya yang harus diimplementasikan melalui produk peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang sudah tentu harus dijiwai semangat
33
“Ketuhanan Yang Maha Esa“, semangat, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab“, semangat “Persatuan Indonesia“, semangat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan“. Dengan semangat “Ketuhanan Yang
Maha Esa“, maka produk peraturan perundangan tentang advokat, polisi, jaksa dan hakim baik pranata hukumnya maupun penyelenggaraan penegakan hukumnya harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang luhur.
4. Teori Perlindungan Hukum
Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.
Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suartu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.25
Philipus M Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.26
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan
25 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 53.
34
falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep rechtstaat dan rule of the law. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Dalam perlindungan hukum khususnya bagi rakyat Indonesia, Philipus M Hadjon membagi 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu:
1. Perlindungan hukum preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 2. Sarana perlindungan hukum represif
35
kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 27
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
• Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
Dalam dunia industrial UU No. 13-2003 hadir untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam hubungan industrial.
• Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU No. 39-2004):
Pasal 102 UU No. 39-2004, menyebutkan:
1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang: a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
36
c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 103 UU No. 39-2004, menyebutkan:
1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
b. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 104 UU No. 39-2004, menyebutkan:
1. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang: