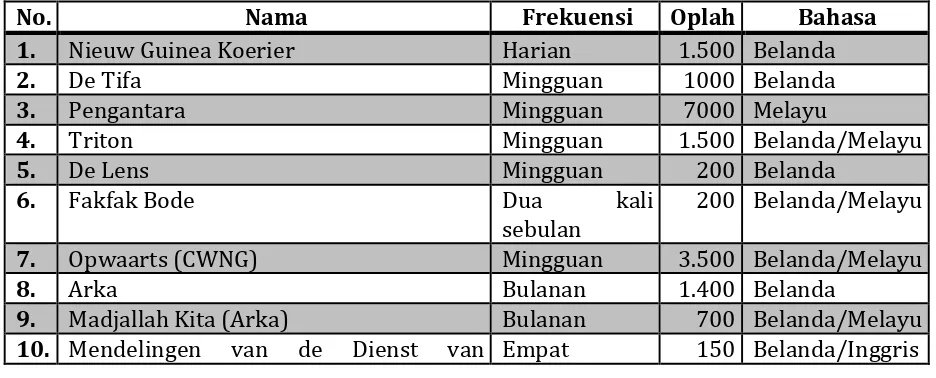GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBUDAYAAN PAPUA: SEBUAH KAJIAN AWAL
Ridwan dan Nalikoy Insowibinderi Sarwom Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)
1. Pengantar
Duka cita telah merundung dunia ketika tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat
(AS) menabrak dan meluluhlantakkan menara kembar World Trade Centre (WTC) pada
11 September 2001 di New York, AS. Selanjutnya, pada 26 Desember 2004, gelombang
tsunami telah menggulung Indonesia, Thailand, Sri Lanka dan India yang
mengakibatkan sekitar 228.000 orang meregang nyawa dan lebih dari 2 juta orang
kehilangan tempat bernaung. Dua tragedi tersebut, sebagai contoh, telah menorehkan
duka yang mendalam bagi masyarakat di dunia akibat aksi terorisme dan gelombang
tsunami yang menelan ribuan korban jiwa yang tidak berdosa.
Terhadap peristiwa tersebut, dunia merespon cepat dengan munculnya berbagai
lembaga bantuan pada tingkat lokal hingga tingkat internasional yang aktif membantu
daerah yang dilanda nestapa tersebut. Misalnya, di Inggris Disaster Emergency
Committee (Komite Bencana Darurat) telah menerima lebih dari 10 juta Euro dalam
kurun waktu 24 jam paska pemberitahuan penggalangan dana, memecahkan rekor
dunia sebagai jumlah dana terbesar yang pernah diterima dalam waktu 24 jam secara
online. Dana mengalir deras dari berbagai pelosok dunia seperti Somalia, Seychelles,
Birma, Maladewa dan donasi pribadi lainnya, total dana yang diterima dari publik
sebesar 392 juta Euro (Kweifio-Okai, 2014).
Dengan demikian, arus deras informasi via media dan internet telah menghantarkan
nation-states (negara-negara bangsa) pada tahap di mana setiap orang dapat melihat,
merasakan dan menaruh simpati pada peristiwa-peristiwa humanitarian, seperti yang
disebutkan di awal tulisan, yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari tempat
tinggalnya menjejak bumi. Fenomena tersebut kerap dinamai “globalisasi”, sebuah
proses yang terus berkembang dengan pesat, yang membuat dunia seolah-olah
Tulisan ini akan memfokuskan perhatian pada dampak globalisasi terhadap
kebudayaan Papua. Dalam implementasinya, tulisan akan dibagi ke dalam beberapa
bagian. Bagian awal akan menjelaskan definisi globalisasi sebagai pembuka wawasan
awal tentang globalisasi. Selanjutnya, akan mendeskripsikan kehadiran globalisasi
secara singkat di Indonesia, khususnya di Papua. Setelah itu, kami akan mengkaji
bagaimana globalisasi membawa dampak terhadap kebudayaan Papua dan diakhiri
dengan kesimpulan. Kami memiliki hipotesis bahwa globalisasi telah memberi dampak
negatif yang cukup signifikan terhadap kebudayaan Papua.
2. Pengertian Globalisasi
Terminologi Globalisasi mulai ramai dipergunjingkan secara akademik sejak tahun
1980-an. Saat itu, istilah tersebut menggambarkan perkembangan hubungan antar
negara atau hubungan internasional. Kata ‘internasional’ pertama kali diperkenalkan
oleh Jeremy Bentham pada tahun 1780-an untuk menjelaskan sebuah ‘realita baru’ yang
sedang terjadi pada waktu itu. ‘Realita baru’ tersebut terus berkembang dari tahun ke
tahun khususnya bersamaan dengan kemajuan teknologi. Saat ini ‘realita baru’ tersebut
dikenal dengan globalisasi dan menurut berbagai ilmuan, era globalisasi ditandai
dengan dunia baru atau a new world yakni dunia kontemporer yang muncul usai perang
dingin (Rudy, 2011: 1)1
Mengutip kamus Penguin Hubungan International, Globalisasi disebut sebagai “the
process whereby state-centric agencies and term references are dissolved in favour of
structure relations between different actors operating in a context which is truly global
and not merely international” (Evans, 1998: 200). Karenanya, globalisasi merupakan
sebuah proses yang melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun
non-pemerintah yang berkerja pada tahap global dan berusaha demi terciptanya suatu relasi
atau hubungan yang saling menguntungkan.
Senada dengan itu, Budi Winarno mendefinisikan globalisasi sebagai “masing-masing
aktor (bangsa-bangsa atau unit-unit politik lainnya, seperti transnational actors)
berperilaku dalam suatu cara yang secara fundamental berkaitan tidak hanya dengan
1 Lihat juga Bab Pendahuluan; Prof.Drs. Budi Winarno,M.A.,PhD. (2011). Dinamika Isu-Isu Global
struktur dan proses internal dalam dimensi politik, sosial dan ekonomi, tetapi juga
berkaitan dengan persepsinya tentang tempat dan perannya didalam sistem global”
(Budi Winarno, 2014: xvii).
Globalisasi dipahami secara luas merupakan fenomena yang menyatukan dunia melalui
kekuatan ekonomi dan teknologi dan perkembangan yang terjadi di satu tempat
memiliki dampak terhadap keberlangsungan hidup seseorang atau sebuah komunitas di
tempat lain. Sebagai contoh, perkembangan ekonomi dan teknologi di Korea Selatan
mampu membuat negara ginseng ini diakui di kawasannya dan mengekspor budaya
mereka secara luas. Budaya K-Pop salah satunya merupakan bukti keberhasilan Korea
Selatan dalam mempromosikan negara mereka sehingga saat ini banyak kalangan muda
di Indonesia ramai-ramai mempelajari bahasa Korea, meniru penampilan artis-artis
Korea dan bahkan mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Korea tersebut. Perlahan
banyak komunitas yang mulai menganut gaya hidup a la Korea (Held,1999: 1).
Pemahaman tentang globalisasi sendiri terus diperdebatkan. David Held dan Anthony
McGrew mencoba mengklasifikasikan perbedaan pandangan tentang globalisasi dari
tiga schools of thought (mazhab pemikiran) yang mana ketiga kelompok dengan
pandangan yang sangat berbeda tersebut mereka sebut sebagai para hyperglobalizers,
para sceptics, dan para transformationalists. Para hyperglobalizers melihat globalisasi
sebagai sebuah era baru dimana manusia di dunia makin terjerumus dalam arus pasar
global, terus mengikuti ketentuan-ketentun yang ada dalam perkembangan ekonomi
dunia. Kenichi Ohmae merupakan salah satu pemikir hyperglobalists dan bagi mereka
kekuatan negara semakin melemah dan kekuatan pasar dunia lebih kuat. Negara yang
memiliki otoritas politik atas masyarakat dan ekonomi terlihat melemah dan otoritas
atau kekuatan tersebut perlahan dikendalikan oleh instutusi-instutusi atau
asosiasi-asosiasi internasional. Bagi mereka, globalisasi ini adalah sebuah fenomena ekonomi
yang memiliki dampak yang cukup luas dan mereka berkeyakinan bahwa akan
terbentuk sebuah masyarakat global atau apa yang mereka sebut sebagai ‘global civil
society’ (Held, 1999: 2-5).
Para sceptics, di lain pihak menilai pandangan hyperglobalists ini adalah ‘cacat’ dan
ini adalah naif. Menurut mereka, kekuatan negara tidak dapat dianggap remeh, dan
melihat bahwa justru kekuatan negara memainkan peran yang signifkan dalam
mengendalikan perekonomian internasional. Kekuatan untuk
menginternasionalisasikan aktifitas ekonomi tetap berada dibawah kendali negara dan
kegiatan tersebut akan tetap bergantung pada tiap negara untuk terus atau tidaknya
melanjutkan liberalisasi prekonomiannya. Oleh karena itu, dunia terlihat ‘kurang
terintegrasi’ dari sebelumnya. Mengutip pernyataan Gordon dan Weiss, ‘dunia secara
geografi terlihat kurang global dalam menjalankan ekonomi internasional dibandingkan
dengan era kerajaan-kerajaan’ (Held, 1999: 5).
Bagi para sceptics, adanya internasionalisasi tidak menghilangkan kesenjangan
‘Utara-Selatan’ dan perekonomian negara berkembang terus termarjinalkan dikarenakan arus
dagang dan investasi mengalir di negara ‘Utara’. Hal ini menyebabkan perkembangan
yang tidak merata antar negara maju dan berkembang. Menurut E.H.Carr (1981),
internasionalisasi merupakan project negara barat untuk mempertahankan kekuatan
dalam urusan dunia dan ia juga melihat bahwa slogan seperti ‘international order’ dan
‘international solidarity’ hanya sebatas slogan dari negara-negara kuat (Held, 1999: 6).
Para transformationalists, seperti Rosenau dan Giddens beranggapan bahwa globalisasi
menyebabkan perubahan pada negara-negara dan masyarakatnya secara mengglobal.
Mereka sepakat bahwa manusia semakin terhubung satu dengan yang lainnya akan
tetapi dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Globalisasi menyebabkan
meleburnya batas-batas negara, tidak jelasnya perbedaan antara internasional dan
domestik, urusan luar negri dan dalam negri. Akan tetapi, keberadaan suatu sistem
global tidak berarti akan menciptakan satu masyarakat global. Bagi mereka, globalisasi
menciptakan jurang pemisah antar masyarakat yang disebabkan oleh perekonomian
dunia. Pola dari globalisasi menyebabkan adanya beberapa negara, masyarakat atau
komunitas yang semakin diuntungkan dengan tatanan global yang baru, sementara
yang lain dikucilkan. Mereka juga meyakini bahwa globalisasi merupakan sebuah
proses perkembangan sejarah yang panjang yang akan menciptakan sebuah
‘sovereignity regime’ baru dan juga akan menciptakan munculnya organisasi politik
dan/atau ekonomi global baru yang kuat seperti korporasi-korporasi multinasional,
mereka meyakini dan seperti yang dipaparkan oleh Rossenau, dengan adanya
globalisasi kekuatan negara tidak hilang atau melemah melainkan berubah atau
terstrukturisasi menyesuaikan dengan kompleksitas perubahan dunia yang semakin
terhubung satu dengan lainnya (Held, 1999: 6-9).
Secara singkat, David Held menyimpulkan pandangan Hyperglobalists, Sceptics dan
Transformationalists tentang globalisasi melalui tabel 1 berikut ini (Held, 1999: 10):
Tabel 1 “Conceptualizing Globalization : three tendencies”
Hyperglobalists Sceptics Transformatinalists
Sumber : Global Transformations, Politics, Economics and Culture (Held, 1999: 10)
Dengan kata lain, globalisasi kerap dikaitkan dengan berbagai kekuatan didunia yang
non-state actor atau bahkan individu dalam suatu negara. Namun, ‘kekuatan’ yang
memainkan peranan paling penting dalam menjembatani negara-negara saat ini adalah
revolusi informasi dan teknologi seperti internet yang memiliki dampak yang tidak
terbatas secara global. ‘Kekuatan’ ini bergerak melintasi batas-batas negara dan tidak
berada di bawah suatu struktur politik (Goldstein, 2013-2014: 19-20). Singkatnya,
dunia yang kita huni saat ini semakin menyatu dibandingkan sebelumnya.
Dalam bukunya The Great Convergence, Kishore Mahbubani (2013 :3) menggambarkan
situasi dunia saat ini khususnya terkait dengan bagaimana nation-states lebih
terintegrasi saat ini.
“Before the era of modern globalization, when humanity lived disceretly in more than one hundred separate countries, humanity was like a flotila of a more than one hundred separate boats. ... Today, global circumstances have changed dramatically. The 7 billion people who inhabit planet earth no longer live in more than one hundred separate boats. Instead they all live in 193 separate cabins on the same boat. It has 193 captains and crews, each claiming exclusive responsibility for one cabin.” (Mahbubani, 2013, hal. 3)
Mahbubani mengibaratkan negara dahulu bak ribuan perahu yang tersebar di atas laut
akan tetapi berkat pengaruh globalisasi perahu-perahu yang tersebar dahulu, kini telah
menyatu dan menjadi sebuah kapal besar dengan 193 kabin yang mana tiap kabin
memiliki seorang kapten dan awak kabin yang secara eksklusif bertangung jawab atas
kabinnya masing-masing. Hal ini membuat dunia semakin terintegrasi dan
menghubungkan ke-7 miliyar penduduk bumi satu sama lain.
Secara keseluruhan, fenomena ini telah merubah wajah negara-negara di planet bumi
dalam berbagai aspek baik secara politik, ekonomi ataupun secara sosial dalam hal ini
budaya. Angin perubahan ini lebih kuat hembusannya dan menyapu dataran Asia,
Afrika dan Amerika Selatan (Movious, 2010: 6-18). Seperti halnya negara lain di Asia,
Indonesia pun tidak luput dari hembusan proses globalisasi. Bagian berikut akan
menjelaskan hembusan ‘badai’ globalisasi yang melanda Indonesia, khususnya di Papua.
3. Globalisasi di Indonesia, Khususnya di Papua
Pada awal tahun 1980-an Indonesia mulai merubah kebijakan ekonominya ketika harga
demikian, mendorong keterbukaan. Pada saat itu, Indonesia memulai proses globalisasi
yang diawali dengan membuka perekonomiannya dan kemudian menyebar pada aspek
lainnya. Para pengambil kebijakan saat itu memahami keuntungan dan peluang dari
membuka pintu perekonomian Indonesia dan bahkan mengikuti arus globalisasi dengan
sangat baik (Kartasasmita, 2001: 3-5).
Secara historis, pada masa Soeharto (1965 – 1998), Indonesia telah mengadopsi politik
bebas aktif yang mengangkat profil Indonesia secara global dan dipercaya untuk
bergabung sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan
Bangsa-Bangasa (PBB) periode 1973 – 1974 dan pada periode 1995 – 1996. Peran Indonesia
dalam ASEAN juga cukup mengagumkan, Indonesia mampu mendampingi dialog terkait
perdamaian dan resolusi konflik antara Kamboja dan Vietnam (1978 – 1991). Pada segi
perdagangan dan investasi, Indonesia menandatangani ASEAN Free Trade Agreement
(AFTA) atau perjanjian bebas dagang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan angka
investasi dan perdagangan sesama anggota ASEAN. Ditambah dengan itu Indonesia juga
telah menandatangani berbagai perjanjian kerjasama dengan negara-negara anggota
ASEAN+3, organisasi internasional seperti WTO dan APEC.
Di samping kerjasama dengan organisasi multinasional dan menandatangani berbagai
perjanjian multilateral, Indonesia juga telah mendatangani berbagai perjanjian bilateral
dalam sektor ekonomi dan perdagangan dengan banyak negara diantaranya seperti AS,
Cina, dan Jepang. Dikarenakan proses ‘membuka diri’ dan kerjasama Indonesia mampu
mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun
1975-1980 tercatat 60% merupakan orang miskin dan angka tersebut berkurang
menjadi 11,2% orang pada tahun 1996 (Wuryandari, 2011 ).
Kini, wajah globalisasi di Indonesia memiliki beragam wujud dan selalu menarik untuk
membahas tiap aspek-aspek tersebut. Tetapi, untuk pembahasan di tulisan ini akan
difokuskan pada aspek sosial budaya dan dari ke-33 provinsi yang ada di nusantara ini,
provinsi Papua atau yang dahulu dikenal dengan Irian Jaya yang akan menjadi inti topik
Papua merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland (Muller, 2008) dan memiliki
posisi yang unik dalam sejarah Republik Indonesia (RI). Setelah kemerdekaan RI pada
tahun 1945, Papua atau Irian Jaya belum menjadi bagian dari wilayah kesatuan RI dan
masih dibawah pemerintahan Belanda. Status Papua selalu menjadi perdebatan antara
Pemerintah RI dan Belanda, permasalahan yang kompleks ini dibawa ke PBB agar dapat
diselesaikan. Pada tanggal 19 November 1969, sesuai keputusan Majelis Umum PBB
dengan resolusi 2504 (XXIV) pada akhirnya Papua secara sah dan utuh diakui sebagai
bagian dari wilayah RI oleh komunitas internasional (Permanent Mission of The Republic
of Indonesia to The United Nations, 2004).
Di sinilah letak keunikan Papua, dalam perdebatan tersebut status Papua terus
dipergunjigkan. Pertanyaan seperti apakah Papua harus bersatu dengan Indonesia atau
merdeka? Terus menjadi permasalahan yang panas dan berlarut-larut hingga saat ini,
sebuah perdebatan yang mana Indonesia meyakini bahwa Papua merupakan bagian
integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dikarenakan debat inilah
Papua terus menjadi korban konflik internal.
Sumber konflik dapat berbeda tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim
LIPI Papua di tahun 2004 menunjukan bahwa ada empat permasalahan stategis yang
menjadi inti atau sumber permasalahan konflik di Papua yakni; sejarah integrasi Papua
kedalam wilayah Indonesia dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kegagalan pembagunan di Papua, dan
ketidapastian pemerintah terkait implementasi otonomi khusus dan juga marginalisasi
masyarakat Papua (Muridan S Widjojo, 2009).
Semenjak bergabung ke dalam pangkuan NKRI terdapat dua perkembangan menarik
terkait Papua. Pertama, dibawah pemerintahan Belanda tanah Papua atau Bumi
Cendrawasih ini dikenal dengan West New Guinea atau Nederlandse Nieuw Guinea.
Setelah integrasi kedalam RI, dataran tersebut dinamai Provinsi Irian Barat. Kemudian,
dibawah pemerintah Soeharto nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya. Pada tanggal
31 Desember 1999 nama Irian Jaya kembali dirubah menjadi Papua. Dibawah
Undang-Undang No.45/1999 dan INPRES No.1/2003 membagi wilayah Papua menjadi tiga
yang dikenal adalah Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat. Lalu semenjak tanggal
18 April 2007, dibawah Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2007, Provinsi Irian Jaya
Barat dikenal sebagai Provinsi Papua Barat (Muridan S Widjojo, 2009).
Perkembangan kedua, sesuai UU No 21 tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No. 4151), di
Papua diberlakukan Otonomi Khusus atau Otsus untuk Provinsi Papua dan telah
dijalankan sejak tanggal 1 Januari 2002. Peraturan ini membantu masyarakat Papua
untuk turut berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan daerah, menentukaan
pembangunan strategis seperti mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM), percepatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan
kemajuan masyarakat Papua dengan menghargai kesetaraan dan keragamannya. Hal ini
juga menyangkut pelestarian budaya dan lingkungan di tanah Papua. Otsus ini
menekankan bahwa penghargaan atas budaya dan pelestarian budaya perlu dijunjung
dan memberikan beberapa kebebasan bagi masyarakat Papua dalam menjalankan
politik dan ekonomi daerah (Permanent Mission of The Republic of Indonesia to The
United Nations, 2004: 60-61).
Sejarah otsus di Papua cukup menarik. Otsus diterapkan di bumi Cendrawasih beberapa
tahun setelah terjungkalnya regim Soeharto dan setelah berbagai kekecewaan yang
dialami oleh masyarakat Papua dengan pemerintah pusat yang membagi provinsi
tersebut menjadi dua. Selain itu, banyak suara yang menyerukan merdeka dan menarik
untuk dilihat bahwa banyak juga yang beranggapan bahwa penerapan otsus ini
merupakan upaya untuk membungkam suara-suara tersebut. Otsus ini merupakan hasil
dialog yang panjang, sebuah ‘negoasiasi panjang, kompromi dan pengambilan keputusan
antara pemerintah Indonesia dan Papua terutama ketika permasalahan terkait aneksasi
wilayah Papua ke Indonesia dan status politiknya diangkat ke permukaan kembali’.
Otsus ini merupakan sebuah win-win solution, sebuah solusi yang saling menguntungkan
dalam menyelesaikan permasalahan status politik Papua.
Terdapat harapan bahwa otsus mampu membawa kesejahteraan dan kesempatan bagi
masyarakat Papua untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik,
tentram dan damai didalam kerangka NKRI. Sesuai dengan yang tertera dalam UU No.21
pendidikan dan budaya menekankan bahwa ‘sudah merupakan kewajiban pemerintah
provinsi untuk melindungi, mengajar dan mengembangkan kebudayaan asli Papua’
(Yoman, 2012). Hal ini dapat dilihat dari kutipan kedua bab tersebut berikut ini:
“Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 43
1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi dan memberdayakan hak-hak masyarakat adat dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat bersangkutan. ...
Pasal 44
Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli dengan peraturan perundangan-undangan. Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 57
1) Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.
2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan.
3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan.
4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Perdasi.
Pasal 58
1) Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan menetapkan jati diri orang Papua.
2) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjangan pendidikan. 3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di
jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, 2008, hal. 15 , 18-19).
Arus atau ‘hembusan’ globalisasi berhembus begitu cepat dan keras di bumi
Cendrawasih ini. Perubahan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh perkembangan
informasi dan teknologi dalam waktu yang singkat mampu merubah kondisi daerah dan
masyarakat setempat. Penerimaan akan suatu hal yang baru dan asing bukanlah hal
yang baru bagi Papua.
Sejarah mencatat bahwa sebelum pos pemerintahan Belanda didirikan pada tahun 1898,
Kristen dan menyelengarakan pendidikan di Papua. Aktivitas zending diawali dengan
kedatangan dua orang Jerman yakni Carl Ottow dan Johan Geissler pada tahun 1855.
Kedua missionaris tersebut memulai memperkenalkan ajaran Kristiani dan pendidikan
barat di Papua. (Meteray, 2012: 31-32)
Kemudian pada tahun 1923, I.S. Kijne, seorang guru Belanda tiba di Papua. Kijne
berupaya untuk mendidik orang asli Papua dan membangun harga diri orang Papua
melalui pengajaran, pengetahuan, dan kesenian. Selama 35 tahun (1923-1952) Kijne
telah menciptakan berbagai macam bahan bacaan dan lagu yang memuat kearifan lokal
(Meterey, 2012: 34-37). Selain Kijne, terdapat pula J.P.K. van Eechoud, pejabat resident
Papua pada tahun 1945 yang memiliki peranan yang besar dalam membangkitkan
kesadaran Papua untuk membangun daerah mereka sendiri. Menurut Bernarda
Meteray, Van Eechoud “memprakarsai pembukaan kursus berpola asrama, yang
memberikan materi pendidikan bidang pemerintahan, kesehatan, pertanian,
kemiliteran, dan pendidikan” (Meterey, 2012: 263). Dia juga merupakan peletak dasar
permasalahan Papua di kancah internasional sejak tahun 1950-1960an. (Meterey, 2012:
131)
Selain zending yang mampu menyebarkan pendidikan dan informasi, perananan media
massa pada tahun 1955 juga memiliki cukup signifikan terutama dalam memberitakan
berbagai kejadian di Papua dan luar negeri serta memberikan informasi terkait ilmu
pengetahuan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.
Tabel 2. Surat Kabar dan Majalah Papua pada 19602
No. Nama Frekuensi Oplah Bahasa
1. Nieuw Guinea Koerier Harian 1.500 Belanda
2. De Tifa Mingguan 1000 Belanda
3. Pengantara Mingguan 7000 Melayu
4. Triton Mingguan 1.500 Belanda/Melayu
5. De Lens Mingguan 200 Belanda
6. Fakfak Bode Dua kali
sebulan
200 Belanda/Melayu
7. Opwaarts (CWNG) Mingguan 3.500 Belanda/Melayu
8. Arka Bulanan 1.400 Belanda
9. Madjallah Kita (Arka) Bulanan 700 Belanda/Melayu
10. Mendelingen van de Dienst van Empat 150 Belanda/Inggris
Gezondheisdszorg Bulanan Sumber: Nasionalisme Ganda orang Papua (Meteray, 2012 : 217)
Paska tahun 1955, beberapa orang antara lain; Kijne, Boelaars, dan P.C. Schoe
berpendapat bahwa perubahan zaman dan laju modernisasi sangat cepat dan
masyarakat asli Papua perlu menyesuaikan dengan tuntutan laju tersebut dan dididik
sesuai dengan tuntutan dunia modern (Meteray,2012: 247). Kini dapat dilihat bahwa
masyarakat asli Papua mulai menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia modern yang
dibawa oleh arus globalisasi ini. Oleh karena itu, pertanyaan saat ini adalah bagaimana
keberadaan kebudayaan Papua bertahan berhadapan dengan tekanan globalisasi saat
ini di samping perlindungan yang telah diberikan oleh Otsus?
4. Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan Papua
Globalisasi itu bersifat multidimensi dan banyak pemikir membagi teori globalisasi
kedalam tiga kategori yakni globalisasi politik, ekonomi dan kebudayaan. Peran mass
media dan komunikasi itu sendiri kerap didiskusikan ketika berbicara tentang
globalisasi kebudayaan (Movious, 2010: 8). Ketika berbicara tentang globalisasi
kebudayaan, sering teori tentang imperialisme kebudayaan turut dibicarakan. Teori
tersebut menjelaskan tentang sebuah bentuk kolonialisme yang baru yang mana mass
media memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan kapitalisme global yang
mempromosikan kebudayaan Amerika seperti konsumerisme, kepuasaan instant dan
individualisme (Movious, 2010: 10). Selain itu, kapitalisme global ini telah menciptakan
industrialisasi dan meningkatkan eksploitasi sumber daya alam dan kejahatan.
Maka, saat kita menganalisa fenomena ini, yang disebarkan melalui teknologi
komunikasi modern dan mass media, hal tersebut telah merusak dan terus mengancam
budaya masyarakat lokal khususnya masyarakat di daerah. Kehidupan tenang
masyarakat daerah yang didasarkan oleh kesederhanaan dan mindset yang
berkecukupan dibombardir dengan berbagai informasi dan tren yang tidak tersaring
terlebih dahulu. Informasi, perkembangan-perkembangan atau tren yang masuk tidak
sedikit merupakan budaya barat atau yang dapat disebut dengan McDonalisasi yang
Namun, teori tersebut masih tetap diperdebatkan dan kita tidak dapat mengatakan
bahwa proses globalisasi ini disebabkan oleh Amerika atau upaya Amerikanisasi dunia.
Perlu diingat juga bahwa proses imperialisme dan globalisasi berbeda. Imperialisme
jelas berbicara tentang dominasi suatu negara atas perekonomian dan politik negara
lain dengan kata lain merupakan sebuah proses yang dilakukan karena maksud
tertentu. Lain halnya dengan globalisasi yang merupakan sebuah proses yang terjadi
tanpa adanya maksud tertentu. Sebuah proses yang tidak bermaksud menciptakan
keterikatan atau ketergantungan antar negara tetapi justru terjadi. Tanpa adanya
pemaksaan atau tekanan yang nyata. Proses ini bekerja pada tingkatan global dan diluar
kekuatan imaginasi manusia (John Thomlinson dikutip oleh Robertson & White, 2003 :
121-123)
Globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks dan rumit yang tidak dapat
berlangsung hanya karena satu nation-state saja melainkan seperti yang sudah dibahas
sebelumnya bahwa proses ini diakibatkan oleh berbagai ‘kekuatan’ atau ‘forces’. Oleh
karena itu perlu ada pemahaman tentang cultural flow atau alur budaya. Menurut Arjun
Appudarai, ada lima ‘scapes’ yang mempengharui budaya yakni ethnoscapes,
mediascapes, technoscapes, financescapes, dan ideoscapes. Ethnoscapes mengacu pada
arus atau pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain seperti turis dan imigran.
Mediascapes mengacu pada teknologi mass media dan gambar. Technoscapes berkaitan
dengan teknologi lintas batas atau transboundary. Sementara Finanscapes mengacu pada
peredaran uang. Dan Ideoscapes intinya mengacu pada aspek politik dan idiologi
(Appudarai dikutip dalam Movious, 2010: 19-20).
Budaya atau ‘Culture’ merupakan salah satu kata tersulit dalam bahasa Inggris. Kata
‘culture’ itu sendiri memiliki definisi yang cukup rumit dan bervariasi, sebuah penelitian
yang dilakukan oleh dua antropolog A.L.Kroeber dan Clyde Kluckhohn pada tahun
1950an menunjukan bahwa ada lebih dari 150 definisi. Hal ini menunjukan bahwa kata
tersebut bisa memiliki makna dan arti yang begitu luas dan kompleks. Namun, untuk
bisa memahami keseluruhan makna dari kata tersebut, kita dapat menggunakan arti
budaya atau culture, yang diggunakan dalam sebuah konferensi UNESCO, sebagai ‘the
way of life of a collectvity’ atau keberlangsungan hidup atau cara hidup secara kolektif.
Berdasarkan pandangan Bronislaw Malinowski, aspek utama budaya itu sendiri
merupakan kesatuan norma-norma yang memungkinkan adanya kerjasama antar
anggota dalam sebuah masyarakat agar dapat mengendalikan lingkungannya.
Malinowski juga menambahkan bahwa kesatuan tersebut dapat berupa lembaga
perekonomian, hal tersebut juga berkaitan dengan teknologi dan institusi pendidikan
dan merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan. Sementara Melville J. Herkovits
memandang hal tersebut sebagai alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan
kekuatan politik (Herkovits dikutip dalam Setiadi, 2006)
Papua terdiri dari beragam suku, “berdasarkan musyawarah Dewan Adat Papua, dapat
diklasifikasikan dalam tujuh kelompok-kelompok suku, yaitu (i) Wilayah adat I (Mamta),
membawahi kurang lebih 86 suku. Wilayah adat ini berada di Papua bagian utara
Jayapura (sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea) hingga Membramo
(sebelah barat), dan bagian selatan berbatasan dengan gunung Jayawijaya. (ii) Wilayah
adat II (Saireri), membawahi kurang lebih 31 suku. Wilayah adat ini berada di Teluk
Cendrawasih, Biak, Yapen – Waropen, hingga Yeretuar. (iii) Wilayah adat III (Bomberai),
membawahi kurang lebih 52 suku. Wilayah adat ini berada dibagian kepala burung, yang
disebelah selatan berbatasan dengan Fakfak (Teluk Bintuni), termasuk Manokwari dan
Sorong. (iv) wilayah adat IV (Domberai), membawahi kurang lebih 18 suku. Wilayah
adat ini berada di Fakfak, Teluk Arguni (Kiamana), dan disebelah utara berbatasan
dengan Teluk Bintuni serta adat Bomberai. (v) Wilayah adat V (Anim-Ha), membawahi
kurang lebih 29 suku. Wilayah adat ini berada di selatan Papua, yang disebelah barat
berbatasan dengan wilayah adat Mi-Pago dan sebelah utara dengan wilayah adat
La-Pago. (vi) Wilayah adat VI (La-Pago), membawahi kurang lebih 19 suku. Wilayah adat ini
di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah adat Anim-Ha, di sebelah barat dengan
wilayah Mi-Pagodan sebelah timur dengan wilayah Papua New Guinea. (vii) Wilayah
adat VII (Mi-Pago), membawahi kurang lebih 13 suku. Wilayah adat ini di sebelah utara
berbatasan dengan wilayah adat Saireri dan Mamta, disebelah barat dengan wilayah
adat Domberai dan Saireri, dan sebelah timur dengan wilayah adat Anim-Ha”. Bahasa
lokal yang digguanakan di tanah Papua berjumlah kurang lebih 255 buah (Prie, 2012:
Dari segi ethnoscapes Papua merupakan salah satu daerah penerima program
transmigran terbesar (hingga tahun 2000) yang menyebabkan banyaknya jumlah
migran yang masuk ke wilayah tersebut yang di antaranya berasal dari pulau Bali, Jawa,
Sulawesi dan Kalimantan. Berdasarkan sebuah laporan, pada tahun 2010 dari jumlah
penduduk provinsi Papua yakni 2, 833, 3813 sementara jumlah penduduk Provinsi
Papua Barat : 526, 9604, di antaranya 49% merupakan warga asli Papua dibanding 51%
migran (Dargur, 2014). Angka persentase migran tersebut dapat terus meningkat jika
melihat pola transmigrasi dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 1971-2000 tercatat migrasi yang masuk ke Papua mencapai 719. 866 jiwa
sementara yang keluar hanya 99. 614 jiwa (Asril, 2015).
Dilema transmigrasi merupakan salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh
masyarakat dan pemerintah daerah di Papua. Pengaruh yang tampak sebagaimana
disebutkan Farhadian (dikutip dalam Asyhari-Afwan, 2015: 18) adalah budaya Papua
mengalami perubahan. Salah satunya, misalnya, adalah kota Jayapura yang mewakili
potret kota metropolitan yang berbanding terbalik dengan situasi yang ada di wilayah
pegunungan. Kondisi di kota Jayapura sesungguhnya dapat kita lihat dari kota-kota
yang terdapat perusahaan multi-nasional seperti Freeport dan British Petroleum, dan
juga berbagai LSM baik lokal maupun internasional berjamuran di daerah ini. Hal
tersebut menambah munculnya keberagaman etnis (Melayu, Kaukasia ataupun Afrika)
di Tanah Papua dan konsekuesinya mempengaruhi kultur Papua secara keseluruhan.
Contoh kasus yang lain adalah kota Timika. Ia dapat menjadi sebuah studi perbandingan
yang cukup menarik terkait akibat dari masuknya beragam etnis, khususnya orang luar
(luar negri) terhadap masyarakat Papua. Sejak tahun 1973, Timika yang terletak di
Kabupaten Mimika, merupakan wilayah operasi salah satu perusahaan tambang emas
dan tembaga terbesar di dunia, Freeport. Kota yang dahulu sepi telah berkembang
menjadi salah satu kota tersibuk, menyebabkan terjadinya perubahan pola hidup
suku-suku asli disekitar kabupaten Mimika dan suku-suku-suku-suku Papua lainnya. Kebudayaan Barat
yang masuk diadopsi oleh masyarakat Papua seperti halnya sarapan roti, mengenakan
jeans dan lain-lain.
Beroperasinya perusahan tambang tersebut menyebabkan degradasi lingkungan dan
ketegangan. Masyarakat yang dahulunya damai dan sederhana menjadi terasuki
pandangan materialistik. Kesuksesan semakin diukur berdasarkan besarnya angka
dalam akun bank seseorang, jumlah kendaraan atau banyaknya rumah yang dimiliki
oleh seseorang. Tinggal di Papua dan berusaha mencari pekerjaan, tidak mengherankan
jika mendengar orang berkata “Kenapa tidak mencoba di Freeport? Gajinya bisa belasan
juta”. Karakteristik tersebut bukanlah karakter masyarakat Papua yang pada dasarnya
merupakan manusia-manusia yang dekat dengan alam dan memiliki ikatan keluarga
yang erat. Namun, karakter tersebut perlahan menghilang dan digantikan dengan
karakter yang baru.
Salah satu contoh perubahan yang dapat dilihat ialah pola pikir orang tua dulu terkait
jumlah anak yang dimiliki, banyak anak merupakan sebuah berkat yang diberikan oleh
Tuhan, berbanding terbalik dengan orang tua sekarang yang menganggap hal tersebut
sebuah beban. Pola pikir masyarakat semakin peka terhadap keuntungan ekonomi dan
materialistik. Tidak hanya di Timika saja melainkan hampir seluruh kota-kota besar di
Papua juga mengalami hal serupa. Kebutuhan dasar masyarakat mengalami pergeseran.
Contohnya dapat kita lihat dari makanan. Makanan khas Papua yang dihasilkan dari
Tanah Papua itu sendiri perlahan tersingkirkan dengan makanan-makanan ‘impor’
seperti hamburger KFC atau Pizza yang menjadi favorit banyak orang ketimbang
papeda. Bahkan makanan seperti nasi goreng, mie, bakso, gado-gado dan lainnya pun
lebih banyak ketimbang makanan tradisional Papua. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
jumlah kios-kios kecil hingga ruko dan pertokoan besar lainnya di jalan raya yang
menjajakan makanan non-Papua. Hal ini juga mencerminkan bagaimana pola hidup
masyarakat di Papua mengalami perubahan dan bagaimana generasi muda Papua yang
tidak sadar akan budayanya sendiri.
Melalui mediascapes dan technoscapes, semenjak televisi dan telepon gengam
(Hanphone) menjadi bagian integral yang sulit dipisahkan dalam pola hidup masyarakat
abad ke-21, Papua juga tidak terkecualikan. Kenyataan yang dapat dilihat di sini ialah
rata-rata masyarakat Papua menikmati waktu luang mereka di depan televisi dan
seterusnya. Anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dibandingkan
sekolah dan program-program yang ada juga lebih menarik ketimbang pelajaran
sekolah. Para orang dewasa pun tidak luput dari cengkeraman televisi yang memberikan
gambaran tentang pola hidup yang mewah dan kebarat-baratan (Wibowo, 2007). Selain
itu, dengan teknologi saat ini yang sangat maju, televisi dilengkapi dengan cable
networks yang mampu menyiarkan program-program dari berbagai belahan dunia,
hanphone yang dilengkapi dengan jaringan internet sehingga mampu menerima dan
berbagi informasi kepada siapa saja di dunia. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan
sebelumnya, kebanyakan masyarakat daerah masih belum siap untuk menerima
informasi dan gambar-gambar yang terlalu berlebihan.
Kebudayaan atau pola hidup asing yang kerap digambarkan melalui televisi, buku,
majalah, film, lagu, gambar dan lain-lain, sementara budaya Papua sendiri jarang
diekspos. Beberapa aspek budaya Papua terkadang mengalami interprestasi yang
negatif, contohnya koteka yang dianggap suatu hal yang menjijikan dan memalukan
(Fatubun, 2011: 112-124). Menurut pendapat beberapa tokoh, peran media khususnya
televisi yang lebih mengutamakan secara perlahan menyisipkan budaya asing
dibandingkan materi-materi yang mendidik bagi para penonton. Media secara khusus
televisi dan internet dapat diberdayakan secara baik dan masyarakat mampu
mendapatkan keuntungan. Melalui kedua ‘alat’ tersebut dapat membantu dalam
perkembangan intelektual, menambah wawasan serta memajukan perkembangan
teknologi di Papua. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa kemajuan teknologi dan
peran mass media diarahkan bukan demi kebutuhan masyarakat melainkan lebih
kepada kebutuhan masyarakat yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
dan mass media (Wibowo, 2007). Dalam nada yang sama, Andreas Goo (dikutip dalam
Asyhari-Afwan, 2015: 26) menyatakan bahwa gelombang kemoderenan yang merambah
Papua sulit dimengerti orang Papua. Nampaknya orang Papua mengalami “lompatan”
budaya dengan berkah globalisasi (hasil teknologi dan media) yang berdampak buruk
terhadap ekonomi, sosial dan budaya mereka, sebagaimana telah disebut di atas.
Sementara itu, keberagamaan orang Papua juga mengalami pergeseran dan pengaruh
dari globalisasi, terutama media, khususnya di kalangan remaja. Kalau sebelum media
sebagai sumber otoritas kegamaan. Pelbagai media, termasuk media sosial, membuat
sumber otoritas keagamaan menjadi lebih luas. Para remaja bisa mencari jawaban atas
permasalahan atau isu-isu sosial melalui layanan media. Di sini, kerap pelbagai media
menawarkan tafsir keagamaan yang beragam dan kerap kontradiktif, sehingga kerap
para remaja bisa memahami agama dari tafsiran yang konservatif atau cenderung
radikal.
‘Ada gula ada semut’ adalah sebuah peribahasa yang relevan untuk menggambarkan
perekonomian Papua. Papua selalu dianggap sebagai salah satu pulau yang melimpah
akan sumber daya alam dan telah menjadi pusat perhatian bagi banyak orang baik
dalam maupun luar negri. Dengan diberlakukannya Otsus, triliunan rupiah masuk ke
provinsi ini. Financescape mengacu pada peredaran uang dan dalam konteks ini
financescape merupakan alat pemicu ethnoscape di tanah Papua. Di tahun 2003, tercatat
bahwa 90% migran di Papua berdomisili di kota-kota besar di Papua dan 90% dari
perekonomian Papua (perdagangan, pekerja, transportasi dan perusahaan swasta dan
bisnis lainnya) dikendalikan oleh mereka. Maka dari itu, masyarakat Papua mulai
tersingkirkan. Pada tahun 1959 jumlah migran hanya 2% dari jumlah penduduk yang
ada, di tahun 1971 angka tersebut meningkat menjadi lebih dari 5% dan di tahun 2000
angka tersebut telah mencapai 35% (Widjojo dkk dikutip Suryawan, 2015). Ada
ketakutan dalam provinsi tersebut bahwa dalam beberapa tahun kedepan masyarakat
Papua akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri dan akhirnya termarginalkan
secara politik dan ekonomi (Widjojo dkk, 2009: 9).5
Tidak diragukan, bahwa arus migran terus meningkat di Papua, terutama kota Jayapura
sebagai ibu kota Provinsi Papua. Jayapura bahkan menjadi tempat destinasi favorit
kedua setelah Kabupaten Sarmi. Pertumbuhan tersebut salah satunya berasal dari kaum
migran yang masuk ke Jayapura yang datang dari berbagai daerah baik dari Papua
maupun Papua yang mana kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap yang
secara tidak langsung berkontribusi terhadap angka pengangguran di kota Jayapura,
sedangkan lapangan kerja yang tersedia relatif terbatas. Hal tersebut juga berpotensi
pada peningkatan angka kriminalitas di Kota Jayapura. Berdasarkan data BPS Provinsi
Papua (2014), jumlah penduduk kota Jayapura dari tahun 2008-2014 meningkat dengan
pesat, hal ini terlihat sejalan dengan tren kriminalitas di Kota Jayapura. Murungnya,
pelbagai modus kriminalitas yang terjadi di Papua juga untuk beberapa derajat
dipelajari dari media yang memborbardir orang Papua dengan berita-berita
kriminalitas.
Ideoscapes yang mengacu pada aspek idiologi dan untuk ‘scape’ ini terdapat dua
pandangan. Pertama yang melihat adanya pengaruh positif dengan masuknya ide atau
pemikiran baru. Pemikiran-pemikiran baru ini dapat membantu terciptanya
pemahaman yang lebih baik akan dunia serta memberikan ide dan inspirasi yang segar
bagi banyak orang. Berkat globalisasi bagi masyarakat Papua konsep demokrasi, hak
asasi manusia dan kebebasan menjadi hal yang tidak asing lagi bagi mereka. Kata-kata
yang dahulu tidak dipahami kini menjadi pokok pembicaraan hangat bagi tiap orang
Papua. Para anak muda juga bersemangat dan memiliki ketertarikan yang dalam ketika
mulai berbicara mengenai hal-hal diatas. Banyak yang akan mengatakan bahwa hal ini
disebabkan oleh kerinduan masyarakat Papua untuk merasakan sebuah pemerintahan
yang lebih demokratis, terutama melihat Otsus yang tidak menghasilkan sesuatu yang
signifikan. Masyarakat Papua merasa tidak bebas di atas tanahnya sendiri dan berbagai
kasus pelanggaran hak asasi manusia terus mewarnai kehidupan mereka. Memang
sebuah ironi bagi banyak orang bahwa tanah yang subur tetapi masyarakatnya
menderita. Pemerintah daerah dan pusat telah mengecewakan banyak orang
(Hardianto, 2011: 7).
Permasalahan yang dihadapi inilah yang membuat orang Papua terbuka terhadap
gagasan-gagasan baru dan dengan membuka pikiran dan diri banyak yang terinspirasi
untuk mencari sebuah solusi dengan cara damai. Pandangan kedua, melihat dari segi
yang pesimistis terhadap bagaimana ideologi asing ‘membombardir’ dengan
pemikiran-pemikiran barat. Hal ini dilihat sebagai sebuah ‘penjajahan terselubung’ dengan cara
‘mengendalikan hati dan pikiran para generasi tua maupun muda di negara-negara
miskin di dunia. Mereka mengendalikan dengan sebuah tekanan tombol menggunakan
internet, media internasional, dan cara telekomunikasi canggih lainnya’ (Razak, 2011:
Karakter sebuah bangsa dibentuk oleh tradisi dan budaya yang terus dijalankan dan
dilestarikan. Kekuatan sebuah bangsa terletak pada kebanggaan rakyatnya terhadap
asal usulnya. Dalam hal ini masyarakat Papua terus mengalami culture shock. Mereka
mengalami lompatan besar dalam sejarah perkembangan manusia, dan yang mana
orang Papua masih mengalami ketidakpastian dan belum dapat menyesuaikam dengan
berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Masyarakat ini masih baru terhadap
berbagai tren luar dan masih belum terbiasa dengan hidup serba modern. Tidak banyak
generasi muda Papua yang bangga dengan budayanya. Mereka cenderung akrab dengan
lagu-lagu luar seperti reggae yang dipopulerkan oleh Bob Marley. Bagi orang Jamaika
reggae merupakan lagu kebebasan tetapi bagi anak muda Papua mereka menyukainya
karena adanya kesamaan warna kulit (Wayar, 2011: 125-128).
Pengaruh globalisasi terhadap budaya Papua menggambarkan sebuah realita yang
menyedihkan yang mana budaya tiap suku-suku mulai kehilangan maknanya.
Berdasarkan analisis di atas tentang berbagai pengaruh terhadap budaya, dapat
disimpulkan bahwa masyarakat Papua dalam hal ini generasi muda Papua perlahan
mulai kehilangan identitas dirinya. Terdapat krisis identitas bagi generasi muda Papua.
Oleh karena itu, peran tiap individu dalam masyarakat sangat penting dalam memahami
pentingnya budaya sendiri. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan juga cukup besar
dalam memfasilitasi masyarakat menghadapi arus globalisasi.
Pada akhirnya, mengikuti garis pemikiran para transformationalists, seperti Rosenau
dan Giddens, kami berpandangan bahwa globalisasi menyebabkan perubahan
kebudayaan di Papua, sebagai bagian dari masyarakat yang mengglobal. Orang Papua
semakin terhubung dengan dunia luar, namun dalam dunia yang penuh dengan
ketidakpastian. Globalisasi menciptakan jurang pemisah antar masyarakat dunia, secara
khusus sebagian orang Papua masih mengalami marjinalisasi di atas tanahnya yang
kaya, mengutip patra transformationalists, disebabkan oleh perekonomian dunia,
dengan menciptakan sebuah ‘sovereignity regime’ baru dan munculnya organisasi politik
dan/atau ekonomi global baru yang kuat seperti korporasi-korporasi multinasional,
di luar keuntungan dan manfaat yang diterima suatu negara dan komunitas
masyarakatnya, memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan masyarakat Papua.
5. Penutup
Tulisan di atas menggambarkan bahwa proses globalisasi terhadap Papua merupakan
sebuah realita yang kelam terkait pelestarian budaya. Banyak yang mengkhawatirkan
bahwa Papua akan mengalami hal yang serupa dengan suku asli Amerika-Indian atau
suku Aborigin di Australia atau seperti halnya suku Betawi yang termarginalkan di
Jakarta. Singkatnya, ada ketakutan bahwa dengan punahnya budaya maka keberadaan
orang Papua pun akan ikut lenyap.
Hal ini tidak berarti bahwa globalisasi merupakan sebuah alat yang jahat atau
menghancurkan atau alat yang digunakan oleh sekelompok orang demi tercapainya
kepentingan kelompok tersebut. Globalisasi itu kompleks. Kami setuju dengan
pernyataan yang pernah disampaikan oleh Kofi Annan, “ debating against globatization
is like debating against the Law of Gravity”. Proses globalisasi memang akan terjadi
setelah beberapa fase perkembangan manusia, mulai dari ketika manusia menciptakan
teknologi, menemukan dataran baru, kolonialisasi, revolusi industri dan pada akhirnya
revolusi informasi dan teknologi. Keberadaan proses tersebut tidak terhindarkan.
Pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Papua itu sendiri positif dan negatif.
Masyarakat Papua perlu memahami hal-hal positif yang didapatkan dari proses ini dan
menolak hal-hal yang akan memberikan dampak negatif. Setiap individu perlu bekerja
sama dengan pemerintah untuk menyaring tiap informasi yang masuk. Kebijakan dalam
negeri dan daerah perlu ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk
memenuhi kepentingan asing yang hadir melalui tekanan komunitas global.
Banyak penyesuaian yang dapat dilakukan demi kepentingan budaya Papua. Seperti
yang telah dibahas sebelumnya, sudah saatnya untuk mengutamakan peran institusi
pendidikan di Papua agar menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab,
berkualitas dan berwawasan. Individu yang akan menerangi kegelapan. Pemerintah
perlu memahami kebutuhan masyarakat Papua dan bukan hal-hal superficial dan yang
masyarakat cukup membantu dalam proses globalisasi. Perlu adanya pemahaman dan
saling menghormati sesama orang Papua, ikatan persaudaran antar sesama orang Papua
yang dilandaskan oleh saling menghargai akan menciptakan sebuah masa depan yang
lebih baik bagi generasi mendatang. Kemudian, perlu ditingkatkan perasaan saling
memiliki dan penerimaan sebagai orang Papua.
Kami berpandangan bahwa ketika masyarakat Papua mampu menghargai, mengenal diri
mereka sendiri dan menerima keanekargaman yang ada di tanah Papua, maka mereka
akan siap menghadapi berbagai tantangan di dunia, termasuk arus deras globalisasi. Di
sini, perlu adanya penekanan untuk saling menghargai dan menerima antar suku yang
ada pada ketujuh wilayah adat di Papua. Penerimaan ini harus terjadi secara mutual,
suku-suku perlu memahami bahwa tiap daerah memiliki karakter dan tradisi yang
berbeda tetapi sama-sama orang Papua. Peranan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan
Dewan Adat Papua memainkan fungsi yang sangat penting dalam menanamkan
pemahaman akan keberagaman suku yang ada dan perlunya mutual respect and
understanding sesama suku yang ada di atas bumi Cendrawasih, dan juga
suku-suku lain di luar Papua. Media massa seperti radio, koran, majalah dan buku dapat
digunakan untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait hal tersebut. Di sini
juga penting bagi media massa, seperti televisi untuk memberikan informasi yang
edukatif sehingga tidak akan memunculkan persepsi yang negatif. Institusi pendidikan
dari dasar hingga perguruan tinggi juga perlu menanamkan pembelajaran tentang
ragam suku yang ada di Indonesia dan secara khusus di Papua.
Disamping itu, korporasi multinasional yang berada di Papua perlu mempertanggung
jawabkan berbagai kerusakan yang telah dilakukan di Papua. Masyarakat bekerja sama
dengan pemerintah daerah dapat mengawasi dan meminta korporasi-korporasi yang
ada untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Bentuk
pertanggungjawaban yang lain ada ialah turut berperan aktif dalam membangun
wilayah atau daerah korporasi ini beroperasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan
menawarkan beasiswa, membangun perpustakaan, sekolah atau rumah sakit yang
Kemudian, kami juga berpendapat dana otsus yang begitu besar perlu dikelola dengan
baik. Perlu adanya sebuah badan pengawas6 yang memantau aliran dana tersebut dan
memastikan bahwa perkembangan yang terjadi itu sustainable atau berlanjut dan akan
membuahkan hasil. Oleh karena hal inilah, diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang unggul. Kesuksesan zending dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh
Belanda dapat ditiru dalam melatih dan memberikan pembekalan kepada masyarakat
Papua terkait pengelolaan dana, pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan dan
pemhaman tentang globalisasi.
Ketika masyarakat Papua telah siap menghadapi dunia global, maka mereka akan bisa
menghargai budaya lain, kepercayaan yang berbeda, dan orang-orang yang beragam.
Penerimaan dan keterbukaan ini akan membantu membangun daerah tanpa harus
kehilangan identitas atau kehilangan tradisi dan kepercayaan yang ada. Bila hal tersebut
dapat tercapai maka globalisasi tidak akan menjadi sebuah ancaman melainkan
keuntungan.
Dalam hal ini bukan serta merta berarti bahwa masyarakat Papua kembali ke kehidupan
tradisional dan menolak modernisasi, melainkan untuk merespons globalisasi perlu
adanya transformasi. Kijne pernah menulis dalam sebuah artikel di Nieuw Guinea
Koerier pada tahun 19617, jika Papua ingin berubah sesuai dengan perkembangan
zaman, maka harus diimbangi dengan keadaan masyarakat setempat. Masyarakat perlu
memahami makna dari perubahan tersebut dan bukan asal berubah mengikuti zaman
atau tren yang ada.
Kami sepahaman dengan para Transformationalists, dan melihat untuk Papua cara yang
dapat dilakukan untuk merespon globalisasi adalah dengan transformasi. Transformasi
bukan berarti berubah melainkan menyesuaikan atau merestrukturiasasi tradisi,
budaya dan kepercayaan sesuai dengan perkembangan yang ada. Sebagai gambaran
kami memberikan sebuah contoh yang sederhana: membangun perumahan,
rumah permanen yang dibangun mengikuti desain yang sesuai dengan iklim dan rumah
adat yang ada di Papua. Dengan ini dapat dilihat bahwa membangun perumahan
menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia modern dan juga menyesuaikan
dengan budaya setempat tanpa mengikis karakter daerah.
Melalui proses globalisasi, dengan adanya informasi yang sesuai dan terekspos ke dunia,
Papua mampu berkembang dengan cepat. Hal ini dapat memberikan berbagai kelebihan
jika pemerintah menggunakan kesempatan ini dengan baik dan tidak terjerumus
olehnya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa sebuah bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Sebuah bangsa yang terdiri dari
manusia-manusia yang bertanggung-jawab dan beradab.
PUSTAKA ACUAN
Asril, S. (2015, June 07). Upaya Hentikan Transmigrasi ke Papua Sudah Dilakukan 15
Tahun Lalu. Retrieved from Kompas.com/National:
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/07/15520261/Upaya.Hentikan.Tra nsmigrasi.ke.Papua.Sudah.Dilakukan.15.Tahun.Lalu
Asyhari-Afwan, B (2015). Mutiara yang Terpendam, Potensi Kearifan Lokal untuk
Perdamaian di Tanah Papua, Yogyakarta: CRCS.
Bertrand, J. (2004). Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge: Cambridge
University Press.
Dargur, R. (2014, November 5). Program Transmigrasi Papua akan Membuat Warga
Lokal Makin Tersingkir . Retrieved from UCAN INDONESIA:
http://indonesia.ucanews.com/2014/11/05/program-transmigrasi-ke-papua-Hardianto, B. J. (2011, December 15). Ironi Papua : Kaya Tetapi Menderita . KOMPAS .
Held, D. (1999). Global Transformations, Politics, Economics and Culture. California:
Standford Univeristy Press.
Kartasasmita, G. (2001). Globalization and the Economic Crisis: The Indonesian Story .
Retrieved from Weatherhead Centre for International Relation Harvard University : http://projects.iq.harvard.edu/files/fellows/files/kartasasmita
Kweifio-Okai, C. (2014, December 12). Global Development 2004 Indian Ocean Tsunami :
10 years on. Retrieved from theguardian: http://www.theguardian.com/global-development/2014/dec/25/where-did-indian-ocean-tsunami-aid-money-go
Mahbubani, K. (2013). The Great Convergence: Asia, The West, and The Logic of One
World. New York: Public Affairs.
Movious, L. (2010). Cultural Globalisation and Challenges to Traditional Communication
Theories. PLATFORM: Journal of Media and Communication 2(1)(January), hal.
6-18.
Muller, K. (2008). Introducing Papua. Indonesia: Daisy World Book.
Widjojo, M.S. (E.D.). (2009). Papua Road Map : Negotiating the Past, Improving the
Present and Securing the Future. Jakarta : Serpica.
Permanent Mission of The Republic of Indonesia to The United Nations. (2004). An
Overview of The Restoration of Papua Into The Republic of Indonesia. New York: Permanent Mission of The Republic of Indonesia to The United Nations .
Prie, M. M. (2012). Ini Tong Pu Hidup. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Winarno, M. B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta : Centra of
Academic Publishing Service (CAPS) .
Razak, M. A. (2011). Globalization and Its Impact on Education and Culture. World
Journal of Islamic History and Civilization 1(1) , hal. 56-69.
Rudy, D. T. (2011). Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global.
Bandung: PT. Refika Aditama .
Setiadi, D. E. (2006). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Prenada Media Group .
Setiawan, I.N. (2015, December 01). Rezim (Berpikir) Penjajah. Retrieved from cahaya
Papua.com: http://www.cahayapapua.com/rezim-berpikir-penjajah/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua. (2008, April 27). Retrieved from
http://prokum.esdm.go.id/uu/2001/uu-21-2001.pdf
Thomlinson, J. (2003). The Discourse of Cultural Imperialism. Dalam Robertson,R.
Kathleen E.W, Globalization: Critical Concepts in Sociology (hal. 89, 121-123).
London dan New York: Routledge (Taylor and Francis Group).
The Jakarta Post. (2008). The Voice of Reason : A Collection of Some of The Best
Editorials of The Jakarta Post 1983 - 2008, Special autonomy for Papua (hal. 262
– 263). Jakarta: Kompas – Gramedia Group.
Wayar, R. (2011). Budaya Epen, Generasi Epen. Dalam I. N. Suryawan, Narasi Sejarah
Sosial Papua : Bangkit dan Memimpin Dirinya Sendiri (hal. 125-128). Malang: Intrans Publishing .
Wibowo, F. (2007). Kebudayaan Menggugat: Menuntut Perubahan atas Sikap, Perilaku
Serta Sistem yang Tidak Berkebudayaan. Yogyakarta : Pinus Book Publisher .
Wuryandari, G. (2011 ). Politik Luar Negri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik
Internasional . Jakarta : Pustaka Pelajar .