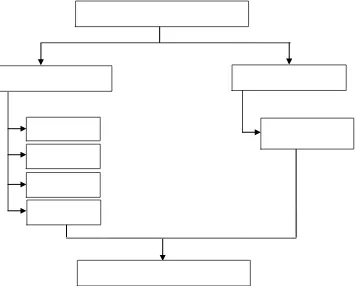BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM
merupakan sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam
aktivitas bisnis sehari-hari.UMKM merupakan salah satu ujung tombak yang
penting bagi Indonesia untuk dapat menguasai pasar bebas di tahun mendatang.
UMKM juga telah menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia karena
mampu menyerap banyak tenaga kerja yang saat itu pengangguran atau terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, UMKM mampu bertahan di
tengah guncangan krisis moneter yang melambungkan harga barang- barang
kebutuhan rumah tangga pada masa itu. UMKM jelas memegang peranan vital
dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Setiap negara memiliki definisi dan konsep UMKM yang berbeda-beda
tetapi secara umum sebuah usaha mikro mengerjakan lima (5) atau kurang pekerja
tetap sedangkan usaha kecil menengah bisa berkisar antara kurang dari 100
pekerja, misalnya di Indonesia. Selain menggunakan klasifikasi jumlah pekerja,
banyak negara yang juga menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung
dan tanah) dan omset dalam mendefisinikan UMKM (Tambunan, 2009).
Di Indonesia sendiri, definisi dan karakteristik UMKM diatur dalam
berbagai perspektif yaitu:
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/atau badan
usaha perorangan dengan aset s/d Rp 50 Juta dan Omset maksimum 300
juta per tahun.
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar dengan aset > 50 Juta-500 Juta dan
omset Rp 300 juta-Rp 2,5 Milyar per tahun.
c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan aset > Rp 500 Juta-Rp 10
Milyar dan omset > Rp 2,5 Milyar-Rp 50 Milyar per tahun.
2. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria usaha adalah:
a. Usaha Mikro, memiliki 1-4 orang tenaga kerja
b. Usaha Kecil, memiliki 5-19 orang tenaga kerja
c. Usaha Menengah, memiliki 20-99 orang tenaga kerja
d. Usaha Besar, memiliki di atas 99 orang tenaga kerja
3. Menurut Bank Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan
a. Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta
b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta.
c. Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total asset maksimal
Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.
d. Omset tahunan lebih besar dari Rp. 1 milyar.
4. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah
kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan
yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar
Rp. 70 juta ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
2.1.1 Faktor yang Menghambat Perkembangan UMKM
Pengembangan UMKM di Indonesia belum terjadi secara maksimal karena
berbagai kendala. Ada dua faktor yang menghambat perkembangan UMKM yaitu
faktor internal dan eksternal.
A. Faktor Internal
Faktor internal yang menghambat perkembangan UMKM meliputi:
1. Kurangnya Permodalan
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk
mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh
karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha
perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan
pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan
modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit
diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang
Sebenarnya di Indonesia sudah terdapat beberapa lembaga
keuangan, baik perbankan maupun non bank, yang dapat diandalkan
untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Untuk skala mikro,
dikenal Lembaga Keuangan Mikro & Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
yang merupakan representasi dari lembaga keuangan perbankan pada
skala mikro. Untuk lembaga keuangan non perbankan, terdapat lembaga
Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sedangkan di tingkat Nasional, ada PT.
Permodalan Nasional Madan (Persero) yang melakukan pembinaan
terhadap lembaga keuangan mikro, baik yang berbentuk perbankan atau
non bank.Selain itu juga terdapat Perum Pegadaian dengan menawarkan
jasa bantuan keuangan bagi pengusaha skala mikro kecil menengah
melalui proses yang relatif sederhana dan cepat. Namun tentu saja
kemampuan finansial lembaga-lembaga tersebut tidak sesuai dengan
jumlah pengusaha skala kecil menengah (Wahyuni dkk, 2005).
Dalam kaitannya dengan permohonan kredit, untuk usaha dengan
skala kecil dan mikro, lembaga keuangan perbankan jelas tidak akan
menerima karena mereka mereka belum memiliki izin usaha dan
perbankan pastinya juga akan melihat kelayakan jenis usaha yang akan
diberikan kredit.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas
Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan
merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha
kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan
usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan
optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha
tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru
untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.
3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga,
mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan
penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan
jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang
kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan
yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat
menjangkau internasional dan promosi yang baik.
Aspek lain yang membuat jaringan usaha dan akses pasar menjadi
terbatas sekali, yaitu UMKM dihadapkan pada persoalan cost of
production yang tinggi. Tingginya cost of production ini juga turut
dipengaruhi oleh mahalnya bahan baku, tingginya cost of transportation,
banyaknya pungutan liar yang mengatasnamakan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta retribusi lain yang irrasional dan
tumpang tindih. Tingginya cost ini membuat produk UMKM kalah
bersaing dengan produk-produk impor yang beredar bebas di pasar.
Barang-barang yang sebagian dipasok secara illegal ini tampil dengan
model dan desain yang lebih bagus, harga lebih murah dan mutu juga
cukup baik. Maka, semakin terpuruklah produk UMKM Sumatera Utara
B. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan UMKM meliputi:
1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
Iklim usaha yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang
melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin, dan
menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi (Tambunan, 2006).
Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus
disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini
terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara
pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.
Selain itu juga diperlukan perlindungan hukum dan jaminan
keamanan bagi pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan usahanya.
Persoalan premanisme, biasanya kelompok preman ini mendatangi
pelaku usaha dengan meminta uang keamanan sehingga para pelaku
UMKM pun memasukkan biaya ini ke dalam cost produksinya dan akan
menyebabkan harga barang juga meningkat. Jika hal ini terjadi di semua
pelaku usaha maka akan terjadi biaya tinggi dan inflasi ekonomi di
tingkat nasional.
Kasus-kasus sweeping dan premanisme menggambarkan
kondusifitas berusaha belum didukung adanya jaminan keamanan untuk
keberlanjutan berusaha. Sekali lagi, pemerintah melalui aparat kepolisian
menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tanpa gangguan dan tekanan
dari berbagai pihak.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang
mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung
kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
3. Implikasi Otonomi Daerah
Ketentuan tentang pengurusan perizinan usaha industri dan
perdagangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) yang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan
menjalankan kegiatan usaha perdagangannya. Selain itu, ada juga
Keputusan Menteri Perindag No. 225/MPP/Kep/7/1997 tentang
Pelimpahan Wewenang dan Pemberian Izin di Bidang Industri dan
Perdagangan sesuai dengan Surat Edaran Sekjen No. 771/SJ/SJ/9/1997
ditetapkan bahwa setiap perusahaan yang mengurus SIUP baik kecil,
menengah dan besar berkewajiban membayar biaya administrasi dan
uang jaminan adalah 0 rupiah (nihil). Artinya, perizinan tidak dikenakan
biaya (Wahyuni dkk, 2005).
Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk
mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa
pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Kecil dan
Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan
menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping
itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi
yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan
usahanya di daerah tersebut.
Pemko Medan melalui Perda No. 10 Tahun 2002 mengeluarkan
aturan tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan,
Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Perda ini menetapkan
besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus perizinan. Para
pelaku usaha sebenarnya tidak keberatan dalam mengurus masalah
perizinan tetapi masalah yang timbul adalah melalui besarnya dana yang
dikeluarkan untuk mendapatkan izin tersebut. Selain itu juga, waktu yang
diperlukan dalam membuat perizinan sangatlah lama. Padahal, untuk
mendapatkan akses permodalan ke Lembaga Keuangan, UMKM harus
mempunyai legalitas dalam hal izin usaha itu (Wahyuni dkk, 2005).
4. Implikasi Perdagangan Bebas
Tahun 2015, akan mulai diberlakukan ASEAN Free Trade Area
(AFTA). Dengan adanya AFTA, maka Indonesia seharusnya sudah
mempersiapkan langkah terencana untuk menghadapi hal tersebut.
Meski demikian, AFTA sewarjanya dinilai bukan sebagai suatu ancaman
yang menakutkan bagi ekonomi Indonesia. AFTA merupakan
unggul di kawasan ASEAN. Dengan AFTA dan pembentukan
masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, maka Indonesia dapat mengambil
peluang tersebut melalui pendayagunaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM). Ada 4 hal yang akan dilakukan pada AFTA yaitu
bebas aliran jasa, bebas investasi, bebas aliran modal, dan bebas aliran
tenaga kerja terampil. Keempat hal ini, mengakibatkan terjadinya
serbuan besar- besaran barang bahkan jasa asing yang masuk ke pasar
Indonesia, demikian pula sebaliknya. Barang- barang dari produsen
Indonesia bisa bebas masuk ke negara- negara ASEAN lainnya. Disinilah
kesempatan bagi produk- produk UMKM lokal Indonesia untuk bisa
bersaing di pasar global.
Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien,
serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar
global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu
lingkungan (ISO 14000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu
ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak adil oleh negara
maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu maka
diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara
keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang
5. Terbatasnya Akses Pasar
Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang
dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional
maupun internasional.
Dalam memanfaatkan pasar global, UMKM kita bisa belajar ke
Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Ketiga negara tersebut memiliki
UMKM yang kontribusinya tinggi terhadap ekspor. Akses pemasaran
yang tidak tertembus UMKM ini juga sangat dipengaruhi lemahnya
penguasaan Teknologi Informasi (TI) oleh pelaku UMKM (Wahyuni
dkk, 2005).
2.1.2 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Kebijakan Pemerintah
Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan
pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan
perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Pengembangan UKM diIndonesia selama ini dilakukan oleh Kantor
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian Negera
KUKM). Selain Kementrian Negara KUKM, instansi yang lain seperti
Depperindag, Depkeu, dan BI juga melaksanakan fungsi pengembangan UKM
fungsi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menyusun
Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah. Demikian juga
Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.
316/KMK.016/1994 mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1-5% Iaba
perusahaan bagi Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK). Bank
Indonesia sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai
kredit bank untuk UKM.
Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20
tahun 2008) adalah:
a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai
dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara
terpadu.
Sesuai dengan UU No.20 tahun 2008, pemberdayaan UMKM
bertujuan:
a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang,
dan berkeadilan;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan
c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,
pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Pemberdayaan
Koperasi Dan UKM Tahun 2014, perkembangan UMKM ditunjukkan oleh
peningkatan jumlah UMKM sebesar 2,4 persen sehingga mencapai 56,5 juta
unit usaha pada tahun 2012 dan jumlah tenaga kerja UMKM juga meningkat
sebesar 5,8 persen menjadi sekitar 107,7 juta orang. Peningkatan jumlah unit
usaha dan tenaga kerja terbesar tercatat pada kelompok usaha menengah, yaitu
masing-masing 10,7 persen dan 14,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan unit
usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan
kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena
pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro
masih dominan yaitu 98,8 persen unit usaha dengan menampung 92,8 persen
tenaga kerja.
Sehingga berdasarkan perkembangan UMKM yang semakin pesat maka
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Pemberdayaan Koperasi Dan UKM
diarahkan kepada kebijakan berikut:
1. Penguatan badan hukum dan pengawasan koperasi.
2. Peningkatan kapasitas usaha bagi koperasi di sektor-sektor produktif.
3. Penguatan akses keuangan bagi UMKM dan penguatan KSP/KJKS.
4. Peningkatan akses dan jaringan/kemitraan usaha dan pemasaran bagi
UMKM.
6. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM di tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurut Suarja (2007) dalam Sudrajat mengungkapkan pemberdayaan
Koperasi dan UMKM dilakukan melalui:
a. Revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posisi UMKM dalam sistem
perekonomian nasional.
b. Revitalisasi koperasi dan perkuatan UMKM dilakukan dengan
memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan
pasar serta memperbaiki iklim usaha.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan.
d. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal.
2.2 Sektor Industri Rumah Tangga
Berbicara tentang UMKM, tentunya tidak terlepas dari sektor industri
rumah tangga. Industri rumah tangga pada umumnya golongan industri tradisional
dengan beberapa ciri khas utamanya, yakni a.l.: (1) sebagian besar dari pekerja
adalah anggota keluarga (istri dan anak) dari pengusaha atau pemilik usaha
(family workers) yang tidak dibayar; (2) proses produksi dilakukan secara manual
dan kegiatannya sehari-hari berlangsung di dalam rumah; (3) kegiatan produksi
sangat musiman mengikuti kegiatan produksi di sektor pertanian yang pada
umumnya sifatnya juga musiman; dan (4) jenis produk yang dihasilkan pada
umumnya dari kategori barang-barang konsumsi sederhana seperti alat-alat dapur
dari kayu dan bambu, pakaian jadi dan alas kaki (Thoha, 1998).
Industri Skala Kecil (ISK) dan Industri Skala Menengah (ISM) di
negara-negara maju memang sangat berbeda dengan industri kecil dan industri skala
menengah di Indonesia, yang sebagian besar terutama industri rumah tangga
masih sangat terbatas akan SDM dan penguasaan teknologi, juga sebagian besar
pekerja dan pengusahanya hanya berpendidikan sekolah dasar saja. Mereka
menggunakan teknologi tradisional yang kebanyakan direkayasa sendiri. Akses
informasi mengenai pasar juga sangat minim. Sangat sedikit industri skala kecil
terutama industri rumah tangga yang menggunakan sistem komputer lengkap
dengan internet. Padahal semua faktor-faktor ini sangat diperlukan untuk
meningkatkan kualitas produk, efisiensi dalam proses produksi, dan fleksibilitas.
Sebagian besar industri skala kecil di Indonesia sangat dominan di sektor
manufaktur. Sebagian besar jumlah tenaga kerja di kelompok industri tersebut
terdapat di industri rumah tangga. Selain itu juga, sebagian besar industri rumah
tangga berada di daerah pedesaan yang kebanyakan dari mereka menjadikan ISK
sebagai mata pencaharian sampingan selain bertani.
Menurut Anderson (1982), salah satu faktor utama penyebab berkurangnya
peranan industri skala kecil, terutama dari kategori industri rumah tangga, di
negara-negara industri maju dengan tingkat pendapatan yang tinggi adalah akibat
pergeseran fungsi konsumsi masyarakat. Dengan perkataan lain, dalam kondisi
seperti ini industri skala kecil harus merubah spesialisasinya dari jenis-jenis
barang yang nilai elastisitas pendapatan dari permintaannya rendah (inferior
goods) ke jenis-jenis produk dengan nilai elastisitas pendapatan dari permintaan
yang tinggi (ferior goods). Faktor-faktor lain yang menurut Anderson (1982) juga
kecil di negara-negara yang tingkat pendapatannya sudah tinggi, adalah termasuk
semakin mahalnya harga bahan-bahan baku utama akibat praktek monopsoni dan
oligopsoni di pasar input oleh sekelompok industri skala besar. Pengaruh
faktor-faktor tersebut akan lebih nyata pada tingkat industrialisasi yang lebih tinggi,
karena resources yang ada semakin terbatas, sementara jumlah pelaku ekonomi
semakin banyak dan kebutuhan konsumsi dan industri semakin besar (Tambunan,
1999).
Di dalam suatu perekonomian, selain pertumbuhan unit usaha dan jumlah
tenaga kerja yang diserap oleh industri skala kecil, pentingnya industri skala kecil
juga diukur dengan pertumbuhan nilai output dan nilai tambah, serta peningkatan
produktivitas. Industri rumah tangga memberikan kontribusi output dan nilai
tambah yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan industri kecil pada
pembentukan output dan nilai tambah dari industri skala kecil di sektor industri
manufaktur. Produktivitas tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan jumlah dan
jenis mesin (termasuk di dalamnya jenis teknologi) yang digunakan di dalam
proses produksi,dan keterampilan tenaga kerja. Produktivitas dari suatu (atau
berbagai) faktor produksi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan
untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan produksi
dalam menggunakan faktor produksi tersebut. Berarti semakin tinggi
produktivitas dari faktor produksi yang digunakan di dalam suatu kegiatan
produksi, semakin efisien dan efektif pelaksanaan proses produksi tersebut.
Tingkat produktivitas tenaga kerja bisa berbeda antara unit usaha walaupun di
produktivitas tenaga kerja di industri rumah tangga dibandingkan di industri kecil
disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu:
1. Keterbatasan akan dana, berarti keterbatasan akan barang modal seperti mesin
dan teknologi modern;
2. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah; dan
3. Organisasi, pola manajemen dan metode produksi yang pada umumnya masih
sangat tradisional
Dalam hal teknologi, bentuk-bentuk permasalahannya yang dihadapi
pengusaha-pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga bervariasi, yang
pada umumnya erat kaitannya dengan masalah-masalah SDM dan dana. Ada
dalam bentuk peralatan-peralatan produksi yang digunakan masih tradisional,
tidak mampu melakukan penelitian dan pengembangan, keterampilan pekerja
dalam menggunakan teknologi yang ada terbatas, informasi tentang teknologi
terbatas; dan ada dalam bentuk dukungan instansi teknis dan perguruan tinggi
dalam pengembangan teknologi terbatas tidak ada.
Suatu kombinasi antara lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya
kualitas SDM (pekerja dan manager), terbatasnya informasi khususnya mengenai
perubahan pasar, teknologi, dan peraturan-peraturan pemerintah maupun
mengenai perdagangan global, dan terbatasnya modal membuat
pengusaha-pengusaha kecil sulit untuk mempertahankan, apalagi meningkatkan kualitas dan
jumlah produknya. Selanjutnya, ini berarti sulit bagi mereka untuk dapat
mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasarnya di pasar ekspor maupun
domestik. Juga, dengan dana serta akses ke informasi mengenai perubahan
pengusaha-pengusaha kecil tidak dapat melakukan inovasi terhadap produk dan proses
produksinya, dan berarti tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan daya
saing global produk-produk mereka.
2.3Kebijakan Skim Kredit
Sejak Pelita III hingga saat ini telah banyak program-program
pengembangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk
mendukung industri skala kecil di tanah air. Diantaranya yang penting adalah
pengembangan sentra-sentra di beberapa provinsi, program kemitraan dengan
sistem Bapak Angkat, yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan dalam
salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,
sumberdaya manusia dan teknologi, dan subkontrakting serta berbagai macam
skema kredit (Tambunan, 1999).
Di Indonesia, pemberian kredit murah kepada pengusaha kecil
jugamerupakan kebijakan pengembangan usaha kecil (UK) dari pemerintah
yang paling populer. Sejak awal tahun 1970-an hingga awal tahun 1998 telah
sekian banyak skema kredit yang khusus didesain untuk usaha kecil,
diantaranya yang sangat populer hingga akhir tahun 1980an adalah Kredit
Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang
disubsidi oleh pemerintah. Kemudian, dua credit schemes ini diganti dengan
Kredit Usaha Kecil (KUK) yang merupakan kredit tidak bersubsidi. Dalam
KUK, bank-bank nasional diminta untuk mengalokasikan 20 persen dari
jumlah kredit yang mereka keluarkan untuk usaha kecil. Hingga Desember
1991, partisipasi dalam KUK masih sangat rendah, hanya sekitar 1 persen
Sebelumnya, KIK dan KMKP boleh dikatakan cukup berhasil dalam
bentuk efeknya terhadap peningkatan kesempatan kerja, investasi dan nilai
tambah usaha kecil. Hanya saja, kedua skema kredit tersebut akhirnya menjadi
high cost credit schemes, dengan tingkat pengembalian yang rendah. Fasilitas
kredit lainnya untuk usaha kecil adalah Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES),
yang berupa kredit komersil/tidak disubsidi, dan ditujukan pada
kegiatan-kegiatan ekonomi yang skalanya lebih kecil daripada KUK. Walaupun, tingkat
suku bunganya lebih tinggi daripada suku bunga untuk pinjaman KIK/KMKP,
KUPEDES ternyata lebih berhasil daripada KIK/KMKP karena sistem
pemberian insentif dan sangsi terhadap pelaksana program kredit tersebut di
bank-bank terkait lebih baik. Hingga awal tahun 1999, terdaftar ada 17 skema
kredit berbunga rendah yang dicanangkan pemerintah, 16 diantaranya untuk
usaha kecil dan menengah (UKM) (Tambunan, 1999).
Saat ini, berbagai skim kredit/pembiayaan dikeluarkan pemerintah untuk
mengembangkan sektor-sektor usaha ke arah yang lebih baik sehingga mampu
bersaing pada era pasar bebas ASEAN 2015 nanti. Skim kredit yang khusus
untuk UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat
adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang
menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang
menerima kredit program dari pemerintah, pada saat permohonan
kredit/pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi
Debitur dikecualikan untuk jenis Kredit Kepemilikan Rumah(KPR), Kredit
Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya diperuntukkan bagi usaha-usaha yang
produktif dengan sumber dana 100% yang berasal dari bank pelaksana.
Bank-bank pelaksana diantaranya yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank
Bukopin, Bank Syariah Mandiri,13 BPD (Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar
Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD
Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua).
2.3.1 Model Pelayanan Kredit bagi UMKM
Menurut Dierdja (2008), di Indonesia saat ini berkembang empat (4)
model pelayanan kredit bagi UMKM, atau umum dikenal dengan sebutan
keuangan mikro. Empat model tersebut yaitu:
1. Pelayanan keuangan yang bertumpu pada mobilisasi dan penggalian
sumber dana dari tabungan anggota kelompok atau koperasi sebagai
pijakan untuk mengembangkan jasa pelayanan keuangan mikro.
2. Keuangan mikro tumbuh berdasarkan keyakinan bahwa tujuan masyarakat
bergabung dengan suatu kelompok dimotivasi untuk memperoleh kredit.
3. Perbankan yang secara khusus didesain untuk menjalankan pelayanan
keuangan mikro, seperti BRI dan LKM lainnya, serta bank-bank umum
yang mengembangkan unit-unit layanan keuangan mikro.
4. Pelayanan keuangan yang memadukan pendekatan perbankan dan
kelompok swadaya masyarakat.
Lembaga keuangan mikro merupakan elemen yang penting dan efektif
bagi pengurangan kemiskinan. Akses yang telah diperbaiki dan provisi
tabungan, kredit, dan fasilitas asuransi yang efisien dapat membantu
membangun asetnya secara gradual dan membangun perusahaan dengan skala
ekonomis sehingga dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam meningkatkan
kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup. Tanpa akses ke lembaga
keuangan mikro, kebanyakan masyarakat miskin bergantung pada sumber
keuangan informal atau bahkan biaya sendiri, sehingga membatasi
kemampuannya untuk berperan aktif dan memperoleh manfaat dari lembaga
keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro dapat menyediakan cara yang
efektif untuk membantu dan memperdayakan wanita miskin, yang
mengakibatkan proporsi masyarakat miskin menjadi signifikan. Lembaga
keuangan mikro dapat berkontribusi terhadap perkembangan semua sistem
keuangan melalui intergrasi pasar keuangan.
2.4 Penelitian Sebelumnya
Silalahi dan Ramdhansyah (2013) melakukan penelitian tentang
Pengembangan Model Pendanaan UMKM berdasarkan Persepsi UMKM. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan UMKM menghadapi banyak masalah dalam
hal pendanaan bisnis mereka, terutama dari sektor perbankan. Peran Bank
sebagai sumber pendanaan masih relatif kecil. Sehingga sumber pembiayaan
yang digunakan untuk meningkatkan modal mereka didominasi oleh sektor
keuangan non formal. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Syarif dan Budhiningsih (2009). Mereka melakukan penelitian tentang
Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan dan Mendukung Permodalan
UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, masalah yang dihadapi oleh UMKM
adalah masalah permodalan. Program kredit yang diberikan oleh Pemerintah
perubahan orientasi kredit program yang semula untuk kepentingan
pembangunan sektoral diarahkan kepada pemberdayaan UMKM,
pengembangan kelembagaan dan kelompok.
Jurnal penelitian yang ditulis oleh Mohd Anwar (2014) dalam
penelitiannya yang berjudul “Impact of Credit Disbursement on Performance
of MSMEs in India: An Empirical Analysis”. Penelitian ini bertujuan Untuk
menguji pengaruh penyaluran kredit terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), ekspor dan output telah seharusnya sebagai indikator
terbaik dari kinerja UMKM dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya
mengungkapkan bahwa penyaluran kredit dan output dari UMKM memiliki
efek positif yang signifikan terhadap ekspor UMKM sedangkan, pekerja
memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekspor di semua negara.
Abhijeet Biswas (2014) dalam penelitiannya yang berjudul“Role of
Financing Policies and Financial Institutions for Micro, Small and Medium
Entrepreneurs”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada prospek yang luas
bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan peluang dengan
mengembangkan sektor UMKM yang bekerjasama dengan pemerintah
sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian.
2.5 Kerangka Konseptual
Saat ini, permasalahan terbesar yang dihadapi UMKM adalah dana yang
terbatas. Skim-skim pembiayaan pun menjadi sia-sia karena manajemen yang
kurang baik. Aspek permodalan merupakan kunci sukses dalam pembiayaan
UMKM. Tidak hanya permodalan, UMKM juga harus memiliki manajemen
mulai UMKM terkecil yaitu sektor industri rumah tangga harus mendapat
perhatian sebab pengembangan sektor UMKM ini sangat memberikan
kontribusi yang positif terhadap perekonomian nasional pada umumnya dan
kesejahteraan masyarakat pada khususnya.
Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan
pada gambar berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Modal
Aspek Manajerial Pola Pembiayaan
Asset
Omset
Sektor Industri Rumah Tangga
Pola Pemasaran