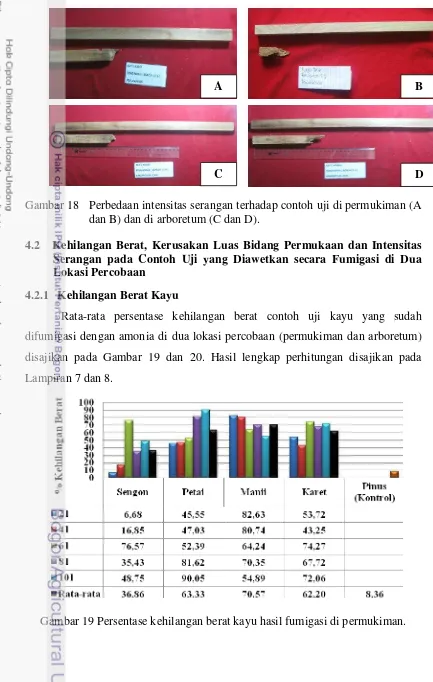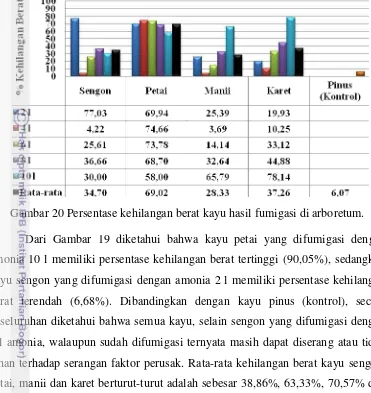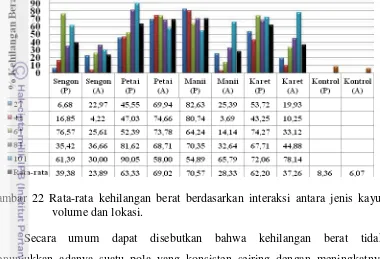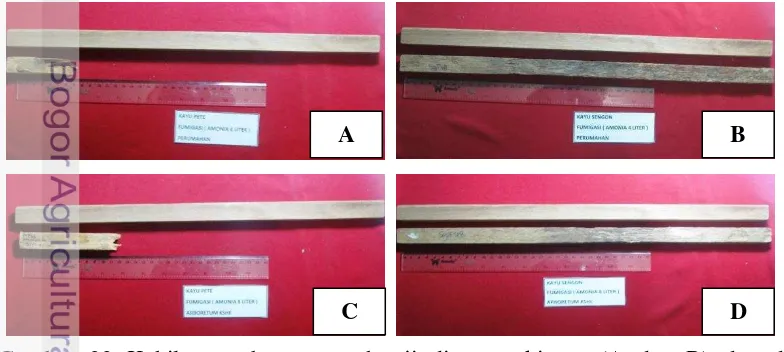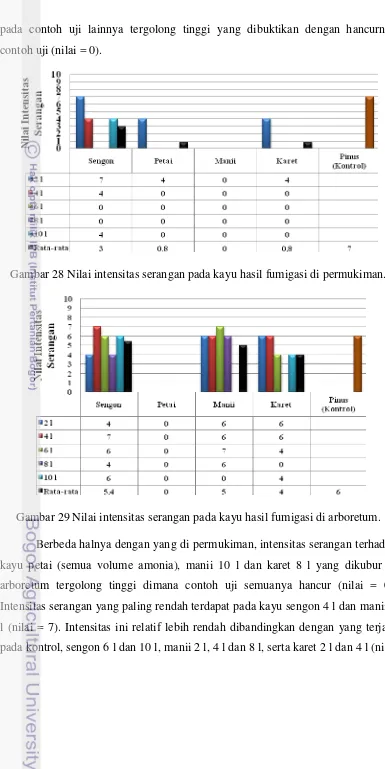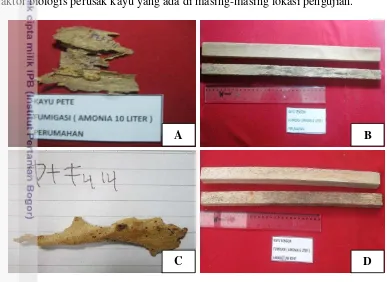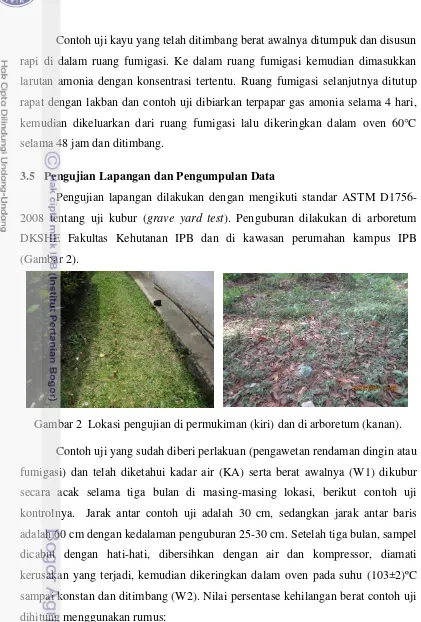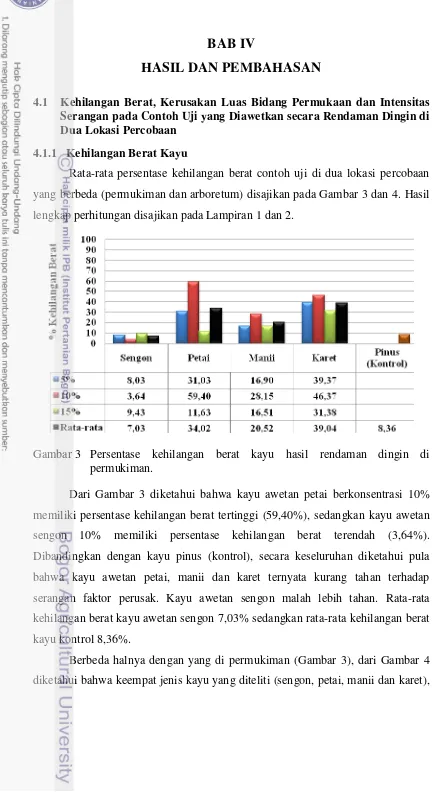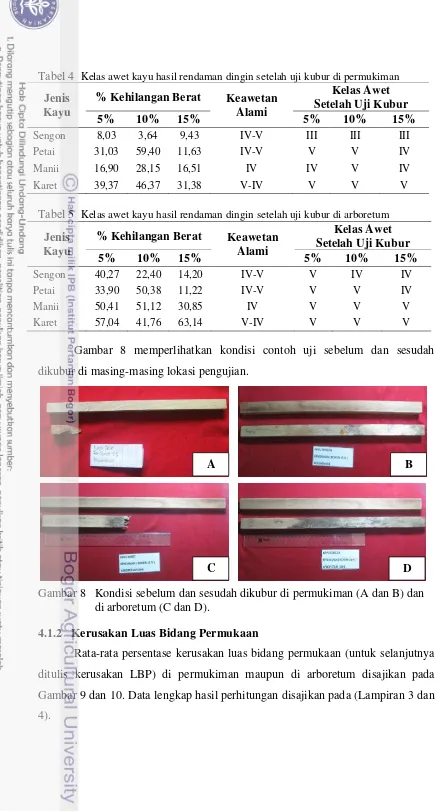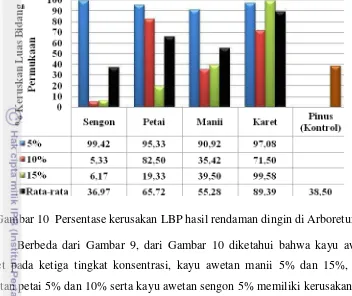COLD BATH AND FUMIGATION
EFFECTS ON THE ATTACK OF WOOD
BIOLOGICAL-DESTROYING FACTORS
AT TWO TESTING SITES
Singgih Mukti Wibowo, Imam Wahyudi and Istie Sekartining Rahayu
INTRODUCTION. The availability of timber from community forests tends to increase year by year. These timbers have important role for many wood industries in Indonesia. Compared to that of the natural forest, unfortunately, such kind of timber is commonly inferior especially in its strength and durability. Therefore, their quality have to be improved before being used, for an example is by wood preservation. Therefore, this research aims to study the influence of two treatments, namely the cold bath process of preservation using boron with several concentrations and the simple fumigation process using ammonia with several volumes, on the percentage of weight loss, the damage of wood surface and the attack intensity at the two testing sites.
MATERIALS AND METHOD. The main materials used were sengon (Paraserianthes falcataria), petai (Parkia speciosa)-, manii (Maesopsis eminii)-, karet (Hevea tree brasiliensis)- and pinus (Pinus merkusii) woods. Other materials consisted of boron solution with 3 concentrations (5-, 10-and 15%) 10-and ammonium hydroxide (technical) with 5 volumes (2-, 4-, 6-, 8- 10-and 10 litres). The cold bath method for 2 hours was applied for wood preservation, while the exposure of ammonia gasses for 4 days was applied for wood fumigation. All treated wood were then burried. Grave yard test for 3 months following the ASTM D 1756 2008 was carried out for these two purposes. Data was statistically analyzed using a factorial experimental design by 3 factors randomly ie. wood species, the concentration of boron or the volume of ammonia (depended on the treatment), as well as the testing sites (resettlement and experimental forest area), with three replications.
RESULT AND DISCUSSIONS.In case of boron treatment, it showed that the weight loss of karet treated-wood burried at the experimental forest area was the highest (53.98%), while in case of sengon treated-wood burried at the resettlement area was the lowest (7.03%). The damage of wood surface of karet treated-wood burried at the resettlement area was the highest (98.31%), while sengon treated-wood at the same site was the lowest (1.92%). Karet treated-wood burried at the resettlement area has the most severe damage (all wood samples destroyed; scoring = 0); while sengon treated-wood burried at the same site was not attack (wood sample relatively exsist; scoring = 9.33). In case of ammonia treatment, it was shown that the weight loss of manii treated-wood burried at the resettlement area was the highest (70.57%), while the same species burried at the experimental forest area was the lowest (28.33%). The damage of wood surface of petai treated-wood burried at the experimental forest area was the highest (98.15%), while sengon treated-wood at the same site was the lowest (47.10%). Manii treated-wood burried at the resettlement area as well as petai treated-wood at the experimental forest area have the most severe damage (all sample destroyed; scoring = 0), while sengon treated-wood burried at the experimental forest area was not attack (wood partly exsist; scoring = 5.4). Either of boron concentration effect or ammonia volume effect on the tree parameters studied was varied. Generally, boron-treated wood was not resistant to wood biological-destroying factors exsist in the experimental forest, but resistant enough to those of similar factors exsist in the resettlement. As the contrary, ammonia-treated wood was resistant enough to wood biological-destroying factors exsist in the experimental forest area, but was not resistant to those of similar factors exsist in the resettlement.
Key words: Wood preservation, cold bath, fumigation, Paraserianthes falcataria, Parkia speciosa,
Maesopsis eminii, Hevea brasiliensis, boron, amonia.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Hutan rakyat di Indonesia sampai dengan tahun 2003 tercatat ada sekitar 1.265.000 ha yang tersebar di 24 provinsi. Lima ratus ribu ha diantaranya terdapat di Pulau Jawa (Djajapertjunda (2003) dalam Mindawati et al. 2006). Potensi tegakan hutan rakyat tersebut diperkirakan mencapai 43 juta m3 per tahun dengan jenis-jenis kayu utama adalah sengon, akasia, jati, mahoni, sonokeling dan kayu-kayu penghasil buah lainnya.
Jumlah kayu rakyat cenderung terus meningkat. Dalam beberapa dekade
terakhir ini, produksi kayu rakyat mencapai 5 juta m3 per tahun atau lebih dari
setengah produksi hutan alam. Kayu rakyat bahkan sudah mampu berperan
sebagai bahan baku industri perkayuan di Indonesia terbukti dari banyaknya
industri perkayuan yang menggunakan kayu rakyat sebagai bahan baku meskipun
tidak semua jenis dapat menggantikan fungsi kayu konvensional yang selama ini
digunakan. Apabila dibandingkan dengan kayu hutan alam, kayu rakyat
cenderung kurang kuat dan kurang awet. Itulah sebabnya kayu-kayu tersebut perlu
ditingkatkan kualitasnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui
proses pengawetan kayu karena seberapapun kuatnya suatu jenis kayu,
pemanfaatannya menjadi kurang berarti apabila kayu tersebut kurang awet.
Pengawetan kayu adalah proses memasukan bahan pengawet beracun
terhadap organisme perusak agar kayu menjadi lebih tahan lama. Menurut
Nandika et al. (1996), melalui pengawetan maka nilai guna kayu-kayu yang
selama ini tidak dimanfaatkan karena kurang awet akan meningkat secara nyata,
biaya perbaikan dan penggantian kayu dalam suatu penggunaan akan berkurang,
serta dalam jangka panjang turut berkonstribusi pada kelestarian sumberdaya
hutan karena konsumsi kayu per satuan waktu menjadi lebih rendah. Hal ini sesuai
dengan tujuan utama dari proses pengawetan itu sendiri yaitu untuk
memperpanjang umur pakai kayu (Hunt & Garrat 1986).
Pengawetan kayu dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang
sederhana (biasanya tanpa tekanan) hingga metode yang menggunakan vakum
pada umumnya akibat adanya aliran (flow) bahan pengawet yang sudah dilarutkan dalam pelarut tertentu dengan konsentrasi tertentu, baik yang masih berupa cairan
maupun pasta. Dalam bentuk gas, kegiatan semacam itu tidak disebut sebagai
proses pengawetan, melainkan proses fumigasi.
Mengingat penelitian peningkatan kualitas kayu rakyat baik melalui
pengawetan maupun fumigasi masih terbatas, maka dilakukanlah penelitian ini.
Proses pengawetan yang dipilih adalah metode rendaman dingin karena sederhana
dan tidak membutuhkan peralatan khusus, menggunakan senyawa boron dengan
beberapa konsentrasi; sedangkan proses fumigasinya adalah fumigasi dalam ruang
sederhana dengan amonia sebagai fumigan pada beberapa volume. Kayu yang
sudah diawetkan dan sudah difumigasi selanjutnya dikubur untuk menilai
ketahanannya terhadap faktor-faktor perusak kayu.
1.2 Tujuan
Penelitian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kayu-kayu
rakyat sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif bagi industri
perkayuan melalui teknik pengawetan dan fumigasi ini bertujuan untuk:
1. Mempelajari pengaruh perbedaan jenis perlakuan antara pengawetan
rendaman dingin dalam larutan boron pada berbagai konsentrasi dan fumigasi
dalam amonia pada berbagai volume terhadap persentase kehilangan berat,
kerusakan luas bidang permukaan dan intensitas serangan faktor perusak
terhadap contoh uji.
2. Mengetahui pengaruh perbedaan lokasi pengujian terhadap daya tahan kayu
rakyat yang sudah diberi perlakuan.
1.3 Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kayu-kayu rakyat yang
memiliki tingkat keawetan yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hutan RakyatHutan rakyat adalah suatu lapangan yang berada di luar kawasan hutan
negara yang bertumbuhan pohon-pohonan sedemikian rupa sehingga secara
keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan yang
pemilikannya berada pada rakyat (Ditjen RRL Departemen Kehutanan 1996).
Menurut SK Menteri Kehutanan No.49/Kpts-II/1997, hutan rakyat adalah hutan
yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk
tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau tanaman
sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektar.
Hutan rakyat yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat telah
lama bekembang dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat
(Martin et al. 2003). Hutan rakyat dalam bentuk agroforestri tradisional sudah
memainkan peranan penting dalam perbaikan produktivitas dan keberlanjutan
sistem pertanian tradisional maupun yang semakin berorientasi pasar (Djogo
1993).
2.2 Pengawetan Kayu
Tidak semua jenis kayu mempunyai tingkat keawetan alami yang sama.
Tingkat keawetan kayu sangat beragam menurut jenis dan umurnya: semakin tua
umur kayu maka semakin awet juga kayunya. Dari 4000 jenis kayu yang ada di
Indonesia, hanya sebagian kecil (15-20%) yang memiliki keawetan tinggi
sedangkan sisanya termasuk jenis kayu yang kurang awet (Duljapar 2001).
Keawetan alami suatu jenis kayu bersifat relatif karena dipengaruhi oleh
beberapa faktor mulai dari zat ekstraktif, organisme perusak, suhu dan
kelembaban (Muslich & Sumarni 2007). Jenis kayu yang tahan terhadap suatu
organisme perusak belum tentu mempunyai ketahanan yang sama terhadap
organisme perusak lainnya. Keadaan iklim mempunyai efek yang nyata terhadap
umur pakai kayu yang tidak diawetkan, karena cuaca panas lembab lebih cocok
Keterawetan kayu adalah tingkat mudah-tidaknya kayu dimasuki oleh
bahan pengawet. Menurut Martawijaya dan Barly (2000), 4 faktor utama yang
mempengaruhi keterawetan kayu, adalah:
a. Jenis kayu, yang ditandai oleh sifat yang melekat pada kayu itu sendiri seperti
struktur anatomi (trakeida, pori/pembuluh, serabut, dan saluran damar),
permeabilitas, kerapatan dan sebagainya.
b. Keadaan kayu pada saat dilakukan pengawetan seperti kadar air, bentuk kayu,
gubal atau teras.
c. Metoda pengawetan yang digunakan.
d. Sifat bahan pengawet yang digunakan.
2.3 Pengawetan Kayu Secara Rendaman Dingin
Metode rendaman dingin merupakan salah satu proses sederhana dalam
metode pengawetan. Metode ini biasa dilakukan untuk mengawetkan kayu yang
akan digunakan pada tempat-tempat yang daya serang organisme perusaknya
tergolong sedang atau pada lokasi yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah
(Bowyer et al. 2003). Proses rendaman dingin dilakukan dengan cara kayu
direndam dalam bak yang berisi larutan bahan pengawet. Bak pengawetan dapat
dibuat dari besi, kayu atau beton bergantung pada keperluan. Lama waktu
perendaman bergantung pada jenis kayu dan ukuran tebal sortimen. Perendaman
dihentikan apabila berat contoh uji sebelum dan semudah diawetkan menunjukkan
nilai retensi yang dikehendaki. Cara tersebut sangat cocok untuk mengawetkan
kayu yang memiliki kelas keterawetan mudah atau sedikit sukar diawetkan.
2.4 Fumigasi
Fumigasi adalah perlakuan pengendalian hama (rayap, kutu buku, tikus,
kecoa, ngengat, kumbang dan lain-lain) dengan menggunakan gas beracun methyl
bromide (CH3Br). Teknik fumigasi memiliki tingkat penetrasi yang tinggi dan
mampu membunuh semua stadia kehidupan hama tanpa mengotori bahan yang
difumigasi (Hendrawan 2007). Giler (2006) menyatakan bahwa fumigan adalah
zat kimia atau campuran dari bahan kimia aktif dan tidak aktif (jika ada) yang
diramu untuk menghasilkan satu fumigan. Formulasi fumigan dapat berupa zat
1. Memiliki tingkat racun yang tinggi terhadap hama yang dijadikan target,
namun tidak berbahaya bagi manusia, tumbuhan, organisme lain yang bukan
menjadi sasaran, komoditas dan lingkungan.
2. Tersedia di pasaran dan hemat dalam penggunaan
3. Tidak terbakar, tidak merusak dan tidak meledak dalam keadaan penggunaan
normal.
4. Mudah menguap dengan penetrasi yang baik.
Amonia merupakan senyawa kimia dengan rumus NH3. Senyawa ini
merupakan senyawa yang berbahaya, bersifat kaustik, korosif dan dapat merusak
kesehatan. Amonia bahkan mampu menyebabkan terjadinya kematian apabila
terjadi kontak langsung dengan gas amonia yang berkonsentrasi tinggi.
Penampilan senyawa ini berupa gas yang tidak berwarna dengan bau tajam yang
khas bersifat iritan dan mudah larut dalam air (Moran et al. 2004).
Amonia memiliki titik didih pada suhu -33ºC dan titik lebur -77ºC, oleh
karena itu cairan amonia harus disimpan pada suhu yang sangat rendah atau
disimpan dalam tekanan yang sangat tinggi. Amonia memiliki berat molekul 17,
tekanan uap 400 mmHg (-45,4ºC), berat jenis uap 0,60 dan memiliki suhu kritis
133ºC (Moran et al. 2004).
2.5 Rayap
Rayap termasuk binatang purba karena sudah ada sejak 200 juta tahun
silam. Jenis serangga yang sangat kecil ini (panjang sekitar 3 mm) merupakan
faktor perusak (biologis) kayu yang paling dikenal. Menurut Lensufie (2008), ada
tiga jenis rayap, yaitu: rayap kayu kering, rayap pohon, dan rayap tanah. Makanan
utama rayap adalah kayu atau bahan yang mengandung selulosa sehingga hampir
semua kayu dapat terserang rayap. Pada beberapa kasus, lignin juga
didekomposisi. Hal tersebut tergantung dari jenis rayap (Lee & Wood 1971).
Namun ada jenis-jenis kayu tertentu yang tahan terhadap rayap, misalnya ulin,
merbau, dan sengon laut.
Rayap tergolong serangga sosial yang hidup dalam suatu komunitas yang
berada dalam koloninya (Nandika et al. 2003). Berdasarkan Tambunan dan
Nandika (1989), rayap mempunyai beberapa sifat penting yaitu:
1. Trophalaksis, yaitu sifat untuk berkumpul saling menjilat dan mengadakan
pertukaran bahan makanan.
2. Cryptobiotik, yaitu sifat untuk menjauhi cahaya. Sifat ini tidak berlaku pada
rayap yang bersayap (calon kasta produktif) dimana mereka selama periode
yang pendek di dalam hidupnya memerlukan cahaya.
3. Kanibalisme, yaitu sifat untuk memakan individu sejenis yang lemah atau
sakit. Sifat ini lebih menonjol bila rayap berada dalam keadaan kekurangan
makanan.
4. Necrophagy, yaitu sifat untuk memakan bangkai sesamanya.
Menurut Tarumingkeng (2000), terdapat beberapa kasta dalam koloni
rayap yang wujudnya berbeda, yaitu:
1. Kasta reproduktif
Terdiri dari individu-individu seksual yaitu betina (abdomennya
biasanya besar) yang tugasnya bertelur, dan jantan (raja) bertugas membuahi
betina. Raja tidak sepenting ratu karena setelah sekali kawin dia akan mati.
Sperma dapat disimpan oleh betina dalam kantong khusus, sehingga mungkin
sekali tidak diperlukan kopulasi berulang-ulang. Biasanya ratu dan raja adalah
individu pertama koloni, yaitu sepasang laron yang mulai menjalin kehidupan
bersama. Pasangan ini disebut reproduktif primer.
2. Kasta prajurit
Kasta ini ditandai dengan bentuk tubuh yang kekar karena penebalan
(sklerotisasi) kulitnya agar mampu melawan musuh dalam rangka
mempertahankan kelangsungan hidup koloninya. Mereka bergerak hilir mudik
diantara para pekerja yang sibuk mencari dan mengangkut makanan. Jika
terowongan kembara diganggu, tidak jarang kita saksikan pekerja-pekerja
diserang oleh semut, sedangkan para prajurit sibuk bertempur melawan
semut-semut. Pada umumnya prajurit tersebut kalah karena semut lebih lincah
bergerak dan menyerang. Prajurit biasanya dilengkapi dengan mandibel
(rahang) yang berbentuk gunting. Sekali mandibel menjepit musuhnya,
3. Kasta pekerja
Kasta ini membentuk sebagian koloni rayap. Tidak kurang dari 80%
populasi dalam koloni merupakan individu-individu pekerja. Tugasnya hanya
bekerja tanpa henti mencari makanan dan mengangkutnya ke sarang, membuat
terowongan-terowongan, menyuapi dan membersihkan rayap reproduktif,
prajurit maupun kasta pekerja sendiri. Rayap pekerja ini mandul, tanpa sayap,
dan buta warna. Warna rayap pekerja lebih muda dan ukurannya sedikit lebih
pendek. Meskipun dengan ciri-ciri rahang yang kurang nampak, tetapi rahang
bawah rayap pekerja ini telah disesuaikan secara khusus untuk menggigit
putus potongan-potongan kayu. Kasta inilah yang membuat segala macam
kerusakan pada kayu.
Menurut Tarumingkeng (2000), hingga saat ini telah tercatat kira-kira
2000 jenis rayap dan tersebar di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia telah
ditemukan lebih kurang 200 jenis rayap. Dari sekian banyak jenis rayap, diketahui
bahwa kerusakan kayu lebih banyak ditimbulkan oleh golongan rayap subteran
(rayap tanah).
Rayap subteran adalah golongan rayap yang bersarang di dalam tanah dan
membangun liang-liang kembara yang berfungsi untuk menghubungkan sarang
dengan benda yang diserang. Golongan rayap subteran selalu menghindari cahaya
dan membutuhkan kelembaban yang tinggi dalam kehidupannya. Karena sifatnya
yang cryptobiotic dan membutuhkan air untuk melembabkan kayu, liang kembara
biasanya tertutup dengan bahan-bahan tanah. Coptotermes curvignathus lebih
sering dikenal dengan sebutan rayap tanah, berukuran besar dan menyebabkan
serangan yang paling parah di Indonesia.
2.6 Jenis Kayu Hutan Rakyat 2.6.1 Kayu Karet
Tanaman karet (Hevea brasiliensis) termasuk salah satu anggota famili
Euphorbiaceae. Tanaman ini sering juga disebut hevea atau rubber-tree (Inggris);
rubberboom (Belanda); atau seringueria (Spanyol). Di Indonesia jenis ini banyak
ditanam di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan sebagai tanaman perkebunan
2006). Bila pohon telah mencapai umur 25-30 tahun, perlu segera diremajakan
karena tidak ekonomis lagi untuk disadap.
Kayu karet memiliki berat jenis (BJ) sekitar 0,61 (0,55-0,70), tergolong
kayu dengan kekerasan sedang dan Kelas Awet V (Mandang dan Pandit 1997).
Variasi BJ kayu disebabkan beberapa hal, antara lain perbedaan genetik, tempat
tumbuh, dan contoh yang dianalisis (Budiman 1987 dalam Boerhendy dan
Agustina 2006). Kayu karet mudah digergaji dengan hasil gergajian yang cukup
halus, serta mudah dibubut dengan permukaan yang rata dan halus. Selain itu,
kayu karet mempunyai sifat perekatan yang baik dengan semua jenis perekat
industri. Kayu karet umumnya digunakan sebagai bahan baku perabot rumah
tangga, panel dinding, bingkai gambar/lukisan, lantai parkit, peti kemas, finir,
kayu lamina, dan papan balok (Pandit dan Kurniawan 2008).
2.6.2 Kayu Manii
Manii dengan nama latin Maesopsis eminii Engl. termasuk ke dalam famili
Rhamnaceae. Tanaman ini banyak terdapat di daerah Jawa Barat. Bagian kayu
gubal berwarna putih, sedangkan bagian terasnya kuning gelap hingga coklat.
Teksturnya kasar dan berbau masam. Pada habitat alaminya, tanaman ini tumbuh
di dataran rendah sampai di ketinggian 1.800 mdpl. Kayu manii biasanya ditanam
di dataran rendah dan tumbuh baik pada ketinggian 600-900 m dpl dengan curah
hujan 1200-3600 mm per tahun dan musim kering sampai 4 bulan (Joker 2002).
Kayu yang ber-BJ 0,38-0,48 ini masuk ke dalam Kelas Kuat III dan Kelas Awet
III-IV sehingga banyak dimanfaatkan untuk konstruksi ringan-sedang di bawah
atap, peti kemas, box, dan kayulapis (Abdurachman dan Hadjib 2006). Menurut
Wahyudi et al. (2007), keterawetan kayu manii tergolong sedang. Manii
merupakan jenis pohon cepat tumbuh dan serbaguna serta banyak ditanam sebagai
sumber kayu bakar.
2.6.3 Kayu Sengon
Sengon atau Paraserianthes falcataria termasuk ke dalam famili
Mimosaceae. Penyebarannya ada di seluruh Jawa, Maluku, hingga Papua. Kayu
sengon memiliki ciri umum: teras berwarna hampir putih atau coklat muda pucat
(seperti daging) dengan bagian gubal yang tidak berbeda dengan kayu teras.
atau berpadu. Permukaan agak licin dan agak mengkilap. Kayu yang masih segar
berbau petai. Kayu ini termasuk Kelas Awet IV/V dan Kelas Kuat IV-V dengan
BJ sekitar 0,33 (0,24-0,49). Kayunya lunak dan mempunyai nilai penyusutan arah
radial dan tangensial dari kondisi basah sampai kering tanur berturut-turut adalah
2,5% dan 5,2%. Kayunya mudah digergaji tetapi tidak semudah kayu meranti
merah, dan dapat dikeringkan dengan cepat tanpa cacat yang berarti. Cacat
pengeringan yang lazim adalah melengkung atau memilin (Martawijaya &
Kartasujana 1997).
2.6.4 Kayu Petai
Petai (Parkia speciosa atau P. timoriana (DC) Merr.) adalah salah satu tanaman asli dari Malaysia, Brunei, Indonesia dan Semenanjung Thailand. Pohon
dapat mencapai tinggi 50 cm dengan permukaan kulit batang halus berwarna
coklat kemerahan. Daun majemuk menyirip ganda dua (bipinnate). Tanaman ini
sering ditanam mulai dari dataran rendah hingga ke ketinggian 1.500 m dpl,
namun tumbuh optimal pada ketinggian 500-1000 m dpl (Abdurrohim 2007).
Kayu teras putih kekuning-kuningan, sedangkan bagian kayu gubalnya
hampir putih sehingga sukar untuk dibedakan. Corak kayu polos, tekstur agak
kasar, arah serat agak berpadu, permukaan kayu mengkilap, dan memiliki tingkat
kekerasan yang lunak. Lingkar tumbuh kayu petai agak jelas, ditandai dengan
adanya lapisan-lapisan yang berbeda kepadatannya dan ketebalan dinding
seratnya.
Menurut Oey Djoen Seng (1990), kayu petai memiliki berat jenis
minimum 0,35 dan maksimum 0,53 dengan rata-rata 0,45 serta termasuk ke dalam
Kelas Awet V dan Kelas Kuat III-V. Dari kelas awet dan kelas kuatnya, maka
kayu petai tidak cocok untuk kayu konstruksi dengan pembebanan yang besar,
tetapi dapat digunakan untuk bangunan ringan sementara, kayu pertukangan,
meubel, kabinet, moulding, perlengkapan interior, pelapis, cetakan beton, peti krat, korek api, usungan, sumpit, pelampung jala, pulp dan kertas, serta kayu
2.6.5 Kayu Pinus
Pinus memiliki nama botani Pinus merkusii Jungh. Et de Vries. Nama
lainnya adalah merkusee pine (Amerika dan Inggris), merkustall (Swedia) atau
Sumatrakiefer (Jerman). Kayu pinus juga memiliki nama daerah damar batu,
damar bunga, huyam, uyam dan sala (Sumatera). Kayu ini memiliki tekstur yang
agak kasar dan serat lurus tapi tidak rata. Warna kayu terasnya sukar dibedakan
dari bagian gubal kecuali pada pohon berumur tua, dimana terasnya kuning
kemerahan sedangkan gubalnya putih krem. Kekerasan kayu pinus tergolong
sedang, sedangkan berat tergolong agak ringan sampai agak berat. Dengan berat
jenis rata-rata sebesar 0,55, kayu pinus termasuk kelas kuat III. Kayu pinus
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Sifat Dasar, Bagian Teknologi
Peningkatan Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut
Pertanian Bogor dan di Laboratorium Biologi Hasil Hutan, Pusat Penelitian
Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB dari bulan Juni sampai Desember 2011.
Lokasi pengujian ketahanan kayu yang sudah diberi perlakuan dibedakan
menurut intensitas serangan dan jenis faktor biologis perusak kayu yang ada,
yaitu: a) Arboretum Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata-Fakultas
Kehutanan Institut Pertanian Bogor mewakili daerah dengan jenis perusak
biologis yang beragam dan diperkirakan memiliki intensitas serangan yang tinggi,
dan b) Perumahan di lingkup Kampus IPB Darmaga yang mewakili daerah bekas
kebun karet dengan jenis perusak biologis yang hidupnya dekat dengan
permukiman dan diperkirakan masih memiliki intensitas serangan yang cukup
tinggi.
3.2 Alat dan Bahan 3.2.1. Rendaman Dingin
Bahan dan alat yang digunakan adalah boraks (Na2B407.10H20) dengan
konsentrasi 5%, 10% dan 15% (b/v), lima jenis kayu yaitu karet (Hevea
brasiliensis), manii (Maesopsis eminii), sengon (Paraserianthes falcataria), petai
(Parkia speciosa) dan pinus (Pinus merkusii), bak rendaman, kompor gas, panci, timbangan elektrik, alat tulis, linggis, tali rafia, plastik, karung, trash bag, sikat, kompressor, dan kamera digital.
3.2.2. Fumigasi
Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari larutan amonia 2, 4, 6, 8, dan
10 liter, 4 jenis kayu yaitu karet, manii, sengon, petai dan pinus, alat tulis, terpal
plastik, lakban, selang, karung, kipas angin, linggis, tali rafia, plastik, karung,
3.3 Pengawetan secara Rendaman Dingin
Ukuran contoh uji yang digunakan adalah (2 x 2 x 45) cm3 dalam kondisi
kering udara (kadar air <18%). Total contoh uji yang dibuat 78 buah dengan
perincian: 4 jenis kayu (karet, manii, sengon dan petai) x 3 konsentrasi larutan
bahan pengawet (5%, 10% dan 15%) x 2 lokasi x 3 ulangan, ditambah 6 buah
kontrol yaitu kayu pinus (masing-masing 3 buah per lokasi pengujian).
Contoh uji yang sudah ditimbang dan diukur kadar airnya disusun rapi
menggunakan ganjal di dalam bak rendaman dan diberi pemberat, lalu ke dalam
masing-masing bak rendaman dimasukkan larutan bahan pengawet sesuai dengan
konsentrasi yang telah disiapkan hingga contoh uji terendam sempurna.
Perendaman dilakukan selama 2 jam dalam suhu kamar. Setelah 2 jam, contoh uji
ditiris kemudian ditimbang, lalu dikering udarakan selama 2 minggu. Dalam
penelitian ini, data retensi dan penetrasi pada masing-masing kayu yang diteliti
mengacu pada hasil penelitian Djauhari (2012).
3.4 Proses Fumigasi Amonia
Contoh uji yang digunakan berukuran (2 x 2 x 45) cm3 dalam kondisi
kering udara (kadar air <18%). Total contoh uji yang digunakan 120 buah dengan
perincian: 4 jenis kayu (karet, manii, sengon dan petai) x 5 volume larutan
amonia (2, 4, 6, 8, dan 10 liter) x 2 lokasi x 3 ulangan. Amonia yang digunakan
adalah amonia cair teknis (ammonium hidroksida 100%) yang tersedia di pasar.
Proses fumigasi dilakukan di dalam ruang fumigasi yang berbentuk kotak
bujur sangkar berukuran 2 m x 1 m x 1 m dan terbuat dari rangka kayu dengan
plastik transparan sebagai penutup (Gambar 1).
Contoh uji kayu yang telah ditimbang berat awalnya ditumpuk dan disusun
rapi di dalam ruang fumigasi. Ke dalam ruang fumigasi kemudian dimasukkan
larutan amonia dengan konsentrasi tertentu. Ruang fumigasi selanjutnya ditutup
rapat dengan lakban dan contoh uji dibiarkan terpapar gas amonia selama 4 hari,
kemudian dikeluarkan dari ruang fumigasi lalu dikeringkan dalam oven 60°C
selama 48 jam dan ditimbang.
3.5 Pengujian Lapangan dan Pengumpulan Data
Pengujian lapangan dilakukan dengan mengikuti standar ASTM
D1756-2008 tentang uji kubur (grave yard test). Penguburan dilakukan di arboretum DKSHE Fakultas Kehutanan IPB dan di kawasan perumahan kampus IPB
(Gambar 2).
Gambar 2 Lokasi pengujian di permukiman (kiri) dan di arboretum (kanan).
Contoh uji yang sudah diberi perlakuan (pengawetan rendaman dingin atau
fumigasi) dan telah diketahui kadar air (KA) serta berat awalnya (W1) dikubur
secara acak selama tiga bulan di masing-masing lokasi, berikut contoh uji
kontrolnya. Jarak antar contoh uji adalah 30 cm, sedangkan jarak antar baris
adalah 60 cm dengan kedalaman penguburan 25-30 cm. Setelah tiga bulan, sampel
dicabut dengan hati-hati, dibersihkan dengan air dan kompressor, diamati
kerusakan yang terjadi, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu (103±2)ºC
sampai konstan dan ditimbang (W2). Nilai persentase kehilangan berat contoh uji
dihitung menggunakan rumus:
P = [(W1* - W2) / W1*] x 100%
Dimana:
P = Penurunan berat (%)
= W1 / [1 + (KA/100)]
W2 = Berat contoh uji kering tanur setelah dikubur (gram)
Ketahanan kayu hasil perlakuan dinilai berdasarkan standar ASTM 2008
dan SNI 2006. Menurut ASTM 2008, ketahanan kayu dinilai berdasarkan derajat
atau intensitas kerusakan secara keseluruhan pada contoh uji (Tabel 1) dan pada
cross section contoh uji (Tabel 2), sedangkan menurut SNI 2006 berdasarkan nilai rata-rata persentase penurunan berat kayu (Tabel 3). Kerusakan atau kehilangan
pada cross section dihitung menggunakan rumus:
Kerusakan = (A1
–
A2) / A1 x 100%
Dimana:
A1 = Luas permukaan contoh uji sebelum dikubur (cm2)
A2 = Luas permukaan contoh uji setelah dikubur (cm2)
Tabel 1 Penilaian tingkat kerusakan contoh uji
Nilai Kondisi Serangan
10 Utuh, lubang gerek di permukaan 9 Serangan ringan
7 Serangan sedang, terjadi penetrasi 4 Serangan berat
0 Hancur
Sumber: ASTM 2008
Tabel 2 Penilaian hasil pengujian lapangan
Nilai Kerusakan oleh Rayap
10 Tidak ada serangan : 1 - 2 lubang gerek kecil 9 Lubang gerek mencapai 3% dari cross section 8 Penetrasi mencapai 3 - 10% dari cross section 7 Penetrasi mencapai 10 - 30% dari cross section 6 Penetrasi mencapai 30 - 50% dari cross section 4 Penetrasi mencapai 50 - 75% dari cross section Sumber: ASTM 2008
Tabel 3 Klasifikasi ketahanan kayu terhadap serangan rayap tanah
Kelas Ketahanan Penurunan Berat (%)
I Sangat tahan < 3,52
II Tahan 3,52 - 7,50
III Sedang 7,50 - 10,96
IV Buruk 10,96 - 18,94
V Sangat buruk 18,94 - 31,89
Sumber: SNI 2006
3.6 Pengolahan Data
Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2007 dan
(Rancangan Acak Lengkap) faktorial dengan 3 faktor, yaitu: faktor A (jenis kayu
yaitu sengon, petai, manii dan karet), faktor B (konsentrasi larutan bahan
pengawet atau volume amonia (tergantung perlakuan), yaitu 5%, 10% dan 15%
(konsentrasi larutan) atau 2 liter, 4 liter, 6 liter, 8 liter dan 10 liter (volume
amonia), serta faktor C (lokasi uji kubur yaitu permukian dan arboretum), dengan
masing-masing 3 kali ulangan (Mattjik dan Sumertajaya 2002).
Model rancangan percobaan statistik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
Yijkl= μ+ αi+ j + k+ (α )ij+ (α )ik+ ( )jk+ (α )ijk+ εijkl
Dimana:
Yijkl = Nilai pengamatan pada masing-masing jenis kayu ke-i, konsentrasi atau
volume larutan ke-j, lokasi pengujian ke-k dan ulangan ke-l
μ = Rataan umum
αi = Pengaruh jenis kayu ke-i
j = Pengaruh konsentrasi atau volume ke-j (tergantung perlakuan)
k = Pengaruh lokasi pengujian ke-k
(α )ij = interaksi pengaruh jenis kayu ke-i dengan konsentrasi/volume ke-j
(α )ik = interaksi pengaruh jenis kayu ke-i dengan lokasi ke-k
( )jk = interaksi pengaruh konsentrasi/volume ke-j dengan lokasi ke-k
(α )ijk = interaksi pengaruh jenis kayu ke-i, konsentrasi/volume ke-j dan lokasi ke-j
εijkl = Kesalahan percobaan
Perlakuan yang berpengaruh terhadap respon dalam analisis sidik ragam,
kemudian diuji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range Test
(DMRT). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kehilangan Berat, Kerusakan Luas Bidang Permukaan dan Intensitas Serangan pada Contoh Uji yang Diawetkan secara Rendaman Dingin di Dua Lokasi Percobaan
4.1.1 Kehilangan Berat Kayu
Rata-rata persentase kehilangan berat contoh uji di dua lokasi percobaan
yang berbeda (permukiman dan arboretum) disajikan pada Gambar 3 dan 4. Hasil
lengkap perhitungan disajikan pada Lampiran 1 dan 2.
Gambar 3 Persentase kehilangan berat kayu hasil rendaman dingin di permukiman.
Dari Gambar 3 diketahui bahwa kayu awetan petai berkonsentrasi 10%
memiliki persentase kehilangan berat tertinggi (59,40%), sedangkan kayu awetan
sengon 10% memiliki persentase kehilangan berat terendah (3,64%).
Dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol), secara keseluruhan diketahui pula
bahwa kayu awetan petai, manii dan karet ternyata kurang tahan terhadap
serangan faktor perusak. Kayu awetan sengon malah lebih tahan. Rata-rata
kehilangan berat kayu awetan sengon 7,03% sedangkan rata-rata kehilangan berat
kayu kontrol 8,36%.
Berbeda halnya dengan yang di permukiman (Gambar 3), dari Gambar 4
meskipun sudah diawetkan ternyata semuanya tidak tahan terhadap serangan
faktor perusak dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol). Rata-rata kehilangan
berat masing-masing jenis kayu yang diteliti pada semua tingkat konsentrasi
bahan pengawet lebih tinggi dibandingkan dengan kontrolnya. Rata-rata
kehilangan berat kayu kontrol sebesar 6,07%, sedangkan rata-rata kehilangan
berat kayu awetan sengon, petai, manii dan karet berturut-turut adalah 25,62%,
31,83%, 44,13% dan 53,98%. Selanjutnya diketahui pula bahwa kayu awetan
yang dikubur di arboretum mengalami rata-rata kehilangan berat yang lebih tinggi
untuk jenis yang sama, kecuali pada kayu awetan petai. Kehilangan berat kayu
awetan sengon, manii dan karet di permukiman berturut-turut hanya 7,03%,
20,52% dan 39,04%. Kehilangan berat kayu awetan petai relatif sama antara yang
di permukiman dengan yang di arboretum (34,02% berbanding 31,83%).
Gambar 4 Persentase kehilangan berat kayu hasil rendaman dingin di arboretum.
Dari Gambar 3 dan 4 juga dapat diketahui bahwa kehilangan berat pada
masing-masing jenis kayu awetan di dua lokasi penelitian tidak memperlihatkan
adanya suatu pola yang konsisten terkait dengan meningkatnya konsentrasi larutan
bahan pengawet, kecuali pada kayu awetan petai. Pola kehilangan berat pada kayu
yang sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi konsentrasi bahan pengawet akan
semakin rendah kehilangan beratnya, hanya terdapat pada kayu awetan sengon di
Hasil analisis sidik ragam atau ANOVAnya (Lampiran 13) menunjukkan
bahwa kehilangan berat contoh uji hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal yaitu
jenis kayu, konsentrasi larutan bahan pengawet dan lokasi pengujian, sedangkan
interaksinya tidak berpengaruh nyata. Hasil uji lanjut Duncan (Lampiran 14)
menunjukkan bahwa kehilangan berat kayu awetan karet sebanding dengan yang
terjadi pada kayu awetan petai dan manii. Ketiganya berbeda dibandingkan
dengan kehilangan berat kayu awetan sengon. Rata-rata kehilangan berat pada
kayu awetan petai, manii dan karet berturut-turut adalah 32,93%, 32,32% dan
46,51%, sedangkan pada kayu awetan sengon hanya 16,33% (Gambar 5).
Gambar 5 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan jenis kayu.
Pengaruh jenis kayu terhadap persentase kehilangan berat dapat
dimaklumi karena masing-masing jenis kayu memiliki karakteristik yang berbeda.
Dalam penelitian ini, perbedaan nilai kehilangan berat antar jenis kayu lebih
disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat keterawetan kayu karena keempat jenis
kayu yang diteliti memiliki kelas awet yang relatif sama, yaitu Kelas Awet IV
(manii), IV-V (sengon dan petai), serta V-IV (karet). Meskipun kelas awetnya
sama, ketahanan kayu terhadap serangan faktor perusak akan berbeda apabila
tingkat keterawetannya berbeda. Inilah sebabnya mengapa kehilangan berat pada
kayu awetan sengon paling rendah dibandingkan dengan ketiga jenis kayu
lainnya. Kayu sengon tergolong kayu yang mudah diawetkan (tingkat
keterawetannya sedang), sedangkan petai, manii dan karet tergolong sulit hingga
Gambar 6 memperlihatkan pengaruh konsentrasi larutan bahan pengawet
terhadap persentase kehilangan berat contoh uji. Konsentrasi 10% menghasilkan
kehilangan berat tertinggi (37,90%), kemudian diikuti oleh konsentrasi 5%
(34,62%), dan yang paling rendah adalah konsentrasi 15% (23,55%). Berdasarkan
uji Duncan (Lampiran 14), pengaruh konsentrasi 10% relatif sama dengan
pengaruh konsentrasi 5% dan pengaruh konsentrasi 5% relatif sama dengan
pengaruh konsentrasi 15%, tetapi pengaruh konsentrasi 10% berbeda nyata
dibandingkan dengan pengaruh konsentrasi 15%. Dengan kata lain, konsentrasi
larutan bahan pengawet 5% sama pengaruhnya dengan konsentrasi 10% maupun
15% terhadap persentase kehilangan berat contoh uji.
Gambar 6 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan konsentrasi.
Pengaruh konsentrasi larutan bahan pengawet terhadap persentase
kehilangan berat hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang berlaku dimana
semakin tinggi konsentrasi akan semakin rendah pula persentase kehilangan berat.
Semakin tinggi konsentrasi larutan bahan pengawet, peluang terjadinya penetrasi
yang dalam dan retensi yang lebih banyak akan semakin besar sehingga kayu
menjadi lebih tahan terhadap serangan faktor perusak. Menurut Hunt dan Garrat
(1986), meski penetrasi tidak selalu berkolerasi dengan retensi, penetrasi yang
dalam cenderung meningkatkan nilai retensi sehingga kayu menjadi lebih awet.
Namun demikian, mengingat harga bahan pengawet yang relatif mahal, maka
penggunaan larutan bahan pengawet dengan konsentrasi 5% sangat disarankan.
Gambar 7 memperlihatkan pengaruh perbedaan lokasi pengujian terhadap
dikubur di arboretum lebih tinggi (38,89%) dibandingkan dengan yang dikubur di
permukiman (25,15%). Perbedaan ini diduga terkait dengan perbedaan intensitas
serangan dan atau perbedaan jenis serta jumlah faktor perusak yang ada di
masing-masing lokasi akibat kondisi lingkungan yang berbeda. Menurut
Tarumingkeng (1993); Nandika et al. (2003), aktifitas manusia dapat
menyebabkan terganggunya ketenteraman dan kenyamanan hidup rayap serta
perusak biologis kayu lainnya. Lebih beragamnya jenis dan jumlah faktor perusak
yang ada di arboretum dibandingkan dengan yang ada di permukiman serta
tingginya intensitas serangan faktor perusak tersebut diduga merupakan faktor
penyebab.
Gambar 7 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan lokasi pengujian.
Tabel 4 dan 5 memuat perbandingan kelas awet kayu sebelum dikubur
(keawetan alami) dan setelah dikubur berdasarkan rata-rata persentase kehilangan
berat contoh uji di dua lokasi. Data yang tersaji membuktikan bahwa persentase
kehilangan berat contoh uji yang dikubur di arboretum secara umum lebih tinggi
dibandingkan dengan yang dikubur di permukiman kecuali kayu sengon. Kondisi
arboretum yang lebih tenang karena tidak banyak gangguan manusia merupakan
A
Tabel 4 Kelas awet kayu hasil rendaman dingin setelah uji kubur di permukiman
Jenis Kayu
% Kehilangan Berat Keawetan
Alami
Kelas Awet Setelah Uji Kubur
5% 10% 15% 5% 10% 15%
Sengon 8,03 3,64 9,43 IV-V III III III
Petai 31,03 59,40 11,63 IV-V V V IV
Manii 16,90 28,15 16,51 IV IV V IV
Karet 39,37 46,37 31,38 V-IV V V V
Tabel 5 Kelas awet kayu hasil rendaman dingin setelah uji kubur di arboretum
Jenis Kayu
% Kehilangan Berat Keawetan
Alami
Kelas Awet Setelah Uji Kubur
5% 10% 15% 5% 10% 15%
Sengon 40,27 22,40 14,20 IV-V V IV IV
Petai 33,90 50,38 11,22 IV-V V V IV
Manii 50,41 51,12 30,85 IV V V V
Karet 57,04 41,76 63,14 V-IV V V V
Gambar 8 memperlihatkan kondisi contoh uji sebelum dan sesudah
dikubur di masing-masing lokasi pengujian.
Gambar 8 Kondisi sebelum dan sesudah dikubur di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).
4.1.2 Kerusakan Luas Bidang Permukaan
Rata-rata persentase kerusakan luas bidang permukaan (untuk selanjutnya
ditulis kerusakan LBP) di permukiman maupun di arboretum disajikan pada
Gambar 9 dan 10. Data lengkap hasil perhitungan disajikan pada (Lampiran 3 dan
4).
A B
Gambar 9 Persentase kerusakan LBP hasil rendaman dingin di permukiman.
Gambar 9 diketahui bahwa kayu awetan karet berkonsentrasi 10%
mengalami kerusakan LBP yang tertinggi (98,42%), sedangkan kayu awetan
sengon 15% memiliki kerusakan LBP terendah (0,83%). Dibandingkan dengan
kayu pinus (kontrol), secara keseluruhan diketahui pula bahwa kayu awetan petai,
manii dan karet meskipun telah diawetkan ternyata masih kurang tahan terhadap
serangan faktor perusak. Kayu awetan sengon (pada semua tingkat konsentrasi)
dan kayu awetan manii berkonsentrasi 15% malah lebih tahan. Rata-rata
kerusakan LBP kayu awetan sengon 1,92%, sedangkan pada kayu awetan manii
15% adalah 1,08%. Rata-rata kerusakan LBP pada kayu kontrol 10,50%.
Gambar 9 juga memperlihatkan bahwa kayu awetan karet dengan
konsentrasi larutan bahan pengawet yang berbeda memiliki nilai kerusakan LBP
yang hampir sama, berturut-turut sebesar 98,33% (konsentrasi 5%), 98,42%
(konsentrasi 10%) dan 98,17% (konsentrasi 15%). Keadaan ini terkait dengan
kelas awet dan keterawetan kayu karet. Dengan Kelas Awet V-IV dan
keterawetan yang tergolong sulit (Wahyudi et al. 2007), maka kayu awetan karet
Gambar 10 Persentase kerusakan LBP hasil rendaman dingin di Arboretum.
Berbeda dari Gambar 9, dari Gambar 10 diketahui bahwa kayu awetan
karet pada ketiga tingkat konsentrasi, kayu awetan manii 5% dan 15%, kayu
awetan petai 5% dan 10% serta kayu awetan sengon 5% memiliki kerusakan LBP
yang lebih tinggi dibandingkan kontrolnya. Kerusakan LBP kayu awetan petai
15% serta kayu awetan sengon dengan 10% dan 15% berturut-turut sebesar
19,33%, 5,33% dan 6,17%. Kerusakan LBP kayu awetan manii 10% tidak jauh
berbeda dibandingkan dengan kerusakan LBP kayu pinus (kontrol), yaitu 35,42%
berbanding 38,50%.
Hasil analisis sidik ragam atau ANOVA pada (Lampiran 15) menunjukkan
bahwa persentase kerusakan LBP dipengaruhi oleh jenis kayu, konsentrasi larutan
bahan pengawet, lokasi pengujian, interaksi antara kayu dan konsentrasi serta
interaksi antara konsentrasi dan lokasi. Hasil uji lanjut Duncannya (Lampiran 16)
dan Gambar 11 menunjukkan bahwa kerusakan LBP kayu awetan petai 10%
setara dengan kerusakan LBP pada semua tingkat interaksi antara jenis kayu dan
konsentrasi bahan pengawet, kecuali pada kayu awetan manii 10% dan sengon
pada seluruh tingkat konsentrasi. Kerusakan LBP kayu awetan karet 10% dan
15% berbeda nyata dengan kerusakan LBP kayu awetan manii 5% dan 10% serta
sengon pada seluruh tingkat konsentrasi. Kerusakan LBP tertinggi (98,88%)
terdapat pada kayu awetan karet 15%, sedangkan yang terendah pada kayu awetan
Gambar 11 Rata-rata kerusakan LBP berdasarkan interaksi antara jenis kayu dan konsentrasi larutan bahan pengawet.
Perbedaan kerusakan LBP sebagaimana di atas dipastikan ada
hubungannya dengan perbedaan struktur anatomi penyusun masing-masing jenis
kayu karena langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keterawetan
kayu. Disini kerapatan kayu relatif tidak ada pengaruhnya karena kayu dengan
kerapatan yang sama menghasilkan persentase kerusakan LBP yang berbeda.
Rata-rata kerapatan kayu sengon, petai, manii dan karet yang diteliti berturut-turut
adalah 0,33 g/cm3, 0,59 g/cm3, 0,35 g/cm3 dan 0,58 g/cm3 (Rahayu et al. 2009). Gambar 12 menunjukkan pengaruh perbedaan lokasi pengujian pada
masing-masing tingkat konsentrasi larutan bahan pengawet terhadap kerusakan
LBP. Hasil uji lanjut Duncannya menunjukkan bahwa konsentrasi 5% di
arboretum berbeda nyata dengan konsentrasi 10% dan 15% di arboretum serta
konsentrasi 5% dan 15% di permukiman. Konsentrasi 10% di permukiman
sebanding dengan konsentrasi 10% dan 15% di arboretum serta konsentrasi 5%
dan 15% di permukiman.
Dari Gambar 12 diketahui bahwa interaksi antara konsentrasi larutan
bahan pengawet dan lokasi memberikan hasil yang berbeda. Pada konsentrasi 5%,
kerusakan LBP contoh uji yang dikubur di arboretum dua kali lebih besar
dibandingkan dengan yang dikubur di permukiman (95,69% berbanding 41,13%).
Pada konsentrasi 10% dan 15%, perbedaan itu tidak begitu besar, dan
LBP contoh uji yang dikubur di permukiman lebih banyak, sedangkan untuk
konsentrasi 15%, kerusakan LBP contoh uji yang dikubur di permukiman lebih
sedikit dibandingkan dengan yang dikubur di arboretum.
Gambar 12 Rata-rata kerusakan LBP kayu berdasarkan interaksi antara konsentrasi larutan bahan pengawet dan lokasi pengujian.
Rata-rata kerusakan LBP tertinggi berdasarkan interaksi antara konsentrasi
larutan bahan pengawet dan lokasi adalah 95,69% (konsentrasi 5% di arboretum),
sedangkan yang terendah adalah 32,60% (konsentrasi 15% di permukiman).
Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kerusakan LBP pada contoh uji
yang dikubur di arboretum cenderung berkurang dengan meningkatnya
konsentrasi larutan bahan pengawet, sedangkan di lokasi permukiman
berfluktuasi. Kerusakan LBP yang dikubur di permukiman meningkat dengan
meningkatnya konsentrasi larutan bahan pengawet (5% ke 10%), namun
kemudian cenderung berkurang dengan meningkatnya konsentrasi larutan bahan
pengawet (10% ke 15%).
Gambar 13 memperlihatkan kerusakan LBP contoh uji di masing-masing
lokasi pengujian.
Gambar 13 Kerusakan LBP contoh uji di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).
4.1.3 Intensitas Serangan
Rata-rata nilai intensitas serangan di dua lokasi percobaan yang berbeda
(permukiman dan arboretum) disajikan pada Gambar 14 dan 15. Data lengkap
hasil perhitungan disajikan pada (Lampiran 5 dan 6).
Gambar 14 Nilai intensitas serangan kayu hasil rendaman dingin di permukiman.
Dari Gambar 14 diketahui bahwa intensitas serangan faktor biologis
perusak kayu terhadap kayu karet pada semua tingkat konsentrasi larutan bahan
pengawet boron, maupun pada kayu awetan petai dan manii pada konsentrasi 10%
tergolong tinggi, yang dibuktikan dengan hancurnya contoh uji (nilai = 0). Contoh
uji lainnya termasuk kontrol relatif utuh (nilai = 6-10), yang menandakan bahwa
intensitas serangan terhadap kayu kontrol tergolong rendah: tidak ada serangan
kecuali 1-2 buah lubang gerek kecil dan penetrasi faktor perusak hanya 30-50%
dari luas penampang permukaan contoh uji.
Sama halnya dengan yang di permukiman, intensitas serangan terhadap
kayu awetan karet pada konsentrasi 5% dan 15%, kayu sengon dan manii 5% serta
kayu awetan petai 5% dan 10%, tergolong tinggi dimana contoh ujinya hancur
(Gambar 15). Contoh uji lainnya termasuk kontrol relatif utuh, yang menandakan
bahwa intensitas serangan tergolong sedang hingga rendah (nilai = 4-8). Secara
keseluruhan intensitas serangan tertingi lebih banyak terjadi pada contoh uji yang
dikubur di permukiman daripada di arboretum. Hal ini merupakan petunjuk bahwa
Gambar 15 Intensitas serangan kayu hasil rendaman dingin di arboretum.
Hasil analisis sidik ragamnya (Lampiran 17) menunjukkan bahwa jenis
kayu, konsentrasi larutan bahan pengawet, lokasi pengujian, serta interaksi antara
kayu dan konsentrasi, maupun interaksi antara konsentrasi dan lokasi pengujian
mempengaruhi intensitas serangan. Hasil lanjut Duncan (Lampiran 18) dan
Gambar 16 menunjukkan bahwa intensitas serangan pada kayu awetan sengon
dengan konsentrasi 10% dan 15% berbeda nyata dibandingkan dengan intensitas
serangan terhadap kayu awetan sengon 5%, maupun terhadap kayu awetan manii
(5% dan 10%), kayu awetan petai (5% dan 10%), dan kayu awetan karet (semua
tingkat konsentrasi). Intensitas serangan pada kayu manii dan petai (konsentrasi
15%) berbeda nyata dengan intensitas serangan pada kayu awetan manii dan petai
(5% dan 10%), serta kayu awetan karet (semua tingkat konsentrasi). Intensitas
serangan tertinggi terdapat pada kayu awetan karet 5% dan 15%, sedangkan
intensitas serangan terendah pada kayu awetan sengon yang diawetkan dengan
Gambar 16 Rata-rata nilai intensitas serangan berdasarkan interaksi antara jenis kayu dan konsentrasi larutan bahan pengawet.
Perbedaan nilai intensitas serangan berhubungan dengan perbedaan kelas
awet kayu setelah diawetkan dimana kelas awet tersebut dipengaruhi oleh struktur
anatomi penyusun kayu khususnya tingkat keterawetan kayu. Itulah sebabnya
kayu karet meskipun sudah diawetkan masih disukai oleh faktor biologis perusak
kayu karena sulit diawetkan. Menurut Martawijaya dan Barly (1982), selain
ditentukan oleh teknik pengawetan dan bahan pengawet yang digunakan,
keberhasilan suatu proses pengawetan juga ditentukan oleh jenis dan kondisi
kayu.
Intensitas serangan juga terkait dengan nilai kerusakan LBP contoh uji.
Semakin tinggi persentase kerusakan LBP, akan semakin tinggi pula intensitas
serangan. Tingginya intensitas serangan akan menghasilkan nilai (scoring) yang semakin rendah.
Hasil lanjut Duncan juga menunjukkan bahwa konsentrasi 15% di
permukiman berbeda nyata dengan konsentrasi 10% di permukiman dan 5% di
arboretum. Konsentrasi 10% dan 15% di arboretum berbeda nyata dengan
konsentrasi 5% di arboretum. Gambar 17 menunjukkan pengaruh perbedaan
lokasi pengujian pada masing-masing tingkat konsentrasi larutan bahan pengawet
terhadap intensitas serangan. Secara keseluruhan, derajat intensitas serangan
tertinggi terjadi di arboretum pada konsentrasi 5% (nilai = 0), sedangkan yang
terendah di permukiman pada konsentrasi 15% (nilai = 6,75). Dengan demikian
maka konsentrasi larutan sebesar 15% merupakan konsentrasi yang paling efektif
mencegah serangan faktor biologis perusak kayu yang ada di kedua lokasi
Gambar 17 Rata-rata nilai intensitas serangan berdasarkan interaksi antara konsentrasi larutan bahan pengawet dan lokasi pengujian.
Rata-rata nilai intensitas di lokasi arboretum sesuai dengan teori dimana
seiring meningkatnya bahan pengawet maka nilai intensitas serangan semakin
tinggi (kayu relatif utuh). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai intensitas
semakin tahan kayu terhadap serangan oleh faktor biologis perusak kayu.
Efektifnya konsentrasi 15% dibandingkan dengan konsentrasi 5% dan
10% disebabkan oleh nilai retensi dan penetrasinya yang lebih tinggi. Menurut
Djauhari (2012), rata-rata retensi dan penetrasi senyawa boron pada
masing-masing konsentrasi berturut-turut adalah 1,64 kg/m3 dan 18,69% (konsentrasi
5%), 3,58 kg/m3 dan 39,07% (konsentrasi 10%) serta 6,40 kg/m3 dan 98,14% (konsentrasi 15%). Ditambah pula dengan curah hujan yang tinggi (151-300 mm)
saat pengujian berlangsung (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 2011)
sehingga boron yang ada pada kayu-kayu awetan 5% dan 10% lebih mudah
tercuci sehingga kayu mudah diserang oleh faktor biologis perusak dibandingkan
dengan kayu awetan berkonsentrasi 15%.
Gambar 18 memperlihatkan kondisi contoh uji setelah di serang oleh
Gambar 18 Perbedaan intensitas serangan terhadap contoh uji di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).
4.2 Kehilangan Berat, Kerusakan Luas Bidang Permukaan dan Intensitas Serangan pada Contoh Uji yang Diawetkan secara Fumigasi di Dua Lokasi Percobaan
4.2.1 Kehilangan Berat Kayu
Rata-rata persentase kehilangan berat contoh uji kayu yang sudah
difumigasi dengan amonia di dua lokasi percobaan (permukiman dan arboretum)
disajikan pada Gambar 19 dan 20. Hasil lengkap perhitungan disajikan pada
Lampiran 7 dan 8.
Gambar 19 Persentase kehilangan berat kayu hasil fumigasi di permukiman. B A
Gambar 20 Persentase kehilangan berat kayu hasil fumigasi di arboretum.
Dari Gambar 19 diketahui bahwa kayu petai yang difumigasi dengan
amonia 10 l memiliki persentase kehilangan berat tertinggi (90,05%), sedangkan
kayu sengon yang difumigasi dengan amonia 2 l memiliki persentase kehilangan
berat terendah (6,68%). Dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol), secara
keseluruhan diketahui bahwa semua kayu, selain sengon yang difumigasi dengan
2 l amonia, walaupun sudah difumigasi ternyata masih dapat diserang atau tidak
tahan terhadap serangan faktor perusak. Rata-rata kehilangan berat kayu sengon,
petai, manii dan karet berturut-turut adalah sebesar 38,86%, 63,33%, 70,57% dan
62,20%, sedangkan rata-rata kehilangan berat kayu kontrolnya hanya 8,36%.
Sama halnya dengan Gambar 19, dari Gambar 20 dapat diketahui bahwa
secara umum semua jenis kayu yang diteliti (sengon, petai, manii dan karet) yang
difumigasi dengan amonia tidak tahan terhadap serangan faktor perusak
dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol), kecuali kayu sengon dan manii yang
difumigasi dengan amonia 4 l karena persentase kehilangan beratnya lebih tinggi
dibandingkan dengan kayu kontrol. Rata-rata kehilangan berat kayu kontrol
sebesar 6,07%, sedangkan rata-rata kehilangan berat kayu sengon, petai, manii
dan karet masing-masing adalah sebesar 34,70%, 69,02%, 28,33% dan 37,26%.
Dibandingkan dengan yang dikubur di arboretum (Gambar 20), ternyata
kayu-kayu yang dikubur di permukiman mengalami rata-rata kehilangan berat yang
kehilangan berat masing-masing jenis kayu di dua lokasi penelitian tidak
memperlihatkan suatu pola yang konsisten (Gambar 19 dan 20).
Hasil analisis sidik ragam atau ANOVA (Lampiran 19) memperlihatkan
bahwa kehilangan berat contoh uji dipengaruhi oleh jenis kayu, volume amonia,
lokasi pengujian, interaksi antara jenis kayu dan lokasi pengujian, serta interaksi
antara jenis kayu, volume dan lokasi pengujian. Uji lanjut Duncan (Lampiran 20)
dan Gambar 21 menunjukkan bahwa kehilangan berat kayu manii yang dikubur di
permukiman, kayu petai yang dikubur di permukiman maupun di arboretum, serta
kayu karet yang dikubur di permukiman ketiganya berbeda nyata dengan
kehilangan berat kayu sengon yang dikubur di permukiman maupun di arboretum
serta kayu manii dan karet yang dikubur di arboretum. Kehilangan berat kayu
manii di permukiman sebanding dengan kehilangan berat kayu petai yang dikubur
di arboretum dan di permukiman serta kayu karet yang dikubur di permukiman.
Kehilangan berat kayu sengon yang dikubur di permukiman juga sebanding
dengan kehilangan berat kayu sengon, manii dan karet yang dikubur di arboretum.
Kehilangan berat tertinggi (70,57%) terdapat pada kayu manii yang dikubur di
permukiman, sedangkan yang terendah pada kayu sengon yang dikubur di
arboretum (23,89%).
Gambar 21 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan interaksi antara jenis kayu dan lokasi pengujian.
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kayu sengon yang sudah
difumigasi relatif lebih tahan terhadap serangan faktor perusak kayu dibandingkan
dengan ketiga jenis kayu yang diteliti, baik di permukiman maupun di arboretum
(Gambar 21). Kehilangan berat kayu sengon baik yang dikubur di permukiman
dan 23,89%. Berbeda dengan kayu yang diawetkan dengan boron, ternyata kayu
yang difumigasi lebih tahan terhadap serangan faktor biologis perusak kayu yang
ada di arboretum. Ini menandakan bahwa amonia tidak disukai oleh faktor
perusak yang ada diarboretum, sedangkan faktor perusak yang ada di permukiman
tidak terpengaruh dengan adanya amonia. Ini memperkuat dugaan bahwa jenis
perusak biologis yang ada di dua lokasi penelitian adalah berbeda.
Gambar 22 memperlihatkan rata-rata kehilangan berat berdasarkan
interaksi antara jenis kayu, volume amonia dan lokasi penelitian. Dari Gambar 22
diketahui bahwa kehilangan berat kayu petai yang difumigasi dalam amonia 8 l
dan 10 l serta kayu manii dalam amonia 2 l yang dikubur di permukiman berbeda
nyata dengan kehilangan berat kayu sengon yang difumigasi dalam amonia 2 l, 4
l, 6 l, 8 l, dan 10 l dan dikubur di arboretum, juga dengan kayu sengon 2 l, 4 l, dan
8 l yang dikubur di permukiman, maupun dengan kayu manii 2 l, 4 l, 6 l, dan 8 l
di arboretum serta dengan kayu karet 2 l, 4 l dan 6 l yang dikubur di arboretum.
Kehilangan berat kayu sengon yang difumigasi dalam 6 l amonia dan dikubur di
permukiman, kayu petai 4 l dan 6 l di arboretum, dan kayu karet 6 l di lokasi
permukiman berbeda nyata dengan kehilangan berat kayu sengon 2 l, 4 l dan 6 l
yang dikubur di arboretum, kayu sengon 2 l dan 4 l di permukiman, kayu manii 2 l
dan 4 l di arboretum, serta dengan kayu karet 2 l dan 4 l yang dikubur di
arboretum. Kehilangan berat kayu petai 2 l dan 8 l yang dikubur di arboretum,
kayu manii 8 l di permukiman serta kayu karet 8 l dan 10 l di permukiman
berbeda nyata dengan kehilangan berat kayu sengon yang difumigasi dalam
amonia 2 l dan dikubur di permukiman, kayu sengon 2 l dan 4 l di arboretum,
kayu manii 4 l dan 6 l di arboretum serta kayu karet 4 l di permukiman.
Kehilangan berat kayu petai yang difumigasi dalam amonia 6 l dan dikubur di
permukiman serta kayu karet 2 l di permukiman berbeda nyata dengan kehilangan
berat kayu sengon yang difumigasi dalam amonia 4 l dan dikubur di arboretum
serta kayu manii 4 l di arboretum. Kehilangan berat kayu petai yang difumigasi
dalam amonia 8 l dan 10 l serta kayu manii 2 l di permukiman berbeda nyata
dengan kehilangan berat kayu sengon dan manii 4 l di arboretum. Kehilangan
kayu karet 8 l di arboretum tidak berbeda nyata dengan kehilangan berat semua
kombinasi lainnya.
Gambar 22 Rata-rata kehilangan berat berdasarkan interaksi antara jenis kayu, volume dan lokasi.
Secara umum dapat disebutkan bahwa kehilangan berat tidak
menunjukkan adanya suatu pola yang konsisten seiring dengan meningkatnya
volume amonia pada setiap lokasi. Rata-rata kehilangan berat tertinggi terjadi
pada kayu manii yang dikubur di permukiman (70,57%). Nilai ini tidak jauh
berbeda dengan kehilangan berat kayu petai di permukiman (63,33%) maupun di
arboretum (69,02%), serta dengan kayu karet di permukiman (62,20%).
Persentase kehilangan berat terendah terdapat pada kayu sengon yang dikubur di
arboretum (23,89%). Semua jenis kayu yang difumigasi dengan amonia relatif
masih tidak tahan terhadap organisme perusak kayu dibandingkan dengan kayu
kontrolnya. Kehilangan berat kayu kontrol di permukiman dan di arboretum
masing-masing sebesar 8,36% dan 6,07%.
Selain diakibatkan oleh perbedaan jenis faktor biologis perusak yang ada
di masing-masing lokasi pengujian, perbedaan nilai kehilangan berat kayu diduga
juga terkait dengan perbedaan struktur anatomi penyusun masing-masing jenis
kayu yang akan mempengaruhi tingkat keterawetan dan kelas awet kayu setelah
kayu difumigasi. Banyak-sedikitnya gas amonia yang masuk ke dalam kayu
sangat menentukan ketahanan kayu terhadap serangan faktor biologis perusak.
[image:35.595.97.477.142.401.2]telah difumigasi memiliki kelas awet yang lebih rendah dibandingkan keawetan
alaminya. Ini menandakan bahwa amonia tidak berikatan dengan komponen
dinding sel kayu namun hanya terdapat di dalam rongga sel kayu terutama rongga
sel pembuluh (pori-pori). Semakin kecil diameter rongga pori-pori kayu maka
akan semakin sedikit pula volume amonia yang masuk. Kondisi ini diperparah
dengan sifat amonia yang mudah menguap.
Tabel 6 Kelas awet kayu hasil fumigasi setelah uji kubur di permukiman
Jenis Kayu
% Kehilangan Berat Keawetan
Alami
Kelas Awet Setelah Uji kubur
2 l 4 l 6 l 8 l 10 l 2 l 4 l 6 L 8 l 10 l
Sengon 6,68 16,85 76,57 35,43 48,75 IV - V III IV V V V Petai 45,55 47,03 52,39 81,62 90,05 IV V V V V V
Manii 82,63 80,74 64,24 70,35 54,89 IV V V V V V Karet 53,72 43,25 74,27 67,72 72,06 IV - V V V V V V
Tabel 7 Kelas awet kayu hasil fumigasi setelah uji kubur di arboretum
Jenis Kayu
% Kehilangan Berat Keawetan
Alami
Kelas Awet Setelah Uji kubur
2 l 4 l 6 l 8 l 10 l 2 l 4 l 6 l 8 l 10 l
Sengon 77,03 4,22 25,61 36,66 30,00 IV - V V II V V V Petai 69,94 74,66 73,78 68,7 58,00 IV V V V V V Manii 25,39 3,69 14,14 32,64 65,79 IV V II IV V V
Karet 19,93 10,25 33,12 44,88 78,14 IV - V V III V V V
Gambar 23 memperlihatkan kehilangan berat contoh uji sebelum dan
sesudah dikubur di masing-masing lokasi pengujian.
Gambar 23 Kehilangan berat contoh uji di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).
A B
[image:36.595.86.478.551.727.2]4.2.2 Kerusakan Luas Bidang Permukaan
Rata-rata persentase kerusakan luas bidang permukaan (kerusakan LBP)di
dua lokasi pengujian disajikan pada Gambar 24 dan 25. Data lengkap hasil
perhitungan disajikan pada Lampiran 9 dan 10.
Dari Gambar 24 diketahui bahwa kayu karet yang difumigasi dengan
amonia 6 l mengalami kerusakan LBP yang tertinggi (99,25%), sedangkan kayu
sengon yang difumigasi dengan amonia 2 l mengalami kerusakan LBP yang
terendah (23,75%). Dibandingkan dengan kayu pinus (kontrol) diketahui bahwa
semua kayu yang diteliti meskipun sudah difumigasi ternyata masih kurang tahan
terhadap faktor perusak. Rata-rata kerusakan LBP kayu kontrol 10,50%.
Secara keseluruhan diketahui pula bahwa meskipun kerusakan LBP pada
semua jenis kayu yang diteliti dan pada setiap volume amonia yang diberikan
lebih besar dibandingkan kerusakan LBP kontrolnya, persentase kerusakan LBP
tidak berhubungan dengan peningkatan volume amonia. Rata-rata kerusakan LBP
kayu sengon, petai, manii dan karet secara keseluruhan berturut-turut adalah
71,43%, 89,95%, 94,83% dan 89,42%. Keadaan ini terkait dengan tingkat
keterawetan dan kelas awet kayu setelah kayu difumigasi. Dengan keterawetan
yang sulit dan kelas awet dari rendah sampai sangat rendah, maka kayu yang
sudah difumigasi pun akan dapat dengan mudah diserang oleh faktor biologis
Gambar 24 Persentase kerusakan LBP hasil fumigasi di permukiman.
Gambar 25 memperlihatkan rata-rata persentase kerusakan LBP kayu yang
telah difumigasi dan dikubur di arboretum.
Gambar 25 Persentase kerusakan LBP hasil fumigasi di arboretum.
Dari Gambar 25 diketahui bahwa kerusakan LBP kayu petai yang
difumigasi dengan amonia 4 l merupakan kerusakan LBP yang tertinggi (99,08%),
sedangkan kerusakan LBP kayu sengon yang difumigasi dengan amonia 4 l
merupakan kerusakan LBP yang terendah (22,25%). Kayu sengon dan karet yang
difumigasi dengan amonia 4 l serta kayu manii yang difumigasi dengan amonia 6
l mengalami kerusakan LBP yang lebih rendah dibandingkan kayu kontrol.
Kerusakan LBP kayu sengon dan karet 4 l masing-masing sebesar 22,5% dan
31,92%, sedangkan kerusakan LBP kayu manii 6 l sebesar 26,08%. Kerusakan
LBP kayu pinus (kontrol) adalah 38,50%.
Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata kerusakan LBP pada semua
jenis kayu yang diteliti lebih tinggi dibandingkan kerusakan LBP kayu kontrol.
Rata-rata kerusakan LBP hasil penelitian ini adalah 47,10% (sengon), 98,15%
(petai), 49,18% (manii) dan 58,25% (karet). Kerusakan LBP kayu petai tidak
dipengaruhi oleh volume amonia yang digunakan, sedangkan pada sengon, manii
dan karet, kerusakan LBP berfluktuasi menurut volume amonia dan tidak
Hasil analisis sidik ragam atau ANOVA (Lampiran 21) menunjukkan
bahwa kerusakan LBP dipengaruhi oleh jenis kayu, lokasi pengujian dan interaksi
antara jenis kayu dan lokasi. Hasil uji lanjut Duncan (Lampiran 22) dan Gambar
26 memperlihatkan bahwa kerusakan LBP kayu petai yang dikubur di arboretum
dan kayu manii yang dikubur di permukiman berbeda nyata dengan kerusakan
LBP kayu sengon yang dikubur di permukiman maupun di arboretum serta kayu
karet, manii, dan sengon yang dikubur di arboretum. Kerusakan LBP kayu petai
dan karet yang dikubur di permukiman berbeda nyata dengan kerusakan LBP
kayu sengon, manii dan karet yang dikubur di arboretum. Kerusakan LBP kayu
petai yang dikubur di arboretum dan kayu manii di permukiman tidak berbeda
nyata dibandingkan dengan kerusakan LBP kayu petai dan karet yang dikubur di
permukiman. Selanjutnya diketahui pula bahwa kerusakan LBP kayu petai dan
karet yang dikubur di permukiman tidak berbeda nyata dibandingkan dengan
kerusakan LBP kayu sengon yang di permukiman. Kerusakan LBP kayu sengon
di permukiman juga tidak berbeda nyata dengan kerusakan LBP kayu karet yang
di arboretum. Kerusakan LBP kayu karet di arboretum tidak berbeda nyata
dengan kerusakan LBP kayu manii yang di arboretum.
Gambar 26 Rata-rata kerusakan LBP berdasarkan interaksi antara jenis kayu dan lokasi pengujian.
Dari Gambar 26 juga diketahui bahwa kerusakan LBP kayu sengon, manii
dan karet yang dikubur di permukiman lebih besar dibandingkan dengan yang
dikubur di arboretum, sedangkan pada kayu petai relatif sama. Rata-rata nilai
pengujian adalah 98,15% (petai di arboretum), sedangkan yang terendah adalah
47,10% (sengon di arboretum).
Perbedaan nilai kerusakan LBP di atas juga terkait dengan perbedaan
macam atau jenis faktor biologis perusak kayu yang ada di dua lokasi serta
perbedaan struktur anatomi penyusun kayu. Perbedaan dalam hal struktur anatomi
kayu akan mengakibatkan perbedaan jumlah amonia yang masuk dan atau yang
bereaksi dengan komponen dinding sel penyusun kayu. Sifat amonia yang mudah
menguap juga turut andil dalam perbedaan nilai kerusakan LBP yang terjadi.
Gambar 27 memperlihatkan kerusakan LBP contoh uji di masing-masing
lokasi pengujian.
Gambar 27 Kerusakan LBP contoh uji di permukiman (A dan B) dan di arboretum (C dan D).
4.2.3 Intensitas Serangan
Rata-rata nilai intensitas serangan di dua lokasi percobaan yang berbeda
(permukiman dan arboretum) disajikan pada Gambar 28 dan 29. Data lengkap
hasil perhitungan disajikan pada (Lampiran 11 dan 12).
Dari Gambar 28 diketahui bahwa intensitas serangan faktor biologis
perusak kayu yang paling rendah terdapat pada kayu sengon yang difumigasi
dengan amonia 2 l. Intensitas serangan ini setara dengan intensitas serangan pada
kayu kontrolnya (nilai = 7). Intensitas serangan pada kayu sengon 4 l dan