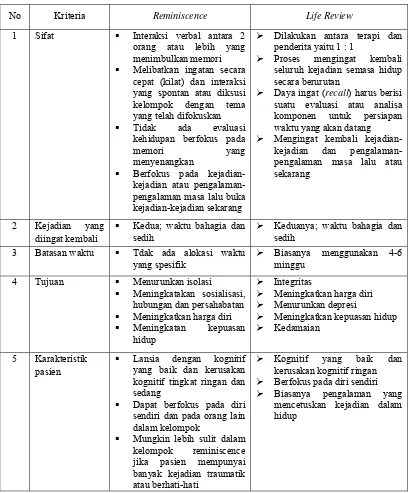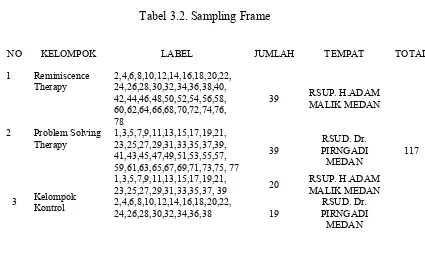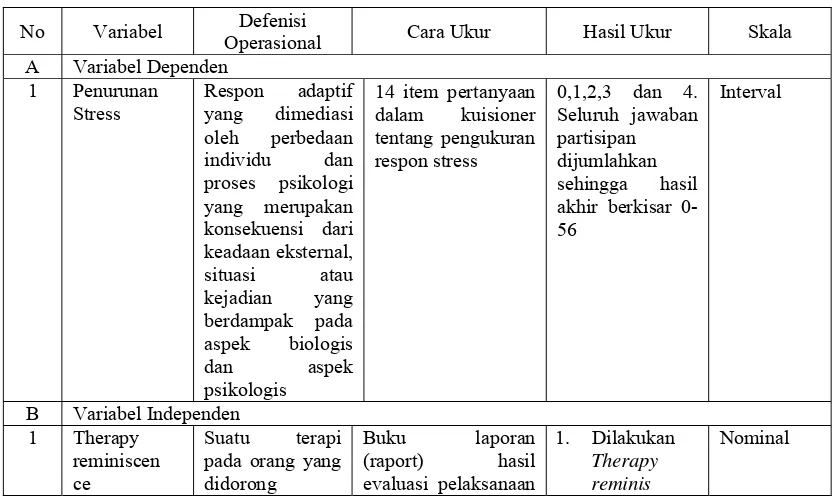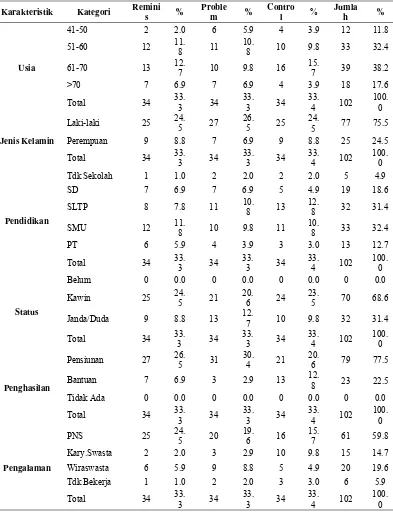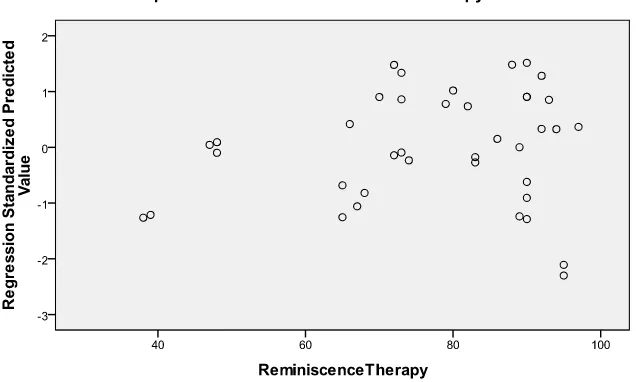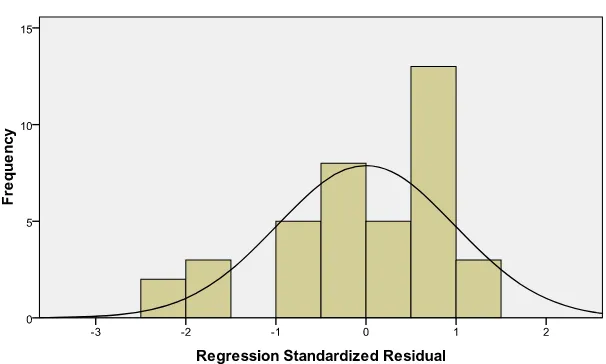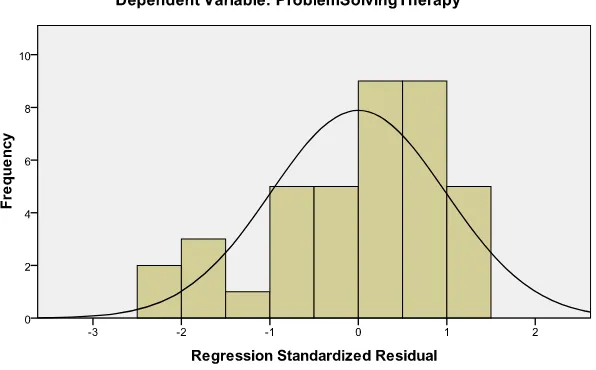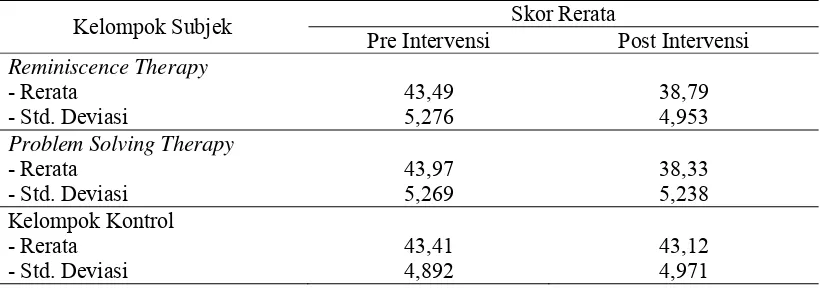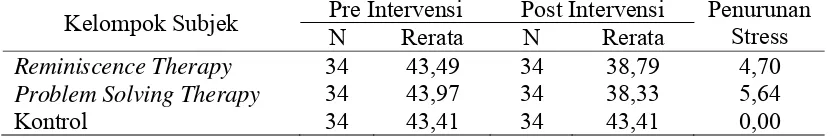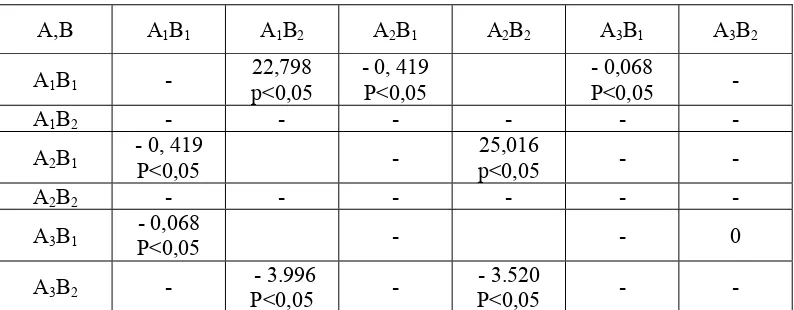TESIS
Oleh
NIXS0N MANURUNG
127046044 / KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Keperawatan (M.Kep) dalam Program Studi Magister Ilmu Keperawatan
Minat Studi Keperawatan Medikal Bedah pada Fakultas Keperawatan
Universitas Sumatera Utara
Oleh
NIXS0N MANURUNG
127046044 / KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Dr. Wiwik Sulistyaningsih, S.Psi.,M.Si. Psi Anggota : 1. Iwan Rusdi, SKp., MNS
Stres Pada Penderita Gagal Jantung
Nama Mahasiswa : Nixson Manurung Program Studi : Magister Ilmu Keperawatan Minat Studi : Keperawatan Medikal Bedah
Tahun : 2014
ABSTRAK
Stres adalah suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Gagal
jantung akan menyebabkan seseorang sesak nafas dan cepat lelah baik dalam
keadaan beraktivitas ataupun dalam keadaan istirahat. Penelitian ini bertujuan
menguji efektifitas reminscence therapy dan problem solving therapy dalam
upaya menurunkan stres pada penderita gagal jantung di RSUD Dr. Pirngadi
Medan dan RSUP H. Adam Malik Medan. Desain penelitian kuasi eksperimen pre
test – post test dengan grup kontrol. Sampel 102 penderita gagal jantung, terdiri
dari 34 kelompok intervensi Reminscence therapy, 34 kelompok intervensi
problem solving therapy dan 34 kelompok kontrol. Reminscence therapy
diberikan sebanyak 5 sesi sedangkan problem solving therapy diberikan sebanyak
4 sesi dalam jangka waktu 7 minggu dengan durasi waktu perlakuan selama 90
penurunan stres sebelum terapi reminiscence dengan setelah terapi reminiscence
sehingga reminiscence therapy bermanfaat untuk menurunkan stres penderita
gagal jantung. Problem Solving Therapy menunjukkan (p<0,05) yang bermakna
terdapat perbedaan penurunan stres sebelum terapi solving problem dengan
setelah terapi solving problem sehingga solving problem therapy bermanfaat
untuk menurunkan stres penderita gagal jantung. Uji Anova Fhitung < Ftabel dan
harga p > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan penurunan stres
pada kelompok reminiscence therapy maupun kelompok problem solving therapy.
Kedua terapi ini dapat direkomendasikan untuk digunakan pada penderita gagal
jantung yang mengalami stres. Diantara kedua terapi ini maka problem solving
therapy lebih efektif digunakan daripada Reminscence therapy.
Name : Nixson Manurung Study Program : Master of Nursing
Field of Specialization : Medical-Surgical Nursing ABSTRACT
Stress is a depressing condition, either physically or psychologically. Heart failure
will cause someone to be in sultry and to be easily exhausted, either in activity or
in rest. The objective of the research was to examine the effectiveness of
reminiscence therapy and problem solving therapy in reducing stress in heart
failure patients at RSUP H. Adam Malik, Medan. The research used a quasi
experiment pre test – post test design with control group. The samples consisted
of 102 heart failure patients; 34 of them respectively belonged to intervention
group of reminiscence therapy, intervention group of problem solving therapy,
and control group. Reminiscence therapy was given in five sessions, and problem
solving therapy was given in four sessions in seven weeks with the duration of 90
minute-treatment time. The data were analyzed by using univatriate, bivatriate,
and multivatriate analyses after assumption test (normality test and homogeneity
test) had been performed. Paired t-test and Anova test were used for statistic test.
The result of the research on the reminiscence therapy showed that (p<0.05)
which indicated that there was the difference in the decrease in stress between pre-
therapy and post-problem solving therapy so that problem solving therapy was
beneficial for reducing stress in heart failure patients. The result of Anova test
showed that Fcount < Ftable and p-value > 0.05 which indicated that there was no
significant difference in the decrease in stress both in the reminiscence therapy
group and in the problem solving therapy group. It is recommended that both
therapies should be used for heart failure patients who undergo stress although
problem solving therapy is better than reminiscence therapy.
“Perbandingan Reminiscence Therapy dan Problem Solving Therapy untuk
Menurunkan Stres pada Penderita Gagal Jantung”.
Selama menyusun tesis ini, penulis mengalami banyak pengalaman yang
berharga dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. dr. Dedi Ardinata., M. Kes. selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas
Sumatera Utara.
2. Setiawan, S.Kp., MNS., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu
Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.
3. Achmad Fathi, S.Kep,Ns, MNS selaku Sekretaris Program Studi Magister
Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.
4. Dr. Wiwik Sulistyaningsih, S.Psi. M.Si.Psikolog selaku dosen pembimbing
pertama, yang telah senantiasa memberikan waktu untuk membimbing,
memberikan arahan, ilmu dan saran yang sangat berharga dalam proses
penyusunan tesis ini.
5. Iwan Rusdi, SKp. MNS, selaku dosen pembimbing kedua, yang juga telah
senantiasa memberikan waktu untuk membimbing, memberikan arahan,
ilmu dan saran yang sangat berharga dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ir. Evawany Yunita Aritonang, M.Si selaku dosen penguji I dan Cholina
peneliti dalam pengambilan data
8. Direktur RSUD Dr. Pirngadi Medan yang telah memberikan izin kepada
peneliti dalam pengambilan data
9. Keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan yang
begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Keperawatan
Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Medan dan terkhusus
untuk teman-teman Magister Keperawatan Konsentrasi Keperawatan
Medikal Bedah angkatan pertama yang telah saling mengingatkan dan
mendukung selama penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah
membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih ada kekurangan, baik dari aspek
bahasa maupun isinya. Oleh karena itu penulis akan menerima saran dan masukan
Medan, 22 Agustus 2014
Penulis
Tempat/Tanggal lahir : P. Pasir, 19 Februari 1977
Alamat Asal : Jl. Gereja No. 37-B Medan
Email : [email protected]
Hp : 0812.6079.4108
Riwayat Pendidikan :
Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun Lulus
SD SD NEGERI – I P. PASIR 1989
SMP SLTP PTP-VII D. ILIR 1992 SMA SMA NEGERI 1 SERBELAWAN 1995
D3 Keperawatan Akper IMELDA Medan 1998
S1 Keperawatan Ekstensi Keperawatan di USU 2001
Ners Ners USU 2003
S2 Keperawatan Magister Keperawatan USU 2014
Riwayat Pekerjaan :
Tahun 1998 s/d sekarang sebagai staf dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Imelda Medan.
Kegiatan Akademik Selama Studi :
Workshop Aplikasi Penelitian Kualitatif Sebagai Landasan Pengembangan
Pengetahuan Bidang Kesehatan tanggal 18 Desember 2012, sebagai
Noc, tahun 2013, sebagai Peserta
2013 Medan International Nursing Conference “ The Application of Caring
Science in Nursing Education Advanced Research and Clinical
ABSTRACT ….……… iii
2.4. Landasan Teori Betty Neuman ………. 64
2.5. Kerangka Konsep ………..….……….. 69
BAB 3 . METODE PENELITIAN ………....……….. 70
3.1. Jenis Penelitian ……….……… 70
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian …….…………..………. 71
3.3. Populasi dan Sampel ……….…..………. 72
3.4. Metode Pengumpulan Data ……….. 75
3.5. Variabel dan Defenisi Operasional ……….……..……… 76
3.6. Definisi Operasional ……… 77
3.7. Metode Pengukuran ………..……… 78
3.8. Prosedur Eksperimen ………..….. 79
3.9. Metode Analisa Data ………..….. 82
3.10.Pertimbangan Etik ………..….. 83
BAB 4 . HASIL PENELITIAN ………..……….….. 86
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ……… 86
4.2. Keterbatasan Penelitian ………..…….. 91
4.3. Hasil Penelitian ……… 92
BAB 5 . PEMBAHASAN ……… 116
5.1. Pengaruh Reminiscence Therapi untuk Menurunkan Stres - Pada Penderita Gagal Jantung……… 116
5.2. Pengaruh Problem Solving Therapy untuk Menurunkan - Stres Pada Penderita Gagal Jantung ………..…… 121
5.3. Perbandingan Reminiscence Therapy dan Problem Solving - Therapy ………..…… 123
5.4. Reminiscence Therapy, Problem Solving Therapy dan - Landasan Teori Betty Neuman ………..…… 125
BAB 6 . KESIMPULAN DAN SARAN …..……….. 127
6.1. Kesimpulan ………..………. 127
6.2. Saran ………..……… 128
Tabel 3.2. Sampling Frame ………. 75 Tabel 3.3. Defenisi Operasional ……….. 77 Tabel 4.1. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Demografi Karakteristik 92 Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas ……… 94 Tabel 4.3. Hasil Uji Homogenitas antar kelompok reminiscence therapy, -
problem solving therapy dan kelompok kontrol sebelum intervens 97 Tabel 4.4. Data Kelompok Variabel Reminiscence dan Problem Solving -
Therapy ……… 98 Tabel 4.5 Perhitungan Penurunan Stres Responden Sebelum dan Sesudah
Terapi ……….. 99 Tabel 4.6. Ringkasan uji-t antar jenis intervensi (kelompok Reminiscence -
Therapy, kelompok Solving Problem Therapy dan kelompok - kontrol) pada pengamatan sebelum dan sesudah intervensi …… 100 Tabel 4.7. HasilRerata danStandar DeviasiKelompok Terapi Post -
Reminiscence dan Kelompok Kontrol ……… 101 Tabel 4.8. Hasil Uji Sampel Independen antara Kelompok Terapi -
Reminiscence dan Kelompok Kontrol Setelah Intervensi …….. 102 Tabel 4.9. Hasil Rerata danStandard Deviasi Kelompok Terapi Post -
Problem Solving dan Kelompok Kontrol ……… 104 Tabel 4.10. Hasil Uji Sampel Independen Kelompok Terapi Problem -
Solving Setelah Intervensi dan Kelompok Kontrol ………. 105 Tabel 4.11. Hasil Rerata danStandard Deviasi Setelah Intervensi antara - Kelompok Terapi Reminiscence dan Kelompok Terapi -
Problem Solving ……… 106
Tabel 4.12. Hasil Uji Sampel Independen Setelah Intervensi antara - Kelompok Terapi Reminiscence dan Kelompok Terapi -
Problem Solving ……….. 107
Tabel 4.13. Perhitungan Anovaantara Kelompok Terapi Reminiscence - dengan Kelompok Terapi Problem Solving ……… 109 Tabel 4.14. Perhitungan Nilai Koefisien antara Kelompok Terapi -
Post Reminiscence dengan kelompok Terapi Post Problem -
Solving ………. 110
Tabel 4.15. Perhitungan Uji Sampel Kelompok Reminiscence Sebelum - dan Sesudah Intervensi ……… 110 Tabel 4.16. Perhitungan Uji Sampel Kelompok ProblemSolving Sebelum -
Gambar 3.1. Kerangka Kerja Perbandingan Reminiscence Therapy
dan Problem Solving Therapy untuk Menurunkan Stres pada Penderita Gagal Jantung ………
79
Gambar 4.1 Grafik Hasil Uji Normalitas Kelompok Reminiscence
Therapy ………. 95
Gambar 42 Histogram Kelompok Reminiscence Therapy…………. 96 Gambar 4.3. Grafik Hasil Uji Normalitas Kelompok Problem
Solving Therapy ……….. 96
a. Lembar Penjelasan tentang Penelitian ... 119
b. Lembar Persetujuan Menjadi Responden ... 120
c. Kuesioner Data Demografi ... 121
d. Instrumen Penelitian ... 122
e. Izin Penggunaan Instrumen ... 123
Lampiran 2 Modul ... 125
Lampiran 3 Izin Penelitian ... 127
a. Surat Pengambilan Data dari Dekan Fakultas Keperawatan ... 128
b. Surat Persetujuan Etik Penelitian ... 129
c. Surat Ijin Pengambilan Data dari RSUD Dr. Pirngadi Medan ... 130
Stres Pada Penderita Gagal Jantung
Nama Mahasiswa : Nixson Manurung Program Studi : Magister Ilmu Keperawatan Minat Studi : Keperawatan Medikal Bedah
Tahun : 2014
ABSTRAK
Stres adalah suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Gagal
jantung akan menyebabkan seseorang sesak nafas dan cepat lelah baik dalam
keadaan beraktivitas ataupun dalam keadaan istirahat. Penelitian ini bertujuan
menguji efektifitas reminscence therapy dan problem solving therapy dalam
upaya menurunkan stres pada penderita gagal jantung di RSUD Dr. Pirngadi
Medan dan RSUP H. Adam Malik Medan. Desain penelitian kuasi eksperimen pre
test – post test dengan grup kontrol. Sampel 102 penderita gagal jantung, terdiri
dari 34 kelompok intervensi Reminscence therapy, 34 kelompok intervensi
problem solving therapy dan 34 kelompok kontrol. Reminscence therapy
diberikan sebanyak 5 sesi sedangkan problem solving therapy diberikan sebanyak
4 sesi dalam jangka waktu 7 minggu dengan durasi waktu perlakuan selama 90
penurunan stres sebelum terapi reminiscence dengan setelah terapi reminiscence
sehingga reminiscence therapy bermanfaat untuk menurunkan stres penderita
gagal jantung. Problem Solving Therapy menunjukkan (p<0,05) yang bermakna
terdapat perbedaan penurunan stres sebelum terapi solving problem dengan
setelah terapi solving problem sehingga solving problem therapy bermanfaat
untuk menurunkan stres penderita gagal jantung. Uji Anova Fhitung < Ftabel dan
harga p > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan penurunan stres
pada kelompok reminiscence therapy maupun kelompok problem solving therapy.
Kedua terapi ini dapat direkomendasikan untuk digunakan pada penderita gagal
jantung yang mengalami stres. Diantara kedua terapi ini maka problem solving
therapy lebih efektif digunakan daripada Reminscence therapy.
Name : Nixson Manurung Study Program : Master of Nursing
Field of Specialization : Medical-Surgical Nursing ABSTRACT
Stress is a depressing condition, either physically or psychologically. Heart failure
will cause someone to be in sultry and to be easily exhausted, either in activity or
in rest. The objective of the research was to examine the effectiveness of
reminiscence therapy and problem solving therapy in reducing stress in heart
failure patients at RSUP H. Adam Malik, Medan. The research used a quasi
experiment pre test – post test design with control group. The samples consisted
of 102 heart failure patients; 34 of them respectively belonged to intervention
group of reminiscence therapy, intervention group of problem solving therapy,
and control group. Reminiscence therapy was given in five sessions, and problem
solving therapy was given in four sessions in seven weeks with the duration of 90
minute-treatment time. The data were analyzed by using univatriate, bivatriate,
and multivatriate analyses after assumption test (normality test and homogeneity
test) had been performed. Paired t-test and Anova test were used for statistic test.
The result of the research on the reminiscence therapy showed that (p<0.05)
which indicated that there was the difference in the decrease in stress between pre-
therapy and post-problem solving therapy so that problem solving therapy was
beneficial for reducing stress in heart failure patients. The result of Anova test
showed that Fcount < Ftable and p-value > 0.05 which indicated that there was no
significant difference in the decrease in stress both in the reminiscence therapy
group and in the problem solving therapy group. It is recommended that both
therapies should be used for heart failure patients who undergo stress although
problem solving therapy is better than reminiscence therapy.
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Penyakit kardiovaskular sekarang merupakan penyebab kematian paling
umum di seluruh dunia. Penyakit kardiovaskular menyumbang hampir mendekati
40% kematian di negara maju dan sekitar 28% di negara miskin dan berkembang
(Gaziano, 2008). Menurut data dari studi Framingham 90% orang yang berumur
diatas 55 tahun akan mengalami hipertensi selama masa hidupnya (Lilly, et al.,
2007). Hal ini menggambarkan masalah kesehatan publik karena hipertensi dapat
meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung
kongestif ( Kotchen, 2008). Sampai saat ini prevalensi hipertensi di Indonesia
berkisar antara 5 - 10%. Kurun 20 tahun terakhir, angka kematian karena serangan
jantung dan stroke yang disebabkan oleh hipertensi mengalami peningkatan
(Pickering, 2008).
Menurut Fisher (2005) pengobatan yang efektif penderita hipertensi yang
tidak diobati terbukti mengalami pemendekan masa kehidupan sekitar 10 – 20
tahun. Bahkan individu yang mengalami hipertensi ringan jika tidak diobati
selama 7 – 10 tahun beresiko tinggi mengalami komplikasi yaitu sekitar 30%
terbukti mengalami aterosklerosis dan lebih dari 50% akan mengalami kerusakan
organ yang berhubungan dengan hipertensi itu sendiri, seperti kardiomegali, gagal
jantung kongestif, retinopati, masalah serebrovaskular, dan/atau insufisiensi
yang progresif dan letal jika tidak segera diobati. Gopal (2009) menyatakan
bahwa gagal jantung merupakan penyebab tersering rawat inap pada pasien
berusia 65 tahun keatas. Cowie (2008) dan Figueroa (2006) juga menuliskan
bahwa prevalensi gagal jantung meningkat seiring dengan pertambahan usia dan
terutama mengenai pasien dengan usia di atas 65 tahun.
Penelitian Merda & Harris (2013) diketahui bahwa prevalensi penyakit
jantung hipertensi pada gagal jantung kongestif dewasa (usia > 20 tahun) yang
dirawat di unit rawat kardiovaskular RSUP H.Adam Malik Medan pada tahun
2011 sebesar 44,5%. Prevalensi hipertensi sebagai penyebab gagal jantung
kongestif dewasa (usia > 20 tahun) yang dirawat di unit rawat kardiovaskular
RSUP H.Adam Malik Medan pada tahun 2011 sebesar 66,5%, berdasarkan jenis
kelamin paling banyak jenis kelamin laki – laki, yaitu sebanyak 135 orang
(67,5%) dengan kelompok usia 50 – 59 tahun yaitu sebanyak 74 orang (37%)
serta yang memiliki riwayat hipertensi adalah sebanyak 133 orang (66,5%).
Saat ini Congestif heart failure (CHF) atau yang biasa di sebut gagal jantung
kongestif merupakan satu-satunya penyakit kardiovaskular yang terus meningkat
insiden dan prevalensinya. Resiko kematian akibat gagal jantung berkisar antara
5-10% pertahun pada gagal jantung ringan yang akan meningkat menjadi 30-40%
pada gagal jantung berat. Selain itu, CHF merupakan penyakit yang paling sering
memerlukan perawatan ulang di rumah sakit (readmission) meskipun pengobatan
rawat jalan telah di berikan secara optimal. (R .Miftah. 2004).
Masalah kesehatan dengan gangguan sistem kardiovaskular masih menduduki
penduduk Amerika menderita CHF , sedangkan berdasarkan profil kesehatan
Sumatera Utara tahun 2000 Penyakit Jantung Koroner menempati urutan ketiga
dari penyakit tidak menular dengan jumlah penderita sebanyak 354 orang yang
berumur ≥60 tahun. Jumlah kematian penyakit jantung koroner sebanyak 37 orang dengan CFR (Case Fatality Rate). Dari penelitian Damanik (2000-2004) di
RSUP H. Adam Malik bahwa jumlah penderita penyakita jantung koroner
sebanyak 230 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 13 orang CFR sebesar
5,65%, berdasarkan usia diketahui bahwa pasien gagal jantung kongestif dengan
kelompok usia 20 – 29 tahun merupakan sampel yang paling sedikit yaitu
sebanyak 2 orang (1%), sedangkan sampel terbanyak berasal dari kelompok usia
50 – 59 tahun yaitu sebanyak 74 orang (37%). Berdasarkan data didapat peneliti
diketahui jumlah penderita penyakit jantung koroner di RSU Dr. Pringadi Medan
tahun 2003 sebanyak 198 kasus, tahun 2004 sebanyak 274 kasus, tahun 2005
sebanyak 259 kasus, tahun 2006 sebanyak 283 kasus. Mann (2008) mengatakan
bahwa gagal jantung lebih sedikit terjadi pada perempuan daripada laki - laki. Hal
ini juga didukung oleh data European Heart Failure Survey pada tahun 2000 –
2001, bahwa 53% pasien gagal jantung yang dirawat di rumah sakit adalah
berjenis kelamin laki - laki (Cowie, 2008).
Menurut Gopal (2009) gagal jantung merupakan penyebab tersering rawat
inap pada pasien berusia 65 tahun keatas. Dalam Cowie (2008) dan Figueroa
(2006) juga dituliskan bahwa prevalensi gagal jantung meningkat seiring dengan
pertambahan usia dan terutama mengenai pasien dengan usia di atas 65 tahun.
meningkat. Oleh karena itu gagal jantung merupakan masalah kesehatan yang
utama. Setengah dari pasien yang terdiagnosis gagal jantung masih punya harapan
hidup 5 tahun. Penelitian Framingham menunjukkan mortalitas 5 tahun sebesar
62% pada pria dan 42% wanita. Kasper (2005) dalam satu randomized trial yang
besar pada pasien yang dirawat dengan gagal jantung yang mengalami
dekompensasi, mortalitas 60 hari adalah 9,6% dan apabila dikombinasi dengan
mortalitas dan perawatan ulang dalam 60 hari jadi 35,2%. Sekitar 45% pasien
gagal jantung akut akan dirawat ulang paling tidak satu kali, 15% paling tidak dua
kali dalam 12 bulan pertama. Angka kematian lebih tinggi lagi pada infark jantung
yang disertai gagal jantung berat dengan mortalitas dalam 12 bulan adalah 30%,
50% rata-rata penderita gagal jantung akan meninggal dalam waktu 5 tahun sejak
diagnosanya ditegakkan.
Stres adalah suatu kondisi dinamik dalam mana seseorang individu
dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala atau tuntutan yang dikaitkan
dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersiapkan sebagai
tidak pasti dan penting. Stres adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh
transaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak
antara tuntutan yang berasal dari situasi dan sumber daya system biologis,
psikologis dan social dari seseorang (Lahey & Ciminero, 1980).
Tanda peringatan pertama dari rasa takut, marah, frustasi, trauma atau
penyakit pada tubuh pertama diterima oleh saraf sensoris yang disebut dengan
organ sensoris seperti mata, telinga, lidah dan kulit yang terletak dibagian luar
korteks serebral. Korteks serebral terlibat dalam fungsi ini untuk meningkatkan
kesadaran seseorang terhadap stres yang dihadapinya agar individu dapat segera
mengatasi stres . Dalam tahap ini, semua sytem dalam organ dalam keadaan siaga
dan siap untuk bertempur atau melarikan diri dari stres. Jantung bekerja lebih
keras untuk meningkatakan curah jantung dan meningkatkan kadar oksigen serta
gizi yang diperlukan untuk pengeluaran energi. Detak jantung bertambah cepat
agar dapat meningkatkan jumlah oksigen yang diperlukan. Pembuluh darah
meningkatkan kontraksi untuk membantu kerja peredaran darah. Otot-otot
berkontraksi sehingga kaki tangan dan punggung siap untuk bertindak jika perlu
untuk melindungi tubuh terhadap ancaman. Produksi keringat meningkat, sebagai
hasil peningkatan suhu tubuh yang dikeluarkan melalui mulut.
Jika individu ini dapat mengatasi stres, maka fungsi tubuh akan normal
kembali tetapi bila gagal maka stres akan berlangsung terus menerus sehingga
persediaan tenaga didalam tubuh akan habis dan individu tersebut menjadi
kepayahan. Seorang individu sering mengalami stres hingga terdapat perubahan
fisiologis dalam jangka waktu lama maka akan terjadi kerusakan yang menetap
dalam tubuh .
1.2.Permasalahan
Melihat latar belakang permasalahan yang didapat oleh peneliti maka yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan
reminiscence therapy dan problem solving therapy dalam menurunkan stres pada
1.3.Tujuan Penelitian
a) Menguji efektifitas reminiscence therapi untuk menurunkan stres pada
pasien gagal jantung
b) Menguji efektifitas problem solving therapi untuk menurunkan stres pada
pasien gagal jantung
c) Menguji keefektifan antara reminiscence therapi dan problem solving
therapi untuk menurunkan stres pada pasien gagal jantung.
1.4.Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan
penelitian yang harus diuji validitasnya secara empiris (Sastroasmoro & Ismael,
2008). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang
relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data (Sugiyono, 2009).
Berdasarkan teori yang berkaitan dengan efektifitas therapy reminiscence dan
problem solving therapy pada penderita gagal jantung, maka hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah :
1. Ada penurunan stres pada penderita gagal jantung setelah diberikan therapy
reminiscence
2. Ada penurunan stres pada penderita gagal jantung setelah diberikan problem
3. Ada perbedaan penurunan stres pada penderita gagal jantung yang
mendapatkan therapy reminiscence dan problem solving therapy.
1.5.Manfaat Penelitian
1.5.1. Aspek teoritis (keilmuan)
1.5.1.1. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan
masukan kepada perawat dalam meningkatkan
pengetahuannya untuk menurunkan stres pada
penderita gagal jantung
1.5.1.2. Meningkatkan kemampuan perawat ataupun petugas
kesehatan lainnya dalam menentukan terapi yang
spesifik untuk menurunkan stres pada penderita gagal
jantung
1.5.1.3. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan
keperawatan dalam upaya menurunkan stres pada
penderita gagal jantung
1.5.2. Aspek praktis
1.5.2.1. Adanya perbandingan antara therapy reminiscence dan
keperawatan spesialis dalam melakukan pilihan untuk
menurunkan stres pada penderita gagal jantung
1.5.2.2. Penelitian ini dapat digunakan dan dikembangkan
sehingga menjadi suatu modul atau acuan untuk
dipakai menjadi standard profesi dan standard nasional
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Stres
Stres dalam arti secara umum adalah perasaan tertekan, cemas dan tegang.
Dalam bahasa sehari – hari stres di kenal sebagai stimulus atau respon yang
menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Sarafino (1994) mengartikan
stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan
lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal
dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari
seseorang.
Ivancevich (2001), mendefinisikan stres sebagai respon adaptif yang
dimediasi oleh perbedaan individu dan proses psikologi yang merupakan
konsekuensi dari keadaan eksternal, situasi atau kejadian yang berdampak pada
keadaan fisik atau psikologis seseorang. Wijono (1997), Stres adalah reaksi alami
tubuh untuk mempertahankan diri dari tekanan secara psikis. Tubuh manusia
dirancang khusus agar bisa merasakan dan merespon gangguan psikis ini.
Tujuannya agar manusia tetap waspada dan siap untuk menghindari bahaya.
Menurut Lazarus & Folkman (1986) stres adalah keadaan internal yang dapat
diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan dan sosial yang
dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali atau melebihi kemampuan
individu untuk mengatasinya. Stres juga adalah suatu keadaan tertekan, baik
suatu istilah yang digunakan dalam ilmu perilaku dan ilmu alam untuk
mengindikasikan situasi atau kondisi fisik, biologis dan psikologis organisme
yang memberikan tekanan kepada organisme itu sehingga ia berada diatas ambang
batas kekuatan adaptifnya. (McGrath, dan Wedford dalam Arend dkk, 1997).
Kondisi ini jika berlangsung lama akan menimbulkan perasaan cemas, takut
dan tegang. Berdasarkan dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa stres
merupakan suatu kondisi pada individu yang tidak menyenangkan dimana dari hal
tersebut dapat menyebabkan terjadinya tekanan fisik maupun psikologis pada
individu. Kondisi yang dirasakan tidak menyenangkan itu disebabkan karena
adanya tuntutan-tuntutan dari lingkungan yang dipersepsikan oleh individu
sebagai sesuatu yang melebih kemampuannya atau sumber daya yang dimilikinya,
karena dirasa membebani dan merupakan suatu ancaman bagi kesejahteraannya.
Menurut Lazarus & Folkman (1986) stres memiliki memiliki tiga bentuk
yaitu:
1. Stimulus, yaitu stres merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang
menimbulkan stres atau disebut juga dengan stressor.
2. Respon, yaitu stres yang merupakan suatu respon atau reaksi individu yang
muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon yang
muncul dapat secara psikologis, seperti: jantung berdebar, gemetar, pusing,
serta respon psikologis seperti: takut, cemas, sulit berkonsentrasi, dan mudah
3. Proses, yaitu stres digambarkan sebagai suatu proses dimana individu secara
aktif dapat mempengaruhi dampak stres melalui strategi tingkah laku, kognisi
maupun afeksi.
Rice (2002) mengatakan bahwa stres adalah suatu kejadian atau stimulus
lingkungan yang menyebabkan individu merasa tegang. Atkinson (2000)
mengemukakan bahwa stres mengacu pada peristiwa yang dirasakan
membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang. Situasi ini disebut
sebagai penyebab stres dan reaksi individu terhadap situasi stres ini sebagai
respon stres. Berdasarkan berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
stres merupakan suatu keadaan yang menekan diri individu. Stres merupakan
mekanisme yang kompleks dan menghasilkan respon yang saling terkait baik
fisiologis, psikologis, maupun perilaku pada individu yang mengalaminya,
dimana mekanisme tersebut bersifat individual yang sifatnya berbeda antara
individu yang satu dengan individu yang lain
2.1.1. Penyebab Stres atau Stressor
Peristiwa atau keadaan yang menantang secara fisik atau psikologis disebut
juga dengan stressor. (Sarafino, 2008) Menurut Lazarus & Folkman (dalam
Morgan, 1987) kondisi fisik lingkungan dan sosial yang merupakan penyebab dari
kondisi stres disebut dengan stressor. Stressor adalah faktor-faktor dalam
kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respon stres. Stressor dapat
berasal dari berbagai sumber, baik dari kondisi fisik, psikologis, maupun sosial
lingkungan luar lainnya. Istilah stressor diperkenalkan pertama kali oleh Selye
(dalam Rice, 2002). Menurut Lazarus & Folkman (1986) stressor dapat berwujud
atau berbentuk fisik (seperti polusi udara) dan dapat juga berkaitan dengan
lingkungan sosial (seperti interaksi sosial). Pikiran dan perasaan individu sendiri
yang dianggap sebagai suatu ancaman baik yang nyata maupun imajinasi dapat
juga menjadi stressor.
Menurut Lazarus & Cohen (1977), tiga tipe kejadian yang dapat
menyebabkan stres yaitu:
a. Daily hassles yaitu kejadian kecil yang terjadi berulang-ulang setiap hari
seperti masalah kerja di kantor, sekolah dan sebagainya.
b. Personal stressor yaitu ancaman atau gangguan yang lebih kuat atau
kehilangan besar terhadap sesuatu yang terjadi pada level individual seperti
kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan dan
masalah pribadi lainnya.
c. Ditambahkan Freese Gibson (dalam Rachmaningrum, 1999) umur adalah
salah satu faktor penting yang menjadi penyebab stres, semakin bertambah
umur seseorang, semakin mudah mengalami stres. Hal ini antara lain
disebabkan oleh faktor fisiologis yang telah mengalami kemunduran dalam
berbagai kemampuan seperti kemampuan visual, berpikir, mengingat dan
mendengar. Pengalaman kerja juga mempengaruhi munculnya stres kerja.
Individu yang memiliki pengalaman kerja lebih lama, cenderung lebih rentan
terhadap tekanan tekanan dalam pekerjaan, daripada individu dengan sedikit
masih ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat stres, yaitu
kondisi fisik, ada tidaknya dukungan sosial, harga diri, gaya hidup dan juga
tipe kepribadian tertentu (Dipboye, Gibsin, Riggio dalam Rachmaningrum,
1999).
Appraisal: Penilaian terhadap suatu keadaan yang dapat menyebabkan stres
disebut stress appraisals. Menilai suatu keadaan yang dapat mengakibatkan
stress tergantung dari 2 faktor, yaitu faktor yang berhubungan dengan orangnya
(Personal factors) dan faktor yang berhubungan dengan situasinya. Personal
factors didalamnya termasuk intelektual, motivasi, dan personality
characteristics. Sedangkan faktor situasi yang ,mempengaruhi stress appraisals,
yaitu:
a. Kejadian yang melibatkan tuntutan yang sangat tinggi dan mendesak sehingga
menyebabkan ketidaknyamanan
b. Life transitions, dimana kehidupan mempunyai banyak kejadian penting yang
menandakan berlalunya perubahan dari kondisi atau fase yang satu ke yang
lain, dan menghasilkan perubahan substansial dan tuntutan yang baru dalam
kehidupan kita.
c. Timing juga berpengaruh terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan kita,
dimana apabila kita sudah merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan
kita dan timing-nya meleset dari rencana semula, juga dapat menimbulkan
stres.
d. Ambiguity, yaitu ketidakjelasan akan situasi yang terjadi
f. Controllability, yaitu apakah seseorang mempunyai kemampuan untuk
merubah atau menghilangkan stressor. Seseorang cenderung menilai suatu
situasi yang tidak terkontrol sebagai suatu keadaan yang lebih stressful,
daripada situasi yang terkontrol. Ancaman merupakan konsep kunci dalam
memahami stress. Lazarus (1986) mengungkapkan bahwa individu yang tidak
akan merasakan suatu kejadian sebagai suatu gangguan bila stressor tersebut
diinterpretasikan sebagai hal yang wajar. Ancaman adalah suatu penilaian
subjektif dari pengaruh negatif yang potensial dari stressor. Transactions yang
mengarah pada kondisi stres umumnya melibatkan proses assesment yang
disebut sebagai cognitive appraisals (Lazarus & Folkman, 1986). Cognitive
appraisals adalah suatu proses mental, dimana ada dua factor yang dinilai oleh
seseorang: (1) apakah sebuah tuntutan mengancam kesejahteraannya dan (2)
resources yang tersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Lazarus
(1986) ada dua macam penilaian yang dilakukan individu untuk menilai
apakah suatu kejadian yang dapat atau tidak menimbulkan stress bagi
individu, yaitu:
a) Primary appraisals yaitu penilaian pada waktu kita mendeteksi suatu
kejadian yang potensial untuk menyebabkan stress. Peristiwa yang
diterima sebagai keadaan stress selanjutnya akan dinilai menjadi 3
akibat yaitu harmloss (tidak berbahaya), threat (ancaman) dan
challenge (tantangan)
b) Secondary appraisals mengarah pada resources yang tersedia pada diri
2.1.2. Reaksi terhadap Stres
a. Aspek Fisiologis Walter Canon (dalam sarafino, 1994) memberikan deskripsi
mengenai bagaiman reaksi tubuh terhadap suatu peristiwa yang mengancam.
Ia menyebutkan reaksi tersebut sebagai fight-or-fight response karena respon
fisiologis mempersiapkan individu untuk menghadapi atau menghindari
situasi yang mengancam tersebut. Fight-or-fight response menyebabkan
individu dapat berespon dengan cepat terhadap situasi yang mengancam. Akan
tetapi bila arousal yang tinggi terus menerus muncul dapat membahayakan
kesehatan individu. Selye (dalam Sarafino, 1994) mempelajari akibat yang
diperoleh bila stressor terus menerus muncul. Ia mengembangkan istilah
General Adaptation Syndrome (GAS) yang terdiri atas rangkaian tahapan
reaksi fisiologis terhadap stressor yaitu:
1. Fase reaksi yang mengejutkan ( alarm reaction ) Pada fase ini individu
secara fisiologis merasakan adanya ketidakberesan seperti jantungnya
berdegup, keluar keringat dingin, muka pucat, leher tegang, nadi
bergerak cepat dan sebagainya. Fase ini merupakan pertanda awal
orang terkena stres.
2. Fase perlawanan (Stage of Resistence ) Pada fase ini tubuh membuat
mekanisme perlawanan pada stres, sebab pada tingkat tertentu, stres
akan membahayakan. Tubuh dapat mengalami disfungsi, bila stres
dibiarkan berlarut-larut. Selama masa perlawanan tersebut, tubuh harus
cukup tersuplai oleh gizi yang seimbang, karena tubuh sedang
3. Fase keletihan ( Stage of Exhaustion ) Fase disaat orang sudah tak
mampu lagi melakukan perlawanan. Akibat yang parah bila seseorang
sampai pada fase ini adalah penyakit yang dapat menyerang bagian –
bagian tubuh yang lemah.
b. Aspek psikologis Reaksi psikologis terhadap stressor meliputi:
1. Kognisi Cohen menyatakan bahwa stres dapat melemahkan ingatan dan
perhatian dalam aktifitas kognitif.
2. Emosi cenderung terkait stres.individu sering menggunakan keadaan
emosionalnya untuk mengevaluasi stres dan pengalaman emosional
(Maslach, Schachter & Singer, dalam Sarafino, 1994). Reaksi emosional
terhadap stres yaitu rasa takut, phobia, kecemasan, depresi, perasaan
sedih dan marah.
3. Perilaku sosial stres dapat mengubah perilaku individu terhadap orang
lain. Individu dapat berperilaku menjadi positif dan negatif (dalam
Sarafino, 1994). Stres yang diikuti dengan rasa marah menyebabkan
perilaku sosial negatif cenderung meningkat sehingga dapat
menimbulkan perilaku agresif (Donnerstein & Wilson, dalam Sarafino,
1994).
Morris (1998) mengklasifikasikan stressor ke dalam lima kategori, yaitu:
1. Frustasi (Frustration) terjadi ketika kebutuhan pribadi terhalangi dan
seseorang gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. frustrasi dapat
terjadi sebagai akibat dari keterlambatan, kegagalan, kehilangan, kurangnya
2. Konflik (Conflicts), jenis sumber stres yang kedua ini hadir ketika
pengalaman seseorang dihadapi oleh dua atau lebih motif secara bersamaan.
Morris (1998) mengidentifikasi empat jenis konflik yaitu,:
approach-approach, avoidence-avoidence, approach-avoidence, dan multiple
approach-avoidance conflict.
3. Tekanan (Pressure), jenis dari sumber stress yang ketiga yang diakui oleh
Morris, tekanan didefinisikan sebagai stimulus yang menempatkan individu
dalam posisi untuk mempercepat, meningkatkan kinerjanya, atau mengubah
perilakunya.
4. Mengidentifikasi perubahan (Changes), tipe sumber stres yang keempat ini
seperti halnya yang ada di seluruh tahap kehidupan, tetapi tidak dianggap
penuh tekanan sampai mengganggu kehidupan seseorang baik secara positif
maupun negative
5. Self-Imposed merupakan sumber stres yang berasal dalam sistem keyakinan
pribadi pada seseorang, bukan dari lingkungan. Ini akan dialami oleh
seseorang ketika ada tidaknya stres eksternal yang nyata. Morris (1998) juga
mengidentifikasikan empat reaksi terhadap stres:
1) Reaksi dari fisiologis terhadap stres menekankan hubungan antara
pikiran dan fisik.
2) Reaksi dari emosional yang diamati dalam reaksi emosional terhadap
stres ini adalah melalui emosi seperti rasa ketakutan, kecemasan, rasa
3) Reaksi dari kognitif mengacu pada pengalaman individu terhadap stres
dan penilaian kognitif yang terjadi dengan penilaiannya mengenai
peristiwa stres dan kemudian apa strategi koping yang mungkin paling
tepat untuk mengelola stres.
4) Reaksi dari perilaku yang berkaitan dengan reaksi emosional seseorang
terhadap stres yang dapat memberikan reaksi menangis, menjadi kasar
kepada orang lain atau diri sendiri dan, penggunaan mekanisme
pertahanan seperti rasionalisasi.
2.1.3. Sumber-sumber Stres
Sumber stres dapat berubah seiring dengan berkembangnya individu, tetapi
kondisi stres dapat terjadi setiap saat selama hidup berlangsung. Menurut
Sarafino (1994) sumber datangnya stres ada tiga yaitu:
1) Diri individu
Hal ini berkaitan dengan adanya konflik. Menurut Miller dalam Sarafino
(2008), pendorong dan penarik dari konflik menghasilkan dua kecenderungan
yang berkebalikan, yaitu approach dan avoidance. Kecenderungan ini
menghasilkan tipe dasar konflik (Sarafino, 1994), yaitu :
a. Approach-approach Conflict
Muncul ketika kita tertarik terhadap dua tujuan yang sama-sama baik.
Contohnya, individu yang mencoba untuk menurunkan berat badan untuk
meningkatkan kesehatan maupun untuk penampilan, namun konflik sering terjadi
b. Avoidance-avoidance Conflict
Muncul ketika kita dihadapkan pada satu pilihan antara dua situasi yang tidak
menyenangkan. Contohnya, pasien dengan penyakit serius mungkin akan
dihadapkan dengan pilihan antara dua perlakuan yang akan mengontrol atau
menyembuhkan penyakit, namun memiliki efek samping yang sangat tidak
diinginkan. Sarafino (2008) menjelaskan bahwa orang-orang dalam menghindari
konflik ini biasanya mencoba untuk menunda atau menghindar dari keputusan
tersebut. Oleh karena itu, biasanya avoidance-avoidance conflict ini sangat sulit
untuk diselesaikan.
c. Approach-avoidance Conflict
Muncul ketika kita melihat kondisi yang menarik dan tidak menarik dalam
satu tujuan atau situasi. Contohnya, seseorang yang merokok dan ingin berhenti,
namun mereka mungkin terbelah antara ingin meningkatkan kesehatan dan ingin
menghindari kenaikan berat badan serta keinginan mereka untuk percaya terjadi
jika mereka ingin berhenti.
2) Keluarga
Sarafino (2008) menjelaskan bahwa perilaku, kebutuhan, dan kepribadian dari
setiap anggota keluarga berdampak pada interaksi dengan orang-orang dari
anggota lain dalam keluarga yang kadang-kadang menghasilkan stres. Menurut
Sarafino (2008) faktor dari keluarga yang cenderung memungkinkan munculnya
stres adalah hadirnya anggota baru, perceraian dan adanya keluarga yang sakit,
3) Komunitas dan Masyarakat
Kontak dengan orang di luar keluarga menyediakan banyak sumber stres.
Misalnya, pengalaman anak di sekolah dan persaingan. Adanya
pengalaman-pengalaman seputar dengan pekerjaan dan juga dengan lingkungan dapat
menyebabkan seseorang menjadi stres. (Sarafino, 1994)
2.1.4. Gejala Stres
Stres dapat berpengaruh pada kesehatan dengan dua cara. Pertama,
perubahan yang diakibatkan oleh stres secara langsung mempengaruhi fisik sistem
tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kedua, secara tidak langsung stres
mempengaruhi perilaku individu sehinggga menyebabkan timbulnya penyakit
atau memperburuk kondisi yang sudah ada (Safarino, 1994). Kondisi dari stres
memiliki dua aspek : fisik/biologis (melibatkan materi atau tantangan yang
menggunakan fisik) dan psikologis (melibatkan bagaimana individu memandang
situasi dalam hidup mereka) dalam Sarafino, 1994.
a) Aspek Biologis
Ada beberapa gejala fisik yang dirasakan ketika seseorang sedang mengalami
stres, diantaranya adalah sakit kepala yang berlebihan, tidur menjadi tidak
nyenyak, gangguan pencernaan, hilangnya nafsu makan, gangguan kulit, dan
produksi keringat yang berlebihan di seluruh tubuh (Sarafino, 1994).
Ada 3 gejala psikologis yang dirasakan ketika seseorang sedang mengalami
stres. Ketika gejala tersebut adalah gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala
tingkah laku (Sarafino, 1994):
1. Gejala kognisi
Gangguan daya ingat (menurunnya daya ingat, mudah lupa dengan suatu hal),
perhatian dan konsentrasi yang berkurang sehingga seseorang tidak fokus dalam
melakukan suatu hal, merupakan gejala-gejala yang muncul pada aspek gejala
kognisi
2. Gejala emosi
Mudah marah, kecemasan yang berlebihan terhadap segala sesuatu, merasa
sedih dan depresi merupakan gejala-gejala yang muncul pada aspek gejala emosi
3. Gejala tingkah laku
Tingkah laku negatif yang muncul ketika seseorang mengalami stres pada
aspek gejala tingkah laku adalah mudah menyalahkan orang lain dan mencari
kesalahan orang lain, suka melanggar norma karena dia tidak bisa mengontrol
perbuatannya dan bersikap tak acuh pada lingkungan, dan suka melakukan
penundaan pekerjaan.
2.1.5. Penilaian Kognitif (Cognitive Appraisal)
Setiap orang memiliki perbedaan dalam menghadapi stres. Menurut Lazarus
& Folkman (1984: 31) penilaian kognitif (cognitive appraisal) yaitu merupakan
yang spesifik atau serangkaian transaksi antara individu dengan lingkungan yang
menimbulkan stres. Selain itu kognitif dapat diartikan sebagai suatu proses
pengkategorian terhadap stimulus atau situasi yang dihadapi, dengan perhitungan
makna serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan seseorang. Penilaian kognitif
dikemukakan oleh Lazarus dan Folkman (1984: 31) terdiri dari penilaian primer
(primary appraisal) dan penilaian sekunder (secondary appraisal). Kedua jenis
penilaian ini tidak dapat dipandang sebagai proses yang terpisah karena keduanya
saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Penilaian primer dan
sekunder berinteraksi satu sama lain membentuk derajat stres serta kualitas atau
kekuatan reaksi emosional sehingga akan membuat situasi semakin kompleks.
1. Penilaian Primer (Primary Appraisal)
Proses ini merupakan suatu proses mental yang berkaitan dengan evaluasi
terhadap suatu situasi. Proses ini terjadi untuk menentukan apakah suatu stimulus
atau situasi yang dihadapi berada dalam derajat penghayatan tertentu.
2. Penilaian Sekunder (Secondary Appraisal)
Penilaian sekunder adalah keputusan tentang apa yang mungkin dapat
dilakukan meliputi evaluasi tentang pilihan strategi pengelolaan yang sesuai dan
evaluatif tentang konsekuensi yang akan muncul dalam konteks tuntutan dan
hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal.
Penilaian kembali menunjukkan pada perubahan penilaian yang terjadi karena
didasari oleh masuknya informasi baru, baik informasi yang berasal dari
lingkungan maupun informasi yang berasal dari reaksi siswa. Proses penilaian
kembali merubah bentuk penilaian yang didasarkan pada informasi baru dari
lingkungan atau diperoleh siswa berdasarkan pengalamannya. Beberapa hal yang
mendasari pentingnya konsep penilaian kognitif menurut Lazarus dan Folkman
(1986: 55) sebagai berikut:
a) Faktor Personal
Ada dua karakteristik individu yang berpengaruh atau menentukan suatu
penilaian kognitif yaitu komitmen (commitment) dan keyakinan (belief).
b) Faktor Situasional Faktor situasional
Faktor situasional yang mempengaruhi penilaian kognitif terbagi menjadi dua
faktor yaitu faktor situasional yang potensial dan temporal (Lazarus & Folkman,
1986: 83).
Stress adalah suatu kejadian atau rangsangan (stimulus) dari luar (stressor)
yang menyebabkan individu akan merasa tegang. Gejala stress dapat berupa aspek
biologis yaitu sakit kepala yang berlebihan, tidur menjadi tidak nyenyak,
gangguan pencernaan, hilangnya nafsu makan, gangguan kulit dan produksi
keringat yang berlebihan serta aspek psikologis yaitu gejala kognisi, gejala emosi
dan gejala tingkah laku..
Ahli saraf Walter Cannon menciptakan istilah homeostasis untuk lebih
menentukan keseimbangan dinamis yang telah dijelaskan Bernard. Dia
eksperimen, dia menunjukkan respons "fight or flight" yang timbul pada manusia
dan binatang ketika terancam. Selanjutnya, Cannon juga mengatakan bahawa
reaksi ini juga disebabkan oleh pelepasan neurotransmitters (neurotransmiter
adalah bahan kimia dalam tubuh yang membawa pesan ke dan dari saraf) dari
kelenjar adrenal, medula. Medula adrenal mengeluarkan dua jenis
neurotransmiter, yaitu epinefrin atau disebut sebagai adrenalin dan norepinefrin
(noradrenalin), dalam respon terhadap stres. Pelepasan neurotransmiter
menyebabkan efek fisiologis terlihat pada respon "fight or flight", misalnya,
denyut jantung yang cepat, peningkatan kewaspadaan, dan lain-lain. (Nasution I.
K., 2007).
Hans Selye, mengatakan bahwa selain daripada respons tubuh, semasa stres
kelenjar pituitary juga memainkan peranan. Dia menggambarkan kontrol oleh
kelenjar sekresi hormon (misalnya, kortisol) yang penting dalam respon fisiologis
terhadap stres dengan bagian lain dari kelenjar adrenal yang dikenal sebagai
korteks. Selain itu, Selye sebenarnya memperkenalkan istilah tegangan dari fisika
dan rekayasa dan didefinisikan sebagai "respons bersama yang terjadi di setiap
bagian tubuh, fisik atau psikologis." (Nasution I. K., 2007). Dalam
eksperimennya, Selye menginduksi stres pada tikus dalam berbagai cara. Pada
tikus yang terkena tegangan konstan, berlakunya pembesaran kelenjar adrenal,
ulkus gastrointestinal dan atrofi sistem imun. (Nasution I. K., 2007)
Stres menyebabkan kelenjar hipotalamus melepaskan hormon adrenalin dan
kortisol melalui kelenjar adrenal. Hormon-hormon ini menyebabkan reaksi
yang penuh tekanan dan tantangan. Reaksi ini meliputi peningkatan denyut
jantung, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan produksi glukosa untuk
meningkatkan pasokan energi serta menonaktifkan sementara sistem kekebalan
tubuh dan sistem pencernaan. Ini yang mungkin terjadi pada kelompok kontrol
apabila tidak penderita tidak diberikan psikoterapi apapun selama dirawat.
Tabel 2.1. Tahapan Stres dan Gejala
Dr. Robert J. Van Amberg (1979, cit. Hawari, 2001) membagi stres atas enam tahap. yaitu :
NO TAHAPAN STRESS TANDA DAN GEJALA
1 Stres tahap – I
Merupakan tahapan stres yang paling ringan
semangat kerja yang berlebihan
(overacting)
penglihatan "tajam" tidak sebagaimana biasanya
merasa senang dengan suatu pekerjaan dan semakin semangat
mengerjakannya, namun tanpa disadari
cadangan energi semakin menipis bahkan dihabiskan (all out)
rasa gugup yang berlebihan
2 Stres tahap – II
Pada tahap ini dampak stres yang semula menyenangkan mulai menghilang dan mulai timbul keluhan-keluhan karena kekurangan energi yang disebabkan waktu istirahat yang kurang.
merasa letih saat bangun pagi dimana
seharusnya pada saat bangun pagi orang merasa segar.
merasa lelah sesudah makan siang
lekas capai menjelang sore hari
jantung berdebar-debar
sering mengalami keluhan pada lambung
atau perut (bowel discomfort) otot punggung dan tengkuk terasa tegang
tidak bisa santai
3 Stres tahap – III
Pada tahap ini keluhan yang terjadi semakin nyata dan mengganggu, hal ini diakibatkan karena keluhan yang terjadi pada stres tahap II diabaikan dan orang tetap memaksakan dirinya untuk bekerja.
gangguan pada lambung dan usus
(gastritis dan diare)
ketegangan otot semakin terasa
ketegangan emosional dan rasa tidak
tenang semakin meningkat
gangguan tidur (insomnia)
koordinasi tubuh terganggu (badan terasa
beban stres serta memberi kesempatan tubuh untuk istin menambah suplai energi yang sudah mengalami defisit.
4 Stres tahap – IV
Bila individu yang mengalami stres tahap III dinyatakan sehat oleh dokter yang memeriksanya sehingga individu tersebut terus memaksakan dirinya bekerja tanpa istirahat maka akan timbul gejala stres tahap IV.
Terasa sulit untuk bertahan sepanjang
hari
Aktivitas pekerjaan yang semula
terasa menyenangkan dan mudah diselesaikan menjadi terasa membosankan dan lebih sulit
Yang semula tanggap terhadap situasi
menjadi kehilangan kemampuan untuk merespon secara ade kuat
Tidak mampu melaksanakan kegiatan
rutin sehari-hari
Gangguan pola tidur disertai mimpi yang
menegangkan
Seringkali menolak ajakan karena tidak
ada semangat dan gairah
Daya konsentrasi dan daya ingat
menurun
Timbul rasa ketakutan dan kecemasan
yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya
5 Stres tahap – V
Bila keadaan stres terus berlanjut maka individu akan mengalami stres tahap V
Kelelahan fisik dan mental semakin
mendalam
Tidak mampu menyelesaikan pekerjaan
sehari-hari yang walaupun ringan dan sederhana
Gangguan sistem pencemaan semakin
parah (gastro-intestinal disorder)
Timbul perasaan ketakutan dan
kecemasan yang semakin meningkat mudah bingung dan panic
6 Stres tahap – VI
Merupakan tahap klimaks dimana individu mengalami panic attack dan perasaan takut mati. Tidak jarang individu yang mengalami stres tahap ini seringkali dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) meskipun pada akhirnya individu tersebut dipulangkan kembali karena tidak ditemukan kelainan fisik dan organ tubuh.
Jantung berdebar sangat keras
Susah bernapas (sesak dan
megap-megap)
Sekujur badan terasa gemetar, dingin,
dan keringat bercucuran
Tidak ada tenaga untuk melakukan
hal-hal yang ringan sekalipun
Pingsan dan kolaps
Menurut Asosiasi Psikologi Amerika adalah suatu penggunaan riwayat hidup
baik melalui tulisan, ucapan/lisan ataupun keduanya yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan. Reminiscence therapy pertama
kali diperkenalkan oleh seorang psikiatrik ternama yaitu Robert Butler pada tahun
1960. Reminiscence therapy digunakan dengan tepat seperti menggunakan photo,
music atau benda-benda yang sangat familiar pada masa lalunya, untuk
mendorong pasien untuk berbicara mengenai memori mereka sebelumnya. Terapi
ini lebih disarankan kepada orang dewasa yang mempunyai masalah mood atau
masalah memori atau kepada orang yang membutuhkan kesulitan seseorang dalam
kesiapan memasuki usia tua.
Menurut Bluck dan Levine (1998, dalam Collings, 2006) reminiscence
adalah proses yang dikehendaki atau tidak dikehendaki untuk mengumpulkan
kembali memori-memori seseorang pada masa lalu. Memori tersebut dapat
merupakan suatu peristiwa yang mungkin tidak bisa dilupakan atau peristiwa yang
sudah terlupakan yang dialami langsung oleh individu. Kemudian memori
tersebut dapat sebagai kumpulan pengalaman pribadi atau “disharingkan” dengan
orang lain. Johnson (2005) mendefenisikan reminiscence adalah proses mengingat
kembali kejadian dan pengalaman masa lalu, dan telah dibentuk sebagai suatu
topik utama baik dalam teori maupun aplikasi pada psikogerontologi. Menurut
Fontaine dan Fletcher (2003) reminiscence atau kenangan adalah suatu
kemampuan pada lansia yang dipandu untuk mengingat memori masa lalu dan
“disharingkan” (disampaikan) memori tersebut dengan keluarga, kelompok atau
adalah suatu terapi pada orang yang didorong (dimotivasi) untuk mendiskusikan
kejadian-kejadian masa lalu untuk mengidentifikasi keterampilan penyelesaian
masa lalu yang telah dilakukan mereka pada masa lalu. Berdasarkan beberapa
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terapi kelompok reminiscence
adalah suatu terapi yang dilakukan pada penderita secara berkelompok dengan
cara memotivasi penderita untuk mengingat kembali kejadian dan pengalaman
masa lalu serta kemampuan penyelesaian masalahnya kemudian disampaikan
dengan keluarga, teman, kelompok atau staf.
Therapy reminiscence adalah suatu terapi yang ditujukan untuk memulihkan
depresi perasaan stress pada pasien. Dalam kegiatan terapi ini, terapis akan
membantu pasien yang mengalami stress pada gagal jantung untuk mengingat
kembali aspek positif dan hal-hal yang berarti bagi penderita pada masa lalunya.
Kemudian terapis juga membantu pasien untuk mengintegrasikan hal positif
tersebut dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini. Proses ini diharapkan dapat
membantu penderita untuk menilai kehidupan yang telah dilaluinya sehingga
penderita dapat merasakan kepuasan atas kehidupannya tersebut. Therapy
reminiscence merupakan hasil langsung dari hipotesis teori life review (Butler,
1963). Terapi ini pada dasarnya menekankan individu untuk merefleksikan
kehidupan mereka kembali atau mengulang kembali memori masa lalu. Melalui
refleksi ini individu untuk menyelesaikan konflik, mengatasi pengalaman masa
lalu yang menyakitkan sehingga individu tersebut mampu menyelesaikan masalah
yang dihadapi saat ini. Therapy reminiscence sangat membantu untuk pribadi
Reminiscence melibatkan pertukaran memori antara orang tua dengan orang
muda, teman dengan keluarga, caregivers dengan professional, melalui informasi,
kebijaksanaan dan keterampilan. Pada intinya memberikan suatu nilai,
kepentingan, kebersamaan, kekuatan dan damai kepada penderita Alzheimer’s.
Aktivitas therapy reminiscence biasanya digunakan dalam kehidupan kita
sehari-hari. Therapy reminiscence ini kita gunakan untuk mengatasi stress seperti dalam
situasi berduka. Terapi ini membantu mengurangi gambaran diri yang buruk,
menciptakan perasaan intim serta memberikan arti yang special ketika berinteraksi
dengan orang lain.
Media yang dapat digunakan dalam therapy reminiscence adalah :
1. Secara visual; foto, lukisan yang mengingatkan kejadian masa lalu yang
menyenangkan
2. Musik; menggunakan lagu-lagu yang familiar dari radio, CD, atau
menciptakan musik menggunakan berbagai macam alat musik
3. Melalui indera pengecapan dan penghiduan; menggunakan parfum, makanan
4. Melalui indera peraba; memegang objek tertentu, merasakan tekstur, melukis
dan puisi.
Tipe terapi dan aktivitas reminiscence dapat digunakan oleh individu, kelompok
dan keluarga. Kategori therapy reminiscence dibagi menjadi 3 kategori utama
yaitu:
1. Simple reminiscence.
Terapi ini merupakan refleksi informasi masa lalu dengan cara yang
2. Evaluative reminiscence adalah evaluasi masa lalu dan digunakan sebagai
pendekatan pemecahan konflik
3. Offensive-defensive reminiscence merupakan kegiatan pengulangan informasi
yang tidak menyenangkan dan meningkatkan stress. Keluarga dan teman
terdekat dapat memberikan informasi dan subjek penting yang menyedihkan
bagi lanjut usia sehingga membutuhkan dukungan yang penuh dari perawat.
Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dinyatakan bahwa reminiscence
therapy dapat memberikan kemudahan untuk memperbaiki perasaan depresi dan
perasaan kesepian dan meningkatkan kenyamanan psikologi. Penelitian juga
menyokong pandangan bahwa reminiscence therapy termasuk riwayat pekerjaan
dapat meningkatkan hubungan antara orang yang mengalami dementia dan karir
mereka dengan cara memberikan keuntungan pada keduanya. Keuntungan lain
dilaporkan termasuk peningkatan kesempatan untuk memberikan perawatan
secara personal dan individual dan membantu individu untuk bergerak antara
perbedaan lingkungan perawatan seperti perawatan dirumah atau diantara
perawatan dirumah.
Reminiscence therapy dapat diselenggarakan secara formal atau informal
secara individu, keluarga atau group. Reminiscence therapy menyajikan
perbedaan fungsi psikologi termasuk taxonomy yang diperkenalkan oleh Webster.
Skala fungsi reminiscence yang dibuat Webster’s termasuk delapan alasan kenapa
orang mengingat : penurunan rasa bosan, peningkatan kebencian, persiapan
kematian, percakapan, identitas, mempertahankan keintiman, pemecahan masalah,
reminiscence untuk meningkatkan efek dan kemampuan koping, walaupun
keefektifan terapi ini masih diperdebatkan.
Therapy reminiscence merupakan salah satu terapi modalitas yang dapat
menurunkan beberapa gangguan kesehatan yang dialami lansia, antara lain lupa
ingatan, dimensia, depresi dan kecemasan (Winslow, 2009). Menurut Coaten
(2001) therapy reminiscence atau mengenang suatu kejadian di masa lalu dapat
memberikan rasa nyaman dan tenang tentang apa yang telah terjadi sebelumnya di
masa lalu. Pasien diharapkan dapat terlibat aktif dalam berbagi cerita masa lalu
pada suatu kelompok. Selain itu, therapy reminiscence dapat meningkatkan
interaksi sosial penderita dengan orang lain yang menjadi lawan bicaranya.
Reminiscence therapy terdiri dari berbicara, komunikasi dan inklusi pada
seorang pasien dengan pasangannya atau group. Terapi ini berguna dalam
hubungannya antara 2 (dua) orang atau lebih untuk menstimulus memori manusia
yang mempunyai dementia dengan menggunakan isi seperti gambar-gambar dan
hal-hal fisik sebagai katalisator dalam merangsang memori. Hal tersebut akan
mengirimkan sinyal kepusat informasi, pada pusat perawatan dirumah. Satu
keuntungan utama dari reminiscence therapy adalah bahwa ini adalah merupakan
proses yang informal yang memerlukan latihan yang panjang maupun kualifikasi
untuk mengaturnya. Hal ini dapat digunakan pada hal dasar dan dapat juga
dikombinasikan dengan terapi yang lain secara personal ataupun sesi grup.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan reminiscence therapy juga
menciptakan ikatan yang lebih kuat antara karir dan tempat tinggal dengan
memahami tentang individu dengan latar belakang demensia. Ini memberikan
transisi yang lebih lembut dan lebih cepat dalam menseting perawatan dirumah
dan dapat juga menolong provider dalam memberikan perawatan dirumah dengan
pendekatan langsung pada pasien.
Reminiscence menunjukkan memori panjang pada masa lampau. Hal ini
sangat familiar pada kita dan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan yang lainnya.
Untuk orang dengan penyakit alzheimer akan memberi harapan untuk melakukan
reminiscence yang sangat bermanfaat pada diri mereka sendiri dan kemampuan
interpersonal. Reminiscence mempengaruhi perubahan memori pada orang tua dan
muda, teman dan keluarga, dengan caregiver dan profesional, menyampaikan
informasi, kebijaksanaan dan keahlian. Ini adalah suatu hal yang memberikan
orang dengan penyakit alzheimer akan mempunyai nilai, kepentingan, kasih
sayang, kekuatan dan kedamaian.
Kegiatan reminiscence therapy digunakan secara berkesinambungan pada
kehidupan sehari-hari pada waktu stress seperti saat berkabung, ini juga dapat
menurunkan kejadian kecelakaan pada gambaran diri dan dapat mengkreasikan
perasaan yang intim dan memberikan arti spesial untuk bersosialisasi dengan
orang lain. Inti kegiatan therapy reminiscence yang berfokus pada eksplorasi
keberhasilan yang pernah dicapai penderita akan sangat mendukung pemulihan
stress pada penderita gagal jantung. Dalam proses kegiatan terapi ini tentunya
terapi dapat memotivasi dan memfasilitasi penderita untuk mengingat kembali
pengalaman keberhasilan atau suka cita yang pernah dialami penderita sehingga
berlangsung. Perasaan bahagia dan bangga ini kemudian diintegrasikan dengan
kemampuan dan keberhasilan penderita saat ini. Dengan demikian melalui
kegiatan therapy reminiscence ini penderita masih dapat memotivasi dirinya untuk
menimbulkan perasaan bahagia dan bangga dengan diri sendiri sehingga
perasaan-perasaan negatif dan kesedihan yang dirasakan dapat menjadi berkurang atau
bahkan hilang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chiang, et al., (2009) bahwa
therapy reminiscence dapat menurunkan stress dan perasaan-perasaan negatif
pada penderita gagal jantung. Frazer, Christensen dan Griffiths (2005) dalam
penelitian pada 23 orang lansia menyimpulkan therapy reminiscene efektif untuk
menurunkan depresi. Timbulnya perasaan senang dan bangga merupakan upaya
untuk meminimalkan tanda dan gejala stress dan depresi. Bohlmeijer (2003;
Haight & Burnside, 1993, dalam Ebersole, et al., 2005) menyatakan bahwa
therapy reminiscence dapat menjadi suatu terapi yang efektif untuk gejala stress
dan depresi. Menurut pernyataan Stuart (2009) bahwa therapy reminiscence
digunakan untuk membantu individu mencapai perasaan integritasi, meningkatkan
harga diri dan menstimulasi individu untuk berpikir tentang dirinya sendiri dan
perawat mempunyai kesempatan untuk memfokuskan, memberikan refleksi dan
penguatan atas perasaan individu terhadap nilai dirinya sendiri. Pada therapy
reminiscence penderita mendapat kesempatan untuk menyampaikan kemampuan
positif yang telah dialaminya. Kemampuan positif tersebut dapat berkaitan dengan
kegiatan fisik seperti pengalaman bermain pada masa anak-anak, pengalaman
rekreasi pada masa remaja dan pengalaman pekerjaan pada masa dewasa. Topik