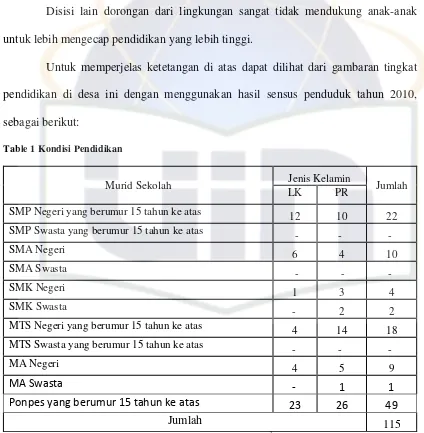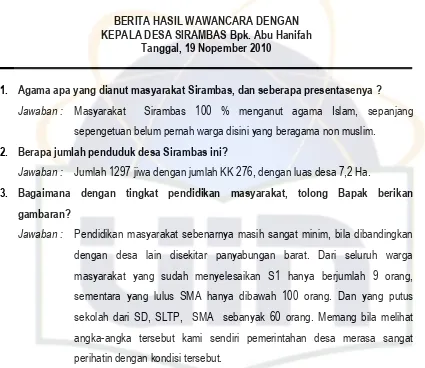(Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Sy)
Oleh :
MUHAMMAD SYARIF NIM:107044102053
Di bawah bimbingan
Dr. Azizah, MA NIP. 1963 0409 198902 2001
K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
(Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Sy)
LOGO
Oleh :
MUHAMMAD SYARIF NIM : 107044102053
K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 28 Januari 2011
Skripsi berjudul LARANGAN MELANGKAHI KAKAK DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Desa Sirambas Kecamatan Panyabugan Barat Mandailing Natal) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 Januari 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada program studi Ahwal al-Syahsiyyah.
Jakarta, 28 Januari 2011 Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM NIP: 1955 0505 198203 1012
PANITIA UJIAN
1. Ketua : Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA (..……….) NIP: 1950 0306 197603 1001
2. Sekretaris : Rosdiana, MA (…..…………...)
NIP: 1969 0610 200312 2001
3. Pembimbing : Dr. Azizah (……..………….)
NIP: 1963 0409 198902 2001
4. Penguji I : Dr. Hj. Mesraini, M.Ag (………..……….)
NIP: 1976 0213 200312 2001
5. Penguji II : Dra. Masykufah, M.Ag (…………..…….)
i
Puji syukur kehadirat-Nya, sebagai Dzat yang maha indah dan terpuji,
dimana seluruh pujian dijagad ini dipersembahkan untuk-Nya, takkan pernah terasa
cukup untuk mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih atas segala rahmat dan
cinta yang diberikan kepada hamba-Nya.
Salam sejahtera semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung,
Muhammad SAW yang menjadi panutan ummat Islam, yang selalu dinantikan
syafaatnya dihari pembalasan.
Tiada untaian kata yang pantas untuk disenandungkan, selain rasa syukur
yang tiada terhingga yang menunjukkan betapa ALLAH telah memberikan rasa kasih
sayang-Nya kepada Penulis dengan memberikan kekuatan fisik, psikis, dan ilmu
pengetahuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “LARANGAN
MELANGKAHI KAKAK DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING (Desa
Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal)”
Penulis sangat menyadari selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari
bantuan beberapa pihak, baik itu berupa sumbangan pemikiran maupun berupa
finansial, sehingga penulisan ini selesai. Dan penulis tidak dapat melukiskan dengan
untaian kata-kata, ungkapan apa yang pantas penulis haturkan kepada mereka.
ii Hidayatullah Jakarta.
2. Drs. H. A. Basiq Djalil S.H., M.A sebagai Ketua Program studi Ahwal
Al-Syahsiyyah, yang selama ini telah memberikan pelayanannya kepada penulis.
3. Dr. Azizah, MA, yang telah membimbing penulis selama melakukan
penulisan skripsi sampai dapat diselesaikan dengan hasil yang cukup
memuaskan.
4. Dr. Hj. Mesraini, M.Ag., dan Dra. Masykufah, M.Ag., yang telah menguji
penulis dalam ujian skripsi ini, dan telah memberikan saran, arahan dan
masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Rosdiana, MA, selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syahshiyyah,
terimakasih atas pelayanan yang sangat memuaskan dan bantuan yang tidak
terlupakan.
6. Bapak dan Ibu dosen yang penulis hormati, yang telah memberikan tenaga
dan pikirannya, untuk mendidik penulis agar kelak menjadi manusia yang
berguna di dunia dan di akhirat, semoga do’a dan didikannya menjadi berkah
dan dapat menuntun penulis untuk memasuki kehidupan yang lebih baik.
7. Pegawai Perpustakaan Utama serta Perpustakaan Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan
Daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang juga meberikan bantuan berupa
iii
penulis agar menjadi manusia yang berguna. Abanganda Muhammad Nuh
SH.I yang selama ini memberikan bantuan financial dan motivasi kepada
penulis agar menjadi orang yang sukses. Kakakku Siti Aisah S.Pd.I, dan
adik-adikku Ahmad Fauzi, Zainab, Muhammad Harmein, dan Ahmad Zulyadain
yang senantiasa mendoakan serta memberikan support kepada penulis.
9. Bapak Dr. Mulia P. Nasution (Sekjen Menteri Keuangan), Bapak Idris Ludfi
(DPR RI Fraksi PKS), yang telah membatu penulis secara financial, sehingga
penulis dapat menjalankan penelitian ini dengan lancar.
10.Teman-teman jurusan Peradilan Agama angkatan 2006, yang selalu menjadi
guru, teman berdiskusi dilokal, semoga apa yang kita cita-citakan dapat
terlaksana.
11.Bapak Ahmad Nizar, MA, Dr. Ibrahim, Anhar, MA, Khalidah Nasution, MA,
dan Kawan-kawan STAIN Padangsidimpuan (Kampus Pertama Saya), ada
Khairunnah Fauziah Ritonga, Pujiati, Ariadi Praja, Erwin Sah, Herman Soni,
Elida Hafni, Ratih, Nelvi, Wiratto, Sarkawi, dll.
12.Bapak Kepala Desa Sirambas (Abu Hanifah Nasution), Ustadz Malim
Sulaiman, Bapak Muhammad Amin (Tokoh Adat), Ibu Amaliah Nasution,
Kepala KUA Panyabungan Barat, Ketua Pengadilan Agama Mandailing
Natal, yang telah memberikan waktu dan pemikirannya buat penulis,
iv
Mahasiswa Sumatera Utara) Jakarta, ada Fadlika Himmah Sahputra Harahap,
Raidong Habibi Rambe, Zulhamdi Bakri Tanjung, Anda, Irsyadurrifai, dan
kawan-kawan LKBHMI, ada Ridho Akmal Nasution (direktur), aji, ubai,
awal, juga kawan-kawan HMI Cabang Mandailing Natal, ada Abdul Wahab,
Faisal, Ramli, serta sahabat lainnya yang tidak disebutkan namanya satu
persatu, yang akan selalu menjadi guru, teman satu ide dan satu perjuangan.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini,
penulis berdo’a semoga Allah SWT., senantiasa mencurahkan rahmat dan
hidayahnya. Harapan terakhir penulis skripsi ini bermanfaat buat pengembangan
ilmu pengetahuan.
Jakarta, 28 Januari 2011
v
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... v
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 7
D. Study Review ... 8
E. Metodologi Penelitian ... 9
F. Sistematika Penulisan ... 13
BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN A. Pengertian Perkawinan ... 13
B. Dasar Hukum Perkawinan ... 20
C. Rukun dan Syarat Perkawinan ... 24
D. Larangan Perkawinan ... 29
E. Tujuan Perkawinan ... 35
F. Hikmah Perkawinan ... 40
BAB III POTRET DESA SIRAMBAS A. Kondisi Geografis Desa Sirambas ... 43
B. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sirambas... 45
vi
A. Pengertian Perkawinan Melangkahi Kakak ... 63
B. Larangan Perkawinan Melangkahi Kakak Menurut:
1. Pandangan Masyarakat, Ulama dan Tokoh Adat
Mandailing ... 64
2. Pandangan Fiqh dan KHI ... 68
C. Analisis Penulis ... 72
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ... 76
B. Saran-saran ... 79
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Naluri seksual bukanlah kekurangan yang harus dihilangkan dari diri manusia,
namun ia adalah keniscayaan fitrah yang perlu diarahkan dengan cara dipraktekkan
dalam koridor Manhaj Ilahi, untuk mewujudkan ketenangan jiwa, serta menjauhkan
dari masalah dan penyakit. Islam tidak mengenal pengebirian naluri seksual, Islam
juga bukan pendukung seks bebas. Oleh karena itu dalam ajaran agama samawi,
masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat dijunjung
tinggi.1
Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut
adanya jalan keluar, menuntut adanya solusi yang jitu untuk mengatasinya. Bilamana
jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami
kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Maka perkawinan merupakan
jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan
memuaskan naluri seks ini.2
Sesuai dengan firman Allah dalam surah ar-Rum:
1
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 2
2
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (al-Rum: 21)
Dalam al-Hadist juga dijelaskan:
Artinya: “Rasulullah SAW bersabda:“Hai para pemuda! siapa saja kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekang) baginya”(HR. Muslim )3
Melalui perkawinan telah menempatkan manusia dalam koridor yang sangat
mulia dan menaikkan derajat manusia dari kehinaan hayawaniah. Bahkan hal ini
jugalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya,
seperti kambing, lembu, kerbau dan lainnya, makhluk Tuhan tersebut tidak
memerlukan adanya perkawinan, karena bagi mereka juga tidak ada rasa malu
sekalipun harus berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Makanya apalah bedanya
manusia yang melakukan hubungan dengan lawanan jenisnya tanpa melalui
pernikahan yang sah.
Disisi lain pernikahan bertujuan besar dan asasi sebagai sarana untuk
melanggengkan kelangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia,
sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai
cerminan yang menentukan terbentuknya sebuah masyarakat yang madani.
3
Dalam al-Qur’an dijelaskan:
Artinya: “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah ciptakan pasangan/istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu” (an-Nisa: 1)
Dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara
seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan
dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti
suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan
dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk
dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan
damai.4
Oleh karena itulah Islam dengan ajaran yang luhur memberikan perhatian
yang serius terhadap persoalan perkawinan. Islam menjelaskan dengan sangat detail
dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, apa yang seharusnya dilakukan seseorang apabila
ingin melangsungkan pernikahan.
Betapapun demikian, dalam praktek pelaksanaannya perkawinan tidak
selamanya lepas dari pengaruh kebudayaan di mana pernikahan itu dilaksanakan. Di
4
Mandailing Natal misalnya, walaupun daerah ini tergolong masyarakat yang sangat
religius dalam mengamalkan ajaran Islam, bahkan diberikan julukan serambi
Mekkahnya Sumatera Utara.5 Akan tetapi dalam praktek perkawinan masih saja
berbaur dengan adat istiadat yang memang sudah ada dan tertanam dalam jiwa
masyarakatnya.
Praktek perkawian di Mandailing Natal memang masih tergolong unik, bila
dibandingkan dengan praktek perkawinan di daerah lain di Indonesia. Misalkan saja
tradisi “mamodomi boru” (menemani calon istri), artinya ada seorang gadis dari
keluarga perempuan yang menemani calon istri tersebut tidur di rumah calon suami
sebelum dilangsungkannya perkawinan, hal ini dilakukan untuk menghindari
terjadinya fitnah. 6
Dan lagi ada tradisi mengaririt boru dalam adat Mandailing, yaitu menjajaki
guna memperoleh informasi apakah seorang gadis telah menerima pinangan atau
telah dijodohkan dengan orang lain.7
Namun dari sekian banyak keunikan praktek perkawinan di Mandailing, ada
satu hal yang menjadi perhatian penulis, yaitu praktek perkawinan “mangalangkai”
(melangkahi) kakak perempuan bagi seorang perempuan yang ingin melangsungkan
perkawinan di Mandailing Natal.
Suatu tradisi apabila ada seorang perempuan ingin menikah, namun masih ada
kakak perempuannya yang belum menikah, maka lamaran yang datangpun untuknya
5
Basyral Hamidi Harahap, Madina Yang Madani, (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), h. 277
6
Musor Lubis Tobing dan Mr. Tanjung, “Mamodomi Boru” artikel diakses pada 25 Oktober 2010 dari http://www.panyabungan.page.tl/Adat-Mandailing.htm
7
akan ditolak oleh pihak keluarga, karena menurut pemahaman masyarakatnya,
apabila ada seorang anak gadis dilangkahi oleh adik perempuannya, maka
kemungkinan sang kakak tersebut sulit untuk mendapatkan jodoh. Bahkan bisa
diasumsikan kakaknya tersebut tidak laku.
Oleh karena itulah pihak keluargapun akan menolak lamaran kepada sang
gadis tersebut. Memang dalam asas hukum adat “perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan orang tua dan kerabat”.8 Hal inilah yang kemudian mengakibatkan
adanya praktek kawin lari, sebagai jalan pintas menghindari penolakan lamaran
tersebut.
Dalam kasus ini terjadi dua pilihan yang sangat sulit bagi keluarga dalam
menentukan keputusan, yang pertama menikahkan anak gadis yang dilamar tersebut
dan mengorbankan kakak perempuannya. Kedua menolak lamaran dan
mengorbankan hak anak yang memang sudah saatnya untuk menikah. Namun ada
juga yang mempraktekkan tetap menerima lamaran, tetapi dengan persyaratan harus
membayar uang pelangkah kepada kakak perempuan yang dilangkahi.
Dalam literatur fiqh klasik maupun yang kontemporer dan juga dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan adanya larangan bagi perkawinan
seorang perempuan yang melangkahi kakak perempuannya, bahkan istilah
melangkahi kakakpun tidak dikenal. Karena memang hal ini hanyalah praktek
perkawinan yang menggunakan hukum adat istiadat. Sehingga muncul suatu
persoalan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak bila tetap dilaksanakan.
8
Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Larangan Melangkahi Kakak dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa
Sirambas Mandailing Natal Sumatera Utara)”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan sesuai dengan studi yang akan
dikaji, maka untuk mempermudah penyusunan skripsi ini penulis membatasi
penelitian ini seputar “Larangan Melangkahi Kakak dalam Perkawinan Adat
Mandailing (Desa Sirambas Mandailing Natal Sumatera Utara)” yang dimaksud
melangkahi kakak disini adalah perkawinan seorang perempuan yang mendahului
kakak perempuannya.
Yang dimaksud dengan kata “kakak” dalam penelitian ini adalah kakak
perempuan saja, tidak termasuk kakak laki-laki.
Sedangkan adat Mandailing adalah salah satu adat istiadat yang berada di
wilayah Sumatera Utara. Maka untuk mempermudah penelitian ini, peneliti
memfokuskan di desa Sirambas Mandailing Natal Sumatera Utara, hal ini ditempuh
karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penulis sendiri, dan demi
tercapainya hasil yang memuaskan dan bisa dipertanggungjawabkan.
2. Perumusan Masalah
Sebagaimana penulis sebutkan dalam latar belakang di atas, adapun yang
menjadi masalah pokok dalam hal ini adalah apakah perkawinan melangkahi kakak
Untuk menjawab masalah pokok tersebut, penulis merumuskannya dalam
bentuk pertanyaan sebagai berikut
1. Adakah larangan melangkahi kakak dalam perkawinan menurut Fiqh dan
KHI?
2. Bagimana tradisi pernikahan dalam adat Mandailing?
3. Bagimana pendapat masyarakat desa Sirambas tentang larangan menikah
melangkahi kakak?
4. Apa pendapat Tokoh Adat dan Ulama tentang larangan menikah
mendahuli kakak?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian
ini adalah:
1. Agar dapat mengetahui apakah ada larangan melangkahi “mengalangkai”
kakak dalam fiqh dan KHI.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana gambaran tradisi pernikahan dalam
adat Mandailing.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat desa Sirambas tentang
larangan melangkahi kakak dalam perkawinan adat Mandailing.
4. Untuk mengetahui pendapat tokoh adat dan ulama terhadap larangan
melangkahi kakak dalam perkawinan adat Mandailing.
Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil
1. Secara Akademis.
Diharapkan dapat memberikan penambahan hazanah keilmuan bagi peneliti,
untuk dapat dikembangkan kemudian, apalagi dalam kajian hukum adat. Dan
diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi perkembangan
penelitian-penelitian yang tema dan kajiannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh
penulis ini.
2. Secara Praktis.
Diharapkan dapat memberikan pencerahan buat masyarakat desa Sirambas
khususnya dan Mandailing Natal umumnya tentang persoalan praktek
perkawinan. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi hazanah bagi
lembaga-lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada
aturan-aturan yang ditetapkan agama.
D. Study Review
Setelah penulis melihat dan memperhatikan skripsi yang ada di Perpustakaan
Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan
Hukum, terdapat skripsi yang topik penelitiannya hampir sama dengan penelitian
yang akan penulis lakukan, yaitu skripsi yang berjudul “Perkawinan Melangkahi
Kakak Menurut Adat Sunda”, penelitian ini dilakukan di desa Cijurey Sukabumi
Jawa Barat.
Namun walaupun demikian antara satu daerah dengan daerah yang lainnya
pasti memiliki budaya yang berbeda satu sama lainnya, adat Sunda dengan Minang
berbeda, dan hukum yang timbul di dalamnya juga akan berbeda, disebabkan
perbedaan tempat, kondisi, dan situasinya.
Atas dasar itulah menurut penulis masih sangat relevan untuk melakukan
penelitian ini, apalagi penelitian ini berkaitan dengan budaya yang ada di Indonesia.
Diharapkan kemudian penelitian ini bukan hanya melihat apakah praktek perkawinan
itu telah sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-undangan, tapi lebih dari itu
diharapkan dapat menggali nilai-nilai budaya yang ada di Mandailing Natal.
E. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research), yaitu mengumpulkan data-data dengan cara langsung turun ke lapangan
untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang objek yang menjadi
penelitian penulis, dan supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis
sendiri.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah berupa metode
kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menggunakan data-data berupa
pandangan-pandangan tentang study etnografi (etnis) dalam perkawinan adat
Mandailing Natal ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Adapun pendekatan
sosial, peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola prilaku, kebiasaan,
dan cara hidup masyarakatnya.9
Sedangkan metode hukum yang digunakan adalah bersifat doktriner
(normatif), yaitu penelitian berdasarkan data-data yang ada sesuai dengan ketentuan
Fiqh dan Hukum Positif.
Adapun yang dimaksud fiqh dalam penelitian ini adalah pendapat ulama yang
bersumber dari al-Qur’an, al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Sedangkan hukum positif
adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan,
yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan
data skunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari
wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama) dan
penduduk desa Sirambas Mandailing Natal Sumatera Utara, dan dokumen-dokumen
yang berupa undang-undang, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawina,
KHI, serta dokumen non Undang-undang, misalnya hasil sensus penduduk, dan
lain-lain.
Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki
kekuatan mengikat ke dalam, berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal,
9Iyan Apriani, “Metode Penelitian Kualitatif”
laporan penelitian, artikel, majalah dan koran,10 yang ada kaitannya dengan penelitian
ini, misalnya buku (Pandapotan Nasution, Uraian Singkat Tentang adat Mandailing
serta tata cara perkawinannya).
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam upaya pengumpulan data untuk memahami realitas yang ada serta
untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang
dapat memberikan informasi dan data-data yang maksimal:
a. Wawancara
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi
atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan
dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in–
depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan
atau orang yang diwawancarai
b. Observasi
Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan Observasi Partisipasi
(participant observation) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer
atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
c. Dokumen
10
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data
tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data dapat
berbentuk surat-surat, catatan harian, hasil survei, dokumen pemerintah atau swasta,
data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain dan sebagainya.
5. Pengolahan Data
Langkah-langkah analisis data pada studi etnografi, yaitu:
a. Mengorganisir file.
b. Membaca keseluruhan informasi.
c. Menguraikan setting sosial dan peristiwa yang diteliti.
d. Menginterpretasi penemuan.
e. Menyajikan presentasi baratif berupa tabel, gambar, atau uraian.
6. Analisis Data
Dalam proses analisa data penulis menggunakan metode analisis eksploratif
berupa metode deskriptif yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis secara
induktif dan deduktif terhadap susunan penelitian. Dalam penelitian kualitatif
memungkin peneliti untuk melakukan analisis mengalir (jalinan), dimana tiga
komponen analisis bisa dilakukan saling menjalin, artinya tanpa harus menunggu
terkumpulnya semua data yang dibutuhkan. Mengenai teknik penulisan, penulis
menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum”
yang diterbitkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2007.11
11
F. Sistematika Penulisan
Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa berurutan, maka akan penulis
sistematisir sedemikian rupa, sehingga menjadi beberapa bagian yang mempunyai
kaitan dan saling melengkapi serta membentuk sutu kesatuan yang utuh dan ada garis
besarnya. Pembahasan skripsi ini diklasifikasikan menjadi 5 bab, yaitu:
Pada Bab Pertama Pendahuluan memuat: Latar Belakang Masalah,
Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian,
Study Review, dan terakhir adalah Sistematika Penulisan.
Bab Kedua Pengertian dan Tujuan Perkawinan. Pada bab ini penulis akan
membahas secara umum tentang: Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Syarat
dan Rukun Perkawinan, Larangan Perkawinan, Tujuan Perkawinan, dan Hikmah
Perkawinan.
Bab Ketiga Potret Desa Sirambas. Membahas tentang: kondisi geografis dan
sosial desa Sirambas, tingkat Pendidikan masyarakat, serta tata cara pernikahan yang
berlaku di desa Sirambas dan Adat Mandailing pada umumnya.
Bab Keempat Melangkahi Kakak dalam Perkawinan Menurut Adat
Mandailing dan Hukum Islam. Membahas tentang: Pengertian perkawinan
melangkahi kakak, larangan perkawinan melangkahi kakak menurut; pandangan
Masyarakat, Ulama dan Tokoh Adat; pandangan Fiqh dan KHI, serta analisis Penulis
tentang ketiganya.
BAB II
PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN
A. Pengertian Perkawinan
Prof. Muhammad Amin Suma dalam bukunya, sebagaimana beliau mengutip
dari pendapat Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan, bahwa kata “kawin” paling tidak
dapat didekati dari tiga aspek pengertian, yakni makna lughawi (etimologis), makna
ushuli (syari’i) dan makna fiqh (hukum). Namun pembahasan di depan ini hanya
ingin mencoba menjabarkan pengertian “nikah” dengan menggunakan paling tidak
dua dari tiga pendekatan tersebut di atas, yaitu dari sudut pandang lughawi dan
makna fiqh (hukum).1 Adapun pendekatan makna ushuli yang menitikberatkan
pembahasannya pada filsafat hukum tidak menjadi pembahasan dalam tulisan ini,
demi untuk mempersingkat penulisan.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”
yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh.2 Sedangkan Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan
bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan
perempuan yang bukan mahram.3
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut
dengan dua kata, yaitu nikah ( حاكن ) dan zawaja (جاوز). Kedua kata ini yang
1
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41
2
Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456 3
terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam
al-Qur’an dan hadits Nabi.4
Secara arti kata nikahberarti “bergabung” (مض ), “hubungan kelamin” (ءطو)
dan juga berarti “akad” (دقع). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah
yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung arti tersebut.5 Kata nikah yang
bermakna hubungan kelamin terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:
Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”
Ayat ini mengandung arti “hubungan kelamin” bukan hanya sekedar akad
nikah, karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan
laki-laki yang kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali
suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan
tersebut.
Dalam al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut
dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 22:
4
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 35
5
Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”
Ayat tersebut seolah ingin menegaskan bahwa hakikat dari perkawinan itu
adalah akadnya. Asalkan saja seorang ayah sudah melangsungkan akad pernikahan
dengan seorang perempuan, sekalipun belum pernah disetubuhi, maka tidak ada
kebolehan bagi anak-anaknya untuk menikahi perempuan tersebut.
Adapun dalam arti terminologis terdapat beberapa defenisi yang berbeda,
tetapi saling melengkapi satu sama lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan
dalam titik pandangan di kalangan ulama. Salah satu di antaranya ialah:
“Akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalakan bersenang-senangnya perempuan dengan
laki-laki”6
Sedangkan dari kalangan Syafi’iyah merumuskan nikah sebagai berikut:
“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja”7
6
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8
7
Pemberian defenisi oleh kalangan Syafi’iyah sebagaimana disebutkan di atas
melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami dan
istri yang berlaku sesudahnya yaitu bolehnya bergaul, sedangkan sebelum akad
tersebut berlangsung di antara keduanya tidak ada kebolehan.
Hampir senada dengan itu kalangan Hanafiyah mendefenisikan dengan:
“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati
kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”.8
Defenisi lainnya dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya
al-Akhwal al-Syakhsiyyah, sebagai berikut:
“Akad yang berfungsi untuk membolehkan bersenang-senang (berhubungan badan)
antara dua orang yang berakad dengan cara yang disyariatkan”9
Namun yang dimaksud dengan dua orang yang berakad di sini adalah antara
calon suami dengan calon istrinya.
Defenisi-defenisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat
dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut di atas begitu pendek dan sederhana hanya
mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan
hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu.10 Oleh karena itu ulama
kontemporer mencoba memperluas jangkauan defenisi ataupun pengertian
8
Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 6514
9
Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Qahirah: Dar al-Fikr, 2005), h. 19
10
perkawinan, misalnya defenisi yang diberikan oleh Dr. Ahmad Ghundur dalam
bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri’ al-Islamiy, mendefenisikan:
“Akad yang membolehkan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak
secara timbal balik hak dan kewajiban”.11
Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal
1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai:12
“Ikatan lahir dan bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan
istri dengan tujaun membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.13
Dalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan tidak
hanya dilihat dari segi hukum formal, tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah
perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga.14 Perkawinan adalah sendi keluarga,
sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya
bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan kehormatan yang tidak
mengutamakan tata aturan perkawinan.15
11
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h. 39
12
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 42
13
Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, Perbandingan Hukum Perdata, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2007), h. 4
14
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 42
15
Pencantuman kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena
Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya berdasarkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
pernikahan adalah, “Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
Dari perumusan defenisi pernikahan di atas, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan:
1. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang perempuan”. Hal ini
mengandung arti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang
berbeda.
2. Ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu
adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga,
bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Penyebutan “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, menandaskan bahwa
bagi Islam perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk
memenuhi perintah agama.16
Dari semua penjelasan yang disebutkan di atas, paling tidak dapat
disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah “suatu akad yang membolehkan hubungan
suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah, kekal, dan diridhoi Allah SWT”
16
B. Dasar Hukum Perkawinan
Hukum asal melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana
hukum Islam adalah ibahah (kebolehan) atau halal.17 Ini juga dengan melihat kepada
hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki perempuan
melakukan sesuatu yang tidak boleh.
Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah, tentu tidak
mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata-mata mubah
saja. Dalam surah an-Nisa’ ayat 3 Allah berfirman:
Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Berdasarkan kepada ayat di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli
hukum Islam dalam menentukan hukum asal perkawinan yang terbagi dalam tiga
kelompok, yakni;
Pertama, golongan yang mengatakan hukum menikah adalah wajib, karena
perintah menikah di dalam al-Qur’an sura an-Nisa ayat 3 menunjukkan perintah
wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap sighat “amar’ itu menunjukkan
17
wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud az-Zhahiry, yakni satu kali
kawin untuk seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten.
Kedua, hukum menikah atau menikahkan adalah sunnah, dengan
mendasarkan pendapatnya pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan
halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan
jalan tasarri yakni memiliki jariyah (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya
adalah menikah dengan memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari
suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya
sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan ijma’ ulama hukum tasarri itu adalah
tidak wajib. Ketentuan surat an-Nisa menyuruh untuk memilih antara tasarri dan
menikah. Oleh karena tasarri tidak wajib ini menunjukkan bahwa menikah
hukumnya tidak wajib.18
Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, kerna yang
dikatakan wajib itu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka
hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan
Imam Ahmad Ibnu Hambal.
Ketiga, Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah
dalam surah an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh
wanita dengan jalan menikah atau dengan tasarri, yang menunjukkan bahwa kedua
jalan itu sama derajatnya. Menurut ijma’, tasarri hukumnya mubah, karena menikah
juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunnah dan
18
mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa asal
hukum nikah adalah jaiz atau mubah, atau dengan kata lain seseorang boleh kawin
dan boleh tidak kawin.
Dari perbedaan dalam menentukan hukum asal menikah tersebut, para pakar
hukum Islam juga berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan hukumnya.
Namun secara umum dapat diberikan perincian hukum nikah berdasarkan kondisi
orang yang mau melaksanakan pernikahan tersebut, karena apabila berubah illah
suatu hukum, maka hukum yang lahirpun akan berubah pula.19
1. Sunnah
Bagi orang-orang yang telah memiliki potensi biologis melakukan hubungan
suami istri, akan tetapi ia tidak takut atau tidak khawatir akan terjebak ke dalam
perbuatan terlarang. Menurut jumhur fuqaha kondisi seseorang pada tingkatan ini
lebih baik baginya melakukan pernikahan daripada menunda-nunda.
2. Wajib
Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan kuat
untuk melakukan hubungan biologis dan memiliki perlengkapan dan ia takut akan
terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
Dalam term Ushul Fiqh disebutkan:
“Tidak sempurna suatu yang wajib tanpa adanya sesuatu yang lain, maka sesautu itu wajib adanya”.
19
Menghindarkan diri dari perbuatan zina itu hukumnya wajib, maka apabila
tidak bisa dicegah kecuali dengan nikah, maka menikah baginya dihukumkan menjadi
wajib.20
3. Haram
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai
kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam
rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan nikah istrinya akan terlantar, maka
baginya haram hukumnya untuk menikah.21
Thabrani menjelaskan sebagaimana pendapatnya dikutip oleh Sayyid Sabiq
bahwa “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk
memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala
konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga benar-benar
merasa mampu.22 Penjelasan Thabrani ini ingin mengatakan bahwa yang mengetahui
apakah seseorang mampu atau tidak untuk melangsungkan perkawinan adalah orang
yang mau menikah tersebut. Pada saatnya dia merasa mampu untuk memenuhi
konsekuensi dari perkawinan, maka kaharaman tersebut hilang.
Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 195 menjelaskan bahwa Allah
melarang orang untuk mendatangkan kerusakan:
20Ahmad Kuzari, NIkah Sebagai Perikatan , h. 30
21
Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h.20 22
Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”
4. Makruh
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, dan
cukup kuat untuk menahan diri sehingga tidak memungkin dirinya tergelincir berbuat
zina, akan tetapi orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat dalam memenuhi
kewajiban suami istri dengan baik. Maka bagi orang ini dimakruhkan untuk
melangsungkan perkawinan.
5. Mubah
Bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan
pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa
pun.23
C. Rukun dan Syarat Perkawinan 1. Rukun Perkawinan
Rukun dalam semua tindakan hukum sangatlah menentukan, terutama yang
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Diskursus tentang rukun
merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi
silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak.24
Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh dalam ranah ijtihadiyah, dan hampir disemua
aspek pembahasan fiqh bahkan sampai tataran teologi akan terjadi perbedaan
pendapat.
23
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h. 46
24
Perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan
mana yang syarat. Jadi bisa saja sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan
ulama yang lainnya menyebut sebagai syarat.
Wahbah Al-Zuhaily dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu
menjelaskan bahwa, menurut kalangan Hanafiyah yang menjadi rukun nikah hanya
“akad” saja, selain itu disebut dengan syarat.25
Hal ini tidak mengherankan karena
menurut kalangan ini hakikat dari pernikahan itu adalah “akadnya”. Senada dengan
itu Abdurrahman al-Jaziri menerangkan dalam kitabnya al-Fiqh ‘ala Mazahib
al-Arba’ah, bahwa yang dikategorikan sebagai rukun nikah itu adalah Ijab dan Qabul
yang pada dasarnya akad itu sendiri. Karena menurutnya tanpa keduanya sebuah
pernikahan tidak akan ada.26
Sedangkan menurut Ijma’ Ulama Indonesia dalam KHI menjelaskan bahwa
rukun perkawinan itu ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat
tertentu. Penjelasan tentang hal itu adalah:
a. Mempelai laki-laki/calon suami, dan syarat-syaratnya:
1) Bukan mahram dari calon istri
2) Tidak terpaksa/atas kehendak sendiri
3) Orangnya tertentu/jelas orangnya
Dalam pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami
minimal berumur 19 tahun.
25
Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,Jilid 9, h. 2522
26
b. Mempelai wanita/calon istri, dan syarat-syaratnya:
1) Tidak ada halangan hukum, yakni
- tidak sedang bersuami
- bukan mahram
- tidak sedang dalam iddah
2) Merdeka atas kemauan sendiri
Dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita,
dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi
dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
3) Jelas orangnya
Pasal 15 KHI ayat 1. “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapi umur
yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya
berumur 16 tahun”
c. Wali nikah, dan syarat-syaratnya:
1) Laki-laki
2) Islam
3) Baligh
4) Waras akalnya
d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
2) Islam
3) Adil
4) Akil Baligh
5) Tidak terganggu ingatannya Waras akalnya
6) Dapat mendegar dan melihat
7) Bebas, tidak dipaksa
e. Ijab dan kabul, dan syarat-syaratnya:
1) dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan
penerima akad dan saksi)
2) akad dilakukan sendiri oleh wali
3) kabulnya diucapkan sendiri oleh calon suami
2. Syarat Pernikahan
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu
pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.27
Jadi syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi
agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara
hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat
berlaku.28
a. Perempuan yang dinikahi bukan mahram
Secara hukum, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal
untuk dijadikan sebagai istri. Jadi, perempuan itu bukanlah perempuan yang
27
H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 12
28
haram dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun haram untuk
selamanya.
b. Mahar
Secara istilah mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari
suaminya dengan adanya akad nikah atau dukhul”. Mahar secara ekplisit
diungkapkan dalam al-Qur’an seperti yang terdapat di dalam surah an-Nisa’
ayat 4, sebagai berikut:
Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi
baik akibatnya”
Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu
hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an. Mahar oleh sebagian ulama
ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu
Rusyd di dalam Bidayatul al-Mujtahidnya.29 Sedangkan ulama kalangan
Malikiyah menempatkan mahar sebagai rukun dari rukun nikah yang ada,
tetapi tidak mewajibkan penyebutannya ketika akad dilangsungkan.30 Berbeda
dengan Wahbah Al-Zuhaily dalam kitabnya al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu
menjelaskan bahwa mahar itu bukanlah rukun dan juga bukan syarat dari
29
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 64 30
perkawinan, melainkan atsar atau akibat hukum dari perkawinan. Dengan
penjelasannya:
31
“bahwasanya mahar bukanlah rukun dan juga bukan syarat dari beberapa syarat perkawinan, akan tetapi mahar merupakan atsar/akibat hukum dari beberapa atsar-atsar perkawinan”
Sejalan dengan itu dengan sangat jelas KHI menyatakan bahwa mahar itu
bukanlah rukun dalam perkawinan, sebagaimana terdapat dalam pasal 34 ayat:
“Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”
D. Larangan Perkawinan
Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang
ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada
satu hal, yaitu perkawinan tersebut telah lepas dari segala yang menghalangi, yang
dimaksud dengan penghalang/larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah
orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan disebabkan hal tertentu.
Adapun yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh
dinikahi oleh seorang laki-laki, dan juga sebaliknya.32 Pembahasan larangan
perkawinan dapat dikelompokkan kedalam dua garis besar:
1. Mahram Muabbad.
Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan
untuk selamanya. Bagian ini ada tiga macam:
31
Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,Jilid 9, h. 6761 32
Pertama: Disebabkan adanya hubungan kekerabatan/nasab. Mereka itu adalah
perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya
disebabkan hubungan kekerabatan, adalah:
a. Ibu
b. Anak Perempuan
c. Saudara
d. Saudara Ayah/bibi
e. Saudara Ibu
f. Anak dari saudara laki-laki
g. Anak dari saudara perempuan
Penjelasan ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam
surah an-Nisa’ ayat 23:
Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”
Kedua: Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang
disebut dengan hubungan mushaharah. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan,
maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan keluarga si perempuan/istrinya
dan demikian pula sebaliknya. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi yang
a. Ibu tiri (perempuan yang telah dinikahi ayah)
b. Menantu (perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki)
c. Ibu istri (mertua)
d. Anak dari istri (anak tiri) dengan ketentuan istri itu telah digauli.
Penjelasan ini dapat ditemukan dalam ayat 22 dan sambungan ayat 23 surah
an-Nisa di atas:
...
Artinya:“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (ayat 23). ....“ Ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”
Ketiga: Larangan perkawinan karena adanya hubungan persusuan. Bila
seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut
akan menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak, sehingga perempuan itu
telah seperti ibu bagi anak itu. Adanya hubungan persusuan ini setelah terpenuhinya
beberapa syarat berikut:
a. Usia anak yang menyusui itu berumur 2 tahun, inilah yang dipegangi oleh
b. Kadar susuan sebanyak 5 kali menyusui, karena apabila kurang dari itu belum
menyebabkan pertumbuhan.
c. Kemurnian air susu, dalam pengertian tidak bercampur dengan air susu lain atau
zat lain.
d. Suami sebagai sebab adanya susu. Jumhur ulama berpendapat bahwa susu yang
itu dari perempuan yang sudah menikah, karena apabila susu itu dari perempuan yang berzina, maka tidak menyebabkan keharaman.
Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka diharamkan bagi
seseorang menikah dengan perempuan-perempuan yang disebutkan di bawah ini:
a. Ibu susuan
b. Anak susuan
c. Saudara susuan
d. Paman susuan
e. Bibi susuan
f. Anak saudara laki dan saudara perempuan susuan.
2. Mahram Ghairu Muabbad
Mahram ghairu muabbad ialah larangan menikah bagi laki-laki dengan
seorang perempuan yang bersifat sementara yang disebabkan oleh hal tertentu; bila
hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Adapun yang
masuk dalam golongan ini adalah:
a. Mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam satu waktu
Bila dua perempuan itu dinikahi sekaligus dalam satu akad, maka
waktu yang berurutan, maka pernikahan pertama dihitung sah dan
pernikahan kedua batal.
b. Poligami di luar batas
Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh memberikan
perluang bagi laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu orang sampai
batas tiga orang, sedangkan apabila lebih dari itu adalah tidak dibolehkan.
c. Larangan karena ikatan perkawinan
Seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain
tidak boleh melangsungkan perkawinan.
d. Larangan karena talak tiga
Bagi perempuan yang telah dijatuhkan talak tiga tidak boleh lagi menikah
dengan mantan suaminya, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain
dan telah dijatuhkan talaknya, dan habis masa iddahnya dengan laki-laki
tersebut. Hal ini tergambar dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 230:
e. Larangan karena ihram
Larangan menikahi seorang permpuan yang sedang ihram berdasarkan
kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:
Artinya: “Dari Utsman Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan." Riwayat Muslim.33
Namun dalam hal perkawinan perempuan yang sedang ihram ini kalangan
Hanafiyah berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama, yang menyatakan
bahwa perkawinan itu tetap sah, berdasarkan kepada hadits dari Ibnu
Abbas yang menjelaskan nabi telah menikahi Maimunah dalam keadaan
ihram, namun sebagain ulama mengatakan bahwa nabi menikah itu sudah
tidak dalam keadaan ihram lagi.
Aritnya: “Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram. Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim dari Maimunah sendiri: Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menikahinya ketika beliau telah lepas dari ihram”34
33
Muhammad Ibnu Ismail al-Amir al-Shan’any, Subulus Salam, juz 6, (Jeddah: Dar Ibnu al-Jauzy, 2004), h. 45
34
f. Larangan menikah karena perbedaan Agama
Larangan menikah ini tergambar dalam firmah Allah dalam surah
al-Baqarah ayat 221:
...
Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman....”
g. Larangan menikahi bekas istri yang diputus perkawinannya karena
sumpah li’an.
Perjelasan larangan perkawinan ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum
Islam sebanyak enam pasal, dimulai dari pasal 39 sampai pasal 44. Penulis tidak akan
menjelaskan lagi menurut KHI, karena secara prinsip tidak terjadi perbedaan yang
signifikan.
E. Tujuan Perkawinan
Perkawinan disyari’atkan tentunya mempunyai tujuan yang sangat mulia.
Nikah disyariatkan Allah seumur dengan perjalanan sejarah manusia. Sejak Nabi
Adam dan Siti Hawa, nikah sudah disyariatkan. Pernikahan Nabi Adam dan Hawa di
surga adalah ajaran pernikahan pertama dalam Islam.
Secara medis (kedokteran), pernikahan dapat memberikan dampak positif bagi
kesehatan. Sebab, sperma bisa keluar secara normal. Bila sprema lama tidak keluar
maka akan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.35 Karena prilaku seksual
yang normal dapat merupakan keseimbangan antara “motor erotik” yang mendorong
hasrat untuk aktifitas seksual, dan suatu “rem seksual” yang menjaga keinginan
35
tersebut tetap terkendali. Apabila sinyal “motor erotik” ini tidak ada pemenuhannya
dapat mengakibatkan kelainan libido yang menyebabkan distress, maupun kesulitan
berhubungan dengan orang lain.36
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam
menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya
ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan
bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan.37
Sejalan dengan itu dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan
dalam pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.38
Dari hal itulah tujuan pernikahan dapat disimpulkan kedalam empat point
besar, yaitu:
1. Menenteramkan Jiwa
Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan dan tidak hanya
manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang
alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.
Bila sudah terjadi “akad nikah”, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena
merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.
36
Linda J. Heffner dan Danny J. Sechust, At a Glance Sistem Reproduksi, edisi kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 74
37
Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h. 22
38
Sebaliknya suami pun akan merasa terteram karena ada yang mendampinginya.39
Karna pada dasarnya juga perkawinan itu dikehendaki oleh ajaran agama adalah
perkawinan yang berdimensi ganda, yaitu melahirkan ketenteraman dunia dan
akhirat.40
Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia
dapat saja ditempuh melalui jalur luar pernikahan; namun dalam mendapatkan
ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin di dapatkan kecuali
melalui perkawinan.41
Dalam al-Qur’an surah ar-Ruum ayat 21 Allah menjelaskan:
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan
sayang antara suami dan istri, tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan
pernikahan tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan pernikahan itu telah gagal,
yang bisa berakibat terjadinya perceraian.
2. Mewujudkan (Melestarikan Keturunan)