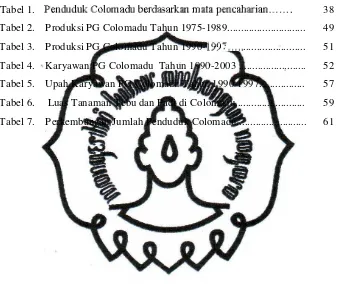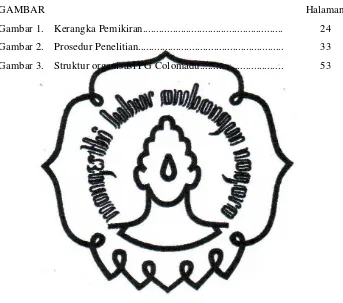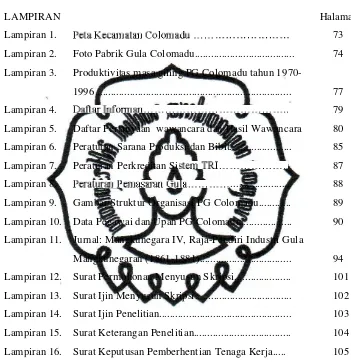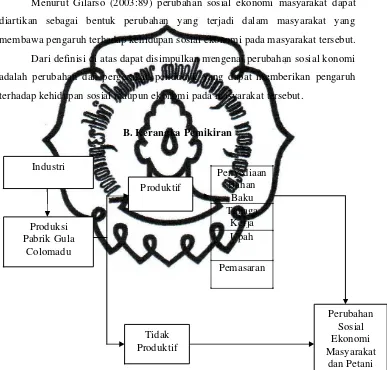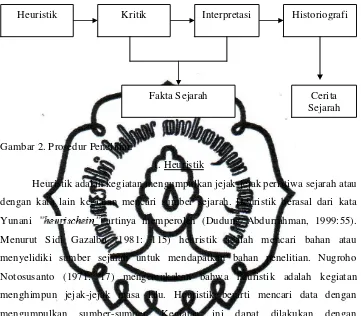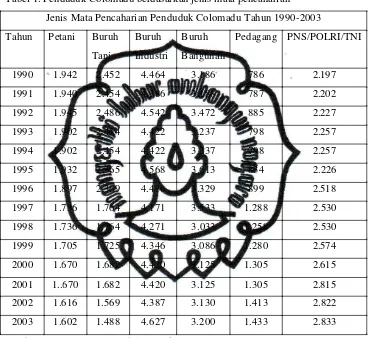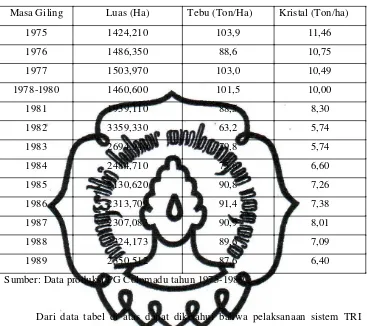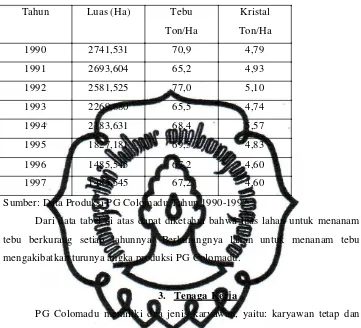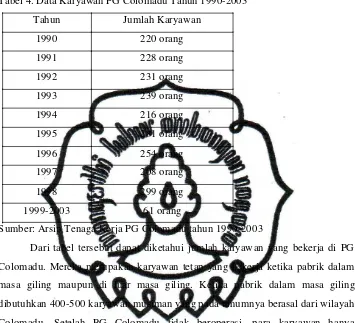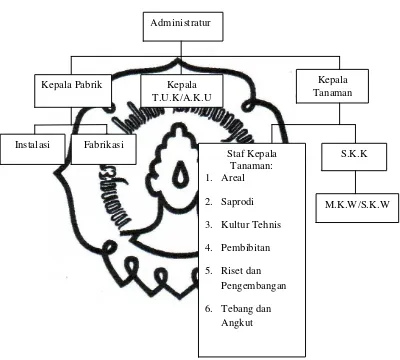commit to user
iPERKEMBANGAN INDUSTRI GULA COLOMADU DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TAHUN 1990-1998
SKRIPSI
Oleh : DIAN FITRIANA
K4407015
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
commit to user
iiPERKEMBANGAN INDUSTRI GULA COLOMADU DAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TAHUN 1990-1998
Oleh : DIAN FITRIANA
K4407015
Skripsi
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
commit to user
iiiPERSETUJUAN
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Surakarta, Juli 2011
Persetujuan Pembimbing,
Pembimbing I
Dra. Sutiyah, M. Pd, M. Hum NIP.19507081986012001
Pembimbing II
commit to user
ivPENGESAHAN
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan telah
diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Pada Hari :
Tanggal :
Tim Penguji Skripsi :
Nama Terang Tanda Tangan
Ketua : Dra. Sri Wahyuni, M. Pd
Sekretaris : Drs. Herimanto, M. Pd, M. Si
Penguji I : Dra. Sutiyah, M. Pd, M. Hum
Penguji II : Drs. Saiful Bachri, M. Pd
Disahkan oleh :
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Dekan,
commit to user
vABSTRAK
Dian Fitriana. Perkembangan Industri Gula Colomadu dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 1990-1998. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juni 2011.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Sejarah berdirinya Pabrik Gula Colomadu, (2) Perkembangan industri gula Colomadu tahun 1990-1998, (3) Perubahan sosial ekonomi masyarakat Colomadu tahun 1990-1998.
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah laporan produksi PG Colomadu, buku, serta sumber lisan dai saksi mata. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis historis yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan data sejarah.
commit to user
viABSTRACT
Dian Fitriana. Development of Colomadu Sugar Industry and Economic Social Change of Colomadu Community in 1990 1998. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, University of Sebelas Maret, July 2011.
This Objectively of the research are observed: (1) History of establishing Colomadu Sugar Factory. (2) Developing Colomadu Sugar Industry 1990 1998. (3) Economic Social change of Colomadu community 1990 1998.
In accordance to the research objective, this research used historical method. Step in historical method covered: heuristic, critic, interpretation, and historiography. Main data source are secondary data used by writer. Collecting data technical are library study. Technical analysis used technically analysis of history, i.e.: analysis that preferred in sharpness of historical fact interpretation.
commit to user
viiMOTTO
h SWT tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka mau berusaha merubah keadaanya yang ada pada diri mereka
-sia semua ada hikmahnya berjalanlah dengan naluri
itu dan akan menjauhkan dari penyesalan. Yang berlalu biarlah menjadi guru
commit to user
viiiPERSEMBAHAN
Karya sederhana ini dipersembahkan kepada:
Ayah dan Ibu tercinta
Mas Aziz dan Dek Yoga tersayang
Drs. Joko Slamet
Teman-temanku
1. Power Rangers (Leley, Fitri, Woe2, Kikis)
2. Laluna (Heri, Perdana, Risang, Sani, Lambang)
3. Bety, Iis, Margi, Renda, Yanis, Heni, Zulaikah
Kalian is the best
Teman-teman Pendidikan Sejarah 2007
commit to user
ixKATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat
dan berkat-Nya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian
dari persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penulisan Skripsi
ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan tersebut dapat
teratasi. Oleh karena itu, atas segala bentuk bantuannya, penulis mengucapkan
terima kasih kepada yang terhormat :
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Ketua Jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui
permohonan penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dra. Sutiyah, M.Pd, M. Hum, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah
memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Drs. Saiful Bachri, M. Pd Selaku Dosen Pembimbing II yang telah
memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu yang setiap malam mendoakan dan setiap butir tetes air
mata dan keringatnya yang terurai untuk memberikan semangat hidup.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu
Pengetahuan Sosial yang secara tulus memberikan ilmu kepada penulis
selama ini.
8. Teman-teman Pendidikan Sejarah 2007
Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal
mungkin, namun penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dan jauh dari
commit to user
xuntuk menyempurnakannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pendidikan khususnya pendidikan sejarah.
Surakarta, Juli 2011
commit to user
xiDAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...
HALAMAN PENGAJUAN ...
HALAMAN PERSETUJUAN ...
HALAMAN PENGESAHAN ...
HALAMAN ABSTRAK ...
HALAMAN ABSTACT...
HALAMAN MOTTO ...
HALAMAN PERSEMBAHAN ...
KATA PENGANTAR ...
DAFTAR ISI ...
DAFTAR TABEL ...
DAFTAR GAMBAR ...
DAFTAR LAMPIRAN ...
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...
B. Rumusan Masalah ...
C. Tujuan Penelitian ...
D. Manfaat Penelitian ...
BAB II KAJIAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka ...
1.
a. Pe
b. Macam-macam Industri ...
commit to user
xiie. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat ...
B. Kerangka Berpikir ...
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ...
B. Metode Penelitian ...
C. Sumber Data ...
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data ...
F. Prosedur Penelitian ...
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Wilayah Colomadu...
1. Letak dan Keadaan Geografis
2. Penduduk Colomadu
B.
C. Perkembangan Pabrik Gula Colomadu Tahun 1998...
1. Penanaman dan Pengolahan Tebu...
2. Produksi...
3. Tenaga Kerja...
4. Pemasaran...
5. Upah...
D. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat tahun
1990-1.
2. Perkembangan Pemuk
3.
4.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ...
B. Implikasi ...
commit to user
xiiiC. Saran ...
DAFTARPUSTAKA...
LAMPIRAN
68
commit to user
xivDAFTAR TABEL
TABEL Halaman
Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5.
Tabel 6.
Tabel 7.
Produksi PG Colomadu Tahun 1975-1989...
Produksi PG Colomadu Tahun 1990- ...
Karyawan PG Colomadu Tahun 1990-2003 ...
Upah Karyawan PG Colomadu Tahun 1990-1997...
Luas Tanaman Tebu dan Padi di Colomadu...
Perkembangan Jumlah Penduduk Colomadu...
38
49
51
52
57
59
commit to user
xvDAFTAR GAMBAR
GAMBAR Halaman
Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.
Kerangka Pemikiran...
Prosedur Penelitian...
Struktur organisasi PG Colomadu...
24
33
commit to user
xviDAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN Halaman
Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9. Lampiran 10. Lampiran 11. Lampiran 12. Lampiran 13. Lampiran 14. Lampiran 15. Lampiran 16. .
Foto Pabrik Gula Colomadu...
Produktivitas masa giling PG Colomadu tahun
1970-1996...
Daftar Pertanyaan wawancara dan Hasil Wawancara
Peraturan Sarana Produksi dan Bibit...
Peraturan Perkreditan Si
...
Gambar Struktur Organisasi PG Colomadu...
Data Pegawai dan Upah PG Colomadu...
Jurnal: Mangkunegara IV, Raja-Pendiri Industri Gula
Mangkunegaran (1861-1881)...
Surat Permohonan Menyusun Skripsi...
Surat Ijin Menyusun Skripsi...
Surat Ijin Penelitian...
Surat Keterangan Penelitian...
Surat Keputusan Pemberhentian Tenaga Kerja...
commit to user
1BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada masa Orde Baru bisa dikatakan masa keemasan pertanian Indonesia.
Hal itu terbukti ketika tahun 1985, Indonesia mampu menjadi Negara swasembada
beras. Berkaca dari keberhasilan tersebut maka pemerintah mencoba keberhasilan
lain dalam bidang perkebunan. Salah satunya perkebunan tebu yang merupakan
salah satu bahan utama dalam pembuatan gula pasir. Program itu dilakukan dalam
rangka untuk mencapai kembali swasembada gula seperti tahun 1930.
Dalam upaya mendorong petani agar mau menanam tebu pemerintah
melakukan berbagai cara seperti, program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Cara
ini merupakan sebuah produk kebijakan pemerintah Orde Baru. Untuk kebijakan
agraria pemerintah selalu menekankan dua segi, (1) memfokuskan kepada
peningkatan produksi dari penataan struktur agraria. Hal ini dilakukan karena
pemerintah Orde Baru lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi sebagai strategi pembangunan, (2) penekanan stabilitas politik dalam
pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dipandang sebagai persyaratan bagi
terlaksananya program kebijakan pemerintah.
Sikap pemerintah yang memberikan dukungan kepada pemilik modal dalam
membangun perkebunan-perkebunan besar dengan tanah-tanah yang luas.
Akibatnya jumlah petani yang tidak bertanah semakin besar. Selain itu secara
tidak sadar kebijakan yang dipilih ini telah meminggirkan petani. TRI dipandang
sebagai solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi gula
secara cepat. Ide ini timbul karena pada dekade tahun 1960-an terjadi pergeseran
dalam konsumsi gula nasional yang terus meningkat sedangkan produksi gula
mengalami penurunan.
Kebijakan agraria diarahkan dengan membuka peluang seluas-luasnya
bagi pemodal besar dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal
ini mendorong pihak swasta agar berperan lebih besar dalam upaya
commit to user
Salah satu cara yang ditempuh adalah penggunaan lahan yang beralih dari
penanaman sumber pangan untuk kelangsungan hidup petani menjadi sumber
penumpukan kapital untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.
Perjalanan dari sistem TRI pada kenyataannya adalah paksaan kepada
petani untuk ikut serta dalam program dengan jalan menanam tebu di tanah
mereka. Paksaan ini bertujuan untuk pencapaian target yang ditetapkan setiap
tahunnya, baik dalam luas lahan areal maupun jumlah produksi. Selain itu paksaan
ini mendorong pemimpin daerah agar mampu mencapai target yang telah
produksi seringkali cara-cara yang bersifat memaksa digunakan agar petani
terlibat dalam penanaman tebu. Cara tersebut biasanya berupa pemangilan kepada
petani yang lahannya tidak mau atau menolak ditanami tebu untuk bertemu
Kepala Desa atau Pamong Desa yang di sertai pegawai Kecamatan. Cara ini
efektif karena petani merasa enggan atau takut berurusan dengan aparat Desa.
Industri gula adalah salah satu industri tua yang pernah ada di dalam
negeri. Terlepas dari masih kurangnya produksi gula, industri ini telah menempuh
perjalanan panjang sejak masa kolonial Belanda. Setidaknya hingga kini
pabrik-pabrik produsen gula yang beroperasi adalah peninggalan masa lalu yang sudah
berusia lebih dari 100 tahun. Barangkali tak ada yang memasukkan pabrik gula
(PG) ini sebagai bangunan cagar budaya. Namun tak ada salahnya memandang
pabrik yang sebagian masih berproduksi ini sebagai saksi sejarah. Di Soloraya ada
beberapa pabrik gula yang sama-sama peninggalan masa kolonial. Dua di
antaranya pernah dimiliki penguasa Mangkunegaran dengan Mangkunagoro IV
sebagai pendirinya, yaitu PG Colomadu dan PG Tasikmadu.
Pabrik Gula Colomadu yang terletak di daerah Desa Malangjiwan,
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini merupakan
salah satu peninggalan kejayaan Mangkunegaran pada abad ke-19. Pabrik ini
merupakan saksi bisu zaman keemasan agroindustri di masa kolonial.
Pada perkembangannya Pabrik Gula Colomadu memberikan banyak
kontribusi terhadap masyarakat di sekitar Pabrik Gula Colomadu. Ratusan hingga
commit to user
3
pembabat tebu adalah serpihan faktor produksi sebuah PG yang menggantungkan
hidupnya di situ. Mengepulnya asap dapur, di samping keberlanjutan ekonomi
daerah, mau tak mau turut dipengaruhi oleh Pabrik Gula Colomadu.
Awal pelaksanaan program TRI di Colomadu dapat berjalan dengan baik
karena hubungan patronase yang kuat antara petani dan elit desa. Hubungan ini
dapat berjalan dengan baik karena elite desa yang ditunjuk oleh pemerintah selalu
memberikan tauladan kepada petani. Tauladan yang diberikan kepada petani
adalah pemberikan penyuluhan tentang menanam tebu yang baik dan benar.
Usaha yang dilakukan oleh elite desa ini telah mendorong petani memperluas
lahan penanaman tebu di Colomadu.
Kebijakan dalam program TRI membuat petani merasa kehilangan
kebebasan untuk mengolah lahan pertanian sendiri. Petani lebih memilih
menanam padi daripada menanam tebu, karena akan lebih banyak memberi
penghasilan bagi para petani. Keengganan petani menanam tebu karena sebelum
masa panen tiba petani sudah punya utang kepada Pabrik Gula. Utang itu
meliputi, penjagaan lahan pertanian, pupuk, bibit, dan obat-obatan yang harus
dibayar setelah panen. Sementara ongkos giling dan ongkos angkutan masih juga
dibebankan kepada petani. Alasan yang dikemukakan di atas membuat perjalanan
sistem TRI di Pabrik Gula Colomadu tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini terlihat
dari Pabrik Gula Colomadu dalam mendapatkan bahan baku merasa kesulitan.
Pada dekade tahun 1990-an di Pabrik Gula Colomadu sudah mulai
kekurangan bahan baku dalam proses pembuatan gula. Hal ini terjadi karena
petani di daerah ini sudah enggan menanam tebu. Keenggan para petani di daerah
Pabrik Gula Colomadu karena mulai berkembangnya daerah Colomadu ke arah
lingkungan perkotaan, sehingga tanah atau lahan di sekitar Pabrik Gula Colomadu
banyak yang beralih fungsi dari sawah menjadi daerah pemukiman (perumahan)
dan tempat usaha seperti misalnya rumah makan. Pengalihan fungsi lahan
membuat para petani enggan tanahnya ditanami tebu. Hal ini bisa terjadi karena
Program TRI sudah tidak bisa mengikat petani.
Menurut Petani program TRI membuat terjadi disintegrasi dalam
commit to user
sedangkan proses pengolahan dilakukan oleh PG. Sementara penyediaan sarana
produksi pertanian dilakukan oleh KUD, dan pembiayaan kegiatan produksi tebu
disediakan pemerintah melalui paket kredit bersubsidi. Konsekuensi dari
pemisahan tersebut adalah terjadinya berbagai hambatan manajemen produksi dan
penurunan standar penerapan budidaya tebu dan teknologi prosesing, sehingga
berakibat pada rendahnya hasil panen tebu (Mubyarto, 1968:57).
Pengalihan lahan pertanian yang semula digunakan untuk penanaman tebu
sebagai bahan baku utama pembuatan gula dialihkan para petani untuk menanam
palawija atau padi. Selain itu, berkembangnya Kecamatan Colomadu yang lebih
dinamis akibat dari perubahan Kota Solo yang semakin berkembang. Perubahan
tersebut berdampak pada tingkat interaksi yang semakin intens. Mengingat bahwa
letak Kecamatan Colomadu berdekatan dengan Kota Solo. Itu merupakan masalah
perkembangan kota yang mempuyai aspek menyangkut perubahan perubahan
yang dikehendaki dan dialami oleh warga kota.
Perubahan yang dikehendaki adalah pemenuhan kebutuhan prasarana dan
fasilitas hidup di kota. Akibat dari itu membuat Colomadu berkembang menjadi
daerah pinggiran kota. Hal ini mendorong lahan di Colomadu menjadi sasaran
dari pemenuhan kebutuhan masyarakat kota. Pemenuhan ini dapat dilihat dari
semakin berkembangnya daerah Colomadu menjadi daerah investasi baru yang
semakin berubah sesuai dengan perkembangan Kota Solo yang dinamis.
Akibatnya Pabrik Gula Colomadu ditutup oleh PTPN IX pada pertengahan
tahun 1998 tepatnya tanggal 1 Mei. Keputusan ini tentu sangat pahit, bagi para
karyawan Pabrik Gula Colomadu. Karyawan tetap yang sudah bekerja di atas 20
tahun dipercepat pensiunnya dan mereka diberi pesangon tergantung pada tingkat
pangkatnya. Sebagian yang lain dipindahkan ke pabrik gula Tasikmadu
Karanganyar, termasuk mesin-mesinnya.
Dalam penulisan ini nantinya akan diakhiri tahun 1998, sebab pada saat itu
Pabrik Gula Colomadu ditutup oleh PT PN IX. Perkembangan Pabrik Gula
Colomadu tahun 1990-1998 memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat yang tinggal disekitar pabrik Gula Colomadu. Pengaruh tersebut tidak
commit to user
5
Berdasarkan latar belakang di depan maka untuk menulis masalah tumbuh
kembangnya industri gula Colomadu sangat menarik dikaji dalam judul
omi
Masyarakat Tahun
1990-B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah sejarah berdirinya industri gula Colomadu?
2. Bagaimanakah perkembangan industri gula Colomadu tahun 1990-1998?
3. Bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar pabrik gula
Colomadu tahun 1990-1998?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan
ini adalah :
1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya industri gula Colomadu
2. Untuk mengetahui perkembangan industri gula Colomadu tahun
1990-1998
3. Untuk mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar pabrik
gula Colomadu tahun 1990-1998
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
a. Menambah ilmu pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan
ilmu sejarah yang berkaitan dengan tema pembahasan.
b. Menambah pemahaman tentang sejarah agraria, terutama tentang sejarah
pergulaan.
c. Memberikan sumbangan terhadap penelitian dan penulisan sejarah
commit to user
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
a. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan
pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
b. Memberikan sumbangan terhadap penelitian selanjutnya, khususnya dalam
sejarah pergulaan yang ada di Indonesia.
c. Digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
commit to user
7BAB II KAJIAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka 1. Industri a. Pengertian Industri
Menurut Nurimansjah Hasibuan (1993:12) secara mikro, pengertian
industri adalah:
Kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun demikian, dari segi pembentukan pendapatan, yakni yang cenderung bersifat makro, industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah.
Menurut Hardjantho Sumodisastro (1985: 1) industri ialah tiap usaha yang
merupakan unit produksi yang membuat barang dan atau yang mengerjakan
sesuatu barang atau bahan untuk masyarakat di suatu tempat tertentu. Pengertian
industri menurut Biro Pusat Statistik (1985: 15) merupakan perusahaan atau usaha
industri yang merupakan satu unit (kesatuan usaha) yang melakukan kegiatan
ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu
bangunan/lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai
produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung
jawab atas resiko usaha tersebut.
Pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk peningkatan
kesejahteraan dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang
lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan
mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal
sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai usaha
untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan
ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan secara
vertikal semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus
secara horisontal semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang
commit to user
Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa industri adalah
berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan ekonomi dapat dilakukan
oleh perorangan maupun oleh perusahaan. Oleh karena itu berbagai ragam atau
jenis perusahaan dapat dikatakan merupakan industri. Dapat dikatakan bahwa
industri adalah suatu perusahaan atau pabrik yang memproduksi bahan mentah
menjadi barang jadi dengan menggunakan mesin dan karyawan yang mempunyai
ketrampilan tertentu.
b. Macam-macam Industri
1) Industri Berdasarkan Proses Produksi
Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi:
a) Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi
barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku
untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri
alumunium, industri pemintalan, dan industri baja.
b) Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi
barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau
dinikmati oleh konsumen. Misalnya: industri pesawat terbang, industri
konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler (http : //geografi-bumi,
blog spot.com//2009/10/ klasifikasi industri.html. 16 April 2011).
2) Industri Berdasarkan Jenis Produksi
a) Industri Berat, yaitu industri yang pada hakekatnya merupakan pangkalan
bagi industri-industri lainnya. Menurut ukurannya, industri berat adalah
industry besar yang mempergunakan mesin/instalasi yang berat misalnya:
pertambangan, industri metallurgi atau industri pengolahan logam-logam,
industri semen, dan industri kimia dasar.
b) Industri Ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk
dikonsumsi. Misalnya: industri obat-obatan, industri makanan, dan industri
minuman (http : //geografi-bumi, blog spot.com//2009/10/ klasifikasi
commit to user
9
3) Industri Berdasarkan Bahan Baku
Setiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada
apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan
baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:
a) Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung
dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan
industri hasil kehutanan.
b) Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasilhasil
industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri
kain.
c) Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya
adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya:
perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata (http://geografi
bumi,blogspot.com//2009/10/ klasifikasi industri.html. 16 April 2011).
4) Industri Berdasarkan Produk yang dihasilkan
Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:
a) Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang
tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan
tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya: industri
anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.
b) Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda
yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau
digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri
baja, dan industri tekstil.
c) Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda
yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak
langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau
membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri
perbankan, industri perdagangan, dan industri
commit to user
2.Produksi a. Faktor yang Mempengaruhi Produksi 1) Penyediaan Bahan Baku
Bahan baku merupakan input dari proses transformasi menjadi produk
jadi. Cara membedakan apakah bahan baku termasuk bahan penolong dengan
mengadakan penelusuran terhadap elemen-elemen atau bahan-bahan ke dalam
produk jadi. Cara pengadaan bahan baku bisa diperoleh dari sumber-sumber alam,
petani atau membeli, misalnya serat diolah menjadi benang-benang (Nasution,
2003:103).
Menurut Baridawan yang dikutip oleh Swandari (2008:12) bahan baku
adalah barang yang akan menjadi bagian dari produk jadi yang dengan mudah
dapat diikuti biayanya.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan baku adalah
bahan-bahan utama yang akan digunakan dalam proses produksi.
2) Produksi
Produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut input
diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang disebut output. Proses
perubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut dengan proses produksi
(Boediono, 1996 : 63).
Pada dasarnya produksi merupakan proses penciptaan atau penambahan
faedah bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat lebih
bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Produksi dapat ditinjau dari dua
pengertian, yaitu pengertian secara teknis dan pengertian secara ekonomis.
Ditinjau dari pengertian secara teknis, produksi merupakan proses pendayagunaan
sumber-sumber yang telah tersedia guna memperoleh hasil yang lebih dari segala
pengorbanan yang telah diberikan. Sedangkan bila ditinjau dari pengertian secara
ekonomis, produksi merupakan suatu proses pendayagunaan segala sumber yang
tersedia untuk memperoleh hasil yang terjamin kualitas maupun kuantitasnya,
terkelola dengan baik sehingga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan.
Adanya hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan output
commit to user
11
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan produksi adalah pen gubahan
barang dan jasa yang disbut input menjadi barang-barng dan jasa yang disebut
output guna memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan industri.
3) Pemasaran
Menurut Suyadi Prawiro (2002:152) pemasaran adalah suatu keseluruhan
system yang meliputi kegiatan-kegiatan bisnis yang dirancang untuk
merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang
(jasa) untuk memuaskan kebutuhan para konsumen rumah tangga maupun
konsumen industri. Termasuk di dalamnya menjaga mutu produk sesuai rencana.
Pemasaran seyogyanya dimulai sejak barang (jasa) belum diproduksi.
Artinya tidak dimulai pada saat produk selesai, juga tidak berakhir saat penjualan.
Semua kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran harus dirancang
sejak dini dan ditujukan untuk menentukan produk apa, berapa luas pasarannya,
berapa harganya dan bagaimana promosinya. Kegiatan pemasaran timbul apabila
manusia memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan cara
yang disebut pertukaran (Suyadi Prawiro, 2002:153)
Pemasaran merupakan kegiatan yang penting dalam menjalankan usaha
pertanian, karena pemasaran merupakan tindakan ekonomis yang sangat
berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan petani. Produksi yang baik
akan sia-sia dengan harga pasar yang rendah karena tingginya produksi tidak
mutlak memberi keuntungan yang tinggi tanpa disertai dengan pemasaran yang
baik dan efisien (Mubyarto, 1995).
Menurut Kotler yang dikutip oleh Erwanto (2010:20) pemasaran adalah
fungsi bisnis yang mengidentifikasikan keinginan dan kebutuhan yang belum
terpenuhi sekarang dan mengatur seberapa besarnya, menentukan pasar-pasar
target mana yang paling baik dilayani oleh organisasi, dan menentukan berbagai
produk, jasa dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Jadi
pemasaran berperan sebagai penghubung antara kebutuhan-kebutuhan masyarakat
dengan pola jawaban industri (dalam hal ini termasuk industri di bidang pertanian)
commit to user
Dari beberapa definisi mengenai pemasaran, dapat disimpulkan bahwa
pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk
memindahkan suatu produk dari produsen ke titik konsumen, termasuk di
dalamnya menjaga mutu produk sesuai rencana.
4) Tenaga Kerja
Tenga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal, sumber
daya alam, dan kewirausahaan. Faktor produksi tenaga kerja sangat penting
karena sangat menentukan keberhasilan produksi. Ciri khusus yang dimiliki faktor
produksi ini ialah tidak dapat hilang atau berkurang apabila faktor produksi itu
dipakai, dimanfaatkan atau dijual. Semakin sering faktor produksi ini dipakai
bukan kadarnya semakin berkurang, akan tetapi justru sebaliknya dan bahkan
nilainya menjadi semakin tinggi.
Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64
tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu
angkatan kerja (labour force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labour
force) adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun
siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku.
Sedangkan penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik bekerja
penuh maupun tidak bekerja penuh (Dumairy, 1997: 74).
Menurut Suroto (1992:17), tenaga kerja adalah kemampuan manusia untuk
mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik
untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Tenaga ini dikeluarkan oleh manusia
dengan menggunakan organ-organ otak sebagai pusat jaringan syaraf dan panca
indra sebagai sistem komunikasinya serta tulang dan otot, terutama pada jari,
tangan, kaki, dan punggung yang menjadi alat mekanismenya. Disebabkan oleh
anggota badan yang digunakan tersebut berbeda, maka sering dibedakan antara
kerja fisik dan kerja psikis. Disebut kerja fisik atau jasmaniah adalah karena
dianggap lebih banyak menggunakan tenaga otot daripada tenaga otak.
Sedangakan kerja psikis atau kerja otak karena dianngap bahwa dalam
commit to user
13
Lebih tepat lagi kalau alasannya karena hasilnya lebih banyak ditentukan dengan
pikiran dan panca indera, imajinasi, dan emosi.
Menurut Mulyadi (2009:319), tenaga kerja dibagi menjadi 2 yaitu: (1).
Tenaga kerja langsung yang merupakan semua karyawan yang secara langsung
ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut secara langsung
pada produk dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam
memproduksi produk, (2). Tenaga kerja tak langsung yaitu tenaga kerja yang
jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga
kerja merupakan seseorang yang siap bekerja untuk mengoptimalkan kemampuan
yang ada pada dirinya baik yang terlibat langsung pada proses produksi maupun
yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi.
5) Upah
Bagi sebagian tenaga kerja atau karyawan di Indonesia, upah masih
merupakan faktor perangsang dalam mendorong karyawan untuk berprestasi. Bagi
sebagian tenaga kerja atau karyawan di Indonesia, upah masih merupakan faktor
yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan baik
dan merupakan faktor kepuasan. Masalah pengupahan bagi manajemen personalia
adalah tugas yang cukup sulit dan komplek karena menyangkut faktor emosional
dari sudut pandang karyawan, serta merupakan salah satu aspek yang berarti bagi
karyawan dan perusahaan.
Upah adalah bagian dari kompensasi yang terbesar. Kompensasi berbentuk
fasilitas-fasilitas yang dapat dinilai dengan uang, selain upah. Dalam
Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1974 No. 33Pasal 7 ayat a dan b, dimaksudkan dengan
upah adalah : (1) tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh
sebagai ganti pekerja (2) perumahan, makan, bahan makanan serta pakaian
dengan percuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu.
Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, memberikan definisi upah
sebagai berikut: Upah ialah suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima
kerja untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi
commit to user
produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut
suatu persetujuan, Undang-Undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Danang Arif Nugraha,
2003:34-35).
Menurut Nitisemito (1997: 89) upah adalah penghargaan dari energi
karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi, atau suatu jasa yang
dianggap sama dengan itu, yang berujud uang tanpa suatu jaminan yang pasti
dalam tiap-tiap minggu atau bulan. Maka hakekatnya upah adalah suatu
penghargaan dari energi karyawan yang dimanifestasikan.
Dari definisi upah di atas meskipun berbeda beda tetapi memiliki maksud
yang sama yaitu upah merupakan pengganti atas jasa yang telah diserahkan oleh
pekerja kepada pihak Majikan.
b. Faktor yang menghambat produksi
Menurut Soekartawi (1990:15) dalam proses produksi terdapat faktor yang
dapat menghambat jalannya produksi. Faktor tersebut antara lain adalah:
1) Kebudayaan Masyarakat
Sebelum membangun dan menjalankan kegiatan industri sebaiknya patut
dipelajari mengenai adat-istiadat, norma, nilai, kebiasaan, dan lain sebagainya
yang berlaku di lingkungan sekitar. Tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat
sekitar mampu menimbulkan konflik dengan penduduk sekitar. Selain itu ketidak
mampuan membaca pasar juga dapat membuat barang hasil produksi tidak laku di
pasaran karena tidak sesuai dengan selera konsumen, tidak terjangkau daya beli
masyarakat, boikot konsumen, dan lain-lain.
2) Teknologi
Dengan berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu akan dapat
membantu industri untuk dapat memproduksi dengan lebih efektif dan efisien
serta mampu menciptakan dan memproduksi barang-barang yang lebih modern
dan berteknologi tinggi. Namun teknologi yang buruk dapat mengakibatkan
commit to user
15
3) Pemerintah
Pemerintah adalah bagian yang cukup penting dalam perkembangan suatu
industri karena segala peraturan dan kebijakan perindustrian ditetapkan dan
dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparat-aparatnya. Pemerintahan yang tidak
stabil dpat mengakibatkan produksi macet, karena kurangnya keamanan, dan
subsidi.
4) Dukungan Masyarakat
Semangat masyarakat untuk mau membangun daerah atau n egaranya akan
membantu industri di sekitarnya. Masyarakat yang cepat beradaptasi dengan
pembangunan industri baik di desa dan di kota akan sangat mendukung sukses
atau tidaknya suatu indutri.
5) Kondisi Alam
Kondisi alam yang baik serta iklim yang bersahabat akan membantu
industri memperlancar kegiatan usahanya. Di Indonesia memiliki iklim tropis
tanpa banyak cuaca yang ekstrim sehingga kegiatan produksi rata-rata dapat
berjalan dengan baik sepanjang tahun. Kondisi alam yang kurang baik dapat
menghambat produksi, misalnya bencana alam.
6) Kondisi Perekonomian
Pendapatan masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan daya beli
masyarakat untuk membeli produk industri, sehingga efeknya akan sangat baik
untuk perkembangan perindustrian lokal maupun internasional. Jika pendapatan
masyarakat rendah maka daya beli rakyat juga rendah dan hal itu dapat
mempengaruhi perkembangan industri.
3.Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat a. Masyarakat
Dalam kehidupan manusia menunjukkan adanya keterikatan dan perasaan
saling membutuhkan satu sama lain. J. L. Gillin dan J. P. Gillin yang dikutip Abu
Ahmadi (1990: 220) menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia
yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan
commit to user
kecil. Menurut Ralp Linton yang dikutip Abu Ahmadi (1990: 220), masyarakat
adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga
mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu
kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Berdasarkan definisi Ralp Linton
tersebut, maka masyarakat timbul dari setiap kumpulan individu, yang telah lama
hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Kelompok manusia yang
dimaksud di atas yang belum terorganisasikan mengalami proses yang
fundamental yaitu: (1) adaptasi dan organisasi dari tingkah laku para anggota, dan
(2) timbul perasaan berkelompok secara lambat laun.
Adanya sarana untuk berinteraksi menyebabkan suatu kolektif manusia itu
akan berinteraksi. Tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi
merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan
lain yang khusus, yaitu tingkah laku yang khas. Ikatan khusus yang membuat satu
kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat yaitu: (1) pola tingkah laku yang
khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu, (2) pola itu
harus bersifat mantap dan kontinyu, atau dengan kata lain pola khas itu sudah
menjadi adat istiadat yang khas dan (3) adanya satu rasa identitas di antara para
warga atau anggotanya bahwa mereka memang merupakan satu kesatuan khusus
yang berbeda dari kesatuan-kesatuan yang lain (Koentjaraningrat, 1983: 147).
Soerjono Soekanto (2006: 27) mengatakan bahwa community adalah
masyarakat yang tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batasbatas tertentu,
di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di
antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas
wilayahnya. Roucek dan Warren yang dikutip Jefta Leibo (1995: 7), menyatakan
bahwa secara umum dalam kehidupan masyarakat di pedesaan mempunyai
beberapa karakteristik, antara lain:
1) Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai
dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku)
2) Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit
ekonomi.Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam
commit to user
17
ekonomi rumah tangga. Selain itu juga sangat ditentukan oleh kelompok
primer, yakni dalam memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan
peranan dalam pengambilan keputusan final.
3) Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada (misalnya
keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya)
4) Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota,
serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar atau banyak.
Karakteristik yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren ini, tidak
semuanya berlaku di setiap desa, karena setiap desa itu memiliki karakteristik
yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa jauh tingkat perubahan (kemajuan)
yang telah dicapai oleh masyarakat desa tertentu.
Masyarakat merupakan obyek studi dari disiplin ilmu sosiologi, oleh
karena itu masyarakat tidak hanya dipandang sebagai suatu kumpulan individu
semata-mata, melainkan suatu pergaulan hidup karena mereka cenderung hidup
bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa ahli sependapat
dengan argumen di atas, yang kemudian lebih ditegaskan lagi oleh Soleman B.
Tanako (1993: 11) bahwa masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan
individu atau penjumlahan dari individu-individu semata-mata. Masyarakat
merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia itu hidup bersama.
Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari
anggotanya. Dengan perkataan lain, masyarakat adalah suatu sistem yang
terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem
kemasyarakatan.
Soleman B. Tanako (1993: 12) menjelaskan bahwa sebagai suatu
pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia maka tentunya
masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yang lebih menegaskan definisi
masyarakat itu sendiri, yaitu:
1) Manusia yang hidup bersama
2) Bergaul selama jangka waktu cukup lama
commit to user
Dari beberapa pendapat para tokoh di atas maka masyarakat dapat
didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dan saling
berinteraksi karena mereka memiliki kesamaan karakteristik dan kepentingan
ataupun tujuan hidup yang minimal sama.
b. Pengertian Perubahan Sosial
Soerjono Soekanto (2006: 13), menjelaskan pengertian sosial sebagai
berikut:
Istilah sosial pada ilmu-ilmu sosial memiliki arti yang berbeda dengan misalnya istilah sosialisme atau istilah sosial pada departemen sosial. Apabila istilah sosial pada ilmu sosial merujuk pada obyeknya, yaitu masyarakat, sosialisme merupakan suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum ( atas alat-alat produksi dan jasa dalam bidang ekonomi). Sementara itu, istilah sosial pada departemen sosial menunjuk pada kegiatan kegiatan di lapangan sosial. Artinya kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan, seperti misalnya tuna karya, tuna susila, orang jompo, yatim piatu dan lain sebagainya, yang ruang lingkupnya adalah pekerjaan ataupun kesejahteraan sosial.
Soerjono Soekanto (2006:261) menjelaskan pengertian perubahan sosial
sebagai berikut:
Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan bisa berkaitan dengan: 1) Nilai-nilai sosial; 2) Pola perilaku; 3) Organisasi; 4) Lembaga kemasyarakatan; 5) Lapisan masyarakat; 6) Kekuasaan, wewenang dll.
Perubahan berkaitan dengan banyak hal, salah satunya adalah dalam
kehidupan sosial masyarakat. Istilah sosial dapat diartikan sebagai hal yang
berkenaan dengan masyarakat dan suka memperhatikan kepentingan umum.
Dari pengertian di atas, maka perubahan yang dimaksud di sini adalah
perubahan yang berkenaan dengan tata kehidupan sosial masyarakat. Perubahan
commit to user
19
definisi, menurut Selo Soemardjan (1991: 304) perubahan sosial dapat dibagi
dalam dua kategori, perubahan yang disengaja dan yang tidak disengaja (intended
dan unintended change). Yang dimaksud dengan perubahan sosial yang disengaja
adalah perubahan yang telah diketahui dan direncanakan sebelumnya oleh para
anggota masyarakat yang berperan sebagai pelopor perubahan. Sedangkan
perubahan sosial yang tidak direncanakan ialah perubahan yang terjadi tanpa
diketahui atau direncanakan sebelumnya oleh anggota masyarakat.
Perubahan sosial tidak hanya diartikan sebagai suatu kemajuan atau
progress tetapi dapat pula berupa suatu kemunduran (regress). Selo Soemarjan
yang dikutip Surjono Soekanto (2006:263) mengartikan bahwa perubahan sosial
sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam
suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya
nilai-nilai, sikap, pola perilakunya di antara kelompok-kelompok dalam
masyarakat. Tekanan definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga
kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang kemudian
mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.
Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi dalam
atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan
sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Jadi perubahan sosial dapat terjadi
karena perbedaan keadaan di antara sistem-sistem sosial dalam sebuah
masyarakat. Kemudian menurut Piott Sztomka (2007:3) konsep dasar perubahan
sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; (3) di
antara keadaan sistem sosial yang sama.
Gillin dan Gillin yang dikutip Surjono Soekanto (2006: 263) mengatakan
perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima,
baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, materiil,
komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun
penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
Mac Iver yang dikutip Surjono Soekanto (2006: 263) mengatakan bah wa
commit to user
(social relantionships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan
(equilibrium) hubungan sosial.
Dari beberapa pengertian mengenai perubahan sosial di atas dapat
disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan hubungan
antara masyarakat dengan pihak tertentu dalam lingkup social misalnya hubungan
antara petani dengan pihak pabrik.
c. Penyebab Perubahan Sosial
Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab
yang melatar belakangi terjadinya perubahan itu. Soerjono Soekanto (2005: 318)
menyatakan bahwa penyebab perubahan sosial sumbernya terletak di dalam
masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar.
a) Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri, antara lain:
1) Bertambah atau berkurangnya penduduk
Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya
perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga
kemasyarakatannya, sedangkan berkurangnya penduduk mungkin
disebabkan berpindahnya penduduk akibat urbanisasi maupun
transmigrasi. Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan,
misalnya dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial, yang
mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan.
2) Penemuan-penemuan baru
Penemuan-penemuan baru yang menyebabkan terjadinya
perubahan-perubahan terdiri dari penemuan baru dalam kebudayaan jasmaniah
maupun rohaniah. Misalnya, dalam kebudayaan jasmaniah yaitu dengan
ditemukannya radio menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembaga
kemasyarakatan seperti pendidikan agama, pemerintahan, rekreasi dan
lain-lain. Penemuan dalam kebudayaan rohaniah misalnya, adanya
ideologi baru, aliran kepercayaan baru, sistem hukum yang baru dan
commit to user
21
3) Pertentangan (conflict) masyarakat
Pertentangan-pertentangan antara individu dengan kelompok atau
perantara kelompok dengan kelompok menyebabkan terjadinya perubahan
sosial dan kebudayaan.
4) Terjadinya pemberontakan atau revolusi
Revolusi yang meletus di sebuah negara mengakibatkan terjadinya
perubahan-perubahan besar dalam negara tersebut, yang dapat merubah
segenap lembaga kemasyarakatan.
b) Sebab-sebab yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain:
1) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar
manusia seperti terjadinya bencana alam yang menyebabkan masyarakat
yang mendiami suatu daerah tertentu terpaksa harus menyesuaikan diri
dengan keadaan alam yang baru.
2) Peperangan
Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya
perubahan-perubahan karena biasanya negara yang menang akan
memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah.
3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain
Penyebab perubahan sosial juga bisa datang dari faktor pribadi
masyarakat, misalnya keinginan dari setiap individu yang ada dalam
masyarakat untuk merubah kehidupannya, sehingga mau tidak mau
struktur masyarakat tersebut berubah pula. Pendapat ini diperkuat oleh
Morris Ginsberg sebagaimana dikutip dalam Tilaar (2002:7) sebagai
berikut;
commit to user
d. Pengertian Perubahan Ekonomi
Perubahan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dan penurunan
pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya
pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam
struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu
negara. Dalam perubahan ekonomi tidak dapat terlepas dari pertumbuhan
ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan
ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses
pembangunan ekonomi (http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi, 13
April 2011).
Perubahan-perubahan dan pergerakan-pergerakan yang relatif dari
penduduk menjadi indikator yang penting mengenai tekanan-tekanan sosial
ekonomi yang lebih besar. Perubahan penduduk dipergunakan sebagai indikator
bagi perbedaan sosial dan perubahan ekonomi. Pertumbuhan atau pergerakan
penduduk pedesaan biasanya disebabkan oleh 3 faktor penting, yaitu kelahiran,
kematian dan perpindahan penduduk (Djoko Suryo, 1989: 11).
Karaketeristik (cirri khas) pada masyarakat pertanian tradisional adalah
sifat ekonominya masih subsisten, yaitu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan
sendiri. Tingkat kesejahteraan individu (dan keluarganya) tergantung pada luasnya
tanah pertanian dan kemampuan yang dimilki keluarga tersebut untuk mengolah
dan mengelola tanahnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh
tingkat kesuburan tanah pertanian yang ditempati.
Dengan adanya Industri, maka orientasi masyarakat sebagian besar tidak
lagi pada pertanian tetapi kepada pabrik. Ada yang menjadi administrator, staf
kantor, masinis lokomotif, sopir, teknisi, buruh pabrik, buruh tebang, dan
lain-lain.
e. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat
Perubahan dan pergerakan yang dari penduduk menjadi indikator yang
commit to user
23
Perubahan-perubahan dan pergerakan-pergerakan yang relatif dari
penduduk menjadi indikator yang penting mengenai tekanan-tekanan sosial
ekonomi yang lebih besar. Perubahan penduduk dipergunakan sebagai indikator
bagi perbedaan sosial dan perubahan ekonomi (Djoko Suryo, 1989: 11).
Menurut Gilarso (2003:89) perubahan sosial ekonomi masyarakat dapat
diartikan sebagai bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang
membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat tersebut.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan mengenai perubahan sosial konomi
adalah perubahan dan pergerakan penduduk yang dapat memberikan pengaruh
terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi pada masyarakat tersebut.
[image:39.588.129.516.198.568.2]B. Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan:
Pabrik gula Colomadu didirikan pada tanggal 8 desember 1861, oleh KGPAA
Mangkunegoro IV (1853-1881) di desa Malangjiwan. Di desa ini terdapat tanah-tanah
yang baik, air mengalir sehingga cocok untuk perkebunan tebu. Pada tahun 1863 Penyediaan
Bahan Baku Tenaga
Kerja Upah
Pemasaran Industri
Produksi Pabrik Gula
Colomadu
Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat
dan Petani Produktif
commit to user
Pabrik Gula Colomadu sudah mulai berproduksi yang mana merupakan tahun panen
yang pertama.
Pada saat pendirian sampai tahun 1942, Pabrik Gula Colomadu tidak pernah
mengalami kesulitan dalam pengadaan lahan untuk penanaman bahan baku, tenaga
kerja dan pemasaran produksinya. Kemudian pada masa pendudukan Jepang Pabrik
Gula Colomadu mengalami penurunan produksi karena kesulitan dalam mendapatkan
tenaga kerja maupun areal untuk menanam tebu. Hal itu karena pada masa
pendudukan Jepang banyak Pabrik Gula yang beralih fungsi. Pemerintah Jepang lebih
memfokuskan tanaman pangan daripada tanaman tebu.
Kesulitan yang dialami Pabrik Gula Colomadu terulang kembali ketika tahun
1990. Pabrik Gula Colomadu kesulitan mendapatkan bahan baku karena para petani
lebih memilih menanam padi daripada menanam tebu. Mereka menganggap
menanam padi lebih menguntugkan daripada menanam tebu. Mulai tahun 1997,
Pabrik Gula Colomadu sudah tidak mampu berproduksi lagi karena kesulitan bahan
baku. Sehingga pada tahun 1998 Pabrik Gula Colomadu ditutup oleh PT Perkebunan
Nusantara IX (Persero).
Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya ketika Pabrik Gula Colomadu
masih produktif. Ketika sudah tidak produktif, Pabrik Gula Colomadu juga
memberikan dampak pada kehidupan masyarakat selain petani. Dampak tersebut
dapat dirasakan langsung oleh para pegawai yang bekerja di Pabrik Gula
Colomadu.
Keberadaan Pabrik gula Colomadu memberikan pengaruh terhadap kehidupan
masyarakat khususnya petani. Karena petanilah yang berhubungan langsung dengan
Pabrik Gula. Pada masa kejayaan industri gula Colomadu, maka masyarakat telah
berubah dari masyarakat pertanian tradisional menjadi masyarakat pertanian
modern yang berorientasi kepada industri, yaitu industri gula. Hal tersebut tentu
merubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tadinya sebagai masyarakat
pertanian tradisional yang berciri khas berbeda dengan masyarakat industri.
Karaketeristik (ciri khas) pada masyarakat pertanian tradisional adalah
sifat ekonominya masih subsisten, yaitu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan
sendiri. Tingkat kesejahteraan individu (dan keluarganya) tergantung pada luasnya
commit to user
25
untuk mengolah dan mengelola tanahnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
commit to user
26BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian
Data penelitian ini, dicari sumber tertulis di perpustakaan. Adapun
perpustakaan yang dipergunakan sebagai tempat penelitian adalah:
a. Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran
b. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta
c. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta
d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Surakarta
e. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta
f. Perpustakaan PT. Perkebunan Nusantara IX Surakarta
g. Wilayah Kecamatan Colomadu
2. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah sejak pengajuan judul
skripsi yaitu bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juli 2011. Adapun
kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu penelitian tersebut adalah
mengumpulkan sumber, melakukan kritik untuk menyelidiki keabsahan dan
kebenaran isi sumber, menetapkan makna yang saling berhubungan dari data yang
diperoleh dan terakhir menyusun laporan hasil penelitian. Secara rinci jadwal
commit to user
27
No Kegiatan Bulan
Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli
1. Pengajuan Judul
2. Proposal
3. Perijinan
4. Pengumpulan
Data
5. Analisis Data
6. Penulisan
Laporan
B. Metode Penelitian
Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti cara atau
jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara
kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang
bersangkutan (Koentjaraningrat, 1983: 7). Penelitian ini merupakan penelitian
yang berusaha merekonstruksikan mengenai
Colomadu Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 1990- ,
maka metode yang digunakan adalah metode sejarah atau metode historis.
Hadari Nawawi (1995: 78-79) mengemukakan bahwa metode penelitian
sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu
atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan
yang berlangsung pada masa lalu. Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung
Abdurrahman (1999: 43) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah
seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber
sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari
hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Louis Gottschalk yang dikutip Dudung
Abdurrahman (1999: 44) menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan
commit to user
dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang
dapat dipercaya.
Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61), yang dimaksud
metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan
peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis
bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita sejarah yang
dapat dipercaya.
Sartono Kartodirjo (1992:37) berpendapat bahwa metode penelitian
sejarah adalah prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah
masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau.
Menurut Sumadi Suryabrata (1992;16) tujuan penelitian sejarah yaitu untuk
membuat rekronstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara
mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti
untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan.
Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian
sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan mengumpulkan
sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji, kemudian
menguji dan menganalisis secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang
dicapai dalam bentuk tertulis untuk dijadikan suatu cerita sejarah yang obyektif,
menarik dan dapat dipercaya.
C. Sumber Data
ak dari kata
tunggal datum
bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian.
Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61) sumber sejarah ialah
bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa
yang terjadi pada masa lampau.
Helius Syamsuddin (1996: 73) mengemukakan tentang pengertian sumber
commit to user
29
kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (past
actuality). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw materials)
sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan
oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa
kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan).
Sumber sejarah juga disebut sebagai data sejarah. Data sejarah berarti
bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyelesaian dan pengkategorian.
Berbagai cara ditempuh untuk mengklasifikasikan sumber data, salah satunya
yaitu dengan meninjau atau melihat sumber data itu dari sudut kegunaanya yang
langsung untuk penyelidikan historis. Klasifikasi sumber sejarah dapat dibedakan
menurut bahannya, asal-usul atau urutan penyampaian dan tujuan sumber dibuat.
Sumber menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan
sumber tidak tertulis. Sumber-sumber demikian menurut asal-usul atau urutan
penyampaiannya dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder
(Dudung Abdurrahman, 1993:31).
Louis Gottshalck (1986:35) mengemukakan bahwa sumber tertulis primer
adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sumber tertulis
primer juga dapat diartikan sebagai data yang didapatkan dari masa yang sejaman
dan berasal dari orang yang sejaman. Sedangkan sumber tertulis sekunder
merupakan kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni
dari seseorang yang tidak hadir dari peristiwa yang dikisahkannya. Sumber tertulis
sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak
sejaman dengan peristiwa yang dikisahkannya.
Sumber sekunder adalah informasi yang diberikan oleh orang yang tidak
langsung mengamati atau orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu kejadian,
keadaan tertentu atau tidak langsung mengamati objek tertentu. Sumber sekunder
biasanya dicatat dan ditulis setelah peristiwanya terjadi (Nugroho
Notosusanto,1971: 35).
Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah berupa
arsip-arsip laporan produksi (tenaga kerja, penyediaan bahan baku, upah) Pabrik
commit to user
mendapatkan banyak informasi melalui wawancara dengan berbagai informan
yang relevan dengan penelitian ini, yaitu pegawai dan mantan pegawai Pabrik
Gula Colomadu, serta para Petani.
Adapun sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku literature,
maupun artikel-artikel yang relevan dengan penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan data yang digunakan, maka dalam pengumpulan data
dilakukan melalui dua macam, yaitu :
1. Studi Pustaka
Koentjaraningrat (1986:3) menyatakan studi pustaka penting sebagai
proses bahan penelitian. Tujuannya sebagai pemahaman secara menyeluruh
tentang topik permasalahan. Teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian
yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah, dengan
cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau
brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan, museum ataupun instansi yang
menyediakan sumber tertulis lainya.
Pengumpulan dengan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan
jalan mengumpulkan buku dan bentuk data lainnya tentang peristiwa masa
lampau di beberapa perpustakaan. Buku atau data yang telah terkumpul
kemudian diteliti dan disesuaikan dengan tema penelitian. Untuk memperoleh
data dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang sumber-sumber
primer dan sumber yang berupa buku-buku, koran dan arsip yang tersimpan di
perpustakaan
Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai
berikut :
1)Mengumpulkan buku-buku, surat kabar, artikel-artikel internet yang
relevan dengan masalah yang diteliti.
2)Membaca dan mencatat sumber-sumber data yang diperlukan baik itu
commit to user
31
3)Memfotokopi dan mencatat literatur kepustakaan yang dianggap penting
dan relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara
Menurut Koentjoroningrat (1986:129) metode wawancara atau metode
interview, mencakup cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba
mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden,
dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Wawancara adalah
sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan
penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview
guide (panduan wawancara). Adapun maksud dari wawancara adalah untuk
mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motif,
tuntutan kepedulian, dan lain-lain.
Suatu wawancara mempunyai tujuan untuk mengumpulkan keterangan
tentang kehidupan manusia di dalam masyarakat, sehingga untuk memperoleh
data yang dapat dipertanggungjawabkan maka diadakan pemilihan personal
yang diwawancarai, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan
tentang masalah yang diteliti. Dalam penelit