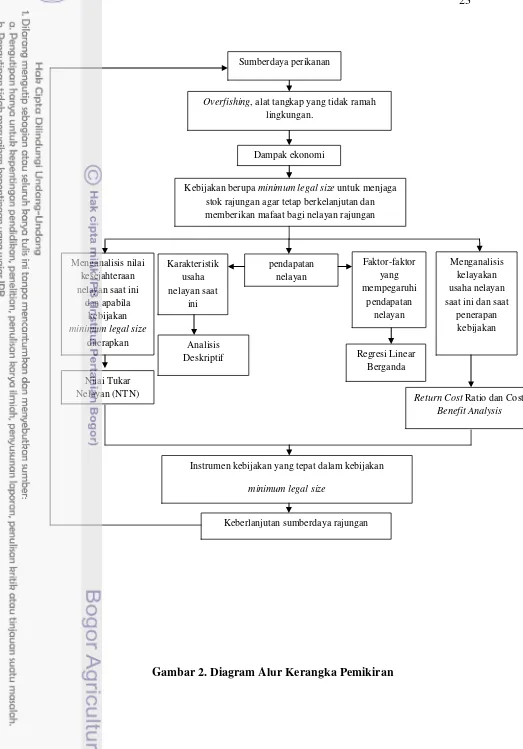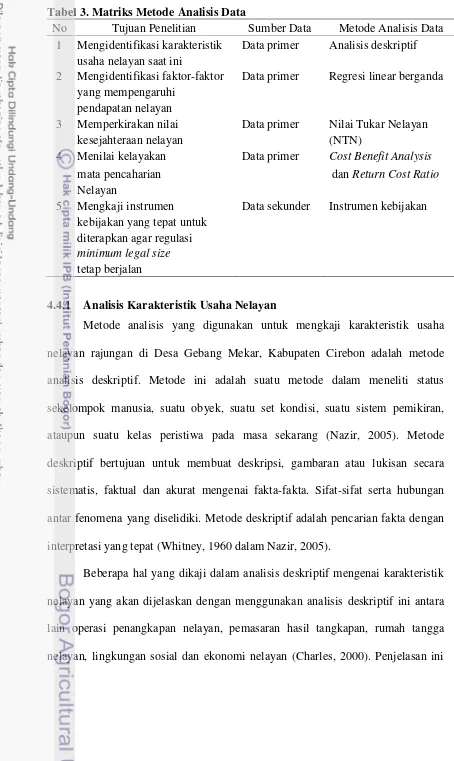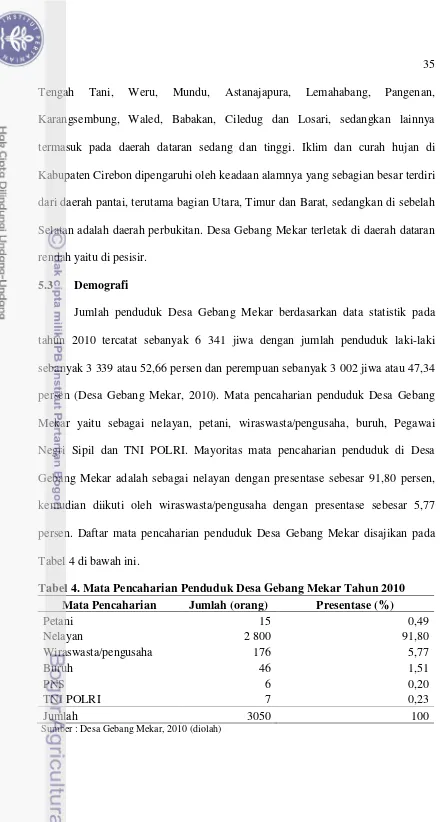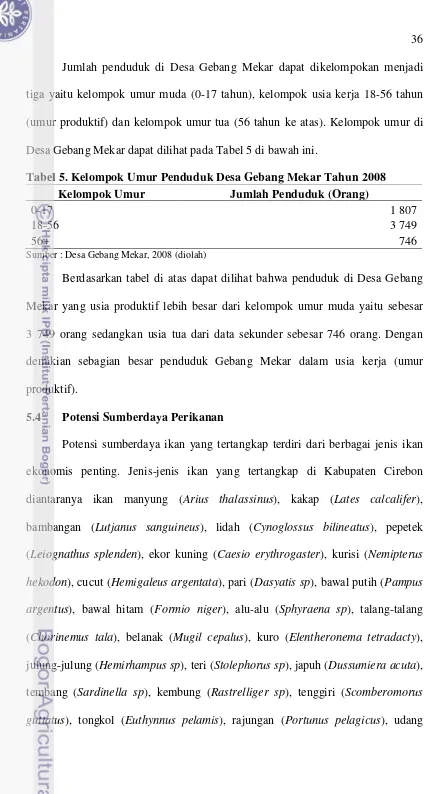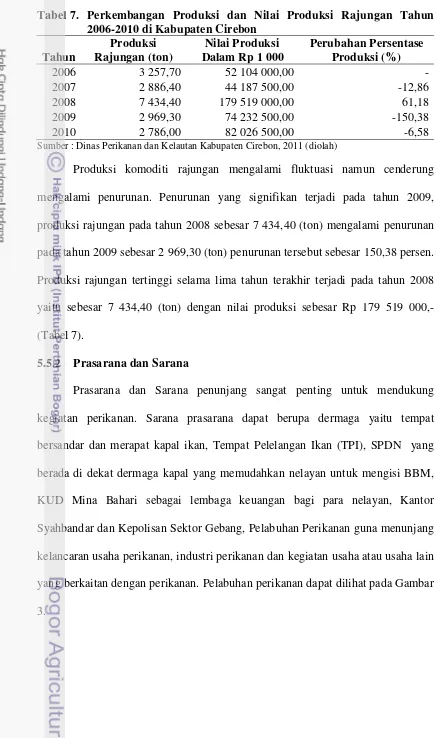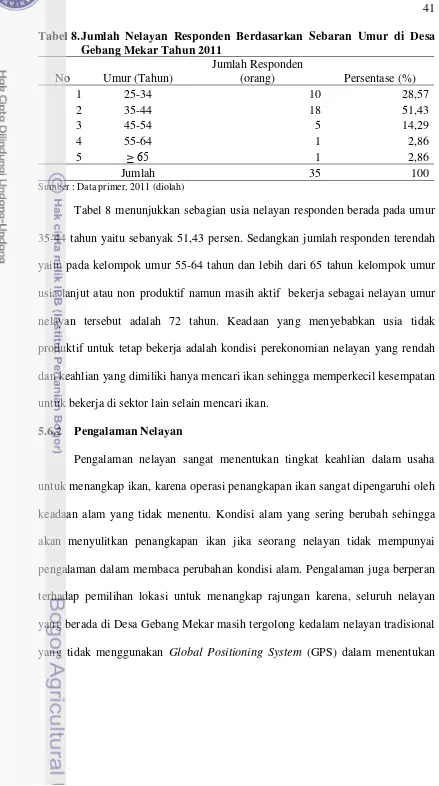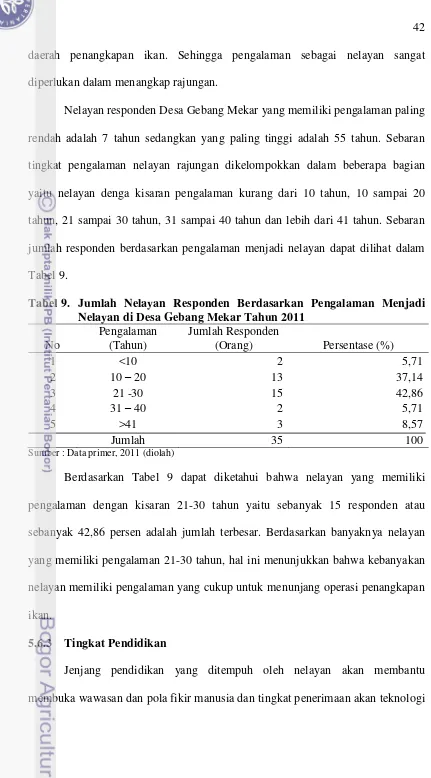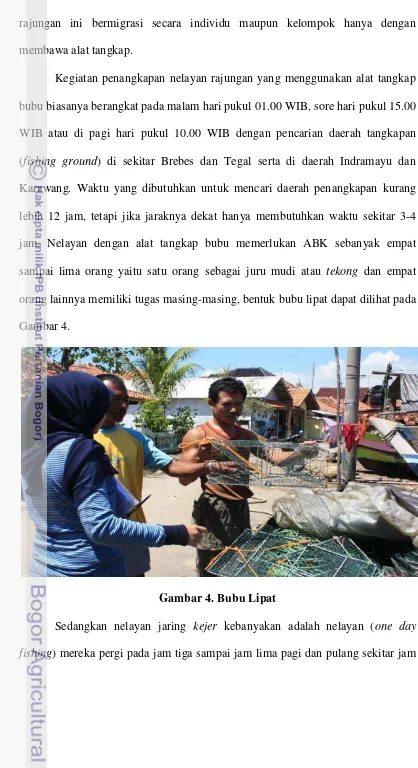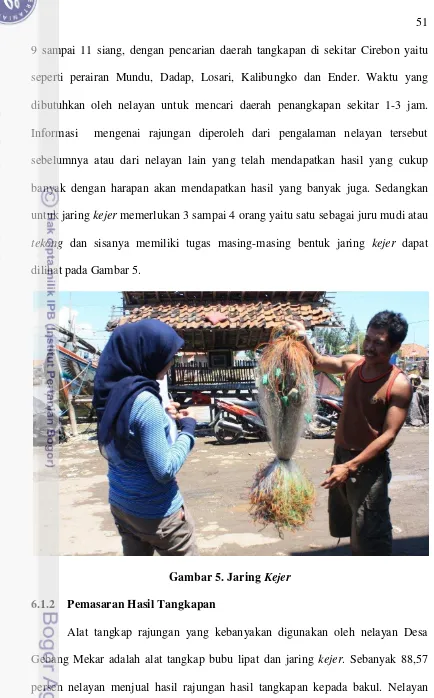MINIMUM LEGAL SIZE
RAJUNGAN (
Portunus pelagicus
)
TERHADAP NELAYAN DESA GEBANG MEKAR
KABUPATEN CIREBON
DINA SETRIANA
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
RINGKASAN
DINA SETRIANA. Analisis Perkiraan Dampak Ekonomi Kebijakan Minimum
Legal Size Rajungan (Portunus pelagicus) Terhadap Nelayan Desa Gebang Mekar
Kabupaten Cirebon. Dibimbing oleh TRIDOYO KUSUMASTANTO dan
RIZAL BAHTIAR.
Rajungan merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dieskpor ke berbagai negara. Kebutuhan ekspor rajungan sampai saat ini masih mengandalkan hasil tangkapan nelayan di laut sehingga untuk mengantisipasi peningkatan penangkapan rajungan yang tidak mencapai
maturity, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan
kebijakan minimum legal size. Banyak stakeholder yang terlibat dalam crab
fishery salah satunya adalah nelayan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui perkiraan dampak ekonomi kebijakan minimum legal size terhadap nelayan. Tujuan penelitian secara khusus yaitu: (1) mengidentifikasi karakteristik usaha nelayan rajungan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan rajungan; (3) memperkirakan nilai kesejahteraan nelayan rajungan sebelum dan setelah kebijakan minimum legal size; (4) menilai kelayakan usaha nelayan rajungan sebelum dan setelah kebijakan
minimum legal size dan (5) mengkaji penerapan kebijakan minimum legal zise.
Penelitian ini dilakukan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pengambilan data primer dilakukan pada bulan April-Mei 2011.
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik usaha nelayan rajungan yaitu yang terdiri dari operasi penangkapan nelayan, pemasaran hasil tangkapan, rumah tangga nelayan dan lingkungan sosial ekonomi nelayan. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan adalah jumlah hasil tangkapan, pengalaman dan jumlah alat tangkap. Analisis kesejahteraan rajungan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Metode analisis yang digunakan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Asumsi yang digunakan dalam NTN adalah semua hasil usaha perikanan tangkap dipertukarkan atau diperdagangkan dengan hasil sektor non perikanan tangkap. NTN dihitung untuk dua alat tangkap yaitu alat tangkap jaring kejer dan bubu lipat pada kondisi saat ini atau sebelum kebijakan minimum legal size dan apabila kebijakan tersebut diterapkan. NTN untuk nelayan jaring kejer sebelum kebijakan bernilai 0,69 dan setelah kebijakan bernilai 0,65. Sedangkan, NTN untuk nelayan bubu lipat sebelum kebijakan bernilai 0,82 dan setelah kebijakan 0,81. Berdasarkan hasil analisis, kesejahteraan nelayan rajungan saat ini dan apabila kebijakan minimum legal size diterapkan nilai NTN untuk nelayan jaring kejer mengalami penurunan sebesar 0,04 dan untuk nelayan bubu lipat mengalami penurunan sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan nelayan rajungan di Desa Gebang Mekar tidak bisa memenuhi kebutuhan subsistennya.
discount rate 6,75% menunjukkan NPV untuk jaring kejer saat ini sebesar Rp 10 087 241, Net B/C 1,97 dan IRR 14 persen dan setelah kebijakan nilai NPV sebesar Rp 2 972 450, Net B/C 1,49 dan IRR 9 persen. Hasil analisis untuk nelayan bubu lipat saat ini menunjukkan NPV sebesar Rp 19 683 730, Net B/C 2,07 dan IRR 17 persen, setelah kebijakan nilai NPV sebesar Rp 14 951 582, Net B/C 1,91 dan IRR 15 persen. Hasil analisis menunjukkan penurunan R-C ratio untuk nelayan jaring kejer dan bubu lipat sama sebelum dan setelah kebijakan. Namun, pada jangka panjang penurunan IRR untuk nelayan jaring kejer sangat signifikan yaitu sebesar 5 persen sedangkan untuk nelayan bubu lipat sebesar 2 persen. Hal ini disebabkan meskipun nelayan bubu lipat memerlukan banyak investasi namun hasil tangkapan rajungan yang ukurannya kurang dari 8,5 cm hanya 1 persen dan untuk nelayan jaring kejer 5 persen dari hasil tangkapannya. Sehingga, dengan adanya kebijakan minimum legal size sangat berpengaruh pada nelayan jaring kejer. Hasil analisis menunjukkan kebijakan minimum legal size berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan rajungan
Kata Kunci : Rajungan, Minimum Legal Size, Nelayan, Nilai Tukar Nelayan,
MINIMUM LEGAL SIZE
RAJUNGAN (
Portunus pelagicus
)
TERHADAP NELAYAN DESA GEBANG MEKAR
KABUPATEN CIREBON
DINA SETRIANA
H44070078
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
Judul Skripsi : Analisis Perkiraan Dampak Ekonomi Kebijakan Legal Minimum
Size Rajungan (Portunus pelagicus) terhadap Nelayan Desa
Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Nama : Dina Setriana
NIM : H44070078
Menyetujui,
Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2
Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS Rizal Bahtiar, S.Pi, M.Si NIP : 19580507 198601 1 001 NIP : 19800603 200912 1 006
Mengetahui, Ketua Departemen
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT NIP : 19660717 199203 1 003
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Analisis Perkiraan Dampak Kebijakan
Minimum Legal Size Rajungan (Portunus pelagicus) Terhadap Nelayan Desa
Gebang Mekar Kabupaten Cirebon adalah benar merupakan hasil karya bersama kerjasama dengan project Economic Evaluation of Implementing Minimum Legal
Size on Blue Swimming Crab Fishery in Indonesia yang diketuai oleh Bapak Rizal
Bahtiar S.Pi, M.Si yang didanai oleh EEPSEA dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya diterbitkan ataupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Bogor, Agustus 2011
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberi bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, terutama
kepada:
1. Mamah (Suwarni S.Pd), Bapak (E. Sadikin), kakak (Hennie Herawati dan
Henna Aditiana), Saudara Kembar (Diny Setriani) dan Dhery Mega Santika
atas segala dukungan, doa dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS (Pembimbing I) dan Bapak
Rizal Bahtiar S.Pi, M.Si (Pembimbing II) selaku dosen pembimbing skripsi
yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan, saran dan motivasi dalam
penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc. Selaku dosen penguji utama dan
Ibu Pini Wijayanti, SP, M.Si selaku dosen perwakilan departemen.
4. Ibu Pini Wijayanti, SP, M.Si. selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Agus, Bapak Supandi (Sekdes Desa), Bapak Nurdiyanto (Kaur
Pemerintahan), Bapak kiat dan seluruh masyarakat Desa Gebang Mekar dan
Gebang Kulon, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bagian
Perikanan Tangkap atas dukungan, data dan informasinya.
6. Rekan satu bimbingan Wezia Berkademi, Fandi W. Ikhsani, Frizka Amalia,
Ria Larastiti, Erlinda dan Astrid Yeyen atas bantuan, semangat dan
7. Dina Berina, Diyah A.P., Nadia Mutiarani, Kartika P.S., Ario B. Sandjoyo,
Bahrion I. Tampubolon, Andrian Irwansyah serta sahabat ESL 44 atas
kebersamaan dan dukungannya.
8. Ahmad Fajri Prabowo, Kriswindya Tasha, Novia F.P., Fithriyani Rahayu,
Rabiah A.S, serta rekan-rekan PSM IPB Agria Swara atas pengalaman,
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang
selalu memberikan rahmat serta karunia-Nya. Skripsi ini disusun sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen
Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut
Pertanian Bogor.
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
perkiraan dampak ekonomi kebijakan terhadap nelayan dimana dalam penelitian
ini adalah kebijakan minimum legal size di Desa Gebang Mekar Kabupaten
Cirebon. Kajian yang dilakukan meliputi karakteristik usaha nelayan rajungan
melalui analisis deskriptif, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan
rajungan melalui analisis linear berganda. Selain itu, dilakukan analisis
kesejahteraan nelayan sebelum dan setelah kebijakan minimum legal size serta
analisis pendapatan dan kelayakan usaha nelayan rajungan sebelum dan setelah
kebijakan. Penelitian ini juga mengkaji implikasi kebijakan minimum legal size
dan kebijakan lain yang dapat diterapkan bersama kebijakan ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Akhir kata,
semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian
sumberdaya perikanan.
Bogor, Agustus 2011
6.5.2.3 Biaya Perawatan Alat Tangkap ... 66
6.5.3 Biaya Operasional Penangkapan ... 67
6.6 Analisis Pendapatan Usaha Nelayan Rajungan ... 68
6.7 Analisis Kelayakan Usaha ... 71
6.8 Implikasi Kebijakan ... 72
VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 75
7.1 Kesimpulan ... 75
7.2 Saran ... 76
DAFTAR PUSTAKA ... 77
LAMPIRAN ... 80
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditi Tahun 2005-2007 .... 2
2 Jumlah sampel menurut unit penangkapan rajungan Desa Gebang Mekar ... 25
3 Matriks Metode Analisis Data ... 26
4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Gebang Mekar Tahun 2010 ... 35
5 Kelompok Umur Penduduk Desa Gebang Mekar Tahun 2008 ... 36
6 Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Tahun 2006-2010 Kabupaten Cirebon ... 37
7 Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Rajungan Tahun 2006-2010 Kabupaten Cirebon … ... 38
8 Jumlah Responden Berdasarkan Sebaran Umur Desa Gebang Mekar Tahun 2011 ………... ... 41
9 Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Desa Gebang Mekar Tahun 2011 ………….. ... 42
10 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Desa Gebang Mekar Tahun 2011 ... 43
11 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan Desa Gebang Mekar Tahun 2011 .. ... 44
12 Banyak Alat Tangkap di Kabupaten Cirebon Tahun 2006-2010 …. ... 45
13 Komponen Biaya Penyusutan Jaring Kejer…………... ... 63
14 Komponen Biaya Penyusutan Bubu Lipat ……… ... 63
15 Komponen Biaya Perawatan Perahu ……….. ... 65
16 Komponen Biaya Perawatan Mesin ... 66
17 Komponen Biaya Perawatan Alat Tangkap …………... ... 67
18 Komponen Biaya Operasional Jaring Kejer ... 68
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1 Spesies Rajungan Portunus pelagicus………. ... 9
2 Diagram Alur Kerangka Pemikiran ………. ... 23
3 Pelabuhan Pendaratan Ikan Desa Gebang Mekar ………. ... 39
4 Bubu Lipat ……… ... 50
5 Jaring Kejer………. ... 51
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1 Kuesioner penelitian ... 81
2 Data Karakteristik Responden Desa Gebang Mekar Tahun 2011 ... 84
3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Nelayan Rajungan Tahun 2011 86 4 Nilai Tukar Nelayan Rajungan Jaring Kejer Sebelum Kebijakan ... 90
5 Nilai Tukar Nelayan Rajungan Jaring Kejer Setelah Kebijakan ... 91
6 Nilai Tukar Nelayan Rajungan Bubu Lipat Sebelum Kebijakan ... 93
7 Nilai Tukar Nelayan Rajungan Bubu Lipat Setelah Kebijakan ... 93
8 Besarnya Penerimaan Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap Sebelum dan Setelah Kebijakan ... 94
9 Analisis Pendapatan Nelayan Rajungan Jaring Kejer Sebelum Kebijakan ... 95
10 Analisis Pendapatan Nelayan Rajungan Jaring Kejer Setelah Kebijakan ... 95
11 Analisis Pendapatan Nelayan Rajungan Bubu Lipat Sebelum Kebijakan ... 96
12 Analisis Pendapatan Nelayan Rajungan Bubu Lipat Setelah Kebijakan ... 96
13 Analisis Finansial Jaring Kejer Sebelum Kebijakan ... 97
14 Analisis Finansial Jaring Kejer Setelah Kebijakan ... 98
15 Analisis Finansial Bubu Lipat Sebelum Kebijakan ... 99
I.PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis
Indonesia mempunyai zona maritim yang sangat luas yaitu, sebesar 5,8 juta km2 yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0,8 juta km2, laut nusantara 2,3 juta
km2 dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km2. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17 480 pulau dan garis pantai sepanjang 95 181 km (Dewan
Kelautan Indonesia, 2008). Kekayaan sumberdaya alam yang begitu besar
menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, salah
satunya adalah potensi wilayah pesisir dan laut.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya
kelautan yang besar dan khususnya memiliki peluang sebagai salah satu negara
pengekspor produk sumberdaya perikanan. Pada tahun 2007, Indonesia
menempati posisi ke 12 negara pengekspor ikan di dunia yaitu sebesar dua persen,
sedangkan pada posisi pertama adalah China sebesar 11 persen, lalu Norwegia
sebesar tujuh persen dan Thailand enam persen1.
Salah satu hasil laut yang banyak dieskpor adalah rajungan (Portunus
pelagicus)-(Blue Swimming Crab). Rajungan merupakan komoditi ekspor
perikanan penting di Indonesia selain dari udang dan tuna. Pada Tabel 1 dapat
dilihat nilai ekspor hasil perikanan menurut komoditi pada tahun 2005-2007.
Komoditas udang dari tahun 2005-2007 menempati urutan pertama untuk nilai
1
www.waspada.co.id Diakses 28 Februari 2011
ekspor hasil perikanan. Komoditas udang memiliki nilai ekspor sebesar US$ 1
029 935 000 menurun dari tahun sebelumnya. Urutan kedua terdapat komoditas
tuna dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun dan memiliki nilai ekspor
pada tahun 2007 sebesar US$ 304 348 000. Urutan ketiga terdapat komoditas ikan
lainnya yang mempunyai nilai ekspor sebesar US$ 568 420 000. Urutan keempat
terdapat komoditas kepiting yang mempunyai nilai ekspor sebesar US$ 179 189
000.
Tabel. 1 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditi Tahun 2005-2007 (US$)
Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008
Total ekspor Rajungan selama bulan Januari-Mei 2010 mencapai 9 000 ton
dengan nilai US$ 84 juta apabila dirata-ratakan eksportir Indonesia mengirim
1 800 ton rajungan. Jumlah ini naik 13,68 persen jika dibandingkan dengan ekspor
2009 sebanyak 1 583,3 ton per bulan2.
Rajungan merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai
ekonomi yang tinggi dan dieskpor terutama ke Amerika dan seperti China,
Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia dan sejumlah negara Eropa lainnya.
Rajungan dalam bentuk segar di ekspor ke Singapura dan Jepang. Sedangkan
rajungan dalam bentuk olahan kaleng diekspor ke Belanda. Hingga saat ini
seluruh kebutuhan ekspor rajungan masih mengandalkan hasil tangkapan nelayan
di laut, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi populasi rajungan di alam.
2
Banyak stakeholder yang terlibat dalam crab fishery salah satunya adalah
nelayan, sedangkan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dan berakibat
pada tingkat kesejahteraan nelayan saat ini. Hal ini menunjukkan peningkatan
upaya penangkapan (catching effort) yang dilakukan oleh para nelayan dan tidak
menghasilkan manfaat ekonomis maksimal.
Guna mengantisipasi kecenderungan peningkatan penangkapan rajungan
yang berukuran kecil dan menyebabkan rajungan tidak bisa mencapai usia dewasa
untuk berkembang biak, diperlukan kebijakan untuk membatasi tingkat
pemanfaatan sumberdaya rajungan yang optimal dan berkelanjutan. Salah satu
cara yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan regulasi pendekatan ukuran
minimum atau minimum legal size sebagai dasar dalam merancang kebijakan
pemanfaatan sumberdaya perikanan rajungan yang berkelanjutan dan dampaknya
terhadap kesejahteraan nelayan rajungan.
Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon merupakan produsen penghasil
perikanan laut terbesar di Kabupaten Cirebon dengan produksi sebesar 9 144 ton
(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2010). Desa Gebang Mekar
adalah salah satu desa di Kecamatan Gebang yang sebagian besar penduduknya
bekerja sebagai nelayan yang menangkap rajungan. Alat tangkap rajungan yang
digunakan oleh nelayan disana adalah jaring kejer, bubu lipat dan jaring arad.
Namun, alat tangkap yang diperbolehkan untuk menangkap rajungan hanya jaring
kejer dan bubu lipat sedangkan jaring arad merupakan alat tangkap yang tidak
ramah lingkungan (illegal).
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebang Mekar merupakan salah satu
Kabupaten belum menerapkan kebijakan untuk rajungan dalam bentuk minimum
legal size sehingga kajian mengenai perkiraan dampak kebijakan ini dapat
menjadi referensi dalam penerapan kebijakan tersebut dan dampaknya bagi
nelayan sehingga dapat mengoptimalkan tingkat pemanfaatan sumberdaya
rajungan yang ada dengan memperhatikan keberlanjutan dari sumberdaya
rajungan dan kesejahteraan nelayan.
1.2 Perumusan Masalah
Saat ini Indonesia tidak mempunyai pengaturan terhadap penangkapan
rajungan, nelayan dapat menangkap rajungan dalam berbagai ukuran dan
menjualnya kepada tengkulak atau perusahaan-perusahaan rajungan. Penangkapan
ikan di bawah ukuran dapat menyebabkan penipisan stok, karena rajungan tidak
mencapai maturity. Berdasarkan beberapa penilitian disebutkan ukuran yang tepat
adalah sekitar 8,5-10 cm lebar cangkang. Sebagian besar perikanan di dunia mulai
dengan proses manajemen yang sederhana untuk melindungi stok spesies yang
banyak dieksploitasi. Pendekatan yang umum digunakan adalah dengan
menggunakan minimum legal size untuk menjamin bahwa spesies tersebut dapat
mencapai usia dewasa dan berkembang biak sebelum ditangkap oleh nelayan.
Implementasi kebijakan ini dalam perikanan dapat memiliki efek positif
dan negatif. Dalam jangka pendek dapat mengurangi jumlah penangkapan dan
akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Namun, dalam
jangka panjang maka stok ikan dapat dipertahankan, dengan kata lain para
nelayan akan mengalami kerugian pada jangka pendek namun akan meningkatkan
Indonesia merupakan negara kepualuan terbesar di dunia tetapi,
masyarakat dan nelayannya masih hidup di bawah tingkat kesejahteraan rata-rata
penduduk Indonesia. Kemiskinan masyarakat nelayan di daerah pesisir bersifat
struktural. Hal ini ditengarai karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar nelayan
seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan infrastruktur. Kurangnya
kesempatan berusaha, kurangnya akses informasi, teknologi dan permodalan,
menyebabkan posisi tawar nelayan semakin lemah. Data Kementerian Kelautan
dan Perikanan tahun 2010 menunjukkan, jumlah nelayan di Indonesia hingga
2008 mencapai 2 240 067 nelayan3.
Industri pengolahan rajungan dan perusahaan pengekspor rajungan serta
nelayan khawatir terhadap dampak negatif yang akan diterima jika regulasi
mengenai ukuran minimum diberlakukan. Hal ini akan merugikan nelayan dalam
waktu singkat, karena mereka akan lebih memilih untuk menangkap rajungan
ukuran kecil agar nelayan tetap mendapatkan penghasilan karena rajungan ukuran
besar semakin sulit untuk didapatkan terutama di daerah utara Jawa.
Namun, apabila pemerintah dan perusahaan tidak mengeluarkan kebijakan
untuk mengontrol penangkapan rajungan kecil akan memberikan dampak
ekonomi negatif pada industri, nelayan dan semua stakeholder yang terlibat dalam
perikanan tersebut. Selain itu, pemulihan stok ikan akibat deplesi jauh lebih sulit
daripada membuat kebijakan saat ini.
Permasalahan yang akan diteliti adalah:
1. Bagaimana karakteristik usaha nelayan rajungan saat ini?
3
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan nelayan rajungan saat
ini?
3. Berapa nilai kesejahteraan nelayan rajungan saat ini dan bagaimana
dampak ekonomi diterapkannya kebijakan minimum legal size?
4. Bagaimana kelayakan usaha nelayan rajungan saat ini dan dampak
diterapkannya kebijakan minimum legal size?
5. Apa saja instrumen kebijakan yang tepat untuk diterapkan agar kebijakan
minimum legal size dapat berjalan?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini
adalah :
1. Mengidentifikasi karakteristik usaha nelayan rajungan saat ini.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan
rajungan saat ini.
3. Memperkirakan nilai kesejahteraan nelayan rajungan saat ini dan setelah
minimum legal size.
4. Menilai kelayakan usaha nelayan rajungan saat ini dan setelah minimum
legal size.
5. Mengkaji penerapan kebijakan minimum legal size.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini bagi :
1. Bagi peneliti
Sebagai media pembelajaran dan penerapan ilmu ekonomi sumberdaya
2. Bagi akademisi
Sebagai bahan untuk menambah khasanah ilmu ekonomi sumberdaya dan
lingkungan.
3. Bagi pemerintah
Sebagai bahan acuan dalam menerapkan kebijakan terhadap sumberdaya
perikanan serta dampak positif dan negatif yang akan diterima oleh
masyarakat.
4. Bagi masyarakat
Sebagai bahan informasi mengenai dampak positif dan negatif dari sebuah
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
1.5 Batasan Penelitian
Penelitian ini memiliki batas-batas :
1. Terdapat tiga alat tangkap yang ada di tempat penelitian yaitu jaring kejer,
bubu lipat dan jaring arad. Namun, untuk semua analisis di skripsi ini
hanya berdasarkan dua alat tangkap yang legal yaitu jaring kejer dan bubu
lipat. Sedangkan, jaring arad tidak dihitung karena merupakan jaring yang
illegal.
2. Preferensi nelayan mengenai kebijakan tidak diteliti.
3. Kesejahteraan nelayan yang dibahas dalam penelitian ini hanya meliputi
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan subsisten nelayan.
4. Analisis yang digunakan dalam kelayakan usaha nelayan adalah benefit
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Klasifikasi Rajungan
Sistematika rajungan (Stephenson dan Chambell, 1959) adalah sebagai
berikut :
Kingdom : Animalia
Sub Kingdom : Eumetazoa
Grade : Bilateria
Divisi : Eucoelomata
Section : Protostomia
Filum : Arthropoda
Kelas : Crustacea
Sub Kelas : Malacostraca
Ordo : Decapoda
Sub Ordo : Reptantia
Seksi : Brachyura
Sub Seksi : Branchyrhyncha
Famili : Portunidae
Sub Famili : Portunninae
Genus : Portunus
Spesies : Portunus pelagicus
Beberapa jenis kepiting yang dapat berenang (swimming crab), sebagian
dimakan (edible portion) mengandung protein 65,72 persen; mineral 7,5 persen;
dan lemak 0,88 persen 4.
Sumber: unlimited4sedoyo.wordpress.com
Gambar 1. Spesies Rajungan (Portunus pelagicus)
2.2 Morfologi Rajungan
Secara umum morfologi rajungan berbeda dengan kepiting bakau,
rajungan memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan capit yang lebih
panjang dan memiliki berbagai warna yang menarik pada karapasnya. Duri akhir
pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih runcing. Rajungan hanya
hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup pada kondisi tanpa air. Bila
kepiting hidup di perairan payau, seperti hutan bakau atau di pematang tambak,
rajungan hidup di dalam laut. Rajungan memang tergolong hewan yang bermukim
di dasar laut.
Rajungan memiliki karapas berbentuk bulat pipih, sebelah kiri-kanan mata
terdapat duri Sembilan buah dimana duri yang terakhir berukuran lebih panjang.
Rajungan mempunyai lima pasang kaki, yang terdiri atas satu pasang kaki (capit)
berfungsi sebagai pemegang dan memasukkan makanan kedalam mulutnya, tiga
pasang kaki sebagai sebagai kaki jalan dan sepasang kaki terakhir mengalami
4
modifikasi menjadi alat renang yang ujungnya menjadi pipih dan membundar
seperti dayung. Oleh sebab itu rajungan digolongkan kedalam kepiting berenang
(swimming crab). Kaki jalan pertama tersusun atas daktilus yang berfungsi
sebagai capit, propodos, karpus dan merus.
Induk rajungan mempunyai capit yang lebih panjang dari kepiting bakau,
dan karapasnya memiliki duri sebanyak sembilan buah yang terdapat pada sebelah
kiri mata. Bobot rajungan dapat mencapai 400 gram, dengan ukuran sekitar 30 cm
(12 inchi). Rajungan bisa mencapai panjang 18 cm, capitnya kokoh, panjang dan
berduri. Rajungan mempunyai karapas berbentuk bulat pipih dengan warna yang
sangat menarik. Ukuran karapas lebih besar ke arah samping dengan permukaan
yang tidak terlalu jelas pembagian daerahnya. Sebelah kiri dan kanan karapasnya
terdapat duri besar, jumlah duri sisi belakang matanya sebanyak 9, 6, 5 atau 4 dan
antara matanya terdapat 4 buah duri besar.
Ukuran rajungan antara yang jantan dan betina berbeda umur yang sama.
Jantan lebih besar dan berwarna lebih cerah serta berpigmen biru terang. Lalu
betina berwarna lebih coklat. Rajungan jantan mempunyai ukuran tubuh lebih
besar dan capitnya lebih panjang daripada betina. Perbedaan lainnya adalah warna
dasar. Rajungan betina berwarna kehijau-hijuan dengan bercak-bercak putih agak
suram. Rajungan jantan berwarna kebiru-biruan dengan bercak putih terang.
Perbedaan ini jelas pada individu yang agak besar walaupun belum dewasa.
2.3 Karakteristik Rajungan
Salah satu hasil perikanan saat ini yang mulai berkembang pesat dan
mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi adalah rajungan. Rajungan berbeda
darat. Rajungan dapat dicirikan dengan warna karapasnya yang
bermacam-macam. Duri akhir pada kedua sisi kerapas relatif panjang dan runcing. Rajungan
ditemukan disetiap tempat yang perairan pantainya dangkal, kedalaman laut
antara 10-30 m, dilaut yang tidak berangin atau berombak besar, di payau, di
lubang pantai dan tambak.
Perairan Indonesia mempunyai beberapa jenis rajungan yang semuanya
dapat dimakan, tetapi tidak banyak dijumpai seperti rajungan biasa. Beberapa
rajungan yang terdapat di perairan Indonesia diantaranya rajungan angin
(Portunus sanguinalentus), rajungan karang (Hrybdis curciata) dan rajungan batik
(Chrybdis natator). Jenis rajungan yang umum dimakan ialah jenis jenis-jenis
yang termasuk cukup besar yaitu sub family portuniade dan podopthalminae.
Jenis rajungan yang terdapat di pasar-pasar Indonesia adalah rajungan bintang
(Portunus pelagicus) (Juwana dan Kasijan, 2000 dalam Gardenia ,2006).
2.4 Ukuran Kedewasaan Rajungan
Rajungan menjadi dewasa sekitar usia satu tahun. Ukuran saat kematangan
terjadi dapat berubah terhadap derajat garis lintang atau lokasi dan antar individu
di lokasi manapun. Betina terkecil rajungan yang telah diobservasi memiliki
moult/pergantian kulit yang cukup umur di Peel-Harvey Estuary ukuran terkecil
adalah 89 mm CW, sedangkan di Leschenault Estuary ukuran terkecil adalah 94
mm CW (Smith, 1982, Campbell & Fielder, 1986, Sukumaran & Neelakantan,
1996, dan Potter et al. 1998 dalam Gardenia, 2006). Karapas rajungan dapat
berkembang hingga 21 cm dan mereka dapat berukuran hingga seberat 1 kg
Rajungan di perairan Australia Selatan dikatakan legal jika panjangnya
lebih dari 11 cm yang diukur dari sisi ke sisi pada dasar tulang punggung atau
dasar duri. Batas ukuran sedang digunakan di semua perairan. Selama pemijahan
kemungkinan terdapat masa telur di bawah lapisan pada betina. Rajungan yang
masih ada telurnya dilindungi sepenuhnya di perairan. Rajungan pada ukuran
tersebut telah matang secara seksual dan telah memproduksi setidaknya 2
kelompok telur untuk satu musim (Kangas dalam Gardenia, 2006).
Rajungan mencapai dewasa kelamin pada panjang karapas sekitar 37 mm.
Dengan demikian rajungan-rajungan tersebut telah mampu bereproduksi. Adapun
yang mempunyai nilai ekonomis setelah mempunyai lebar karapas antara 95-228
mm (Rounsenfell, 1975 dalam Gardenia, 2006). Batasan ukuran rajungan yang
dianggap telah mencapai dewasa mempunyai beberapa pendapat diantaranya
adalah 9 cm CW dan 3,7 cm CL (Kumar et al. 2000, Rounsefell, 1975 dalam
Gardenia, 2006).
2.5 Nelayan
Nelayan merupakan bagian dari unit penangkapan ikan yang memegang
peranan penting dalam keberhasilan operasi penangkapan ikan. Peranan tersebut
didasarkan pada kemampuan nelayan dalam menggunakan dan mengoperasikan
alat tangkap serta pengalaman dalam menentukan fishing ground (daerah
penangkapan ikan).
Nelayan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun
2009 adalah orang yang melakukan pekerjaan menangkap ikan. Nelayan adalah
orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan
antara lain yaitu aspek pengadaan input, pemasaran dan pengolahan. Nelayan
diartikan sebagai orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan atau orang
yang ikut mengoperasikan peralatan tangkap dan orang yang mempunyai kapal.
Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan membuat jaring, mengangkat
alat-alat atau perlengkapan ke dalam kapal atau perahu tidak termasuk dalam kategori
sebagai nelayan. Orang yang bermatapencaharian sebagai nelayan memilliki
karakter keras, hal ini disebabkan kondisi alam yang dihadapi oleh para nelayan
yang ekstrim dan memiliki resiko yang besar.
Berdasarkan kepemilikan modal dan peralatan, nelayan dapat dibedakan
menjadi dua yaitu :
1. Nelayan juragan adalah orang yang memiliki modal, kapal dan peralatan
untuk menjalankan usaha penangkapan ikan.
2. Nelayan buruh atau Anak Buah Kapal (ABK) yaitu tenaga kerja yang
melakukan penangkapan dan pengangkutan hasil tangkapan.
Antara nelayan juragan dan buruh (ABK) terdapat perbedaan status sosial,
hal ini dikarenakan pembagian hasil tangkapan dari melaut. Juragan sebagai
pemilik modal dan peralatan mendapatkan bagian yang lebih besar dan ditambah
dengan biaya perawatan kapal dan peralatan, sedangkan buruh mendapatkan
bagian lebih kecil yaitu sisa bagian hasil dari juragan dan bagian tersebut
dibagi-bagi dengan buruh lainnya berdasarkan jumlah ABK yang ikut dalam kapal.
Nelayan dapat dibedakan berdasarkan teknologi yang dipakai untuk
aktivitas menangkap ikan di laut, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional.
Nelayan modern menggunakan metode dan peralatan dan penangkapan yang lebih
meningkatkan produksi semaksimal mungkin. Sedangkan, nelayan tradisional
hanya mengandalkan alam dan pengalaman untuk mencari ikan. Pengalaman
sangat penting dalam menentukan posisi kapal dan daerah penangkapan ikan.
Peralatan dan metode untuk mengangkap ikan juga sangat sederhana, oleh karena
itu hasil tangkapan yang diperoleh nelaya tradisional jauh lebih sedikit dibanding
dengan nelayan modern.
Berdasarkan waktu yang diperlukan untuk penangkapan ikan, nelayan
dapat menggolongkan sebagai berikut:
1. Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan
untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.
2. Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktunya
digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.
3. Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu
kerjanya digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.
Lamanya waktu yang dicurahkan sangat berpengaruh terhadap banyaknya
hasil tangkapan yang diperoleh, semakin lama waktu nelayan untuk menangkap
ikan maka akan semakin banyak ikan hasil tangkapan yang diperoleh sehingga
akan meningkatkan pendapatan nelayan (Monintja, 1989 dalam Yustiarani, 2008).
2.6 Return Cost Ratio (R-C Ratio)
Return Cost Ratio merupakan analisa yang bertujuan untuk menguji
seberapa jauh setiap nilai rupiah biaya yang dipakai dalam kegiatan cabang usaha
perikanan yang bersangkutan dapat memberikan sejumlah penerimaan.
Jika R-C ratio > 1, maka usaha perikanan yang dijalankan mengalami
kerugian, sedangkan bila R-C ratio = 1, maka cabang usaha perikanan ini tidak
rugi dan juga tidak untung (Soekartawi, 1995 dalam Santoso et al, 2005).
2.7 Benefit Cost Analysis (BCA)
Tujuan-tujuan analisis dalam analisis usaha harus disertai dengan definisi
biaya-biaya dan manfaat-manfaat. Biaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu
yang mengurangi suatu tujuan. Manfaat dapat diartikan sebagai segala sesuatu
yang membantu tujuan (Gittinger, 1986). Biaya dapat juga didefinisikan sebagai
pengeluaran atau korbanan yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap
manfaat yang diterima. Biaya-biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan pada
saat proyek mulai dilakukan, sedangkan biaya operasional adalah biaya yang
dikeluarkan pada saat proyek berjalan. Biaya operasional dibagi menjadi biaya
tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung
dari besarnya output yang dihasilkan. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya
berubah selama proses produksi. Biaya yang diperlukan suatu proyek dapat
dikategorikan sebagi berikut :
1. Biaya modal merupakan dana untuk investasi yang penggunaannya
bersifat jangka panjang.
2. Biaya operasional atau modal kerja merupakan kebutuhan dana yang
diperlukan pada saat proyek mulai dilaksanakan.
3. Biaya lainnya.
Sedangkan menurut (Kadariah, 1999), manfaat dapat dibagi menjadi tiga
bagian, yaitu :
1. Manfaat langsung (direct benefit) yang diperoleh dari adanya kenaikan
2. Manfaat tidak langsung (indirect benefit) yang disebabkan adanya proyek
tersebut dan biasanya dirasakan oleh orang tertentu dan masyarakat berupa
adanya efek multiplier, skala ekonomi yang lebih besar dan adanya
dynamic secondary effect.
3. Manfaat yang tidak dapat dilihat dan sulit dinilai dengan uang (intangible
effect).
Kriteria yang biasanya digunakan sebagai dasar persetujuan atau
penolakan suatu proyek adalah perbandingan antara jumlah nilai yang diterima
sebagai manfaat dari investasi tersebut dengan manfaat-manfaat dalam situasi
tanpa proyek. Nilai perbedaannya adalah berupa tambahan manfaat bersih yang
akan muncul dari investasi dengan adanya proyek (Gittinger, 1986). Kriteria
pertama adalah NPV (Net Present Value). Proyek atau kebijakan layak
dilaksanakan jika NPV > 1, jika NPV = 0 pengembalian proyek hanya untuk biaya
social opportunity dari modal dan tingkat suku bunga, sedangkan jika NPV < 0
proyek atau kebijakan tidak layak dilaksanakan. Kriteria kedua adalah BCR
(Benefit Cost Ratio). Jika nilai B/C lebih dari satu maka kebijakan atau proyek
layak untuk dilaksanakan. Namun, apabila nilai B/C kurang dari satu maka proyek
atau kebijakan tidak layak untuk dilaksanakan (Kadariah, 1999). Kriteria ketiga
adalah Internal Rate of Return (IRR). Jika hasil yang didapat IRR > i (tingkat
suku bunga) maka proyek atau kebijakan layak untuk dilaksanakan. IRR < i maka
proyek atau kebijakan tidak layak untuk dilaksanakan.
2.8 Nilai Tukar Nelayan
Konsep nilai tukar (terms of trade) umumnya digunakan untuk
diperdagangkan antara dua atau lebih negara, sektor atau kelompok sosial
ekonomi. Walaupun asal mula dan penggunaan yang lebih luas dari konsep ini
berasal dari perdagangan internasional, dewasa ini konsep nilai tukar juga sering
digunakan untuk membuat gambaran mengenai perubahan sistem harga dari
barang-barang yang dihasilkan oleh sektor produksi yang berbeda dalam suatu
negara. Penggunaan seperti ini timbul konsep mengenai nilai tukar sektor. Nilai
tukar menurut (Soeharjo et al, 1980 dalam Ustriyana, 2005) dapat digunakan
untuk keperluan dua macam analisis. Penggunaan yang pertama adalah sebagai
alat deskripsi (descriptive tool). Sebagai alat deskripsi konsep ini digunakan untuk
menerangkan dan menjelaskan secara statistik atau indeks mengenai
kecenderungan jangka pendek dan jangka panjang tentang sejarah kelakuan
barang-barang yang diperdagangkan. Penggunaan kedua yang sangat erat
hubungannya dengan pertama, adalah sebagai alat untuk keperluan penetapan
kebijakan (tool for policy).
NTN yang pada dasarnya merupakan indikator untuk mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif. Oleh karena indikator tersebut
juga merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan
subsistensinya, NTN juga disebut sebagai Nilai Tukar Subsisten (Subsistence
Terms of Trade). NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran
rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu (Basuki et al, 2001 dalam
Ustriyana, 2005). Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan kotor atau dapat
Perkembangan NTN dapat ditunjukan dalam Indeks Tukar Nelayan
(INTN). INTN adalah rasio antara indeks total pendapatan terhadap indeks total
pengeluaran rumah tangga nelayan selama waktu tertentu.
Asumsi dasar dalam penggunaan konsep NTN dan INTN tersebut adalah
semua hasil usaha perikanan tangkap dipertukarkan atau diperdagangkan dengan
hasil sektor non perikanan tangkap. Barang non perikanan tangkap yang diperoleh
dari pertukaran ini dipakai untuk keperluan usaha menangkap ikan, baik untuk
proses produksi (penangkapan) maupun untuk konsumsi keluarga nelayan, karena
data yang tersedia tidak memungkinkan untuk memisahkan barang non nelayan
yang benar-benar dipertukarkan dengan bahan pangan. Pengeluaran subsisten
rumah tangga nelayan dapat diklasifikasikan sebagai :
1. Konsumsi harian makanan dan minuman
2. Konsumsi harian non makanan dan minuman
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Perumahan
6. Pakaian
7. Rekreasi.
2.9 Regresi Linear Berganda
Regresi berganda (multiple regression model) dengan asumsi bahwa
peubah tak bebas (repons) Y merupakan fungsi linier dari beberapa peubah bebas
X1, X2, ..., Xk dan komponen sisaan e (error) (Juanda, 2009). Model ini
peubah bebas sehingga asumsi mengenai sisaan e, peubah bebas X dan peubah
tak-bebas Y juga sama.
Metode kuadrat terkecil OLS (Ordinary Least Square) digunakan untuk
mendapatkan koefisien regresi parsial. Metode OLS dilakukan dengan pemilihan
parameter yang tidak diketahui sehingga jumlah kuadrat kesalahan pengganggu
(Residual Sum of Square atau RSS) yaitu Σei minimum (terkecil). Pemilihan
model ini didasarkan dengan pertimbangan metode ini mempunyai sifat-sifat
karakteristik optimal, sederhana dalam perhitungan dan umum digunakan.
Menurut (Firdaus, 2004) asumsi utama yang mendasari model regresi berganda
dengan metode OLS adalah sebagai berikut :
1. Nilai yang diharapkan bersyarat (Conditional expcted Value) dari εi
tergantung pada Xi tertentu adalah nol.
2. Tidak ada korelasi berurutan atau tidak ada korelasi (non-autokorelasi)
artinya dengan Xi tertentu simpangan setiap Y yang manapun dari nilai
rata-ratanya tidak menunjukan adanya korelasi, baik secara positif atau
negatif.
3. Varian bersyarat dari ε adalah konstan. Asumsi ini dikenal dengan nama
asumsi homoskedastisitas.
4. Variabel bebas adalah nonstokastik yaitu tetap dalam pengambilan contoh
berulang jika stokastik maka didistribusikan secara independent dari
gangguan ε.
5. Tidak ada multikolinearitas antara variabel penjelas satu dengan lainnya.
6. Sisaan didistribusikan secara normal dengan rata-rata dan varian yang
Apabila semua asumsi yang mendasari model tersebut terpenuhi maka
suatu fungsi regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan pendugaan dengan
metode OLS dari koefisien regresi adalah penduga tak bias linier terbaik (best
linier unbiased estimator atau BLUE). Sebaliknya jika ada asumsi dalam model
regresi yang tidak terpenuhi oleh fungsi regresi yang diperoleh maka kebenaran
pendugaan model tersebut atau pengujian hipotesis untuk pengambilan keputusan
dapat diragukan. Penyimpangan 2, 3, dan 5 memiliki pengaruh yang serius
III.
KERANGKA PEMIKIRAN
Pemanfaatan sumberdaya alam merupakan sebuah fenomena yang tidak
bisa dihindarkan dan menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Pemanfaatan
sumberdaya ini akan semakin tidak terkendali dengan semakin berkembangnya
teknologi dan konsumsi masyarakat terhadap sumberdaya tersebut. Oleh karena
itu pengelolaan sumberdaya merupakan hal yang penting untuk menjaga
keberlanjutan sumberdaya tersebut. Apabila pengelolaan berbasis wawasan
lingkungan tidak dilakukan maka akan berdampak pada penurunan kualitas dan
kuantitas sumberdaya tersebut.
Kabupaten Cirebon adalah salah satu wilayah yang memberikan kontribusi
paling besar dari hasil penangkapan ikan di Provinsi Jawa Barat. Jumlah produksi
di Kabupaten Cirebon sebesar 19 875 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Barat, 2009). Rajungan adalah salah satu komoditas perikanan yang terdapat
di Kabupaten Cirebon dan merupakan sumberdaya perikanan yang mempunyai
nilai ekonomis tinggi, permintaan rajungan dari negara-negara seperti Amerika,
Belanda, China dan negara Asia lainnya sangat tinggi. Namun, kendala saat ini
adalah rajungan yang ditangkap oleh nelayan akhir-akhir ini telah menunjukan
adanya penipisan stok, rajungan semakin sulit didapatkan terutama di sekitar
Utara Laut Jawa.
Salah satu penyebab penipisan stok rajungan adalah penangkapan rajungan
yang belum sampai ke dalam tahap dewasa atau minimal berkembang biak satu
kali telah ditangkap oleh nelayan sehingga stok rajungan tidak berada dalam
kondisi yang berkelanjutan. Sehingga apabila tidak secepatnya diberlakukan suatu
sehingga bisa terjadi deplesi. Sedangkan pemulihan untuk stok deplesi jauh lebih
sulit daripada menerapkan kebijakan saat ini. Alat tangkap rajungan yang tidak
ramah lingkungan mempengaruhi jumlah populasi rajungan di alam, sehingga
penipisan stok tidak bisa dihindari. Hal ini berdampak secara ekonomi dalam
jangka pendek maupun jangka panjang terhadap semua stakeholder dalam crab
fishery. Jumlah rajungan yang semakin berkurang akan menimbulkan persaingan
antar nelayan. Salah satu kebijakan yakni minimum legal size dapat digunakan
untuk menjaga stok rajungan agar tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat
bagi nelayan dalam jangka panjang.
Kebijakan minimum legal size berdampak langsung terhadap pendapatan
nelayan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis mengenai karakteristik usaha
nelayan rajungan saat ini dan identifikasi mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi pendapatan nelayan. Apabila kebijakan minimum legal size
diterapkan, diduga terdapat dampak terhadap pendapatan nelayan maupun
kelayakan usaha nelayan rajungan.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dampak
positif dan negatif baik terhadap para stakeholder maupun sumberdaya rajungan.
Oleh sebab itu, perlu dilakukakan kajian mengenai instrumen kebijakan yang
sesuai agar keberlanjutan sumberdaya rajungan dapat dicapai. Secara singkat
Gambar 2. Diagram Alur Kerangka Pemikiran
Overfishing, alat tangkap yang tidak ramah
lingkungan.
Kebijakan berupa minimum legal size untuk menjaga stok rajungan agar tetap berkelanjutan dan memberikan mafaat bagi nelayan rajungan
Instrumen kebijakan yang tepat dalam kebijakan
IV. METODOLOGI PENELITIAN 4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Pengambilan data di lapangan dilakukan pada bulan April – Mei 2011.
Kegiatan penelitian meliputi tahap studi pustaka, pembuatan proposal,
pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian.
Lokasi penelitian bertempat di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon, Provinsi
Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja karena Kacamatan Gebang
merupakan produsen penghasil perikanan laut terbesar di Kabupaten Cirebon
dengan produksi sebesar 9 144 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Cirebon, 2010).
4.2 Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei. Berdasarkan
tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka metode penentuan lokasi penelitian
dilakukan dengan secara sengaja, karena Kecamatan Gebang Mekar merupakan
produsen rajungan terbanyak di Kabupaten Cirebon. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini
dilakukan analisis perkiraan dampak kebijakan terhadap nelayan rajungan dengan
dua alat tangkap jaring kejer dan bubu lipat.
4.3 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi
penelitian. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap unit
penangkapan rajungan serta wawancara menggunakan kuesioner kepada nelayan
sesuai dengan keperluan analisis dan tujuan penelitian. Kuesioner dapat dilihat
rajungan, nelayan dan para stakeholder di lokasi penelitian. Data sekunder berupa
produksi dan nilai produksi rajungan tahunan (time series data) Kabupaten
Cirebon, produksi dan nilai produksi seluruh komoditas perikanan Kabupaten
Cirebon, gambaran umum perikanan di Kabupaten Cirebon dan gambaran umum
wilayah penelitian, yang diperoleh melalui berbagai sumber data yang relevan
berupa buku referensi, laporan kegiatan, jurnal ilmiah, internet serta informasi dan
sumber dari instansi terkait. Mengingat keterbatasan sumberdaya penelitian
(tenaga, waktu dan dana) jumlah sampel yang akan diamati dibatasi
sekurang-kurangnya 10 persen dari unit populasi untuk setiap unit penangkapan rajungan
(bubu lipat dan jaring kejer). Perbandingan antara jumlah dengan populasi jenis
alat tangkap rajungan yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
Pemilihan unit tersebut dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan cara
memastikan diperolehnya sejumlah sampel yang mewakili populasi yang akan
diteliti (Mangkusubroto dan Trisnadi, 1985).
Tabel 2. Jumlah sampel menurut unit penangkapan rajungan di Desa Gebang Mekar
No Jenis Alat Tangkap Rajungan
Populasi
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2006
4.4 Metode Analisis Data
Data yang telah diperoleh lalu dikumpulkan kemudian diolah secara
kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data yang akan dilakukan dalam
Tabel 3.Matriks Metode Analisis Data
No Tujuan Penelitian Sumber Data Metode Analisis Data
1 Mengidentifikasi karakteristik Data primer Analisis deskriptif usaha nelayan saat ini
2 Mengidentifikasi faktor-faktor Data primer Regresi linear berganda
yang mempengaruhi
pendapatan nelayan
3 Memperkirakan nilai Data primer Nilai Tukar Nelayan
kesejahteraan nelayan (NTN)
4 Menilai kelayakan Data primer Cost Benefit Analysis
mata pencaharian dan Return Cost Ratio
Nelayan
5 Mengkaji instrumen Data sekunder Instrumen kebijakan
kebijakan yang tepat untuk
diterapkan agar regulasi
minimum legal size
tetap berjalan
4.4.1 Analisis Karakteristik Usaha Nelayan
Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji karakteristik usaha
nelayan rajungan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon adalah metode
analisis deskriptif. Metode ini adalah suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005). Metode
deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat serta hubungan
antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat (Whitney, 1960 dalam Nazir, 2005).
Beberapa hal yang dikaji dalam analisis deskriptif mengenai karakteristik
nelayan yang akan dijelaskan dengan menggunakan analisis deskriptif ini antara
lain operasi penangkapan nelayan, pemasaran hasil tangkapan, rumah tangga
diilakukan untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta
karakteristik nelayan saat ini.
4.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pendapatan nelayan. Pendapatan nelayan (Y) merupakan fungsi
dari beberapa variabel bebas, yaitu:
Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, D, e)
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tersebut dianalisis dengan
metode regresi linear berganda pada aplikasi Statistical Product and Service
Solution (SPSS) 15. Model yang digunakan adalah model regresi linear berganda.
Persamaan regresi besarnya pendapatan nelayan adalah sebagai berikut :
Yi = β0 + β1X1i - β2X2i + β3X3i+ β4X4i - β5X5i+ β6X6i–β7Di + εi
Dimana :
Yi = Pendapatan nelayan (Rp)
β0 = Intersep
β1,..β7 = Koefisien regresi
X1 = Jumlah hasil tangkapan (Kg)
X2 = Jumlah awak kapal (Orang)
X3 = Jumlah trip melaut (Hari)
X4 = Pengalaman (Tahun)
X5 = Jumlah biaya melaut (Rp)
X6 = Jumlah alat tangkap (Unit)
D = Pendapatan lain (ada = 1; tidak ada = 0)
ε = Galat
Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan teori-teori dan observasi ke
tempat penelitian.
4.4.3 Analisis Kesejahteraan Nelayan
Analisis data mengenai penurunan kesejahteraan nelayan adalah Nilai
Tukar Nelayan (NTN). NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total
pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu (Basuki dkk,
2001 dalam Ustriyana, 2005). Asumsi yang digunakan dalam NTN adalah semua
hasil usaha perikanan tangkap dipertukarkan atau diperdagangkan dengan hasil
sektor non perikanan tangkap. Barang non perikanan tangkap yang diperoleh dari
pertukaran ini dipakai untuk keperluan usaha penangkapan ikan, baik untuk proses
produksi (penangkapan) maupun untuk konsumsi keluarga nelayan. NTN dapat
dirumuskan sebagai berikut :
NTN = Yt/Et
Yt = YFt+YNFt
Et = EFt+EKt
Dimana :
Yt = Total penerimaan (Rp/Bulan)
YFt = Total penerimaan nelayan dari usaha perikanan (Rp/Bulan)
YNFt = Total penerimaan nelayan dari non perikanan (Rp/Bulan)
Et = Total pengeluaran (Rp/Bulan)
EFt = Total pengeluaran nelayan untuk usaha perikanan (Rp/Bulan)
EKt = Total pengeluaran nelayan untuk konsumsi keluarga nelayan (Rp/Bulan)
Analisis kesejahteraan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat
kesejahteraan nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya sebelum dan
setelah kebijakan.
4.4.4 Analisis Kelayakan Usaha Nelayan
Analisis kelayakan usaha rajungan digunakan untuk mengetahui apakah
usaha nelayan saat ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Digunakan
metode analisis return cost ratio untuk jangka pendek dan benefit cost analysis
(BCA) untuk jangka panjang.
4.4.4.1 Return Cost Ratio
Metode R-C ratio menunjukkan suatu nilai sebagai indikator apakah usaha
nelayan rajungan masih menguntungkan untuk dijalankan dalam jangka pendek
apabila kebijakan minimum legal size diterapkan. Besarnya biaya, pendapatan
dan R-C ratio menggunakan rumus (Hermanto, 1993 dalam Santoso et al, 2005):
Biaya produksi (C) : TC = TFC + TVC ………. (1) Keterangan:
TC = Total Cost / biaya total (Rp)
TFC = Total Fixed Cost / total biaya tetap (Rp)
TVC = Total Variable Cost / total biaya variabel (Rp)
Pendapatan (I) : I = TR – TC ; TR = y . Hy ………. (2) Keterangan:
I : Pendapatan (Rp)
TR : Total Revenue / total penerimaan (Rp)
TC : Total Cost / total pengeluaran (Rp)
y : Jumlah rajungan
R-C ratio:
(TR/TC) = Penerimaan (TR) ………. (3) Pengeluaran (TC)
Penyusutan:
Penyusutan = Biaya Investasi – Nilai Sisa ... (4)
Umur Teknis
Kriteria : R-C ratio > 1, maka usaha nelayan rajungan menguntungkan,
R-C ratio < 1, maka usaha nelayan rajungan tidak menguntungkan, R-C ratio = 1
maka usaha nelayan rajungan impas.
4.4.4.2Benefit Cost Analysis (BCA)
Benefit Cost Analysis (BCA) merupakan metode yang digunakan untuk
mengetahui kelayakan usaha nelayan dan apabila kebijakan minimum legal size
diterapkan. BCA menunjukkan nilai dari beberapa indikator untuk melihat
kelayakan usaha nelayan rajungan dalam jangka panjang. Tujuan-tujuan analisis
dalam analisis usaha harus disertai dengan definisi biaya-biaya dan
manfaat-manfaat. Tiga indikator yang harus dipenuhi untuk mengetahui apakah usaha
perikanan layak untuk diterapkan yaitu:
Net Present Value (NPV) merupakan selisih dari nilai investasi sekarang
dengan nilai penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Untuk
menghitung nilai sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga
yang dianggap relevan. Menurut Gray et al. (1993), formula yang digunakan untuk
menghitung NPV adalah sebagai berikut.
∑
Keterangan:
Bt = keuntungan pada tahun ke-t
Ct = biaya pada tahun ke-t
i = tingkat suku bunga (%)
t = periode investasi (t = 0,1,2,3,…,n)
n = umur teknis proyek
Proyek dianggap layak dan dapat dilaksanakan apabila NPV > 0. Jika NPV
< 0, maka proyek tidak layak dan tidak perlu dijalankan. Jika NPV sama dengan
nol, berarti proyek tersebut mengembalikan persis sebesar opportunity cost faktor
produksi modal.
Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) merupakan angka perbandingan antara
jumlah present value yang bernilai negatif (modal investasi). Perhitungan net B/C
dilakukan untuk melihat berapa kali lipat manfaat yang diperoleh dari biaya yang
dikeluarkan (Gray et al, 1993). Formulasi perhitungan net B/C adalah sebagai
berikut :
Jika net B/C bernilai lebih dari satu, berarti NPV > 0 dan proyek layak
dijalankan, sedangkan jika net B/C kurang dari satu, maka proyek sebaiknya tidak
Keterangan :
B = benefit
C = cost
i = discount rate
t = periode
IRR adalah discount factor yang membuat NPV = 0 dengan rumus yaitu :
Keterangan :
і' = nilai suku bunga yang menyebabkan NPV positif
і" = nilai suku bunga yang menyebabkan NPV negatif
NPV' = NPV dan tingkat suku bunga (і')
NPV" = NPV dengan tingkat suku bunga (і")
Jika hasil yang didapat IRR > і maka proyek atau kebijakan layak untuk
dilaksanakan. IRR < і maka proyek atau kebijakan tidak layak untuk
dilaksanakan.
Analisis finansial dilakukan dengan beberapa asumsi yang merupakan
prediksi terhadap kondisi yang tidak dapat diketahui secara pasti. Diharapkan
dengan asumsi yang ditetapkan hasil estimasi tidak akan berbeda nyata dengan
kondisi aktual di lapangan. Berikut asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan
finansial:
1. Harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada tingkat nelayan bukan
harga yang berlaku di pasar;
3. Umur proyek ditetapkan 10 tahun berdasarkan umur teknis komponen utama
usaha penangkapan yaitu kapal;
4. Discount factor yang digunakan merupakan tingkat suku bunga pinjaman BI
V. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 5.1 Letak dan Geografis Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang
terletak pada lintang 06°30’ LS-07°00’ LS dan 108°40’ BT. Wilayah tersebut
mempunyai ketinggian 0-130 m di atas permukaan laut. Kedalaman perairan
berkisar antara 0-20 m dengan dasar perairan lumpur dan lumpur berpasir. Secara
keseluruhan wilayah ini mempunyai luas 981 029 km2 dengan pantai sepanjang ±54 km (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon, 2011).
Gebang Mekar merupakan salah satu desa pantai yang berada di
Kecamatan Gebang dan merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Cirebon yang
berada di wilayah timur dengan luas wilayah 242 615 m2. Secara geografis Desa
Gebang Mekar berada pada posisi 108°43’5” BT dan 6°49’ LS. Desa Gebang
mekar secara administrasi terdiri dari empat dusun, 06 rukun warga (RW) dan 18
rukun tetangga (RT) yang dipisahkan oleh sungai tempat berlabuhnya kapal-kapal
nelayan. Desa Gebang Mekar terletak di wilayah paling utara Kecamatan Gebang,
dengan batas administratif sebagai berikut :
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Desa Gebang Ilir
Sebelah Selatan : Desa Gebang Ilir
Sebelah Barat : Desa Gebang Kulon
5.2 Topografis
Secara topografi Kabupaten Cirebon mempunyai ketinggian antara 0-130
meter di atas permukaan laut dan dibedakan menjadi dua bagian yaitu daerah
dataran rendah yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa antara lain:
Tengah Tani, Weru, Mundu, Astanajapura, Lemahabang, Pangenan,
Karangsembung, Waled, Babakan, Ciledug dan Losari, sedangkan lainnya
termasuk pada daerah dataran sedang dan tinggi. Iklim dan curah hujan di
Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri
dari daerah pantai, terutama bagian Utara, Timur dan Barat, sedangkan di sebelah
Selatan adalah daerah perbukitan. Desa Gebang Mekar terletak di daerah dataran
rendah yaitu di pesisir.
5.3 Demografi
Jumlah penduduk Desa Gebang Mekar berdasarkan data statistik pada
tahun 2010 tercatat sebanyak 6 341 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 3 339 atau 52,66 persen dan perempuan sebanyak 3 002 jiwa atau 47,34
persen (Desa Gebang Mekar, 2010). Mata pencaharian penduduk Desa Gebang
Mekar yaitu sebagai nelayan, petani, wiraswasta/pengusaha, buruh, Pegawai
Negri Sipil dan TNI POLRI. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa
Gebang Mekar adalah sebagai nelayan dengan presentase sebesar 91,80 persen,
kemudian diikuti oleh wiraswasta/pengusaha dengan presentase sebesar 5,77
persen. Daftar mata pencaharian penduduk Desa Gebang Mekar disajikan pada
Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gebang Mekar Tahun 2010 Mata Pencaharian Jumlah (orang) Presentase (%)
Petani 15 0,49
Jumlah penduduk di Desa Gebang Mekar dapat dikelompokan menjadi
tiga yaitu kelompok umur muda (0-17 tahun), kelompok usia kerja 18-56 tahun
(umur produktif) dan kelompok umur tua (56 tahun ke atas). Kelompok umur di
Desa Gebang Mekar dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5. Kelompok Umur Penduduk Desa Gebang Mekar Tahun 2008
Kelompok Umur Jumlah Penduduk (Orang)
0-17 1 807
18-56 3 749
56+ 746
Sumber : Desa Gebang Mekar, 2008 (diolah)
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Gebang
Mekar yang usia produktif lebih besar dari kelompok umur muda yaitu sebesar
3 749 orang sedangkan usia tua dari data sekunder sebesar 746 orang. Dengan
demikian sebagian besar penduduk Gebang Mekar dalam usia kerja (umur
produktif).
5.4 Potensi Sumberdaya Perikanan
Potensi sumberdaya ikan yang tertangkap terdiri dari berbagai jenis ikan
ekonomis penting. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di Kabupaten Cirebon
diantaranya ikan manyung (Arius thalassinus), kakap (Lates calcalifer),
bambangan (Lutjanus sanguineus), lidah (Cynoglossus bilineatus), pepetek
(Leiognathus splenden), ekor kuning (Caesio erythrogaster), kurisi (Nemipterus
hekodon), cucut (Hemigaleus argentata), pari (Dasyatis sp), bawal putih (Pampus
argentus), bawal hitam (Formio niger), alu-alu (Sphyraena sp), talang-talang
(Chorinemus tala), belanak (Mugil cepalus), kuro (Elentheronema tetradacty),
julung-julung (Hemirhampus sp), teri (Stolephorus sp), japuh (Dussumiera acuta),
tembang (Sardinella sp), kembung (Rastrelliger sp), tenggiri (Scomberomorus
putih (Penaeus merguiensis), cumi-cumi (Loligo sp) dan kepiting (Scylla serrata)
(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2011).
5.5 Kondisi Perikanan
Kondisi perikanan yang dimaksudkan adalah suatu gambaran tentang
keadaan perikanan yang meliputi produksi perikanan, sarana prasarana dan musim
dan daerah penangkapan ikan.
5.5.1 Produksi dan Nilai Produksi
Produksi perikanan merupakan salah satu andalan sebagai pemasukan
APBD bagi pemerintah Kabupaten Cirebon. Industri perikanan merupakan sektor
yang cukup penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten
Cirebon. Sektor ini dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi
pengangguran. Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan laut selama
periode 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Cirebon
Tahun
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon, 2011 (diolah)
Pada Tabel 6 di atas, pada tahun 2008 produksi perikanan laut mengalami
penurunan sebesar 23,50 persen dari produksi tahun sebelumnya yaitu 39 657,90
(ton) pada tahun 2007 menjadi 32 111,90 (ton). Namun penurunan terbesar terjadi
pada tahun 2010 produksi perikanan laut mengalami penurunan sebesar 29,06
persen dari produksi tahun 2009 yaitu dari 35 393,30 (ton) menjadi 27 424,00
Tabel 7. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Rajungan Tahun
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon, 2011 (diolah)
Produksi komoditi rajungan mengalami fluktuasi namun cenderung
mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2009,
produksi rajungan pada tahun 2008 sebesar 7 434,40 (ton) mengalami penurunan
pada tahun 2009 sebesar 2 969,30 (ton) penurunan tersebut sebesar 150,38 persen.
Produksi rajungan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2008
yaitu sebesar 7 434,40 (ton) dengan nilai produksi sebesar Rp 179 519 000,-
(Tabel 7).
5.5.2 Prasarana dan Sarana
Prasarana dan Sarana penunjang sangat penting untuk mendukung
kegiatan perikanan. Sarana prasarana dapat berupa dermaga yaitu tempat
bersandar dan merapat kapal ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), SPDN yang
berada di dekat dermaga kapal yang memudahkan nelayan untuk mengisi BBM,
KUD Mina Bahari sebagai lembaga keuangan bagi para nelayan, Kantor
Syahbandar dan Kepolisan Sektor Gebang, Pelabuhan Perikanan guna menunjang
kelancaran usaha perikanan, industri perikanan dan kegiatan usaha atau usaha lain
yang berkaitan dengan perikanan. Pelabuhan perikanan dapat dilihat pada Gambar