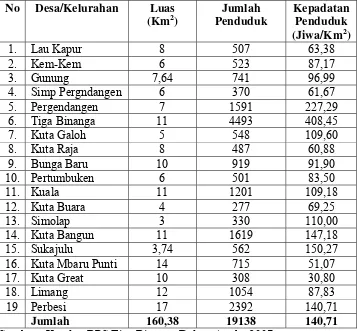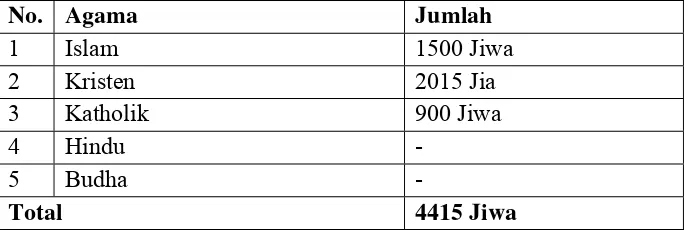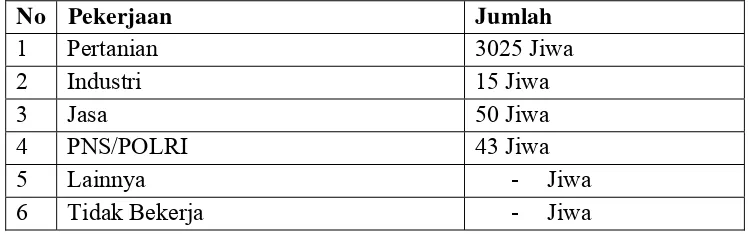ASIMILASI ANTARA PENDUDUK MIGRAN DENGAN PENDUDUK LOKAL
(Studi kasus : Interaksi Multietnis di Kelurahan Tigabinanga,Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo)
Oleh :
Sri Handayani Ginting
(100901075)
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
ABSTRAK
Keberadaan masyarakat yang majemuk tidak menutup kemungkinan untuk bisa hidup berbaur. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dihilangkan ketika masyarakat kembali menyadari bahwa ia adalah mahluk sosial dan berawal dari proses interaksi yang terjalin aktif sehingga menimbulkan suatu pengenalan satu akan yang lain. Keberadaan penduduk lokal (Suku Karo) yang dikenal memiliki nilai adat istiadat yang kental dan pembuka wilayah Kelurahan Tiga Binanga (Host Population), bisa menerima kedatangan para migran yang berasal dari daerah dan kebudayaan yang berbeda. Pekerjaan ganda yang dimiliki oleh penduduk lokal menjadikan mereka sangat membutuhkan bantuan jasa tenaga kerja guna membantunya dalam mengelola berbagai kegiatan atau usahanya. Interaksi yang mereka jalin terlihat bukan seperti hubungan majikan dan buruh namun terlihat seperti keluarga. Penduduk lokal mempercayakan kegiatannya dikerjakan oleh penduduk migran dan bukan oleh kerabatnya yang lain. Perbedaan yang ada otomatis membutuhkan banyak startegi bagi penduduk migran, untuk mendekatkan diri dan mengenal penuduk lokal yang memiliki latarbelakang kebudayaan yang berbeda dengannya. Hal tersebutlah yang pada saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga.
Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga merupakan lokasi penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan penghayatan. Penelitian ini dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) orang informan. 12(dua belas) penduduk migran dan 5 (lima) orang penduduk lokal.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya proses asimilasi antara penduduk migran dan penduduk lokal. Berawal dari interaksi yang aktif dan sikap masyarakat yang sama-sama saling menghargai satu sama lain serta lebih mementingkan tujuan bersama. Hubungan penduduk migran dan penduduk lokal menimbulkan rasa ketergantungan satu sama lain. Strategi yang dilakukan penduduk migran untuk mendekatkan diri dengan penduduk lokal berujung kepada hubungan kerja sama yang baik sehingga terbentuk suatu ikatan kekeluargaan. Penduduk migran diberikan penghormatan “Marga” dan berlanjut kepada adanya proses amalgamasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak bersikap etnosentrisme namun mau belajar dan mengenal kebudayaan yang lain dapat meningkatkan nilai teloransi selaku rakyat Indonesia dan hal tersebut menjadi kekayaan Bangsa Indonesia.
KATA PENGANTAR
Kemuliaan bagi Allah yang Esa yang Maha Kasih dan Adil. Oleh karena
anugerah-Nya semata, saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa
S1 di departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sumatera Utara. Saya sangat bersyukur oleh bimbingan-Nya melalui doa, firman,
dan dukungan orang-orang di sekeliling saya, Ia menyatakan kehendak-Nya
dalam mengarahkan saya sebagai mahasiswa yang takut akan Allah.
Dalam pengerjaan skripsi ini, saya menyadari keterbatasan saya dalam hal
pengetahuan, pengalaman, dan kelemahan lainnya sebagai mahasiswa. Namun, itu
tidak menjadi penghalang bagi saya untuk selalu berjuang memberikan yang
terbaik sebagai mahasiswa. Saya menyadari penyelesaian skripsi ini tidak terlepas
dari dukungan doa dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dukungan moral
maupun materil. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:
1. Kedua orang tua saya yaitu, Bapak B. Ginting dan Mamak K. Br Sebayang
yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta doa dalam setiap
keterbatasannya sebagai manusia, tetapi terus berusaha memberikan yang
terbaik untuk anak-anaknya. Untuk Biring, K’Maria, B’Darwan, Arya,
terimakasih untuk dukungannya.
2. Bapak Prof. Badarudin M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik yang juga pernah membimbing saya dalam memahami sosiologi.
3. Ibu Dr. Rosmiani, MA, selaku Sekretaris Dekan yang telah memberikan
motivasi dan semangat dalam belajar dan mengajarkan banyak ilmu
selama saya menjadi mahasiswa.
4. Ibu Dra. Lina Sudarwati, M.Si, selaku Ketua Departemen Sosiologi yang
telah memberikan pengajaran yang sangat berarti selama saya menjadi
seorang mahasiswa sehingga saya mengerti bagaimana seharusnya
menjadi mahasiswa yang berprestasi dan rajin dalam belajar.
5. Bapak Dr. Sismudjito, M.Si, selaku dosen pembimbing saya yang
memberikan pengajaran yang sangat berarti selama saya menjadi seorang
mahasiswa. Terimakasih untuk motivasi dan kasih sayang yang diberikan.
6. Seluruh dosen pengajar Departeen Sosiologi yang telah membimbing saya
selama saya menjadi mahasiswa.
7. Seluruh pegawai departemen dan pendidikan yang membantu dan
mendukung proses penyelesaan studi dalam urusan administrasi di
Departemen dan Pendidikan.
8. PKK dan teman-teman KTB saya, Calvary Evangelion, yaitu Kakak
Mutiara Ginting M.Sp, Yolanda Friscilia Pandia, Santiur Manurung.
Terimakasih atas persekutuan kita dalam belajar menjadi mahasiswa yang
takut akan Allah. Semoga kita menjadi garam dan terang dimanapun kita
berada.
9. Adik-adik rohani saya yang saya kasihi yaitu, Tania Naibaho (Sosiologi
2013) dan Bonar (Sosiologi 2013). Terimakasih atas doa dan perhatian
kalian. Semoga kalian juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan
mengerjakan studi kalian dengan tetap mengandalkan Tuhan.
10.TPP (Tim Pengurus Pelayanan) UKM KMK USU UP PEMA FISIP 2013
(Davit, Chintya, Kak Damai, Bang Mian, Chandra, Elisabet, Marisi,
Meriau, Yolanda, Santiur). Terimakasih atas dukungan dan motivasi
teman-teman, semoga kita menjadi alumni yang bisa menjadi berkat bagi
setiap orang.
11.Seluruh keluarga besar UKM KMK USU dan UKM KMK UP PEMA
FISIP, tetap semangat dalam mengerjakan tugas sebagai seorang murid
Kristus.
12.Seluruh keluarga besar IMKA EGUANINTA FISIP (B’Salmen Sembiring,
Terangta, Ginta, Jopy, Indah, Ana, Nobina, Sinta,) serta teman-teman dari
IMKA Universitas lain (Jefry, Philip, dll), mari kita tetap belajar mengenal
dan memlihara kebudayaan kita.
13.Seluruh sahabat dan rekan-rekan saya yang telah mendukung saya di
dalam doa. Buat kakak terkasih K’Desmi, K’Yanti, K’Melva, Sahabat saya
Nevo, Oki, ABSTEIN, B’Bowo, B’ Iwan Peyek, Lemon, Lyus, Dicky, dan
teman-teman lainnya.
14.Seluruh informan yang telah membantu saya dalam proses penelitian
skripsi.
15.Seluruh staf pegawai kantor Kelurahan Tiga Binanga.
Medan, Oktober 2014
DAFTAR ISI
ABSTRAK ... i
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR TABEL ... viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Rumusan Masalah ... 10
1.3 Tujuan Penelitian ... 10
1.4 Manfaat Penelitian ... 11
1.5 Defenisi Konsep ... 12
BAB II Tinjauan Pustaka 2.1Interaksi Sosial ... 14
2.2 Interaksionisme Simbolis ... 15
2.3 Hubungan Antar-Kelompok ... 18
2.4 Teori Asimilasi Budaya ... 19
2.5 Adaptasi Sosial ... 21
2.6 Amalgamasi ... 24
2.7 Teori Migrasi ... 25
3.2 Lokasi Penelitian ... 28
3.3 Unit Analisis dan Informan ... 29
3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 29
3.5 Interpretasi Data ... 31
3.6 Jadwal Kegiatan ... 31
BAB IV TEMUAN DATA DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ... 32
4.1.1Keadaan Geografis ... 32
4.1.2 Keadaan Penduduk ... 35
4.2 Profil Informan ... 38
4.2.1Profil Penduduk Migran ... 39
42.2 Profil Penduduk Lokal ... 64
4.3 Pola Asimilasi Antara Penduduk Migran dengan Penduduk Lokal . 72 4.3.1Terjalin interaksi yang baik ... 72
4.3.2 Terjalin Kerja Sama ... 74
4.3.3 Adanya Simbiosa Mutualisme ... 77
4.3.4 Terjalin Hubungan Kekeluargaan ... 79
4.3.5 Terjadi Amalgamasi ... 82
4.4 Strategi yang Dilakukan Oleh Penduduk Migran Sehingga Mampu Menjalin Kerja Sama dan Membentuk Kekeluargaan denegan Penduduk Lokal ... 85
4.4.2 Belajar Mengenal Nilai dan Norma di Tengah-Tengah
Masyarakat ... 86
4.4.3 Berusaha Mendekatkan Diri ... 87
4.4.3.1 Sering Berkunjung ke Rumah Penduduk Lokal ... 88
4.4.3.2 Memberi Makanan Kepada Tetangga atau Penduduk
Lokal ... 89
4.4.3.3 Meningkatkan Intensitas Pertemuan di Warung ... 90
4.4.3.4 Berpartisipasi di dalam Kegiatan-kegiatan
Sosial Budaya ... 91
4.4.4.4 Memperlihakan Kualitas Kerja ... 93
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ... 96
5.2 Saran ... 98
DAFTAR PUSTAKA ... 100
DAFTAR TABEL
4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/
Kelurahan Tahun 2007 Kecaamatan Tiga Binanga
4.2 Data Jumlah Penduduk di Kelurahan Tiga Binanga
4.3 Agama Penduduk di Kelurahan Tiga Binanga
4.4 Jumlah Sarana Ibadah
4.5 Jumlah Penduduk 10 (Sepuluh) tahun ke Atas Menurut Pekerjaan
4.6 Jumlah Usaha yang Ada di Desa
4.7 Data Penduduk Migran Berdasarkan Usia, Pendidikan Terakhir, Asal, dan
ABSTRAK
Keberadaan masyarakat yang majemuk tidak menutup kemungkinan untuk bisa hidup berbaur. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dihilangkan ketika masyarakat kembali menyadari bahwa ia adalah mahluk sosial dan berawal dari proses interaksi yang terjalin aktif sehingga menimbulkan suatu pengenalan satu akan yang lain. Keberadaan penduduk lokal (Suku Karo) yang dikenal memiliki nilai adat istiadat yang kental dan pembuka wilayah Kelurahan Tiga Binanga (Host Population), bisa menerima kedatangan para migran yang berasal dari daerah dan kebudayaan yang berbeda. Pekerjaan ganda yang dimiliki oleh penduduk lokal menjadikan mereka sangat membutuhkan bantuan jasa tenaga kerja guna membantunya dalam mengelola berbagai kegiatan atau usahanya. Interaksi yang mereka jalin terlihat bukan seperti hubungan majikan dan buruh namun terlihat seperti keluarga. Penduduk lokal mempercayakan kegiatannya dikerjakan oleh penduduk migran dan bukan oleh kerabatnya yang lain. Perbedaan yang ada otomatis membutuhkan banyak startegi bagi penduduk migran, untuk mendekatkan diri dan mengenal penuduk lokal yang memiliki latarbelakang kebudayaan yang berbeda dengannya. Hal tersebutlah yang pada saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga.
Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga merupakan lokasi penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan penghayatan. Penelitian ini dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) orang informan. 12(dua belas) penduduk migran dan 5 (lima) orang penduduk lokal.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya proses asimilasi antara penduduk migran dan penduduk lokal. Berawal dari interaksi yang aktif dan sikap masyarakat yang sama-sama saling menghargai satu sama lain serta lebih mementingkan tujuan bersama. Hubungan penduduk migran dan penduduk lokal menimbulkan rasa ketergantungan satu sama lain. Strategi yang dilakukan penduduk migran untuk mendekatkan diri dengan penduduk lokal berujung kepada hubungan kerja sama yang baik sehingga terbentuk suatu ikatan kekeluargaan. Penduduk migran diberikan penghormatan “Marga” dan berlanjut kepada adanya proses amalgamasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak bersikap etnosentrisme namun mau belajar dan mengenal kebudayaan yang lain dapat meningkatkan nilai teloransi selaku rakyat Indonesia dan hal tersebut menjadi kekayaan Bangsa Indonesia.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki sekitar 500-an suku
bangsa. Sejak berdiri, wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai kelompok etnik,
agama dan ras yang hidup bersama dalam suatu wilayah Indonesia.
Keanekaragaman yang berbeda-beda menjadi kekayaan bangsa Indonesia, setiap
suku yang ada didalamnya memiliki ciri-ciri dan latar belakang kebudayaan yang
berbeda yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki lima buah
pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan banyak lagi
pulau-pulau kecil yang ditempati oleh masyarakat Indonesia. Pulau-pulau tersebut
ditempati oleh suku-suku yang beranekaragam dengan bahasa, sikap, dan budaya
yang mencirikan jati diri mereka.
Bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi BHINEKA TUNGGAL IKA
yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang artinya bahwa masyarakat
Indonesia menghormati setiap perbedaan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa
yang ada didalamnya. Budaya dan kebiasaan yang khas pada suatu suku bangsa
merupakan salah satu ciri untuk membedakan antara suatu suku bangsa dengan
suku bangsa yang lain. Kekhasan itu dapat dianggap sebagai kebudayaan dari
suku bangsa yang bersangkutan. Keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat
Indonesia pada dasarnya adalah sebuah potensi untuk membentuk identitas kita
Kebudayaan suku bangsa salah satunya adalah tingkah laku atau prilaku
manusia baik dalam kehidupan sehari-harinya, maupun caranya ia berhubungan
dengan orang lain, karena hal tersebut menimbulkan interaksi. Setiap tindakan
yang ditunjukkan dari setiap suku bangsa yang berbeda biasanya akan
menimbulkan pola interaksi yang berbeda pula, seturut dengan latar belakang
budaya yang mereka miliki masing-masing.
Manusia memiliki naluri untuk senantiasa berhubungan dengan
sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pola
pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Manusia memiliki sifat yang
dapat digolongkan ke dalam manusia sebagai makhluk sosial artinya dituntut
untuk menjalin hubungan sosial dengan sesamanya. Hubungan sosial merupakan
salah satu hubungan yang harus dilaksanakan, mengandung pengertian bahwa
dalam hubungan itu setiap individu menyadari tentang kehadirannya di samping
kehadiran individu lain. Hal ini disebabkan bahwa dengan kata sosial berarti
“hubungan yang berdasarkan adanya kesadaran yang satu terhadap yang lain, di
mana mereka saling berbuat, saling mengakui dan saling mengenal atau mutual
action dan mutual recognition”. Manusia sebagai makhluk sosial, dituntut pula
ada kehidupan berkelompok, sehingga keadaan ini mirip sebuah community,
seperti desa, suku bangsa dan sebagainya yang masing-masing kelompok
memiliki ciri yang berbeda satu sama lain (Santosa, 1999:13).
Tidak dipungkiri bahwa selama manusia itu masih hidup maka manusia
tersebut akan melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut
menunjukan bahwa manusia tersebut adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup
aktivitas-aktivitas sosial. Melalui interaksi tersebut maka manusia mampu mengevaluasi
dirinya. Kehidupan masyarakat yang setiap harinya melakukan aktivitas guna
kelangsungan hidup, dimana interaksi terjadi melalui kontak sosial dan
komunikasi. Manusia senantiasa untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang
yang ada di sekitarnya. Arti penting dari komunikasi adalah bahwa seorang
memberikan tafsiran pada prilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan,
gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang
tersebut. Kontak sosial terjadi apabila orang yang bersangkutan kemudian
memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain
tersebut. Melalui komunikasilah masyarakat akan menjalin kerja sama (Soekanto,
1990:67).
Salah satu penelitian yang menunjukkan kehidupan masyarakat yang
majemuk dalam penelitian Novendra dan kawan-kawan dalam buku Integrasi
Nasional di Daerah Riau Suatu Pendekatan Budaya tentang hubungan sosial
penduduk ”asal” dengan ”pendatang” yaitu masyarakat Melayu dan Banjar.
Terjalinnya hubungan sosial menimbulkan kerja sama dalam berbagai aspek
kehidupan. Bidang ekonomi misalnya, interaksi terjadi di pasar. Pedagang di pasar
Tembilahan adalah orang-orang Banjar, hanya sebagian kecil dari Cina dan
Minang. Para penduduk melayu yang bertindak sebagai pembeli, berinteraksi
dengan parapenjual dari Banjar. Bentuk kerja sama lain terlihat dalam lingkungan
tempat tinggal yang membaur dengan lingkungan RT atau RW dan membentuk
kelompok arisan. Dari bidang sosial kerjasama mereka terlihat pada
peristiwa-peristiwa hari raya, pesta perkawinan atau sunat Rasul, upacara keagamaan,
Melayu dan Banjar baik, akrab dan saling tenggang rasa diakibatkan karena
pemukiman mereka yang membaur dan mereka memiliki satu keyakinan agama
(Novendra dkk, 1995/1996 : 25-26).
Contoh kasus di atas yang membahas pola interaksi masyarakat Banjar dan
Melayu memperlihatkan meskipun mereka memiliki banyak perbedaan baik dari
kebudayaan dan prilaku namun tetap saja mereka dapat bekerjasama dalam
aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh kondisi tempat tinggal
mereka yang membaur dan keyakinan yang sama, namun bagaimana pola
interaksi masyarakat jika masyarakat Indonesia yang melakukan migran hidup di
suatu daerah dengan banyak perbedaan dan dalam lingkungan tempat tinggal yang
tidak membaur. Tidak semua hubungan antar kelompok etnik mengarah kepada
konflik. Keberagaman kelompok etnik dan perbedaan budaya yang ada dalam
suatu masyarakat juga dapat menghasilkan hubungan kerja sama, bahkan
pembauran antar kelompok etnik dalam interaksi sehari-hari secara alamiah.
Dalam konteks sehari-hari kita juga dapat merasakan perbedaan budaya dan
keberagaman kelompok etnik tidak serta merta menjadi halangan dalam
berinteraksi. Hal itu justru merupakan potensi masyarakat yang secara positif
dapat dikembangkan sebagai unsur-unsur pembentuk identitas masyarakat
Indonesia (Wirutomo, 2012:88).
Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia
yang terdiri dari berbagai etnis yaitu Batak, Angkola atau Mandailing, Melayu
dan Nias, serta terdapat juga berbagai daerah di dalamnya. Kabupaten Karo
merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Karo
dalam bahasa aslinya disebut Kalak Karo merupakan salah satu suku asli di
Sumatera Utara. Suku ini memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Karo atau
Cakap Karo dan aksaranya sendiri. Bramderisco. 2010. Suku Karo
http://bramderisco.wordpress.com/tag/suku‐karo/. diakses 7 Maret 2014, pukul
21.31 WIB.
Kabanjahe sebagai Kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Karo
merupakan salah satu wilayah yang memiliki masyarakat majemuk. Kabanjahe
dominan ditempati oleh masyarakat asli suku Karo dan beberapa suku pendatang
lainnya. Suku Karo ini mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara
dengan baik dan sangat mengikat bagi suku Karo sendiri. Masyarakat Karo kuat
berpegang kepada adat istiadat yang luhur, merupakan modal yang dapat
dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Dilihat dari letak geografis Tanah Karo
maka mata pencarian utama masyarakat Karo adalah pertanian dan peternakan.
Penduduk asli di daerah Kabanjahe adalah masyarakat Suku Karo. Meskipun di
Kabanjahe didomisili oleh masyarakat Suku Karo, namun tidak terpungkiri
persebaran masyarakat baik dari kalangan Suku lain juga tetap terjadi. Hal
tersebut dapat dilihat dari keanekaragaman masyarakat yang tinggal dan bekerja
di Kabanjahe. Suku Karo yang merupakan mayoritas dari penduduk Kabanjahe,
yaitu 60% dari keseluruhan penduduk kota ini. Selain dari Suku Karo masih ada
suku-suku lain di Kabanjahe, seperti Suku Toba, Simalungun, Dairi,
Minangkabau, Jawa dan Cina. Payung, 1981. Pelapisan sosial di Kabanjahe.
Jakarta: UI FISIP
http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=91277&lokasi=lokal,
Persebaran masyarakat yang berasal dari suku lain menjadikan semakin
tingginya keanekaragaman di wilayah Kabanjahe dan semakin memungkinkan
adanya interaksi sosial didalamnya. Sejauh ini meskipun pulau Sumatera
memiliki berbagai macam suku namun hingga saat ini belum pernah ditemukan
konflik antara suku didalamnya. Demikian juga dengan daerah Kabanjahe yang
penduduk aslinya adalah Suku Karo yang hingga pada saat ini juga belum pernah
ditemukan kerusuhan antar etnik. Terlihat meskipun dengan beranekaragam suku
yang ada didalamnya menjadikan interaksi masyarakat semakin meningkat dan
hidup saling menghormati perbedaan. Dapat diartikan bahwa dengan
keanekaragaman tersebut tidak menjadi konflik bagi masyarakat.
Masyarakat yang tinggal di Kabanjahe terdiri dari berbagai ragam etnik,
bukan hanya Suku Karo. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya dijumpai
rumah peribadatan masyarakat baik Mesjid dan bangunan Gereja suku seperti
GBKP (Gereja Batak Karo Protestan), GKPS (Gereja Kristen Protestan
Simalungun ), HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), keragaman suku yang
meningkatkan tingkat interaksi juga terdapat di daerah Tiga Binanga yang
merupakan salah satu daerah Kecamatan di wilayah Kabanjahe. Penduduk asli
masyarakat Tiga Binanga adalah Suku Karo atau diidentikkan dengan etnis yang
lebih dahulu menghuni teritori pemukiman. Mereka hidup dengan bekerja sebagai
petani dan akrab dengan alam. Kehidupan masyarakat di Kecamatan Tiga Binanga
tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Karo. Kehidupan masyarakat yang
terdapat di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga yang menjadi tuan
tanah (host population) dengan sistem kebudayaan yang masih kental dengan
hingga saat ini tetap dipertahankan yang biasa disebut dengan sangkep nggeluh.
Yaitu suatu sistem kekeluargaan pada masyarakat Karo yang secara garis besar
terdiri atas senina, anak beru dan kalimbubu (Tribal Collibium) ( Prinst, 2008:43).
Masyarakat Suku Karo memiliki lahan perladangan yang luas karena
nenek moyang mereka merupakan pembuka tanah (Host Population) di wilayah
Tiga Binanga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sejarah berdirinya wilayah
Kelurahan Tiga Binanga yang dahulunya dikepalai oleh Ngadang Sebayang yang
menjadi pemimpin selama empat dasawarsa di Kelurahan Tiga Binanga. Hingga
saat ini yang menjadi tuan tanah di wilayah Kelurahan Tiga Binaga adalah
bermarga Sebayang yang merupakan keturunan dari Ngadang Sebayang yang
menjadi pembuka Kelurahan tersebut. Menjabat menjadi Kepala Kampung selama
46 tahun menjadikan keturunan dari beliau memiliki warisan tanah yang luas,
hingga sekarang masyarakat tetap mempertahankan sistem pertanian sebagai salah
satu sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Irwan. 2011.
Silima Merga. Tanah Karo. (http://silima‐
merga.blogspot.com/2011/02/gambaran‐umum‐kecamatan‐tiga‐binanga.html
diakses pada tanggal 11 Februari 2014, pukul 8.29 WIB).
Kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Tiga Binanga
dapat dikatakan memiliki semangat tinggi dalam bekerja. Terlihat hampir
keseluruhan masyarakat bekerja keras guna meningkatkan pendapatan
perekonomian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Misalnya saja
dilihat dari semangat kerja masyarakat Suku Karo, meskipun mereka memiliki
lahan pertanian yang luas namun masyarakat tidak hanya sepenuhnya berprofesi
usaha dagang, baik membuka pertokoan, rumah makan dan layanan sosial lainnya,
ada juga masyarakat yang berjualan ketika tiba hari selasa yang merupakan hari
pekan bagi masyarakat Kecamatan Tiga Binanga. Selain itu ada juga masyarakat
yang membuat usaha home industry, misalnya seperti menganyam tikar,
membuat kursi dari bahan bambu. Artinya masyarakat memiliki pekerjaan ganda
sehingga membutuhkan orang lain guna membantu mengelola pekerjaannya.
Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 Kabupaten Karo,
Kalvin Sitepu sebagai kordinator BPS Kecamatan Tiga Binanga menyatakan
bahwa kondisi kehidupan sosial ekonomi meningkat di Kelurahan Tiga Binanga.
Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata pendapatan hasil panen masyarakat
khususnya dari sektor pertanian ladang sawah yaitu mencapai 356 ton/Ha/tahun.
Jadi hal tersebut dapat menjadi salah satu pemicu banyaknya masyarakat yang
berasal dari luar daerah Tiga Binanga tertarik untuk datang dan mencari
pekerjaan. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi penduduk Kelurahan Tiga
Binanga dapat dilihat dari semakin tingginya kesadaran para masyarakat akan
pentingnya peran pendidikan dalam memperbaiki kualitas kehidupan serta
semakin bersemangatnya penduduk bekerja dalam upaya meningkatkan
pendapatan ekomoni.
Kalvin. 2013.Tiga Binanga dalam angka. Kabanjahe : BPS
(http://karokab.bps.go.id/data/publikasi/kca030_13/files/search/searchtext.xml
diakses 11 Februari 2014, pukul 21.00 WIB).
Penduduk migran yang datang dan memasuki Kelurahan Tiga Binanga
berasal dari suku Jawa, Batak Toba , Padang dan Nias. Beberapa suku yang ada di
Sumatera seperti Suku Batak Toba, Padang dan Nias memiliki suatu ciri budaya
suku-suku tersebut untuk mengadu nasib. Hal ini disebabkan karena masyarakat di
Kelurahan Tiga Binanga memiliki lahan perladangan yang luas dan secara
otomatis membutuhkan pekerja yang banyak guna mengerjakan kegiatan
pertanian. Selain itu juga banyak ditemukan usaha-usaha masyarakat yang
membutuhkan pekerja sehingga menjadi suatu peluang bagi penduduk migran
untuk memperoleh pekerjaan. Peningkatan luas lahan panen masyarakat mencapai
676 ha/tahun serta hasil produksi mencapai 2407 ton/tahun. Kalvin. 2013.Tiga
Binanga dalam angka. Kabanjahe : BPS
(http://karokab.bps.go.id/data/publikasi/kca030_13/files/search/searchtext.xml
diakses 11 Februari 2014, pukul 21.30 WIB). Hal tersebut menjadikan anggota
keluarga tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan ladangnya. Maka dari itu
mereka membutuhkan banyak tenaga kerja guna membantu mereka dalam
mengelola pekerjaannya. Pada awalnya kegiatan pertanian dikerjakan oleh kerabat
atau keluarga sipemilik lahan secara bergotong-royong, namun sekarang justru
migran tersebut yang mengambil alih sebagai pekerja. Penduduk lokal justru
mengajak para migran untuk bekerjasama dengannya dalam mengelola lahan
pertaniannya. Padahal penduduk lokal memiliki kerabat-kerabat yang dapat diajak
untuk bekerja sama dalam megelola pekerjaan ladangnya. Namun penduduk lokal
mempercayakan para migran yang tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk
bekerjasama. Hal yang menjadi sorotan lainnya adalah hubungan antara penduduk
migran dengan penduduk lokal tersebut tidak hanya sebatas hubungan majikan
dengan pekerja. Namun hubungan mereka menjadi terlihat lebih akrab satu
dengan yang lainnya. Berawal dari interaksi yang kerap dilakukan sehingga
memungkinkan juga timbulnya pola asimilasi di tengah-tengah kehidupan
masyarakat.
Maka dari itulah penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pola
diharapkan terlihat jelas adanya pola asimilasi di tengah-tengah kehidupan
masyarakat. Termasuk didalamnya strategi adaptasi seperti apa yang dilakukan
oleh penduduk migran sehingga mereka dapat membentuk kerja sama dan sistem
kekerabatan dengan penduduk lokal yang ada di daerah Kelurahan Tiga Binanga.
1.2Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah dijelaskan melihat kondisi wilayah
Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo yang
memiliki jenis tanah yang subur dan penduduk lokal tersebut hidup dengan
sistem peradatan yang masih kental. Namun kondisi wilayah saat ini terlihat ramai
didatangi oleh penduduk migran yang berasal dari suku dan kebudayaan yang
berbeda dengan penduduk lokal, namun dapat membentuk suatu sistem
kekerabatan dan menjalin kerja sama. Untuk itu adapun yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana Pola asimilasi penduduk Migran dengan Penduduk Lokal di
Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo ?
2. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh Penduduk Migran
sehingga mampu menjalin kerja sama dan membentuk kekeluargaan
dengan penduduk lokal di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga
Binanga?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan yang
1. Dari analisa mengetahui bagaimana pola asimilasi penduduk Migran dan
Penduduk Lokal yang ada di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga
Binanga Kabupaten Karo serta bagaimana strategi yang mereka lakukan
untuk membentuk kerja sama dan menjalin sistem kekerabatan.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman
peneliti beserta para pembacanya guna meningkatkan pemahaman akan
kehidupan masyarakat.
1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat teoritis
a. Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber
informasi dalam pengembangan ilmu khususnya sosiologi Pedesaan,
Sosiologi Keluarga dan Hubungan Antar-Kelompok.
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber dan masukan bagi
pembacanya guna lebih memahami kehidupan masyarakat sosial
khususnya lebih mengetahui bagaimana pola asimilasi penduduk
Migran dengan Penduduk Lokal serta bagaimana strategi yang
dilakukan oleh pendatang migran sehingga membentuk kerja sama
dan menjalin sistem kekerabatan di Kelurahan Tiga Binanga
kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.
1.4.2Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis
dalam membuat karya ilmiah dan dapat menjadi bahan rujukan bagi
1.5 Definisi Konsep a. Asimilasi
Asimilasi adalah Suatu proses sosial dimana seseorang diperhadapkan
dengan kebudayaan asing dan kebudayaan asing tersebut disaring dan
diterima namun kebudayaan asing tersebut tidak merubah kebudayaan
aslinya. Dalam hal ini menjelaskan adanya asimilasi yang berawal dari
interaksi sosial antara masyarakat lokal (Host Population) yaitu
masyarakat Suku Karo dengan masyarakat Migran yang berasal dari Suku
Jawa, Batak Toba, Padang dan Nias. Bermula dari interaksi sosial
sehingga adanya proses asimilasi, setelah hal tersebut terealisasikan
sehinnga memungkinkan terjadinya suatu proses amalgamasi di
tengah-tengah masyarakat.
b. Penduduk Lokal
Penduduk lokal merupakan masyarakat yang tinggal di dalam suatu daerah
dengan tetap menerakpan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang
mereka atau yang lebih dahulu menghuni teritori pemukiman (host
population). Masyarakat lokal (asli) juga memiliki salah satu dari marga
yang terdapat di wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat memiliki lahan
serta usaha-usaha yang membutuhkan bantuan orang lain dalam mengelola
pekerjaannya.
c. Penduduk Migran
Penduduk migran adalah orang-orang yang melakukan migrasi. Migrasi
adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dan
potensi untuk mendapatkan pekerjaan guna memperbaiki tingkat
prekonomian. Perpindahan tersebut juga cenderung menghasilakan proses
amalgamasi di daerah yang ditempati.
d. Strategi Adaptasi
Strategi merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok
untuk menghasilkan suatu fokus yang ingin dicapai. Dalam menjalankan
strategi tersebut pasti ditemukan usaha dan kerjasama antara satu dengan
yang lainnya. Adaptasi merupakan penyesuaian diri oleh penduduk migran
dengan penduduk lokal. Dalam strategi adaptasi ini masyarakat migran
datang dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan serta aturan yang terdapat di
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 1nteraksi Sosial
Interkasi sosial dapat diartikan oleh para ahli seperti S.S Sargent yang
berpendapat bahwa interaksi sosial pada pokoknya memandang tingkah laku
sosial yang selalu dalam rangka kelompok seperti struktur dan fungsi dalam
kelompok. Tingkah laku sosial dipandang sebagai akibat adanya struktur
kelompok seperti struktur dan fungsi kelompok. H. Bonner memberi rumusan
interaksi sosial adalah hubungan antara dua atau lebih individu manusia ketika
kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki
kelakuan individu lain, atau sebaliknya (Sentosa, 2009:11).
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bentuk umum proses sosial adalah
interaksi sosial, oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya
aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial
yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara
kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok
manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu.
Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin
berkelahi.
Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara
kelompok tersebut sebagai kesatuan. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala
Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat,
yaitu:
A. Adanya kontak sosial (sosial-contact)
Dalam bahasa latin cum (bersama-sama) dan Tango (menyentuh).
Secara harafiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak
baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, sebagai gejala sosial itu
tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, oleh karena orang dapat
mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Kontak
sosial dapat pula bersifat primer dan skunder. Kontak primer terjadi
apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan
muka. Sebaliknya kontak yang skunder memerlukan suatu perantara.
B. Adanya komunikasi
Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Dalam komunikasi
kemungkinan seringkali terjadi pelbagai macam penafsiran terhadap
tingkah laku orang lain. Seulas senyuman, misalnya dapat ditafsirkan
sebagai keramah-tamahan, sikap bersahabat itu bahkan sebagai sikap sinis
dan sikap ingin menunjukan kemenangan. Dengan demikian komunikasi
memungkinkan kerja sama antara orang perorangan atau anatara
kelompok-kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah
satu syarat terjadinya kerja sama (Soekanto, 1990 :61-64).
2.2 Interaksionisme Simbolik
Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai
interactionism). Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George Herbert Mead.
Dari kata interaksionisme sudah nampak bahwa sasaran pendekatan ini ialah
interaksi sosial, kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam
interkasi.
Herbert Blumer dalam Kamanto Sunarto (2004: 35-36), salah seorang
penganut pemikiran Mead, berusaha menjabarkan pemikiran Mead mengenai
interaksionisme simbolik. Menurut Blumer pokok pikiran interaksionisme
simbolik ada tiga :
A. Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (Thing) atas dasar makna
(meaning) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya.
B. Makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atau muncul dari
interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya.
C. Makna diperlukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran
(interpretative process), yang digunakan orang menghadapi sesuatu yang
dijumpainya.
Blumer dalam buku Poloma (2010:263) menyatakan keistimewaan
pendekatan kaum interaksionis simbolis ialah manusia dilihat saling menafsirkan
atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi
kepada setiap tindakan itu menurut metode stimulus-repon. Seseorang tidak
langsung memberi respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian
yang diberikan kepada tindakan itu. Ia menyatakan, “dengan demikian interaksi
manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh
kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain, Dalam kasus perilaku
stimulus dan repon”. Blumer berpandangan tidak mendesakkan prioritas dominasi
kelompok atau struktur, tetapi melihat tindakan kelompok sebagai kumpulan dari
tindakan inividu: “masyarakat harus dilihat sebagai terdiri dari tindakan
orang-orang, dan kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan-tindakan orang itu”.
Blumer menunjukan ide ini dengan menujukan bahwa kelompok yang demikian
merupakan respon pada situasi-situasi dimana orang menemukan dirinya.
Interaksionisme-simbolis yang diketengahkan Blumer dalam Margaret M.
Poloma (2010 : 264-266) mengandung sejumlah “root images” atau ide-ide dasar,
yang dapat diringkas sebagia berikut:
A. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi
B. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan
kegiatan manusia lain.
C. Obyek-obyek, tidak mempunyai makna yang intrinsik ; makna merupakan
produk interaksi-simbolis.
D. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat
dirinya sebagai obyek.
E. Tindakan manusia adalah tindakan interpretative yang dibuat oleh manusia
itu sendiri.
F. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota
kelompok: hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai;
“organisasi sosial dari prilaku tindakan-tindakan berbagai manusia”.
Sebagian besar tindakan bersama terlumer dalam Polsebut berulang-ulang
dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai
2.3 Hubungan Antar-Kelompok
Pembahasan menegnai hubungan antar kelompok cenderung dipusatkan
pada deskripsi dan penjelasan hubungan sosial anatara kelompok yang statusnya
berbeda. Kata kelompok dalam konsep hubungan antar kelompok mencakup
semua kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria ciri fisiologis,
kebudayaan, ekonomi dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi kelompok
minoritas dapat dikaji dengan menggunakan dimensi sejarah, demografi, sikap,
institusi, gerakan sosial dan tipe utama hubungan antar-kelompok. Suatu bentuk
hubungan yang banyak disoroti dalam kajian terhadap hubungan antar-kelompok
ialah hubungan mayoritas-minoritas. Dalam defenisi Kinloch kelompok mayoritas
ditandai oleh adanya kelebihan kekuasaan, konsep mayoritas tidak dikaitkan
dengan jumlah anggota kelompok. Adapula ilmuan sosial yang berpendapat
bahwa konsep mayoritas didasarkan pada keunggulan jumlah anggota (Sunarto,
2004 :143-149).
Stanley Liberson mencoba mengklasifikasikan pola hubungan antara
kelompok. Menurutnya kita dapat membedakan antara dua pola utama: pola
dominasi kelompok pendatang atas pribumi (migrant superordination), dan pola
dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang (indigenous
Superordination). Menurut Liberson perbedaan pola hubungan
superordinasi-subordinasi antara migran penduduk asli menentukan pola hubungan antara kedua
kelompok.
Dominasi pribumi di bidang ekonomi dan politik, di pihak lain, kurang
memancing konflik dengan pihak migran yang didominasi. Penguasa pribumi
Kelompok pribumi dominan, di pihak lain, berusaha mempertahankan dominasi
mereka dengan jalan mengendalikan jumlah dan jenis migran yang masuk dalam
masyarakat mereka. Dalam situasi dominasi penduduk setempat, di pihak lain,
kelompok migran cenderung mengasimilasikan diri dengan penduduk setempat
(Sunarto, 2004 :150-151).
Melihat kondisi saat ini, Kelurahan Tiga Binanga banyak dikunjungi oleh
para migran yang berasal dari berbagai Daerah dengan berbagai perbedaan baik
ekonomi, kebudayaan dan ciri pisiologis. Maka dari itu akan terjadi hubungan
antar-kelompok yaitu adanya hubungan yang terjalin antara masyarakat Suku
Karo sebagai penduduk pribumi serta mendominasi wilayah teresebut dengan
penduduk migran yang berasal dari Suku Jawa, Batak Toba, Padang dan Nias.
Adanya perbedaan kebudayaan menyebabkan terjadinya proses saling
mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki kelakuan individu sesuai dengan
nilai dan norma yang berlaku di Kelurahan Tiga Binanga. Hubungan
antar-kelompok juga terlihat dari adanya proses asimilasi dan amalgamasi pada
masyarakat Kelurahan Tiga Binanga , sehingga dalam penelitian ini saya
menyoroti hal tersebut di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Tiga Binanga
kecamatan Tiga Binanga.
2.4 Teori Asimilasi Budaya
Arti dari kata asimilasi menurut Koentjaraningrat (2002: 248) adalah proses
sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan
tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan
sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima
dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya
Koentjaraningrat (2002: 255) mengatakan bahwa asmilasi timbul bila ada,
golongan- golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda- beda,
saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga,
kebudayaan- kebudayaan golongan- golongan tadi masing- masing berubah sifat
khasnya, dan juga unsur- unsurnya masing- masing berubah wujudnya menjadi
unsur- unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara
suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu
biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan
golongan mayoritas, sehingga sifat- sifat khas dari kebudayaan lambat- laun
berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan Mayoritas.
Asimilasi merupakan adanya usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang
terdapat diantara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan
meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan
proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama. (Setiadi dan Kolip,
2011: 81). Apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok
manusia atau masyarakat, maka dia tidak akan lagi membeda-bedakan dirinya
dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai
orang asing. Dalam proses asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan
kepentingan-kepentingan secara tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok
manusia mengadakan asimilasi, batas-batas anatara kedua kelompok tadi dengan
pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional,
dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi
(Soekanto, 1990 : 81).
A. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi antara
lain:
1. Teloransi
2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi
3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya
4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat
6. Perkawinan campur (amalgamation)
7. Adanya musuh bersama dari luar (Setiadi dan Kolip 2011: 83-84).
2.5 Adaptasi Sosial
Walaupun konsep tindakan sosial tetap dipakai sebagai dasar teori,
perburuan intelektual Parsons dalam Poloma (2010: 171 ) secara perlahan ternyata
bergeser dari tekanan atas tindakan sosial ke struktur dan fungsi masyarakat.
Parsons melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial
bisa terorganisir. Disamping itu terdapat dua sistem tindakan lain yang saling
melengkapi yaitu ; sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol-simbol
serta sistem kepribadian para pelaku individual. Sistem sosial individu menduduki
satu tempat (status), dan bertindak (peranan) sesuai dengan norma atau
aturan-aturan yang dibuat oleh sistem.
Konsepsi Parsons mengenai Teori Induk dimana Parsons setuju terhadap
kesatuan ilmu-ilmu prilaku, yang keseluruhannya meruapakan suatu studi tentang
sistem yang hidup (living system). Dia menyatakan bahwa konsep fungsi
merupakan inti untuk memahami semua sistem yang hidup. Dia menekankan
bahwa sistem yang hidup itu adalah sistem terbuka yaitu mengalami saling
pertukaran dengan lingkungannya.
Functional imperatives atau prasyarat. Ciri-ciri umum yang ada dalam
seluruh sistem yang hidup adalah prasyarat atau functional imperative. Menurut
Parsons terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus
dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting
1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan
sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (sumbu
internal-eksternal), dan
2) yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana
yang perlu untuk mencapai tujuan itu (sumbu
instrumental-consummatory).
Berdasarkan premis itu secara deduktif Parsons menciptakan empat
kebutuhan fungsional. Keempat fungsi primer itu, yang dapat dirangkaikan
dengan seluruh sistem yang hidup adalah Latent pattern-maintenance (L),
integration (I), Goal attainment (G) dan Adaptation (A). Dalam hal ini kita akan
membahas mengenai adaptasi. Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi
sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungan. Ada dua dimensi masalah yang
pertama, harus ada penyesuaian diri sistem itu terhadap tuntutan kenyataan yang
keras yang tidak dapat diubah (inflexible) yang datang dari lingkungan (atau kalau
menggunakan terminology Parsons yang terdahulu, pada kondisi tindakan).
Kedua, ada proses transformasi aktif dari situasi itu. Ini meliputi penggunaan
segi-segi situasi itu yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.
Tetapi, usaha untuk memperoleh alat itu secara analisis harus dipisahkan dari
pencapaian tujuan. Lingkungan, meliputi yang fisik yang sosial. Untuk suatu
kelompok kecil, lingkungan sosial akan terdiri dari satuan intitusional yang lebih
besar dimana kelompok itu berada. (Dalam studi Bales mengenai kelompok kecil,
lingkungan itu adalah lingkungan akademis). Untuk sistem-sistem yang lebih
sistem-sistem sosial lainnya (masyarakat lain) dan lingkungan fisik (Jhonson,
1990 : 130).
Persons menyatakan bahwa adaptasi merupakan Kebutuhan fungsional
berupa kemampuan sistem menjamin kebutuhannya dari lingkungan dan
mendistribusikan sumber-sumber itu ke seluruh sistem; dalam masyarakat fungsi
ini dilakukan oleh sistem ekonomi (Poloma, 2010: 170-181).
Contohnya dalam buku Suprapti dan kawan-kawan yang berjudul adaptasi
migran musiman terhadap lingkungan tempat tinggal daerah khusus ibukota
Jakarta Raya dimana masyarakat yang berpindah tersebut bertujuan untuk bekerja
dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Di tempat perantauan
hubungan sosial dengan warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya hanya
terbentuk dalam hubungan sepintas lalu atau saling kenal. Namun demikian,
dengan beberapa warga biasanya tetangga bersebelahan rumah hubungan sosial
cukup akrab. Hubungan akrab terwujud dalam saling bertandang dan
berbincang-bincang, saling memberi makan, saling memberi bantuan dan sebagainya, yang
mereka wujudkan karena frekuensi tatap mukanya cukup tinggi. Dengan mereka
yang pergi ke Jakarta bekerja sebagai penjaja bakso dan penjaja sayur juga
memiliki hubungan interaksi yang cukup baik dengan warga disekitar tempat
tinggal mereka. Terlebih lagi bagi para pelanggan dagangannya serta hubungan
dengan pemilik kontrakan.
Bentuk hubungan yang mereka wujudkan cukup mendalam atau akrab
yang tercermin pula dalam kehidupan sehari-harinya, bersenda-gurau,
mengungkapkan masalah yang dialami, memberikan makanan dan memberi
dagang secara kekeluargaan. Supaya banyak pembeli dan dagangan cepat laku,
para penjaja sayur bersikap ramah dan berusaha melayani dengan sebaik-baiknya
dan memberi pelanggan berhutang dengan bayar bulanan. Sementara hubungan
dengan pejabat RT setempat terjalin dengan cara berpartisipasi dan mematuhi
peraturan yang berlaku, misalnya memberi sumbangan untuk kegiatan perayaan
hari-hari besar nasional, memberi sumbangan untuk warga RT yang kemalangan,
membayar iuran keamanan dan iuran sampah khusus bagi migran yang
mengontrak. Serta migran juga tetap menjalin hubungan dengan keluarga di
daerah asal mereka (Suprapti dkk, 1990: 167-187).
2.6 Amalgamasi
Perkawinan campur (amalgamation) agaknya merupakan faktor paling
menguntungkan bagi lancarnya proses asimilasi. Hal itu terjadi apabila seorang
warga dari golongan tertentu menikah dengan warga golongan lain. Apakah itu
terjadi antara golongan minoritas dan mayoritas dan sebaliknya. Proses asimilasi
dipermudah dengan adanya kawin campur walau memakan waktu yang agak
lama. Hal ini disebabkan oleh karena antara penjajah dan yang dijajah terdapat
perbedaan-perbedaan ras dan kebudayaan. Penjajah pada mulanya tidak
menyetujui perkawinan campur dan ini memperlambat proses asimilasi. Setelah
waktu yang relatif agak lama penjajah biasanya memperistri wanita-wanita warga
masyarakat yang dijajahnya. Apabila dari mereka yang dijajah ada yang
dipekerjakan (sebagai budak, pegawai rendahan dan sebagainya), maka golongan
dengan cara memperluas kebudayaan penjajah di kalangan masyarakat yang
dijajah (Soekanto, 1990 :80-84).
Isu-isu pembaruan antara warga pribumi dan nonpribumi, perkawinan antara
suku, antar ras yang terpisah-pisah sebagaimana yang pernah disosialisasikan oleh
pemerintah diharapkan mampu menekan perpecahan antar kelomok suku, agama,
ras dan antargolongan (Setiadi dan Kolip 2011 : 84). Amalgamasi juga ditemukan
di Kelurahan Tiga Binanga dimana adanya perkawinan campur antara penduduk
migran dengan penduduk lokal. Penduduk migran yang berasal dari kebudayaan
yang berbeda dengan penduduk lokal bersatu dan menghasilkan budaya
campuran.
2.7 Teori Migrasi
Migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi
permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya,
yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa. Migran biasanya
mempunyai alasan-alasan tertentu yang menyebabkan mereka meninggalkan
kampung halamannya dan seterusnya memilih tempat-tempat yang mereka
anggap dapat memenuhi kalau sekiranya tetap bertahan di tempat asal. Migran
akan bergerak dari tempat yang kurang berkembang menuju daerah-daerah yang
lebih maju. Alasan migran paling utama meninggalkan negara/daerah asal
adalah karena faktor ekonomi, terutama disebabkan sukarnya menapatkan
pekerjaan, serta wujudnya keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih
Proses migrasi terjadi sebagai jawaban terhadap adanya sejumlah
perbedaan antartempat. Perbedaan tersebut menyangkut faktor-faktor ekonomi,
sosial dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat. Faktor
ekonomi merupakan faktor primer yang mempengaruhi migrasi. Faktor ekonomi
tersebut seperti mobilitas jabatan (mobilitas sosial), upah yang lebih tinggi,
kesempatan kerja yang lebih banyak dan lainnya. Aswatini mengemukakan
bahwa alasan pindah biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya,
dan keamanan, kesulitan ekonomi, tekanan penduduk dan faktor geografis
(Nasution, 1999: 109-110).
Secara teoritis pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, negara, kawasan
ataupun daerah tertentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan mendasar dalam
segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan pola konsumsi masyarakat
misalnya merupakan salah satu aspek yang terlihat paling memonjol. Aktivitas
migrasi yang belangsung dari wilayah ke wilayah tertentu pun merupakan imbas
positif yang berkembang sebagai konskuensi pertumbuhan ekonomi daerah
bersangkutan. Makin baik perkembangan ekonomi suatu wilayah maka
kemungkinan terjadinya perkembangan volume migrasipun makin tinggi.
Kedatangan migran kedalam suatu wilayah dapat juga menimbulkan
etnosentrisme misalnya dalam penelitian Muba Simanihuruk mengenai interaksi
antara migran pendatang dengan penduduk lokal studi tentang interaksi antara
migran Batak toba, Tionghoa dan Melayu di Pangkalan Brandan. Hasil
penelitian menunjukkan, ertnis Melayu menganggap (terutama) etnis Tionghoa
bersifat licik dan tidak dapat disaingi lagi karena mereka telah menguasai
menjadi pekerjaan utama mereka. Kebencian yang sama juga ditujukan oleh
kelompok etnis Batak Toba dengan tingkatan yang lebih rendah, dengan
tuduhan bahwa kelompok etnis Tionghoa “pintar”menipu. Namun pada dimensi
kultural dan agama, mereka masih bisa berafilasi. Bahkan dalam kegiatan
ekonomi, etnis Batak Toba dan Tionghoa melakukan kerjasama ekonomi yang
saling menguntungakan, dimana etins Batak Toba menyewakan rumah-rumah
mereka di pusat bisnis kota dengan harga relatif mahal pada kelompok
orang-orang Tionghoa. Simbioasa mutualisme juga terjelma pada saat kelompok etnis
Tionghoa meminjam modal kepada etnis Toba yang berprofesi sebagai rentenir
(bank berjalan). Sebaliknya terjadi dengan etnis Melayu dimana secara kultural
berbeda jauh dengan kelompok etnis Batak Toba dan Tionghoa di samping
perbedaan secara ekonomi. Di kubu lain, etnis Tionghoa merasa diperlakukan
secara diskriminatif oleh pemerintah dan sering dijadikan sapi perahan baik oleh
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus. Studi kasus sebagai kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa
tertentu. Studi kasus (case study) merupakan penelitian yang penelaahannya
kepada suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam dan mendetail.
Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang dapat menghasilkan data
, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati (Moleong,2006). Dengan demikian
peneliti akan memperoleh data atau informasi lebih mendalam mengenai Pola
asimilasi antara penduduk lokal dengan migran pendatang.
3.2Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tiga Binanga kecamatan Tiga
Binanga kabupaten Karo Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih judul ini karena
peneliti cukup memahami daerah lokasi penelitian dan mengenal masyarakat yang
tinggal di daerah tersebut sehingga memudahkan si penliti dalam mengambil dan
mengumpulkan data karena kemudahan mengambil data adalah hal yang
terpenting dan signifikan dalam sebuah penelitian. Peneliti melihat bahwa pada
kondisi saat ini daerah kelurahan Tiga Binanga ramai sekali didatangi oleh para
3.3 Unit Analisis dan Informan 3.3.1 Unit Analisis
Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah :
3.3.1.1Pola asimilasi penduduk migran dengan penduduk lokal. Di
mana penduduk lokal (asli) adalah masyarakat Suku Karo
dan penduduk migran berasal dari Suku Jawa, Batak Toba,
Padang dan Nias.
3.3.1.2Strategi adaptasi yang dilakukan oleh penduduk migran
3.3.2 Informan
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :
3.3.2.1Warga masyarakat kelurahan Tiga Binanga
3.3.2.2Para migran yang pada saat ini tinggal di Kelurahan Tiga
Binanga minimal kurun waktu 3 tahun.
3.4Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :
3.4.1 Pengumpulan Data Primer
Teknik pengumpulan data primer adalah peneliti melakukan
kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang
lengkap dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik
pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :
3.4.1.1 Observasi
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penghimpun data
115). Observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu
dengan panca indera lainnya. Dalam hal ini penelitian dapat
melihat secara langsung pola asimilasi penduduk migrant dan
penduduk lokal.
3.4.1.2 Wawancara
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada
orang-orang yang menjadi informan dari peneliti ini bisa disebut dengan
metode interview guide yakni aturan-aturan daftar pertanyaan
sebagai acuan bagi peneliti untuk memperoleh data yang
diperlukan. Metode pengumpulan data dengan wawancara yang
dilakukan berulang-ulang kali dan membutuhkan waktu yang
cukup lama bersama informan di lokasi penelitian (Bungin, 2007 :
108). Wawancara mendalam yang dimaksud adalah percakapan
yang sifatnya luwes terbuka dan tidak baku. Dalam hal ini peneliti
melakukan wawancara mendalam terhadap informan yaitu
penduduk migran dan penduduk lokal.
3.4.1.3 Penghayatan (einfuehlen)
Suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan
penghayatan secara mendalam.
3.4.2Pengumpulan Data Sekunder
Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang
dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan yang diperlukan untuk
penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dianggap relevan
dan keabsahan dengan masalah yang diteliti.
3.5 Interpretasi Data
Pengumpulan data mulai dari menelaah seluruh data yang tersedia yaitu
pengamatan dan wawancara mendalam yang sudah ada dalam catatan lapangan.
Data-data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dipelajari yang kemudian
dikumpulkan untuk dapat di analisis berdasarkan dukungan teori dan kajian
pustaka yang telah disusun, hingga pada akhirnya sebagai laporan penelitian.
3.6Jadwal Kegiatan
No. Kegiatan
Bulan ke -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pra Observasi √
2 Acc judul √
3 Penyusunan Proposal penelitian √ √ √
4 Seminar proposal √
5 Revisi Proposal √
6 Penelitian ke Lapangan √ √ √
7 Pengumpulan dan Analisis Data √ √ √
8 Bimbingan Skripsi √ √ √ √
9 Penulisan Laporan Akhir √ √ √ √
BAB IV
TEMUAN DATA DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN
4.1Deskripsi Lokasi Penelitian 4.1.1 Keadaan Geografis
Tiga Binanga merupakan sebuah nama kelurahan di Kecamatan
Tiga Binanga Kabupaten Karo yang berjarak 0 km dari Kecamatan Tiga
Binanga dan 37 km dari Kota Kaban Jahe. Luas wilayah Kelurahan Tiga
Binanga adalah 535 Ha atau 160,38 Km2 dan terletak 600-700M di atas
permukaan laut. Secara letak geografis Kelurahan ini di kelilingi oleh sungai
sehingga kerap juga di panggil Singalor Lau (arti dalam bahasa Indonesia
yang di aliri suangai). Makna dari Tiga Binanga adalah Tiga yag berarti
pekan/pajak/pasar dan Binanga adalah sungai. Batas-batas Kelurahan Tiga
Binanga secara administratif adalah sebelah utara berbatas dengan Uruk Biru,
sebelah selatan berbatas dengan Desa Gunung, sebelah timur berbatas dengan
Desa Kuala dan sebelah barat berbatas dengan Desa Kuta Galuh. Kelurahan
Tiga Binanga didirikan oleh Marga Sebayang dari Desa Kuala sebagai marga
tanah beserta dengan anak berunya Marga Ginting Tampune, Sembiring
Brahmana, Tarigan Sibayak Juhar dan Karo-Karo Sinulingga sebagai anak
beru tanah dan kalimbubunya Marga Sembiring Meliala sebagai kalimbubu
tanah.
Sejak berdirinya Kecamatan Tiga Binanga Kelurahan Tiga
yang melangsungkan perjalanan jauh lintas Medan ke Kota Cane, Aceh, Dairi
dan Kota lainnya. Tiga Binanga merupakan Daerah yang dilintasi jalan
Provinsi sehingga Daerah Tiga Binanga tidak asing di kalangan masyarakat
yang tinggal di luar Tiga Binanga. Selain itu Tiga Binanga juga merupakan
tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Hasil-hasil alam seperti
rempah-rempah yang dijual oleh masyarakat juga di datangi oleh pembeli
yang berasal dari daerah Tapian nauli (Tapanuli dalam bahasa Karo).
Kehidupan sosial budaya masyarakat Kelurahan Tiga Binanga
masih menerapkan nilai-nilai peradatan yang diajarkan oleh leluhur mereka.
Masyarakat masih hidup dalam ikatan kekeluargaan yang sangat erat yang di
sebut dengan sangkep nggeluh (kerabat dalam bahasa indonesia). Sikap
saling menghormati di tengah-tengah kehidupan masyarakat hingga saat ini
tetap di pertahankan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari sikap hormat yang
diberikan kepada Kalimbubu (si pemilik darah atau keluarga dari ibu) yang
posisikan sebagai Dibata ni idah (Tuhan yang terlihat). Selain itu hingga
pada saat ini masyarakat masih tetap melaksanakan pesta-pesta budaya
seperti pesta tahunan (Kerja Tahun) yang dilaksanakan setiap tahun, acara
pernikahan/kematian secara adat, menerapkan sistim rebu (budaya tidak
bercakapan antara mertua dengan menantu perempuan dan menantu
laki-laki).
Ketetapan masyarakat Tiga Binanga dalam memelihara adat
istiadat mereka menjadi suatu ciri khas bagi Suku Karo yang ada di Daerah
tersebut, selain itu warisan budaya leluhur dalam meracik obat-obatan
bukanlah Daerah yang asing bagi kalangan masyarakat yang berdomisili di
Tanah Karo.
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2007 KECAMATAN TIGA BINANGA
Jumlah 160,38 19138 140,71
Sumber : Katalog BPS Tiga Binanga Dalam Angka 2007
4.1.2 Keadaan Penduduk
Berdasarkan Pengumpulan data-data menurut Desa untuk Kecamatan/
Daerah Dalam Angka tahun 2011 mencapai 4415 Jiwa. Penduduk
dimayoritasi oleh etnis Suku Karo dan agama Kristen Protestan. Mayoritas
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk di Kelurahan Tiga Binanga
No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-Laki 2162 Jiwa
2. Perempuan 2253 Jiwa
3. Total 4415 Jiwa
4. Jumlah Rumah Tangga 1200 RT
Sumber: Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk
KCDA Tahun 2011
Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut adalah sebagai
berikut.
Tabel 4.3 Agama Penduduk di Kelurahan Tiga Binanga
No. Agama Jumlah
1 Islam 1500 Jiwa
2 Kristen 2015 Jia
3 Katholik 900 Jiwa
4 Hindu -
5 Budha -
Total 4415 Jiwa
Sumber : Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk KCDA
Tahun 2011
Adapun jumlah sarana ibadah di Desa sebagai berikut.
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Ibadah
No. Sarana Ibadah Jumlah
1 Masjid 2 Buah
2 Langgar/Musholla -
4 Kuil -
5 Vihara -
Sumber : Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk KCDA
Tahun 2011
Adapun jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sebagai berikut.
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk 10 tahun ke-atas Menurut Pekerjaan
No Pekerjaan Jumlah
1 Pertanian 3025 Jiwa
2 Industri 15 Jiwa
3 Jasa 50 Jiwa
4 PNS/POLRI 43 Jiwa
5 Lainnya - Jiwa
6 Tidak Bekerja - Jiwa
Sumber : Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk KCDA
Tahun 2011
Adapun jumlah usaha yang di miliki oleh penduduk adalah sebagai berikut.
Tabel 4.6 Jumlah Usaha yang ada di Desa
No. Jenis Usaha Jumlah
1 Kedai Kopi 62 Usaha
2 Kedai Kelontong 29 Usaha
3 Gudang/Expedisi -
4 Industri Besar/Sedang 6 Usaha
5 IndustriKecil 2 Usaha
6 Industri RT/Anyaman 6 Usaha
7 Bengkel Mobil 14 Usaha
8 Bengkel Sepeda Motor 12 Usaha
9 Bengek Sepeda 2 Usaha
Sumber : Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk KCDA
Tahun 2011
4.2 Profil Informan
Adapun penduduk migran dan penduduk lokal yang menjadi informan
berjumlah 17 (Tujuh belas) orang. Berikut data penduduk migran dan penduduk
lokal tersebut.
Tabel 4.7 Data Penduduk Migran Berdasarkan Usia, Pendidikan Terakhir, Asal dan Lama Tinggal.
No Nama Usia
53 Wiraswasta 6 SD Campag
o, Padang
44 Tahun
5 Julardi 54 Wiraswasta SMA Padang 44 Tahun
6 Asir Maulana
52 Wiraswasta SMA Padang 37 Tahun
7 Andi Riswanto
47 Wiraswasta SMA Tebing
Tinggi
14 Tahun 8 Binharun
Sitorus
45 Bertani SMA Siantar 24
4.2.1 Profil Penduduk Migran
4.2.1.1 Nila Agustina (29 Tahun)
Nila Agustina adalah seorang migran yang berasal dari Kota
Siantar. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara dan berasal dari
etnis Jawa. Nila Agustina mengecap pendidikan hingga sekolah menengah
atas, mempunyai empat saudara yang mana adiknya yang pertama dan
kedua adalah perempuan dan yang ketiga dan keempat adalah
laki.Kedua adik perempuannya sudah berumah tangga dan adik yang
laki-laki tinggal bersama dengan orang tuanya.
Pada tahun 1993 ayah dan ibu Nila pergi merantau dari Siantar ke
Kelurahan Tiga Binanga. Meraka melihat bahwa di Daerah Tiga Binanga
mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu Nila masih memasuki
sekolah kelas 1SD. Di Tiga Binanga Ayah Nila bekerja sebagai buruh di
toko bangunan Apolo dan ibunya bekerja sebagai penjual kue di pasar.
Mereka mengontrak salah satu rumah dari penduduk yang yang tinggal di
Tiga Binanga bernama Terulin Ginting. Mereka juga belajar berbahasa
Karo dan mengikuti aturan –aturan adat yang berlaku, contohnya seperti
cara berpakaian. Perbedaan kebudayaan dan keyakinan tidak menjadi
penghalang bagi mereka untuk berinteraksi. Dengan sikap saling
menghormati dan keramah tamahan yang senantiasa diaplikasikan oleh
keluarga Nila dengan penduduk yang ada di sekitar tempat tinggal mereka
menjadikan mereka semakin nyaman dan seakan memiliki keluarga baru
juga menrasakan kecocokan dalam bekerja dan berkomunikasi dengan
ayah Nila sehingga bos di tempat kerjanya juga mengajak Ayah Nila untuk
menjalin kekeluargaan dan akan di berikan marga Karo-Karo sesuai nama
marga si pemilik usaha. Namun karena segan melihat bosnya Ayah nila
menolak karena merasa tidak pantas. Kemudian hari si pemilik rumah
kontrakannya yang bernama Terulin Ginting juga mengajak Ayah Nila
untuk bekerja di lahannya. Mendapati bahwa ayah Nila dan keluarganya
memiliki kejujuran dan rasa rendah hati maka sikap tersebut menarik
simpati dari Terulin Ginting untuk memberikan marga kepada keluarga
bapak Nila. Sejak itu Nila bersama keluarganya di sahkan menjadi
bermarga Ginting.
Dengan adanya marga yang dimiliki oleh Ayah Nila dan
keluarganya maka ketika ada pesta dari keluarga besar Ginting, adanya
perayaan pesta tahunan maka Ayah Nila sekeluarga juga turut
berpartisipasi selayaknya mereka adalah benar penduduk lokal. Mereka
tidak menemukan adanaya diskriminasi ketika mereka bekerja dan
berkomunikasi dengan penuduk setempat. Ketika ada perayaan hari-hari
besar mereka juga berpartisipasi, baik kegiatan arisan, siskamling dan
bakti sosial.
Nila yang sudah disahkan menjadi beru Ginting pada tahun 2005
menikah dengan Intim Sembiring Meliala berumur 27 tahun yang
merupakan putra Daerah di Kelurahan Tiga Binanga. Pertemuan mereka
diawali karena tempat sekolah yang sama dan seringnya terjalin
keduanya memiliki perbedaan suku dan agama, namun hal tersebut tidak
menjadi penghalang. Keduanya memutuskan untuk menjadi muslim, Pesta
pernikahan mereka dilaksanakan dengan adanya pelaksanaan akad nikah
dan dilaksanakan juga dengan kebudayaan etnis Karo. Nila mendapati
bahwa kehidupannya setelah merantau dari Siantar jauh lebih baik. Beliau
sudah memiliki keluarga dan anak di Kelurahan Tiga Binanga sehingga
memutuskan untuk tidak kembali lagi ke daerah asalnya di Siantar. Pada
saat ini Nila bersama dengan suaminya mengelola lahan yang merupakan
warisan yang diberikan kepada suaminya.
4.2.1.2 Lilis Suryani Mendrofa (32 tahun)
Lilis Suryani Mendrofa adalah seorang migran yang berasal dari
Dairi, namun menurut penjelasan dari informan bahwa sejak lama ayah
beserta keluarganya sudah lama merantau ke Dairi, dan sebelumnya Lilis
Suryani Mendrofa berasal dari Gunung Sitoli Nias. Beliau adalah anak ke
empat dari lima bersaudara. Pada waktu Lilis berusia 2 tahun keluarganya
pergi merantau ke Daerah Dairi. Sejak kecil hingga menyelesaikan
pendidikannya di sekolah menengah umum Lilis beserta keluarganya
tinggal di Dairi. Pada tahun 1989 setelah tamat dari sekolah menengah
umum, Lilis beserta keluarganya pindah merantau ke Daerah Tiga
Binanga. Di Tiga Binanga Lilis dan keluarganya bekerja sebagai buruh