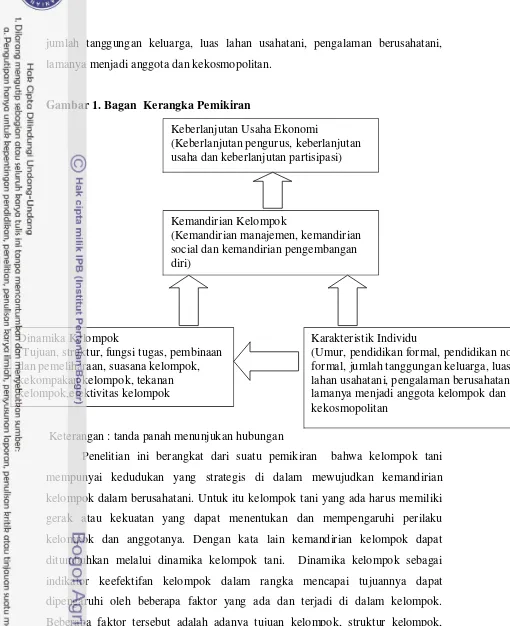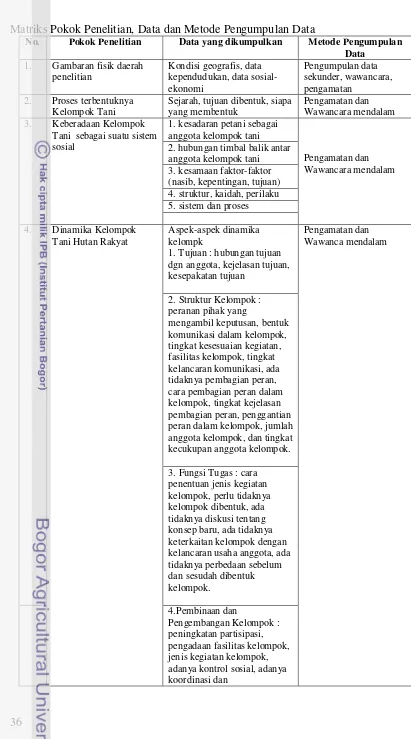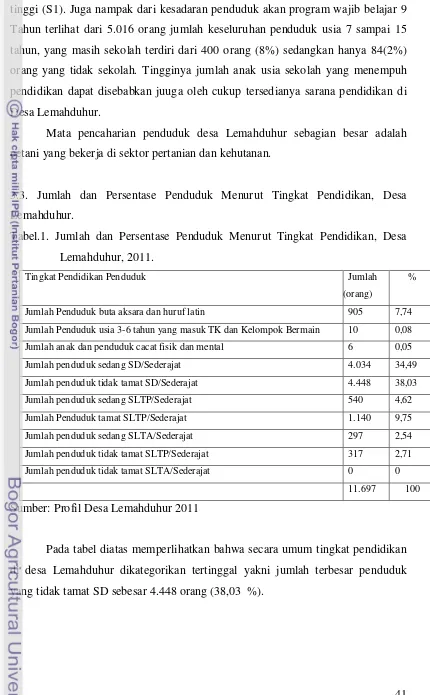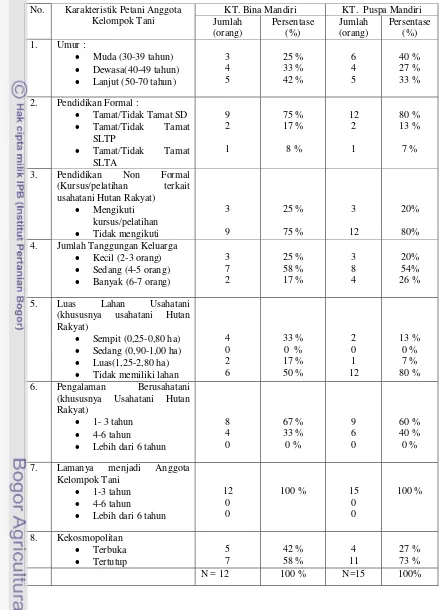DINAMIKA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT
DESA LEMAHDUHUR
(
Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)GENTINI IKA LESTARI
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN
SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur (Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Agustus 2012
ABSTRACT
DINAMIKA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT DESA LEMAHDUHUR
(Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan CaringinKabupaten Bogor)
THE DYNAMICS OF COMMUNITY FOREST FARMER GROUPS IN LEMAHDUHUR
Abstract
The objectives of this research are, first, to analyze the dynamics and self reliance of the community forest farmer groups of the Lemahduhur Village, Caringin Sub-District, Bogor; second, to identify the factors that affect to the dynamic and self reliance of the farmer groups; and the last, third, to explore the sustainability of the said forest farmer groups. Research was conducted on March-May 2011. Two farmer groups were studied through qualitative approach i.e the ‘Bina Mandiri’ and the ‘Puspa Mandiri’. The results show that the dynamic and self-reliance of the both groups are categorized as low. Educational background, ages, farm experiences and land size are factors that strongly influence the dynamic and self-reliance of the groups. The last findings, the sustainability of the studied groups were categorized as low or limited in terms of its management, efforts and participation of the member.
RINGKASAN
GENTINI IKA LESTARI. Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur (Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). Dibawah bimbingan : Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS., sebagai ketua dan Ir. Nuraini Wahyuning Prasodjo, MS., sebagai anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis dinamika dan kemandirian kelompok tani hutan rakyat di desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor; 2) menganalisis karakteristik individu anggota kelompok yang berperan penting dalam membangun dinamika kelompok tani hutan rakyat; dan 3) menelaah keberlanjutan pengembangan usaha ekonomi kelompok tani hutan rakyat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dua kelompok tani yang secara historis berbeda proses pembentukannya (top down dan bottom up)
menjadi fokus utama studi ini, yakni kelompok tani Bina Mandiri (bentukan dari atas, top down) dan kelompok tani Puspa Mandiri (bentukan dari bawah, bottom up). Kedua kelompok berada di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Kedua kelompok tersebut ditelaah dalam konteks melaksanakan kegiatan Program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (in depth interview), metode pengamatan (observasi), dan dukungan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2011. Data selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.
Merujuk pada konsep dinamika kelompok, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kedua kelompok tani yang diteliti tergolong rendah. Namun demikian, kelompok tani Puspa Mandiri (yang dibentuk secara bottom up)
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
DINAMIKA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT
DESA LEMAHDUHUR
(
Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)GENTINI IKA LESTARI
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Studi Sosiologi Pedesaan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbilalamin, penulis panjatkan ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan bimbingan dan karuniaNya sehingga Tesis yang berjudul ” Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur (Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor) dapat terselesaikan. Tesis ini berusaha mengkaji dinamika kelompok dan kemandirian kelompok serta keberlanjutan usaha ekonomi kelompok tani di Desa Lemahduhur Kacamatan Caringin Kabupaten Bogor. Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:
1. Dr.Ir. Soeryo Adiwibowo, MS. dan Ir. Nuraini Wahyuning Prasodjo, MS. atas bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Kementrian Kehutanan, atas kesempatan yang sangat berharga ini, semoga penulis mampu memberi yang terbaik.
3. Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Bina Mandiri dan Kelompok Tani Puspa Mandiri serta warga masyarakat petani Desa Lemahduhur yang telah menerima penulis dengan tulus dan memberikan informasi yang dibutuhkan. 4. Kedua Orangtua dan Adik-adik tersayang atas doa, perhatian dan dukungan
semangat semoga Alloh SWT membalasnya.
5. Heru Pramono. S., suami tercinta atas doa, perhatian, kepercayaan dan dukungannya.
6. Alya Raihana Alifa, Amira Rasyanda Alifa dan Adinda Rizqulla Alifa, putri-putri sholehah yang menjadi energi terbesar dalam setiap langkahku.
7. Teman seperjuangan SPD Angkatan 2008 ; Nendah Kurniasari, Eko Cahyono, Dian Ekowati, Nurul Hayat, Usep Setiawan, Aldi Basir dan Favor A. Bancin terimakasih atas doa dan dukungan semangatnya.
8. Seluruh keluarga dan sahabat atas doa dan motivasi yang sangat berharga. Penulis sangat menyadari jika tesis ini jauh dari sempurna, oleh karenanya untuk memperoleh hasil yang lebih baik masukan berupa saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat.
RIWAYAT HIDUP
GENTINI IKA LESTARI, dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 10 Desember 1970, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan H.Soleh Sukmana, dan Hj. Nyinyih Wasyiah. Saat ini penulis merupakan istri dari H. Heru Pramono S., dan ibu dari tiga orang putri yaitu Alya Raihana Alifa, Amira Rasyanda Alifa dan Adinda Rizqulla Alifa.
Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah Taman Kanak-Kanak Mexindo pada Tahun 1977, Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 2 Bogor tahun 1984, SMPN 4 Bogor tahun 1987, SMAN 1 Salatiga Tahun 1990. Kemudian penulis melanjutkan ke program Sarjana jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta yang diselesaikan pada tahun 1995. Sejak September 2008, penulis melanjutkan studi ke Program Pascasarjana Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor atas Biaya dari Kementrian Kehutanan.
xii
2.1.1.1. Kelompok dan Dinamika Kelompok... 11
2.1.1.2. Kelompok Tani... 17
2.1.1.3. Hutan Rakyat... 19
2.1.1.4. Kemandirian Kelompok Tani... 20
2.1.1.5. Karakteristik Individu... 21
2.1.1.6. Keberlanjutan Usaha Ekonomi... 23
2.1.1.7. Kepemimpinan... 24
2.1.1.8. Hasil Beberapa Penelitian Tentang Dinamika Kelompok dan Hutan Rakyat... 26 2.1.2. Kerangka Pemikiran... 27
2.2. Pendekatan Lapang... 33
2.2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian... 33
2.2.2. Pendekatan Penelitian... 33
2.2.3. 2.2.4. Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data... Pendekatan Kualitatif... 34 35 III. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 3.1. Keadaan Geografis dan Kondisi Alam... 39
3.2. Kependudukan dan Matapencaharian Penduduk... 40
3.3. Tingkat Pendidikan Penduduk... 41
3.4. Sejarah Penguasaan Lahan... 42
3.5. Profil Kelompok Tani... 45
3.5.1. Profil Kelompok Tani Bina Mandiri... 45
3.5.2. Profil Kelompok Tani Puspa Mandiri... 46
3.6. Karakteristik Responden... 48
3.7. Ikhtisar... 55
IV. DINAMIKA KELOMPOK 4.1. Dinamika Kelompok... 57
4.1.1. Dinamika Kelompok Tani Bina Mandiri... 57
4.1.2. Dinamika Kelompok Tani Puspa Mandiri... 86
Karakteristik Individu...
4.1.4. Faktor Eksternal... 119
4.1.5. Ikhtisar... 124
V. KEMANDIRIAN KELOMPOK DAN KEBERLANJUTAN USAHA EKONOMI 5.1. Kemandirian Kelompok... 129
5.1.1. Kemandirian Kelompok Tani Bina Mandiri... 122
5.1.2. Kemandirian Kelompok Tani Puspa Mandiri... 125
5.2. Keberlanjutan Usaha Ekonomi... 134
5.2.1. Keberlanjutan Usaha Ekonomi Pada Kelompok Tani Bina Mandiri... 134 5.2.2. Keberlanjutan Usaha Ekonomi Pada Kelompok Tani Puspa Mandiri... 142 5.3. Ikhtisar... 147
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 151 6.1. Kesimpulan... 151
6.2. Saran... 154
DAFTAR PUSTAKA
xiv
DAFTAR TABEL
Halaman
DAFTAR GAMBAR
xvi
LAMPIRAN
DAFTAR ISI
2.1.1.1. Kelompok dan Dinamika Kelompok... 11
2.1.1.2. Kelompok Tani... 17
2.1.1.3. Hutan Rakyat... 19
2.1.1.4. Kemandirian Kelompok Tani... 20
2.1.1.5. Karakteristik Individu... 21
2.1.1.6. Keberlanjutan Usaha Ekonomi... 23
2.1.1.7. Kepemimpinan... 24
2.1.1.8. Hasil Beberapa Penelitian Tentang Dinamika Kelompok dan Hutan Rakyat... 26 2.1.2. Kerangka Pemikiran... 27
2.2. Pendekatan Lapang... 33
2.2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian... 33
2.2.2. Pendekatan Penelitian... 33
2.2.3. 2.2.4. Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data... Pendekatan Kualitatif... 34 35 III. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 3.1. Keadaan Geografis dan Kondisi Alam... 39
3.2. Kependudukan dan Matapencaharian Penduduk... 40
3.3. Tingkat Pendidikan Penduduk... 41
3.4. Sejarah Penguasaan Lahan... 42
3.5. Profil Kelompok Tani... 45
3.5.1. Profil Kelompok Tani Bina Mandiri... 45
3.5.2. Profil Kelompok Tani Puspa Mandiri... 46
3.6. Karakteristik Responden... 48
3.7. Ikhtisar... 55
IV. DINAMIKA KELOMPOK 4.1. Dinamika Kelompok... 57
4.1.1. Dinamika Kelompok Tani Bina Mandiri... 57
xiii Karakteristik Individu...
4.1.4. Faktor Eksternal... 119
4.1.5. Ikhtisar... 124
V. KEMANDIRIAN KELOMPOK DAN KEBERLANJUTAN USAHA EKONOMI 5.1. Kemandirian Kelompok... 129
5.1.1. Kemandirian Kelompok Tani Bina Mandiri... 122
5.1.2. Kemandirian Kelompok Tani Puspa Mandiri... 125
5.2. Keberlanjutan Usaha Ekonomi... 134
5.2.1. Keberlanjutan Usaha Ekonomi Pada Kelompok Tani Bina Mandiri... 134 5.2.2. Keberlanjutan Usaha Ekonomi Pada Kelompok Tani Puspa Mandiri... 142 5.3. Ikhtisar... 147
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 151 6.1. Kesimpulan... 151
6.2. Saran... 154
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
Halaman
xv
DAFTAR GAMBAR
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dewasa ini perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk lebih
memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Pengembangan
hutan rakyat dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial
secara adil dan lestari. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Reboisasi Lahan dan
Perhutanan Sosial (RLPS), Departemen Kehutanan (2009) dinyatakan bahwa luas
total hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3.589.343 hektar. Prosentase luas
hutan rakyat masih akan terus bertambah bila melihat data luas lahan kritis di luar
kawasan hutan di Indonesia yang saat ini tercatat sekitar 10.690.312 hektar. Hutan
rakyat berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi kayu, meningkatkan
pendapatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan
hutan rakyat diarahkan untuk mendorong berkembangnya bisnis rakyat berbasis
hutan khususnya di pedesaan. Pembangunan hutan rakyat dimaksudkan untuk
merehabilitasi dan meningkatkan produktivitas lahan serta kelestarian sumber
daya alam agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani
pemilik hutan rakyat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Disamping dapat memberikan sumbangan berupa pemenuhan kebutuhan akan
kayu, hutan rakyat dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan rakyat
yang cukup besar dari hasil hutan non kayu yang memiliki nilai ekonomi yang
cukup tinggi. Dengan demikian hutan rakyat memberikan manfaat ekonomi yang
cukup tinggi.
Tujuan usaha hutan rakyat adalah untuk penyediaan bahan baku industri,
memperluas lapangan kerja dan meningkatkan mutu lingkungan. Berdasarkan
tujuan tersebut, pembangunan hutan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara
perorangan/parsial, tetapi harus secara bersama-sama. Pembangunan hutan rakyat
lebih efektif dilaksanakan secara komunal (kelompok). Menurut pendapat yang
dikemukakan oleh Margono (2001) bahwa pendekatan kelompok dipandang lebih
efisien dan dapat menjadi media untuk terjadinya proses belajar dan berinteraksi
yang lebih baik atau berkualitas. Pendekatan kelompok dan keberadaan kelompok
tani di masa depan masih sangat diperlukan karena membantu memudahkan
bimbingan dan pendampingan petani yang jumlahnya besar melalui
pengelompokkan. Disamping itu pendekatan kelompok juga mampu mengurangi
berbagai kendala seperti luasnya wilayah, sebaran kondisi geografis yang
beragam, terbatasnya jumlah petugas, waktu dan biaya penyuluhan pertanian
(Suharno, 2009). Dalam pengelolaan hutan rakyat diperlukan pengorganisasian
petani yang terlembaga. Pentingnya pembinaan petani dengan pendekatan
kelompok tani dikemukakan oleh Mosher (1968) dalam Djiwandi (1994) bahwa
salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan petani
yang tergabung dalam kelompok tani.
Hutan rakyat di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin pada umumnya
dikelola secara komunal (kelompok) pada lahan milik perorangan yang tersebar
berdasarkan letak, luas kepemilikan lahan dan pola usaha taninya. Secara
keseluruhan pola pengembangan hutan rakyat di Desa Lemahduhur, Kecamatan
Caringin dapat diklasifikasikan ke dalam pola hutan rakyat wanatani
(Agroforestry), yaitu kombinasi antara tanaman kayu dengan tanaman perkebunan serta tanaman bawah tegakan. Pola pengembangan hutan rakyat sangat terkait
dengan luas kepemilikan lahan. Secara umum luas pemilikan lahan berkisar antara
25 ha. Kepemilikan lahan yang tidak terlalu luas menyebabkan para petani
mengelola hutan rakyat dengan sistem yang lebih intensif. Hal ini dapat terlihat
dari beragamnya jenis tanaman yang dikembangkan. Pengelolaan hutan rakyat di
Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin dalam pelaksanaannya dilakukan secara
terprogram, diperlukan pengorganisasian petani yang terlembaga. Dalam kaitan
tersebut kelompok tani sebagai lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya),
keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya mempercayai, serta
mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Departemen Pertanian,
1989).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarko (2010) tentang Hubungan
Dinamika dan Peran Kelompok dengan Kemampuan Anggota dalam Penerapan
3 berkelompok menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan
yang tidak berkelompok. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa usahatani
secara berkelompok berperan cukup besar dalam mengembangkan skala usaha
yang lebih ekonomis dan efisien. Berkembangnya kelompok tani ini berarti terjadi
peningkatan dinamika kelompok, berarti pula peningkatan fungsi dan
kegiatannya.
Keuntungan berkelompok dalam mengelola hutan rakyat, diantaranya
petani dapat saling menukar informasi, pengetahuan, inovasi teknologi dan
pengalaman mengenai usahatani hutan rakyat melalui wadah kelompok. Petani
juga dapat saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan dalam usahataninya
dalam wadah kelompok. Melalui wadah kelompok tani akan memudahkan dalam
penyampaian program, tujuan dan proyek yang akan dan hendak dicapai oleh
kelompok tani.
Namun persoalanya banyak kelompok tani baik yang terbentuk secara top
down maupun kelompok yang terbentuk secara bottom up telah ditumbuhkan,
tetapi banyak pula kelompok tani yang mati atau hanya tinggal nama saja
sehingga dipertanyakan eksistensinya. Sering kelompok tumbuh menjamur seiring
dengan adanya bantuan program dari pemerintah atau instansi swasta. Fakta juga
menunjukkan, dengan berakhirnya bantuan tersebut, maka berakhir pula
kelompoknya dan teknologi anjuran mulai ditinggalkan (Purwanto & Wardani
2006).
Disamping itu, matinya kelompok tani juga diakibatkan adanya
ketidakpastian kebijakan pemerintah. Menurut Purwanto dan Wardani (2006)
adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dan Menteri Dalam
Negeri Tahun 1991 menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak
berfungsi, karena BPP berfungsi sebagai instalasi Dinas Subsektor. Balai
Informasi Penyuluhan Pertanian yang mempunyai instalasi BPP adalah pengelola
kelompok tani sehingga apabila lembaga pengelolanya tidak jelas maka
keberadaan kelompok tani juga tidak jelas pula. Artinya, walaupun kelompok tani
tersebut ada namun akibat tidak jelas pembinaannya umumnya kelompok tani
tersebut kurang atau tidak dinamis, peran dan fungsi kelompok tani tidak berjalan
Sebaliknya ada juga kelompok tani yang berumur panjang dan bertahan
lama. Hasil Penelitian Sutjipta (1987) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Dinamika Subak dan Hubungannya dengan Mutu Hidup Anggota, menyimpulkan
bahwa faktor pengikat subak sampai kini terus terpelihara, sehingga kehidupan
kelompok dapat terus terjaga. Faktor-faktor pengikat tersebut meliputi : (1)
ketergantungan anggota subak pada kebutuhan air, (2) keterikatan anggota pada
pura sebagai tempat persembahyangan bersama, (3) keterikatan pada tata upacara
adat dan keagamaan, (4) otonomi subak, baik kedalam maupun keluar, (5) konsep
hidup ”tri hita karana”, yaitu tiga cara mencapai kebahagiaan melalui keselarasan
hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Keteraturan
pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi anggota yang tinggi dan adanya
keterbukaan pada perubahan yang terjadi menyebabkan subak dapat
mempertahankan hidupnya.
Terbentuknya kelompok tani tersebut memberikan banyak manfaat bagi
masyarakat. Kelompok tani yang ada di desa Lemahduhur ada yang terbentuk atas
inisiatif warga (bottom up) dan ada juga yang terbentuk secara topdown karena
keproyekan atau program. Pada saat dilakukan penelitian di desa Lemahduhur
sedang berjalan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang
merupakan program yang diperkenalkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Bogor dengan sumber dana APBD I (Propinsi). Gerakan Rehabilitasi
Lahan Kritis (GRLK) merupakan gerakan moral untuk membangun kesadaran
masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat dalam rangka memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga. Adapun yang menjadi tujuan GRLK adalah untuk
meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk merehabilitasi lahan; mengurangi
luasan lahan kritis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2010). Anggaran APBD I (Propinsi) melalui
kegiatan GRLK berupa kegiatan pengayaan tanaman/pembuatan hutan rakyat.
Sasaran pembuatan tanaman hutan rakyat diutamakan pada lahan dengan rata-rata
5 disalurkan kepada kelompok tani Bina Mandiri berupa bibit sengon, suren dan
cengkeh untuk ditanam pada lahan seluas 50 hektar yaitu ; 25 hektar Blok Sinagar
dan 25 hektar blok Punjul. Sedangkan kelompok tani Puspa Mandiri menerima
bantuan bibit untuk ditanam di blok Pasir Ipis seluas 25 hektar.
Kelompok tani yang telah terbentuk, diharapkan dapat dijadikan media
untuk berkelompok dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dengan atau
tanpa adanya intervensi dari luar sehingga pendapatannya dapat meningkat, dan
akhirnya kesejahteraan akan turut meningkat pula, sehingga akan timbul
kedinamisan dari kelompok tersebut. Peran kelompok tani terhadap anggotanya
diharapkan akan berdampak terhadap pembangunan hutan rakyat, sehingga para
anggota akan dengan serius terus mengembangkan tanaman hutannya. Oleh
karena itu pembentukan kelompok tani yang beranggotakan masyarakat sekitar
merupakan suatu keharusan (Diniyati , 2003). Dengan adanya kelompok tani
diharapkan imbas pembelajaran dalam pengelolaan hutan rakyat diharapkan akan
lebih tersebar.
Kelompok yang dinamis ditandai oleh selalu adanya kegiatan atau
interaksi baik didalam maupun dengan pihak luar kelompok untuk secara efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuannya (Djoni, 2000). Lebih lanjut Soekanto
S (1990) mengemukakan bahwa kelompok sosial haruslah memenuhi syarat,
yaitu: 1) anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok
yang bersangkutan; 2) ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan
anggota yang lainnya; 3) ada faktor ( misalnya; nasib, kepentingan, tujuan,
ideologi, politik dan lain-lain) yang sama, sehingga hubungan diantara mereka
bertambah erat; 4) berstruktur, berkaidah dan mempunyai perilaku dan 5)
bersistem dan berproses.
Pengertian dan syarat yang harus dimiliki oleh suatu kelompok menjadi
petunjuk bahwa setiap kelompok sosial cenderung untuk tidak statis, akan tetapi
selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas
maupun bentuknya. Seperti dikemukakan oleh Soekanto S (1990), bahwa
kelompok sosial seperti kelompok tani ini bukan merupakan kelompok yang
statis, karena pasti mengalami perkembangan serta perubahan sebagai akibat
karena pengaruh dari luar. Selain itu keadaan yang tidak stabil tersebut juga dapat
terjadi karena adanya konflik antar individu dalam kelompok atau karena adanya
konflik antar bagian kelompok tersebut sebagai akibat tidak adanya keseimbangan
antara kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya menurut
Santoso (1992) perubahan disebabkan oleh interaksi dan interdependensi antara
anggota kelompok secara timbal balik, yang mencerminkan adanya dinamika
kelompok.
Dinamika kelompok merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh
kelompok yang akan menentukan perilaku kelompok dan anggota-anggotanya.
Dengan dinamisnya suatu kelompok diharapkan terjadinya perubahan perilaku
anggota kelompok yang pada gilirannya akan merubah pola pikir masyarakat
dalam pemanfaatan hutan rakyat. Kelompok yang kompak akan memiliki daya
lekat tinggi yang akan mendorong keefektifan anggota pada kelompoknya.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat merupakan hal
yang tidak dapat dihindari, karena tidak ada sedikitpun bagian kawasan hutan
yang bebas dari kepentingan hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu modal sosial yang dapat
dikembangkan secara integratif melalui berbagai kegiatan kreatif dalam rangka
memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan.
Pengelolaan hutan rakyat dituntut untuk memenuhi azas keadilan, yaitu hutan
harus menjadi sumber daya bagi masyarakat setempat dan harus dapat
memberikan kontribusi bagi peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.
Masyarakat setempat yang terkonsentrasi dalam kelompok-kelompok harus dapat
melakukan pengelolaan hutan rakyat secara utuh mulai dari pemanfaatan,
rehabilitasi, sampai pada perlindungan hutan. Partisipasi tersebut tidak
berdasarkan pada motivasi untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan
bersama.
Mengingat pentingnya kelompok tani baik dalam hal meningkatkan
kesejahteraan petani itu sendiri dan keluarganya maupun dalam memberikan
sumbangan pada pelestarian hutan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang dapat
7 arena itu kelompok tani perlu ditumbuhkembangkan agar supaya produktif dan
dapat mencapai tujuan-tujuannya secara efektif.
Untuk meningkatkan manfaat atau keuntungan dari adanya kelompok tani
tidak terlepas dari bagaimana meningkatkan peran kelompok tani tersebut, yaitu
dengan menjaga bagaimana kelompok tani tersebut dinamis. Suatu kelompok
dapat dikatakan dinamis apabila kelompok itu efektif dalam mencapai
tujuan-tujuannya. Suatu konsep yang menunjukan kefektifan kelompok dalam mencapai
tujuan-tujuannya adalah konsep dinamika kelompok. Dengan dinamika kelompok
ini memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anggota untuk bekerjasama dan
berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Oleh karena itu studi ini ingin
mendalami tentang bagaimana kelompok mampu berkelanjutan.
1.2. Perumusan Masalah
Di Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin terdapat tiga kelompok tani
yang masing-masing diberi nama: Kelompok Tani Puspa Mandiri, Kelompok
Tani Bina Mandiri, Kelompok Tani Berkah dan Satu Gabungan Kelompok Tani
yang diberi nama Gapoktan Berkah. Pengelolaan hutan rakyat di Desa
Lemahduhur Kecamatan Caringin didukung oleh keberadaan kelompok tani.
Kelompok tani Bina Mandiri dan Kelompok Tani Puspa Mandiri mengelola hutan
rakyat bantuan program sedangkan kelompok tani Berkah di bidang hortikultura.
Program yang sedang berjalan di Kecamatan Caringin yaitu Program Gerakan
Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang diperkenalkan oleh Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten Bogor dengan sumber dana APBD I (Propinsi), dengan
target penanaman 1000 pohon per hektar, bantuan berupa bibit tanaman sengon,
suren, dan cengkeh, dikelola oleh kelompok tani Bina Mandiri dan kelompok tani
Puspa Mandiri, yang ditanam pada lahan milik seluas 75 hektar terbagi di 3 Blok
yaitu blok Sinagar, blok Punjul dan blok Pasir Ipis.
Kenyataannya kelompok tani yang ada sekarang ini, umumnya merupakan
hasil dari bentukan program pemerintah. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai
diantaranya disebabkan program masih memberikan bantuan berupa subsidi
kepada petani peserta program yang terorganisir dalam kelompok-kelompok tani.
akan tetap berlanjut dan apakah kelompok-kelompok tani yang ada akan tetap
survive? Dilihat secara sosiologis apakah program tersebut telah melembaga dalam kehidupan petani? Seiring dengan waktu, banyak kelompok tani yang tidak
dapat mempertahankan para anggotanya sehingga kelompok tersebut hanya
tinggal nama saja. Namun ada juga kelompok yang semakin maju walaupun tidak
ada lagi bantuan yang diterima oleh kelompok tani (Diniyati, Dian 2000).
Dinamika kelompok merupakan suatu konsep yang dapat mengukur
keefektifan kelompok tani dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dinamika kelompok
merupakan tenaga atau kekuatan yang diturunkan dari individu-individu anggota
dan interaksi di dalam kelompok. Totalitas dari kekuatan-kekuatan itu akan
membawa kelompok berperilaku aktif (dinamis). Karena itu, dinamika kelompok
mencakup faktor-faktor yang menyebabkan kelompok itu hidup, bergerak, aktif
dan efektif dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor inilah yang dikaji dalam
penelitian ini. Sudah tentu, dari sekian banyak kelompok tani memiliki
kekuatan-kekuatan yang bervariasi sehingga menyebabkan tingkat dinamika kelompok tani
bervariasi pula.
Melihat kenyataan tersebut, dengan demikian timbul masalah menyangkut
eksistensi kelompok tani yang ada, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut:
1. Menganalisis dinamika dan kemandirian kelompok tani hutan rakyat di desa
Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis karakteristik individu anggota kelompok yang berperan penting
dalam membangun dinamika kelompok tani hutan rakyat.
3. Menelaah keberlanjutan pengembangan usaha ekonomi kelompok tani hutan
rakyat.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk :
1. Menganalisis dinamika kelompok tani hutan rakyat di Desa Lemahduhur
Kecamatan Caringin.
2. Menganalisis kemandirian kelompok tani hutan rakyat di Desa Lemahuduhur
9 3. Menelaah keberlanjutan pengembangan usaha ekonomi kelompok tani hutan
rakyat di Desa Lemahuduhur Kecamatan Caringin.
3. Mengetahui faktor-faktor karakteristik individu (anggota kelompok) apa
sajakah yang mempengaruhi tingkat dinamika kelompok tani hutan rakyat.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Dari sudut akademis ; hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan informasi mengenai Dinamika Kelompok dan Kemandirian
Kelompok .
2. Dari sudut implikasi praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan informasi dan
sebagai pertimbangan bagi penentu kebijakan mengenai program-program
Kehutanan yang saling menguntungkan dan program penanggulangan
kemiskinan lainnya.
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melaksanakan
penelitian sejenis (penelitian evaluasi) secara mendalam atau dalam lingkup
yang lebih luas.
BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Pendekatan Teoritis
2.1.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1.1. Kelompok dan Dinamika Kelompok
Beberapa konsep tentang kelompok yang dikemukakan oleh pakar dapat
kita jumpai, baik yang membahas dari sudut pandang sosiologis, antropologis,
maupun dari sudut pandang psikologis. Beberapa konsep tentang kelompok antara
lain: Soedijanto(1981), mengemukakan bawa definisi kelompok adalah ”dua atau
lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui
pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang
relatif panjang”. Hubungan antara dua orang atau lebih individu ini dinyatakan
oleh Gunardi sebagaimana dikutip oleh Soedijanto(1981) adalah ”mereka yang
mempunyai beberapa kesamaan obyek perhatian, berinteraksi secara mantap,
bersama menyusun suatu struktural, dan bersama berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan tertentu”. Ungkapan yang hampir sama dikemukakan oleh Gerungan
(1978) bahwa kelompok sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua
orang atau lebih yang telah mengadakan interaksi yang intensif dan teratur
sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma
tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut. Tidak berbeda dengan pandangan
Syamsu, dkk (1990) kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih, yang
secara intensif dan teratur selalu mengadakan interaksi sesama mereka untuk
mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dan secara sadar mereka merasa
bagian dari kelompok yang memiliki norma tertentu, peranan, struktur fungsi dan
tugas masing-masing anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas jelaslah bahwa kelompok merupakan
kumpulan orang-orang yang menyatukan diri karena adanya kesamaan tujuan
yang hendak dicapai. Kemudian Horton dan Hunt (1999) mendefinisikan bahwa
kelompok merupakan setiap perkumpulan orang yang memiliki kesadaran
12
adalah adanya interaksi dan saling ketergantungan, serta memiliki kepentingan
bersama dan tujuan bersama. Kelompok-kelompok sosial timbul karena manusia
dengan sesamanya mengadakan hubungan yang langgeng untuk suatu tujuan atau
kepentingan bersama (Soemardjan dan Soemardi, 1964). Menurut pengertian
sosiologis kelompok sosial adalah kumpulan individu-individu yang mempunyai
hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, dimana didalamnya terdapat
ikatan perasaan yang relatif sama.
Kelompok-kelompok dalam sistem sosial bukan merupakan kelompok
yang statis, karena setiap kelompok sosial cepat atau lambat hampir dapat
dipastikan akan mengalami perubahan dan perkembangan. Sistem sosial
merupakan entitas sosial yang dicirikan oleh individu-individu atau unit sosial
lainnya yang berproses secara fungsional saling terkait satu sama lain. Menurut
Cartwright dan Zander (1968) salah satu orientasi teoritis dalam mempelajari
dinamika kelompok yaitu pendekatan teori sistem. Dalam pandangan ini
kelompok dilihat sebagai suatu sistem yaitu merupakan sistem orientasi, sistem
saling keterhubungan dari posisi-posisi dan peran-peran, dan sistem komunikasi.
Kelompok dipandang sebagai sistem yang terbuka, yang dianalogikan dari konsep
biologi. Teori sistem menekankan kepada berbagai jenis input ke dalam sistem
dan output keluar sistem. Menurut Slamet (2006), sistem sosial adalah suatu
kesatuan dari banyak unsur yang dapat menghasilkan suatu output tertentu. Sistem
terbentuk oleh adanya komponen atau unsur-unsur yang berhubungan satu sama
lain membentuk suatu jaringan. Masing-masing komponen mempunyai fungsi
sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Fungsi komponen yang satu
dipengaruhi oleh fungsi komponen lain yang berhubungan dengannya. Kelompok
sebagai sistem sosial memiliki beberapa ciri misalnya dalam kelompok terdapat
orang-orang yang saling berinteraksi; mempunyai pola perilaku yang teratur dan
sistematis; bisa diidentifikasi bagian-bagiannya; dan bisa dilihat sebagai sistem
sosial. Sistem sosial terdiri dari interaksi yang terpola dari para anggotanya.
Sistem sosial merupakan interaksi dari beragam individu yang hubungannya satu
dengan yang lain diorientasikan kepada definisi dan mediasi dari pola
simbol-simbol terstruktur dan harapan-harapan. Dalam sistem sosial, terdapat interaksi
Kelompok - kelompok sosial bersifat dinamis dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, selalu bergerak dan aktif. Dalam sosiologi gerak perubahan dan
pergerakan kekuatan yang ada dalam kelompok lazim disebut Dinamika
Kelompok. Menurut Soekanto S (1990) definisi dinamika kelompok di dalam
kelompok sosial cenderung tidak merupakan kelompok yang statis, akan tetapi
selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas
maupun bentuknya. Dinamika kelompok diartikan sebagai suatu studi yang
menganalisis berbagai kekuatan yang menentukan perilaku anggota dan perilaku
kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok untuk
mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dinamika kelompok akan
mencakup faktor-faktor yang menyebabkan suatu kelompok itu hidup, bergerak,
aktif, efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Jetkins (1950) dalam
Sudaryanti (2002), Dinamika Kelompok merupakan kajian terhadap
kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan
menentukan perilaku anggota kelompok dan perilaku kelompok yang
bersangkutan, untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi
tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut. Menelaah
dinamika kelompok berarti menelaah kekuatan-kekuatan yang muncul dari
berbagai sumber di dalam kelompok, mencoba menerangkan
perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok dan mencoba menemukan serta
mempelajari keadaan dan gaya yang dapat mempengaruhi kehidupan kelompok.
Lebih lanjut Horton dan Hunt (1999) mengutarakan bahwa dinamika kelompok
mempelajari interaksi dalam kelompok dan pemecahan masalah serta
pengambilan kesimpulan untuk mencapai pemahaman dan penanggulangan
masalah organisasi.
Menelaah dinamika kelompok berarti menelaah kekuatan-kekuatan yang
muncul dari berbagai sumber didalam kelompok. Menurut Slamet (1978) dalam
Tonny (1988) kekuatan-kekuatan didalam kelompok tersebut, yaitu:
1. Tujuan Kelompok (Group Goals)
Tujuan kelompok merupakan gambaran tentang sesuatu hasil yang
14
tujuan kelompok karena kelompok mempunyai tujuan yang jelas dan anggota
kelompok mengetahui arah kelompok. Akibatnya tujuan kelompok sebagai salah
satu unsur dinamika kelompok menjadi kuat karena kegiatan anggota kelompok.
Anggota kelompok yang berorientasi kepada kelompoknya (group oriented
motives) menggambarkan kesetiaan atas kelompok sehingga dengan tercapainya tujuan kelompok mengakibatkan masing-masing anggota kelompok merasa puas.
Tujuan kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok menjadi semakin
lemah jika tujuan kelompok semakin tidak mendukung tujuan anggota kelompok.
2. Struktur Kelompok (Group Structure)
Struktur kelompok yaitu hubungan antara individu-individu di dalam
kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peranan masing-masing individu.
Kelompok yang telah memiliki struktur yaitu kelompok yang telah memiliki
hubungan yang stabil antar anggota kelompok. Struktur kelompok berhubungan
dengan struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan, tugas dan pembagian
kerja, struktur komunikasi dan bagaimana aliran komunikasi terjadi dalam
kelompok serta sarana bagi kelompok untuk berinteraksi. Struktur kelompok
sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin lemah jika pengambilan
keputusan kelompok semakin didominasi oleh orang-orang tertentu, Struktur
tugas menjadi semakin baik jika masing-masing anggota kelompok semakin
merasakan terlibat dalam tugas-tugas kelompok. Semakin baik struktur tugas
maka struktur kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin
kuat. Dalam struktur komunikasi, anggota kelompok menjadi puas jika
komunikasi di dalam kelompok lancar dan struktur kelompok menjadi semakin
kuat. Sedangkan dalam proses interaksi, struktur kelompok semakin kuat jika
semakin besar kemungkinan berinteraksi.
3. Fungsi Tugas (Task Function)
Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok
sehingga tujuannya tercapai. Kriteria yang digunakan untuk melihat fungsi tugas,
adalah (1) fungsi memberi informasi, kelancaran arus-arus informasi
menunjukkan fungsi tugas berjalan dengan baik sehingga fungsi tugas sebagai
salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat; (2) fungsi memuaskan
fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat; (3)
fungsi menyelenggarakan koordinasi, semakin baik penyelenggaraan koordinasi
maka fungsi tugas semakin baik yang berarti fungsi tugas sebagai salah satu unsur
dinamika kelompok semakin kuat; (4) fungsi menghasilkan inisiatif, semakin
tinggi tingkat inisiatif kelompok maka fungsi tugas semakin baik yang berarti
fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat; fungsi
mengajak untuk berperanserta, semakin sering kelompok mengajak anggotanya
berperanserta dalam setiap kegiatan kelompok maka fungsi tugas semakin baik,
dan fungsi tugas semakin kuat; fungsi menjelaskan kepada anggota tentang segala
sesuatu yang kurang jelas maka fungsi tugas semakin baik. Dengan demikian
fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat.
4. Pembinaan Kelompok (Group Building and Maintenance)
Pembinaan kelompok dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan
kehidupan kelompok. Usaha mempertahankan kehidupan kelompok dapat dilihat
dari (1) peranserta semua anggota kelompok, (2)adanya fasilitas dalam
pelaksanaan pembinaan kelompok, (3) adanya kegiatan kelompok, (4)adanya
kesempatan mendapatkan anggota baru, dan (5)adanya sosialisasi sebagai proses
pendidikan yang membuat anggota mengetahui norma, tujuan dan lain-lainnya
didalam kelompok. Apabila semua ciri tersebut ada di dalam kelompok maka
pembinaan kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat.
5. Kekompakan Kelompok (Group Cohesion)
Anggota kelompok yang tingkat kekompakan kelompoknya tinggi lebih
terangsang untuk aktif mencapai tujuan kelompok dibandingkan anggota
kelompok yang tingkat kekompakan kelompoknya rendah. Kekompakan
kelompok yaitu adanya keterikatan anggota kelompok terhadap kelompoknya.
Tingkat rasa keterikatan yang berbeda-beda menyebabkan adanya perbedaan
kekompakan. Tujuh faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok, yaitu :
(1)kepemimpinan kelompok dapat menumbuhkan rasa kesamaan diantara anggota
kelompok, (2)anggota kelompok menunjukkan kemauan dan saling memilki
sehingga kelompok terasa sebagai milik bersama, anggota kelompok memiliki
16
6. Suasana Kelompok (Group Atmosphere)
Kelompok mempunyai suasana yang menentukan reaksi anggota terhadap
kelompoknya. Suasana kelompok yang dimaksud yaitu rasa hangat dan setia
kawan, rasa takut dan saling mencurigai, sikap saling menerima dan sebagainya.
Kelompok yang suasananya kondusif adalah kelompok yang memiliki suasana
dimana anggotanya merasa saling diterima dan dihargai. Demikian juga halnya
jika suasana kelompok penuh rasa persahabatan maka kelompok menjadi menarik.
Faktor yang mempengaruhi suasana kelompok, yaitu : hubungan antara anggota
kelompok, kebebasan berperanserta dan lingkungan fisik.
7. Tekanan Pada Kelompok (Group Pressure)
Tekanan pada kelompok ialah segala sesuatu yang menimbulkan tegangan
pada kelompok untuk menumbuhkan dorongan berbuat sesuatu dan tercapainya
tujuan kelompok. Sistem penghargaan maupun hukuman bagi anggota kelompok
merupakan salah satu tekanan pada kelompok. Memberi penghargaan kepada
anggota kelompok yang berbuat baik dan menghukum anggota yang berbuat salah
terhadap kelompok menimbulkan ketegangan psikologis sehingga mempengaruhi
dorongan berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan kelompok.
8. Efektifitas kelompok
Efektifitas kelompok mempunyai pengaruh timbal balik dengan
kedinamisan kelompok. Kelompok yang efektif meningkatkan kedinamisan
kelompok. Kelompok yang dinamis meningkatkan efektifitasnya. Efektifitas
dilihat dari segi : (1) produktivitas, moral dan (2)kepuasan anggota. Tercapainya
tujuan kelompok dipakai mengukur produktivitas. Semangat dan sikap anggota
dipakai mengukur moral misalnya para anggota merasa bangga dan bahagia
berasosiasi dengan kelompoknya. Keberhasilan anggota mencapai tujuan pribadi
dipakai mengukur kepuasan anggota. Semakin berhasil kelompok mencapai
tujuannya, semakin bangga anggota berasosiasi dengan kelompoknya dan semakin
puas anggota karena tujuan pribadinya tercapai, maka kelompok semakin efektif.
Dengan demikian efektifitas kelompok sebagai salah satu unsur dinamika
kelompok semakin kuat.
Dinamika kelompok dalam penelitian ini akan dilihat sari 8(delpan) unsur
(I)Tujuan
Tujuan kelompok yang dianalisis dilihat dari indikator-indikator yaitu:
hubungan tujuan dengan anggota, kejelasan tujuan dan kesepakatan tujuan.
(II) Struktur Kelompok
Indikator yang digunakan untuk melihat struktur kelompok dalam tujuan
ini yaitu; struktur kekuasaan, struktur tugas dan struktur komunikasi.
(III). Fungsi Tugas
Dalam melihat fungsi tugas kelompok ini digunakan indikator: pemberian
informasi, pemberian dorongan belajar, pemberian penjelasan dan penyalur sarana
produksi.
(IV). Pembinaan dan Pemeliharaan Kelompok
Dalam melihat pembinaan kelompok ini digunakan indikator: peningkatan
partisipasi, pengadaan fasilitas kelompok, jenis kegiatan kelompok, adanya
kontrol sosial, adanya koordinasi dan komunikasi antar anggota kelompok.
(V). Kekompakan Kelompok
Indikator yang digunakan untuk melihat kekompakan kelompok adalah:
kerjasama, kinerja pengurus kelompok dan keanggotaan kelompok.
(VI). Suasana Kelompok
Indikator lingkungan fisik dan interaksi dalam kelompok digunakan untuk
melihat hal suasana kelompok.
(VII). Tekanan Pada Kelompok
Ada dua indikator untuk melihat tekanan kelompok, yaitu: tekanan dari
dalam dan tekanan dari luar.
(VIII) Efektivitas Kelompok
Ada tiga indikator untuk melihat efektivitas kelompok, yaitu: produktivitas
kelompok, moral kelompok dan kepuasaan.
2.1.1.2. Kelompok Tani
Menurut Departemen Pertanian (1989), kelompok tani adalah kumpulan
petani yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi
18
bersama. Penumbuhan kelompok tani didasarkan atas faktor-faktor pengikat
antara lain: a) adanya kepentingan bersama antara anggotanya; b) adanya
kesamaan kondisi sumberdaya alam dalam berusahatani; c) adanya kondisi
masyarakat dan kondisi sosial yang sama; d) adanya saling percaya mempercayai
diantara sesama anggota. Kerjasama antara individu anggota kelompok dalam
proses belajar, proses berproduksi, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil untuk
peningkatan pendapatan dan kehidupan yang layak dapat dijalin melalui
pendekatan kelompok (Abbas, 1995).
Kelompok tani secara khusus biasanya mempunyai ciri-ciri: 1) antara
sesama anggota saling mengenal dengan baik, akrab dan saling mempercayai; 2)
mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusahatani; 3)
memiliki kesamaan-kesamaan seperti dalam tradisi/kebiasaan, pemukiman,
hamparan usahatani, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial; dan 4) bersifat
non formal, dalam arti tidak berbadan hukum tetapi mempunyai pembagian tugas
dan tanggungjawab atas kesepakatan bersama baik tertulis atau tidak (Departemen
Pertanian, 1989).
Terbentuknya kelompok tani tersebut memberikan banyak manfaat bagi
masyarakat. Kelompok tani ini akan berfungsi sebagai kelas belajar, wahana
bekerjasama dan unit produksi serta sebagai sarana untuk menyampaikan suatu
program. Oleh sebab itu, pembentukan kelompok dalam rangka pelaksanaan
program merupakan salah satu alternatif untuk keberhasilan program. Selain itu
kelompok dapat berfungsi sebagai wadah kerjasama antar pesanggem, dalam hal
ini adalah: modal, tenaga kerja, dan informasi serta lebih efektif melakukan
kontrol sosial (Wong 1979 dalam Suharjito 1994).
Kelompok sosial seperti kelompok tani ini bukan merupakan kelompok
yang statis, karena pasti mengalami perkembangan serta perubahan sebagai akibat
formasi ataupun reformasi dari pola-pola didalam kelompok tersebut, dan karena
pengaruh dari luar (Soekanto S, 1990). Lebih lanjut Soekanto S mengutarakan
bahwa perubahan dalam setiap kelompok sosial, ada yang mengalami perubahan
secara lambat, namun adapula yang mengalami perubahan secara cepat (Soekanto
S, 1982). Suatu kelompok yang dinamis akan mudah melakukan kerjasama
kelompok yang dinamis ditandai oleh selalu adanya kegiatan ataupun interaksi
baik di dalam maupun dengan pihak luar kelompok untuk secara efektif dan
efisien mencapai tujuan-tujuannya.
2.1.1.3. Hutan Rakyat
Pengertian dan Dasar Hukum Hutan Rakyat
Pengertian hutan rakyat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan SK Menteri Kehutanan No.
49/Kpts-II/1997 adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan ketentuan luas minimum
0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50% dan atau pada
tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman. Adapun tujuan usaha
hutan rakyat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penyediaan bahan
baku industri, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan mutu lingkungan.
Hutan rakyat ini dapat dibangun pada lahan hak milik dan hak-hak lainnya serta
pada kawasan hutan yang dapat dikonversi yang tidak bertumbuhan pohon-pohon.
Pendapat Hardjosoediro (1981), Hutan rakyat adalah hutan yang
pengelolaannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat baik pada lahan
individu, lahan komunal (bersama), lahan adat maupun lahan yang dikuasai oleh
negara. Hutan rakyat atau hutan milik adalah semua hutan yang ada di Indonesia
yang tidak berada di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah, dimiliki oleh
masyarakat, proses terjadinya dapat dibuat oleh manusia, dapat terjadi secara
alami dan dapat juga karena upaya rehabilitasi tanah kritis.
Lebih lanjut Hardjanto,2000 ( dalam Daniyati,2009) menegaskan bahwa
hutan rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang dinyatakan
kepemilikan lahan, karenanya hutan rakyat juga disebut hutan milik. Hutan rakyat
yang ada di lokasi lahan milik perorangan dikelola berdasarkan keinginan
pemiliknya, sedangkan hutan rakyat yang ada di lahan milik kelompok dikelola
secara kelompok/komunal yang terikat oleh peraturan kelompok. Sementara itu
Hinrichs et.al, 2008 (dalam Daniyati, 2009) memandang bahwa hutan rakyat
20
Sistem pengelolaan hutan rakyat tidak mengarah hanya pada kayu, namun
lebih pada pengembangan pengelolaan hasil hutan non kayu sebagai produk
utama dari sistem hutan rakyat. Pada umumnya hutan rakyat tidak berwujud
suatu kawasan hutan yang murni, melainkan berdiri bersama-sama dengan
penggunaan lahan yang lain, seperti tanaman pertanian, tanaman perkebunan,
rumput pakan ternak atau dengan tanaman pangan lainnya yang bisanya disebut
dengan pola Agroforestry atau wanatani. Pola Agroforestry atau wanatani
bermanfaat secara ganda, disamping meningkatkan pendapatan petani, juga
menjaga kelestarian lingkungan (ekologi) karena pola ini berorientasi pada
pemanfaatan lahan secara rasional baik dari aspek ekologi, ekonomi, maupun
aspek sosial budaya (Fauzi, 2005).
2.1.1.4. Kemandirian Kelompok Tani
Ismawan (1994) mengemukakan bahwa definisi kemandirian adalah
kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat digunakan
untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berkelanjutan. Sedangkan
Kartasasmita mengartikan bahwa kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap
seseorang atau suatu bangsa mengenali dirinya, masyarakatnya, serta semangat
dalam menghadapi tantangan-tantangan. Kemandirian juga dapat diartikan
sebagai perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan oleh kemampuan dan
kebebasan menentukan perilaku yang terbaik (Hubeis, 1992). Berdasarkan
beberapa pendapat tersebut diatas, kemandirian dapat didefinisikan sebagai
keberadaan individu atau kelompok dalam melangsungkan kehidupan yang serasi
dan berkelanjutan dengan kemampuan sendiri. Kemandirian petani adalah suatu
kondisi yang dapat ditumbuhkan melalui proses pemberdayaan (empowerment).
Kemandirian petani dapat diartikan sebagai perwujudan kemampuan (perilaku
aktual yang ditampilkan) petani untuk memanfaatkan segala potensi dirinya dalam
menjalankan agribisnis sesuai kehendak sendiri (merdeka) dan diyakini
manfaatnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
Menurut Steinberg (2001) menjelaskan bahwa dimensi kemandirian
(behavioral autonomy) dan kemandirian nilai (values autonomy). Harigust (1972) menambahkan kemandirian terdiri dari beberapa aspek yaitu: emosi, ekonomi,
intelektual dan sosial. Soedijanto (2001) kegiatan penyuluhan pertanian dalam
pembangunan sistem dan usaha agribisnis harus memiliki sasaran tercapainya
kemandirian petani dan perilaku agribisnis lainnya yang meliputi kemandirian
material, kemandirian intelektual dan kemandirian pembinaan. Menurut Badan
Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM dan LPM UNIBRAW, 2001
(dalam Marliati, 2008) kemandirian petani dalam beragribisnis dicirikan oleh
empat elemen pokok, yaitu terdiri dari : kemandirian intelektual, kemandirian
sikap mental, kemandirian manajemen dan kemandirian material.
2.1.1.5. Karakteristik individu
Faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan tingkat dinamika
kelompok tani dan kemandirian anggota kelompok (petani) adalah karakteristik
individu/anggota. Karakteristik adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang melekat pada
sesuatu (benda, orang atau mahluk hidup lainya) yang berhubungan dengan
berbagai aspek kehidupannya (Mardikanto, 1993). Lebih jauh, Mardikanto (1993)
memberikan contoh tentang karakteristik individu, yaitu sifat-sifat yang melekat
pada diri seseorang yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupannya,
antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, status sosial dan agama.
Lionberger (1960) mengemukakan bahwa karakteristik individu atau personal
adalah semua faktor yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan
lingkungan, yaitu umur, pendidikan dan karaktersitik psikologis. Karakteristik
psikologis ialah rasionalitas, fleksibilitas mental, orientasi pada usahatani sebagai
bisnis, dan kemudahan menerima inovasi. Merujuk pada pengertian tersebut,
maka yang dimaksud dengan karakteristik individu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat
pribadi yang dimiliki seseorang yang diwujudkan dalam pola pikir, sikap dan
tindakannya terhadap lingkungan.
Karakteristik individu atau petani dalam penelitian ini adalah (1)umur,
(2)pendidikan formal, (3)pendidikan non formal, (4)jumlah tanggungan keluarga,
22
Menurut Padmowihardjo (2002) menyatakan bahwa umur bukan merupakan
faktor psikologis. Terdapat dua faktor yang menentukan kemampuan seseorang
berhubungan dengan umur. Faktor pertama adalah mekanisme belajar dan
kematangan otak, organ-organ sensual dan otot organ-organ tertentu. Faktor kedua
adalah akumulasi pengalaman dan bentuk-bentuk proses belajar lainnya. Umur
menggambarkan pengalaman dalam diri seseorang sehingga terdapat keragaman
tindakannya berdasarkan usia yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa umur
merupakan suatu indikator tentang kapan sutau perubahan harus terjadi.
Mardikanto (1993) menyatakan bahwa pendidikan petani umumnya
mempengaruhi cara dan pola pikir petani dalam mengelola usahatani. Pendidikan
yang relatif tinggi dan umur yang muda menyebabkan petani lebih dinamis. Salah
satu faktor yang dapat mengubah pola pikir dan daya nalar petani adalah
pendidikan( Soekartawi, 1986). Menurut Tjondronegoro (Sastraatmaja, 1986),
bahwa pendidikan non formal merupakan perpaduan dari kegiatan mengubah
minat atau keinginan, menyebarkan pengetahun, ketrampilan dan kecakapan
sehingga diharapkan terjadinya perubahan perilaku (sikap, tindakan dan
pengetahuan). Menurut Kusnadi (2006), pendidikan formal memiliki hubungan
yang nyata terhadap efektivitas kelompok tani.
Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya orang yang menjadi
tanggungan baik keluarga maupun bukan yang tinggal serumah dan menjadi
tanggungjawabnya (Soekartawi, 1986). Jumlah anggota keluarga berpengaruh
terhadap kegiatan ekonomi suatu keluarga (Asdi, 1996). Menurut Istiyanti dan
Hadidarwanto (1999), bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh nyata
terhadap perilaku petani terutama terhadap pengambilan resiko dalam berusaha
tani.
Lahan merupakan sarana produksi bagi usahatani, termasuk salah satu
faktor produksi dan pabrik hasil pertanian. Lahan adalah sumberdaya alam fisik
yang mempunyai peranan penting dalam berbagai segi kehidupan manusia
khususnya petani (Mosher, 1986). Lahan usahatani merupakan aset bagi petani
dalam menghasilkan produksi dan sekaligus sumber kehidupan.
Mosher (1986) mengemukakan bahwa pengalaman berusahatani
dalam usahataninya. Menurut Padmowihardjo (2002) bahwa pengalaman, baik
yang menyenangkan maupun yang mengecewakan akan berpengaruh pada proses
belajar seseorang. Seseorang yang pernah mengalami keberhasilan dalam proses
belajar, maka ia telah memiliki perasaan optimis akan keberhasilan di masa
mendatang, Sebaliknya, seseorang yang pernah memiliki pengalaman
mengecewakan, maka dia telah memiliki perasaan pesimis untuk dapat berhasil.
Pengalaman seseorang bertambah sejalan dengan bertambahnya usia.
Kusnadi (2006) berpendapat bahwa masa keanggotaan memiliki hubungan
yang nyata terhadap efektivitas kelompok tani. Lamanya seorang petani menjadi
anggota kelompok akan berdampak kepada pengalaman yang dimiliki sebagai
anggota kelompok. Setiap anggota kelompok memiliki masa keanggotaan yang
dapat bersamaan dan juga dapat berbeda-beda.
Menurut Rogers dan Shoemoker (1995) sikap kekosmopolitan akan dapat
mempertinggi kemampuan empati dan daya empati. Kekosmopolitan dapat
diartikan sebagai sifat-sifat keterbukaan petani terhadap dunia luar dan dapat
dengan mudah menerima bentuk ide-ide baru dalam rangka pembaharuan.
2.1.1.6. Keberlanjutan Usaha Ekonomi
Pada awalnya konsep keberlanjutan (sustainable) merupakan konsep yang
banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai usaha-usaha yang dilakukan
mempertahankan keberlangsungan atau keberlanjutan suatu pembangunan yang
akan dilakukan di masa yang akan datang. Namun pada saat ini, penerapan konsep
keberlanjutan (sustainable) lebih menitikberatkan pada perlunya keseimbangan
antara berbagai aspek yang ada dalam pembangunan tersebut, yaitu aspek
lingkungan, ekonomi dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep
keberlanjutan (sustainable) harus berbicara untuk jangka waktu yang lama dan
perlu menerapkan pendekatan yang terintegrasi. Disamping itu keberlanjutan juga
menekankan perlunya penerapan teknologi praktis untuk memanfaatkan seoptimal
mungkin sumber-sumber yang ada guna meningkatkan kesejahteraan anggota
masyarakat (dalam Tampubolon Joyakin, 2006).
24
to remain productive while maintaining the resource base. Artinya bagaimana kita harus dapat mengelola sumberdaya yang ada untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan manusia (human need) dengan tetap menjaga keseimbangan dan
kelestarian sumberdaya yang ada.
Untuk menjaga keberlanjutan program, maka pelaksanannya harus
dilandasi oleh konsep-konsep tertentu yang dapat menjamin bahwa program ini
dapat dan harus sampai pada kelompok sasaran (target group) untuk mencapai
tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membawa
peningkatan sumberdaya manusia dan sumberdaya social (social capital) dari
kelompok sasaran (Khandker,et al.,1995 dalam Yuliarso, 2004). Di dalam
keberlanjutan perlu adanya unsur kemandirian, seperti yang dikemukakan oleh
Hubeis (1992).
2.1.1.7. Kepemimpinan
Dinamika dalam suatu kelompok akan sangat terkait peran pemimpin
kelompok dalam menggerakkan para anggotanya untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Tersirat juga didalamnya proses kepemimpinan yang terjadi dalam
mewujudkan dan mempertahankan para anggota kelompok dalam mengambil
keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan program dimana bimbingan dan
arahan tersebut dapat mempertahankan bahkan mencapai keefektifan dari
kelompok. Paranowo (1985) dalam Sri Rejeki (1988) mengelompokkan pemimpin
dalam dua kelompok status kepemimpinan, yaitu (1)pemimpin formal dan
(2)informal. Menurut Kartono (2001) pemimpin formal adalah orang yang oleh
organisasi/lembaga ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan
pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi,
dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai
sasaran organisasi. Sedangkan pemimpin informal adalah orang yang tidak
mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki
sejumlah kualitas unggul, dia memiliki keunggulan sebagai orang yang mampu
mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.
Ciri-cirinya adalah : a) tidak memiliki penunjukkan formal atau legitimasi sebagai
pemimpin dan status kepemimpinannya itu berlangsung selama kelompok yang
bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya, c) tidak
mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas
kepemimpinannya, d) tidak mendapatkan imbalan balas jasa atau apabila
mendapatkan imbalan balas jasa, maka imbalan itu diberikan secara sukarela, e)
tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu, dan f) tidak dapat dihukum
apabila melakukan kesalahan, kecuali pribadinya tidak diakui lagi dan
ditinggalkan massanya. Termasuk dalam pemimpin formal adalah kepala desa dan
perangkatnya,sedangkan pemimpin informal adalah tokoh adat, tokoh agama, dan
kaum intelektual desa.
Dalam Shaw(1971) dikatakan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan
dengan kepemimpinan, yaitu 1) Group goal facilitation (fasilitasi tujuan
kelompok) artinya kemampuan pemimpin dalam membantu kelompok untuk
mencapai tujuannya; 2) Group sociability (sosiabilitas kelompok) artinya
factor-faktor yang diperlukan untuk menjaga kelompok tetap berfungsi dengan baik; 3)
Individual prominence (kemajuan individu) yang meliputi faktor-faktor yang mewakili aspirasi anggota. Peran kepemimpinan dalam kelompok (Gibson et all :
1993) merupakan suatu karakteristik penting dalam kelompok. Pemimpin
kelompok mempunyai pengaruh tertentu terhadap para anggota kelompok. Peran
kepemimpinan juga merupakan faktor penting dalam kelompok informal. Orang
yang menjadi pemimpin kelompok informal pada umumnya dipandang sebagai
anggota yang dihormati dan berwibawa yang berfungsi: 1) membantu kelompok
dalam mencapai tujuannya; 2) memungkinkan para angota memenuhi kebutuhan;
dan 3) mewujudkan nilai kelompok. Pemimpin pada pokoknya merupakan
personifikasi dari nilai, motif dan aspirasi dari keanggotaan; 4) Merupakan pilihan
para anggota kelompok untuk mewakili pendapat mereka dalam interaksi dengan
pemimpin kelompok lain; 5) Merupakan seorang fasilitator yang dapat
menyelesaikan konflik kelompok (Jaka Sulaksana, 2002).
Pemimpin informal seringkali dapat berganti-ganti karena situasi dan
kondisi yang berbeda-beda yang terdapat pada suatu saat tertentu. Seorang
26
yang diangap lebih berwibawa dan pantas sesuai dengan aspirasi keanggotaan
kelompok. Jika ingin tetap menjadi pemimpin dalam jenis kelompok apapun juga,
orang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membantu dan
membimbing kelompok ke arah penyelesaian tugas.
Kepemimpinan muncul dalam dua bentuk yaitu kepemimpinan formal dan
kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal diperoleh individu karena
ditunjuk atau dipilih dalam posisi tertentu oleh otoritas formal dari organisasi.
Kepemimpinan informal dimiliki individu dan menjadi berpengaruh karena
memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh orang lain.
2.1.1.8. Hasil Beberapa Penelitian Tentang Dinamika Kelompok dan Tentang Hutan Rakyat
Hasil penelitian Dinamika Kelompok dan Partisipasi Anggota dalam
Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Nusa Tenggara Barat, yang dilakukan
oleh Syarifuddin (1999) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan
metode deskriptif, dan pengumpulan data dengan menggunakan tehnik survai
melalui wawancara langsung serta pengamatan langsung membuktikan bahwa
kelompok yang dinamis memiliki tingkat partisipasi dan tingkat kemandirian yang
tinggi dibandingkan kelompok yang kurang dinamis.
Penelitian Dinamika Kelompok Tani Hutan berdasarkan pendekatan
psikologi sosial yang dilakukan oleh Sudaryanti (2002) pada Program Perhutanan
Sosial Desa Kemang BKPH Ciranjang Selatan, Kabupaten Cianjur membuktikan
bahwa kelompok yang dinamis mempengaruhi perilaku anggotanya.
Penelitian lain mengenai dinamika kelompok yang juga menggunakan
pendekatan psikologi sosial dengan judul Analisis Dinamika Kelompok Tani
Sebagai Pelaksana Intensifikasi Padi Sawah di WKBPP Cikampek Kabupaten
Karawang Propinsi Jawa Barat oleh Sugandi (1990). Dari hasil analisis data
disimpulkan bahwa faktor suasana kelompok tani yang merupakan salah satu
unsur dinamika kelompok tani memberikan peranan yang besar terhadap
kedinamisan kelompok tani. Sedangkan faktor tekanan kelompok memberikan
Sedangkan penelitian tentang Peranan Pemimpin Lokal dalam
Meningkatkan Dinamika Kelompok oleh Rejeki (1998) membuktikan bahwa
dinamika kelompok dipengaruhi oleh peranan pemimpin lokal.
Hasil penelitian mengenai hutan rakyat, dari Daniyati (2009) dengan judul
Efektifitas Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi Kasus di
Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo)
menyatakan bahwa keberadaan kelompok tani hutan rakyat telah memberikan
banyak manfaat bagi anggota dalam menambah pengetahuan.
Penelitian lainnya mengenai Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan
Rakyat (Kasus di Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah)
oleh Fauzi (2009) membuktikan bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan hutan
rakyat di kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga berada pada kategori
sedang. Partisipasi dalam perencanaan berada pada kategori tinggi, partisipasi
dalam pelaksanaan termasuk dalam kategori sedang dan partisipasi dalam
pemanfaatan hasil termasuk kategori sedang.
2.1.2. Kerangka Pemikiran
Terbentuknya kelompok tani hutan rakyat pada umumnya merupakan
bantuan dari proyek. Bantuan dari proyek serta lingkungan pemberi pengaruh
seperti ketua kelompok, pembina, penyuluh atau lingkungan lain merupakan
stimulus untuk mempersatukan anggota kelompok dalam mencapai tujuan yang
telah ditentukan bersama yaitu pelaksanaan pembangunan hutan rakyat untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Namun perlu diperhatikan, bahwa
keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai tersebut diantaranya disebabkan
proyek masih memberikan bantuan berupa subsidi kepada kelompok tani peserta
proyek (program). Mengacu pada kenyataan tersebut timbul suatu pertanyaan
pokok, apabila program(proyek) berakhir apakah program tersebut akan tetap
berlanjut dan apakah kelompok-kelompok tani yang ada akan tetap survive? Dari
sudut pandang sosiologis, memunculkan pertanyaan; sampai sejauhmana
program tersebut telah melembaga dalam kehidupan petani? Banyak hasil riset
28
nama saja. Namun ada juga kelompok yang semakin maju walaupun tidak ada lagi
bantuan yang diterima oleh kelompok tani. Karena itu, kelompok tani ini perlu
ditumbuhkembangkan agar supaya produktif dan dapat mencapai
tujuan-tujuannya secara efektif.
Mengacu pada kenyataan tersebut, maka dalam penelitian ini akan digali
mengenai (1)keberadaan kelompok tani , apakah kelompok tersebut benar-benar
ada, hidup dan aktif dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, (2)
kemandirian, dan (3) keberlanjutan usaha ekonomi kelompok.
Untuk melihat keberadaan kelompok tani dalam penelitian ini akan
digunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Soekanto(2000), bahwa
kelompok sosial haruslah memenuhi syarat, yaitu: 1) anggota kelompok sadar
bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan; 2) ada
hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya; 3)
ada faktor (misalnya; nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, politik dan lain-lain)
yang sama, sehingga hubungan diantara mereka bertambah erat; 4) berstruktur,
berkaidah dan mempunyai perilaku dan 5) bersistem dan berproses.
Menelaah kehidupan atau eksistensi suatu kelompok berarti menelaah pula
dinamikanya dan selanjutnya menelaah unsur-unsur yang menjadi kekuatan
kelompok. Dalam kaitannya dengan program pengelolaan hutan rakyat yang fokus
pelaksanannya adalah masyarakat yang telah membentuk kelompok dalam hal ini
kelompok tani , maka penelitian ini akan mengkaji proses dinamika kelompok
tani berdasarkan aspek-aspek dinamika kelompok seperti yang dikemukakan oleh
Slamet (1978). Aspek-aspek yang membentuk dinamika kelompok adalah: (1)
Tujuan Kelompok; (2) Struktur Kelompok; (3) Fungsi Tugas ; (4) Pembinaan dan
Pengembangan Kelompok; (5) Kekompakan Kelompok; (6) Suasana Kelompok;
(7) Tekanan Kelompok; (8) Efektifitas Kelompok. Dalam penelitian ini peubah
Dinamika kelompok diukur berdasarkan 8 (delapan) indikator, yaitu : Tujuan
kelompok, Struktur Kelompok, Fungsi Tugas , Pembinaan dan Pengembangan
Kelompok, Kekompakan Kelompok, Suasana Kelompok, Tekanan Kelompok,
Efektifitas Kelompok.
Tujuan kelompok tani yang jelas dan sesuai dengan tujuan anggota