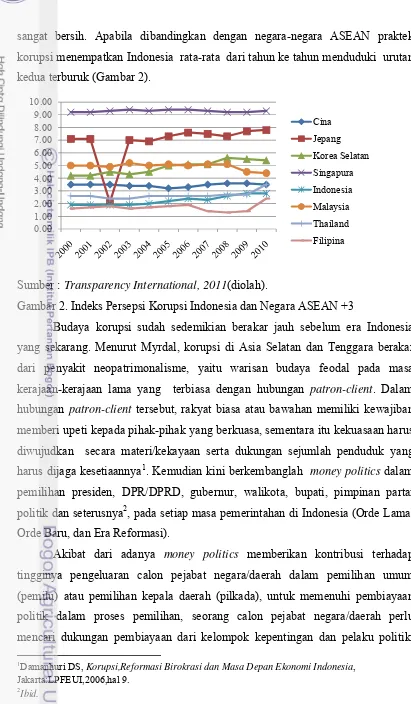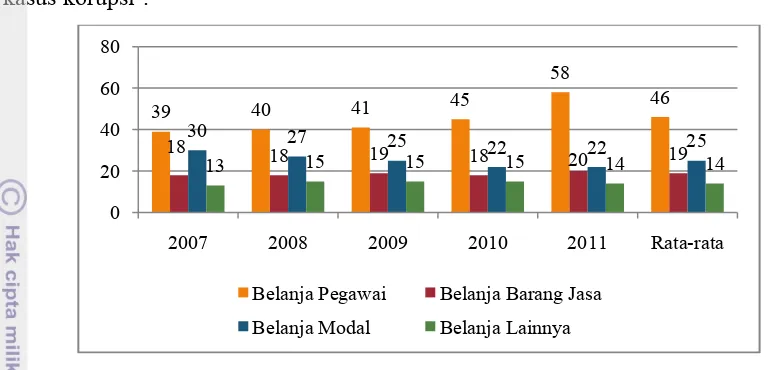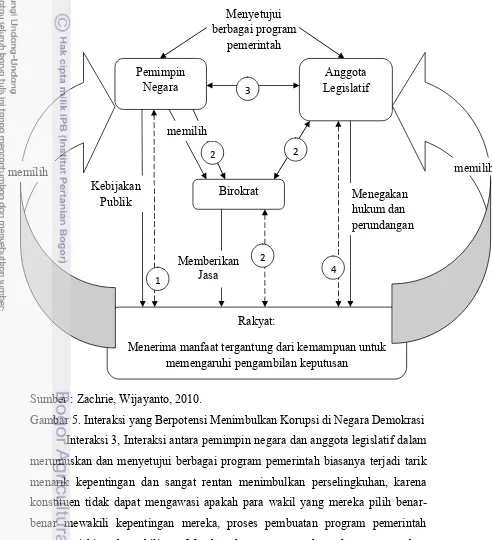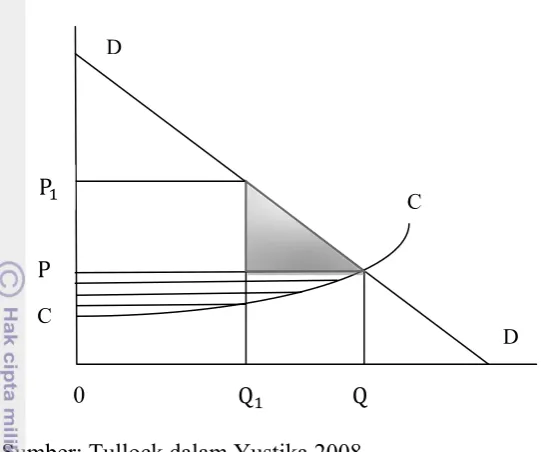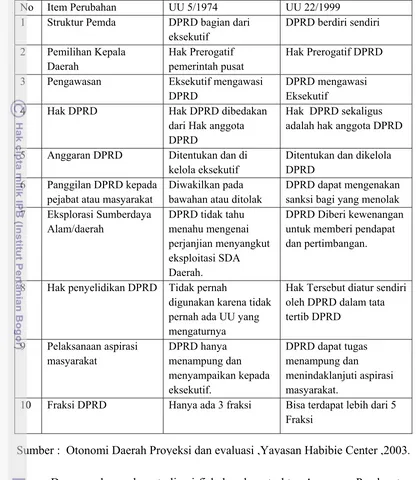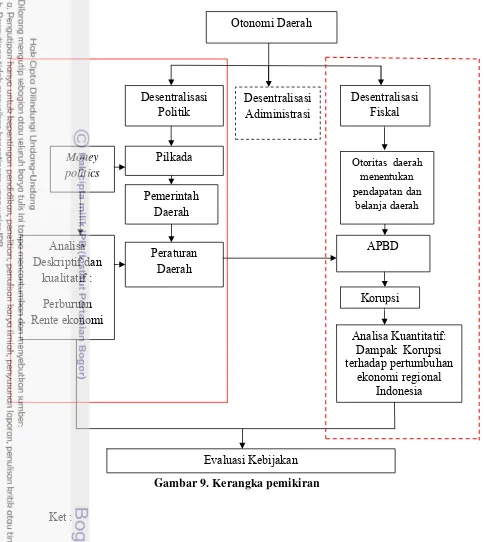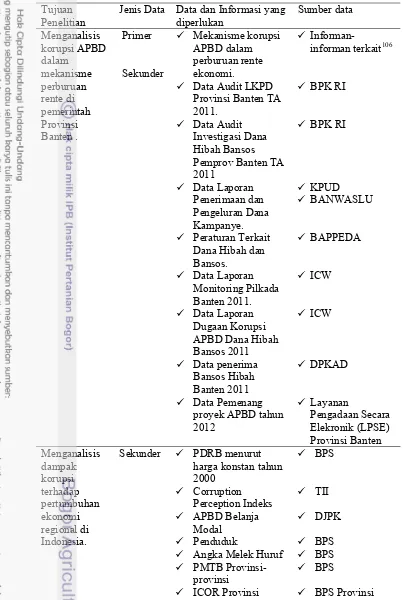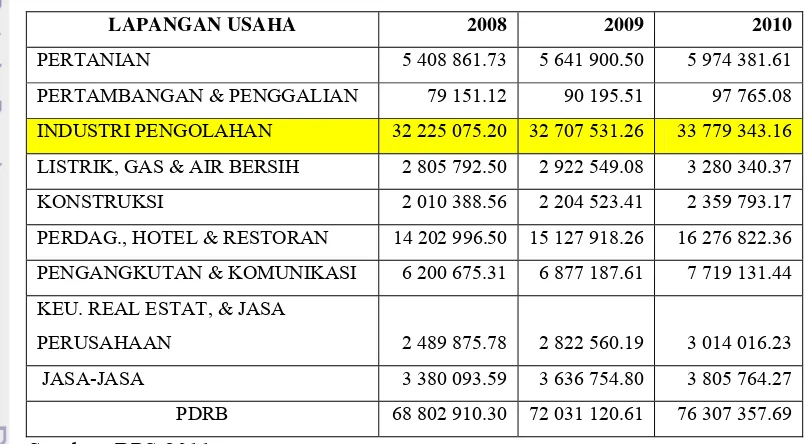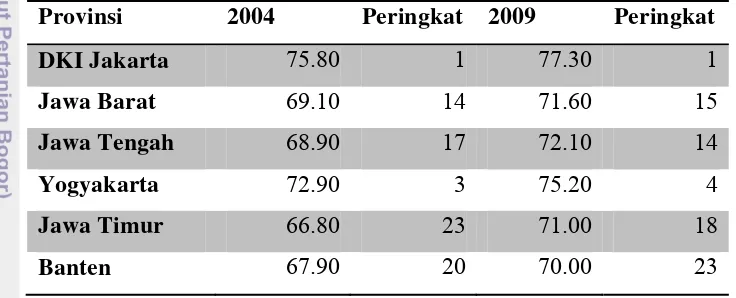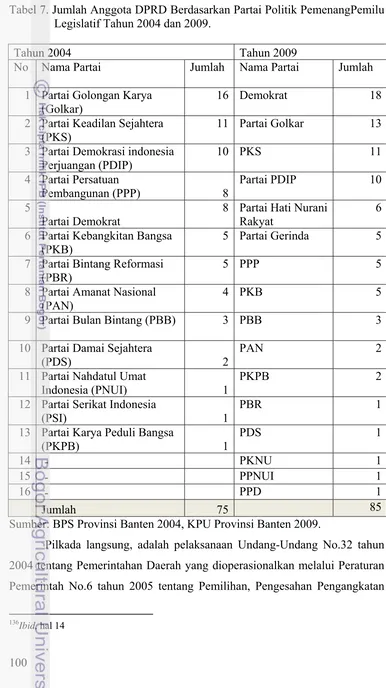DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA
(Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah
Provinsi Banten Tahun 2011)
AIRIN NURAINI
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SURAT PERNYATAAN
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis saya yang berjudul :
DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011)
Merupakan gagasan atau hasil penelitian saya sendiri dengan bimbingan komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan sumbernya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah menyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, April 2013
ABSTRACT
AIRIN NURAINI. 2013. Impact of Corruption to Regional Economic Growth in Indonesia (Study Case: Regional Budget Corruption Assumption Mechanism in Banten Province Government at 2011). (Didin S Damanhuri as Chairman and Muhammad Findi is a Member of the Advisory of Committee)
Decentralization is marked with the announcement of Regulation Number 22 in 1999 about the Region Government, and Regulation Number 25 in 1999 about the Financial Proportion between Central and Region Government. But apparently there are lots of problems in the implementations, one of them is a lot of corruption cases are revealed, with lots of corruption suspects are the authorities in that region and the resource of corruption is the local budget. Finally, that may bring a negative impact for the region economic growth. The aims of this study are: (1) To analyze local budget corruption in the mechanism of rent seeking at Banten Province, (2) To analyze the impact of corruption for the regional economic growth in Indonesia. Result showed that there is a local budget corruption assumptions have been done by the executive and legislative persons with the cooperation with the third person in the local budget managing, that behavior is triggered by the high cost political system. Then the result of the data processing showed that the impact of corruption for the regional economic growth is negative and significant, which means the region economic growth should have been more higher than now. In that case, an effort should be done to increase the region economic growth by eliminating the corruption in Region/national level by starting to create a low budget political system.
RINGKASAN
AIRIN NURAINI. 2013. Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional di Indonesia (studi kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011). Di bawah bimbingan Prof. Dr. Didin S Damanhuri, M.S., DEA dan Dr. Muhamad Findi A, M.E.
Desentralisasi ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomer 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, ternyata mengalami banyak permasalahan dalam implementasinya, salah satunya adalah terkuaknya berbagai kasus korupsi di daerah dengan pelaku korupsi sebagian besar adalah para pemegang kekuasaan di daerah, dengan sumber utama yang di korupsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada akhirnya diduga akan berakibat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada intinya penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis korupsi APBD dalam mekanisme perburuan rente di Pemerintah Provinsi Banten, (2) Menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode campuran, untuk tujuan pertama menggunakan metode deskriptif dan kualitatif yang meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam untuk mengungkap perilaku koruptif yang berbentuk aktivitas pencarian rente ekonomi, dengan pendekatan analisa ekonomi politik, yaitu studi keterkaitan antara fenomena politik dan fenomena ekonomi. Informan/ Narasumber yang dipilih untuk menjawab tujuan pertama yaitu dari pihak pejabat publik (eksekutif, legislatif), Akademisi, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sedangkan untuk mencapai tujuan yang kedua, menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel statis . Data korupsi yang digunakan untuk tujuan kedua adalah indeks korupsi daerah 48 kabupaten/kota di Indonesia yang diperoleh dari Transparency International Indonesia (TII).
Hasilnya, dalam studi kasus Provinsi Banten telah terjadi korupsi APBD dalam aktivitas pencarian rente oknum eksekutif dan legislatif bergandengan tangan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan APBD, perilaku tersebut dipicu oleh adanya sistem politik berbiaya tinggi. Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan, beberapa dokumen pendukung, dan pemberitaan media massa maka dapat diketahui bahwa ada dua korupsi APBD dalam mekanisme perburuan rente di Pemerintah Provinsi Banten. Mekanisme pertama, yaitu mekanisme korupsi APBD pos Belanja (Bantuan Sosial) Bansos dan Hibah dalam APBD yang dapat digunakan sebagai dana taktis pembiayaan kampanye, yang dimulai dari tahap
perencanaan anggaran (by design), meluas ke tahap pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban. Mekanisme kedua, yaitu mekanisme perolehan rente melalui proyek-proyek APBD.
Kemudian pada tahap pelaksanaan, APBD dana hibah dan bansos disalurkan kepada lembaga/ organisasi yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepada lembaga/ organisasi yang dipimpin keluarga/ kerabat Gubernur dan lembaga/ organisasi masyarakat lainnya. Keluarga/ kerabat Gubernur yang memimpin lembaga/ organisasi yang diberi dana hibah bansos juga memiliki badan-badan usaha yang memberikan kontribusi dalam dana kampanye, sehingga menimbulkan dugaan bahwa sebagian kecil dari dana hibah bansos yang diterima bisa diputar kembali untuk dana sumbangan kampanye.
Dugaan yang kedua adalah dana hibah dan bansos bisa langsung digunakan sebagai dana taktis untuk membiayai aktivitas politik dengan dalih diberikan kepada lembaga/ organisasi yang dikuasai lingkaran kelompoknya, sehingga mudah direkayasa secara administratif. Sedangkan penyaluran dana hibah bansos kepada lembaga/ organisasi masyarakat juga bisa dijadikan dana taktis untuk membiayai aktivitas politik maupun kepentingan pribadi/ kelompok yang lain, caranya dengan merekayasa lembaga/ organisasi yang diberi dana hibah dan bansos (lembaga fiktif, alamat tidak jelas, alamat sama) atau juga dengan cara disalurkan kepada masyarakat namun jumlahnya jauh lebih kecil dari nilai pagu anggaran yang ditentukan. Dana hibah bansos yang menjadi dana taktis ini kemudian digunakan dalam membiayai aktivitas politik salah satunya adalah untuk melakukan money poltics. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, tidak ada peraturan tegas yang mengatur sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban, bahkan tidak dilakukan mekanisme monitoring pelaksanaan dan evaluasi pertanggungjawaban.
Untuk mekanisme yang kedua, perolehan rente diperoleh melalui proyek-proyek APBD. Penguasaan proyek-proyek dikoordinasi oleh Gubernur informal atau yang disebut dengan Gubernur Malam, dia memiliki oknum-oknum kepercayaan disejumlah “dinas basah” yang menjaga proyek-proyek APBD, agar akses informasi dengan mudah dia dapatkan. Gubernur informal sebagai pemborong dalam proyek-proyek APBD berkoordinasi dengan Gubernur formal/ jajaran eksekutif dalam menentukan proyek APBD dan siapa saja yang akan menangani proyek. Gubernur formal/ jajaran eksekutif akan menerima beberapa persen dari nilai proyek.
Bagi Gubernur Formal keputusan proyek-proyek APBD dan penentuan pemenangnya adalah salah satu cara mengembalikan modal kampanye bagi dirinya dan pihak-pihak yang telah mendukung pembiayaan pada masa kampanye. Gubernur Malam kemudian mengendalikan DPRD melalui eksekutif agar meloloskan usulan mereka, yaitu dengan cara membeli proyek. Membeli proyek dilakukan dengan memberikan bagian dari proyek atau beberapa persen dari nilai proyek kepada oknum DPRD.
pemenang terakhir, yaitu badan usaha swasta lainnya, sebelum mereka memenangkan suatu proyek maka harus memperoleh restu dari Gubernur informal, badan usaha swasta harus menyetorkan sebesar 20 persen sampai dengan 40 persen dari nilai proyek-proyek APBD.
Setelah mengetahui mekanisme korupsi di salah satu daerah di Indonesia (Banten), kemudian dilakukan analisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional (48 kabupaten/kota) dengan regresi data panel statis menggunakan fixed effect, hasilnya dapat diketahui bahwa setiap kenaikan indeks persepsi korupsi akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi 48 kabupaten/kota di Indonesia sebesar 0.0223 persen, ceteris paribus. Karena variabel indeks persepsi korupsi TII merupakan indeks antara 0 sampai dengan 10, dimana angka 0 untuk korupsi parah, dan 10 untuk kondisi suatu daerah tidak ada korupsi, sehingga semakin tinggi indeks semakin baik. Dengan demikian terbukti bahwa korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Potensi pertumbuhan yang dicapai daerah-daerah seharusnya lebih tinggi daripada yang dicapainya sekarang. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan melakukan pemberantasan korupsi di level daerah/ nasional yang dimulai dengan menciptakan suatu sistem politik yang berbiaya rendah.
Kata kunci : Korupsi, Pertumbuhan ekonomi, Pencarian rente ekonomi.
© Hak Cipta milik IPB, Tahun 2013 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau
DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA
(Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011)
AIRIN NURAINI
Tesis
Sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Tesis : Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia (Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011).
Nama Mahasiswa : Airin Nuraini
Nomor Pokok : H151100231
Mayor : Ilmu Ekonomi
Menyetujui,
Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, M.S.,DEA Ketua
Dr. Muhammad Findi A, M.E. Anggota
Mengetahui,
Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Dr.Ir.R.Nunung Nuryartono, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia (Studi kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011).
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, M.S.,DEA sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak Dr. Muhammad Findi A, M.E., sebagai anggota komisi pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini. Ibu Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc., Agr. selaku penguji luar komisi, serta Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si selaku penguji wakil Program Studi Ilmu Ekonomi atas saran perbaikan tesis. Bapak Dr.Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si selaku Koordinator Mayor Ilmu Ekonomi dan seluruh staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan proses pembelajaran selama penulis kuliah di Mayor Ilmu Ekonomi.
Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang telah bersedia berbagi informasi, terutama pihak dari Indonesian Corruption Wacth (ICW) yang selama ini telah banyak membantu dalam pembuatan tesis ini, juga kepada orang tua ibu Eni Hayani, Ayah Muhammad Arief yang selama ini telah memberikan dukungan semangat, materi, do’a dan kasih sayang kepada penulis, juga suami dan anak tercinta Novan Widianto dan Alisa Adivia atas dukungan semangat dan do’anya. Teman-teman IE angkatan 2010 dan Staff sekretariat IE terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan kerjasamanya selama kuliah.
Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat.
Bogor, April 2013
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 9 Oktober 1984, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Arief dan Ibu Eni Hayani.
Pada tahun 1991 penulis menempuh pendidikan formal di SDN Pengadilan 3 Bogor dan tamat tahun 1997. Setelah tamat dari SD penulis melanjutkan sekolah di SMPN 4 Bogor sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan di SMUN 5 hingga tahun 2003.
Kemudian, pada tahun yang sama melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada Program Studi Ekonomi jurusan Akuntansi. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2007.
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ... v
DAFTAR GAMBAR ... vii
DAFTAR LAMPIRAN... ... x
1. PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 7
1.3. Tujuan Penelitian... ... 9
1.4. Manfaat Penelitian ... 9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 9
2. TINJAUAN PUSTAKA ... 11
2.1. Landasan Teori ... 11
2.1.1. Korupsi... ... 11
2.1.2. Korupsi Di Indonesia... ... 21
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi... ... 26
2.1.4. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi.. ... 34
2.1.5. Korupsi dan Perburuan Rente Ekonomi.. ... 37
2.1.6. Desentralisasi ... 48
2.1.7. Indeks Persepsi Korupsi Transparency International .... 55
2.2. Penelitian Terdahulu ... 57
2.3. Kerangka Pemikiran ... 62
3. METODOLOGI PENELITIAN ... 65
3.1. Jenis dan Sumber Data ... 65
3.2. Metode Analisis Data ... 67
3.4.1. Metode Analisis Mekanisme Rent Seeking Economy Activity………... 67
3.4.2. Model Regresi Data Panel Pertumbuhan Ekonomi ... 71
3.2.2.2 Metode Analisis Regresi Data Panel ... …… 74
4. GAMBARAN UMUM ... 79 4.1. Gambaran Umum Korupsi Daerah (termasuk yang bersumber dari
APBD) di Indonesia ... 79
4.2. Gambaran Umum Provinsi Banten ... … 88
5. HASIL DAN PEMBAHASAN……… ... 5.1. Mekanisme Korupsi APBD dalam Perburuan Rente Ekonomi :
Pendekatan Studi Kasus Provinsi Banten……… ...
5.1.1. Faktor Penyebab Korupsi APBD : Dugaan Kasus Korupsi
Pilkada Gubernur Banten Tahun 2011 ... 105
5.1.2. Mekanisme Dugaan Korupsi APBD Dana Hibah Bansos Provinsi Banten 2011……… 115
5.1.3 Mekanisme Perburuan Rente dalam Dugaan Korupsi
pada Proyek-Proyek APBD Provinsi Banten………... …… 144
5.2. Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di
Indonesia ... 160
5.2.1. Estimasi Model Pertumbuhan Ekonomi ... 161
5.2.2. Evaluasi Model Pertumbuhan Ekonomi ... 164
5.2.3. Pembahasan Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuh
Ekonomi Regional di Indonesia ... 165
5.2.4. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Banten (Analisis ICOR) ... 172
6. KESIMPULAN, IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN SARAN ... 175 6.1. Kesimpulan ... 178 6.2. Implikasi Kebijakan dan Saran ... 179
DAFTAR PUSTAKA ... 181
LAMPIRAN ... 187 103
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1. Perubahan Setelah Desentralisasi ……….………...51
2. Tujuan Penelitian, Jenis dan Sumber Data yang diperlukan...66
3. Tren Korupsi APBD Tahun 2009-2011……….………...83
4. PDRB Banten Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2010……...93 5. Perkembangan RLS dan AMH Sebagai Komponen IPM Provinsi Banten
tahun 2000-2010...94 6. Peringkat IPM Provinsi Banten di Pulau
Jawa...95
7. Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik Pemenang Pemilu
Legislatif Tahun 2004 dan 2009...100
8. Daftar Incumbent dalam Pilkada Gubernur Langsung
Banten...102
9. Jumlah Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten Tahun 2011... 114
10. Gambaran Umum Hibah dan Bantuan sosial... ... . ...119
11. Tren Realisasi Anggaran Hibah dan Bansos Provinsi Banten…………... 122
12. Jumlah Voucher dalam Proses Perencanaan………...…127
13. Lembaga Fiktif Penerima Dana Hibah……… 130
14. Lembaga Penerima Hibah yang Memiliki Alamat Sama……….131
15. Daftar Aliran Dana ke Lembaga yang dipimpin Keluarga Gubernur…….132
16. Kepatuhan Instansi Vertikal Kota Serang………135
17. Normatif Pertanggungjawaban Hibah Bansos……….137
19. Badan Usaha Penyumbang Dana Kampanye PilGub Tahun 2011 yang Memenangkan Proyek APBD TA 2012 di Provinsi Banten………153
20. Proyek APBD TA 2012 yang dimenangkan Badan Usaha Milik Keluarga Gubernur………...156
21. Chow test antara Pooled Least Square dan Fixed Effect……….161
22. Hausman Test antara fixed effect dan random effect………162
23. Hasil Regresi Data Panel………..164
24. Interpretasi Hasil Estimasi………...165
25. ICOR tahun 2008 di Pulau Jawa dan Bali………174
DAFTAR GAMBAR
Halaman
20 Mekanisme Dugaan Korupsi APBD dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos……….. 21 Penguasaan Berbagai Aspek Strategis di Provinsi Banten dalam
Lingkaran Keluarga……….... 22 Mekanisme Pengerukan APBD Melalui Penguasaan Proyek-Proyek
APBD di Provinsi Banten………
1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara Lain di Dunia... 1 2 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN +3... 2
3 Postur Belanja APBD 2007-2011 (%)……… 5
4 Jumlah Kasus Korupsi Menurut Lembaga Tahun 2011…... 6 5 Interaksi yang Berpotensi Menimbulkan Korupsi di Negara
Demokrasi... 6 Korupsi dan Kemungkinan Produksi... 35
7 Biaya Monopoli Akibat Prilaku Pencarian Rente………... 41
8 Penentuan Output Oleh Birokrat………. 45
9 Kerangka pemikiran……… 64
10 Tahapan Analisa Studi Kasus Korupsi APBD dalam Perburuan Rente ekonomi………...
11 Tren Korupsi Indonesia berdasarkan Pelakunya Tahun 2011…………. 85 12 Komposisi Realisasi Pendapatan Provinsi Banten tahun Anggaran
2010 dan 2011……….
13 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2001-2011 ………. 92 14 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2008-2011………...
15 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 1961- 2010…... 94
16 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten………... 96
17 Kompilasi Penggunaan Kekuasaan Berdasarkan Modus………... 106 18 Kompilasi Politik Uang Berdasarkan Modus……….. 110
19 Rangkuman berbagai regulasi penyusunan APBD………. 116
71
90
92
142
147
23 Dampak Perubahan (Penambahan) Pengeluaran Pemerintah Terhadap
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. Daftar Informan/Nara Sumber ……… 187
2. Data ICW : Rincian Kejanggalan Penyumbang Dana Kampanye Incumbent 1 Pada Pilkada Banten Tahun 2011 Uji Petik
Terhadap 30 persen dari Jumlah Penyumbang... 188
3. Output pendekatan pooled least square estimasi model
pertumbuhan ekonomi regional. ... 191
4. Output pendekatan fixed effects estimasi model pertumbuhan ekonomi regional………... 192
5. Output pooled least square/ fixed effects testing dengan menggunakan
rendundant fixed effects – likelihood ratio... 193 6. Output pendekatan Random effects estimasi model pertumbuhan
ekonomi regional... 194 7. Output fixed effects/random effects testing dengan menggunakan
correlation random effects-Hausmant test... 195
8. Output hasil estimasi fixed effect dengan GLS weight: cross section weight dan cross section weight (PCSE)... 196
9. Tingkat Korupsi rata-rata tahun 2008 dan 2010 48 ibukota/kabupaten di Indonesia ... ... 197
10. Contoh lembar survey kuisioner TII... ... 198
sangat bersih. Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN praktek
korupsi menempatkan Indonesia rata-rata dari tahun ke tahun menduduki urutan
kedua terburuk (Gambar 2).
Sumber : Transparency International, 2011(diolah).
Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN +3
Budaya korupsi sudah sedemikian berakar jauh sebelum era Indonesia
yang sekarang. Menurut Myrdal, korupsi di Asia Selatan dan Tenggara berakar
dari penyakit neopatrimonalisme, yaitu warisan budaya feodal pada masa
kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan patron-client. Dalam hubungan patron-client tersebut, rakyat biasa atau bawahan memiliki kewajiban memberi upeti kepada pihak-pihak yang berkuasa, sementara itu kekuasaan harus
diwujudkan secara materi/kekayaan serta dukungan sejumlah penduduk yang
harus dijaga kesetiaannya1. Kemudian kini berkembanglah money politics dalam pemilihan presiden, DPR/DPRD, gubernur, walikota, bupati, pimpinan partai
politik dan seterusnya2, pada setiap masa pemerintahan di Indonesia (Orde Lama,
Orde Baru, dan Era Reformasi).
Akibat dari adanya money politics memberikan kontribusi terhadap tingginya pengeluaran calon pejabat negara/daerah dalam pemilihan umum
(pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada), untuk memenuhi pembiayaan
politik dalam proses pemilihan, seorang calon pejabat negara/daerah perlu
mencari dukungan pembiayaan dari kelompok kepentingan dan pelaku politik.
1
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Aditjondro di daerah Poso, menengarai
bahwa para pelaku bisnis di tingkat provinsi dan nasional memiliki kepentingan
sendiri untuk mendukung seorang calon yang pada gilirannya harus “dibayar”
kelak ketika sang calon berhasil terpilih3. Pada akhirnya nanti kebijakan-
kebijakan yang lahir dari para pemerintah negara/daerah sudah tidak lagi
independen, bukan lagi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi
lebih banyak menguntungkan segelintir pihak yang terkait dengan money politics tersebut.
Dalam kondisi seperti yang diuraikan di atas, Myrdal dalam bukunya
Asian Drama pernah memberikan kritikan terhadap negara berkembang yang dikatakan berstruktur lembek (soft state) terutama berlangsung di Asia Selatan dan Asia Tenggara4. Dimana para elite politik di negara-negara tersebut sangat
kompromistik dengan segala bentuk korupsi.
Korupsi bisa menjadi kontributor utama terhadap tingkat pertumbuhan
yang rendah dari banyak negara berkembang5, disamping itu korupsi juga dapat
tumbuh bersama dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, walaupun demikian
pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berkualitas melalui pemborosan
dana pembangunan (high cost economy), sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak merata.
Korupsi tidak menunjukan hubungan langsung terhadap kemiskinan.
Korupsi mempunyai konsekuensi terhadap faktor-faktor yang menentukan
pertumbuhan ekonomi, seperti menghambat investasi, mendistorsi alokasi
sumberdaya, menurunkan kapasitas fiskal dan membuat kualitas infrastruktur
rendah. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat kemiskinan.
Sebagai contoh, untuk pengembangan sumber daya manusia, korupsi membuat
kualitas dan kuantitas sekolah jadi tidak optimal, demikian juga dengan upaya
ketersediaan kebutuhan dasar (basic needs), seperti air bersih, pangan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat Indonesia menjadi
3
Aditjondro (tidak dipublikasikan) dalam Taufik R, Maria P,Dewi D, Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi, Bank Dunia, 2007, hal 15.
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_ dprd.pdf, 28 Desember 2012.
4
Asian Drama dalam Damanhuri DS, Ekonomi Politik dan Pembangunan, Jakarta:LPFEUI, 2010, hal 30.
5
kurang terdidik, kurang gizi dan gampang sakit. Sehingga pada akhirnya
masyarakat Indonesia kurang siap bersaing secara regional maupun internasional.
Dari tahun ke tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
Indonesia jumlahnya terus meningkat. Pada masa Orde Baru APBN diperkirakan
mengalami kebocoran mencapai 30 persen (Incremental Capital Output Ratio/ ICOR) hingga lebih dari 50 persen (Input Output/ IO), dengan demikian sesungguhnya potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 12 persen
menjadi hanya tumbuh 7 persen per tahun6. Pada masa reformasi, dengan adanya
desentralisasi fiskal maka ada sebagian dari APBN yang ditransfer ke daerah.
Desentralisasi atau otonomi daerah/khusus di negeri ini dimulai sejak
berlakunya Undang-Undang (UU) Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomer 5 tahun 1974 tentang
Pemerintahan Daerah, yang diimplementasikan sejak januari 2001. Perubahan
paling penting adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah
menyangkut sektor pelayanan publik7. Bidang pemerintahan yang wajib
dilaksanakan pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja8.
Secara normatif, otonomi daerah merupakan sebuah alat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Pertanyaannya
adalah setelah lebih dari satu dasawarsa lebih otonomi daerah diterapkan, apakah
tujuannya telah tercapai? dari segi ekonomi, peran pemerintah daerah memang
semakin besar, dari berbagai sumber data diketahui beberapa daerah mampu
meningkatkan pendapatan perkapita daerahnya lebih besar daripada pendapatan
perkapita nasional. Namun, hal itu hanya sebatas data, pada kenyataannya rakyat
daerah yang penuh sumber daya alam belum tentu sejahtera. Di daerah yang kaya,
6
Damanhuri DS, op. cit, hal 128. 7
Pasal 7 UU No.22/1999 8
seperti Riau, Kalimantan Timur dan Papua sejumlah pejabatnya justru terbelit
kasus korupsi9.
Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2012.
Gambar 3. Postur Belanja APBD, 2007-2011 (%)
Besarnya dana transfer yang berlebihan juga akan memberikan implikasi
bagi daerah untuk menggunakan anggaran secara tidak efisien10. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata masih bias kepentingan elite,
dana yang dialokasilkan untuk elite terlalu besar daripada untuk anggaran
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementrian Keuangan mencatat APBD
periode 2007-2011 rata- rata persentase untuk belanja pegawai lebih tinggi
dibandingkan untuk belanja modal (Gambar 3).
Terlebih lagi sisa persentase dari anggaran yang dimaksudkan untuk
membangun ekonomi masyarakat masih juga dikorupsi oleh oknum pemerintah
daerah maupun masyarakat. Kompleksitas permasalahan yang muncul
kepermukaan adalah terkuaknya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat
daerah dan anggota legislatif daerah. Jadi bukan hanya saja kekuasaan yang di
desentralisasikan dari pusat ke daerah tapi juga korupsi itu sendiri. Desentralisasi
yang tidak diiringi dengan kesiapan pemerintah daerah yang mengelola
menorehkan tambahan panjang sejarah korupsi di Indonesia.
9
Elok D. Briggita I (Maria Hartiningsih), Korupsi yang Memiskinkan, Jakarta:PT.Kompas Media Nusantara, 2011, hal 73.
10
Mardiasmo dalam Suparno, Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian di Indonesia, Tesis, FEM IPB, 2010.
39 40 41 45
58
46
18 18 19 18
20 19
30 27 25
22 22 25
13 15 15 15 14 14
0 20 40 60 80
2007 2008 2009 2010 2011 Rata-rata
bidang pemerintah, sangat rentan menyebabkan penyalahgunaan wewenang
dalam penggunaan anggaran.
1.2Perumusan Masalah
Sejak Otonomi daerah, semakin banyak kasus korupsi di berbagai daerah
yang terungkap dengan objek utamanya adalah APBD. Korupsi di daerah yang
diwarnai korupsi dalam proses politik telah membelokan tujuan dari pelaksanaan
desentralisasi.
Praktek korupsi di pemerintahan daerah terjadi di berbagai negara di
dunia, begitu pula negara Indonesia. Untuk menangkap gambaran korupsi di
salahsatu daerah di Indonesia, maka dilakukan penelitian kasus korupsi di wilayah
Provinsi Banten. Wilayah Banten terutama Kota/kabupaten Tanggerang
merupakan wilayah penyangga ibukota negara. Setelah lebih dari satu dasawarsa
otonomi daerah ternyata Provinsi Banten tidak menunjukan prestasi yang
menggembirakan.
Diperkuat sejumlah data, seperti misalnya pada tahun 2008, Indeks
governance di Banten hanya rata-rata 0.3 dari skala 1 yang berarti sangat rendah,
menurut Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
(PSKK UGM). Demikian juga Indeks Integritas Pemerintah daerah yang menurut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang, yakni hanya 5.88 dari skala 10.
Juga Indeks Persepsi Korupsi menurut Transparency Internasional Indonesia (TII) hanya sebesar 4.6 dari skala 10. Terakhir, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut Banten sebagai provinsi terkorup ke-15 dari 33 provinsi di
Indo-nesia.
Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) di daerah provinsi Banten
yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2011 untuk periode 2011-2016, sebagai
potret salahsatu pelaksanaan pilkada di Indonesia. Pilkada yang terbebas dari
praktek korupsi pemilu, dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu penyalahgunaan
kekuasaan, politik uang, dan kepatuhan terhadap dana kampanye. Berdasarkan
data ICW pilkada di pemerintah Provinsi Banten telah meninggalkan banyak
Bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam para pendukung
dana kampanye melibatkan para pemburu rente yang mengincar kekayaan alam
tersebut, namun pada kasus Provinsi Banten para pemburu rente mengincar
proyek-proyek APBD. APBD menjadi sasaran bagi para pencari rente ekonomi
yang mengharapkan keuntungan tanpa dasar, para pencari rente bukan hanya
sektor swasta, namun juga pemerintah (politisi dan birokrasi).
Korupsi APBD di daerah biasanya dilakukan bahkan sebelum kepala
daerah berkuasa, sumber pembiayaan dimanipulasi, perburuan rente ekonomi
dilakukan untuk modal kampanye dan kemenangan calon kepala daerah.
Kekuasaan yang diperoleh atas kemenangan kepala daerah dari proses pilkada
yang tidak bersih hanya akan menghasilkan perburuan rente yang lebih luas lagi.
Maka diduga akibat biaya politik yang tinggi (high cost politic) di dalam pilkada adalah salahsatu faktor yang menyebabkan pemborosan/ kebocoran sumber-
sumber ekonomi ( high cost economic) dalam hal ini adalah APBD.
Korupsi memang tidak menunjukan hubungan langsung terhadap
kemiskinan dan upaya perbaikan kebutuhan dasar, tetapi korupsi mempunyai
konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi rendah di daerah yang merupakan
indikator utama dalam pembangunan daerah, yang pada gilirannya pemerintah
daerah (pemda) menjadi tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan
memenuhi kebutuhan dasar. Namun korupsi juga pernah diyakini dapat
memperlancar perekonomian, sebagai uang pelicin (speed money) dalam menjalankan roda bisnis dan perdagangan, yang dapat memfasilitasi pertumbuhan
ekonomi.
Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah korupsi APBD dalam mekanisme perburuan rente ekonomi
di pemerintah Provinsi Banten ?
2. Bagaimanakah dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional
1.3Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka
penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis korupsi APBD dalam mekanisme perburuan rente di
pemerintah Provinsi Banten.
2. Menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di
Indonesia.
1.4Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Memberikan informasi tentang praktek korupsi di daerah.
2. Dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan mampu membantu
masyarakat dan pemerintah meminimalkan korupsi pada tingkat daerah,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengungkap akar permasalahan
dari korupsi yang ada di daerah, juga menyarankan solusi yang tepat
sasaran, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah
dalam mengambil kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.
1.5Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini, menganalisis mekanisme perburuan rente ekonomi dalam
studi kasus dugaan korupsi APBD di pemerintah Provinsi Banten pada tahun
2011. Sangat luas pengertian korupsi maka untuk tujuan pertama penelitian,
memfokuskan pada korupsi di daerah yang terjadi pada APBD. Korupsi APBD
disini adalah korupsi yang mencakup korupsi pada pos-pos yang terdapat dalam
APBD. Dalam konteks ini, korupsi mencakup perilaku koruptif (corruptive behavior) yang berbentuk aktivitas pencarian rente. Analisis yang dilakukan yaitu dengan pendekatan analisa ekonomi politik, yaitu studi keterkaitan antara
fenomena politik dan fenomena ekonomi.
Analisis untuk studi kasus mekanisme perburuan rente ekonomi di
1. Dugaan korupsi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2011.
2. Dugaan korupsi APBD pada Dana bantuan sosial dan hibah tahun
2011.
3. Dugaan korupsi dalam proyek-proyek APBD.
Kemudian, untuk menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan
ekonomi regional dilakukan pada tahun 2008 dan 2010 pada 48 kota/kabupaten di
Indonesia. Untuk tujuan kedua penelitian ini, pengertian korupsi adalah definisi
dari Transparency International, yaitu mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara
tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka
dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer
yang diambil sesuai dari kebutuhan penelitian yaitu hasil dari wawancara
mendalam (in depth interview). Data sekunder yang digunakan diambil dari dokumen-dokumen terkait seperti pemberitaan media massa, hasil penelitian,
dokumen-dokumen pemerintah sertadata lainnya yang relevan dengan penelitian
2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini diuraikan berbagai pustaka yang menjadi dasar dalam
penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari pembahasan teori-teori, penelitian
terdahulu, dan kerangka pemikiran. Sementara itu teori-teori yang dibahas adalah
teori tentang korupsi, pertumbuhan ekonomi, perburuan rente ekonomi dan
desentralisasi. Selain itu ada juga sub-bab pembahasan tentang variabel-variabel
yang membangun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang digunakan dalam
penelitian ini.
Kemudian penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian tentang
korupsi yang berkaitan dengan perilaku pencarian rente, penelitian tentang
korupsi dan pertumbuhan ekonomi, juga penelitian tentang pertumbuhan ekonomi
regional. Setelah mengkaji berbagai teori dan penelitian terdahulu maka
disusunlah suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini yang disajikan dalam
bentuk bagan alur.
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Korupsi
Menurut Transparency International11definisi korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik baik politisi maupun pegawai negeri, yang
memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau
orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang
dipercayakan kepada mereka. Korupsi secara lebih spesifik dikelompokan dalam
dua kategori, yaitu korupsi sesuai peraturan yang berlaku dan korupsi melanggar
peraturan yang berlaku.
Korupsi sesuai peraturan yang berlaku terjadi dalam situasi, apabila
seorang pejabat mendapat keuntungan pribadi secara illegal karena melakukan
sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan sesuai dengan
undang-undang. Korupsi melanggar peraturan yang berlaku terjadi dalam situasi,
suap diberikan kepada pejabat yang menurut undang-undang dilarang untuk
11
melakukan pelayanan tersebut. Keduanya dapat terjadi dalam semua tingkat
hierarki pemerintahan.
Namun, korupsi dapat juga dipandang sebagai prilaku tidak mematuhi
prinsip “mempertahankan jarak”, artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang
ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat
publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Prinsip ini
adalah landasan untuk organisasi apapun mencapai efisiensi, apabila sekali
dilanggar, maka korupsi akan timbul.
Menurut World Bank Guidelines12“Praktek Korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, langsung atau tidak
langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi tindakan pihak lain
secara tidak patut . Sedangkan “Praktek Kecurangan “ adalah suatu tindakan atau
penghapusan, termasuk misrepresentasi yang secara sadar maupun secara
sembrono menyesatkan atau berupaya menyesatkan , suatu pihak untuk
mendapatkan keuntungan financial atau keuntungan lain atau menghindari
kewajiban. “Praktek Kolusi” adalah kesepakatan dua pihak atau lebih yang
dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak sepatutnya, termasuk untuk
memengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut.
“Praktek pemaksaan (koersif)” mencakup merusak atau merugikan , atau
mengancam untuk merusak atau merugikan , secara langsung ataupun tidak
langsung, suatu pihak atau property pihak tersebut untuk memengaruhi
tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut. Dan “Praktek obstruktiif” adalah (i)
dengan sengaja merusak, memalsukan, mengubah, atau menyembunyikan bahan
bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik
untuk secara material menghalangi investigasi bank terhadap tuduhan praktek
korupsi kecurangan, pemaksaan atau kolusi, dan atau mengancam ,mengganggu,
mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkap
pengetahuannya tentang hal hal yang terkait dengan investigasi atau dalam
melakukan investigasi, (ii) perbuatan yang secara material menghalangi hak
pelaksanaan Bank dalam mengaudit atau mengakses informasi.
12
Menurut Undang Undang, definisi korupsi telah secara lengkap dijelaskan
dalam 13 buah pasal dalam Undang Undang (UU) Nomer 31 tahun 1999 jo. UU
No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana
terdapat 30 jenis korupsi yang dikelompokan menjadi Kerugian Keuangan Negara
(2 jenis), Suap Menyuap (12 Jenis), Penggelapan dalam jabatan (5 Jenis),
Pemerasan (3 jenis), Perbuatan curang (6 Jenis), Benturan kepentingan dalam
pengadaan (1 jenis), Gratifikasi (1 jenis)13.
Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
terdiri atas14: Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21), tidak
memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo.Pasal
28), bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo.
Pasal 29), dan Sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan palsu ( Pasal 22 jo.Pasal 35), orang yang memegang rahasia jabatan
tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22
jo.Pasal 36) dan saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo.Pasal 31).
Damanhuri15 membagi korupsi menjadi 7 macam, yaitu korupsi
transaktive (kolusi), extortive (memeras), investive (suap), nepotisme, autogenic (Dilakukan seorang diri), Supportive (bias kekuasaan), dan defensive (Keterpaksaan). Sedangkan Lopa16 membagi korupsi menjadi dua bentuk, yaitu
material/economic corruption dan political corruption. Bentuk pertama, adalah yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang) dengan
manipulasi di bidang ekonomi yang merugikan perekonomian negara, dan yang
kedua, berupa perbuatan manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan,
intimidasi, paksaan, dan campur tangan yang dapat memengaruhi kebebasan
memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada
keputusan yang bersifat admnistaratif, janji jabatan dan sebagainya.
13 KPK, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta:KPK, 2006,hal 15,
http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1250, 28 November 2011. 14 Ibid.
15
Damanhuri DS, Ekonomi Politik Alternatif, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1996, hal 124. 16
Menurut Klitgaard17 korupsi dapat dilakukan secara free lance yang artinya pejabat secara sendiri atau dalam sekelompok kecil menggunakan
wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap dan hypercorruption yaitu korupsi yang tidak menghiraukan aturan main sama sekali, yang sistematis
menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik,
kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan-tangan yang
tidak berhak. Namun sayangnya jenis hypercorruption adalah yang dewasa ini sering kita jumpai di pemerintahan daerah di berbagai negara di dunia, sehingga
hak milik tidak dihormati, aturan hukum diremehkan, membuat kacau insentif
investasi, dan berakibat melumpuhkan pembangunan ekonomi dan politik daerah.
Hubungan pola korupsi dalam hierarki ada dua macam18, yaitu hubungan
pola dari bawah ke atas (bottom-up) dan hubungan dengan pola dari atas ke bawah (top-down). Pola yang pertama dilakukan dengan cara para pegawai tingkat rendah mengumpulkan suap dan membaginya dengan atasan mereka,
secara langsung maupun tidak langsung. Pola yang kedua beroperasi dimana
pegawai tinggi/ pimpinan menutup mulut para bawahannya dengan membagikan
keuntungannya yang didapatkan dengan korupsi, melalui gaji yang tinggi dan
fasilitas untuk bawahan atau keuntungan dibawah meja.
Bentuk dan definisi korupsi yang luas menjadikan makna korupsi masih
rancu (ambigu) sehingga sulit dibedakan. Contohnya adalah batas perbedaan
antara korupsi ekonomi (economic corruption) dan korupsi politik (political corruption). Walaupun demikian menurut Riyanto19 usaha untuk kepentingan pribadi termasuk upaya merancang kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan
peluang atau kesempatan agar tetap bertahan di pemerintahan dapat dipandang
sebagai korupsi ekonomi politik (political economic corruption).
Dari berbagai pandangan para ahli, ada banyak faktor yang mendorong
terjadinya korupsi, menurut Nisjar20ada empat faktor penyebab terjadinya korupsi,
17
Klitgaard R, Penuntun Pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah, Jakarta:Yayasan Obor, 2005,hal 3.
18
Ackerman SR, Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, akibat dan reformasi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hal 115
19
Riyanto,Korupsidalam Pembangunan Ekonomi Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya, Disertasi, Pascasarjana IPB, 2008, hal 35.
20
yaitu: (1) Sistem administrasi yang memberi peluang terjadinya kebocoran, (2)
Tingkat kesejahteraan aparatur rendah, (3) Hukum yang ada belum cukup
menangani perkembangan tindak korupsi yang merajalela, serta sanksi hukum
atas tindak pidana korupsi belum maksimal dijalankan, (4) Kecenderungan kolusi
yang sulit dibuktikan. Sedangkan Lutfi menyatakan faktor-faktor penyebab
korupsi adalah (1) Motif, motif ekonomi maupun politik,(2) Peluang,(3) lemahnya
pengawasan21.
Singh22 menemukan bahwa sebab terjadinya korupsi di India adalah
kelemahan moral (41.3 persen), tekanan ekonomi (23.8 persen), hambatan
struktur administras (17.2 persen), hambatan struktur social (7.08 persen). Ainan
23
menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu : (1) Perumusan
undang-undang yang kurang sempurna, (2) Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak
luwes dan (3) Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat
pemerintah dengan upeti dan suap.
Selain itu, Menurut Pope faktor paling populer yang sering disebut-sebut
sebagai penyebab korupsi, yaitu kemiskinan dan mitos kebudayaan. Kemiskinan
menurut sebagian orang adalah akar korupsi, dimana ketiadaan harta dan
kemakmuran membuat orang terpaksa untuk mencari sumber dana tidak legal
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun persepsi tersebut segera
terbantahkan karena banyaknya koruptor-koruptor pada berbagai kasus korupsi
melibatkan banyak kelompok konglomerat dan pejabat-pejabat daerah yang tidak
termasuk dalam kelompok “miskin”, apabila kemiskinan menyebabkan korupsi
maka sulit menjelaskan mengapa negara-negara kaya dan makmur pun penuh
dengan skandal korupsi.
Korupsi merupakan pisau bermata dua, dimana korupsi dapat muncul dari
harta dan kemakmuran, atau juga dapat muncul dari ketiadaan harta dan
kemakmuran. Korupsi justru dapat menyebabkan kemiskinan, karena
keputusan-keputusan mengenai anggaran publik di dasarkan pada pertimbangan keuntungan
21
Lutfi dalam Sopanah, Wahyudi I, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi APBD di Malang Raya, hal 5. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/277/290, diakses 14/9/2012
22
Singh dalam Soesatyo B, Perang-perangan Melawan Korupsi : Pemberantasan Korupsi di Bawah pemerintahan Presiden SBY, Jakarta:Ufuk Press, 2010, hal 26.
23
pribadi dan ditopang oleh uang sogok luar biasa besar dari perusahaan-perusahaan
dari negara industri tanpa mempertimbangkan sedikitpun kepentingan negara
bersangkutan atau rakyatnya24.
Di Negara-negara berkembang korupsi merupakan bagian dari
kebudayaan, yang berasal dari kebiasaan memberi hadiah, bahkan di beberapa
lembaga negara korupsi menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Namun apabila kita
lihat kebelakang korupsi merupakan sebuah kebudayaan yang dibawa oleh
kekuatan asing, misalkan di negara-negara Afrika penjajahan ditandai oleh tidak
adanya transparansi. Pengadilan yang ada bukan untuk menegakan keadilan dan
hukum, justru untuk mempertahankan penjajahan. Sesungguhnya dalam konsep
Afrika mengenai hormat-menghormati dan sopan santun, hadiah biasanya kecil
saja, memberi hadiah bukanlah suatu keharusan, nilai yang dilihat adalah
semangatnya bukan dari berapa besar hadiahnya. Pemberian hadiah biasa
dilakukan secara terbuka, bukan sembunyi-sembunyi, dan nilainya apabila
berlebihan akan membuat orang merasa malu.
Klitgaard memodelkan secara sederhana faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya korupsi, yaitu Korupsi (Corruption) sama dengan kekuasaan monopoli (Monopoly power) ditambah wewenang pejabat (Discretion by officials) dikurangi akuntabilitas (Accountability) atau dapat pula dirumuskan seperti di bawah ini25: C = M + D – A………(2.0)
Korupsi adalah kejahatan kalkulasi , orang cenderung melakukan korupsi
apabila resikonya rendah, sanksi ringan dan hasilnya besar. Apabila kekuasaan
monopoli makin besar maka hasil yang diperoleh akan lebih besar. Berdasarkan
model yang disusun Klitgaard menunjukan bahwa korupsi akan muncul jika
terjadi monopoli terhadap sumber-sumber ekonomi, terjadinya penyimpangan
kebijakan publik, dan tidak adanya pertanggungjawaban terhadap publik setiap
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Maka salah satu pendekatan membasmi
korupsi adalah dengan cara mengurangi monopoli, memperjelas dan membatasi
wewenang, juga meningkatkan akuntabilitas.
24
Pope J, op.cit, hal 17. 25
Semua faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di atas tidak dapat
dipisahkan, seluruhnya adalah satu kesatuan yang pada akhirnya menciptakan
prilaku korupsi. Namun khusus bagi kasus Indonesia pada era desentralisasi
fiskal, ada faktor politik yang mendorong terjadinya korupsi di daerah, termasuk
yang bersumber dari APBD, yaitu kekeliruan dalam penyelengaraan pemilu
kepala daerah (PILKADA). Pilkada dijadikan ajang transaksional, biaya tinggi dalam pemilihan membuat calon kepala daerah mencari sumbangan dari sektor swasta. Akibatnya , setelah calon terpilih kepala daerah sibuk mengembalikan uang yang dikeluarkan dalam pemilihan, sekaligus mengembalikan investasi yang diberikan pihak swasta yang membantunya26.
Sedangkan pada praktek pilkada di daerah Sulistio27 mengungkap ada lima
hal tindakan korupsi yang biasa dilakukan kontestan, terutama incumbent dalam proses pelaksanaan pilkada, yaitu: (1)Penyelewengan jabatan, (2)Pemakaian
fasilitas publik, (3)Money politics, (4)Manipulasi dana kampanye, dan (5)Pemakaian anggaran publik.
Secara lebih jelas, Jain28 melakukan pemetaan area tempat korupsi terjadi
di negara demokrasi, yang kemudian disesuaikan untuk kondisi di Indonesia oleh Zachrie dan Wijayanto29, Gambar 5 di bawah ini membantu memberikan
gambaran untuk tempat yang berpotensi korupsi.
Interaksi 1, melibatkan rakyat dan pemimpin negara (dalam kasus daerah
adalah rakyat dan pemimpin daerah) yang dipilih berdasarkan proses demokrasi,
dalam interaksi ini menimbulkan peluang korupsi politik dalam berbagai bentuk,
termasuk salah satunya money politics, dukungan pembiayaan mereka dapatkan dari para investor politik. Interaksi 2 terdiri atas 3 bagian, yaitu (1) interaksi
antara birokrat dan pemimpin pilihan rakyat, (2) Interaksi antara birokrat dan
26
Pernyataan Arif Nur Alam (Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre) dalam Soesatyo B, Op.cit, hal 29.
27
Sulistio F, Perilaku Korupsi dalam Pemilukada, Dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi PPK FH UB.http://faizinsulistio.lecture.ub.ac.id/2011/05/perilaku-korupsi-dalam-pemilukada/, diakses 6/4/2012
28
Jain AK, Corruption: A Review, Jurnal of Economic Survey, Vol 15, No.1, Corcodia University, 2001, hal 74.
29
anggota legislatif dan (3) Interaksi antara birokrat dan rakyat. Interaksi ini
membuka peluang terjadinya korupsi birokrat. Birokrat/ pejabat publik yang
dipilih oleh pemimpin negara adalah perpanjangan tangan untuk memeras
kekayaan negara, dan menyerahkan setoran rutin kepada para elit politik untuk
melanggengkan posisi politik mereka melalui proses demokrasi yang koruptif.
Sumber : Zachrie, Wijayanto, 2010.
Gambar 5. Interaksi yang Berpotensi Menimbulkan Korupsi di Negara Demokrasi
Interaksi 3, Interaksi antara pemimpin negara dan anggota legislatif dalam
merumuskan dan menyetujui berbagai program pemerintah biasanya terjadi tarik
menarik kepentingan dan sangat rentan menimbulkan perselingkuhan, karena
konstituen tidak dapat mengawasi apakah para wakil yang mereka pilih
benar-benar mewakili kepentingan mereka, proses pembuatan program pemerintah
sangat miskin akuntabilitas. Mereka dapat merumuskan dan memutuskan Birokrat
Anggota Legislatif Pemimpin
Negara
Rakyat:
Menerima manfaat tergantung dari kemampuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan
1
2 2
2 3
4
memilih memilih
Menyetujui berbagai program
pemerintah
Kebijakan
Publik Menegakan
hukum dan perundangan memilih
kebijakan yang tidak menomorsatukan kepentingan rakyat, misalnya dalam
kebijakan alokasi anggaran, elite politik dapat mengarahkan penggunaan anggaran
pemerintah untuk sektor yang kurang bermanfaat bagi rakyat, tapi dapat
memperbesar bisnis para “investor politik” mereka (mereka adalah pemimpin
negara dan legislatif).
Interaksi 4 Korupsi Legislatif, interaksi yang melibatkan rakyat dan
anggota legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum, seringkali dalam proses
pemilihan umum legislatif, legislatif menyuap rakyat agar mereka terpilih dalam
pemilu (vote buying) sehingga mereka terpilih bukan berdasarkan kinerja tapi berdasarkan kemampuan financial mereka. Tentu saja pada akhirnya para investor
politik dimana uang tersebut bersumber mengharapkan “pengembalian investasi”
berupa kebijakan yang menguntungkan mereka.
Menurut Kwik30 korupsi kolusi nepotisme (KKN) adalah akar dari segala
permasalahan negara (the roots af all evils). KKN tidak terbatas pada mencuri uang namun juga sudah merasuk kedalam mental, moral, tata nilai, dan cara
berfikir. Sejak Jaman Yunani kuno sudah dikenal adanya pikiran yang teracuni
oleh korupsi (Corrupted mind). Daya rusaknya sangat dahsyat, karena sudah menjadikan orang tersebut menjadi tidak normal lagi dalam sikap, prilaku, dan
nalar berpikirnya. Menurutnya konsep dasar pemberantasan korupsi itu sederhana,
yaitu menerapkan Carrot and Stick.
Carrot adalah pendapatan bersih (net take home pay) untuk pegawai negeri, sipil, maupun Tentara Negara Indonesia (TNI) Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI) yang jelas mencukupi untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan
pendidikan, pengetahuan, tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat dan
martabatnya. Pendapatan tersebut dibuat tinggi, sehingga tidak hanya cukup untuk
hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan gaya “gagah” namun tidak
berlebihan, sehingga sama dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan serta
kepemimpinan yang sama di sektor swasta.
Stick atau arti harfiahnya pentung adalah hukuman yang dikenakan apabila semua telah terpenuhi tetapi masih berani korupsi. Maka siapapun yang telah
30
melakukan korupsi harus siap menerima hukuman yang seberat-beratnya. Konsep
Carrot and Stick ini harus dijalankan beriringan, dalam era pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang konsep Carrot sudah mulai ditegakan namun Stick belum.
Selain itu, penerapan Good Governance dapat menjadi solusi dalam meminimalisir korupsi pada tubuh pemerintahan, menurut United Nation Development Programme (UNDP) 1997 ada sembilan prinsip yang menandai adanya Good Governance31, yaitu :
1. Partisipasi masyarakat : Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam
pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui
lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.
Partisipasi menyeluruh di bangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara
konstruktif.
2. Tegaknya supremasi hukum : Kerangka hukum harus adil dan
diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum
yang menyangkut hak asasi manusia. Penegakan hukum yang netral
memerlukan suatu sistem peradilan yang independen dan kesatuan polisi
netral yang tidak korup.
3. Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang
bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi
perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi
yang tersedia harus memadai agar dapat dipantau dan mudah dipahami.
4. Peduli pada pemangku kepentingan stakeholder (Rensponsif) : lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua
pihak yang berkepentingan dengan jangka waktu yang wajar.
5. Berorientasi pada konsensus : tata pemerintahan yang baik menjebatani
kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu
konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi masyarakat, dan
bila mungkin, consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.
31
6. Kesetaraan : Semua masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan
mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan efisiensi : Proses pemerintahan dan lembaga-lembaga
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas : Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan
organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada
masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu sama lainnya,
tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi dan Strategis : Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif
yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan
pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa yang dibutuhkan untuk
mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus
memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial
yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
2.1.2 Korupsi di Indonesia
Menurut Damanhuri analisis korupsi di Indonesia dikemukakan oleh dua
pemikir, yaitu Myrdal dan Alatas. Myrdal menyatakan korupsi di Asia Selatan
dan Asia Tenggara berasal dari penyakit neopatrimonalisme, yakni warisan feodal
kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan patron-client. Dalam hal ini rakyat biasa atau bawahan terbiasa memberi “upeti” kepada pemegang
kekuasaan atau atasan. Sedangkan Alatas, pakar sosiologi korupsi, menyatakan
korupsi di Asia dikaitkan dengan warisan dari kondisi historis struktural yang
telah berjalan akibat lamanya masa penjajahan . Dengan demikian secara terus
menerus bangsa ini melakukan pemutarbalikan norma, dimana yang salah jadi
benar, dan yang benar jadi salah, namun yang diutamakan adalah terjaganya
loyalitas terhadap penguasa32.
Pengulangan terus menerus terjadi terhadap norma, baik dilakukan oleh
penguasa maupun masyarakat, akhirnya penyakit menahun itu, menjadi kebiasaan
32
dan mendarah daging dalam intelektual juga emosional. Maka norma lain
terbentuk, norma negatif yang bertentangan dengan norma lama. Menurut Alatas,
walaupun kebijakan anti-korupsi banyak dibentuk, akhirnya korupsi diterima
sebagai praktek yang tak terhindarkan karena dirasakan terlalu berakar, sehingga
sulit untuk diberantas. Secara tidak disadari penyakit-penyakit tersebut sudah
menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia33.
Menurut sejarah, korupsi di Indonesia yang terjadi pada masa kini, tidak
terlepas dari watak para elite-nya. Sejarahwan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Lohanda34 memaparkan pada masa Majapahit sebelum Portugis
datang ke Malaka. Suku Jawa adalah pedagang dan pelaut yang memasarkan
berbagai rempah di Malaka, Mereka bermitra dengan China, India, dan Arab.
Kapiten Jawa sebagai ketua komunitas pedagang jawa merupakan bandar dunia
saat itu. Proses kolonialisasi di Indonesia terjadi pada masa kesultanan, dimana
ketika para elite penguasa saat itu sangat suka menerima upeti-upeti tanpa
melakukan kerja keras, dan menerima berbagai bentuk hutang. Pada saat mereka
tidak mampu membayar hutang, pembayaran dilakukan dengan melepas satu
persatu pelabuhan dan berbagai wilayah strategis di Indonesia kepada pihak asing.
Rickleffs adalah sejarahwan Australia yang menegaskan bahwa raja
Mataram pernah mengeluarkan ketentuan bahwa orang Jawa tidak boleh berlayar
kemanapun diluar Jawa, Madura dan Bali. Ketentuan tersebut lahir karena
banyaknya pelabuhan yang sudah dilepaskan ke tangan pihak asing. Suku bangsa
Jawa pada akhirnya berorientasi kedaratan, namun ketika terjadi perang suksesi
dan sang raja terdesak lengser dari tahta, dia menjanjikan daerah-daerah strategis
kepada VOC. Selain itu, Windu alumnus jurusan arkeologi Universitas Udayana
Bali, mengisahkan besarnya angka pajak dalam prasasti-prasasti kerajaan sudah
dilakukan pemahalan (mark up) terlebih dahulu oleh para pemungut cukai kerajaan pada saat itu35. Berbagai hal tersebut menunjukan korupsi sudah terjadi
sejak masa kerajaan di Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, VOC
bangkrut pada awal abad ke-20 karena korupsi yang merajalela ditubuhnya.
33
Ibid.
34
Santosa I (Maria Hartiningsih), opcit, hal 108-109. 35
Menurut Damanhuri36 pemerintahan Orde Lama juga tidak luput dari
praktek korupsi, sejarah pernah mencatat bahwa Iskak Tjokroadisuryo, mentri
ekonomi pada kabinet Alisostroamidjojo I, telah melakukan penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power). Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan pada lisensi impor dari kebijakan politik Benteng yang bertujuan untuk memberdayakan para
pengusaha pribumi yang kompeten, namun ternyata dijual kepada para pengusaha
Cina dan konco-konconya.
Sejak itu KKN skala mega mulai berkembang, namun karena masih
diwarnai semangat kemerdekaan, berhasil dilakukan kebijakan tindakan
pemberantasan korupsi yang efektif, yang dilakukan oleh Perdana Mentri
Burhanudin Harahap yang bekerjasama dengan TNI angkatan Darat. Namun
kabinet ini berumur pendek karena terdapat konflik antarpartai sehingga
konstituate dibubarkan pada 5 Juli 1965, seiring dengan nasionalisasi perusahaan
asing. Sejak itu BUMN banyak diwarnai oleh KKN karena di lakukan pihak
partai, dan akhirnya menjadi ciri khasnya hingga masa kini.
Masa Orde Baru (OrBa) adalah masa yang penuh dengan praktek kolusi
yang terus menerus dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 30 tahun.
Praktek kolusi begitu melembaga dan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang
memiliki kekuasaan (pemerintah) dengan kalangan pengusaha swasta. Kolusi
yang terjadi adalah untuk memperebutkan lisensi, perizinan dan bentuk
pemburuan rente lainnya. Sumber daya pemerintah yang ada kemudian hanya
akan dinikmati oleh segelintir kelompok kepentingan yang bertujuan
memperkaya diri sendiri.
Hal ini terjadi, karena di satu sisi pemerintah (penguasa dan birokrat)
membutuhkan pengusaha untuk pembangunan ekonomi, sedangkam kalangan
pengusaha swasta membutuhkan penyediaan sumber-sumber ekonomi dan
perlindungan. Pada saat itu, pengusaha swasta tidak meningkatkan kemampuan
kompetitifnya dan pemerintah tidak mau menciptakan kondisi persaingan yang
sehat. Karena, pemerintah tidak menginginkan menguatnya kalangan pengusaha
swasta yang mengancam kedudukan mereka, melainkan lebih ingin menjadi
36
penyedia sumber daya ekonomi , proteksi dan monopoli, sehingga dapat menarik
“upeti” yang lebih besar lagi dari para kalangan pengusaha swasta37. Semua hal
itu pada akhirnya menciptakan kesenjangan yang lebar antara pusat dan daerah,
yang akhirnya menciptakan ketidakstabilan kekuasaan Orde Baru.
Damanhuri38 mencatat potret korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru,
yaitu dimulai oleh korupsi pertamina yang berskala mega pada tahun 1975,
dengan kerugian negara sebesar 12,5 miliar dollar AS. Namun tidak adanya
tindakan hukum kepada pelaku-pelaku yang terlibat, menunjukan kelumpuhan
penegakan hukum untuk kasus korupsi pada saat itu. Kemudian terdapat aliran
utang luar negeri rata-rata sebesar 5 miliar dollar AS per tahun, sehingga pada saat
Pak Soeharto lengser, stok utang pemerintah sudah mencapai 70 miliar dollar AS.
Pada masa itu terdapat banyak investasi langsung perusahaan asing, dan
eksploitasi terhadap sumber daya alam (terutama migas dan hutan). Masa OrBa
adalah masa pertumbuhan dan perkembangbiakan segala jenis dan bentuk korupsi,
sehingga adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang harusnya dapat tumbuh 12
persen per tahun hanya tumbuh di sekitar 7 persen per tahun.
Keruntuhan Orde Baru ditandai dengan reformasi yang dilakukan sejak
1998, Namun ternyata adanya era baru yang memiliki tujuan positif untuk
kemajuan ekonomi maupun politik, justru membuka celah korupsi yang semakin
menyebar ke daerah dan berbagai lembaga pemerintah, yudikatif maupun
legislatif (pusat dan daerah). Rachbini39 memaparkan demokrasi pada masa
desentralisasi berada masa transisi yang belum matang. Wujud kelahirannya yang
tiba-tiba tidak memberikan kesempatan belajar yang cukup. Akhirnya , pelaku
demokrasi kaget dan tidak memiliki keseimbangan untuk mendorong demokrasi
yang adil, transparan dan tertuju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bentuk demokrasi yang tidak sempurna muncul kembali, seperti bentuk
kolusi pada masa Orde Baru, bahkan lebih parah yaitu kolusi yang melibatkan
tidak hanya pemerintah dan pengusaha swasta, tetapi antar parlemen
(DPR/DPRD) dengan pemerintah maupun pemerintah daerah, dengan
37
Harman BK, Negeri Mafia Republik Koruptor:Menggugat Peran DPR Reformasi, Yogyakarta:Lamalera,2012, hal 102.
38
Damanhuri DS, op.cit, hal 128. 39
memperebutkan kekuasaan maupun anggaran yang ada yaitu pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Pada masa pascareformasi parlemen semakin kuat, Parlemen memiliki
fungsi legislasi dalam membentuk undang-undang, fungsi budget dalam membahas dan menyetujui anggaran, dan fungsi controlling untuk melakukan pengawasan melalui berbagai instrumen yang dapat dioptimalkan bagi
pemberantasan dan pengurangan secara efektif terhadap praktek korupsi40.
Namun alih-alih melakukan check and balance, parlemen justru banyak melakukan penyelewengan, melakukan praktek-praktek kolusif yang bertujuan
hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan lingkaran kecil disekitarnya. Di
sisi lain tidak ada kekuatan yang mengontrol parlemen, sehingga DPR/DPRD
menjadi tempat berkembangnya praktek politik uang dan korupsi.
Kondisi daerah-daerah di Indonesia setelah lebih dari satu dasawarsa
otonomi daerah, ternyata kurang memperlihatkan perbaikan pertumbuhan
ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Otonomi daerah
dimaksudkan untuk membentuk keseimbangan antara pusat dan daerah, namun
sejauh ini hasil yang dapat dirasakan dalam hanyalah ditebarkannya anggaran
besar ke berbagai daerah dalam rangka otonomi anggaran. Pemerintah daerah dan
DPRD dapat menentukan pembiayaannya sendiri sesuai kewenangannya,
sehingga kekuasaan yang ada di tangan DPR/DPRD dapat disalah gunakan,
misalnya untuk jual beli pengalokasian anggaran ,dan proses pengambilan
keputusan diambil tidak transparan. Ternyata desentralisasi menghasilkan bukan
hanya praktek kolusi yang vertikal (model patron-client) tapi juga horizontal (eksekutif-legislatif).
Harman41 menggambarkan secara singkat bagaimana dampak korupsi
terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah kerugian negara,
yang secara tidak langsung berdampak pada kemajuan pembangunan ekonomi.
Kekuatan negara disokong oleh APBN/APBD, namun kebocoran anggaran
maupun pendapatan itu tentu saja akan menghambat tercapainya tujuan, hambatan
40
Harman BK, op.cit, hal 20-21. 41