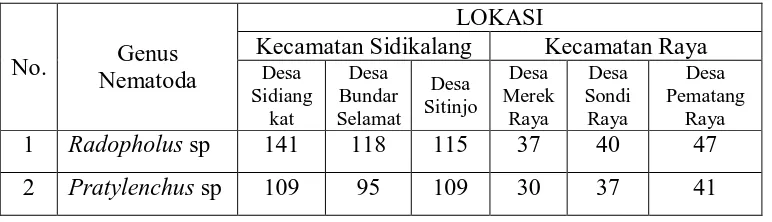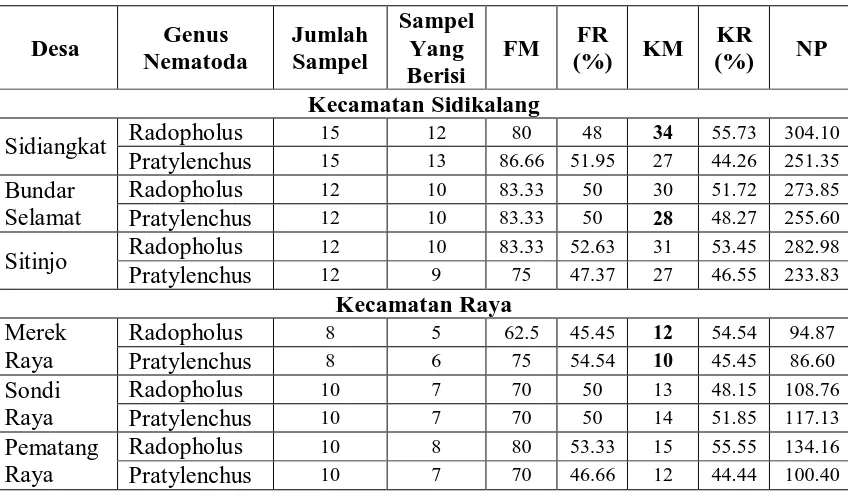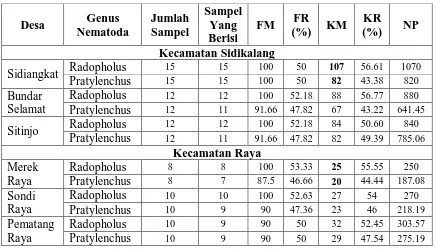KEANEKARAGAMAN HAYATI NEMATODA PARASITIK PADA
TANAMAN KOPI (Coffea sp.) DI SUMATERA UTARA
SKRIPSI
OLEH:
FRANSIUS SIMANJUNTAK
060302012
HPT
DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI NEMATODA PARASITIK PADA
TANAMAN KOPI (Coffea sp.) DI SUMATERA UTARA
Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara, Medan.
DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
ABSTRACT
Fransius Simanjuntak, The Biodiversity Of Plant Parasitic Nematodes
On Coffea Crop (Coffea sp) At North Sumatera. Supervised by
Lisnawita and Lahmuddin Lubis. The research was conducted to determine
biodiversity of plant parasitic nematodes associated with the soil and root of
coffea in Dairi and Simalungun, three locations in Dairi and three locations in
Simalungun. Survey was using random sampling for soil and root and using
corong Baerman modification for plant parasitic extraction at Plant Disease
Laboratory, Plant Pest and Disease Department, Agriculture Faculty, USU from
May to September 2010. Based on this survey two genera of plant parasitic
nematodes where encountered in Dairi and Simalungun.
Plant parasitic nematodes included Radopholus spp and Pratylenchus spp
were most distributed with population densities varying from low to high. The
hightes population densities of Radopholus spp and Pratylenchus spp were found
in Sidiangkat and Bundar Selamat (Dairi) with 34 and 28 juvenile respectively in
soil samples and in the root samples were found in Sidiangkat (Dairi) with 107
and 82 juveniles respectively while the lowest population densities of
Radopholus spp and Pratylenchus spp were found in Merek Raya (Simalungun)
with 12 and 10 juveniles respectively in soil samples and in the root samples were
found in Merek Raya with 25 and 20 juvenile respectively.
ABSTRAK
Fransius Simanjuntak, Keanekaragaman Hayati Nematoda Parasitik
Pada Tanaman Kopi (Coffea sp.) Di Sumatera Utara. Dibawah bimbingan
Lisnawita dan Lahmuddin Lubis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
keanekaragaman hayati nematoda parasit tanaman kopi yang terdapat di tanah dan
akar kopi di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun, dimana dipilih tiga
lokasi di Dairi dan tiga lokasi di Simalungun. Penelitian ini menggunakan sistem
acak dalam pengambilan sampel, dimana sampel akar dan tanah diekstraksi
dengan menggunakan metode modifikasi Corong Baerman di Laboratorium
Penyakit Tumbuhan, Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas
Pertanian, Universitas Sumatera Utara yang dimulai dari bulan Mei dan selesai
bulan September 2010. Hasil penelitian ini ditemukan dua genus nematoda
parasitik tanaman kopi di Dairi dan Simalungun.
Nematoda parasitik yang ditemukan yaitu Radopholus spp dan
Pratylenchus spp yang penyebaran dan kerapatan populasinya bervariasi mulai
dari rendah hingga tinggi. Kerapatan populasi tertinggi Radopholus spp dan
Pratylenchus spp ditemukan di desa Sidiangkat dan Bundar Selamat (Dairi) yaitu
sebesar 34 dan 28 juvenil pada sampel tanah dan sampel akar tertinggi secara
berurutan terdapat di Sidiangkat sebesar 107 dan 82 juvenil sementara populasi
terendah Radopholus spp dan Pratylenchus spp terdapat di Merek Raya
(Simalungun) secara berurutan pada sampel tanah 12 dan 10 juvenil dan pada
sampel akar di Merek Raya sebesar 25 dan 20 juvenil.
RIWAYAT HIDUP
Fransius Simanjuntak, dilahirkan pada tanggal 10 Mei 1988 di Medan,
merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari Ayahanda Drs. J. Simanjuntak
dan Ibunda R. br Ginting.
Pendidikan yang ditempuh :
Tahun 2000 lulus dari Sekolah Dasar Free Methodist II Medan.
Tahun 2003 lulus dari Sekolah Menengah Pertama Methodist VI Medan. Tahun 2006 lulus dari Sekolah Menangah Atas Negeri (SMAN) XV
Medan.
Tahun 2006 diterima di Universitas Sumatera Utara Fakultas Pertanian
Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan melalui jalur SPMB.
Aktifitas dari kegiatan selama perkuliahan yang diikuti penulis :
Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PTPN III Kebun
Rambutan, Tebing Tinggi periode Juni – Juli 2010.
Melaksanakan penelitian di Laboratorium Penyakit Departemen Hama dan
Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara,
Medan pada bulan April – Agustus 2010.
Sebagai peserta pada Seminar Nasional “Tindak Lanjut Pembangunan
Pertanian Pasca Swasembada Beras 2008” di Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara, Medan.
Mengikuti Dialog Pemuda Tingkat Regional 2009 yang diselenggarakan
KEMENPORA RI di Hotel Tiara, Medan.
Sebagai Asisten di Laboratorium Pestisida dan Teknik Aplikasi pada tahun
ajaran 2009/2010.
Sebagai Asisten di Laboratorium Hama dan Penyakit Pasca Panen pada
DAFTAR ISI
ABSTRAK ... i
KATA PENGANTAR ... iii
RIWAYAT HIDUP ... iv
DAFTAR ISI ... .. v
DAFTAR GAMBAR ... vii
PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1
Tujuan Penulisan ... 4
Hipotesa Penelitian ... 4
KegunaanPenulisan ... 5
Nematoda Parasitik Tanaman Kopi Biologi Nematoda ... 8
Gejala Serangan ... 9
Pengendalian ... 11
BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian ... 15
Bahan dan Alat ... 15
Metode Penelitian ... 15
Pelaksanaan Penelitian ... 16
Survei Pendahuluan ... 16
Pengambilan Sampel ... 16
Peubah yang Diamati Genus Nematoda ... 17
Populasi Nematoda Dari Setiap Genus ... 18
HASIL DAN PEMBAHASAN
KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Hal.
1 Tanaman kopi di lapangan 8
2 Radopholus similis 12
3 Pratylenchus coffeae 15
4 Akar kopi yang diserang nematoda (kanan) dan yang masih sehat (kiri)
15
5 Metode Modifikasi Corong Baerman 20
6 Gejala serangan nematoda luka akar di atas permukaan tanah 22
7 Gejala nekrotik pada tepi jaringan korteks akar 23
8 Gejala serangan yang mengakibatkan permukaan akar terkelupas dan rambut akar habis
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat dan kasih-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan
penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
Adapun judul dari skripsi ini adalah ” Keanekaragaman Hayati
Nematoda Parasitik Pada Tanaman Kopi (Coffea sp.) Di Sumatera Utara “
yang disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat melaksanakan penelitian di
Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara, Medan.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Dr. Lisnawita, SP, MSi selaku ketua komisi pembimbing dan
Bapak Ir. Lahmuddin, MP selaku anggota, yang telah memberikan saran dan
arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki
kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun
demi kesempurnaan tulisan ini.
Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.
Medan, September 2010
ABSTRACT
Fransius Simanjuntak, The Biodiversity Of Plant Parasitic Nematodes
On Coffea Crop (Coffea sp) At North Sumatera. Supervised by
Lisnawita and Lahmuddin Lubis. The research was conducted to determine
biodiversity of plant parasitic nematodes associated with the soil and root of
coffea in Dairi and Simalungun, three locations in Dairi and three locations in
Simalungun. Survey was using random sampling for soil and root and using
corong Baerman modification for plant parasitic extraction at Plant Disease
Laboratory, Plant Pest and Disease Department, Agriculture Faculty, USU from
May to September 2010. Based on this survey two genera of plant parasitic
nematodes where encountered in Dairi and Simalungun.
Plant parasitic nematodes included Radopholus spp and Pratylenchus spp
were most distributed with population densities varying from low to high. The
hightes population densities of Radopholus spp and Pratylenchus spp were found
in Sidiangkat and Bundar Selamat (Dairi) with 34 and 28 juvenile respectively in
soil samples and in the root samples were found in Sidiangkat (Dairi) with 107
and 82 juveniles respectively while the lowest population densities of
Radopholus spp and Pratylenchus spp were found in Merek Raya (Simalungun)
with 12 and 10 juveniles respectively in soil samples and in the root samples were
found in Merek Raya with 25 and 20 juvenile respectively.
ABSTRAK
Fransius Simanjuntak, Keanekaragaman Hayati Nematoda Parasitik
Pada Tanaman Kopi (Coffea sp.) Di Sumatera Utara. Dibawah bimbingan
Lisnawita dan Lahmuddin Lubis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
keanekaragaman hayati nematoda parasit tanaman kopi yang terdapat di tanah dan
akar kopi di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun, dimana dipilih tiga
lokasi di Dairi dan tiga lokasi di Simalungun. Penelitian ini menggunakan sistem
acak dalam pengambilan sampel, dimana sampel akar dan tanah diekstraksi
dengan menggunakan metode modifikasi Corong Baerman di Laboratorium
Penyakit Tumbuhan, Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas
Pertanian, Universitas Sumatera Utara yang dimulai dari bulan Mei dan selesai
bulan September 2010. Hasil penelitian ini ditemukan dua genus nematoda
parasitik tanaman kopi di Dairi dan Simalungun.
Nematoda parasitik yang ditemukan yaitu Radopholus spp dan
Pratylenchus spp yang penyebaran dan kerapatan populasinya bervariasi mulai
dari rendah hingga tinggi. Kerapatan populasi tertinggi Radopholus spp dan
Pratylenchus spp ditemukan di desa Sidiangkat dan Bundar Selamat (Dairi) yaitu
sebesar 34 dan 28 juvenil pada sampel tanah dan sampel akar tertinggi secara
berurutan terdapat di Sidiangkat sebesar 107 dan 82 juvenil sementara populasi
terendah Radopholus spp dan Pratylenchus spp terdapat di Merek Raya
(Simalungun) secara berurutan pada sampel tanah 12 dan 10 juvenil dan pada
sampel akar di Merek Raya sebesar 25 dan 20 juvenil.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kopi (Coffea sp.) sebagai salah satu komoditi non migas. Kopi memiliki
pasaran yang cukup di pasar dunia. Hal ini disebabkan dari berbagai penjuru dunia
banyak orang yang suka minum kopi, karena kopi dapat diolah menjadi minuman
yang lezat rasanya. Pada mulanya orang minum kopi bukan kopi bubuk yang
berasal dari biji, melainkan dari cairan daun kopi yang masih segar atau kulit buah
yang diseduh dengan air panas. Setelah ditemukan cara memasak kopi bubuk
yang lebih sempurna, yaitu menggunakan biji kopi yang masak kemudian
dikeringkan dan dijadikan bubuk sebagai bahan minuman. Akhirnya penggemar
kopi cepat meluas. Kopi yang pertama adalah Arabia yang dikenal pada
pertengahan abad XV. Selanjutnya menyebar luas di negara Timur Tengah,
seperti Kairo pada tahun 1510 dan Konstantinopel (Turki) sekitar tahun 1550.
Pada tahun 1616 kopi Arabia mulai masuk ke Eropa, yakni di Venesia
(Anonimusc, 2010).
Di Indonesia, tanaman kopi diperkenalkan pertama kali oleh VOC antara
tahun 1696 – 1699. Sejarah perkembangan kopi di Indonesia pernah mengalami
goncangan yaitu pada tahun 1878 terjadi ledakan penyakit Hemelia vastatrix (HV)
yang menyerang daun dan sangat membahayakan. Berbagai tindakan
pengendalian dilakukan tetapi kurang memuaskan (Najiyati dan Danarti, 1997).
Dewasa ini produksi kopi nasional 94% dihasilkan dari kebun rakyat.
Selain itu kopi merupakan salah satu komoditi andalan Sub Sektor Perkebunan
kesempatan kerja dan perolehan devisa (Ka. BIP Propinsi Irian Jaya, 1991).
Kopi di Sumatera Utara terdiri dari 2 jenis kopi yakni arabika (A) dan
robusta (R) dengan masing – masing luas areal ± 19.649,16 Ha untuk Arabika
dan ± 57.433,17 Ha untuk Robusta. Kopi arabika baru dikelola oleh rakyat dan
belum ada perusahaan negara, swasta maupun asing yang mengusahakan komoditi
kopi jenis arabika. Sedangkan untuk kopi robusta terdiri perkebunan rakyat :
56.782,17 Ha dan perkebunan besar swasta negara : 651 HA dengan total
produksi sebesar + 19.137,31 ton (A) yang dikelola oleh rakyat. Total produksi
kopi robusta adalah sebesar: ± 30.219,28 ton. Dari luas ini yang dikelola oleh PR
adalah 29.638,78 ton dan yang dikelola PBSN adalah 580,50 ton (Girsang, 2010).
Dari total produksi kopi Indonesia, 550.000 ton (81,2%) berupa kopi
robusta dan 125.000 ton (18,8%) berupa kopi arabika. Lampung, Sumatera
Selatan dan Bengkulu merupakan daerah utama penghasil kopi robusta Indonesia
yang dalam pasar dunia lebih dikenal sebagai Kopi Robusta Sumatera.
Sedangkan daerah penghasil kopi arabika adalah Nanggro Aceh Darussalam
(NAD), Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Beberapa daerah
seperti Jawa Timur, Bali dan Flores menghasilkan kopi arabika dan robusta
(Purnomo, 2008).
Sebagai salah satu sentra kopi di Indonesia, Sumatera Utara ada 14
kabupaten / kota yang membudidayakan tanaman kopi dengan total luas lahan
23 079,74 Ha yang mencakup tanaman belum menghasilkan, tanaman
menghasilkan, dan tanaman tidak produktif. Dengan total produksi 8 580,25 ton.
Dari daerah – daerah ini ada 5 kabupaten yang menjadi daerah budidaya kopi
dan Tapanuli Utara. Kabupaten Dairi memiliki luas areal budidaya kopi terluas
dengan 9 429,00 Ha dengan produksi 2 652,40 ton (BPS, 2008).
Sama seperti budidaya komoditi lainnya. Dalam budidaya kopi juga
menghadapi kendala dalam peningkatan produksi kopi secara kualitas dan
kuantitas. Salah satunya adalah gangguan hama dan penyakit. Salah satu penyakit
yang saat ini banyak menginfeksi tanaman kopi adalah nematoda parasit
tumbuhan.
Nematoda adalah binatang yang bergerak aktif, lentur dan berbentuk
seperti pipa, hidup pada permukaan yang lembab atau lingkungan yang berair.
Nematoda memiliki sistem organ yang lengkap sebagaimana binatang yang
mempunyai organ kompleks, tetapi mereka tidak memiliki sistem peredaran
darah. Nematoda terbagi dua jenis yaitu memiliki stilet dan tidak. Nematoda yang
memiliki stilet menjadi perhatian lebih dikarenakan merupakan nematoda parasit.
Nematoda parasit tumbuhan adalah nematoda yang mengakibatkan kerusakan
pada tumbuhan karena mengurangi kemampuan tanaman mencegah infeksi jamur
dan menularkan penyakit antar tanaman inang (Dropkin, 1992).
Beberapa nematoda parasit yang diinformasikan banyak menginfeksi
tanaman kopi adalah Radopholus sp dan Pratylenchus sp. Kedua nematoda ini
memiliki gejala serangan yang sama yaitu melubangi akar sehingga pada akar
kopi terdapat luka nekrotik dan rambut akar habis dimakan. Kerugian yang
diakibatkan oleh nematoda ini dapat mematikan tanaman kopi.
Selama enam tahun (1981-1986) serangan nematoda Pratylenchus coffeae,
menyebabkan kehilangan hasil rata-rata sebesar 56,84%, atau sekitar 150 ton kopi
mengurangi kualitas produk. Penurunan produksi oleh P. coffeae pada kopi
Robusta berkisar antara 28,7% sampai 78,4%. Serangan P. coffeae terhadap kopi
Arabika, biasanya tanaman hanya bisa bertahan selama 2 tahun (Mustika, 2005).
Di Sumatera Utara, informasi tentang kerusakan tanaman kopi yang
disebabkan oleh nematoda masih sangat kurang. Padahal informasi ini penting
mengingat budidaya kopi di Sumatera Utara telah dilakukan secara intensif dalam
waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan peluang gangguan nematoda sangat
besar.
Berdasarkan informasi di atas, penulis melakukan penelitian ini untuk
mengetahui keanekaragaman hayati nematoda parasitik pada tanaman kopi di
Sumatera Utara.
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui genus nematoda parasitik yang menginfeksi tanaman
kopi di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
Hipotesa Penelitian
Terdapat beberapa genus nematoda parasitik pada tanaman kopi dengan
di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan informasi dan acuan dalam usaha mengantisipasi terjadinya
epidemi penyakit yang disebabkan nematoda parasit tumbuhan baik
yang membutuhkan terutama yang membudidayakan tanaman kopi di
Sumatera Utara.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen
Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera
TINJAUAN PUSTAKA
Botani Tanaman Kopi (Coffea sp.)
Adapun klasifikasi tanaman kopi (Coffea sp.) dari literatur Hasbi (2009)
adalah sebagai berikut :
Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisio : Angiospermae
Kelas : Dycotiledoneae
Ordo : Rubiales
Famili : Rubiaceae
Genus : Coffea
Spesies : Coffea sp.
Kopi (Coffea sp.) adalah spesies tanaman berbentuk pohon. Tanaman ini
tumbuh tegak, bercabang dan bila dibiarkan akan mencapai tinggi 12 m. Tanaman
ini memiliki beberapa jenis cabang : cabang reproduksi, cabang primer, cabang
sekunder, cabang kipas, cabang pecut, cabang balik, dan cabang air
(Najiyati dan Danarti, 1997) (Gambar 1).
Meskipun kopi adalah tanaman tahunan, tetapi memiliki perakaran yang
dangkal. Secara alami tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak
mudah rebah. Oleh sebab itu tanaman ini mudah mengalami kekeringan pada
kemarau yang panjang bila di daerah perakarannya tidak diberi mulsa
Daun tanaman kopi berbentuk bulat telur dengan ujung tegak meruncing.
Daun tumbuh berhadapan pada batang, cabang dan ranting – rantingnya
(Najiyati dan Danarti, 1997).
Tanaman kopi mulai berbunga setelah berumur ±2 tahun. Mula – mula
bunga keluar dari ketiak daun yang terletak pada batang reproduksi. Jumlah
kuncup pada setiap ketiak daun terbatas. Pada setiap ketiak daun menghasilkan
8 – 18 kuntum, setiap buku menghasilkan 16 – 36 kuntum bunga. Waktu yang
dibutuhkan untuk bunga hingga jadi buah matang 6 – 11 bulan. Penyerbukan kopi
ada 2 jenis yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan menyilang
(Najiyati dan Danarti, 1997).
Syarat Tumbuh
Iklim
Iklim yang optimal untuk pertumbuhan tanaman kopi adalah tinggi
tempat : 800 – 2000 m dpl, suhu : 15º C – 25 ºC, curah hujan : 1.750 –
3000 mm/thn, lamanya bulan kering 3 bulan (Asmacs, 2008).
Tanah
Syarat tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman kopi
adalah : letaknyas terisolir dari pertanaman kopi varietas lain ± 100 meter,
lahan bebas hama dan penyakit, mudah melakukan pengawasan, pH
tanah : 5,5 – 6,5, top soil : minimal 2 %, strukrur tanah : subur, gembur ke
Gambar 1.Tanaman kopi di lapangan di Pematang Raya, Simalungun
Nematoda parasitik pada tanaman kopi
Ada beberapa jenis nematoda parasit yang menyerang tanaman kopi,
antara lain :
1. Radopholus sp
Biologi nematoda Radopholus sp
Adapun klasifikasi nematoda Radopholus sp menurut literatur
Anonimusa (2010) adalah sebagai berikut :
Kingdom : Animalia
Phylum : Nematoda
Class : Secernentea
Subclass : Diplogasteria
Ordorer : Tylenchida
Family
Genus : Radopholus
Radopholus atau nematoda pelubang akar (burrowing nematode)
(Gambar 2) diketahui sebagai endoparasit migratori pada berbagai jenis
tanaman. Nematoda merusak atau makan bagian korteks akar, sehingga
terjadi lubang – lubang pada akar tersebut. Semua stadia dapat dijumpai di
dalam akar dan tanah. Jantan bersifat non parasit, sedangkan stadia lainnya
bersifat parasit terhadap tanaman. Ada beberapa tanaman yang terserang
nematoda ini yaitu : pisang, nilam, kopi, teh, jagung, sayuran, tebu, dan
lain - lain (Mustika, 2003).
Radopholus sp merupakan parasit migratori, endoparasit polifag
yang berada di dalam akar dan umbi pada umumnya di jaringan korteks.
Nematoda ini berbentuk benang di seluruh hidupnya. Nematoda ini
merupakan patogen yang agresif. Seperti nematoda peluka akar lainnya,
nematoda pelubang akar ini aktivitas makannya mengakibatkan luka
nekrotik pada jaringan akar inangnya. Seluruh stadia hidupnya merupakan
parasit dan bereproduksi secara seksual. Telur diletakkan di dalam
jaringan akar dan perkembangan embrionik berlangsung beberapa hari.
Seluruh siklus hidup diselesaikan dalam 3 minggu pada kondisi optimal
dengan suhu 240 – 270C (Bridge dan James, 2007).
Nematoda ini mengakibatkan luka nekrotik berwarna coklat
kemerahan sampai hitam di sepanjang jaringan korteks. Lubang
terowongan meluas tetapi tidak melewati jaringan endodermis. Reproduksi
dan serangan terhadap akar terjadi pada suhu 120 – 320C. Perluasan
serangan nematoda rata – rata 5 m per tahun pada tanah berpasir
Nematoda banyak menimbulkan kerugian pada pertanaman kopi,
lada, manila henep, pisang, teh, tebu, bambu, dan tanaman lainnya. Ukuran
nematoda betina yang dewasa lebih panjang dari 0,7 mm, sedangkan yang
jantan berukuran lebih kecil. Sifat – sifatnya mirip dengan
Pratylenchus coffeae (Soetedjo, 1989).
R. similis sangat peka terhadap suhu dingin dan tingkat
kemampuan hidupnya rendah pada tanaman teh di daerah elevasinya di
atas 1000 m dpl. Umumnya terdapat di daerah perakaran bersama – sama
dengan P. loosi. Pada pertanaman teh, nematoda menyukai daerah yang
lahannya mendapat curah hujan tinggi dan merata (Luc et al, 1995).
R. similis adalah spesies amphimictic ditandai dengan aksen
dimorfisme seksual. Nematoda jantan dari spesies ini memiliki stilet yang
kurang berkembang, bibir tinggi yang berbeda wilayah berangkat oleh
penyempitan yang berbeda dan bursa crenate kasar menyelubungi 2 / 3
dari ekor. R. similis betina memiliki esofagus dan stilet dengan ukuran
[18 (16-21) µm] (Gambar 2). Spermatheca bulat seperti batang berisi
sperma dan memanjangkan-konoideum ekor sempit dengan ujung
membulat atau melekuk (Anonimusa, 2010).
Pengendalian nematoda selama ini banyak digunakan adalah
melalui pemanfaatan bahan organik, penggunaan varietas tahan,
nematisida, dan solarisasi. Dalam pelaksanaannya metode pengendalian
yang digunakan hanya cara dan target utamanya hanya terhadap nematoda
yang dikendalikan dan kurang memperhatikan akibatnya terhadap
Gambar 2. Radopholus similis
2. Pratylenchus coffeae
Biologi nematoda Pratylenchus coffeae
Adapun klasifikasi nematoda Pratylenchus sp menurut literatur
Anonimusa (2010) adalah sebagai berikut :
Kingdom : Animalia
Phylum : Nematoda
Class
Subclass : Diplogasteria
Ordorer : Tylenchida
Superfamily : Tylenchoidea
Family
Genus : Pratylenchus
Spesies : Pratylenchus coffeae
Pratylenchus sp berukuran kecil, yang jantan sekitar 0,42 mm
telur tiap induk antara 50 – 60 butir dalam waktu sekitar 5 minggu.
Perioda telur berlangsung antara 15 – 17 hari, sedang perioda larvanya
untuk menjadi dewasa sekitar 15 – 16 hari (Soetedjo, 1989).
Pratylenchus sp (Gambar 3) merupakan endoparasit berpindah
yang memakan korteks akar. Beberapa efek tanaman yang terserang
mengakibatkan daun klorotik dan tanaman kerdil. Nematoda ini ditemukan
di akar dan tanah. Kematian sel selalu diikuti perluasan makanan yang
diakibatkan Pratylenchus sp. Ketika kelembaban tanah rendah, beberapa
spesies dari Pratylenchus dapat bertahan hidup lebih dari setahun pada
tanaman inang. Pewarnaan jaringan akar dapat menampakkan nematoda
yang tersembunyi dalam jaringan akar (Shurtleff dan Charles, 2000).
Pratylenchus sp menyukai tanah yang berstruktur kasar atau tanah
berpasir. Populasi nematoda mencapai tingkat tertinggi pada tanaman
alfalfa yang dipangkas daripada yang tidak dipangkas. Nematoda ini
mengadakan invasi ke dalam korteks akar dan mematikan sel – sel pada
waktu mereka makan. Luka yang berbentuk memanjang dan berwarna
coklat hitam merupakan akibat serangannya pada permukaan akar. Gejala
serangan pada permukaan tanah adalah layu, daun menguning, cabang
mati muda dan kerdil. Serangan parah dapat mematikan tanaman
(Dropkin, 1992).
Pratylenchus atau nematoda luka akar (NLA), hidup sebagai
endoparasit berpindah dalam akar tanaman, makan dan merusak pada
dapat ditemukan dalam tanah dan akar. P. coffeae bertelur di dalam
jaringan akar. Daur hidupnya berkisar antara 45 – 48 hari (Mustika, 2003).
Nematoda luka akar yang terdapat pada pertanaman kopi antara
lain: Pratylenchus coffeae, P. goodeyi, P. pratensis, P. brachyurus. Untuk
jangka waktu yang lama P. brachyurus merupakan satu – satunya spesies
Pratylenchus yang menyerang tanaman kopi di Amerika Selatan.
P. coffeae terdapat di pertanaman kopi di India dan Pulau Jawa
(Luc et al, 1995).
Akar tanaman kopi yang terserang oleh P. coffeae warnanya
berubah menjadi kuning, selanjutnya berwarna coklat dan kebanyakan
akar lateralnya busuk (Gambar 4). Tanaman yang terserang tampak kerdil
dan terdapat sedikit klorosis pada daunnya. Tanaman berangsur – angsur
layu yang diikuti oleh kematian. Tanaman yang terserang berat akan mati
sebelum dewasa. Di lahan, gejala kerusakan tersebut terjadi secara
setempat – setempat yang dapat mengurangi hasil berdasarkan berat
ringannya serangan. Luka yang terjadi pada akar berakibat merusak
seluruh sistem perakaran tanaman kopi (Luc et al, 1995).
Pengendalian P. coffeae dapat diperoleh dengan baik dengan
menggunakan Nemacur. Nematisida tersebut tetap efektif pada kondisi
lapangan selama 90 hari setelah aplikasi. Di India, kopi robusta lebih
toleran dibanding arabika. Penggunaan metil bromida pada dosis
150 cm3/m3 tanah merupakan cara yang paling efektif untuk sterilisasi
Gambar 3. Pratylenchus coffeae
Gambar 4. Akar tanaman kopi (a) Akar kopi yang masih sehat
(b) Akar kopi yang terinfeksi nematoda Sumber. Simanjuntak, 2002
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Percobaan
Penelitian dilakukan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi di desa
Sidiangkat, Bundar Selamat, Sitinjo dan Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun
di desa Pematang Raya, Merek Raya dan Sondi Raya dengan ketinggian ± 1000
mdpl. Penelitian dimulai pada bulan Mei sampai September 2010.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah tanaman kopi dari perkebunan rakyat,
aquadest, tanah dari sekitar perakaran tanaman kopi, akar tanaman kopi yang
terserang nematoda, Clorox, HCl, Acid Fuchsin, NaOCl2 dan gliserin.
Alat yang digunakan adalah bor tanah, cangkul, kantong plastik potilen,
kertas label, pisau cutter, kain saring, kawat kassa, corong Baerman, corong kaca,
mikroskop binokuler, mikroskop stereo,kamera digital,mikro pipet, pipet tetes,
telenan, cawan hitung, corong plastik. Buku identifikasi nematoda yang
digunakan, antara lain: Shurtleff dan Charles (2000), Dropkin (1992) dan
Luc, et al (1995).
Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode survei dengan cara mengamati
langsung di lapangan tanaman kopi yang terserang nematoda, lalu sampel tanah
disekitar perakaran dan akar tanaman kopi yang diduga terserang nematoda
Pelaksanaan Penelitian
Survei Pendahuluan
Survei pendahuluan bertujuan untuk menentukan desa yang mewakili
daerah sentra produksi, yaitu desa yang berada di Kecamatan Sidikalang di desa
Sidiangkat, Bundar Selamat, Sitinjo dan Kecamatan Raya di desa Pematang Raya,
Merek Raya dan Sondi Raya. Masing – masing kecamatan dipilih tiga desa, dari
tiap desa dipilih kebun kopi yang diduga terserang nematoda. Ciri – ciri atau
gejala tanaman yang terinfeksi nematoda pada tingkat lapang adalah tanaman
tumbuh lebih kerdil/ merana dari tanaman lain dalam kebun, daun menguning
atau klorosis dan tanaman kurang kokoh atau hampir roboh, sedangkan gejala
tingkat individu ditandai dengan adanya bercak nekrosis pada akar serta terdapat
gall atau pembengkakan pada akar – akar muda. Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel pada lokasi terpilih dilakukan jika ditemukan adanya
tanaman kopi yang diduga terserang nematoda pada lokasi tersebut. Sampel
diambil dengan metode zig – zag. Setiap sampel tanah dan akar diambil dari
empat penjuru tanaman dengan kedalaman ±25 cm. Masing – masing sampel
dimasukkan ke dalam plastik potilen dan diberi label yang berisi tanggal
pengambilan, lokasi, kultivar kopi, kondisi tanaman dan tanaman yang berada di
sekitar sampel.
Selanjutnya sampel diekstraksi untuk memperoleh suspensi nematoda
Ekstraksi sampel akar
Sampel akar diperoleh dari akar kopi yang diambil dari
lapangan penelitian kemudian diekstraksi dengan metoda
Modifikasi Corong Baerman. Sampel akar dicuci sampai bersih
dari tanah dan kotoran, dipotong – potong sepanjang 1 – 1,5 cm,
kemudian diambil akar sebanyak 25 gram dan diekstraksi dengan
metode modifikasi corong Baerman (Luc et al, 1995). Keadaan ini
dibiarkan selama 48 jam, sesudah 48 jam suspensi diambil dan
siap diamati.
Selanjutnya pengamatan dilakukan dan diulang sebanyak
3 kali. Tiap ulangan diambil sebanyak 10 cc yang dituang ke
dalam cawan hitung, lalu populasi dihitung dengan menggunakan
mikroskop binokuler. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan
mikroskop stereo yang dibantu oleh buku identifikasi nematoda. Ekstraksi sampel tanah
Untuk ekstraksi sampel tanah yang berasal dari lapang
dilakukan dengan metode modifikasi corong Baerman
(Luc et al, 1995). Masing – masing sampel tanah diambil
sebanyak 100 ml (Gambar 5). Keadaan ini dibiarkan selama 48
jam agar nematoda yang ada turun ke dalam air. Setelah 48 jam
suspensi yang berada di dalam corong diambil dan nematoda yang
ada diamati dan diidentifikasi.
Selanjutnya perhitungan dan identifikasi nematoda
Jumlah contoh yang mengandung
suatu genus nematoda
Jumlah seluruh contoh
Frekuensi mutlak suatu genus
Jumlah semua frekuensi mutlak
Jumlah individu suatu genus
nematoda dari setiap contoh
Jumlah seluruh individu dari
genus nematoda Parameter Pengamatan
Genus nematoda
Identifikasi untuk setiap sampel akar dan tanah dilakukan
sampai tingkat genus dengan menggunakan buku identifikasi. Populasi genus nematoda dari akar dan tanah
Setelah diidentifikasi selesai dilakukan, dilanjutkan dengan
menghitung populasi nematoda dari masing – masing genus
dengan cara mengambil 10 cc suspensi dari masing – masing
ekstraksi tanah dan akar.
Dalam menghitung populasi dari tiap genus nematoda
digunakan rumus sebagai berikut :
a. Frekuensi Mutlak (FM) = ×100%
b. Frekuensi Nisbi (FN) = × 100%
c. Kepadatan Mutlak (KM) = Jumlah aktual individu suatu genus nema- toda dari tiap contoh
×100%
d. KepadatanRelatif (KR)=
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Genus Nematoda
Hasil identifikasi nematoda parasit tanaman kopi pada sentra produksi
tanaman kopi di Kecamatan Sidikalaang, Dairi dan Kecamatan Raya, Simalungun
ditemukan dua genus nematoda parasit yang paling dominan, yaitu Radopholus sp
dan Pratylenchus sp.
Gambar 6. Radopholus similis
Tanaman kopi yang terserang di lapangan memiliki gejala serangan pada
bagian di atas permukaan tanah adalah daun menguning / layu, daun berguguran
dan tanaman kerdil. Hal ini sesuai literatur Shurtleff dan Charles (2000) yang
menyatakan beberapa efek tanaman yang terserang mengakibatkan daun klorotik
dan tanaman kerdil (Gambar 6).
Gambar 8. Gejala serangan nematoda luka akar di atas permukaan tanah di Kecamatan Sidikalang
Pada akar tanaman kopi yang terserang nematoda memiliki gejala
serangan kulit luar akar luka terkelupas, rambut akar tinggal sedikit atau habis
(Gambar 10), dan jika dibelah melintang akan tampak berkas nekrotik pada tepi
akar kopi (Gambar 9). Shurtleff dan Charles (2000) menyatakan nematoda
mengakibatkan luka nekrotik berwarna coklat kemerahan sampai hitam di
sepanjang jaringan korteks. Lubang terowongan meluas tetapi tidak melewati
jaringan endodermis. Begitu juga pada literatur Luc et al (1995) yang menyatakan
akar tanaman kopi yang terserang oleh P. coffeae warnanya berubah menjadi
Gambar 9. Gejala nekrotik pada tepi jaringan korteks akar
Gambar 10. Gejala serangan yang mengakibatkan permukaan akar terkelupas dan rambut akar habis.
B. Populasi Nematoda
Untuk mengetahui populasi kedua genus nematoda tersebut pada tiap
Tabel 1. Genus nematoda parasit yang dominan di pertanaman kopi di masing – masing lokasi pengambilan sampel.
No. Genus
Nematoda
LOKASI
Kecamatan Sidikalang Kecamatan Raya
Desa
Kopi merupakan tanaman perkebunan penting di Indonesia dan Sumatera
Utara khususnya yang merupkan slah satu sentra penghasil kopi. Budidaya kopi
yang dilakukan di Sumatera Utara menyebabkan perubahan stabilitas ekosistem.
Perubahan ini menjadikan dari semua lokasi pertanaman kopi yang digunakan
sebagai tempat pengambilan sampel akar dan tanah ditemukan 2 genera nematoda
parasit tumbuhan yang paling dominan berasosiasi dengan kopi yaitu
Radopholus spp dan Pratylenchus spp (Tabel 1). Populasi Radopholus spp yang
tertinggi dari sampel tanah dan akar ditemukan pada lokasi desa Sidiangkat yaitu
141 juvenil sedangkan yang terendah di desa Merek Raya 37 juvenil. Populasi
Pratylenchus spp yang tertinggi terdapat di desa Sidiangkat dan Sitinjo yaitu 109
juvenil sedangkan yang terendah terdapat di desa Merek Raya 30 juvenil.
Nematoda parasit merupakan kendala utama pada tanaman kopi di
Indonesia, terutama untuk jenis kopi Arabika. Spesies penting yang dijumpai di
Indonesia adalah Pratylenchus coffeae dan Radopholus similis. Hampir semua
propinsi produsen kopi di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan Sulawesi
Pada tabel 1, kita bisa melihat bahwa serangan nematoda di Kecamatan
Sidikalang lebih tinggi dari Kecamatan Raya. Hal ini diakibatkan oleh beberapa
faktor, antara lain di Sidikalang tanaman kopi telah ditanam selama bertahun –
tahun. Sedangkan di Raya tanaman kopi hasil konversi dari berbagai tanaman
seperti padi, jagung, cabai, dan lain – lain. Selain itu kondisi lahan di Sidikalang
kurang terawat yaitu banyak ditumbuhi gulma. Kondisi ini menyebabkan
nematoda parasit dapat berkembang dengan lebih baik, karena inang terus tersedia
sepanjang tahun. Kondisi lahan di Raya lebih bersih sehingga nematoda parasit
kurang berkembang dengan baik karena inangnya tidak selalu tersedia.
Tabel 3. Hasil ekstraksi dari sampel akar untuk tiap – tiap genus nematoda parasit tanaman kopi dari lokasi terpilih
Desa Genus
Dari Tabel 2 dan 3, nilai prominensi tertinggi adalah genus Radopholus
sebesar 304.10 pada tanah dan 1070 pada akar di desa Sidiangkat. Sedangkan nilai
prominensi terendah adalah genus Pratylenchus sebesar 86.60 pada tanah dan
187.08 pada akar di desa Merek Raya. Hal ini menunjukkan genus Radopholus
merupakan nematoda yang paling penting dan sangat berpotensi menimbulkan
kerusakan dan kerugian pada tanaman kopi di Sumatera Utara. Semakin tinggi
NP, maka menunjukkan semakin pentingnya nematoda tersebut pada tanaman
tersebut.
Kerusakan tanaman kopi yang disebabkan nematoda sangat merugikan
karena dapat mengakibatkan kematian tanaman. Hal ini sesuai literatur Ika (2005)
yang menyatakan serangan nematoda Pratylenchus coffeae, menyebabkan
kehilangan hasil rata-rata sebesar 56,84%, atau sekitar 150 ton kopi per tahun.
produk. Penurunan produksi oleh P. coffeae pada kopi Robusta berkisar antara
28,7% sampai 78,4%. Serangan P. coffeae terhadap kopi Arabika, biasanya
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Terdapat 2 genus nematoda parasit tumbuhan yang berasosiasi pada
tanaman kopi di Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Raya.
2. Populasi genus Radopholus yang tertinggi dari sampel akar ditemukan
pada lokasi desa Sidiangkat (Kecamatan Sidikalang) yaitu 107 juvenil
infeksi (ji) dan yang terendah ditemukan pada lokasi Merek Raya
(Kecamatan Raya) yaitu 25 juvenil infeksi (ji).
3. Populasi genus Radopholus yang tertinggi dari sampel tanah ditemukan
pada lokasi desa Sidiangkat (Kecamatan Sidikalang) yaitu 34 juvenil
infeksi (ji) dan yang terendah ditemukan pada lokasi Merek Raya
(Kecamatan Raya) yaitu 12 juvenil infeksi (ji).
4. Populasi genus Pratylenchus yang tertinggi dari sampel akar ditemukan
pada lokasi desa Sidiangkat (Kecamatan Sidikalang) yaitu 82 juvenil
infeksi (ji) dan yang terendah ditemukan pada lokasi Merek Raya
(Kecamatan Raya) yaitu 20 juvenil infeksi (ji).
5. Populasi genus Pratylenchus yang tertinggi dari sampel tanah ditemukan
pada lokasi desa Bundar Selamat (Kecamatan Sidikalang) yaitu 28 juvenil
infeksi (ji) dan yang terendah ditemukan pada lokasi Merek Raya
Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui tingkat kerusakan
yang disebabkan masing – masing genus nematoda parasit pada tanaman
kopi.
2. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui varietas kopi yang tahan
DAFTAR PUSTAKA
Anonimusa. 2010. http://en.wikipedia.org / wiki / Radopholus _ similis. Diakses tanggal 9 Maret 2010.
_______b. 2008.
2010.
_______c. 2009.
Maret 2010
Asmacs. 2008. Diakses tanggal 9 Maret 2010.
BPS., 2008. 18 September 2010.
Bridge, J dan James L. Starr. 2007. Plant Nematodes Of Agricultural Importance A Colour Handbook. Mansion Publishing Ltd. London.
Dropkin, V.H., 1992. Pengantar Nematologi Tumbuhan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Girsang, B., 2010. Komoditas – Komoditas Unggulan. Dinas Perkebunan. Propinsi Sumatera Utara.
Hasbi H. 2009. http://budidayatanamantahunan.blogspot.com / 2009 / 12 / budidaya-kopi.html. diakses tanggal 9 Maret 2010.
Ka. BIP Propinsi Irian Jaya. 1991. BUDIDAYA KOPI. Sentani.
Leroy., 2005. Plant Cell Rep 2006 Mar; 25 (3) :214-22. Epub 2005 Dec 6.
Luc, Zokora dan J. Bridge., 1995. Nematoda Parasitik Tumbuhan di Pertanian Subtropik dan Tropik Gadjah Mada University press, Yogyakarta.
Munif A. 2003. Prinsip – Prinsip Pengelolaan Nematoda Parasit Tumbuhan di Lapangan. dalam. Bahan Pelatihan. Identifikasi dan Pengelolaan Nematoda Parasit Utama Tumbuhan. 26 – 29 Agustus 2003. Bogor.
Mustika I. 2003. Penyakit – Penyakit Utama Tanaman Yang Disebabkan Oleh Nematoda. dalam. Bahan Pelatihan. Identifikasi dan Pengelolaan Nematoda Parasit Utama Tumbuhan. 26 – 29 Agustus 2003. Bogor.
Perkebunan di Indonesia. files/File/publikasi/perspektif/Perspektif_vol_4_No_1_2_IkaMustika.pdf. Diakses tanggal 13 Oktober 2010.
Najiyati, S dan Danarti. 1997. Kopi Budidaya dan Penanganan Lepas Panen. Penebar Swadaya. Jakarta.
Poinar, G.O., 1983. The Natural History Of Nematodes. Prentice Hall, Inc. New Jersey.
Purnomo B., 2008 Diakses tanggal 12 Oktober 2010.
Shurtleff, M.C. dan Charles W.A.III., 2000. Diagnosis Plant Diseases Caused By Nematodes. APS Press. St.Paul, Minnesota.
Simanjuntak, H. 2002. Musuh Alami Hama Dan Penyakit Tanaman Kopi.Proyek Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta.
Soetedjo, M.M. 1989. Hama Tanaman Keras Dan Alat Pemberantasannya. Bina Aksara. Jakarta.
Walker, John Charles. 1957. Plant Pathology. Kogakusha Company, Ltd. Tokyo.
Foto Lahan Kopi di Kecamatan Sidikalang