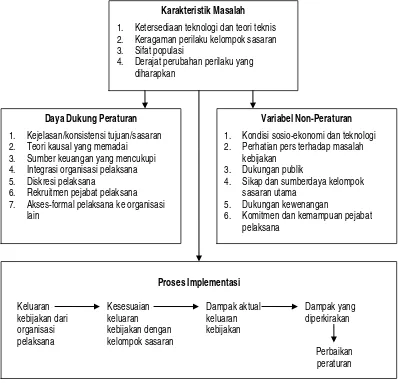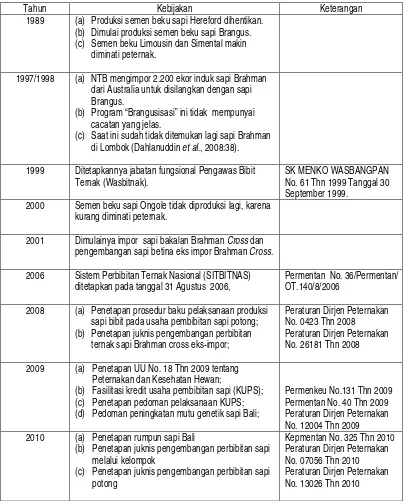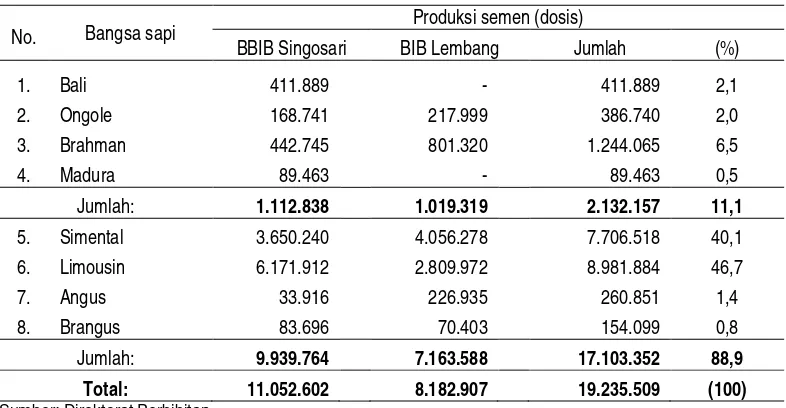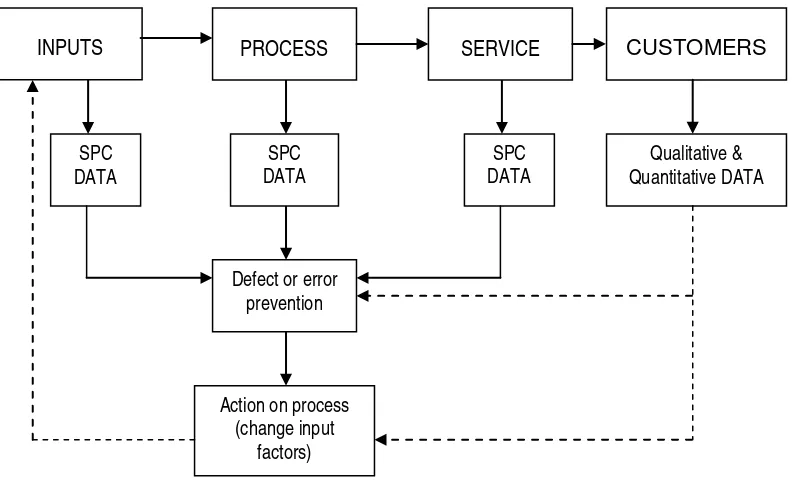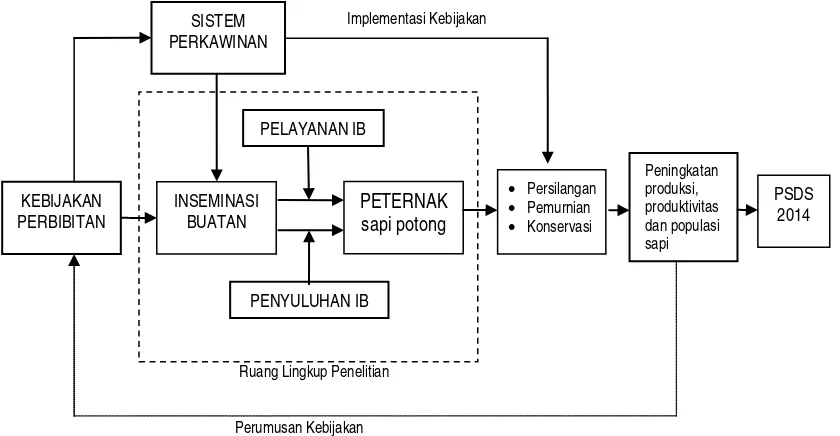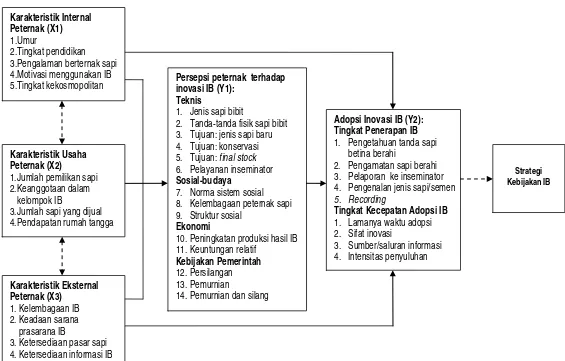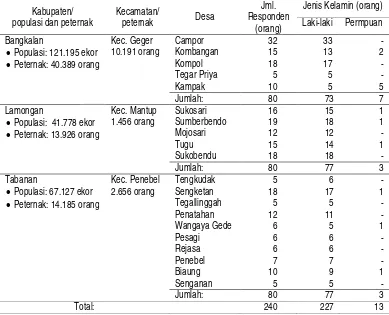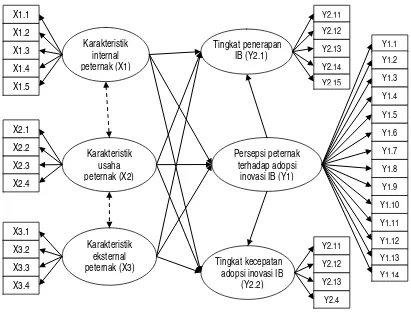TERHADAP ADOPSI INOVASI INSEMINASI BUATAN
PADA PETERNAK SAPI POTONG
Mursyid Ma’sum
P. 016014011
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
ii
Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang
berjudul:
IMPLIKASI KEBIJAKAN PERBIBITAN SAPI TERHADAP ADOPSI INOVASI
INSEMINASI BUATAN PADA PETERNAK SAPI POTONG
adalah merupakan hasil karya dan hasil penelitian saya sendiri, dengan
pembimbingan dari komisi pembimbing. Disertasi ini belum pernah diajukan
dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi dan
data yang digunakan berasal atau dikutip dari karya penulis lain yang diterbitkan
maupun tidak diterbitkan telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam
daftar pustaka secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, Juli 2011
iii
ADOPTED ARTIFICIAL INSEMINATION INNOVATION ON SLAUGHTER CATTLE’S FARMERS. Under supervised by AIDA VITAYALA S. HUBEIS, AMIRUDDIN SALEH and BUDI SUHARJO.
The general objective of the research is to describe and analyze the implementation and rate of adopted artificial insemination (AI) innovation on slaughter cattle’s farmers. The result showed that the internal, external and bussiness farm characteristic of slaughter cattle’s farmers and their perception on AI were signifcantly different among the locations of the research. The average of AI implementation by the farmers was 51.1%. There were significant different of average implementation of AI aspects among all locations. The average of the rate of AI adoption was 2.39 years. There are significant different between locations where the cross breeding policy have been applied (Lamongan and Bangkalan districts) and the location where the pure breeding policy have been applied (Tabanan district). In adoption of AI, the farmers in the Tabanan district were relatively faster than other districts. Based on the result of structural equation modelling analysis, the relationship among variables were (1) the variables of internal characteristic of slaughter cattle’s farmers and their perception to AI significantly influenced to the implementation of AI, but the variables of external and farm bussiness characteristic of slaughter cattle’s farmers did not significantly influence to the implementation of AI. The variable of the perception of the farmer to AI contributed to the implementation of AI relatively bigger than the internal characteristic of slaughter cattle’s farmers variable; (2) the variables of internal, external and farm bussiness characteristic of slaughter cattle’s farmers and their perception to AI significantly influenced to the rate of AI adoption. The most influence variable to the rate of AI adoption was the external characteristic of slaughter cattle’s farmers; (3) the perception of slaughter cattle’s farmers on AI influenced both to the implementation of AI and to the rate of AI adoption; (4) cumulatively, the influence of the internal, external, farm bussiness characteristics of slaughter cattle’s farmers and their perception to AI implementation aspects and to the rate of AI adoption was 0.51 (51%) and 0,86 (86%) respectively. The implementation of AI as an instrument to achieve breeding policy’s purposes on slaughter cattle did not give yield yet as it was hoped. This case was caused by the breeding policy on slaughter cattle still have not clear and the implementation of the AI in the field have not been controlled.
iv
Inovasi Inseminasi Buatan pada Peternak Sapi Potong. Pembimbing: AIDA VITAYALA S. HUBEIS, AMIRUDDIN SALEH dan BUDI SUHARJO.
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan dan kecepatan adopsi inovasi IB pada peternak sapi potong. Secara khusus tujuan penelitian adalah untuk (1) mengidentifikasi penerapan IB berdasarkan karakteristik internal dan eksternal serta karakteristik usaha peternak sapi potong; (2) mengidentifikasi persepsi peternak sapi potong terhadap aspek teknis, sosial-budaya, ekonomis dan kebijakan di bidang IB; (3) membangun model yang dapat menjelaskan pola keterkaitan faktor-faktor yang terkait dengan penerapan IB pada peternak sapi potong; dan (4) merancang strategi kebijakan IB pada peternak sapi potong. Penelitian dilakukan di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur dan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Penelitian dirancang sebagai penelitian survai deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jumlah sampel total 240 peternak akseptor IB dengan teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Analisis secara statistik menggunakan SEM (structural equation modeling).
Hasil identifikasi menunjukkan bahwa karakteristik internal, eksternal, usaha dan persepsi peternak sapi potong serta tingkat penerapan dan tingkat kecepatan adopsi inovasi IB menunjukkan perbedaan yang signifikan antar lokasi penelitian. Beberapa indikator yang signifikan terhadap konstruk karakteristik internal peternak sapi potong adalah umur peternak, tingkat pendidikan, pengalaman dalam memelihara sapi dan tingkat kekosmopolitan peternak. Untuk jumlah pemilikan sapi, tujuan pemeliharaan sapi, motivasi menggunakan IB, keanggotaan dalam kelompok IB dan besarnya pendapatan menjual pedet tidak signifikan terhadap konstruk karakteristik internal peternak sapi potong. Dari konstruk karakteristik eksternal peternak sapi potong, beberapa indikator yang signifikan adalah keadaan sarana prasarana, kepastian pasar sapi, intensitas penyuluhan IB dan ketersediaan informasi IB. Kelembagaan IB dan sumber informasi IB tidak signifikan terhadap konstruk karakteristik eksternal peternak sapi potong. Untuk konstruk persepsi, beberapa indikator yang signifikan adalah jenis sapi bibit, tanda-tanda fisik sapi bibit, pelayanan inseminator, tanda-tanda sapi induk berahi, norma sistem sosial, struktur sosial, peningkatan produksi hasil IB, keuntungan relatif menggunakan IB, kebijakan persilangan dan pemurnian; sedangkan tujuan pembibitan/IB, kelembagaan peternak sapi dan kebijakan campuran tidak signifikan terhadap konstruk persepsi peternak sapi potong terhadap IB.
v
karakteristik eksternal peternak dan persepsi peternak sapi potong terhadap tingkat penerapan IB (TPA-IB) dan tingkat kecepatan adopsi inovasi IB (TKA-IB) dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaruh peubah karakteristik usaha (KUP) dan karakteristik eksternal peternak sapi potong (KEP) terhadap tingkat penerapan IB secara statistik tidak signifikan (t-hitung<1,96). Sedangkan peubah karakteristik internal peternak sapi potong (KIP) dan persepsi berpengaruh secara nyata terhadap tingkat penerapan IB. Berdasarkan muatan faktornya, maka peubah persepsi terhadap IB (0,19) mempunyai kontribusi yang lebih besar dibanding peubah karakteristik internal peternak sapi potong (KIP=0,10) terhadap tingkat penerapan IB. Seseorang cenderung menyusun pengalamannya dalam bentuk yang memberi arti, dengan mengubah yang berserakan dan menyajikannya dalam bentuk yang bermakna. Dalam konteks ini, salah satu indikator yang dominan dari konstruk persepsi ini adalah persepsi peternak tentang keuntungan relatif dari inovasi IB (aspek ekonomi), yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi sapi hasil IB dan harga sapi hasil IB. Persepsi seseorang bisa berlainan satu sama lain dalam situasi yang sama karena adanya perbedaan kognitif. Setiap proses mental, individu bekerja menurut caranya sendiri tergantung pada faktor-faktor kepribadian. (2) Untuk tingkat kecepatan adopsi inovasi IB, semua peubah, yaitu karakteristik internal (KIP), usaha (KUP) dan eksternal (KEP) peternak sapi potong serta persepsi mereka terhadap IB, secara statistik keempat peubah tersebut berpengaruh secara nyata (t-hitung >1,96). Peubah yang paling besar kontribusinya terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ini secara berturut-turut adalah KUP (0,95), KIP (0,21), Persepsi (0,09) dan KEP (0,04). Beberapa indikator peubah karakteristik usaha yang dominan adalah jumlah sapi yang dijual dan indikator pendapatan rumah tangga. Fakta ini menunjukkan, bahwa aspek ekonomi IB sangat berpengaruh terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB. Sedangkan dari peubah KIP, indikator yang dominan adalah umur peternak dan pengalaman beternak sapi. (3) Persepsi peternak sapi potong tentang IB mempunyai pengaruh yang nyata, baik terhadap tingkat penerapan IB maupun terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB. Pengaruh persepsi peternak tentang IB ini lebih besar kontribusinya terhadap tingkat penerapan IB dibanding terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB. (4) Karakteristik internal, usaha dan eksternal peternak sapi potong serta persepsi peternak sapi potong terhadap IB secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penerapan IB sebesar 0,51 (51%) dan sisanya sebesar 0,49 (49%) merupakan pengaruh peubah lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. (5) Karakteristik internal, usaha dan eksternal peternak sapi potong serta persepsi peternak sapi potong terhadap IB secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB dengan koefisien determinasi sebesar 0,86 (86%) dan sisanya sebesar 0,14 (14%) merupakan pengaruh peubah lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
vi
©Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2011
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan
vii
PADA PETERNAK SAPI POTONG
MURSYID MA’SUM
Disertasi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada
Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
viii
Penguji luar komisi pada ujian tertutup: 1. Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc.
(Direktur Magister Bisnis IPB) 2. Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA
(Anggota Komisi Pascasarjana, SPs-IPB)
Penguji luar komisi pada ujian terbuka:
1. Drh. Prabowo Respatiyo Caturroso, MM, PhD (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian)
2. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc. Agr.
ix
Nama :
Nomor Pokok :
Program Studi :
BUATAN PADA PETERNAK SAPI POTONG
MURSYID MA’SUM
P.016014011
Ilmu Penyuluhan Pembangunan
Disetujui,
Komisi Pembimbing:
Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S, Hubeis
Ketua Anggota
Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS
Anggota
Dr. Ir, Budi Suharjo, MS
Diketahui
Ketua Program Studi/Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana,
Ilmu Penyuluhan Pembangunan,
Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.
x
dengan judul “Implikasi Kebijakan Perbibitan Sapi terhadap Adopsi Inovasi
Inseminasi Buatan pada Peternak Sapi Potong” ini dapat diselesaikan.
Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah
membantu, mendorong dan mendo’akan agar disertasi ini selesai, yaitu kepada:
1. Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala, S Hubeis, selaku ketua komisi pembimbing dan
Dr. Ir. Amiruddin Saleh MS serta Dr. Ir. Budi Suharjo MS sebagai anggota
komisi pembimbing, atas korbanan waktu, tenaga dan pikiran serta
kesabaran dalam membimbing penyusun.
2. Para penguji luar komisi, ujian tertutup: Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc. (Direktur
Magister Bisnis IPB) dan Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA (Anggota Komisi
Pascasarjana, SPs-IPB); ujian terbuka: Drh. Prabowo Respatiyo Caturroso,
MM, PhD (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian) dan Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc. Agr. (Dekan Fakultas Peternakan
IPB Bogor), yang dengan pertanyaan dan sarannya telah menyempurnakan
disertasi ini.
3. Seluruh teman-teman di dinas yang telah membantu proses penelitian ini,
baik di Provinsi Jawa Timur maupun di Provinsi Bali, yaitu:
a. Ir. Rohayati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Timur dan Drh. Suhardi serta enumerator pak Sunarji di Bangkalan.
b. Ir. Wardoyo, kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan dan Dekan
Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan dan para enumerator:
Wahyuni, Abdurahim, Abdul Wakhid, Kurniawan Dani dan Karmuji.
c. Ir. Nyoman Rusmini, MMA, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten
Tabanan dan Wayan Tami, para enumerator: I Gusti Putu Arum Jaya, I
Made Puja Astika, I Made Santra dan I Nyoman Sunata di Dinas
Peternakan Tabanan, Bali.
4. Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor beserta jajarannya
dan para dosen di Program Studi Penyuluhan Pembagunan yang tidak
mungkin penyusun sebut satu persatu, khususnya kepada Ketua Program
Studi/Mayor Penyuluhan Pembagunan Dr. Ir. Siti Amanah, MSc. dan
sekretaris ibu Dessi yang telah banyak membantu dalam urusan
xi
6. Kedua orang tuaku, ayahanda H. Ma’sum Edrisy (Alm) dan ibunda Hj. Siti
Zubaidah yang telah mengajarkan menuntut ilmu itu adalah ibadah.
7. Isteriku, dr. Henny Hanna, Sp.RM, MARS dan anak-anakku Ibnu Sina dan
Salman Al-Farisy yang dengan tulus dan caranya sendiri, masing-masing
telah membantu penyelesaian disertasi ini.
8. Kakanda Yusuf Selamat dan Laksdewi; adinda Syukri dan Rini;
sanak-saudara serta para sahabat dan kolega yang telah hadir untuk memberikan
dukungan dalam ujian terbuka.
Akhirul kalam, mudah-mudahan disertasi ini dapat memberi manfaat bagi
penyusun dan pihak-pihak terkait dalam pembangunan peternakan, khususnya
yang terkait dengan perbibitan dan penerapan IB.
Jakarta, Juli 2011
xii
1956 dari pasangan H. Ma’sum Edrisy (alm) dan Hj. Siti Zubaidah. Penulis adalah putra ke delapan dari sebelas bersaudara. Telah menikah dengan Dr. Hj. Henny Hanna, SpRM, MARS pada tanggal 4 Juli 1986 dan dikaruniai 2 putra bernama Ibnu Sina dan Salman Al-Farisy, keduanya kini kuliah di ITB Bandung dan UNDIP Semarang.
Penulis tamat pendidikan dasar di sekolah Al-Irsyad tahun 1969, melanjut-kan di SMP Muhammadiyah tamat tahun 1972 dan pendidimelanjut-kan menengah atas di SMA Negeri tamat tahun 1975, semuanya di Banyuwangi. Pendidikan tinggi (S1) di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 1983 dengan skripsi di bidang reproduksi ternak. Tahun 1994, melalui program OTO BAPPENAS, penulis berkesempatan menempuh pendidikan S2 di Fakultas Pertanian Gifu University Jepang, lulus tahun 1997 dalam bidang ilmu terapan
remote sensing (penginderaan jauh) untuk mengestimasi potensi wilayah dalam
penyediaan pakan hijauan ternak menggunakan data satelit. Selain pendidikan formal, penulis juga berkesempatan mengikuti beberapa pelatihan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain di Jerman tahun 1990 tentang Farming
System and Livestock Production, di Inggris tahun 1999 tentang Manajemen dan
teknik fasilitasi, dan studi banding pembangunan peternakan ke Sudan-Afrika tahun 2007, penulis tergabung sebagai anggota Tim Ahli Departemen Pertanian.
Setelah lulus S1 tahun 1983, penulis langsung bekerja sebagai petugas lapangan (satgas) Proyek Pengembangan Petani-Ternak Kecil bantuan Bank Dunia (IFAD) ditempatkan di daerah transmigrasi Lampung. Tahun 1983-1986 di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan 1983-1989 di Kecamatan Palas Lampung Selatan. Tahun 1989 penulis pindah ke Jakarta masih bekerja di proyek yang sama, di Bagian Teknis dari Project Management
Office (PMO) IFAD di Jakarta. Tahun 1994, ketika proyek IFAD selesai, penulis
ditempatkan di Bagian Organisasi dan Tatalaksana (ORTALA) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan. Tahun 1997 sepulang sekolah S2, penulis diangkat sebagai Kasubbag Organisasi dan Perpustakaan. Kemudian berturut-turut diangkat sebagai Kasubbag Analisis Jabatan dan Jabatan Fungsional tahun 1999; Kasubbag Mutasi Kepegawaian tahun 2000 s/d tahun 2005. Akhir tahun 2005 dipromosikan sebagai Kasubdit Pakan, Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia. Awal tahun 2008, penulis kembali ke Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Peternakan. Akhir tahun 2008 dimutasi kembali sebagai Kasubdit Pakan dan sejak tanggal 29 November 2010 dipercaya menjabat sebagai Direktur Pakan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Aktivitas lain penulis, sejak tahun 1998 adalah aktif sebagai fasilitator pelatihan dengan pendekatan partisipatif dan pendidikan orang dewasa. Tema sentral pelatihan umumnya adalah berkaitan dengan “mewirausahakan birokrasi,” beberapa subyek pelatihan yang penulis fasilitasi adalah “Manajemen mutu terpadu (TQM)” “Perencanaan secara partisipatif” “Penyusunan logical
xiii
DAFTAR TABEL ………...
DAFTAR GAMBAR ………...
DAFTAR LAMPIRAN ...
I. PENDAHULUAN ... Latar Belakang Penelitian………... Masalah Penelitian ………... Tujuan Penelitian ………... Kegunaan Penelitian dan Novelty.………...
II. TINJAUAN PUSTAKA ... Proses Adopsi dan Difusi Inovasi ...
Proses Adopsi Inovasi...………... Proses Difusi Inovasi ...………... Proses Komunikasi …... ……….... Sistem Sosial dan Perubahan Sosial ... Tingkat dan Kecepatan Adopsi Inovasi ... Persepsi ... Penelitian Terkait Adopsi Inovasi dan Implementasi IB ...…………. Karakteristik Peternakan Sapi Potong ... Kebijakan Perbibitan ... ………....
Kebijakan Publik ...………... Konsep Perbibitan ... Sejarah Kebijakan Perbibitan di Indonesia ……… Inseminasi Buatan dan Sejarah Perkembangannya ...………. Pengorganisasian Inseminasi Buatan .……… Penyuluhan ...
Konsep dan Pengertian Penyuluhan ... Empat Generasi Penyuluhan di Asia ... Paradigma Baru Penyuluhan ... Pelayanan yang Bermutu ………...
Filosofi dan Konsep Pelayanan yang Bermutu ... Konsep Mutu .………... Konsep Pelanggan ……….
III. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS ... Kerangka Pemikiran ... Hipotesis ...
IV. METODE PENELITIAN ………... Rancangan Penelitian ………... Lokasi dan Waktu Penelitian ………... Populasi dan Sampel ………... Populasi ... Sampel ... Jenis dan Teknik Pengumpulan Data ………...
Jenis data ... Teknik pengumpulan data ...
xiv
Analisis Data ...
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... Gambaran Umum Daerah Penelitian ... Pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Timur dan Bali ... Kondisi Peternakan Sapi Potong... Identifikasi Karakteristik Internal, Eksternal, Usaha dan Persepsi Peternak Sapi Potong ...
Karakteristik Internal Peternak Sapi Potong ... Karakteristik Usaha Peternak Sapi Potong ... Karakteristik Eksternal Peternak Sapi Potong ... Persepsi Peternak Sapi Potong terhadap Inovasi IB ... Tingkat Penerapan dan Kecepatan Adopsi Inovasi IB ... Tingkat penerapan IB ... Tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ... Model Keterkaitaan Faktor-Faktor dalam Penerapan IB pada Peternak Sapi Potong...
Validitas dan Reliabilitas konstruk ... Konstruk karakteristik internal peternak sapi potong (KIP) ... Konstruk karakteristik usaha peternak sapi potong (KUP) ... Konstruk karakteristik eksternal peternak sapi potong (KEP) ... Konstruk persepsi peternak sapi potong terhadap IB ... Konstruk tingkat penerapan IB (TPA-IB) ... Konstruk tingkat kecepatan adopsi inovasi IB (TKA-IB) ... Model Pengukuran dan Persamaan Struktural Adopsi Inovasi IB... Strategi Kebijakan Perbibitan terhadap Penerapan IB pada Peternak Sapi Potong ...
Konsep perbibitan sapi ... Penerapan IB pada sapi potong dalam sistem perbibitan ... Arah kebijakan perbibitan sapi potong ... Proses formulasi strategi kebijakan perbibitan sapi potong ... Faktor internal strategis penerapan IB pada peternak sapi potong... Faktor eksternal strategis penerapan IB pada peternak sapi potong... Strategi kebijakan IB ...
VI. SIMPULAN DAN SARAN ... Simpulan... Saran ...
DAFTAR PUSTAKA ………....
xv
1. Kronologis tindakan pemerintah di bidang perbibitan sapi ...
2. Produksi semen nasional dalam kurun waktu 2001-2010 ...
3. Perbandingan antara barang dan jasa ...
4. Populasi sapi, peternak dan penyebaran responden di masing-masing lokasi penelitian ...
.
5. Distribusi indikator karakteristik internal peternak sapi potong ...
6. Rataan nilai indikator KIP sapi potong antar lokasi penelitian...
7. Distribusi indikator karakteristik usaha peternak sapi potong ...
8. Tujuan pemeliharaan sapi potong ...
9. Rataan nilai indikator KUP sapi potong antar lokasi penelitian...
10. Distribusi indikator karakteristik eksternal peternak sapi potong...
11. Rataan nilai indikator KEP sapi potong antar lokasi penelitian...
12. Persepsi peternak sapi potong terhadap aspek teknis IB...
13. Persepsi peternak sapi potong terhadap aspek sosial budaya IB ...
14. Persepsi peternak sapi potong terhadap aspek ekonomi IB ...
15. Persepsi peternak sapi potong terhadap aspek kebijakan IB ...
16. Rataan nilai indikator persepsi sapi potong antar lokasi penelitian...
17. Tingkat penerapan IB ...
18. Rataan nilai indikator tingkat penerapan IB antar lokasi penelitian...
19. Tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ...
20. Rataan nilai indikator tingkat kecepatan adopsi inovasi IB antar lokasi penelitian...
21. Dekomposisi pengaruh antar peubah/sub peubah model tingkat penerapan dan kecepatan adopsi dan inovasi IB ...
22. Koefisien dan t-hitung pengaruh KIP, KUP, KEP dan Persepsi peternak sapi potong terhadap tngkat penerapan dan kecepatan adopsi inovasi IB..
23. Indikator-indikator yang signifikan terhadap konstruk ...
24. Ringkasan faktor analisis internal kekuatan dan kelemahan penerapan IB pada peternak sapi potong ...
25. Ringkasan faktor analisis eksternal peluang dan ancaman penerapan IB pada peternak sapi potong ...
26. Matriks analisis SWOT untuk perumusan strategi kebijakan perbibitan/IB pada peternak sapi potong ...
29
36
49
58
84
87
88
90
91
92
94
99
101
102
104
106
110
114
115
117
142
145
155
157
159
xvi
1. Model proses keputusan inovasi ………..
2. Tahapan proses adopsi oleh individu ………..
3. Model implementasi kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian ...
4. Metode kualitas jasa menurut Deming: proses yang diperluas ………...
5. Model konseptual mutu pelayanan ...
6. Keterkaitan kebijakan perbibitan sapi dan penerapan IB dalam
mendukung PSDS 2014 ... ...
7. Kerangka pemikiran penelitian implikasi kebijakan perbibitan sapi terhadap adopsi inovasi IB pada peternak sapi potong ...
8. Kerangka hipotetik model struktural peubah penelitian ...
9. Model hubungan antar faktor-faktor terkait dalam penerapan IB ...
10. Statistik t-hitung parameter hubungan antara konstruk KIP dan variabel indikatornya ...
11. Estimasi parameter hubungan antara konstruk KIP dan
variabel indikatornya ...
12. Statistik t-hitung parameter hubungan antara konstruk KUP dan
variabel indikatornya ...
13. Estimasi parameter hubungan antara konstruk KUP dan
variabel indikatornya ...
14. Statistik t-hitung parameter hubungan antara konstruk KEP dan
variabel indikatornya ...
15. Estimasi parameter hubungan antara konstruk KEP dan
variabel indikatornya ...
16. Statistik t-hitung parameter hubungan antara persepsi dan indikatornya...
17. Estimasi parameter hubungan antara persepsi dan indikatornya ...
18. Statistik t-hitung parameter hubungan antara TPA-IB dan indikatornya...
19. Estimasi parameter hubungan antara TPA-IB dan indikatornya ...
20. Statistik t-hitung parameter hubungan antara TKA-IB dan indikatornya...
21. Estimasi parameter hubungan antara TKA-IB dan indikatornya ...
22. Statistik t-hitung parameter model struktural tingkat penerapan IB
dan tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ...
23. Estimasi parameter model struktural tingkat penerapan IB dan tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ...
24. Model struktural hubungan antara KIP, KUP, KEP, Persepsi dan tingkat penerapan serta tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ...
xvii
1. Produksi semen beku BBIB Singosari dan BIB Lembang tahun 2001-2011.. 177
2. Kuesioner penelitian implikasi kebijakan perbibitan sapi terhadap adopsi
inovasi inseminasi buatan pada peternak sapi potong... 179
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Tujuan umum pembangunan peternakan, sebagaimana tertulis dalam
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2010-2014,
adalah meningkatkan penyediaan pangan hewani dan kesejahteraan peternak
melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan yang berdaya saing
dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.
Secara khusus tujuan pembangunan peternakan adalah (1) Meningkatkan
jaminan ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas, (2) Meningkatkan
populasi dan produktivitas ternak ruminansia, (3) Meningkatkan populasi dan
produktivitas ternak non-ruminansia, (4) Meningkatkan dan mempertahankan
status kesehatan hewan, (5) Meningkatkan jaminan keamanan produk hewan
dan (6) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan
prioritas Direktorat Jenderal Peternakan adalah Pencapaian Swasembada
Daging Sapi (PSDS) 2014, melalui kegiatan pokok: (1) Peningkatan kuantitas
dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal, (2)
Peningkatan produksi ternak ruminansia dan nonruminansia dengan
pendaya-gunaan sumberdaya lokal, (4) Pengendalian dan penanggulangan penyakit
hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, (5) Penjaminan pangan asal
hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan
non-pangan dan (6) Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang
peternakan (Ditjennak 2009a: 28-51).
PSDS Tahun 2014. Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014
merupakan salah satu dari 21 program utama Departemen Pertanian terkait
dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis
sumberdaya domestik. Saat ini kebutuhan daging sapi terus meningkat. Produksi
daging sapi lokal selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 mengalami
fluktuasi. Dari tahun 2005 hingga tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar
19,2%, lalu terjadi penurunan pada tahun 2007 menjadi 18,8% dan selanjutnya
mengalami peningkatan lagi sampai dengan tahun 2009 dengan rata-rata
peningkatan 9,1% per tahun. Kekurangan kebutuhan untuk konsumsi dipenuhi
dari impor ternak bakalan (feeder cattle) dan daging sapi. Selama kurun waktu
tahun 2005 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar
dibanding tahun 2008. Sementara itu, pertumbuhan populasi sapi potong dari
tahun 2005 hingga 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 populasi sapi
sebanyak 10,5 juta ekor dan pada thaun 2006 menjadi 10,9 juta ekor, atau
meningkat 2,8%. Kenaikan populasi meningkat tajam pada tahun 2007 dan 2008
yakni masing-masing 5,5% dan 6,9%. Kenaikan sapi ini kemudian melambat
pada tahun 2009 yaitu menjadi 2,4%. (Ditjennak 2010:12).
Isu strategis yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan menuju
swasembada daging sapi ini adalah masih rendahnya produktivitas sapi lokal,
yang ditunjukkan dengan (1) tingginya tingkat kematian sapi di beberapa wilayah,
yaitu untuk pedet antara 20 sampai 40% dan sapi induk 10 hingga 20 persen, (2)
sapi betina produktif yang dipotong mencapai 150-200 ribu ekor per tahun (3)
banyak sapi-sapi muda yang dipotong sebelum mencapai berat optimalnya,
sehingga sapi hanya memproduksi daging sekitar 60-80% dari potensi
maksimalnya, (4) produktivitas sapi yang masih sangat beragam, antara lain sapi
persilangan hasil inseminasi buatan (IB) yang dipelihara dengan cara seadanya
dan (5) langkanya sapi jantan di daerah sumber bibit dengan pola pemeliharaan
ekstensif (digembalakan) karena semua sapi jantan dijual atau dipotong.
PSDS 2014 ini diimplementasikan melalui lima kegiatan pokok, yaitu (a)
Penyediaan sapi bakalan/daging sapi lokal, (b) Peningkatan produktivitas dan
reproduktivitas sapi lokal, (c) Pencegahan pemotongan sapi betina produktif, (d)
Penyediaan sapi bibit, (e) Pengaturan stock daging sapi dalam negeri. Secara
lebih rinci, lima kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi 13 kegiatan
operasional yang meliputi: (1) Pengembangan usaha pembiakan dan
penggemukan sapi lokal, (2) Pengembangan pupuk organik dan biogas, (3)
Pengembangan integrasi ternak-tanaman, (4) Pemberdayaan dan peningkatan
kualitas rumah potong hewan, (5) Optimalisasi kegiatan IB dan intesivikasi kawin
alam, (6) Penyediaan dan pengembangan pakan dan air, (7) Penanggulangan
gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, (8)
Penyelamatan sapi betina produktif, (9) Penguatan wilayah sumber bibit dan
kelembagaan usaha perbibitan, (10) Pengembangan usaha perbibitan sapi
potong melalui village breeding center (VBC), (11) Penyediaan bibit sapi melalui
subsidi bunga (program kredit usaha pembibitan sapi/KUPS), (12) Pengaturan
stock sapi bakalan dan daging, (13) Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi
Beberapa kegiatan operasional PSDS 2014 dalam mendukung kegiatan
pokok sebagaimana tersebut di atas, antara lain melalui (1) penguatan wilayah
sumber bibit dan kelembagaan usaha perbibitan, (2) pengembangan usaha
pembibitan sapi potong melalui VBC dan (3) kegiatan optimalisasi IB. Khusus
kegiatan optimalisasi IB, ini dilakukan mengingat (1) potensi populasi ternak sapi
induk yang ada, (2) teknologi IB yang sudah dikuasai dan sudah banyak
diadopsi oleh peternak, (3) jumlah SDM (inseminator, pemeriksa kebuntingan
dan asisten teknik reproduksi) yang tersedia dan (4) dukungan infrastruktur
(produksi semen, peralatan, kelembagaan IB dan peternak). Hal ini juga sejalan
dengan visi Direktorat Jenderal Peternakan 2009-2014, yaitu menjadi direktorat
jenderal peternakan yang profesional dalam mewujudkan peternakan yang
berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani
serta meningkatkan kesejahteraan peternak.
Teknologi IB diperkenalkan di Indonesia pada tahun lima-puluhan.
Kemudian mulai dilakukan ujicoba dan disosialisasikan ke daerah-daerah pada
tahun 1969, namun kebijakan penerapan IB oleh Pemerintah c.q Direktorat
Jenderal Peternakan baru dimulai tahun 1976 bersamaan dengan diresmikannya
Sentra Inseminasi Buatan Lembang. Kebijakan penerapan IB saat itu ditujukan
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah dan sapi potong.
Untuk sapi perah ditempuh melalui grading-up dengan mendatangkan pejantan
unggul (proven bull) dari luar negeri. Sedangkan untuk sapi potong, melalui
grading-up ternak asli seperti sapi Bali dan Ongole dan melalui persilangan
dengan sapi potong dari luar negeri (BIB Lembang 2001:1).
Inseminasi Buatan sebagai teknologi reproduksi dalam penerapannya tidak
dapat dipisahkan dengan sistem perkawinan yang merupakan salah satu
instrumen dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang perbibitan. Menurut
Gordon (2004:49-50), bahwa IB sebagai teknologi reproduksi, tidak diragukan
lagi adalah cara yang paling penting yang diterapkan pada sapi selama abad 20,
karena IB secara relatif, lebih murah dan mudah untuk diterapkan. Menurut
Skjervold (1982:13-14), selama dua dekade terakhir IB telah menjadi cara
perkawinan yang paling penting, dan lebih jauh IB telah memberikan dimensi
baru pada kegiatan pembibitan ternak sapi.
Inseminasi Buatan, secara umum bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu
keturunannya dan (3) meningkatkan efisiensi penggunaan pejantan unggul
(Foote 1981:13-39 dan Gordon 2004:51). Implikasi dari penerapan IB ini adalah
meningkatnya produksi dan produktivitas ternak turunannya, sekaligus dapat
meningkatkan populasi. Setelah hampir empat dekade sejak IB diperkenalkan,
fenomena respons masyarakat terhadap teknologi IB ini bervariasi. Fenomena
tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi empat macam: (1) menjadi
IB minded, (2) menerima, (3) masih mencoba-coba dan (4) menolak.
Dari aspek penyuluhan, teknologi IB telah menggantikan cara perkawinan
sapi yang selama ini dilakukan secara turun-temurun, yaitu kawin secara alami.
Aspek lain, pemeliharaan sapi potong dan cara perkawinan telah menjadi bagian
dari sistem sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu,
proses perubahan perilaku peternak sapi potong dalam merespons IB sebagai
suatu inovasi teknologi reproduksi bukanlah hal yang sederhana. Hal ini
dipengaruhi oleh banyak faktor dan prosesnya membutuhkan waktu. Beberapa
faktor yang mempengaruhi respons peternak dengan diperkenalkannya suatu
inovasi, secara umum dipengaruhi oleh masalah teknis, sosial, ekonomi dan
budaya. Menurut Lionberger dan Gwin (1982:5) hal tersebut sebagian
dipengaruhi oleh (1) faktor individu, (2) sebagian oleh situasi di mana dia berada,
dan (3) sifat dari gagasan inovasi tersebut. Lebih jauh dikatakan, bahwa respons
terhadap suatu inovasi sangat berbeda antara orang-perorang dan masyarakat
yang satu dengan yang lain, serta peubah-peubahnya juga berbeda. Hal ini
mengindikasikan diperlukannya pendekatan yang berbeda dalam memberikan
penyuluhan IB kepada masyarakat.
Terhadap perkawinan silang ataupun pemurnian yang menggunakan IB di
Indonesia, Hardjosubroto et al., (1997:250) mengingatkan agar memperhatikan
aspek sosial dan budaya. Artinya, persoalan kebijakan bibit tidak semata-mata
masalah teknis dan/atau ekonomi saja, tetapi juga menyangkut masalah sosial
dan budaya. Sebagai contoh, persilangan antara sapi Madura dengan pejantan
Santa Gertrudis di Socah Madura, telah menghasilkan sapi Madrali yang lebih
produktif. Tetapi sapi Madrali akhirnya ditolak oleh penduduk karena sapi Madrali
tidak dapat digunakan untuk karapan. Contoh lain misalnya hasil persilangan
antara sapi PO dengan sapi Hereford di Sawangan Jawa Tengah, yang
walaupun dari segi produksi cukup baik, tetapi telah mengecewakan penduduk
karena sapi hasil silangan ini tidak berpunuk sehingga tidak dapat digunakan
Dari aspek kebijakan perbibitan, Pane (1993:2) sangat menyayangkan
bahwa hingga saat ini tidak ada data yang lengkap, baik itu hasil pemurnian sapi
Ongole di Sumba maupun hasil persilangan antara sapi Ongole (murni) dengan
sapi Jawa menjadi sapi PO (Peranakan Ongole). Bahkan sapi PO, walaupun
sudah menjadi suatu jenis tersendiri –kini banyak disilangkan dengan sapi
Simental dan Limousine- tapi performansnya belum diketahui. Demikian pula
dengan komposisi darahnya. Seharusnya, sebelum suatu usaha peningkatan
mutu sapi tersebut dimulai, sudah diketahui terlebih dahulu mutu dan komposisi
darah tetuanya (Pane 1993: 23). Belum lagi sapi perah Grati, bagaimana
komposisi darahnya? Hal ini mengakibatkan tujuan perbaikan mutu genetik
sapi-sapi di Indonesia menjadi tidak jelas.
Pengorganisasian IB ini melibatkan banyak institusi, baik pemerintah,
swasta maupun masyarakat. Dari aspek kebijakan, masalah perbibitan masih
merupakan kewenangan Pusat (Pemerintah). Penyediaan peralatan dan bahan,
khususnya container dan N2
Setelah sekitar empatpuluhan tahun IB ini diperkenalkan dan diterapkan
pada peternakan sapi potong, maka perlu dilakukan penelitian yang
komprehensif dan mendalam, apakah hasilnya ini sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan kebijakan perbibitan; atau, adakah
implikasi-implikasi lain yang mengharuskan pemerintah untuk meninjau kembali
kebijakan perbibitan tersebut.
cair oleh perusahaan swasta. Sedangkan pelaksana
di lapangan dilakukan oleh inseminator. Terdapat dua status inseminator, yaitu
(1) sebagai aparat pemerintah (Inseminator plat merah) dan (2) yang dilakukan
oleh masyarakat sendiri (inseminator swadaya/mandiri), khususnya untuk
daerah-daerah yang sudah maju dan peternaknya sudah IB-minded.
Masalah Penelitian
Proses adopsi dan difusi inovasi IB bukanlah hal yang sederhana. Hal ini
dipengaruhi banyak faktor, yaitu (1) peternaknya sendiri, (2) lingkungan di mana
peternak berada dan (3) persepsi peternak terhadap IB dari aspek teknis,
sosial-budaya, ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang perbibitan. Oleh karena itu,
IB sebagai suatu inovasi, akan membawa implikasi baik secara teknis,
sosial-ekonomi maupun budaya suatu sistem sosial (masyarakat). Menurut van den
Ban dan Hawkins (1999:140), dalam kebanyakan penelitian tentang difusi
inovasi, sedikit sekali perhatian diberikan terhadap perubahan yang besar dalam
masyarakat jarang diteliti, padahal perubahan sosial yang demikian sangat
penting, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.
Inseminasi Buatan adalah salah satu teknologi reproduksi yang
diperkenalkan sejak empat dekade yang lalu. Beberapa hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi peternak terhadap IB, ada yang
setuju dengan penerapan IB, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang menolak.
Secara teknis, IB sebagai salah satu teknik perkawinan sekaligus sebagai
instrumen implementasi kebijakan perbibitan pada sapi, telah (1) mempercepat
penyebaran gen-gen sapi unggul, baik yang berasal dari sapi pejantan asli dan
lokal, maupun yang berasal dari sapi-sapi impor, khususnya jenis Simental,
Limousin dan Brahman, (2) menggantikan sistem kawin alami yang selama ini
digunakan oleh masyarakat. Hal ini berarti telah mengubah (a) status
kepemilikan sapi jantan, khususnya pejantan “unggul” sebagai pemacek, (b)
peran peternak pemilik pemacek dalam masyarakat dan (c) hubungan (interaksi)
sosial antara peternak pemilik pemacek dan masyarakat pengguna pemacek
tersebut. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sapi turunan hasil
perkawinan silang antara sapi impor dan sapi asli atau lokal, mempunyai harga
jual yang lebih tinggi dibanding dengan harga sapi turunan hasil perkawinan
antar sapi asli ataupun sapi lokal (pemurnian). Hal ini disebabkan turunan hasil
persilangan mempunyai berat lahir, pertambahan berat badan harian dan berat
hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perkembangan jumlah akseptor IB,
khususnya untuk persilangan, pada tiga dekade awal sangat pesat. Sedangkan
pada separuh dekade terakhir menunjukkan tanda-tanda kejenuhan, bahkan
penurunan.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, dari sisi tujuan pemerintah untuk
meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi potong, dan meningkatkan
pendapatan peternak sapi potong, telah menunjukkan keberhasilan. Namun, dari
sisi perbibitan sapi potong, jika keinginan peternak untuk menyilangkan sapi asli
atau lokal dengan sapi impor tidak direncanakan dengan baik, dikendalikan,
tidak dicatat secara rapih dan lengkap, maka arah kebijakan perbibitan sapi
potong akan menjadi kabur. Sapi asli dan lokal sebagai kekayaan sumberdaya
genetik ternak Indonesia akan punah karena tidak dilakukan konservasi, seperti
kasus sapi Jawa. Sementara, hasil persilangan dengan sapi impor tidak
teridentifikasi dengan jelas, baik silsilah maupun komposisi darah tetuanya. Dari
terjadi peningkatan produktivitas sapi turunan hasil persilangan, tetapi secara
sosial-budaya tidak dapat diterima oleh masyarakat, seperti hasil persilangan
antara sapi Madura dan Santa gertrudis, tidak dapat untuk karapan. Begitupun
persilangan antara sapi PO dan sapi Hereford walaupun dari segi produksi
cukup baik, tetapi telah mengecewakan penduduk karena turunannya tidak
berpunuk sehingga tidak dapat digunakan untuk menarik bajak, dan lain-lain.
Fenomena ini perlu diteliti lebih beragam dan lebih dalam untuk memperoleh
realitas sebenarnya dari implikasi penerapan IB di masyarakat.
Sebagai suatu inovasi teknologi, sejauh ini penelitian IB lebih banyak
dilakukan terhadap aspek teknisnya, sedikit sekali penelitian IB dikaitkan dengan
masalah ekonomi dan sosial-budaya, lebihjauh dikaitkan dengan masalah
perilaku dan perubahan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang
menyeluruh dan mendalam terhadap implikasi penerapan IB dalam masyarakat,
terutama dikaitkan dengan karakteristik peternak sapi potong dan persepsi
mereka terhadap IB baik dari aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi dan
kebijakan pemerintah.
Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah karakteristik internal dan eksternal serta karakteristik usaha
peternak sapi potong peserta IB?
2. Bagaimanakah persepsi peternak sapi potong terhadap IB dari aspek teknis,
sosial-budaya, ekonomis dan kebijakan di bidang IB?
3. Bagaimanakah pola keterkaitan karakteristik internal dan eksternal peternak
sapi potong, karakteristik usaha dan persepsi peternak tentang IB terhadap
tingkat penerapan dan kecepatan adopsi inovasi IB?
Tujuan Penelitian
Penelitian implikasi kebijakan perbibitan sapi terhadap adopsi inovasi IB
pada peternak sapi potong ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat
dan kecepatan adopsi inovasi IB.
Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mengidentifikasi penerapan IB berdasarkan karakteristik internal dan
eksternal serta karakteristik usaha peternak sapi potong.
2. Mengidentifikasi persepsi peternak sapi potong terhadap aspek teknis,
sosial-budaya, ekonomis dan kebijakan di bidang IB.
3. Membangun model yang dapat menjelaskan pola keterkaitaan faktor-faktor
4. Merancang strategi kebijakan IB dilihat dari karakteristik internal dan
eksternal, karakteristik usaha, persepsi peternak tentang IB, tingkat
penerapan dan kecepatan adopsi inovasi IB pada peternak sapi potong.
Kegunaan Penelitian dan Novelty
Melalui pemahaman karakteristik internal dan eksternal, karakteristik usaha
dan persepsi peternak sapi potong terhadap tingkat penerapan dan kecepatan
adopsi inovasi IB sebagai instrumen implementasi kebijakan perbibitan di sentra
sapi potong, maka dapat diperoleh novelty berupa informasi dasar sebagai
bahan masukan penyusunan modul/kurikulum penyuluhan di bidang perbibitan
sapi potong yang berbasis spesifikasi lokasi dan sebagai dasar penyusunan
standar pelayanan IB yang berorientasi kepada kebutuhan dan harapan peternak
sapi potong sebagai pengguna.
Kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah khasanah
keilmuan penyuluhan pembangunan pertanian dengan menyediakan data
dan informasi tentang keterkaitan karakteristik internal dan eksternal
peternak, karakteristik usaha, persepsi dan tingkat penerapan IB serta
kecepatan adopsi inovasi IB peternak sapi potong.
2. Diperolehnya informasi kebutuhan dan harapan peternak sapi potong
sebagai sasaran penyuluhan dan pelanggan pelayanan IB.
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal
Peternakan dalam penyusunan kebijakan di bidang perbibitan sapi potong
TINJAUAN PUSTAKA
Proses Adopsi dan Difusi Inovasi
Teknologi IB diperkenalkan di Indonesia pada tahun limapuluhan.
Kemudian mulai dilakukan uji-coba dan disosialisasikan ke daerah-daerah pada
tahun 1969. Namun kebijakan penerapan IB oleh Pemerintah c.q Direktorat
Jenderal Peternakan baru dimulai tahun 1976 bersamaan dengan diresmikannya
Sentra Inseminasi Buatan Lembang. Sebagai suatu inovasi teknologi di bidang
reproduksi ternak, IB tidak langsung diterima oleh peternak.
Inovasi menurut Rogers (2003:11) adalah suatu gagasan, tindakan atau
obyek yang dianggap baru oleh suatu individu atau beberapa individu.
Inseminasi Buatan sebagai salah satu teknologi reproduksi, masuk pada kategori
“technological innovation.” Menurut Rogers (2003:12-15, 35) setiap teknologi
terdiri dua komponen, yaitu (1) suatu perangkat keras (hardware) yang terdiri dari
peralatan dan (2) suatu perangkat lunak (software) yang merupakan informasi
ataupun pengetahuan dasar dari peralatan tersebut dan cara penggunaannya.
Dalam konteks IB, yang termasuk perangkat keras seperti frozen semen,
container, insemination gun dan lain-lain, yang berwujud benda atau fisik.
Sedangkan yang termasuk perangkat lunak adalah selain pengetahuan dasar
dari peralatan tersebut dan cara penggunaannya, juga pengetahuan peternak
tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh pelayanan IB serta pasca
pelayanan IB.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil
keputusan inovasi mulai dari ”pengenalan” sampai dengan mengambil
”keputusan” apakah menerima inovasi tersebut ataupun menolaknya. Begitu juga
setelah mengambil keputusan, diperlukan waktu untuk ”konfirmasi” apakah akan
diteruskan menerima ataupun berhenti. Bagi yang menolak, mungkin akan terus
menolak ataupun pada akhirnya menerima setelah melihat banyak bukti yang
berhasil (Rogers & Shoemaker 1995:102).
Proses individu mengambil suatu keputusan inovasi, dapat dilihat pada
Gambar 1. Model proses keputusan inovasi (Rogers & Shomaker 1995: 102).
Dalam Gambar 1 tersebut jelas terlihat setidak-tidaknya ada beberapa
faktor yang berpengaruh terhadap tingkat maupun kecepatan proses adopsi
inovasi, yaitu latar belakang peternak, baik yang berkaitan dengan individu
(karakteristik internal) maupun sistem sosial (karakteristik eksternal), proses
komunikasi dan sifat dari inovasinya serta dimensi waktu.
Proses Adopsi Inovasi
Adopsi adalah suatu keputusan untuk menerima sepenuhnya suatu inovasi
(gagasan, tindakan dan/atau obyek) sebagai pilihan terbaik yang tersedia untuk
bertindak atau melakukan sesuatu (Rogers 2003:21). Menurut Lionberger dan
Gwin (1982:60-62), sebelum sampai pada adopsi, proses yang dilalui oleh
individu adalah kepedulian, ketertarikan, penilaian, mencoba dan menerima
(awareness, interest, evaluation, trial dan adoption). Tahapan proses adopsi oleh
individu dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
a.Ganti b.Kecewa
(LATAR BELAKANG) (PROSES) (KONSEKUENSI)
PEUBAH PENERIMA SUMBER KOMUNIKASI
1.Sifat-sifat pribadi 2.Sifat-sifat sosial 3.Kebutuhan akan inovasi 4.Dan lain-lain
PENGENALAN PERSUASI KEPUTUSAN KONFIRMASI ADOPSI
TERUSKAN
HENTIKAN
SISTEM SOSIAL SIFAT INOVASI MENOLAK
1.Norma-norma sistem 2.Toleransi terhadap
perubahan 3.Kesatuan komunikasi 4.Dan lain-lain
1.Keuntungan relatif 2.Kompatibilitas 3.Kompleksitas 4.Trialabilitas 5.observabilitas
ADOPSI LAMBAT
TERUS MENOLAK INFORMASI
Gambar 2. Tahapan proses adopsi oleh individu (Lionberger & Gwin 1982:61)
Pada tahap awareness, seseorang menjadi peduli terhadap gagasan,
produk, ataupun cara baru ketika melihatnya untuk pertama kali. Orang tersebut
hanya memiliki sedikit pengetahuan ataupun informasi tentang hal baru tersebut.
Pada tahap interest, muncul ketertarikan terhadap hal yang baru tersebut. Pada
tahap ini, informasi yang bersifat umum tidak cukup, tetapi dia mulai ingin
mengetahui apa yang sesungguhnya tentang hal tersebut, bagaimana hal itu
akan bekerja dan sebagainya. Orang tersebut membutuhkan informasi lebih
lanjut dan secara aktif mencari informasi tambahan yang lebih rinci. Pada tahap
evaluation, sebagai calon adopter yang sudah mengumpulkan informasi, maka
orang tersebut mulai menimbang-nimbang antara pro dan kontra dari gagasan
baru tersebut, dan ini terkait pada keadaan mental dari orang yang
bersangkutan, dikarenakan dia harus memutuskan dua hal, yaitu (1) apakah ini
sesuatu yang baik dan (2) apakah ini baik untuk saya. Pada tahap trial,
seseorang mulai mencoba gagasan ataupun cara baru tersebut. Hasil penelitian
membuktikan bahwa pola yang umum yang dilakukan pada tahap ini adalah
seseorang pada awalnya mencoba sedikit demi sedikit, dan jika semuanya
berjalan dengan baik, maka dia akan mencoba lebih banyak. Akhirnya, jika
percobaan permulaan berhasil, yang biasanya dilakukan oleh seseorang pada
usahanya sendiri dan sering setelah mengamati atau berkonsultasi dengan yang
lain, maka dia akan mengadopsi inovasi tersebut untuk digunakan seterusnya.
Atau, bisa juga dia sama sekali tidak menggunakan inovasi tersebut. Pada tahap
adoption, seseorang memutuskan bahwa suatu inovasi cukup baik untuk
digunakan dalam skala penuh, dan akan dipertahankan sampai ada inovasi lagi
(Lionberger & Gwin 1982:61-62).
Namun, tidak ada kesepakatan di antara para peneliti bahwa keputusan
untuk mengadopsi suatu inovasi merupakan hasil dari sekuens pengaruh yang
bekerja saat itu atau sebagai sesuatu yang terjadi secara instan. Lebih jauh
dikatakan, ada variasi dalam proses adopsi, yaitu tidak semua orang mengalami
semua tahapan secara persis urutannya dalam mengambil keputusan
(Lionberger & Gwin 1982:62).
Proses adopsi adalah bersifat individual, dan hal ini akan menyebar ke
anggota masyarakat yang lain dalam proses yang dikenal sebagai difusi inovasi.
Proses Difusi Inovasi
Difusi adalah suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan
sepanjang waktu melalui saluran tertentu kepada anggota dari suatu sistem
sosial. Unsur utama dari difusi ini adalah (1) suatu inovasi, (2) menggunakan
saluran komunikasi tertentu , (3) dalam suatu jangka waktu dan (4) di antara para
anggota sistem sosial (Rogers 2003:10-37; Nasution 2002:124).
Inovasi. Dari unsur inovasi, beberapa aspek yang perlu diperhatikan
adalah (1) inovasi teknologi, informasi dan ketidakpastian, (2) klaster teknologi
dan (3) karakteristik inovasi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa
yang dimaksud dengan inovasi adalah suatu gagasan, tindakan atau obyek
yang dianggap baru oleh suatu individu atau beberapa individu. Anggapan
”kebaruan” suatu ”gagasan, tindakan atau obyek” akan menentukan bagaimana
orang bereaksi. Sebagai suatu ”technological innovation,” inovasi menciptakan
semacam ketidakpastian dalam pikiran seorang adopter potensial (Rogers
2003:13). Oleh karena itu dibutuhkan banyak informasi untuk mengurangi
ketidakpastian tersebut. Suatu klaster teknologi terdiri dari satu atau lebih unsur
teknologi yang dapat dibedakan dan dianggap mempunyai kemiripan dengan
inovasi lain. Klaster teknologi adalah batas-batas sekitar suatu inovasi teknologi.
Hal ini penting karena menyangkut suatu konsep dan metodologi dari inovasi
teknologi tersebut. Karakteristik inovasi, sebagaimana mereka persepsikan,
akan menjelaskan perbedaan kecepatan proses adopsi. Beberapa hal yang
terkait dengan ini adalah (1) kelebihan/keutamaan relatif (relative advantages),
(2) kesesuaian (compatibility), (3) kerumitan (complexity), (4) dapat dicoba
(trialability) dan (5) dapat dilihat (observability). Penjelasan berikut adalah dari
Nasution (2002:125):
1. Keuntungan relatif (relative advantages), yaitu apakah inovasi tersebut
memberikan sesuatu keuntungan relatif bagi mereka yang menerima inovasi
tersebut.
2. Keserasian (compatibility), yaitu apakah inovasi yang hendak diadopsi sesuai
dengan nilai-nilai, sistem kepercayaan, gagasan yang lama, kebutuhan,
selera, adat-istiadat dan sebagainya dari masyarakat yang bersangkutan;
3. Kerumitan (complexity), yaitu apakah inovasi tersebut dirasakan rumit. Pada
sebab selain sukar dipahami, juga cenderung dirasakan sebagai tambahan
beban baru.
4. Dapat dicobakan (trialability), yaitu suatu inovasi akan lebih cepat diterima,
bila dapat dicobakan terlebih dahulu dalam ukuran kecil sebelum orang
terlanjur menerimanya secara menyeluruh. Ini adalah hal yang wajar, karena
seseorang akan selalu berupaya menghindari resiko yang besar terhadap hal
baru.
5. Dapat dilihat (observability), jika suatu inovasi dapat disaksikan dengan
mata, dapat terlihat langsung hasilnya, maka orang akan lebih mudah untuk
mempertimbangkan untuk menerimanya, ketimbang bila inovasi itu berupa
sesuatu yang abstrak, yang hanya dapat dibayangkan.
Saluran komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses, di mana anggota
masyarakat menciptakan dan berbagi informasi satu dengan yang lainnya, dalam
rangka mencapai pemahaman yang saling menguntungkan. Difusi adalah suatu
jenis komunikasi khusus di mana isi pesan yang saling dipertukarkan adalah
berkaitan dengan gagasan baru. Prosesnya melibatkan (1) suatu inovasi, (2)
individu atau satuan lain adopsi yang mempunyai pengetahuan tentang inovasi
atau berpengalaman menerapkan inovasi tersebut, (3) individu lain atau satuan
lain yang belum berpengalaman menerapkan inovasi tersebut dan (4) saluran
komunikasi yang menghubungkan kedua satuan tersebut. Jadi, saluran
komunikasi adalah suatu tindakan dimana pesan diperoleh dari satu individu ke
individu yang lain.
Dimensi waktu. Waktu adalah unsur ketiga utama dari suatu proses difusi.
Dimensi waktu tidak bisa diabaikan, hal ini terkait (1) dalam innovation process,
individu melewati dari pengetahuan awal tentang inovasi sampai kepada
menerima atau menolak inovasi, (2) bisa diperbandingkan antara yang relatif
cepat atau lambat dalam mengadopsi suatu inovasi dan (3) kecepatan
mengadopsi suatu inovasi dalam suatu sistem, biasanya diukur dari jumlah
anggota yang mengadopsi inovasi tersebut dalam periode waktu tertentu.
Anggota sistem sosial. Penyebar-serapan (difusi) inovasi terjadi secara
terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu waktu ke kurun
waktu yang berikutnya, dan dari bidang tertentu ke bidang lainnya melalui
anggota sistem sosial. Difusi inovasi sebagai suatu gejala kemasyarakatan
berlangsung berbarengan dengan perubahan sosial yang terjadi. Bahkan kedua
2002:123). Rogers (2003:24) menyatakan bahwa difusi terjadi di dalam suatu
sistem sosial. Struktur sosial dari sistem akan mempengaruhi difusi inovasi
dengan beberapa cara. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses
adopsi inovasi adalah proses komunikasi dan ketersediaan sumber-sumber
informasi. Oleas et al. (2010:43) menambahkan peran dari opinion leaders.
Proses Komunikasi
Seperti dinyatakan oleh Rogers (2003:17), bahwa komunikasi adalah suatu
proses dimana peserta (participants) menciptakan dan berbagi informasi satu
dengan yang lain dalam rangka untuk memperoleh pemahaman bersama. Dalam
proses pengambilan keputusan inovasi, terlihat bahwa informasi dari ”sumber
komunikasi” sangat diperlukan sejak proses ”pengenalan,” ”persuasi” dan
pengambilan ”keputusan.” Begitu juga ketika proses konfirmasi berlangsung.
Ross (1979:12) mendefinisikan komunikasi dengan banyak pendekatan,
yaitu (1) suatu proses saling berhubungan, mengendalikan satu dengan yang
lainnya dan saling memahami, (2) interaksi sosial yang menggunakan lambang
dan pesan, (3) pengetahuan tentang perilaku mengirimkan pesan kepada
penerima dengan maksud menyadarkan dan merubah perilaku penerima, (4)
kemampuan berbahasa dengan banyak lambang dan berhubungan dengan
perilaku dalam suatu sistem sosial, (5) fungsi sosial tentang perilaku, (6)
komunikasi terjadi kapan saja dimana seseorang menunjukkan pesan yang
berhubungan dengan perilaku dan (7) komunikasi manusia melibatkan segala
sesuatu yang mengandung arti. Ditambahkan kemudian, bahwa semua
komunikasi terdiri hanya 35% verbal dan sisanya 65% adalah bahasa nonverbal.
Dalam konteks nonverbal ini, peranan budaya sangat besar. Bahkan tiap-tiap
komunitas mungkin mempunyai sistem komunikasi nonverbal sendiri. Di sini
pentingnya untuk mengamati secara langsung proses komunikasi suatu
komunitas.
Saluran komunikasi (communication channel) adalah cara (the means)
dimana pesan-pesan diperoleh dari seseorang ke orang lainnya. Beberapa
contoh saluran komunikasi adalah media massa, seperti radio, televisi,
suratkabar dan lain-lain, yang memungkinkan satu sumber atau sedikit sumber
dapat mencapai banyak pendengar (Rogers 2003:18). Di lain pihak, saluran
antar pribadi (interpersonal channels), adalah lebih efektif dalam mempengaruhi
seseorang untuk menerima suatu gagasan baru, khususnya jika saluran antar
sosial-ekonomi, pendidikan dan pandangan yang sama. Saluran-antar-pribadi
melibatkan pertukaran melalui ”pertemuan langsung” antara dua individu atau
lebih. Dalam penyuluhan pertanian di Indonesia, hampir semua saluran
komunikasi tersebut di atas pernah digunakan.
Sistem Sosial dan Perubahan Sosial
Ada dua pendekatan dalam melihat suatu kelompok di masyarakat, yaitu
(1) dari sudut psikologi sosial yang sering disebut dengan istilah ”dinamika
kelompok” dan (2) dari sudut ilmu sosiologi, yang sering disebut sebagai
pendekatan ”sistem sosial.” Menurut Rogers (2003:23), sistem sosial adalah ”a
set of interrelated units that are engaged in joint problem-solving to accomplish a
common goal” (suatu susunan satuan yang saling terkait, bergabung dalam
pemecahan masalah untuk mencapai tujuan bersama). Anggota atau satuan dari
suatu sistem sosial bisa bersifat individu-individu, kelompok informal, organisasi
dan/atau subsistem sosial.
Menurut Loomis (1960:5) unsur-unsur pokok sistem sosial adalah (1) tujuan
(goal), (2) keyakinan (belief/knowledge), (3) sentimen/perasaan (sentiment/
feeling), (4) norma (norm), (5) sanksi (sanctions), (6) peranan/kedudukan
(status/roles), (7) kewenangan/kedudukan (power/authority), (8) jenjang sosial
(social rank), (9) fasilitas (facility) dan (10) tekanan dan ketegangan (stress and
strain). Lebih jauh dikatakan, bahwa secara teoritis, kelompok sebagai suatu
sistem sosial harus mempunyai kesepuluh unsur ini. Jika ada yang kurang atau
tidak ada, maka itu merupakan kelemahan kelompok tersebut, karena
masing-masing unsur tersebut adalah sebagai peubah yang mempunyai pengaruh pada
interaksi anggota dalam kelompok, juga akan berpengaruh pada perilaku individu
dan perilaku kelompok.
Dengan pendekatan proses, maka masing-masing unsur menjelaskan
proses (1) pencapaian sasaran dan menyertai aktivitas yang bersifat laten, yang
mengartikulasikan unsur tujuan (end, goal atau objective) dan mempunyai fungsi
pencapaian (achieving), (2) pemetaan cognitive dan validasi sebagai artikulasi
unsur keyakinan (belief/knowledge) yang mempunyai fungsi mengetahui
(knowing), (3) manajemen tegang dan komunikasi sentimen, yang
mengartikulasikan unsur sentimen/perasaan (sentiment) yang mempunyai fungsi
perasaan (feeling), (4) evaluasi, yang mengartikulasikan unsur norma (norm),
yang mempunyai fungsi penormaan, penstandaran dan pemolaan (norming,
sanksi (sanctions) yang mempunyai fungsi memberi sanksi (sanctioing), (6)
performans status-peran, yang mengartikulasikan unsur peranan/kedudukan
(status/roles), yang mempunyai fungsi pembagian fungsi (dividing of functions),
(7) pembuat keputusan dan inisiasi tindakan, yang mengartikulasikan unsur
kewenangan/kedudukan (power/authority), yang mempunyai fungsi pengendalian
(controlling), (8) evaluasi pelaku dan alokasi status-peran, yang
mengartikulasi-kan unsur jenjang sosial (social rank), yang mempunyai fungsi penetapan
tingkatan (ranking) dan (9) pemanfaatan fasilitas, yang mengartikulasikan unsur
fasilitas (facility), yang mempunyai fungsi fasilitasi (facilitating);
Rogers (2003:30-31), menyatakan bahwa setiap inovasi akan mempunyai
konsekuensi. Konsekuensi adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap
individu ataupun sistem sosial sebagai hasil dari penerimaan (adopsi) ataupun
penolakan (rejeksi) suatu inovasi. Menurutnya, setidaknya ada tiga klasifikasi
konsekusensi inovasi, yaitu (1) antara konsekuensi diinginkan dan tidak
diinginkan. Ini tergantung apakah suatu inovasi di dalam suatu sistem sosial,
berfungsi atau tidak, (2) antara konsekuensi langsung dan tidak langsung. Hal ini
tergantung apakah perubahan individu ataupun sistem sosial terjadi segera
setelah diresponsnya suatu inovasi (direct consequence), atau merupakan hasil
tidak langsung (second-order) dari konsekuensi langsung suatu inovasi dan (3)
antara konsekuensi dapat diantisipasi dan tidak dapat diantisipasi. Hal ini
tergantung apakah perubahan ini dikenali dan yang dimaksud oleh anggota dari
sistem sosial atau tidak.
Menurut van den Ban dan Hawkins (1999:140-141), sebagian besar studi
difusi inovasi menekankan pada perubahan teknis yang kecil dan khusus. Sedikit
saja perhatian diberikan terhadap perubahan yang besar dalam struktur sosial
atau cara hidup masyarakat. Dengan demikian perhatian lebih banyak ditujukan
pada inovasi bagian pinggir (periferal) daripada yang di pusat dari suatu sistem
sosial. Lebih jauh, dinyatakan, bahwa perubahan individu dan kelompok
merupakan pusat perhatian pada penelitian difusi inovasi. Perubahan
kelembagaan dan masyarakat jarang diteliti, padahal perubahan sosial yang
demikian sangat penting, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.
Perubahan sosial secara konseptual adalah sebagai suatu proses,
terencana ataupun tidak direncanakan secara kualitatif ataupun kuantitatif
perubahan di dalam fenomena sosial, yang dapat digambarkan dalam suatu
identitas, level, durasi, arah, magnitut dan tingkat kecepatan perubahan (Vago
1989:24). Menurut Rogers (2003:6) difusi adalah sejenis dengan perubahan
sosial, yang didefinisikan sebagai proses perubahan yang terjadi pada struktur
dan fungsi dalam suatu sistem sosial.
Menurut Vago (1989:10-14) beberapa faktor yang mempengaruhi
perubahan sosial, yaitu (1) Penduduk. Perubahan dalam ukuran (jumlah),
komposisi, distribusi penduduk akan mempengaruhi perubahan sosial, (2)
Konflik. Banyak perubahan sosial dihasilkan oleh terjadinya konflik antar
kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat muncul antar kelas sosial, penduduk
dari daerah yang berbeda, dan rasial serta kelompok-kelompok etnis, (3)
Determinasi ekonomi. Kepemilikan modal, akan menentukan organisasi dari
masyarakat bukan pemilik modal. Struktur kelas dan susunan kelembagaan, juga
nilai-nilai budaya, keyakinan, agama, dogma dan gagasan sistem yang lain,
adalah benar-benar merefleksikan dasar ekonomi masyarakat, (4) Inovasi.
Inovasi merujuk kepada suatu cara baru dalam melakukan sesuatu, (5) Difusi.
Diffusi adalah proses di mana suatu inovasi dan sifat-sifat budaya lain menyebar
dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya dan (6) The Legal System. Melalui
proses berkelanjutan, regulasi, deregulasi dan penegakan hukum secara selektif,
legal system adalah suatu instrumen dalam perubahan sosial.
Berkenaan dengan inovasi, Vago (1989:12-13) menyatakan bahwa ada
tiga tipe dasar inovasi yang sering menyebabkan perubahan sosial, yaitu (1)
teknologi baru, (2) budaya baru dan (3) bentuk baru dari struktur sosial. Dalam
konteks ini, IB merupakan inovasi teknologi. Pengaruh teknologi ini mempunyai
akibat yang besar terhadap kehidupan individu-individu dalam masyarakat,
terhadap nilai-nilai sosial, terhadap struktur dan fungsi dari kelembagaan sosial,
dan terhadap organisasi politik dalam masyarakat (Vago, 1989:87).
Latar belakang peternak, sistem sosial, proses komunikasi dan sifat suatu
inovasi di atas akan menentukan tingkat penerapan maupun kecepatan adopsi
suatu inovasi.
Tingkat Penerapan dan Kecepatan Adopsi Inovasi
Keputusan seseorang untuk menerima ataupun menolak suatu inovasi dan
berapa lama waktu yang dibutuhkan, menurut Lionberger dan Gwin (1982:5)
dipengaruhi oleh (1) sebagian dari faktor individu, (2) sebagian dari situasi
dimana dia berada dan (3) sifat dari inovasi tersebut. Faktor individu yang
(inherited characteristics) dan pengalaman belajar (learned experiences)
(Lionberger & Gwin 1982:8).
Beberapa faktor individu (personality variables) yang mempengaruhi adopsi
suatu inovasi (perubahan), menurut Rogers (2003:272-274), mencakup (1) rasa
empati, (2) sikap dogmatis, (3) kemampuan melakukan abstraksi, (4)
rasionalitas, (5) kecerdasan, (6) sikap terhadap perubahan, (7) sikap terhadap
ketidakpastian, (8) sikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, (9)
fatalisme dan (10) aspirasi. Faktor situasi di mana individu tersebut berada,
menurut Lionberger dan Gwin (1982:10-13) terdiri dari (1) family, (2) friendship
groups, (3) locality groups, (4) religious groups, (5) reference groups dan (6)
special interest groups. Hasil penelitian Ginting (1984: 84) tentang respons
peternak sapi perah terhadap IB di Kecamatan Pujon Malang menyimpulkan
bahwa persepsi peternak - yang mencerminkan tingkat adopsi inovasi IB- adalah
35,33% sangat setuju dan 43,33% setuju. Sedangkan hasil penelitian Amrawati
dan Nurlaelah (2008:92) yang menganalisis tingkat adopsi IB oleh peternak sapi
Bali di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
menyimpulkan tingkatan adopter sebagai berikut: inovator 10%, early adopter
20%, early majority 30%; late majority 23,33% dan laggard 16,67%.
Khusus untuk waktu yang dibutuhkan dimana suatu inovasi diadopsi oleh
sebagian anggota dari suatu sistem sosial, Rogers (2003:206-207) menyebutnya
sebagai rate of adoption. Tingkat kecepatan adopsi inovasi ini dipengaruhi oleh
(1) sifat-sifat yang melekat pada inovasi (relative advantage, compatibility,
complexity, trialability dan observability), (2) jenis keputusan inovasi (optional,
collective atau authority), (3) saluran komunikasi (misal: media massa,
interpersonal), (4) sistem sosial dan (5) intensitas upaya promosi oleh agen
perubahan (penyuluh). Sebagai contoh, Lionberger dan Gwin (1982:63)
menyatakan bahwa dibutuhkan waktu lima tahun bagi petani di Iowa untuk mau
menggunakan (mengadopsi) benih jagung hibrida, dan dibutuhkan waktu sekitar
12-14 tahun untuk semua petani menggunakan benih jagung hibrida tersebut.
Adapun hasil penelitian Ali-Olubandwa et al. (2010:26) tentang perbaikan
teknologi produksi jagung pada petani skala kecil di Kenya, menunjukkan bahwa
terendah 17,2% (Busia District) dan tertinggi 56,7% (Lugari District) responden
yang mengadopsi paket teknologi tersebut secara penuh (100%).
Menurut Nasution (2002:125), perbedaan kecepatan proses adopsi, antara
Persepsi
Persepsi adalah pemberian makna pada stimuli inderawi. Persepsi juga
mempengaruhi keberhasilan suatu komunikasi, sebab dalam prosesnya persepsi
mempengaruhi rangsangan (stimulus) pesan yang diterima dan makna yang
diberikan (DeVito 2000: 75). Menurut Tubb dan Moss (2005:34), sebagai
komunikator, kita bergantung pada persepsi dalam hampir semua aspek
kehidupan sehari-hari. Hal ini berati, bahwa dalam proses mengadopsi inovasi
IB, peternak juga dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang IB dan hal-hal lain
terkait dengan IB.
Menurut van den Ban dan Hawkins (1999:83-85), persepsi adalah proses
menerima informasi atau stimuli dari lingkungan dan mengubahnya ke dalam
kesadaran psikologis. Dijelaskan, bahwa ada beberapa prinsip umum persepsi,
yaitu (1) Relativitas, setiap persepsi bersifat relatif, walaupun suatu obyek tidak
dapat diperkirakan bagaimana yang tepat, tetapi dapat dikatakan bahwa yang
satu melebihi yang lainnya. (2) Selektivitas, persepsi sangat selektif. Panca indra
menerima stimuli dari sekelilingnya dengan melihat obyek, mendengar suara,
mencium bau dan sebagainya. Karena kapasitas memproses informasi terbatas,
maka tidak semua stimuli dapat ditangkap, tergantung pada faktor fisik dan
psikologis seseorang. (3) Organisasi. Setiap persepsi terorganisir. Seseorang
cenderung menyusun pengalamannya dalam bentuk yang memberi arti, dengan
mengubah yang berserakan dan menyajikannya dalam bentuk yang bermakna,
antara lain berupa gambar dan latar. Dalam sekejap panca indera melakukan
seleksi dan sosok yang menarik akan menciptakan pesan. (4) Arah. Melalui
pengamatan, seseorang dapat memilih dan mengatur serta menafsirkan pesan.
Lebih jauh van den Ban dan Hawkins (1999:90) menjelaskan, bahwa persepsi
seseorang bisa berlainan satu sama lain dalam situasi yang sama karena adanya
perbedaan kognitif. Setiap proses mental, individu bekerja menurut caranya
sendiri tergantung pada faktor-faktor kepribadian, seperti toleransi terhadap
ambiguitas, tingkat keterbukaan atau ketertutupan pikiran, sikap otoriter dan
sebagainya.
Dalam penelitian Ginting (1984:51) menyatakan, bahwa persepsi terhadap
IB adalah pemberian arti/makna yang diberikan berdasarkan proses pengamatan
ataupun pengalaman dalam diri peternak terhadap IB dalam pernyataan setuju
menyatakan setuju tentan