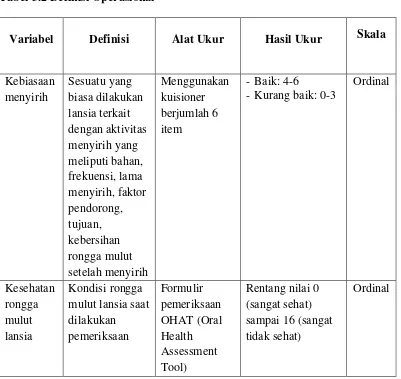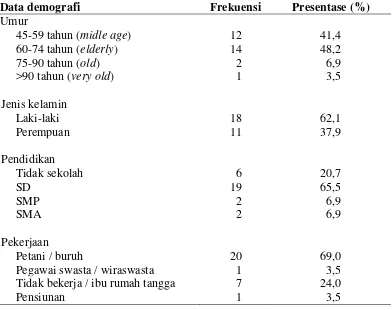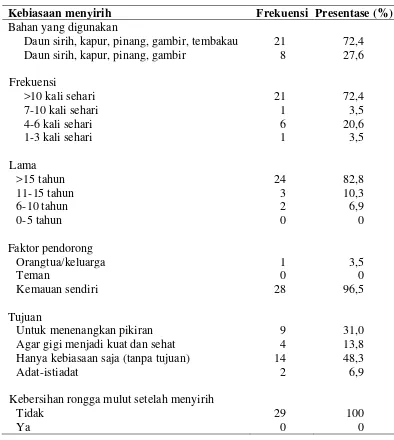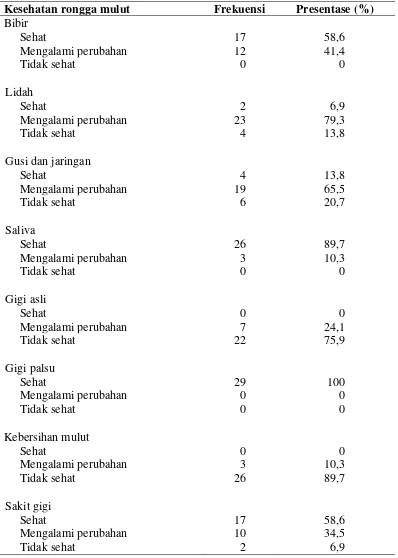KEBIASAAN MENYIRIH DAN KESEHATAN RONGGA
MULUT LANSIA DI DESA HILIBADALU
KABUPATEN NIAS
SKRIPSI
Oleh:
Elvis Sofyan Lombu 101101035
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Title : Betel Chewing Habit and Oral Health in Elderly in the Village of Hilibadalu Nias Regency
Name of Student : Elvis Sofyan Lombu
Student Number : 101101035
Program : Bachelor of Nursing
Year : 2014
Abstract
Betel chewing is part of tradition that completes the structure of culture and usually closely related to habits in the community in certain areas in Indonesia. This habit is a tradition made hereditary in the majority of the rural population which was originally closely related to local customs. But this habit can lead to health problems in the oral cavity. This research aims to find out how betel chewing betel and oral health by using a descriptive research design. The population in this research is the elderly who chew betel in village of Hilibadalu of Nias Regency by the number of samples 29 people. Research Instrument consists of questionnaire data demographics, habits of betel chewing and oral health assessment tool (OHAT) form. The research results concluded that betel chewing habit of elderly in village of Hilibadalu is poorly. The research results showed that the material used is betel leaf, areca nut Gambier and tobacco lime (72.4%). Chewing betel habits has been conducted when people are still under 15 years (82.8%) with frequency > 10 times a day (72.4 %). The driving factor of chewing betel is their own accord (96.6 %) where the elderly do it only as a custom course (48.3 %). Although they often do it, all elderly has less attention to their oral health. Based on the results of the study using OHAT, oral health status of the elderly who chew betel in the village of Hilibadalu ranges from 6.79 from 0 (very healthy) to 16 (very unhealthy). The research results showed that oral health of elderly in village of Hilibadalu is poorly. It is advisable to heath care officers to do health counseling about the health of oral cavity and habits that can interfere with the oral health.
Judul : Kebiasaan Menyirih dan Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias
Nama Mahasiswa : Elvis Sofyan Lombu
NIM : 101101035
Jurusan : Sarjana Keperawatan (S.Kep)
Tahun : 2014
Abstrak
Menyirih adalah bagian yang melengkapi struktur kebudayaan dan biasanya berkaitan erat dengan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat di daerah tertentu di Indonesia. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada sebagian besar penduduk pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan setempat. Namun, kebiasaan menyirih dapat menimbulkan masalah kesehatan pada rongga mulut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias dengan jumlah sampel 29 orang. Instrumen penelitian terdiri dari kuisioner data demografi, kebiasaan menyirih dan formulir pengkajian kesehatan rongga mulut lansia (OHAT). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebiasan menyirih lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Pada umumnya bahan yang digunakan adalah daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau (72,4%). Kebiasaan menyirih telah dilakukan >15 tahun (82,8%) dengan frekuensi >10 kali sehari (72,4%). Faktor pendorong utama menyirih adalah kemauan sendiri (96,6%) dimana lansia menyirih hanya sebagai kebiasaan saja (48,3%). Walaupun sering menyirih, semua lansia kurang memperhatikan kesehatan rongga mulut mereka. Berdasarkan hasil pengkajian menggunakan OHAT, nilai status kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu adalah 6,79 dari rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat tidak sehat). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Disarankan kepada petugas puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan terkait kesehatan rongga mulut dan kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan rongga mulut.
PRAKATA
Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebiasaan Menyirih dan
Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias”.
Pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu dengan selesainya skripsi, dengan penuh rasa
hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. dr. Dedi Ardinata, M.Kes selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas
Sumatera Utara Medan.
2. Erniyati, S.Kp, MNS selaku pembantu dekan satu Fakultas Keperawatan
Universitas Sumatera Utara Medan.
3. Evi Karota, S.Kp, MNS selaku pembantu dekan dua Fakultas Keperawatan
Universitas Sumatera Utara Medan.
4. Ikhsannudin Harahap, S.Kp, MNS selaku pembantu dekan tiga Fakultas
Keperawatan Universitas Sumatera Utara.
5. Ismayadi, S.Kep, Ns, M.Kes, CWCCA selaku dosen pembimbing yang
telah mendukung, membimbing dan memberi banyak masukan selama
menyelesaikan skripsi ini.
6. Rosina Tarigan, S.Kp, M.Kep, Sp.KMB, selaku dosen penguji I.
7. Lufthiani, S.Kep, Ns, M.Kes selaku dosen penguji II
8. Kedua orangtua yang tidak henti-hentinya memberi doa, dukungan dan
9. Teman-teman yang selalu memberi semangat dan bantuan untuk
mengerjakan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan,
baik dari segi materi maupun cara penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
perbaikan skripsi ini.
Medan, 11 Juli 2014
DAFTAR ISI
Halaman Judul ... i
Halaman Persetujuan Skripsi ... ii
Bab 6. Kesimpulan dan Saran ... 39
6.1 Kesimpulan ... 39
6.2 Saran ... 40
Daftar Pustaka ... 41
Lampiran
1. Informed Consent 2. Instrumen Penelitian 3. Hasil Analisa Data 4. Master Tabel
5. Jadwal Tentatif Penelitian 6. Taksasi Dana
7. Surat Uji Validitas
8. Lembar Persetujuan Komisi Etik 9. Surat Izin Reliabilitas
10.Surat Izin Penelitian
DAFTAR TABEL
Tabel 3.2 Definisi Operasional ... 21
Tabel 5.1 Distribusi responden berdasarkan data demografi ... 29
Tabel 5.2 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan menyirih ... 30
Tabel 5.3 Kebiasaan menyirih lansia ... 31
Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan hasil pengkajian menggunakan Oral Health Assessment Tool ... 32
DAFTAR SKEMA
Title : Betel Chewing Habit and Oral Health in Elderly in the Village of Hilibadalu Nias Regency
Name of Student : Elvis Sofyan Lombu
Student Number : 101101035
Program : Bachelor of Nursing
Year : 2014
Abstract
Betel chewing is part of tradition that completes the structure of culture and usually closely related to habits in the community in certain areas in Indonesia. This habit is a tradition made hereditary in the majority of the rural population which was originally closely related to local customs. But this habit can lead to health problems in the oral cavity. This research aims to find out how betel chewing betel and oral health by using a descriptive research design. The population in this research is the elderly who chew betel in village of Hilibadalu of Nias Regency by the number of samples 29 people. Research Instrument consists of questionnaire data demographics, habits of betel chewing and oral health assessment tool (OHAT) form. The research results concluded that betel chewing habit of elderly in village of Hilibadalu is poorly. The research results showed that the material used is betel leaf, areca nut Gambier and tobacco lime (72.4%). Chewing betel habits has been conducted when people are still under 15 years (82.8%) with frequency > 10 times a day (72.4 %). The driving factor of chewing betel is their own accord (96.6 %) where the elderly do it only as a custom course (48.3 %). Although they often do it, all elderly has less attention to their oral health. Based on the results of the study using OHAT, oral health status of the elderly who chew betel in the village of Hilibadalu ranges from 6.79 from 0 (very healthy) to 16 (very unhealthy). The research results showed that oral health of elderly in village of Hilibadalu is poorly. It is advisable to heath care officers to do health counseling about the health of oral cavity and habits that can interfere with the oral health.
Judul : Kebiasaan Menyirih dan Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias
Nama Mahasiswa : Elvis Sofyan Lombu
NIM : 101101035
Jurusan : Sarjana Keperawatan (S.Kep)
Tahun : 2014
Abstrak
Menyirih adalah bagian yang melengkapi struktur kebudayaan dan biasanya berkaitan erat dengan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat di daerah tertentu di Indonesia. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada sebagian besar penduduk pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan setempat. Namun, kebiasaan menyirih dapat menimbulkan masalah kesehatan pada rongga mulut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias dengan jumlah sampel 29 orang. Instrumen penelitian terdiri dari kuisioner data demografi, kebiasaan menyirih dan formulir pengkajian kesehatan rongga mulut lansia (OHAT). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebiasan menyirih lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Pada umumnya bahan yang digunakan adalah daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau (72,4%). Kebiasaan menyirih telah dilakukan >15 tahun (82,8%) dengan frekuensi >10 kali sehari (72,4%). Faktor pendorong utama menyirih adalah kemauan sendiri (96,6%) dimana lansia menyirih hanya sebagai kebiasaan saja (48,3%). Walaupun sering menyirih, semua lansia kurang memperhatikan kesehatan rongga mulut mereka. Berdasarkan hasil pengkajian menggunakan OHAT, nilai status kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu adalah 6,79 dari rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat tidak sehat). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Disarankan kepada petugas puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan terkait kesehatan rongga mulut dan kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan rongga mulut.
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Menyirih merupakan proses meramu campuran dari unsur-unsur yang
telah terpilih yang dibungkus dalam daun sirih kemudian dikunyah dalam waktu
beberapa menit. Menyirih merupakan suatu kebiasaan yang yang popular di Asia.
Menurut catatan sejarah, kebiasan menyirih telah dilakukan lebih dari 2000 tahun
lalu di China dan India (Hasibuan dkk., 2003). Kebiasaan ini sudah dilakukan
oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dan diperkirakan muncul sebelum
abad ke-4 Masehi (Hamzuri, 1997 dalam Susiarti, 2005).
Menyirih adalah bagian yang melengkapi struktur kebudayaan dan
biasanya berkaitan erat dengan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat di
daerah tertentu yang dilakukan oleh berbagai suku di Indonesia seperti Karo,
Batak, Simalungun, Aceh, Nias, Jawa, dan yang lain-lain (Ginting, 2011).
Kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada sebagian
besar penduduk di pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan
setempat. Adat kebiasaan ini dilakukan pada saat upacara kedaerahan atau pada
acara yang bersifat ritual keagamaan (Andriyani, 2005).
Kebiasaan menyirih juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk merawat
gigi. Diketahui bahwa daun sirih (Piper betle Linn), mengandung kandungan
minyak atsiri yang berfungsi sebagai zat antibakteri. Masyarakat Indonesia sudah
sejak lama mengenal daun sirih sebagai bahan untuk menyirih dengan keyakinan
mulut, menghilangkan bau mulut, menghentikan pendarahan gusi, dan sebagai
obat kumur. Daun sirih juga digunakan sebagai antimikroba terhadap
Streptococcus mutans yang merupakan bakteri yang paling sering mengakibatkan
kerusakan pada gigi (Astuti, 2007).
Namun, hasil penelitian Samura (2009) pada masyarakat suku Karo di
Desa Biru-biru Kab. Deli Serdang menunjukkan bahwa keadaan status kesehatan
periodontal masyarakat dengan kebiasaan menyirih masuk kategori parah
sebanyak 74 orang (80,4%) dan sangat parah sebanyak 18 orang (19,6%), berarti
seluruh responden mengalami masalah kesehatan periodontal akibat dari
kebiasaan menyirih.
Penelitian yang dilakukan di desa Gurukinayan, Payung, Sinaman, dan
Semangat di Kabupaten Karo, menunjukkan ada hubungan antara kebiasaan
menyirih dengan adanya lesi-lesi di mukosa mulut. Hasil penelitian melaporkan
bahwa lesi mukosa penyirih 47,9%, preleukoplakia 14,3% , leukoplakia tipe
homogen 7,1%, oral submukusfibrosis 8,2% (Ginting, 2011).
Dari hasil pengamatan peneliti, kebanyakan lansia di Desa Hilibadalu
Kabupaten Nias memiliki kebiasaan menyirih dimana kaum pria lebih banyak dari
kaum wanita. Kebiasaan menyirih ini menjadi suatu hal yang akan sering terlihat
terutama ketika lansia sedang bersantai atau berada di warung/kedai minuman.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana
kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut lansia di Desa Hilibadalu
Kabupaten Nias.
1.2 PERTANYAAN PENELITIAN
Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:
1.2.1 Bagaimana kebiasaan menyirih (bahan yang digunakan, frekuensi, lama
menyirih, faktor pendorong, tujuan dan kebersihan rongga mulut) lansia di
Desa Hilibadalu Kabupaten Nias?
1.2.2 Bagaimana kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di Desa
Hilibadalu Kabupaten Nias?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1.3.1 Mengetahui bagaimana kebiasaan menyirih (bahan yang digunakan,
frekuensi, lama menyirih, faktor pendorong, tujuan dan kebersihan rongga
mulut) lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.
1.3.2 Mengetahui bagaimana kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di
Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan
praktik keperawatan, pendidikan keperawatan, dan bagi penelitian keperawatan
1.4.1 Bagi praktik keperawatan
Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sumber informasi bagi
perawat untuk mengetahui kebiasaan masyarakat yang berhubungan
dengan kesehatan dan kondisi rongga mulut lansia yang menyirih. Perawat
diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan dengan
memperhatikan kebiasaan menyirih lansia.
1.4.2 Bagi pendidikan keperawatan
Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa
keperawatan tentang kebiasaan menyirih serta kondisi kesehatan rongga
mulut lansia yang menyirih.
1.4.3 Bagi penelitian keperawatan
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 MENYIRIH
2.1.1 Pengertian Menyirih
Menyirih merupakan salah satu bentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang ada
di masyarakat yang secara turun temurun dilakukan. Sirih adalah jenis tumbuhan
yang mirip dengan tanaman lada, dengan nama ilmiahnya adalah Piper Betle. L,
dan ada beberapa daerah di Indonesia memberikan nama lain terhadap sirih yaitu
Suruh, Sedah (Jawa), Seureuh (Sunda), Ranup (Aceh), Belo (Batak Karo),
Cambai (Lampung), Uwit (Dayak), dan Afo (Nias) (Samura, 2009).
Menyirih merupakan proses meramu campuran dari unsur-unsur yang
telah terpilih yang dibungkus dalam daun sirih kemudian dikunyah dalam waktu
beberapa menit. Menyirih dilakukan dengan cara yang berbeda dari satu negara
dengan negara lainnya dan satu daerah dengan daerah lainnya dalam satu negara.
Meskipun begitu komposisi terbesar relatif konsisten, yang terdiri dari biji buah
pinang, daun sirih, kapur dan gambir (Hasibuan, dkk., 2003).
Menyirih merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh berbagai suku di
Indonesia. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada
sebagian besar penduduk di pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan adat
kebiasaan masyarakat setempat. Pada mulanya menyirih digunakan sebagai
suguhan kehormatan untuk orang-orang/tamu-tamu yang dihormati pada upacara
pertemuan atau pesta pernikahan. Dalam perkembangannya menyirih menjadi
melakukan setiap hari sementara orang lain mungkin makan sirih sesekali.
Frekuensi menyirih mungkin berkaitan dengan beberapa faktor, seperti: pekerjaan
dan pertimbangan sosial ekonomi (Dentika, 2004 dalam Samura, 2009)
Para pengunyah sirih memiliki alasan dan sebab mengapa kebiasaan
tersebut dilakukan secara terus menerus. Dilaporkan bahwa mengunyah sirih
memiliki beberapa pengaruh yang menjadi daya tarik pada para penggunanya
seperti efek stimulant atau efek euphoria, efek untuk menstimulasi air ludah, obat
untuk saluran pernapasan, menghilangkan rasa lapar serta kemungkinan memiliki
efek untuk menguatkan gigi serta gusi dan sebagai penyegar nafas. Kepercayaan
bahwa mengunyah sirih dapat melawan penyakit mulut kemungkinan telah
benar-benar mendarah daging diantara para penggunanya (Prayitno, 2003 dalam
Samura, 2009).
2.1.2 Bahan yang digunakan untuk Menyirih
Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk menyirih adalah daun sirih,
gambir, kapur sirih dan buah pinang
a. Daun sirih
Sirih termasuk jenis tumbuhan merambat dan bersandar pada batang
pohon lain. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung dengan ukuran panjang
antara 8-12 cm, lebar antara 10-15 cm dan tangkai agak panjang. Daun sirih
biasanya digunakan sebagai pembungkus untuk menyirih. Dulu, daun sirih
digunakan juga sebagai obat kumur bagi yang sakit gigi, gargarisma bagi orang
(Sundari,1992). Selain itu, dapat digunakan sebagai obat sariawan, abses rongga
mulut, luka bekas cabut gigi dan penghilang bau mulut (Syukur dan Hernani,
1999 dalam Hermawan, 2007).
Menurut Supartinah (1985) dalam Astuti (2007), komponen yang terurai
dari daun sirih adalah eugenol (26,8%-42,5%), eugenol metir eter (8,2%-15,85%),
kariofilen (6,2%-11,9%), kavikol (5,1%-8,2%) dan antifungi karvakol (4,8%).
Daun sirih bersifat bakteriostatik terhadap S. mutans, yang merupakan salah satu
bakteri penyebab karies dalam mulut. Efek bakteriostatik dari daun sirih
disebabkan oleh komponen yang terurai yaitu kavikol yang memiliki efek lima
kali lebih besar dari fenol (Astuti, 2007).
Daun sirih mengandung phenolic yang menstimulasi katekolamin,
sehingga mempengaruhi fungsi simpatik dan parasimpatik. Daun sirih juga
memiliki manfaat sebagai bahan obat, antara lain sebagai obat batuk,
menghilangkan bau badan, keputihan dan sebagainya. Bahkan, rebusan daun sirih
juga sangat bermanfaat untuk obat sariawan, pelancar dahak, pencuci luka dan
obat gatal-gatal (Sembiring, 2007).
b. Gambir
Gambir merupakan tanaman yang tumbuh liar di hutan dan di
tempat-tempat lain yang bertanah agak miring dan cukup mendapatkan sinar matahari.
Gambir yang kita kenal biasanya dalam bentuk ekstrak kering yang diambil dari
daun dan ranting. Tanaman ini mengandung zat lemak yaitu catechin yang
bersifat anti-oksidan (Andriyani, 2005). Pada masyarakat tradisional di berbagai
menambah rasa, gambir juga memberi manfaat lain, yaitu untuk mencegah
berbagai penyakit di daerah kerongkongan.
Gambir juga digunakan untuk mencuci luka bakar dan luka pada penyakit
kudis. Selain itu digunakan untuk menghentikan diare, tetapi penggunaan lebih
dari 1 ibu jari bukan sekedar menghentikan diare tetapi akan menimbulkan
kesulitan buang air besar selama beberapa hari. Gambir dapat mengakibatkan
atrisi dan abrasi pada gigi karena adanya kandungan yang bersifat abrasif yaitu
catechin (Katno, 2008 dalam Sinuhaji, 2010)
c. Kapur sirih
Kapur atau curam (kapur mati) berwarna putih kilat seperti krim yang
dihasilkan dari cengkerang siput laut yang telah dibakar. Hasil dari debu
cengkerang tersebut dicampur dengan air untuk memudahkan pada saat kapur
disapukan keatas daun sirih (Andriyani, 2005).
Penggunaan kapur sirih dapat menyebabkan penyakit periodontal.
Penyebab terbentuknya penyakit periodontal adalah karang gigi akibat stagnasi
saliva penguyah sirih karana adanya kapur. Gabugan kapur dan pinang
mengakibatkan respon primer terhadap formasi oksigen reaktif dan mungkin
mengakibatkan kerusakan oksidatif pada DNA di bukal mukosa penyirih (Chiba,
2001 dalam Sinuhaji, 2010)
d. Buah pinang
Pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan
di dunia Barat dikenal sebagai betel nut. Biji ini dikenal sebagai salah satu
campuran orang makan sirih, selain gambir dan kapur (Andriyani, 2005).
Secara tradisonal, biji pinang (Areca catecu) sudah digunakan secara luas
sejak ratusan tahun lalu. Penggunaan paling populer adalah kegiatan menyirih
dengan bahan campuran biji pinang, daun sirih, dan kapur. Ada juga yang
mencampurnya dengan tembakau. Sebelum dikonsumsi, pinang diproses terlebih
dahulu dengan dibakar, dijemur, dan dipanaskan. Pinang diduga dapat
menghasilkan rasa senang, rasa lebih baik, sensasi hangat di tubuh, keringat,
menembah saliva, menambah stamina kerja, menahan rasa lapar. Selain tersebut
di atas, pinang juga mempengaruhi sistem saraf pusat dan otonom (Gandhi, 2001
dalam Sinuhaji, 2010).
Komponen penting dari pinang adalah tannin (11-26%) dan alkoloid
(0,15-0,67%). Sedangkan komposisi kecilnya adalah arakaidin, guakin guvokalin, dan
arekolidin (kandungan alkoloid terbesar), yang dapat digunakan sebagai obat
cacing. Namun penggunaan pinang berlebihan justru membahayakan kesehatan.
Karena arekolin merupakan senyawa alkoloid aktif yang mempengaruhi syaraf
parasimpatik dengan merangsang reseptor muskarinik dan nikotinik sehingga
harus digunakan dalam jumlah kecil. Sebanyak 2 mg arekolin murni sudah dapat
menimbulkan efek stimulan yang kuat, sehingga dosis yang dianjurkan tidak
melebihi 5 mg untuk sekali pakai. Penggunaan serbuk biji sebaiknya tidak lebih
dari 4 kg untuk sekali pakai. Jika digunakan pada dosis 8 g, akan segera berakibat
fatal karena arekolin bersifat sebagai sitoksik dan sastatik kuat. Secara in vitro
(milimol) mengakibatkan penurunan daya hidup sel serta penurunan kecepatan
sintesis DNA dan protein. Arekolin juga menyebabkan terjadinya kegagalan
glutationa, yaitu sejenis enzim yang berfungsi melindungi sel dari efek merugikan
(Agusta, 2001 dalam Sinuhaji, 2010).
Biji pinang juga mengandung senyawa golongan fenolik dalam jumlah
relatif tinggi. Selama proses pengunyahan biji pinang di mulut, oksigen reaktif
(radikal bebas) akan terbentuk senyawa fenolik itu. Adanya kapur sirih yang
menciptakan kondisi pH alkali akan lebih merangsang pembentukan oksigen
reaktif itu. Oksigen reaktif inilah salah satu penyebab terjadinya kerusakan DNA
atau genetik sel epiteltial dalam mulut (Chiba, 2001 dalam Sinuhaji, 2010).
Kandungan berbahaya lain pada biji pinang adalah senyawa turunan
nitroso, yaitu N-nitrosoguvakolina, N-nitrosoguvasina, 3-(N-nitrosometilamino)
propinaldehidida dan 3-(N-nitrosometillamino) propianitrile. Keempat turunan
nitroso ini merupakan senyawa bersifat sitotosik (meracuni sel) dan geneositoksik
(meracuni gen) pada sel ephithialbuccal, dan dapat juka menyebabkan terjadinya
tumor pada pankreas, paru-paru dan hati. Pada hewan percobaan, senyawa nitroso
biji pinang juga terbukti dapat menyebabkan efek diabetogenik yaitu pemunculan
diabetes secara spontan (Agusta, 2001 dalam Sinuhaji, 2010).
Daun sirih, gambir, kapur sirih dan buah pinang merupakan bahan-bahan
yang lebih sering digunakan. Selain bahan-bahan tersebut, terkadang ditambahkan
B1) dan tembakau (Nicotiana Tabaccum L) yang hanya digunakan sebagai sugi
atau susur dan tidak dimasukkan dalam ramuan yang dikunyah (Andriyani, 2005).
2.1.3 Frekuensi dan Lama Menyirih
Menyirih berkaitan dengan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat
tertentu. Kuantitas, frekuensi dan usia saat mulai menyirih bergantung oleh tradisi
setempat. Beberapa pengunyah sirih melakukannya setiap hari, sementara orang
lain mungkin menguyah sirih sesekali. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lim
(2007) di Kecamatan Pancur Batu dijumpai kebiasaan menyirih sebagian besar
dilakukan setiap hari (68,38%) dan dilakukan sesekali saja (37,34%). Frekuensi
menyirih lima kali dalam sehari adalah sebesar 81,25%.
2.1.4 Faktor Pendorong, Tujuan Menyirih dan Kebersihan Rongga Mulut
Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2007) di Kecamatan Berastagi
dijumpai kebiasaan menyirih diperoleh dari orangtua, keluarga maupun teman
sejawat. Sirih digunakan pada acara pertunangan dan pernikahan sebagai lambang
kehormatan dan komunikasi. Suku Karo juga menganggap bahwa menyirih
mempuyai dampak positif yang lebih banyak dari pada dampak negatif. Dampak
negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan kapur, gambir dan tembakau
hanyalah berupa stein dan iritasi mukosa mulut.
Tujuan mengunyah sirih paling banyak adalah untuk menenangkan
pikiran, mengurangi rasa sakit gigi, agar gigi kuat dan sehat dan sekedar
menggosok gigi setelah menyirih, rongga mulut kemudian dibersihkan dengan
cara menggosok gigi dan kumur-kumur dengan air (Lim, 2007).
2.1.5 Efek Menyirih Terhadap Kesehatan Rongga Mulut
Kebiasaan menyirih menyebabkan perubahan atau pengaruh pada
kesehatan rongga mulut. Perubahan terjadi pada gigi, gingiva dan mukosa mulut.
a. Efek menyirih terhadap gigi
Efek positif dari kebiasaan menyirih adalah terhambatnya proses
pembentukan plak atau karies. Daya antibakteri daun sirih terutama minyak atsiri
disebabkan oleh senyawa fenol dan senyawa chavicol yang memiliki daya
bakterisida. Sementara efek negatifnya adalah terbentuknya stein atau perubahan
warna menjadi merah yang terjadi karena oksidasi polifenol dari buah pinang
dalam lingkungan alkalis. Selain itu, gigi juga mengalami atrisi dan abrasi yang
kemungkinan besar disebabkan oleh gambir dan kapur (Andriyani, 2005).
b. Efek menyirih terhadap gingiva
Gingiva juga mengalami perubahan warna atau terbentuknya stein yang
diakibatkan oleh penggunaan yang lama dan tetap. Kebiasaan menyirih akan
menimbulkan masalah periodontal. Freud dkk (1964) menyatakan bahwa gigi
menjadi coklat, terjadi penimbunan kapur pada gigi, leher gigi terpisah dari gusi
dan gigi dapat tanggal akibat menyirih (Samura, 2009). Penyakit periodontal
terjadi karena adanya karang gigi yang terdapat pada bagian subgingiva. Karang
gigi terbentuk karena stagnasi saliva dan adanya kapur Ca(OH)2 di dalam saliva
c. Efek menyirih terhadap mukosa mulut
Menyirih menyebabkan terjadinya lesi-lesi di mukosa mulut. Faktor yang
mendukung timbulnya kelainan pada mukosa mulut antara lain zat-zat dalam
bahan ramuan sirih, iritasi yang terus-menerus dari bahan ramuan sirih pada
selaput lendir rongga mulut serta kemungkinan tingkat kebersihan rongga mulut.
Menyirih juga menyebabkan oral higiene yang buruk akibat lapisan kotor yang
didapat dari menyirih (Andriyani, 2005). Selain itu, mukosa mulut mengalami
kekeringan, adanya atropi papila di lidah serta lobul pada seluruh maupun
sebagian dari dorsum lidah (Hasibuan, 2003).
2.2 LANSIA
2.2.1 Definisi Lansia
Lanjut usia (lansia) dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada
daur kehidupan manusia (Keliat, 1999 dalam Maryam, 2008). Menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menyatakan
bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
Sementara itu WHO menyatakan bahwa lanjut usia mulai dari usia pertengahan
(45-59 tahun) (Nugroho, 2008).
2.2.2 Batasan Lansia
Menurut WHO, lansia digolongkan menjadi empat tahap berdasarkan usia,
(elderly) antara 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua (old) antara 75 sampai 90
tahun dan usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun.
2.2.3 Teori Penuaan
Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam
kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak
hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan
kehidupan. Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara
perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti diri dan
mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan
terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita
(Darmojo, 1994 dalam Nugroho, 2008)
Teori Biologis
Teori biologi mencoba untuk menjelaskan proses fisik penuaan, termasuk
perubahan fungsi dan struktur, pengembangan, panjang usia dan kematian.
Perubahan-perubahan dalam tubuh termasuk perubahan molekular dan seluler
dalam sistem organ utama dan kemampuan tubuh untuk berfungsi secara adekuat
dan melawan penyakit. Teori biologis juga mencoba untuk menjelaskan mengapa
orang mengalami penuaan dengan cara yang berbeda dari waktu ke waktu dan
faktor apa yang mempengaruhi umur panjang, perlawanan terhadap organisme
dan kematian atau perubahan seluler. Teori biologi mencakup teori genetika, teori
wear and tear (dipakai dan rusak), teori lingkungan, teori imunitas dan teori
Teori Psikososial
Teori psikososial memusatkan perhatian pada perubahan sikap dan
perilaku yang menyertai peningkatan usia, sebagai lawan dari implikasi biologi
pada kerusakan anatomis. Teori psikososial mencakup teori kepribadian, teori
tugas perkembangan, teori disengagement (pemutusan hubungan), teori aktivitas,
teori kontinuitas dan teori ketidakseimbangan sistem (Stanley, 2006)
2.3 Status Kesehatan Rongga Mulut Lansia
Lansia mengalami proses penurunan fungsi alamiah yang tidak dapat
dihindari oleh setiap manusia, dimana terjadi perubahan jaringan tubuh yang
sangat kompleks. Proses ini juga mempengaruhi keadaan rongga mulut pada
lansia (Hasibuan, 1998). Pada lansia biasanya terjadi penurunan higiene mulut,
berkurangnya jumlah gigi dan penurunan sensitivitas mukosa rongga mulut
terhadap iritasi. Selain itu juga terjadi kelemahan pada jaringan penyangga gigi
sehingga kemampuan mengunyah berkurang. Infeksi serta keganasan sering
terjadi dalam rongga mulut sehubungan dengan proses penuaan. Status kesehatan
gigi dan mulut pada lansia berbeda dengan orang muda. Pada lansia terjadi
perubahan-perubahan dalam rongga mulutnya yang mencakup perubahan pada
jaringan keras (gigi, tulang dan sendi rahang), jaringan lunak (mukosa mulut,
lidah, kelenjar saliva dan otot-otot pengunyahan) dan jaringan periodontal
2.3.1 Gigi
Pada lansia gigi berubah menjadi lebih rapuh dan lebih kering serta adanya
abrasi. Warna gigi kelihatan lebih tua dengan migrasi gigi kearah apikal. Dalam
pulpa terjadi peningkatan jaringan kolagen, sel adontoblast berkurang, terbentuk
rangka jaringan ikat dan sel pulpa menjadi berkurang. Disamping itu terbentuknya
sekunder dentin dan pengapuran pada saluran akar yang mempersempit ruang
saluran akar. Foramen apikal menjadi sangat kecil yang disebabkan oleh
peningkatan sel semen. Karies yang sering terjadi pada lansia adalah karies
sekunder dan karies pada akar (Winasa, 1995). Selain itu, terjadi kehilangan
substansi gigi akibat atrisi yang disebabkan oleh karena pemakaian gigi
terus-menerus. Hal ini tergantung konsistensi makanan dan kekerasan gigi (Carranza,
1986 dalam Hasibuan, 1998)
2.3.2 Tulang, Sendi Rahang dan Otot-Otot Wajah
Ditemukan adanya atrofi senilis tulang alveolar maxilla dan mandibula.
Pada beberapa kasus, tulang rahang berada di bawah alveolar berubah menjadi
lebih padat. Pada keadaan yang lain dapat dijumpai pula adanya osteoporosis
senilis secara bersamaan yang terlihat pada bagian tulang lainnya (Winasa, 1995).
Sendi rahang dapat mengalami berbagai perubahan seseuai dengan bertambahnya
usia. Pada usia lanjut dijumpai adanya pengerasan dan berkurangnya elastisitas
ligamen kapsul dan diskus interartikularis. Zona artikulasi berubah menjadi
bertambahnya fibrous. (Kaplan, 1997 dalam Winasa, 1995). Otot wajah yang
tonus otot dan kadang dijumpai fibrosis otot. Akibatnya fungsi mengunyah dan
menelan menjadi berkurang (Lynch, 1984 dalam Hasibuan, 1998).
2.3.3 Mukosa Mulut
Mukosa mulut manusia dilapisi oleh lapisan sel epitel yang berfungsi
sebagai barrier terhadap pengaruh dari dalam dan luar mulut. Pada lansia, lapisan
tersebut mengalami penipisan, berkurangnya keratinasi, berkurangnya supali
darah dan serabut kolagen yang terdapat pada lamina propia mengalami
penebalan. Akibatnya, mukosa mulut menjadi lebih pucat, tipis dan kering, proses
penyembuhan menjadi lebih lambat, mukosa mulut lebih mudah iritasi (Pedersen
dan Loe, 1986 dalam Winasa, 1995).
Selain itu, perubahan yang sering dijumpai pada mukosa mulut adalah
atrofi dengan warna yang pucat dan jaringan yang kering. Populasi sel pada
lamina propia jumlahnya mengalami penurunan, terutama sel fibrolas menjadi
menyusut dengan inti yang memadat dan memanjang. Semua perubahan tersebut
merupakan proses degenerasi yang menyebabkan menurunnya resistensi mukosa.
Mukosa menjadi mudah terluka oleh karena makanan yang keras dan diperberat
karena mulut kering akibat menurunnya produksi saliva (Winasa, 1995).
2.3.4 Lidah
Sering dijumpai bentuk lidah yang melebar karena tidak adanya tahanan
oleh lengkung geligi. Lidah mengalami proses kehilangan tonus otot dan
terjadi penurunan di dalam sensitivitas perasa terhadap rasa manis, asam, pahit
dan asin. Berkurangnya jumlah putik pengecap disertai menurunnya produksi
saliva dapat mengakibatkan menurunnya nafsu makan pada lansia (Winasa,
1995).
2.3.5 Kelenjar Saliva
Perubahan morfologi kelenjar saliva pada lansia berupa meningkatnya
infiltrasi kelenjar parenkim oleh jaringan lemak dan jaringan penyambung.
Akumulasi granula autophagik, didapatinya sel oncosit dan perubahan sel-sel
yang jinak. Akibatnya terlihat kelenjar saliva minor yang terdapat di rongga mulut
dengan beberapa acini yang masih berfungsi. Pada usia 45 tahun keatas ditemukan
pula adanya infiltrasi sel limfosit yang tersebar pada lebih dari 70% kelenjar.
Penurunan fungsi pada kelenjar saliva ini menimbulkan mulut kering yang
bersifat absolut atau relatif (Winasa, 1995).
2.3.6 Otot-otot Pengunyahan
Seperti halnya yang terjadi pada otot-otot skeletal, otot di daerah orofasial
mengalami proses atrofi, menurunnya tonus dan kadang-kadang dijumpai fibrosis
otot. Kekuatan gigit otot pengunyahan menurun dari 300 lb per inchi kuadrat
2.3.7 Jaringan Periodontal
Penyakit periodontal sebagian besar bersifat inflamatif dengan penyebab
utamanya plak dan bakteri didukung oleh faktor lokal dan faktor sistemik.
Kadang-kadang sulit membedakan kerusakan fisiologik dengan kerusakan
patologik suatu jaringan pada usia lanjut. Tanda-tanda klinis yang berhubungan
dengan dengan jaringan periodontal pada usia lanjut adalah atrisi, resesi, migrasi,
BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL
3.1 KERANGKA PENELITIAN
Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan menyirih
dan kesehatan rongga mulut lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konsep penelitian dapat
dilihat pada skema di bawah ini:
Skema 3.1 Kerangka Penelitian Kebiasaan Menyirih dan Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias
Kebiasaan menyirih - Bahan yang digunakan - Frekuensi menyirih - Lama menyirih - Faktor pendorong - Tujuan menyirih
- Kebersihan rongga mulut setelah menyirih
Lansia yang menyirih
Kesehatan rongga mulut
3.2 DEFINISI OPERASIONAL
Tabel 3.2 Definisi Operasional
Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala
BAB 4
METODOLOGI PENELITIAN
4.1 DESAIN PENELITIAN
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif yang
bertujuan untuk menggambarkan kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut
lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.
4.2 POPULASI DAN SAMPEL
4.2.1 Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia yang memiliki kebiasaan
menyirih di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias berjumlah 29 orang. Jumlah ini
diambil dari data lansia yang menyirih bulan Oktober 2013 di Desa Hilibadalu
Kabupaten Nias.
4.2.2 Sampel
Pada penelitian ini sampel dipilih dengan metode total sampling, dimana
seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 29 orang.
4.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias pada bulan
Februari 2014 sampai Maret 2014 dengan pertimbangan Desa Hilibadalu
memiliki banyak lansia dengan kebiasaan menyirih dan belum pernah dilakukan
4.4 PERTIMBANGAN ETIK
Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan surat permohonan institusi
Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara dan Komisi Etik Penelitian
Kesehatan Fakultas Keperawatan USU untuk mendapatkan izin persetujuan
penelitian. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti
memulai penelitian dengan mempertimbangkan etik, yaitu : Informed consent atau
lembar persetujuan, anonimity, dan confidentialty.
Lembar persetujuan diserahkan kepada subjek yang akan diteliti. Peneliti
menjelaskan maksud dan tujuan serta penelitian yang dilakukan dan manfaat
penelitian. Responden yang bersedia diminta untuk menandatangani lembar
persetujuan tersebut. Peneliti tidak memaksa calon responden yang menolak dan
tetap menghormati hak-haknya.
Untuk menjaga kerahasian responden, peneliti tidak mencantumkan
namanya pada lembar pengumpulan data, tetapi cukup dengan memberi nomor
kode pada masing-masing lembar tersebut. Kerahasian informasi responden
dijamin oleh peneliti, hanya sekelompok data tertentu saja yang disajikan atau
dilaporkan sebagai hasil penelitian.
4.5 INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan
lembar observasi. Kuisioner terdiri dari 2 bagian yaitu kuisioner data demografi
dan kuisioner kebiasaan menyirih. Kuisioner data demografi meliputi usia, jenis
dari 6 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan mewakili sub variabel.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Pertanyaan nomor 1
bernilai 0 jika alternatif jawaban yang dipilih adalah “daun sirih, kapur, pinang ,
gambir, tembakau” dan bernilai 1 jika alternatif jawaban yang dipilih “daun sirih,
kapur, pinang, gambir” atau “alternatif lain (disebutkan)”. Pertanyaan nomor 2
bernilai 0 jika alternatif jawaban yang dipilih “7-10 kali sehari” atau “>10 kali
sehari” dan bernilai 1 jika alternatif jawaban yang dipilih “1-3 kali sehari” atau
“4-6 kali sehari”. Pertanyaan nomor 3 bernilai 0 jika alternatif jawaban yang
dipilih “11-15 tahun” atau “>15 tahun” dan bernilai 1 jika alternatif jawaban yang
dipilih “0-5 tahun” atau “6-10 tahun”. Pertanyaan nomor 4 bernilai 0 jika
alternatif jawaban yang dipilih “orang tua/keluarga” atau “teman” dan bernilai 1
jika alternatif jawaban yang dipilih “kemauan sendiri” atau “alternatif lain
(disebutkan). Pertanyaan nomor 5 bernilai 0 jika alternatif jawaban yang dipilih
“untuk menenangkan pikiran” atau “agar gigi menjadi kuat dan sehat” dan diberi
nilai 1 jika alternatif jawaban yang dipilih “hanya kebiasaan saja (tanpa tujuan)”
atau “adat-istiadat” atau “alternatif lain (disebutkan). Pertanyaan nomor 6 bernilai
0 jika alternatif jawaban yang dipilih “tidak” dan bernilai 1 jika alternatif jawaban
yang dipilih “ya”.
Untuk menentukan panjang kelas dipakai rumus:
P = rentang/banyak kelas
Dimana P adalah panjang kelas dengan rentang nilai tertinggi dikurang
dengan nilai terendah dan dibagi banyak kelas. Nilai tertinggi adalah 6 dan nilai
penilaian total skor adalah skor 0-3 kebiasaan kurang baik dan skor 4-6 adalah
kebiasaan baik.
Penilaian terhadap kesehatan rongga mulut dilakukan dengan pemeriksaan
(observasi) langsung terhadap responden. Pengukurannya menggunakan
instrumen yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu Oral Health Assessment
Tool (OHAT). Instrumen ini terdiri dari 8 item yang menilai status kesehatan dan
fungsi rongga mulut (bibir, lidah, gusi dan jaringan sekitarnya, saliva, gigi asli,
gigi palsu, kebersihan mulut dan sakit gigi). Penilaian dilakukan dengan
menggunakan skala ordinal 0-2, dengan nilai 0 mengindikasikan keadaan normal
(sehat), nilai 1 mengindikasikan adanya perubahan dari keadaan normal dan nilai
2 mengindikasikan keadaan tidak sehat. Skor akhir adalah jumlah skor dari 8 item
dengan rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat tidak sehat). Alat-alat
yang dibutuhkan dalam pemeriksaan adalah : sarung tangan, kain kasa, pen light
(sumber cahaya) dan tongue spatel. Pemeriksaan memerlukan waktu sekitar 10-20
menit.
4.6 UJI VALIDITAS DAN RELIABILTAS
Instrumen penelitian tentang kebiasaan menyirih dibuat oleh peneliti
sehingga perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas untuk mengetahui seberapa
besar derajat kemampuan alat ukur dalam mengukur secara konsisten sasaran
yang akan diukur.
Uji validitas pada penelitian ini adalah uji validitas isi yang dilakukan oleh
Departemen Keperawatan Medikal Bedah Dasar Fakultas Keperawatan USU.
Berdasarkan uji validitas isi tersebut, pertanyaan dan pilihan jawaban dalam
kuesioner disusun kembali dengan bahasa yang lebih efektif dan dengan item-item
pernyataan yang mengukur sasaran yang ingin diukur sesuai dengan tinjauan
pustaka dan kerangka konsep.
Uji reliabilitas instrumen adalah suatu uji yang dilakukan untuk
mengetahui konsistensi dari instrumen sehingga dapat digunakan untuk penelitian
selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama (Siswanto dkk, 2013). Uji reliabilitas
dalam penelitian ini menggunakan uji rumus Cronbach Alpha. Peneliti melakukan
uji reliabilitas di Desa Tuhembuasi Kabupaten Nias kepada 10 responden. Hasil
uji reliabilitas instrumen adalah 0,724.
Instrumen penelitian tentang kesehatan rongga mulut adalah instrumen
yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu Oral Health Assessment Tool.
Instumen ini telah diuji oleh para ahli dengan hasil reliabilitas instrumen
menggunakan derajat kesesuaian Kappa dalam rentang 0,61-0,80 dan nilai
korelasi Pearson adalah 0,74. Peneliti telah mendapatkan izin penggunaan dari
Halton Region Health Department.
4.7 PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data dimulai setelah mendapat izin penelitian dari institusi
pendidikan serta Komisi Etik Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara
dan Pemerintah Desa Hilibadalu. Peneliti langsung mendatangi tiap responden
penelitian serta meminta kesediaan responden dengan menandatangani lembar
persetujuan menjadi responden. Kemudian peneliti melakukan pengambilan data
kepada responden.
Dalam mengisi kuisioner kebiasaan menyirih, peneliti membacakan
pertanyaan dan membimbing responden dalam mengisi kuisioner. Sedangkan
instrumen kesehatan rongga mulut diisi dengan melakukan pengamatan langsung
kepada responden.
4.8 ANALISA DATA
Analisa data dilakukan setelah semua data terkumpul melalui beberapa
tahap yang terdiri dari editing untuk memeriksa kelengkapan data responden serta
memastikan bahwa semua pernyataan telah diisi. Selanjutnya setiap kuesioner
diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam melakukan tabulasi data.
Pengolahan data dilakukan dengan teknik komputerisasi untuk analisis data
deskriptif yaitu analisis distribusi frekuensi. Data yang telah diolah selanjutnya
disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase untuk
mendeskripsikan data demografi, kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut
BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan
Februari sampai Maret 2014 terhadap 29 lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu
Kabupaten Nias. Penyajian data meliputi data demografi, kebiasaan menyirih dan
kesehatan rongga mulut.
5.1.1 Data Demografi
Deskripsi data demografi mencakup umur, jenis kelamin, pendidikan dan
pekerjaan. Jumlah responden terbanyak berada pada kelompok usia 60-74 tahun
(elderly) yaitu sejumlah 14 orang (48,2%). Berdasarkan jenis kelamin, responden
laki-laki lebih banyak yaitu sejumlah 18 orang (62,1%). Berdasarkan tingkat
pendidikan, responden lebih banyak tamatan SD yaitu sejumlah 19 orang (65,5%)
dan lebih banyak yang bekerja sebagai petani/buruh yaitu sejumlah 20 orang
Tabel 5.1 Distribusi responden berdasarkan data demografi di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)
Data demografi Frekuensi Presentase (%)
Umur
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sejumlah 21
orang (72,4%) menyirih dengan komposisi daun sirih, kapur, pinang, gambir dan
tembakau. Berdasarkan frekuensi mayoritas responden sejumlah 21 orang (72,4%)
menyirih dengan frekuensi >10 kali sehari dengan lama kebiasaan menyirih lebih
dari >15 tahun yaitu sejumlah 24 orang (82,8%). Faktor pendorong menyirih
mayoritas responden sejumlah 28 orang (96,5%) adalah kemauan sendiri dengan
kebiasaan saja (tanpa tujuan). Semua responden tidak membersihkan mulut
setelah menyirih.
Tabel 5.2 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan menyirih lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)
Kebiasaan menyirih Frekuensi Presentase (%)
Bahan yang digunakan
Daun sirih, kapur, pinang, gambir, tembakau 21 72,4
Daun sirih, kapur, pinang, gambir 8 27,6
Hanya kebiasaan saja (tanpa tujuan) 14 48,3
Adat-istiadat 2 6,9
Kebersihan rongga mulut setelah menyirih
Tidak 29 100
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sejumlah 25 orang (86,2%) memiliki kebiasaan menyirih yang kurang baik.
Tabel 5.3 Kebiasaan menyirih lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)
Kebiasaan menyirih Frekuensi Presentase (%)
Baik 4 13,8
Kurang baik 25 86,2
5.1.3 Kesehatan Rongga Mulut
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bibir lebih banyak responden
sejumlah 17 orang (58,6%) dalam keadaan sehat dan 12 responden (12%)
mengalami perubahan dari keadaan normal. Lidah mayoritas responden sejumlah
23 orang (79,3%) mengalami perubahan dari keadaan normal dan kondisi lidah 4
orang responden (13,8%) tidak sehat. Gusi dan jaringan lebih banyak responden
sejumlah 19 orang (65,5%) mengalami perubahan dari keadaan normal dan 6
orang responden (20,7%) memiliki kondisi gusi dan jaringan yang tidak sehat.
Saliva mayoritas responden sejumlah 26 orang (89,7%) dalam keadaan sehat,
hanya 3 orang responden (10,3%) yang mengalami perubahan. Gigi mayoritas
responden sejumlah 22 orang (75,9%) tidak sehat dan 7 orang responden (24,1%)
mengalami perubahan. Semua responden tidak memiliki gigi palsu. Kebersihan
mulut mayoritas responden sejumlah 26 orang (89,7%) tidak sehat dan 3 orang
responden (10,3%) mengalami perubahan. Mayoritas responden sejumlah 17
orang (58,6%) tidak mengalami sakit gigi, hanya 2 orang responden (6,9%) yang
Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan hasil pengkajian menggunakan Oral Health Assessment Tool di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nilai rata-rata status
kesehatan rongga mulut responden adalah 6,79 dari rentang nilai 0 (sangat sehat)
sampai 16 (sangat tidak sehat) dengan standar deviasi 1,677. Nilai terendah adalah
2 dan nilai tertinggi adalah 10.
Tabel 5.5 Status kesehatan rongga mulut di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)
Mean Standar deviasi
Status kesehatan rongga mulut 6,79 1,677
5.2 PEMBAHASAN
5.2.1 Kebiasaan Menyirih
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 29 responden menunjukkan
bahwa kebiasaan menyirih lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Selain itu,
kebiasaan menyirih lansia tersebut memiliki karakteristik yang sedikit berbeda
dengan masyarakat daerah lain.
Komposisi bahan yang digunakan pada umumnya adalah daun sirih, kapur,
pinang, gambir dan tembakau (72,4%) dan daun sirih,kapur, pinang dan gambir
(27,6%). Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan Samura (2009), dimana
komposisi terbanyak adalah daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau
(65,2%). Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa semua responden laki-laki
menggunakan tembakau. Perempuan tidak suka menambahkan tembakau dalam
campurannya. Bagi laki-laki, tembakau memberikan rasa yang lebih enak. Hal ini
sedikit dipengaruhi oleh kebiasaan laki-laki merokok dimana mereka sering
terpapar dengan tembakau .
Berbeda dengan kebiasaan masyarakat Batak Karo yang menggunakan
tembakau untuk menyuntil, lansia di Desa Hilibadalu mengunyah tembakau
sebagai bahan campuran menyirih walaupun dalam jumlah yang sedikit.
Kebiasaan ini juga dilakukan oleh penyirih di Kamboja, mereka selalu
menambahkan tembakau ke dalam ramuannya dan dikunyah bersama-sama
(Reichart, 1996 dalam Hasibuan, 2003).
Kebiasaan menyirih dilakukan >10 kali sehari (72,4%). Hasil ini lebih
China dimana kebiasaan menyirih dilakukan hanya 3-10 kali sehari (61,5%). Dari
hasil ini, dapat dilihat bahwa responden memiliki tingkat kecanduan yang tinggi.
Hal ini mungkin berhubungan dengan kandungan dalam bahan menyirih.
Kebiasaan menyirih tetap dilakukan di tengah-tengah aktivitas/pekerjaan mereka.
Menyirih sudah menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan
sehari-hari sama halnya dengan makan.
Lamanya kebiasaan menyirih adalah >15 tahun (82,8%). Hasil ini berbeda
dengan hasil penelitian yang dilakukan Samura (2009) di Desa Sibiru-biru dimana
kebiasaan menyirih dilakukan 1-5 tahun (82,6%). Hal ini mungkin disebabkan
karena responden adalah lansia dimana kebiasaan menyirih telah dilakukan sejak
remaja.
Kemauan sendiri merupakan faktor pendorong responden untuk menyirih
(96,6%). Hasil ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Lim (2007)
dimana faktor pendorong terbanyak untuk menyirih berasal dari diri sendiri
(46,87%). Kemungkinan para responden awalnya hanya ingin mencoba-coba
akibat terdorong dari lingkungan yang memiliki kebiasaan serupa.
Mayoritas responden menyirih karena kebiasaan saja (48,3%). Hal ini
dilakukan karena menyirih membuat mereka nyaman dan mulut terasa kurang
nyaman apabila tidak menyirih. Sebagian responden (31%) menyirih untuk
menenangkan pikiran. Hal ini mungkin dipengaruhi kandungan yang terdapat
dalam pinang dan tembakau. Pinang mengandung Arecoline yang menstimulasi
sistem saraf pusat yang dikombinasikan dengan daun sirih menghasilkan euphoria
menimbulkan ketagihan atau adiksi. Namun, ada 4 orang responden (13,8%) yang
menyirih dengan tujuan agar gigi menjadi kuat dan sehat. Hal ini mungkin
disebabkan oleh kavikol dalam daun sirih yang bersifat bakteriostatik terhadap S.
mutans yang merupakan salah satu bakteri penyebab karies dalam mulut (Astuti,
2007).
Walaupun kebiasaan menyirih menimbulkan kebersihan rongga mulut
tidak baik, semua responden tidak membersihkan mulut setelah menyirih. Hal ini
berbeda dengan pengunyah sirih pada masyarakat Batak Karo di Kecamatan
Pancur Batu, dimana mayoritas pengunyah sirih menggunakan tembakau untuk
menggosok gigi setelah menyirih, rongga mulut kemudian dibersihkan dengan
cara menggosok gigi dan kumur-kumur dengan air (Lim, 2007). Frekuensi
menyirih yang sering dan dilakukan terus menerus membuat lansia malas untuk
membersihkan mulut. Buruknya pemeliharaan kebersihan rongga mulut mungkin
juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pentingnya kebersihan mulut. Latar
belakang pendidikan menyebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya
menjaga kesehatan rongga mulut. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas
responden berpendidikan SD dan tidak sekolah.
5.2.2 Kesehatan Rongga Mulut
Secara umum, nilai status kesehatan rongga mulut responden adalah 6,79
dari rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat tidak sehat). Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut lansia di Desa
mulut buruk. Hal ini dapat disebabkan karena kurang menjaga kebersihan rongga
mulut, kurangnya pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan rongga mulut,
adanya kebiasaan menyirih ataupu proses fisiologis tubuh lansia sendiri akibat
dari proses penuaan. Latar belakang pendidikan berperan penting terhadap kondisi
kesehatan rongga mulut seseorang. Latar belakang pendidikan yang rendah pada
lansia menyebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan
rongga mulut.
Pada lansia, gigi berubah menjadi lebih rapuh dan lebih kering serta
adanya abrasi. Kehilangan substansi gigi terjadi akibat atrisi yang disebabkan oleh
karena pemakaian gigi terus-menerus. Hal ini tergantung konsistensi makanan,
kebiasaan dan kekerasan gigi (Carranza, 1986 dalam Hasibuan, 1998).
Masalah pada gusi/jaringan dan lidah memiliki presentase yang cukup
banyak dan perlu untuk diperhatikan. Perubahan yang terjadi pada mukosa mulut
merupakan proses degenerasi yang menyebabkan menurunnya resistensi mukosa.
Mukosa menjadi lebih mudah terluka oleh karena makanan yang keras. Keadaan
tersebut dapat diperberat karena mulut kering akibat menurunnya produksi saliva
(Winasa, 1995).
Pada lansia di Desa Hilibadalu, masalah pada gusi/jaringan dan lidah
dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama oral hygiene yang buruk dan konsumsi
makanan atau zat yang dapat memperburuk kesehatan rongga mulut. Hasil ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samura (2009) dimana status
kesehatan periodontal pada masyarakat suku karo yang menyirih adalah parah
periodontal akibat menyirih. Pada penelitian tersebut didapatkan kesimpulan
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan periodontal adalah
BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 KESIMPULAN
Menyirih merupakan salah satu kebiasaan lansia di Desa Hilibadalu
Kabupaten Nias. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebiasan menyirih
lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Pada umumnya, bahan yang digunakan
adalah daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau. Kebiasaan menyirih
umumnya telah dilakukan >15 tahun dengan frekuensi >10 kali sehari. Faktor
pendorong utama menyirih adalah kemauan sendiri dimana lansia menyirih hanya
sebagai kebiasaan saja. Walaupun sering menyirih, lansia kurang memperhatikan
kesehatan rongga mulut mereka.
Secara umum, nilai status kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di
Desa Hilibadalu adalah 6,79 dari rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat
tidak sehat). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut
lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Masalah utama yang ditemukan pada lansia
adalah tanggal/busuknya gigi serta kondisi lidah dan gusi/jaringan yang kurang
6.2 SARAN
6.2.1 Praktik Keperawatan
Hasil ini diharapkan menjadi informasi bagi tenaga perawat khususnya
yang ada di daerah dengan budaya menyirih khususnya Desa Hilibadalu
Kabupaten Nias dalam melakukan penyuluhan kesehatan. Perawat perlu
menekankan pentingnya menjaga kesehatan rongga mulut dengan kebersihan
yang mulut yang baik dan membatasi makanan yang mengandung bahan yang
dapat mempengaruhi kesehatan rongga mulut.
6.2.2 Pendidikan Keperawatan
Penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pendidikan
keperawatan dalam asuhan keperawatan lansia khususnya kesehatan rongga
mulut.
6.2.3 Penelitian Keperawatan
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menilai hubungan antara kebiasaan
menyirih dengan kesehatan rongga mulut serta faktor-faktor yang mempengaruhi
DAFTAR PUSTAKA
Andriyani. (2005). Efek Menyirih terhadap Gigi dan Jaringan Lunak Mulut. Skripsi : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.
Astuti, Dyah H., dkk. (2007). Efek Aplikasi Topikal Laktoferin dan Piper Betle Linn pada Mukosa Mulut terhadap Perkembangan Karies Gigi. Jurnal M.I Kedokteran Gigi, 22(1): 28-31.
Chalmers JM, dkk. (2005). The Oral Health Assessment Tool – Validity and reliablity. Australian Dental Jurnal, 50(3): 191-199.
Chalmers JM, dkk. (2009). Caring for oral health in Australian residential care. Dental statistics and research series, (48). Canbera: AIHW.
Chen JW, dkk. (1996). A study on betel quid chewing behavior among Kaousiung resident age 15 years and above. J Oral Pathol Med 1996, (240): 140-143.
Ginting, Mediawati. (2011). “Man Belo” (Sebuah Etnografi Kegiatan Menyirih Sebagai Identitas Sosial Generasi Muda Karo di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Medan. Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politim Universitas Sumatera Utara.
Hasibuan, Sayuti. (1998). Keadaan-keadaan di Rongga Mulut yang perlu diketahui pada Usia Lanjut. Majalah Kedokteran Gigi Usu, (4): 40-45.
Hasibuan, S., Pernama, G., Aliyah, S. (2003). Lesi-lesi Mukosa Mulut yang Dihubungkan dengan Kebiasaan Menyirih di Kalangan Penduduk Tanah Karo, Sumatera Utara. Jurnal Dentika, 8(2): 67-73.
Hermawan, Anang. (2007). Pengaruh Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan Metode Difusi Disk. Artikel Ilmiah: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya.
Maryam, R. Siti, dkk. (2008). Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya. Jakarta: Salemba Medika.
Kayser-Jones, Jeanie, dkk. (1995). An Instrument To Assess the Oral Health Status of Nursing Home Resident. The Gerontologist, 35(6): 814-824.
Lim, Emerson. (2007). Kebiasaan menguyah sirih dan lesi yang dijumpai pada mukosa oral masyarakat batak karo. Skripsi : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.
Nugroho, Wahyudi H. (2008). Keperawatan Gerontik & Geriatrik. Jakarta: EGC.
Samura, Jul A. (2009). Pengaruh Budaya Makan Sirih terhadap Status Kesehatan Periodontal pada Masyarakat Suku Karo di Desa Biru-Biru Kabupaten
Deli Serdang Tahun 2009. Tesis: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara.
Sembiring, Bernadetta. (2007). Perilaku penggunaan sirih pada suku karo : Studi kasus di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Skripsi: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.
Sinuhaji, L. N. (2010). Perilaku menyirih dan dampaknya terhadap kesehatan yang dirasakan wanita karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Skripsi: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
Siswanto, Susila & Suyanto. (2013). Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran. Yogyakarta: Bursa Ilmu.
Stanley, Mickey dan Beare Patricia G. (2006). Buku Ajar Keperawatan Gerontik. Jakarta: EGC
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sundari, Siti, dkk. (1992). Minyak Atsiri Daun Sirih dalam Pasta Gigi; Stabilitas Fisis dan Daya Antibakteri. Warta Tumbuhan Obat Indonesia, 1(1): 5-6.
Susiarti, Siti. (2005). Jenis-jenis Pengganti Pinang dan Gambir dalam Budaya Menginang Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua. Jurnal Biodiversitas, 6(3): 217-219.
Wahyuni, A.S. (2010). (2011). Statistika Kedokteran. Jakarta: Bamboedoea Commnunication.
Winasa, I. G. (1995). Perubahan Jaringan Rongga Mulut pada Usia Lanjut. The Indonesian Journal of Dental Health, 1(4): 15-18.
Penjelasan Tentang Penelitian
Judul: Kebiasaan Menyirih dan Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.
Saya bernama Elvis Sofyan Lombu, mahasiswa S-1 Keperawatan,
Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, Medan. Saya ingin melakukan
penelitian di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias dengan tujuan untuk mengetahui
kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut lansia.
Penelitian ini adalah salah satu kegiatan untuk menyelesaikan tugas skripsi
di Program Studi S-1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera
Utara. Peneliti menjamin bahwa penelitian yang dilakukan tidak akan
menimbulkan dampak negatif kepada Bapak/Ibu sebagai responden. Penelitian ini
akan memberikan manfaat bagi pengembangan pelayanan dan ilmu keperawatan.
Peneliti juga menghargai dan menghormati hak responden dengan cara
menjaga kerahasiaan identitas diri dan data yang diberikan responden selama
pengumpulan data hingga penyajian data. Peneliti sangat mengharapkan
partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini, namun jika
Bapak/Ibu tidak bersedia maka Bapak/Ibu berhak untuk menolak karena tidak ada
unsur paksaan dalam pengisian kuesioner penelitian. Demikianlah informasi ini
saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan
terimakasih.
Medan, Februari 2014
Lembar Persetujuan Menjadi Responden
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama:
Umur:
Jenis kelamin:
Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian yang
berjudul “Kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut lansia di Desa
Hilibadalu”, maka saya dengan sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia
menjadi responden dalam penelitian tersebut.
Medan, Februari 2014
Responden
KUISIONER PENELITIAN KEBISAAN MENYIRIH LANSIA DI DESA HILIBADALU KABUPATEN NIAS
Nomor responden
A. Data demografi
Petunjuk pengisian :
Di bawah ini adalah data demografi yang dibutuhkan sebagai identitas responden
penelitian. Isilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang
sebenarnya, dengan memberi tanda check list (√) pada kotak yang telah
disediakan.
1. Usia : tahun
2. Jenis kelamin Laki-laki
Perempuan
3. Pendidikan Tidak sekolah
SD SMP SMA D3/S1
4. Pekerjaan Petani / Buruh
PNS / Polri Pegawai swasta / Wiraswasta
Tidak bekerja / Ibu rumah tangga
B. Kuisioner kebiasaan menyirih
Petunjuk pengisian :
Pertanyaan berikut ini berkaitan dengan kebiasaan menyirih Bapak/Ibu selama ini.
Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu, dengan memberi tanda
check list (√) pada kotak yang telah disediakan.
1. Apa bahan-bahan yang bapak/ibu gunakan untuk menyirih? Daun sirih, kapur, pinang, gambir, tembakau
Daun sirih, kapur, pinang, gambir Lain-lain (sebutkan) ...
2. Berapa kali dalam satu hari bapak/ibu menyirih? >10 kali sehari
7-10 kali sehari 4-6 kali sehari 1-3 kali sehari
3. Berapa lama bapak/ibu sudah menyirih? >15 tahun
11-15 tahun 6-10 tahun 0-5 tahun
4. Siapa yang mendorong bapak/ibu menyirih? Orangtua/keluarga
Teman
Kemauan sendiri
Lain-lain (sebutkan) ...
5. Apa tujuan bapak/ibu makan sirih? Untuk menenangkan pikiran Agar gigi menjadi kuat dan sehat Hanya kebiasaan saja (tanpa tujuan) Adat-istiadat
Lain-lain (sebutkan) ...
6. Setelah menyirih, apakah gigi dan mulut dibersihkan? Tidak
Oral Health Assessment Tool (modified from Kayser-Jones et al (1995) by Chalmers (2000)
No Responden ___________ TOTAL SCORE _________
KATEGORI 0 = sehat 1 = berubah 2 = tidak sehat Skor pecah atau merah di
bagian sudut ulkus/ titik sakit di
bawah gigi palsu
Bengkak, berdarah, ulkus, bercak merah/putih, kemerahan
merata di bawah gigi palsu dan merah, air liur sangat
sedikit/tidak ada, air liur pekat, lansia berpikir
4 atau lebih gigi/akar busuk dan tanggal, atau gigi sangat aus, kurang
dari 4 gigi
GIGI PALSU
Tidak ada daerah atau gigi palsu yang
rusak
1 daerah/gigi rusak, atau hanya dipakai
selama 1-2 jam sehari
Lebih dari 1 daerah/gigi rusak, gigi palsu lepas
atau tidak dipakai, atau pada gigi palsu
Sisa makanan/tartar pada banyak tempat di dalam
mulut atau pada gigi palsu
Adanya tanda fisik nyeri (pipi/gusi bengkak, gigi
rusak, ulkus), tanda verbal/perilaku nyeri (wajah merenggut, tidak
Oral Health Assessment Tool (modified from Kayser-Jones et al (1995) by Chalmers (2000))
Resident’s Name _________ TOTAL SCORE ____ _____
CATEGORY 0=healthy 1=changes 2=unhealthy Skor
LIPS Smooth, pink,
moist
Dry, chapped, or red at corners
Swelling or lump, white/red/ulcerated patch, bleeding/ulcer at
corners
TONGUE Normal, moist
roughness, pink
Patchy, fissured, red, coated
Patch that is red &/or white, ulcerated, swollen
Tissues parched and red, very little/no saliva present, saliva is thick, resident thinks they have
a dry mouth
1 broken are/tooth or dentures only worn for 1-2 hrs daily, or dentures not named
More than 1 broken area/tooth, denture missing or not worn, needs denture adhesive the mouth or dentures
Food
particles/tartar/plaque in most areas of the mouth or on most of dentures
DENTAL pain such as pulling at face, chewing lips, not eating, aggression
Are physical pain signs (swelling of cheek or
gum, broken teeth, ulcers), as well as verbal
&/or behavioural signs (pulling at face, not