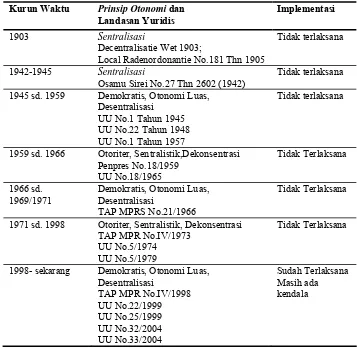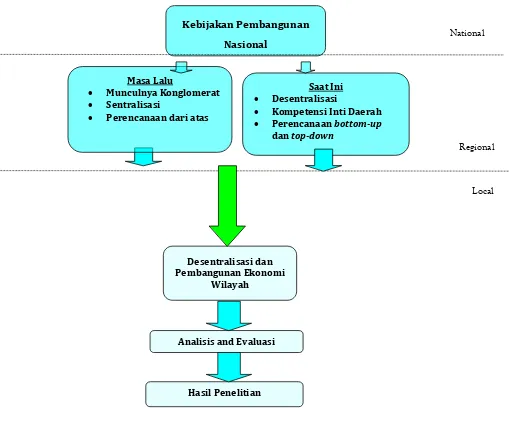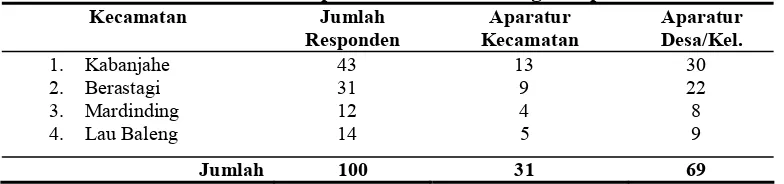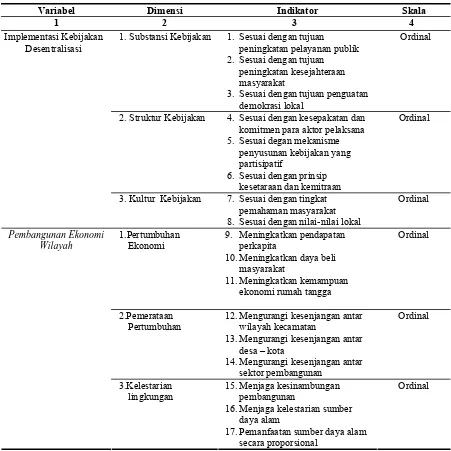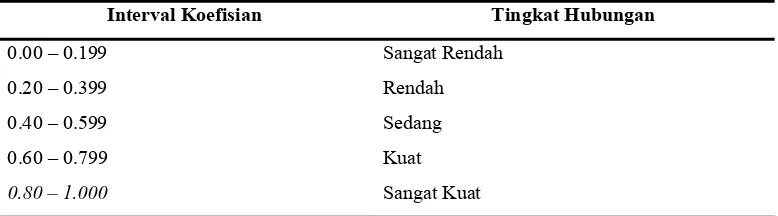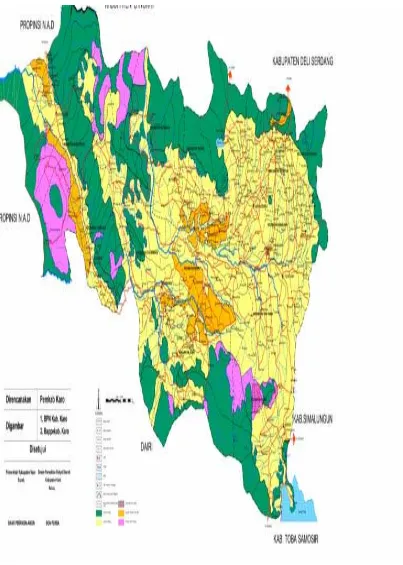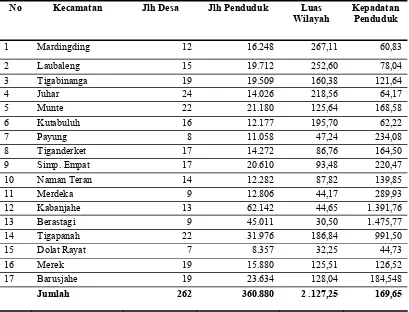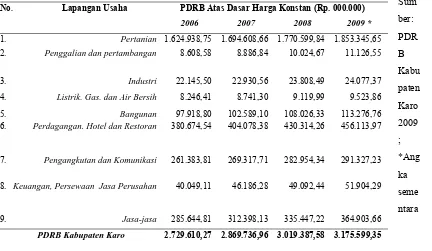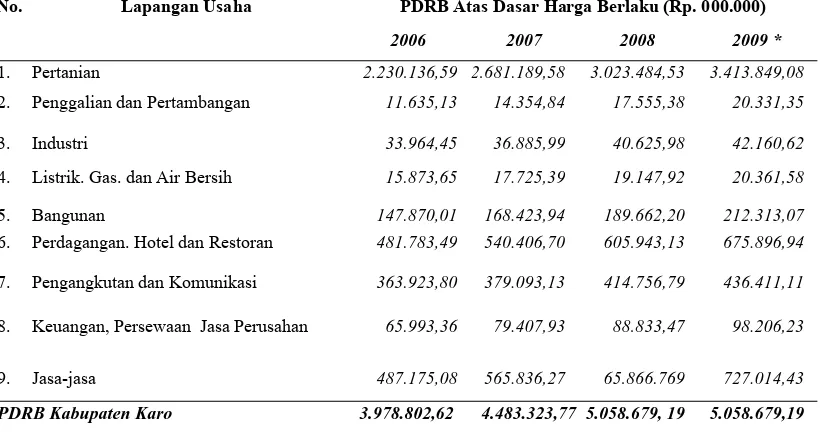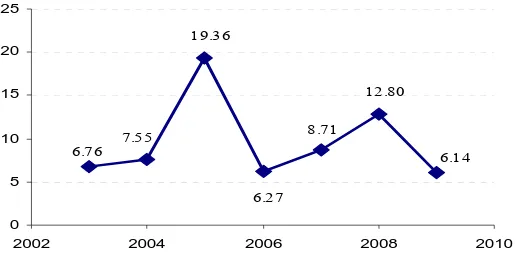ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI EBIJAKAN
DESENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO
TESIS
Oleh
RANIN PINEM
087003056/PWD
S
E K O L A H
P A
S C
A S A R JA
NA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI EBIJAKAN
DESENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh
RANIN PINEM
087003056/PWD
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Judul Tesis : ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO
Nama Mahasiswa : Ranin Pinem Nomor Pokok : 087003056
Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA) Ketua
(Kasyful Mahalli, SE, M.Si) (Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec)
Anggota Anggota
Ketua Program Studi Direktur
Telah diuji pada Tanggal : 29 Juli 2011
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA Anggota : 1. Kasyful Mahalli, SE, M.Si
2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec 3. Agus Suryadi, S.Sos, M.Si
ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO ABSTRAK
Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan desentralisasi terhadap pengembagan ekonomi wilayah yang dilakukan di Kabupaten Karo. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan responden 100 orang yang terdiri dari kalangan aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Berastagi, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng. Teknik analisis yamg digunakan menggunakan analisis korelasi product moment dari Karl Pearson dengan bantuan aplikasi komputer SPSS versi 15.00.
Hasil analisis menunjukkan besaran koefisien korelasi sebesar 0.405 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000. Pengujian dilakukan dengan pengujian dua ekor (2 tailed) dengan kasus yang berlaku adalah 100 (N=100). Adapun ketentuan bahwa apabila signifikansi di bawah atau sama dengan 0,05 maka Ha (Hipotesis Alternatif) diterima dan Ho (Hipotesis nol) ditolak. Bila dibandingkan dengan tabel nilai r product moment pada taraf signifikansi 5 % dan 1 % dengan N = 100, masing-masing secara berturut-turut 0,195 dan 0,256 berarti 0,405 > 0,256 > 0,195. Kesimpulan yang dapat diambil dari besaran nilai koefisien korelasi product moment tersebut adalah “terdapat hubungan pengaruh yang nyata dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Desentralisasi (IKD) terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah (PEW)”. Dengan demikian, data sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil.
Disarankan agar upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desentralisasi dapat dilakukan dengan memperbaiki substansi kebijakan sehingga lebih mencerminkan tujuan desentralisasi, memperbaiki struktur kebijakan dengan memperkuat kemitraan yang sinergis antar tiga pilar pemerintahan yakni masyarakat sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta. Sedangkan penguatan kultur kebijakan lebih pada upaya sosialisasi kebijakan agar lebih sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat dan nilai-nilai lokal.
Pembangunan ekonomi wilayah juga perlu dilakukan dengan lebih komprehensif melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kelestarian lingkungan.
ANALYZE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION POLICY IMPLEMENTATION TOWARD REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT IN KARO REGENCY
ABSTRACT
This research aims is to answer the research question on influence of decentralization policy implementation toward regional economic development in Karo Regency. This research used survey approach with 100 respondents consist of local apparatus from Kecamatan(sub-regency), Kelurahan and Desa (Village) government respectively in Berastagi, Kabanjahe , Mardinding and Lau Baleng. Analytical technique used product moment correlation from Karl Pearson which supported by computer application SPSS 15.00 version.
Result of the research explain that corellation coefficient 0.405 with degree of significancy 0.000, two-tailed test with 100 cases run. In accordance with degree of significancy regulation less or equal with 0.05 then caused the receive alternative hypothesis and Null Hypothesis would be rejected. As a result of correlation measurement (r) is equal with 0.405 compare toward r table value respectively 5% and 1% with N = 100, 0.195 and 0.256 means 0.405>0.256>0.195. From the analysis can be concluded that relationship or influence of Decentralization Policy Implementation toward Regional Economic Development was real and significant.. It means, data from sample can be generalized toward population where the sample derived.
Recommendation proposed deals with endeavour to improve the quality of decentralization policy implementation can be done through resive policy substance more suitable with the goal of decentralization, improve the structure of policy by encourage mutual partnership amongs civil society, local government and private sector. Meanwhile, policy culture can be emphasized through internalized local values and alignment with degree of society understanding on decentralization policy.
Regional economic development need to more comprehensively formulate through development policy with more emphasized on equilibrium amongs economic growth, growth with equity and environment sustainability.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Desentralisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Karo”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD).
Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Segenap perhatian yang diberikan kepada penulis merupakan sumbangsih yang sangat berharga, sehingga penulis patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si. dan Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec., masing-masing selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan ketulusan, kearifan dan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.
2. Bapak Agus Suryadi, S.Sos, M.Si, Bapak Drs. Rujiman, MA dan Bapak Dr.Irsyad Lubis, M.Sos, M.Sc, selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan banyak masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Bupati Karo beserta seluruh staf Pemda Karo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan peneitian di Kabupaten Karo. 5. Bapak/Ibu Dosen, Staf Administrasi dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
6. Rekan saya Anderiasta Tarigan, S.Sos, M.Si, yang telah membantu penyusunan tesis ini.
Secara khusus penulis ingin mengucapkan sayang dan terima kasih yang mendalam kepada ibunda Dk. Sita Sadaarih Br. Ketaren, abangku Dr. Edyan Pinem, Sp. PD, kakakku Dra. Niarita Pinem, Apt. serta adikku Iman Pinem, SE, M.Si, beserta seluruh keluarga atas doa, nasehat, dorongan semangat serta bantuan yang diberikan selama ini.
Kepada suami tercinta AIPTU Henry Sihombing, SH, anak-anakku tersayang Maureen Claudia Sihombng dan Hera Vanesa Sihombing, yang selalu menjadi motivator bagi penulis selama mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD).
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidakdapat disebutkan satu persatu yang turut andil dan memberi bantuan langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Semoga hasil penulisan ini nantinya dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. .
. Medan, September 2011
RIWAYAT HIDUP
Ranin Pinem, lahir di Medan pada tanggal 04 Desember 1966. Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Drs. DJ. Pinem (Almarhum) dan Ibunda Dk. Sita Sadaarih Br. Ketaren.
Menikah pada tahun 1994 dengan Aiptu Henry Sihombing, SH.
Tamat Sekolah Dasar Kristen Immanuel Medan tahun 1979, melanjutkan ke SMP Kristen Immanuel Medan dan tamat tahun 1982, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Kristen Immanuel Medan pada tahun 1985, melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara Medan dan tamat pada tahun 1990.
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL ...………..………... viii
DAFTAR GAMBAR ... ix
DAFTAR LAMPIRAN ... x
BAB I PENDAHULUAN ………..………... 1
1.1 Latar Belakang ...………... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 9
1.3. Hipotesis Penelitian ……….…... 10
1.4. Tujuan Penelitian………... 10
1.5. Manfaat Penelitian ……….... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...…... 11
2.1. Perkembangan Konsep Desentralisasi ..………... 11
2.2. Perkembangan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia ... 27
2.3. Konsep Pembangunan Ekonomi Wilayah ... 30
2.3.1. Central Places Theory ... 30
2.3.2. The Growth Pole Theory ... 32
2.4. Penelitian Sebelumnya ... 34
2.5. Kerangka Pemikiran ... 39
BAB III METODE PENELITIAN... 41
3.1. Desain Penelitian………..….………... 41
3.2. Jenis dan Sumber Data ………... 41
3.3.1. Populasi ... 42
3.3.2. Sampel ... 42
3.4. Definisi Operasionalisasi ………... 44
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian ... 45
3.6 Teknik Analisis Data ... 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 50
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………... 50
4.2. Karakteristik Responden ……….…….. 61
4.3. Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen ………….…….. 64
4.4. Gambaran Empirik Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah ... 65
4.4.1. Implementasi Kebijakan Desentralisasi………... 66
4.4.2. Pembangunan Ekonomi Wilayah ……….... 81
4.5. Pengaruh Implementasi Kebijakan Desentralisasi ... 93
terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah ………... BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ………... 100
5.1. Kesimpulan ……….... 100
5.2. Saran ……….. 101
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
2.1. Konfigurasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia...…... 13
2.1. Kerangka Pemekiran Penelitian ... 13
3.1. Jumlah Responden Menurut Kluster Kecamatan ...…... 43
3.2. Jumlah Responden Menurut Kategori Aparatur …..……... 43
3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian ………... 44
3.4. Kriteria Penilaian Korelasi ………..…... 49
4.1. Jumlah Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2008 …... 53
4.2. Perkembangan PDRB periode tahun 2006-2009 ………..…... 54
4.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar Harga Berlaku Perode Tahun 2006-2009 ….………... 55
4.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2006-2008 ………..…... 56
4.5. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku Thn. 2006-2009 ... 58
4.6. PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2006-2008 ...….. 59
4.7. Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karo Sebelum dan Setelah Kebijakan Otonomi (2000-2006) ………... 60
4.8. Derajat Reliabilitas Instrumen ………... 64
4.9. Uji Validitas Instrumen ………... 65
4.10. Pemekaran Daerah di Indonesia Tahun 1999-2008 ……... 72
4.11. Trend Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah 2006 – 2010 ... 75
4.12. Ringkasan APBD Kabupaten Karo Tahun 2008 ...………... 78
4.13. Koefisien Korelasi Produk Moment Antara Implementasi Kebijakan Desentralisasi (Variabel Independen) terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah (Variabel Dependen) …... 93
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
1.1 Grafik Perkembangan Komponen Penerimaan Daerah 2008-2010 ... 2
2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian ………... 40
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Karo ...…….. 51
4.2. Grafik Laju Inflasi di Kabupaten Karo 2003 - 2010 ... 56
4.3. Grafik Profil Responden Menurut Pendidikan ... 62
4.4. Grafik Profil Responden Menurut Jabatan ... 63
4.5. Grafik Persepsi Responden terhadap Substansi Kebijakan Desentralisasi ... 67
4.6. Grafik Persepsi Responden terhadap Struktur Kebijakan Desentralisasi …... 70
4.7. Grafik Persepsi Responden tentang Kultur Kebijakan Desentralisasi 71 4.8. Grafik Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2008-2010 ……... 77
4.9. Grafik Persepsi Responden terkait Pertumbuhan Ekonomi ….…... 82
4.10. Grafik Persepsi Responden terhadap Pemerataan Pertumbuhan ... 83
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
1. Instrumen Penelitian ……… 106
2. Tabulasi Hasil Jawaban Responden ………. 110
ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO ABSTRAK
Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan desentralisasi terhadap pengembagan ekonomi wilayah yang dilakukan di Kabupaten Karo. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan responden 100 orang yang terdiri dari kalangan aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Berastagi, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng. Teknik analisis yamg digunakan menggunakan analisis korelasi product moment dari Karl Pearson dengan bantuan aplikasi komputer SPSS versi 15.00.
Hasil analisis menunjukkan besaran koefisien korelasi sebesar 0.405 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000. Pengujian dilakukan dengan pengujian dua ekor (2 tailed) dengan kasus yang berlaku adalah 100 (N=100). Adapun ketentuan bahwa apabila signifikansi di bawah atau sama dengan 0,05 maka Ha (Hipotesis Alternatif) diterima dan Ho (Hipotesis nol) ditolak. Bila dibandingkan dengan tabel nilai r product moment pada taraf signifikansi 5 % dan 1 % dengan N = 100, masing-masing secara berturut-turut 0,195 dan 0,256 berarti 0,405 > 0,256 > 0,195. Kesimpulan yang dapat diambil dari besaran nilai koefisien korelasi product moment tersebut adalah “terdapat hubungan pengaruh yang nyata dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Desentralisasi (IKD) terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah (PEW)”. Dengan demikian, data sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil.
Disarankan agar upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desentralisasi dapat dilakukan dengan memperbaiki substansi kebijakan sehingga lebih mencerminkan tujuan desentralisasi, memperbaiki struktur kebijakan dengan memperkuat kemitraan yang sinergis antar tiga pilar pemerintahan yakni masyarakat sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta. Sedangkan penguatan kultur kebijakan lebih pada upaya sosialisasi kebijakan agar lebih sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat dan nilai-nilai lokal.
Pembangunan ekonomi wilayah juga perlu dilakukan dengan lebih komprehensif melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kelestarian lingkungan.
ANALYZE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION POLICY IMPLEMENTATION TOWARD REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT IN KARO REGENCY
ABSTRACT
This research aims is to answer the research question on influence of decentralization policy implementation toward regional economic development in Karo Regency. This research used survey approach with 100 respondents consist of local apparatus from Kecamatan(sub-regency), Kelurahan and Desa (Village) government respectively in Berastagi, Kabanjahe , Mardinding and Lau Baleng. Analytical technique used product moment correlation from Karl Pearson which supported by computer application SPSS 15.00 version.
Result of the research explain that corellation coefficient 0.405 with degree of significancy 0.000, two-tailed test with 100 cases run. In accordance with degree of significancy regulation less or equal with 0.05 then caused the receive alternative hypothesis and Null Hypothesis would be rejected. As a result of correlation measurement (r) is equal with 0.405 compare toward r table value respectively 5% and 1% with N = 100, 0.195 and 0.256 means 0.405>0.256>0.195. From the analysis can be concluded that relationship or influence of Decentralization Policy Implementation toward Regional Economic Development was real and significant.. It means, data from sample can be generalized toward population where the sample derived.
Recommendation proposed deals with endeavour to improve the quality of decentralization policy implementation can be done through resive policy substance more suitable with the goal of decentralization, improve the structure of policy by encourage mutual partnership amongs civil society, local government and private sector. Meanwhile, policy culture can be emphasized through internalized local values and alignment with degree of society understanding on decentralization policy.
Regional economic development need to more comprehensively formulate through development policy with more emphasized on equilibrium amongs economic growth, growth with equity and environment sustainability.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Secara teoritis, salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada
masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi (Smith, 1985).
Berangkat dari pemahaman konseptual bahwa desentralisasi dapat mendekatkan
pelayanan publik kepada masyarakat maka di Indonesia kebijakan desentralisasi
senantiasa menjadi bahan perbincangan sepanjang sejarah pemerintahan.
Namun yang sangat disayangkan, di Kabupaten Karo merujuk hasil penelitian
lembaga riset SMERU (2001), kebijakan desentralisasi ternyata baru sebatas
menambah jumlah organisasi perangkat daerah dan mendongkrak besaran belanja
aparatur hingga mencapai 45% dari total APBD pada tahun anggaran 2000.
Hasil riset SMERU di atas, menghadirkan sejumlah kekhawatiran. Apakah
implementasi kebijakan desentralisasi benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik dan mengembangkan potensi
unggulan daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Ataukah kebijakan desentralisasi hanya sebatas keleluasaan
bagi elit politik di daerah mengeruk kekayaan daerah.
Kekhawatiran tersebut sangat beralasan mengingat secara empirik
desentralisasi di Kabupaten Karo sampai saat ini masih ditandai dengan tingginya
Ketergantungan finansial dapat ditelaah melalui komponen pembentuk
pendapatan daerah, yang mana secara umum masih didominasi oleh dana
perimbangan (lihat Grafik 1.1).
Sumber: DPPKAD Kab.Karo, 2010
Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Komponen Penerimaan Daerah 2008-2010
Data yang diperlihatkan melalui Gambar 1.1. menunjukan relatif tingginya
tingkat ketergantungan terhadap transfer dana dari Pusat. Selama tahun 2008 s/d 2010
rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah hanya berkisar 5%. Pada
tahun anggaran 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 26.490.000.000,-
Dana Perimbangan (DP) sebesar Rp. 478.820.158.477.,- Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah sebesar Rp. 18.630.683.850. Konsekuensinya, ketergantungan pemerintah
daerah terhadap transfer dari pusat sangat tinggi.
Terkait dengan pelayanan publik, Roth (1987) menyebutkan bahwa dalam
negara kesatuan yang terdesentralisasi, disamping pernerintah pusat terdapat
utama melaksanakan pelayanan kepada masyarakatnya. Hal tersebut dinyatakan oleh
Roth (1987:1) bahwa “... that are generally considered the responsibility of
government whether central, regional or local”.
Tugas yang diemban oleh pemerintah terutama pemerintah daerah dalam
pelayanan, dapat dipisahkan ke dalam beberapa alternatif pemberi layanan. Alternatif
tersebut menyangkut pilihan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Leach, et.al. (1994: 4), terdapat empat model alternatif kewenangan yang
digunakan dalam memberikan pelayanan, yaitu traditional bureaucratic authority,
residual enabling authority, market oriented authority, dan community oriented
enabler.
Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menganut traditional
bureaucratic authority, merupakan pelayanan yang dilakukan secara langsung oleh
pemerintah daerah. Pemerintah daerah merasa mampu untuk melakukan pelayanan
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan dengan cara ini pada umumnya
kebutuhan publik diinterpretasikan oleh pegawai professional pada organisasi
pemberi layanan. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan Stewart yang dinyatakan
bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebaiknya sesuai dengan
kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat.
Sementara itu pemerintah daerah yang melakukan pelayanan dengan
menggunakan residual enabling authority, adalah pelayanan yang dilakukan dengan
menggunakan mekanisme pasar. Pemerintah daerah hanya melakukan pelayanan
yang spesifik. Pelayanan cara ini dianggap ideal dan lebih akuntabel.
Pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan dengan dasar market
oriented authority, merupakan kegiatan pemerintah daerah dalam pelayanan yang
hampir sama dengan residual enabling authority. Perbedaannya adalah dalam market
oriented authority peran pemerintah daerah lebih aktif dan sebagai kunci perencanaan
serta agen koordinasi untuk pengembangan ekonomi lokal. Hal ini akan
memampukan masyarakat dalam melayani dirinya sendiri. Sementara itu residual
enabling authority peran pasar lebih aktif dan peran pemerintah daerah. Pelayanan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dasar kewenangan yang bersifat
community oriented enabler, mendasarkan pelayanan pada asumsi untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang bervariasi. Pelayanannya sendiri dilakukan dengan
menggunakan berbagai saluran, misalnya pelayanan yang dilakukan secara langsung
oleh pemerintah daerah, sektor privat, sukarela, atau yang dilihat paling pantas.
Pelayanan yang dilakukan dengan cara ini menekankan pentingnya pc.rtisipasi
komunitas (publik) dan akuntabilitas.
Keempat alternatif di atas memberikan peluang bagi setiap pemerintah daerah
untuk memilih cara pemberian pelayanan pada masyarakatnya. Pemilihan
kewenangan itu berpengaruh pada penyediaan barang dan jasa yang menjadi
tanggung jawab baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Pada dasarnya kegiatan
members the citizens”. Dengan demikian pemerintah merupakan organisasi yang
bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan.
Teori di atas memberikan gambaran tentang berbagai alternatif pemberian
pelayanan. Namun implementasi pelayanan yang dilakukan di Indonesia tidak
sepenuhnya menggunakan alternatif-alternatif di atas. Pelayanan di Indonesia
menggunakan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi. Kedua pendekatan
merupakan kontinum dan tidak dikhotomi. Pendekatan sentralisasi dalam pelayanan
dapat mencerrninkan adanya negara dan bangsa sebagai refleksi konsepsi Negara
Kesatuan. Sedangkan pendekatan desentralisasi dapat merepresentasikan
kemajemukan masyarakat serta sekaligus menggambarkan adanya pendemokrasian.
Pelayanan yang dilakukan dengan pendekatan desentralisasi, dijelaskan oleh
Hoessein bertujuan untuk efisiensi dan demokrasi. Tujuan efisiensi biasanya
berpasangan dengan nilai-nilai komunitas politik yang disebut dengan kesatuan
bangsa. Sementara itu, tujuan demokrasi berpasangan dengan kemandirian sebagai
penjelmaan dan otonomi, efisiensi, dan pembangunan sosial ekonomi. Dengan kata
lain, dalam desentralisasi terkandung makna mengakomondasikan nilai-nilai yang ada
pada masyarakat untuk tujuan politik dan birokrasi dalam rangka menciptakan
efisiensi birokrasi.
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian
direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
dengan undang-undang ini, masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk
berinovasi, mengembangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai, serta
menghasilkan bentuk pemerintah otonom. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan
publik dapat dipenuhi sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat.
Di sisi lain, pengembangan ekonomi lokal juga diharapkan dapat meningkat
seiring dengan penerapan kebijakan desentralisasi. Hal ini berangkat dari asumsi
bahwa kebijakan desentralisasi lebih memberikan peluang bagi daerah memilih
kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan potensi dan kemampuan lokal (Kuncoro,
2004: 110-118).
Banyak ahli mengemukakan pandangan bahwa desentralisasi mampu menjadi
pendorong pembangunan ekonomi wilayah (Kuncoro, 2004: Mardiasmo, 2002;
Muhammad, 2008). Studi Kuncoro (2004) di Kabupaten Kutai Timut menunjukkan
adanya korelasi antara desentralisasi dengan pembanguna ekonomi wilayah. Hal yang
sama dikemukakan oleh Fadel Muhammad (2008) bahwa pengembangan ekonomi
wilayah dapat dikembangkan dengan pendekatan manajemen kewirausahaan. Inilah
yang diterapkan oleh Fadel Mudahmmad di Propinsi Gorontalo.
Memang harus diakui, selama ini kebijakan pembangunan ekonomi masih
memberi penekanan pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator keberhasilan
dapat diamati melalui: 1) pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun rata-rata 6,7 s/d 7
persen per-tahun; 2) terjadinya pengurangan jumlah orang miskin dari 70 juta orang
struktur perekonomian dari berasas pertanian on-farm menjadi berasas industri dan
jasa (Sumodiningrat, 2001).
Namun di balik berbagai prestasi pembangunan, tercatat pula sejumlah sisi
gelap pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Semakin meningkatnya
pengangguran, bertambahnya hutang luar negeri, bertambahnya berbagai bentuk
ketimpangan maupun semakin besarnya ketimpangan antar wilayah (Husaini, 2001).
Fenomena ketimpangan antar wilayah maupun melemahnya efektivitas
pemerintahan daerah bermula dari serangkaian pilihan kebijakan pembangunan
sektoral, keruangan, maupun politik-administrasi yang dijalankan selama ini. Pilihan
kebijakan selama ini ternyata mengandung kekeliruan dan kurang memberi perhatian
yang memadai terhadap dinamika internal maupun eksternal yang berlangsung.
Dengan demikian, kebijakan desentralisasi maupun pembangunan ekonomi wilayah,
ternyata menimbulkan pemerasan ganda (double squeeze)oleh wilayah kota terhadap
wilayah desa.
Bentuk pemerasan ganda tersebut berlangsung melalui munculnya gejala
“under employment” dan “under investment” di wilayah-wilayah pedesaan. Gejala
tersebut bermula dari adanya capital drain maupun brain drain dari wilayah
perdesaan yang tersedot ke wilayah perkotaan. Ekonomi desa tidak memperoleh nilai
tambah (value added) yang proporsional akibat wilayah perkotaan hanya sekedar
menjadi lahan/aliran (marketing pipe) bagi arus komoditi primer dari perdesaan
Keterkaitan antara wilayah (regional linkages) yang ingin diwujudkan,
ternyata menghasilkan kebocoran wilayah (regional leakages). Studi Fu-Chen Lo
(1981) menegaskan bahwa kemiskinan kota (urban poverty)berakar pada kemiskinan
perdesaan (rural poverty). Penegasan Fu-Chen Lo tersebut, merujuk pengalaman
beberapa negara di Asia terutama dalam upayanya meningkatkan keterkaitan
desa-kota, diantaranya Thailand, Malaysia, Laos dan Indonesia.
Di Indonesia, kebijakan untuk mengurangi disparitas antar wilayah dilakukan
dengan adanya berbagai program/proyek pembangunan perdesaan seperti
Pembangunan Desa Terpadu, Projek Desa Tertinggal, Poverty Alleviation through
Rural-Urban Linkages (PARUL), SPAKU (Sentra Pengembangan Agrobisnis
Komoditas Unggulan), KSP (Kawasan Sentra Produksi), Corporate Farming, dan
lain-lain.
Seiring dengan upaya mengurangi disparitas antar wilayah dan mengupayakan
keterkaitan antar wilayah, pilihan kebijakan desentralisasi diterapkan dengan
perencanaan wilayah yang sesuai. Untuk itulah, konsep perencanaan wilayah pun
mengalami perubahan.
Konsep sebelumnya yang relevan dengan sistem pemerintahan yang
sentralistik beralih kepada konsep “agropolitan development”, “selective spatial
closure”, “development from below”, “locally integrated economic circuits”, yang
sesuai dengan konsep desentralisasi.
kebijakan desentralisasi relevan dalam melakukan akselerasi pembangunan
ekonomi wilayah? Atau justru kebijakan desentralisasi menghambat pembangunan
ekonomi wilayah. Serangkaian pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui
studi empirikal.
Terkait dengan kondisi sebagaimana diuraikan, maka permasalahan yang
menjadi lokus dan fokus penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:
1. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang sangat mendasar dari
sentralistik kepada desentralistik belum membawa perubahan signifikan dalam
konteks politik maupun administratif;
2. Perubahan strategi pembangunan wilayah dari top-down planning menjadi
bottom-up planning belum menemukan konsep perencanaan wilayah yang sesuai
dengan kondisi setempat (local spesific).
3. Pilihan kebijakan desentralisasi belum disinergikan dengan pembangunan
ekonomi wilayah.
1.2. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Kabupaten Karo
khususnya diukur dari aspek tujuan utama desentralisasi berupa peningkatan
2. Bagaimanakah pembangunan ekonomi wilayah dilaksanakan di Kabupaten Karo
khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan dan
kelestarian lingkungan ?
3. Adakah hubungan antara pelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan
pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Karo?
1.3. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini
dihipotesiskan bahwa:
1. Implementasi kebijakan desentralisasi di Kabupaten Karo telah dilaksanakan
sesuai dengan tujuan utama desentralisasi berupa peningkatan pelayanan publik,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas demokrasi lokal.
2. Pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Karo ditujukan untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan pertumbuhan dan kelestarian lingkungan.
3. Implementasi kebijakan desentralisasi memiliki hubungan positif dan nyata
dengan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Karo.
1.4. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi dan penjelasan tentang
hubungan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan pembangunan ekonomi
1.5. Manfaat Penelitian
Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk memahami pengaruh kebijakan
desentralisasi terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Secara praktis, untuk
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Perkembangan konsep dan kebijakan desentralisasi hingga saat ini mengalami
perjalanan yang cukup panjang. Demikian pula dengan konsep pembangunan ekonomi
wilayah. Untuk menjelaskan kedua konsep besar tersebut pada bagian ini dijelaskan
secara singkat perkembangan konsep desentralisasi maupun kebijakan yang mengatur
desentralisasi di Indonesia.
Pada bagian selanjutnya dijelaskan pula perkembangan konsep dalam
menganalisis pembangunan wilayah. Tinjauan ini perlu dilakukan untuk memilih
paduan strategi yang komprehensif dan aplikabel.
Pada bagian akhir tinjauan pustaka ini dikonstruksikan kerangka konseptual
penelitian untuk membantu penajaman uraian dan analisis agar tetap fokus dan runtut
dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah ditentukan.
2.1. Perkembangan Konsep Desentralisasi
Dinamika pelaksanaan desentralisasi pemerintahan menimbulkan beberapa
pertanyaan penting tentang bentuk desentralisasi yang ingin dikembangkan di
Indonesia, apakah desentralisasi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia terbatas pada
desentralisasi vertikal atau termasuk juga desentralisasi horisontal (Rondinelli, 2007).
Apakah desentralisasi terpisah dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana
yang digunakan di Indonesia, atau mengikuti klasifikasi Rondinelli dan Cheema
devolusi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu penting menjadi bahan pemikiran
bersama dalam mengembangkan kebijakan desentralisasi di Indonesia.
Bentuk desentralisasi memiliki pilihan yang sangat beragam, berupa
dekonsentrasi, medebewind, devolusi atau privatisasi. Pelaksanaan kebijakan
desentralisasi ini berangkat dari asumsi bahwa kalau pemerintahan berada dalam
jangkauan masyarakat, maka pelayanan lebih cepat, hemat, murah, responsif,
akomodatif, inovatif, dan produktif.
Semua pihak mengakui bahwa otonomi diperlukan, namun upaya
mewujudkannya tidaklah “semudah membalik telapak tangan.” Bahkan, sekalipun
kesepakatan telah dicapai melalui undang-undang atau peraturan pemerintah, namun
dalam praktek otonomi tetap sulit untuk diwujudkan.
Selama kurun waktu dua periode pelaksanaan otonomi daerah yaitu di era UU
No.22/1999 dan UU No.32/2004, ternyata model otonomi daerah yang diberlakukan
masih belum final dan belum menemukan pola yang mapan. Sekarang sedang muncul
perspektif tentang kemungkinan akan diakomodasinya konsep desentralisasi asimetris,
devolusi dan asas privatisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di
Indonesia, prinsip-prinsip otonomi yang dianut dan dasar peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasannya senantiasa dilakukan perubahan. Dinamika
konfigurasi hubungan pusat-daerah sejak masa pendudukan Belanda sampai sekarang
Tabel 2.1. Konfigurasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Kurun Waktu Prinsip Otonomi dan
Landasan Yuridis
Implementasi
1903 Sentralisasi
Decentralisatie Wet 1903;
Local Radenordonantie No.181 Thn 1905
Tidak terlaksana
1942-1945 Sentralisasi
Osamu Sirei No.27 Thn 2602 (1942)
Tidak terlaksana
1945 sd. 1959 Demokratis, Otonomi Luas, Desentralisasi
UU No.1 Tahun 1945 UU No.22 Tahun 1948 UU No.1 Tahun 1957
Tidak terlaksana
1959 sd. 1966 Otoriter, Sentralistik,Dekonsentrasi Penpres No.18/1959
1971 sd. 1998 Otoriter, Sentralistik, Dekonsentrasi TAP MPR No.IV/1973
UU No.5/1974 UU No.5/1979
Tidak Terlaksana
1998- sekarang Demokratis, Otonomi Luas, Desentralisasi
Pada satu sisi, kebijakan desentralisasi membawa nuansa baru dalam tata kelola
pemerintahan. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya transfer dana perimbangan
dari pusat ke daerah, semakin besarnya diskresi daerah dalam menetapkan kebijakan
terkait dengan kepentingan lokal.
Namun di sisi lain, kebijakan desentralisasi juga tak luput dari serangkaian
permasalahan. Munculnya pembengkakan organisasi daerah, terjadinya oligarki politik
oleh elit lokal maupun gejala pembangkangan daerah terhadap pemerintah pusat
Secara akademik Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memiliki
landasan paradigma yang tegas dan jelas tentang sistem pemerintahan itu sendiri,
termasuk landasan paradigma sistem administrasi dan manajemen publik. Sementara
itu, secara praktis Undang-undang ini juga memerlukan peraturan pelaksanaan berupa
Peraturan Pemerintah (memberi beban yang relatif banyak untuk menyusun peraturan
pemerintahnya karena terlalu banyak aspek yang diatur) sehingga memperlambat
pelaksanaannya.
Kritikan lain yang paling sering dilontarkan oleh pemerintah daerah adalah
bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan usaha Pemerintah untuk
melakukan resentralisasi, karena mengurangi secara signifikan isi otonomi daerah
terutama untuk daerah kabupaten/kota yang telah memperolehnya secara sangat luas
pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999.
Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
telah memberikan otonomi yang jauh lebih luas kepada daerah. Hal ini terjadi karena
pemahaman tentang otonomi di negara kesatuan belum dirumuskan secara jelas
sehingga banyak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda, pertanyaan dan bahkan
kecurigaan.
Adapula yang berpandangan bahwa Undang-Undang ini dilihat sebagai milik
Departemen Dalam Negeri. Akibatnya departemen sektoral merasa tidak harus
memperhatikannya apalagi isi Undang ini tidak sejalan dengan
Undang-Undang sektoral yang masih berlaku. Undang-Undang-undang tentang pemerintahan daerah
sebagai “lex spesialis”. Departemen sektoral lebih memperhatikan Undang-undang
sendiri daripada Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Isu ini sangat terkait
dengan kurangnya fasilitasi kepada semua stakeholders baik di pusat maupun di
daerah.
Akibat beragamnya penafsiran terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun
UU Nomor 32 Tahun 2004, tidak sedikit daerah otonom melakukan improvisasi yang
justru kontra produktif terhadap maksud awal pencapaian tujuan desentralisasi yang
dibingkai dalam regulasi tersebut.
Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia memang menghasilkan cerita yang
beragam di daerah (Dwiyanto, 2003a and Dwiyanto, 2003b). Walaupun secara umum
desentralisasi mampu memperbaiki pelayanan publik tetapi juga menimbulkan banyak
masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Pengalaman mengenai kegagalan desentralisasi juga banyak ditemukan di
negara-negara lain (Rondinelli, 2007; Fleurke and Hulst, 2006). Karena itu tidak
mengherankan kalau dalam beberapa tahun terakhir muncul pertanyaan yang serius
ketika harapan tentang hasil yang dijanjikan desentralisasi tidak terwujud.
Pertanyaan yang dikemukakan oleh Turner dan Hulme (1997), misalnya,
menyoal tentang desentralisasi itu apanya yang salah, teori atau prakteknya.
Pertanyaan Turner dan Hulme tentang sumber masalah dari pelaksanaan desentralisasi,
yaitu apakah teori atau praktek, mengingatkan semua pihak secara terbuka dan kritis
Persoalan desentralisasi dapat muncul dari keduanya, atau bahkan interaksi
antar keduanya. Subtansi yang kabur dalam peraturan perundangan dapat menjadi
sumber masalah dalam pelaksanaan desentralisasi sebagaimana juga kegagalan untuk
melaksanakan desentralisasi sesuai semangat dari peraturan perundangan yang
berlaku. Bahkan, subtansi yang salah dalam pengaturan dapat memicu implementasi
yang salah pula.
Banyak penelitian membuktikan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan
kebijakan desentralisasi menimbulkan masalah dalam implementasi (Dwiyanto,
2003a). Akibatnya, pelaksanaan desentralisasi tidak dapat berjalan sebagaimana
diharapkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
Apa yang terjadi selama ini menunjukkan pentingnya membuat kebijakan
desentralisasi yang jelas dan benar, karena kegagalan untuk membuat kebijakan yang
tepat dan jelas dapat memicu bukan hanya kegagalan implementasi tetapi juga
kegagalan untuk mencapai tujuan dari kebijakan desentralisasi itu sendiri. Untuk itu,
upaya yang serius dan menyeluruh perlu dilakukan untuk meninjau kembali berbagai
pengaturan yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai menimbulkan
kerancuan dalam memahami tujuan kebijakan desentralisasi dan dalam pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia.
Serangkaian koreksi terhadap persoalan baik yang sistemik ataupun yang
kontekstual diharapkan dapat mewujudkan desentralisasi yang mampu membawa
Munculnya paradigma New Public Management (NPM) yang mendoktrinkan
agar dilakukan desentralisasi dalam tubuh pemerintahan, membawa implikasi bahwa
isu desentralisasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengalaman tentang keberhasilan di luar negeri seperti di Inggeris, New Zealand,
Australia, Amerika Serikat dan Kanada menumbuhkan keyakinan bahwa desentralisasi
membawa perbaikan bagi kinerja pemerintah sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Banyak pihak berharap bahwa desentralisasi mampu memperbaiki kualitas lingkungan,
pemberian pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas pegawai daerah
(Kauneckis & Anderson, 2006).
Beberapa pakar yakin bahwa ada banyak keuntungan yang diperoleh dari
desentralisasi. Melalui desentralisasi, kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih
cepat terwujud karena pemerintah daerah akan lebih fleksibel bertindak dalam respons
perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Desentralisasi juga lebih
melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ketimbang menunggu
keputusan dari pemerintah pusat sehingga kehidupan demokrasi lebih terwujud, lebih
memberi ruang untuk berkreasi dan berinovasi, dan menghasilkan semangat kerja,
komitmen dan produktivitas yang lebih tinggi (Osborne & Gaebler, 1993; Pollit,
Birchall dan Putman, 1998).
Keunggulan desentralisasi yang lainnya adalah preferensi penduduk lebih
terakomodasikan (Oates 1972; Manin, Przeworski and Stokes 1999), tingkat
akuntabilitas ditingkat lokal akan menjadi lebih baik karena lebih mudah
setempat (Peterson 1997), manajemen fiskal menjadi lebih baik (Meinzen-Dick, Knox
and Gregorio 1999), dan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jaminan pasar akan
menjadi lebih baik (Wibbels 2000). Pendek kata, cukup banyak literatur sangat optimis
bahwa tingkat efisiensi menjadi lebih baik, tingkat korupsi juga akan berkurang
(Fisman, dkk. 2002), dan akan terjadi peningkatan demokratisasi dan partisipasi
(Crook and Manor 1998).
Meski banyak literatur yang mengandalkan desentralisasi, namun kenyataan
atau pengalaman empiris tidak selamanya demikian. Kajian Treisman (2000), Oyono
(2004) menyebutkan bahwa dalam implementasi desentralisasi didapati juga hal-hal
seperti kinerja pemerintah daerah tidak meningkat, partisipasi dan demokratisasi juga
tidak membaik. Justru desentralisasi meningkatkan kesempatan untuk “rent-seeking”
dan korupsi.
Meski demikian, desentralisasi tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih dari itu yaitu memberikan kesempatan belajar
berdemokrasi, berpartisipasi, membangun kepercayaan dan tanggungjawab,
memberdayakan masyarakat di daerah, dan menjamin pelayanan publik yang lebih
luas dan baik.
Desentralisasi adalah kata dengan multi makna. Menurut Conyers (1984: 187),
hampir setiap orang mengetahui arti desentralisasi secara umum, namun perbedaan
sering timbul dalam mendefinisikan desentralisasi secara tepat karena desentralisasi
memiliki banyak aspek, sehingga konteks pembicaraan menjadi sangat penting dalam
desentralisasi, Rondinelli (1989: 9-15) sebagaimana dikutip Cohen and Peterson
(1995: 10) memberikan pemahaman tentang desentralisasi dalam kaitannya dengan
politik, wilayah, pasar dan administrasi.
Di samping itu, desentralisasi juga merupakan suatu peristilahan yang kaya
dengan konsep-konsep dan bersifat dinamis. Fesler (1964) mengemukakan,
“desentralisasi adalah suatu terminologi yang kaya akan makna konseptual dan makna
empiris, terminologi ini dapat menunjukkan dan menggambarkan suatu perubahan
yang ideal dan suatu perubahan yang moderat dan bertahap”.
Dalam beberapa dekade terakhir ini, mengenai defenisi desentralisasi dan
identifikasi bentuk-bentuk dan tipe-tipe desentralisasi. Salah satu yang terpenting
adalah elaborasi konsep pada awal tahun 1980-an yang merupakan hasil kerja
Rondinelli dkk, (1983: 14). Menurut mereka, definisi desentralisasi yang relatif luas
dan mencakup seluruh fenomena organisasi adalah pendelegasian kewenangan untuk
merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola urusan publik dan tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi kepada organisasi atau lembaga pada tingkatan yang
lebih rendah.
Berdasarkan tujuannya, Rondinelli (1989) mengklasifikasikan desentralisasi
menjadi empat bentuk, yaitu desentralisasi politik, desentratisasi spasial, desentralisasi
pasar, dan desentralisasi administratif. Desentralisasi potitik, digunakan oleh pakar
ilmu politik yang menaruh perhatian di bidang demokratisasi dan masyarakat sipil
untuk mengidentifikasi transfer kewenangan pengambilan keputusan kepada unit
perwakilan rakyat. Dengan demikian Desentralisasi poiltik juga melimpahkan
kewenangan pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah,
mendorong masyarakat dan perwakilan mereka untuk berpartisipasi di dalam proses
pengambilan keputusan. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat
bawahan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara
independen, tanpa intervensi dan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.
Desentralisasi politik bertujuan memberikan kekuasaan yang lebih besar dalam
pengambilan keputusan kepada masyarakat melalui perwakilan yang dipilih oleh
masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan
dan implementasi kebijakan. Biasanya desentralisasi dalam bidang politik merupakan
bagian dan upaya demokratisasi sistem pemerintahan. Litvack dkk. (1998) juga
menjelaskan sebagai berikut.
Administrative Decentralization seeks to redistribute authority, responsibility, and financial resources for providing public services among different levels of government. It is the transfer of responsibility for planning, financing, and managing certain functions from the central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or levels government, semi-autonomous public authorities or corporations, or area wide, regional, or functional authorities.
Desentralisasi pasar, umumnya digunakan oleh para ekonom untuk
menganalisis dan melakukan promosi barang dan jasa yang diproduksi melalui
mekanisme pasar yang sensitif terhadap keinginan dan melalui desentralisasi pasar
barang-barang dan pelayanan publik diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah,
Desentralisasi administratif, memusatkan perhatian pada upaya ahli hukum
dan pakar administrasi publik untuk menggambarkan hierarki dan distribusi
kewenangan serta fungsi-fungsi di antara unit pemerintah pusat dengan unit
pemerintah non pusat (sub-national government).
Rondinelli (1981:133) maupun Cheema and Rondinelli (1983: 18) membagi
desentralisasi ke dalam empat bentuk, yaitu dekonsentrasi; delegasi atas organisasi
semi-otonomi atau parastaral; devolusi; dan privatisasi (transfer fungsi dan pemerintah
ke lembaga non-pemerintah). Sementara itu, Mawhood (1983) menyatakan bahwa
desentralisasi adalah pembentukan suatu badan hukum yang terpisah dan pemenintah
pusat, di mana lembaga perwakilan lokal memberikan kewenangan formal untuk
mengambil keputusan di dalam masalah-masalah publik. Basis politiknya bersifat
lokalitas dan bukan merupakan kepanjangan tangan pegawai negeri. Ruang lingkup
kewenangannya terbatas, tetapi didalam ruang lingkup kewenangan tersebut mereka
mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang dilindungi oleh hukum dan hanya
dapat dibatalkan oleh perundang-undangan yang baru.
Untuk menjelaskan tentang perbedaan antara dekonsentrasi dengan
desentralisasi, Maddick (1963: 23) mengatakan bahwa desentralisasi merupakan
pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun
fungsi residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan
dekonsentrasi merupakan “the delegation of authority adequate for the discharge of
specified functions to staff of a central department who are situated outside the
menciptakari “local self government” dan dekonsentrasi menciptakan “local state
government” atau “field administration”. Dari pengertian desentalisasi yang
dikemukakan oleh Maddick di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi
mengandung dua elemen pokok, yaitu melalui desentralisasi di satu pihak dilakukan
pembentukan daerah otonom dan di lain pihak dilakukan penyerahan kekuasaan secara
hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci
maupun yang dirumuskan secara umum.
Peristilahan desentralisasi yang dinamis mengalami perkembangan dan
perluasan arti. Desentralisasi tidak hanya diartikan sebagai pelimpahan kewenangan
dari Pusat kepada Daerah, tetapi juga diartikan pelimpahan kewenangan dan
pemerintah kepada sektor swasta. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh Litvack
dkk. (1998:) yang memberi pengertian desentralisasi sebagai berikut.
Decentralization—the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subcordinate or quasi independent government or organization or the private sector—covers a broad rang of concepts. Each type of decentralization—political, administrative, fiscal, and market—has different characteristics, policy implications, and conditions for success.
Pergeseran paradigma desentralisasi yang lebih memilih bentuk devolusi,
menempatkan daerah otonom kabupaten/kota sebagai daerah otonom murni (split
model). Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kabupaten/kota dilaksanakan atas
asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pada provinsi asas desentralisasi dan asas
wilayah administrasi, dan dengan demikian pemerintah propinsi melakukan fungsi
otonomi dan fungsi dekonsentrasi.
Sebagai daerah otonom Provinsi dan Kabupaten/kota adalah dua bentuk
otonomi yang setara, tidak hierarkhis atau subkordinasi. Dalam kedudukan sebagai
daerah otonom, keduanya dapat melakukan kerjasama dalam hubungan yang setara.
Selain menjadi daerah otonom, Propinsi juga berkedudukan sebagai wilayah
administratif yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pada kedudukan sebagai wakil Pemerintah
Pusat, kemudian membentuk hubungan provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat
hirarkhis karena propinsi menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan,
pengawasan terhadap Kabupateri/Kota.
Studi berbagai kepustakaan menunjukkan bahwa desentralisasi dan sentralisasi
dilaksanakan secara simultan dalam suatu negara baik negara berkembang maupun
negara maju (Cheema dan Rondinelli, 1983; Conyers, 1983; Deakin, 1985). Hal ini
juga ditunjukkan dalam perdebatan antara Slater (1989) dengan Rondinelli (1990)
mengenai implikasi potitik dan desentralisasi. Rondinelli tidak sependapat dengan
Slater yang menyatakan bahwa sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang
saling bertentangan dan bentuk organisasi politik dan administrasi yang lepas satu
sama lain. Menurut Rondinelli, seluruh pemerintahan memiliki fungsi yang merupakan
campuran antara sentralisasi dan desentralisasi.
Kebanyakan analisis kebijakan desentratisasi memfokuskan diri pada
sentralisasi atau desentralisasi seratus persen. Hubungan antara sentralisasi dan
desentralisasi sebenarnya lebih kompleks, seperti yang dikemukakan oleh Fesler
(1968), Cohen et. all. (1981) Faltas (1982), Apthorpe dan Conyers (1982).
Mengingat hubungan yang demikian kompleks, sangat penting untuk
memahami bahwa sentralisasi dan desentralisasi lebih tepat dilihat sebagai suatu
perubahan (variable) ketimbang keadaan yang statis (attribute), dan tidak realistis
apabila sistem pemerintahan sentralistis sepenuhnya atau sistem pemerintahan
desentralistis diterapkan sepenuhnya. Dengan demikian, jangan melihat desentralisasi
dan sentralisasi sebagai hal yang dikotomis, tetapi lebih realistis memandang
desentralisasi dan sentralisasi sebagai serangkaian kontinum.
Sampai sejauh ini, dan berbagai definisi mengenal pengertian desentralisasi yang
diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa ada persamaan mengenai obyek
yang didesentralisasikan, yaitu fungsi dan masalah publik; kewenangan, kekuasaan,
atau kebebasan bertindak dengan tidak bertentangan terhadap perencanan,
pengambilan keputusan, dan pengelolaan; tanggung jawab; dan pembiayaan
(sumber-sumber). Dengan demikian, terlihat bahwa pembagian urusan pemerintahan
sebenarnya merupakan salah satu substansi atau elemen inti dan proses desentralisasi.
Elemen desentralisasi lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Smith (1985) meliputi
pembagian wilayah; kewenangan (politis dan birokratis); peran dan fungsi. Program
desentralisasi di Inggris merupakan salah satu bagian dan banyak debat besar tentang
pembagian kewenangan dan fungsi di antara semua tingkat politik dan administrasi
Sehubungan dengan itu, pengertian desentralisasi dalam kajian akademis ini
adalah penyerahan urusan pemerintahan dan Pusat kepada Daerah atau yang lazim
disebut sebagai desentralisasi teritorial. Pengertian tersebut juga dipergunakan dalam
Pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen dan berbagai UU tentang pemerintahan
daerah.
Menurut Hoessein (1993) desentralisasi yang dimaksud dalam UUD 1945 Pasal
18 dan berbagai perundang-undangan yang mengatur pemenintah daerah terbatas pada
desentralisasi teritorial dan desentralisasi pemerintahan.
Dari uraian di atas terlihat bahwa kajian peran dan fungsi termasuk dalam kajian
administrasi. Sementara tergambar dalam “preface” buku editorialnya, Farazmand
mengutarakan bahwa “As a worldwide phenomenon, administrative reform has been a
widespread challenge to almost all national and sub-national governments around the
globe”.
Dalam kajian akademis fokus desentralisasi umumnya pada kajian kedudukan,
kewenangan, peran dan fungsi daerah otonom. Keberhasilan pembangunan di negara
maju memicu munculnya gelombang kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup
dalam bidang perekonomian dan sosial. Hal ini menjadikan sebagai agenda untuk
memajukan negara dan bangsa.
Pemerintah diharuskan memiliki inisiatif untuk membangun sistem yang lebih
efisien, efektif, dan bahkan lebih responsif. Selain itu, didasarkan pada asumsi bahwa
birokrasi pemerintah selayaknya dapat memainkan peran dan fungsi utama dalam
Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan keputusan politik yang sangat
mendasar yang telah mengalihkan sentralisme dari pusat ke kekuasaan di daerah
kabupaten/kota. Pengalihan sentralisme dari pusat ke kabupaten/kota mengakibatkan
terjadi sentralisasi pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan di
tingkat kabupaten/kota. Dampak politis yang cukup nyata dari hal tersebut adalah
terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang berada di bawah
kabupaten/kota dalam menghadapi masyarakat/warga atau publiknya.
Otonomi daerah yang sangat luas dan bertanggungjawab melalui tuntutan
sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan politik yang digerakkan oleh berbagai elemen
masyarakat yang menuntut koreksi total dan fundamental terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang sangat desentralistik. Hoessein (1993) menggambarkan
pencanangan kebijakan memperkuat otonomi daerah sebagai hasil bekerjanya dua
kekuatan besar. Pertama, kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan yang
melanda tanah air dengan tuntutannya demokratisasi di segala bidang kehidupan.
Kedua, kekuatan supra nasional berupa globalisasi dengan berbagai konsekuensi dan
implikasinya yang memerlukan tanggap dalam negeri melalui proses penyesuaian
terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan demokratik di tingkat lokal.
Implikasinya terjadi perubahan landasan hukum mendasar dalam tata pemerintahan
yang membawa dampak pada perubahan berbagai aspek dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah mulai dari tataran filosofi hingga kepada tataran praktis.
Berdasarkan hal tersebut, secara makro perlu diikuti secara mikro pada
mendasar di dalam peran dan fungsi merupakan bentuk pemerintahan lokal secara
mikro yang diharapkan menjadi motor penggerak dan lini terdepan dalam
pemerintahan dan pelayanan.
Untuk konteks Indonesia, yang memiliki kompleksitas geografis, suku/etnis,
agama, budaya, nampak tidak ada pilihan lain yaitu sistem pemerintahan yang
desentralistis. Sistem ini akan lebih responsif terhadap tuntutan kebutuhan, situasi dan
kondisi lokal, sementara pemerintah pusat akan memusatkan perhatiannya pada hal-hal
yang bersifat strategis dan urusan-urusan lintas propinsi.
Mencermati uraian perkembangan konsep desentralisasi, maka tidak berlebihan
kiranya pandangan Fakih et.all (2001) bahwa sebuah kebijakan senantiasa
mengandung 3 (tiga) dimensi, yakni content atau substansi muatan hukum sebuah
kebijakan publik, struktur atau pelembagaan hubungan antar aktor dalam sebuah
kebijakan publik maupun kultur atau nilai-nilai yang dianut dalam sebuah kebijakan
publik sebagai satu kesatuan. Demikian halnya kebijakan desentralisasi, ketiga unsur
tergambar dari muatan pasal-pasal yang dituangkan dalam peraturan perundangan
tersebut sebagai content, struktur dan sebagai kultur.
2.2. Perkembangan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia
Sejarah pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan selalu menghadirkan
otonomi sebagai sistem bernegara. Dalam setiap UUD yang pernah berlaku selalu
terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia.
Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UUD, hampir
satu program kerjanya. Amanat konstitusi tersebut diterjemahkan dan
diimplementasikan oleh pemerintah yang silih berganti secara berbeda-beda dalam hal
gradasi, skala, dan besaran subtansi desentralisasi, sebagai hasil sintesis dari kondisi
sosial politik pada masanya.
Setidaknya, sampai kini, tujuh undang-undang yang mengatur tentang
pemerintahan daerah dengan masing-masing corak dan kecenderungan, yaitu: UU No.
1 Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965,
UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004.
Dinamika kebijakan desentralisasi serta dampaknya terhadap berbagai aspek
dalam pembangunan daerah juga telah banyak dikaji. Secara umum, dalam perjalanan
sejarah kebijakan desentralisasi selalu saja terjadi tarik menarik antara dua ekstrim
sentralisasi dan desentralisasi.
Ketika reformasi bergulir, di mana desentralisasi merupakan aspirasi yang
masif dan intensif disuarakan rakyat sebagai antitesis langgam pemerintahan yang
sangat sentralistis di masa Orde Baru, lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 yang sangat
desentralistis. Sayangnya, sebagaimana dikemukakan desentralisasi yang dimaksud
UU No. 22 Tahun 1999 dipahami dan dilaksanakan secara kebablasan oleh elit di
daerah.
Sebagai koreksi atas hal itu lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 yang ternyata
merupakan pengaturan yang sama sekali baru dan dinilai banyak kalangan merupakan
“resentralisasi” atas kewenangan otonomi yang sempat diatur dalam UU No. 22 Tahun
Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (khususnya UU nomor 22 Tahun 1999
dan UU nomor 32 Tahun 2004).
Studi yang dilakukan Mudrajad Kuncoro yang dibukukan di bawah judul
Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang
(2004) mengungkap sejumlah fakta empirik terkait praktika desentralisasi di Indonesia.
Berbagai studi kasus yang diangkat dalam buku tersebut membuka nuansa pemahaman
bahwa otonomi senantiasa membawa peluang sekaligus tantangan.
Perkembangan kebijakan desentralisasi yang cukup intensif ternyata kurang
baik dalam membangun sistem yang padu. Revisi kebijakan dari UU Nomor 22 Tahun
1999 ke UU Nomor 32 Tahun 2004 misalnya, dilakukan dengan sangat tergesa-gesa
dan nyaris menutup ruang partisipasi publik dalam proses penyusunannya. Bersamaan
dengan itu terjadi perubahan (amandemen) konstitusi, yang belakangan dinilai masih
menyimpan banyak kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kerancuan dalam
sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.
Proses revisi yang terkesan tergesa-gesa digabung dengan proses amandemen
konstitusi yang belum tuntas/belum sempurna menyebabkan UU No. 32 Tahun 2004
mengandung problematik yang cukup serius. Semakin problematik jika proses
penyusunan UU No 32 Tahun 2004 didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan
otonomi luas di bawah UU No. 22 Tahun 1999 akan mengancam NKRI dan
menyebabkan disintegrasi nasional, KKN baru yang menghasilkan “raja-raja kecil” di
daerah, ekonomi biaya tinggi, dan atas nama itu semua diperlukan “resentralisasi.”
UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dilakukan hendaknya membawa kembali
desentralisasi pada titik keseimbangan (tentunya keseimbangan antar pelbagai dimensi
hubungan pusat-daerah).
2.3. Konsep Pembangunan Ekonomi Wilayah
2.3.1. Central Places Theory
Teori central places awalnya dikembangkan di Jerman pada tahun 1933 oleh
Christaller. Sejak saat itu teori ini mulai digemari utamanya dalam konteks
pembangunan wilayah di berbagai negara.
Teori ini berbicara mengenai pengambilan keputusan di mana sebaiknya lokasi
dari lembaga penyedia layanan publik maupun layanan privat (misalnya: pasar,
sekolah, universitas, rumah sakit) ditempatkan agar dapat melayani konsumen secara
optimal.
Teori ini bertujuan untuk menjelaskan pilihan lokasi baik oleh privat dan atau
pemerintah, serta untuk tujuan intervensi pemerintah yang dibutuhkan agar tempat
lokasi layanan dapat memberikan service yang optimum (concerning supply of
services to the population and minimising costs).
Hipotesis pokok yang dianut adalah, pilihan atas lokasi lembaga penyedia
layanan ditentukan oleh dua faktor yakni: 1) kapasitas minimum yang dimiliki
lembaga penyedia jasa layanan hendaknya masih dalam batas yang menguntungkan
dari segi pasar/ekonomis; 2) jarak maksimum lokasi yang masih memungkinkan bagi
Menurut teori ini, paduan antara jarak minimum dan maksimum menentukan
lokasi dan jenis kegiatan perdagangan yang dibutuhkan. Dengan demikian,
terbentuklah hirarki lokasi dan jenis kegiatan yang sesuai dilaksanakan di lokasi
tersebut.
Sebagai contoh, pusat desa cocok untuk menyediakan barang-barang yang
dibutuhkan setiap hari, kota menengah cocok untuk menyediakan kebutuhan periodik,
dan kota besar sebagai pusat utama lebih cocok untuk kebutuhan-kebutuhan luxury.
Konsekuensinya, dalam melakukan perencanaan wilayah, prinsip-prinsip di
atas diaplikasikan untuk memutuskan lokasi penyediaan layanan. Seperti lokasi untuk
Sekolah Dasar, didasarkan pada jumlah murid yang akan masuk dan jarak yang cocok
untuk murid tersebut pergi ke sekolah.
Bagi pemerintah hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan
pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar memberikan akses yang luas bagi
para warganya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.
Contoh penerapan model ini, misalnya, di Malawi, di mana pusat layanan
perdesaan didirikan untuk melayani sekitar 20,000 - 40,000 warga, yang tinggal sejauh
5 sampai dengan 10 mil dari lokasi pusat layanan. Layanan yang disediakan meliputi:
sekolah, rumah sakit, pasar musiman, maupun pengolahan hasil pertanian.
Melalui gambaran teoritis di atas, maka teori central places ini merupakan
salah satu upaya untuk mengkompromikan antara kebutuhan akan biaya yang
minimum dan tanggungjawab penyediaan layanan yang sejauh mungkin dapat diakses
Namun demikian, konsep ini cenderung melakukan sentralisasi layanan lebih
daripada yang dibutuhkan. Tampaknya lokasi yang terdesentralisasi lebih sesuai untuk
mengurangi kecenderungan tersebut, selain itu sarana dan prasarana yang dibangun
hendaknya sedapat mungkin menggunakan bahan baku lokal.
2.3.2. The Growth Pole Theory
Konsep pusat pertumbuhan (growth pole) ini diperkenalkan sejak 1949 oleh
seorang ekonom Perancis bernama Francois Perroux. Pandangan Perroux sebagaimana
dikutip oleh Darwent (1969) pada awalnya terlepas dari konteks geografis atau
persoalan keruangan.
Nuansa konsep growth pole lebih berorintasi pemikiran ekonomi dibanding
kewilayahan. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dari definisi yang diberikan terhadap
growth pole itu sendiri sebagai “... centers (poles or foci) from which centrifugal forces
emanate and to which centripetal forces are attracted. Each center being a center of
attraction and repulsion has its proper field which is set in the field of all other
centers” (Darwent, 1969: 5).
Konsep yang semula didasari pemikiran ekonomi tersebut semakin dilekatkan
dengan konteks kewilayahan yang mengadopsi pemikiran bahwa satu wilayah
geografis adalah satu skala ekonomi. Dalam konteks pemikiran inilah dikonsepsikan
adanya tiga tipe perwilayahan ekonomis, yaitu homogenous, polarized, dan planning
regions (Boudeville, 1966).
Homogenous merupakan suatu perwilayahan yang terpusat dengan adanya satu