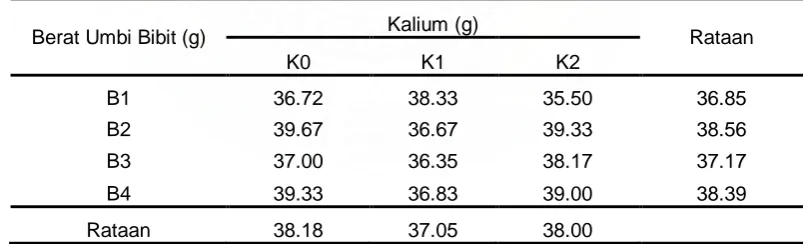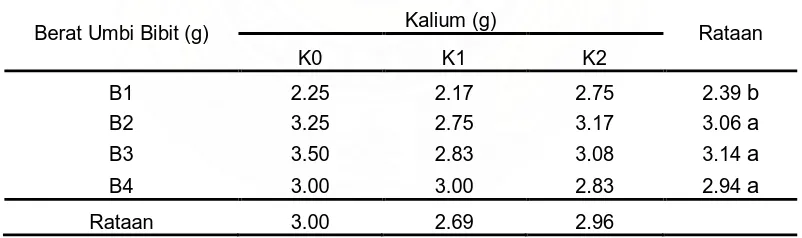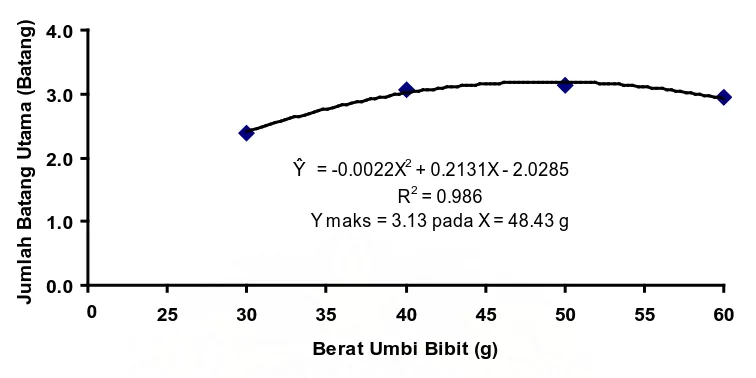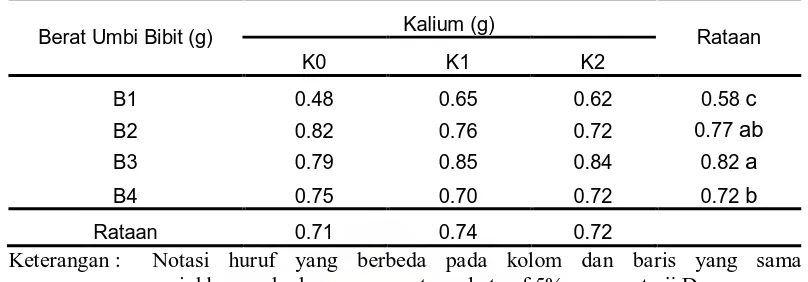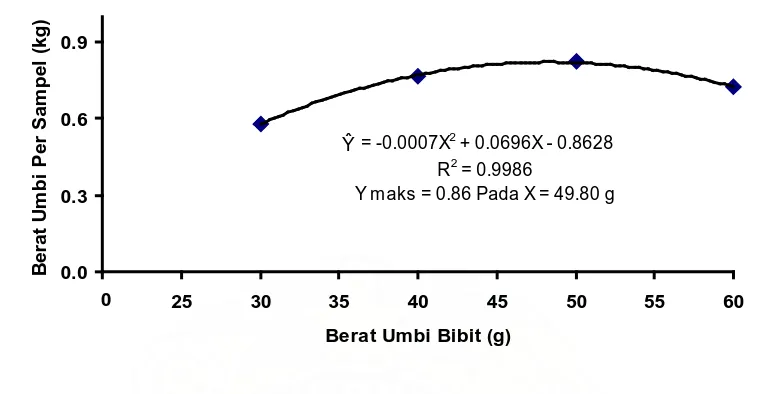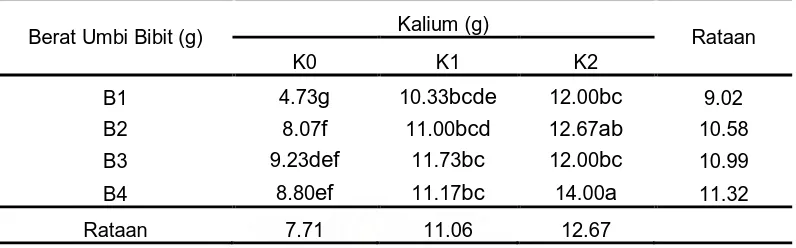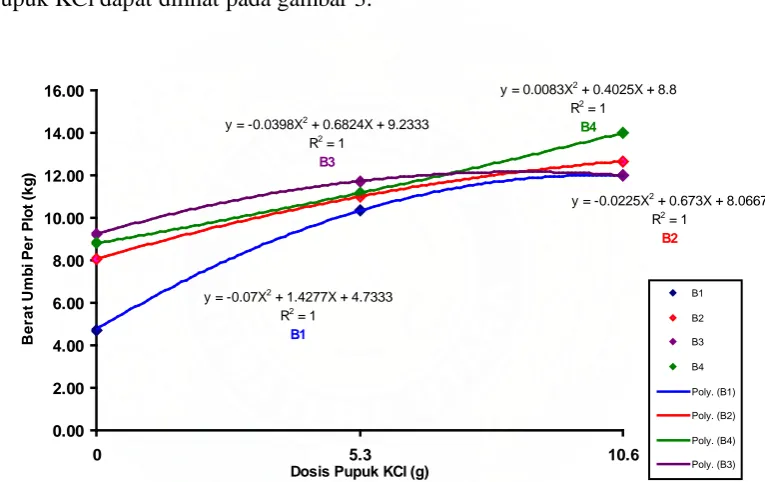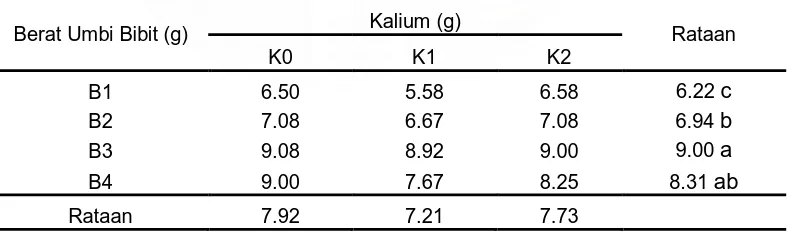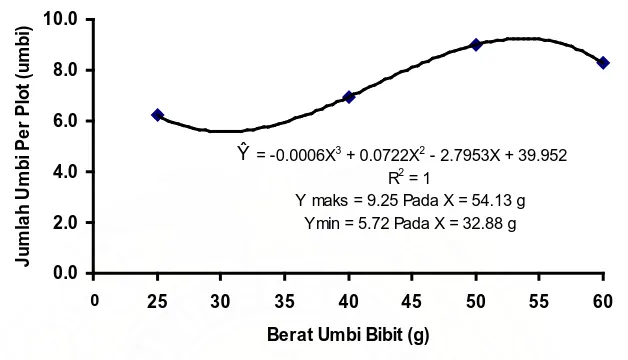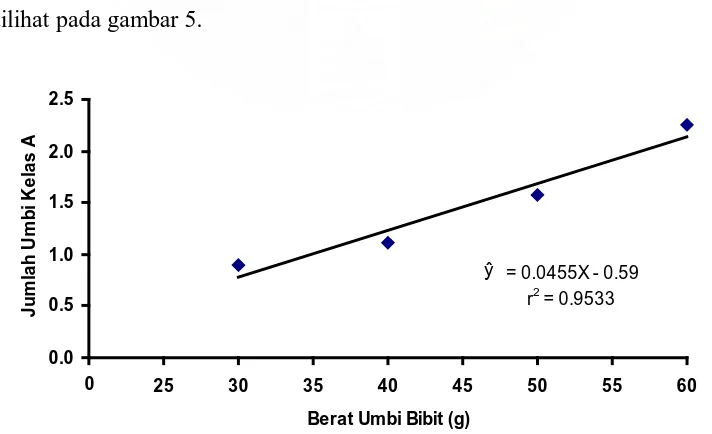PENGARUH BERAT UMBI BIBIT DAN DOSIS PUPUK KCl
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI
KENTANG (Solanum tuberosum L.)
SKRIPSI
Oleh :
APRIIN BUKIT
030301004
BDP – AGR
PROGRAM STUDI AGRONOMI
DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
PENGARUH BERAT UMBI BIBIT DAN DOSIS PUPUK KCl
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI
KENTANG (Solanum tuberosum L.)
SKRIPSI
Oleh :
APRIIN BUKIT
030301004
BDP – AGR
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Dapat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara
PROGRAM STUDI AGRONOMI
DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
Judul Skripsi : Pengaruh Berat Umbi Bibit dan Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kentang (Solanum tuberosum L)
Nama : Apriin Bukit
NIM : 030301004
Departemen : Budidaya Pertanian Program Studi : Agronomi
Disetujui oleh Komisi Pembimbing
( Ir. Asil Barus, MS ) ( Ir. Jasmani Ginting, MP Ketua Anggota
)
Mengetahui
Ketua Jurusan Ir. Edison Purba, Ph.D.
ABSTRACT
The objective of the research was to know the response of tuber weight and potassium fertilizer of growth and production of potato. The research was done in Ujung sampun, Tanah Karo North Sumatera above ±1250 metres sea level rise from Agustus to November 2007. The research used using Randomized Block Design Factorial with two factors. The first factor was tuber weight with four levels namely : 25-30 g (B1); 35-40 g (B2); 45-50 g (B3); 55-60 g (B4). The second factor was potassium fertilizer with three levels namely : 0 kg (K0); 5.3 g (K1); 10.6 g (K2). The result of the research showed that, especial bar, tuber weight/sample, tuber weight/plot, tubers total/sample, tubers total class A, B, C, D and production/hectare, tuber weight is significant on but not significant on plant hight. Potassium fertilizer showed significant on tuber weight/plot, tubers total class C, D but not significant on plant height, aspecial bar, tuber weight/sample, tubers total/sample, tuber total class A, B and production/hectare. The interaction between tuber weight and potassium fertilizer showed significant on tuber weight/plot but not significant on plant height, aspecial bar, tuber weight/sample, tubers total/sample, tuber total class A, B, C, D and production/hectare.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kentang. Penelitian di laksanakan di Desa Ujung Sampun Tanah Karo yang berada + 1250 m dpl dari bulan Agustus sampai November 2007. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan dua faktor perlakuan. Faktor pertama adalah berat umbi bibit dengan empat taraf yaitu : 25-30 g (B1); 35-40 g (B2); 45-50 g (B3); 55-60 g (B4) dan faktor kedua adalah dosis pupuk KCl dengan tiga taraf yaitu : 0 kg (K0); 5.3 g (K1); 10.6 g (K2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap jumlah batang utama, berat umbi per sampel, berat umbi per plot, jumlah umbi per sampel, jumlah umbi kelas A, B, C, D dan produksi per hektar namun tidak nyata pada tinggi tanaman. Perlakuan dosis kalium berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot, jumlah umbi kelas C, D namun tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah batang utama, berat umbi per sampel, jumlah umbi per sampel, jumlah umbi kelas A, B dan produksi per hektar. Interaksi antara kedua perlakuan berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot namun tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah batang utama, berat umbi per sampel, jumlah umbi per sampel, jumlah umbi kelas A, B, C, D dan produksi per hektar.
RIWAYAT HIDUP
Apriin Bukit dilahirkan di Berastagi pada tanggal 07 April 1985 dari
Ayahanda A. Bukit dan Ibunda J Br. Ginting. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4
bersaudara.
Pendidikan yang ditempuh adalah SD Methodist Berastagi lulus tahun
1996, SLTP Negeri 1 Berastagi lulus tahun 1999, SMU Methodist Berastagi lulus
tahun 2002. Terdaftar sebagai mahasiswa Agronomi Departemen Budidaya
Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003
melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. SOCFIN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
”Pengaruh Berat Umbi Bibit dan Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan
dan Produksi Kentang (Solanum tuberosum L)” yang merupakan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara, Medan.
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Ir. Asil Barus, MS sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak
Ir. Jasmani Ginting, MP sebagai anggota komisi pembimbing yang telah
memberikan bimbingan selama persiapan penelitian sampai penulisan skripsi ini.
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada
Ayahanda A. Bukit dan Ibunda J. Br Ginting yang telah membesarkan penulis
dengan segenap cinta dan kasih sayang, juga kepada kakak, abang dan adik ku
tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama melakukan
studi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua rekan – rekan stambuk 03
atas doa dan motivasi.
Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan
penulisan skripsi ini.Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.
DAFTAR ISI
TINJAUAN PUSTAKA ... 5
Botani Tanaman ... 5
Pelaksanaan Penelitian ... 15
Pengolahan Tanah ... 15
Pembuatan Bedengan dan Saluran Drainase ... 16
Pengamatan Parameter ... 19
Tinggi Tanaman(cm) ... 20
Jumlah Batang Utama ... 20
Berat Umbi Per Sampel (kg) ... 20
Berat Umbi Per Plot (kg) ... 20
Jumlah Umbi Per Sampel (umbi) ... 20
Jumlah Kelas Umbi ... 21
Produksi Per Hektar ... 21
HASIL DAN PEMBAHASAN ... 22
Hasil ... 22
Pembahasan... 40
KESIMPULAN DAN SARAN ... 48
Kesimpulan ... 48
Saran ... 48
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
No Hal.
1. Rataan tinggi tanaman pada umur 10 MST pada berbagai
perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 22
2. Rataan jumlah batang utama per sampel pada umur 8 MST pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 23
3. Rataan berat umbi per sampel pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 25
4. Rataan berat umbi per plot pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 27
5. Rataan jumlah umbi per sampel pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 29
6. Rataan jumlah umbi kelas A pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 31
7. Rataan jumlah umbi kelas B pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 32
8. Rataan jumlah umbi kelas C pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 34
9. Rataan jumlah umbi kelas D pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl ... 36
DAFTAR GAMBAR
No Hal.
1. Hubungan antara jumlah batang utama dengan berat umbi bibit ... 24
2. Hubungan antara berat umbi per sampel dengan berat umbi bibit ... 26
3. Hubungan interaksi antara berat umbi per plot dengan pupuk KCl ... 28
4. Hubungan antara jumlah umbi per sampel dengan berat umbi bibit ... 30
5. Hubungan antara jumlah umbi kelas A dengan berat umbi bibit ... 31
6. Hubungan antara jumlah umbi kelas B dengan berat umbi bibit ... 33
7. Hubungan antara jumlah umbi kelas C dengan berat umbi bibit ... 35
8. Hubungan antara jumlah umbi kelas C dengan dosis pupuk KCl ... 35
9. Hubungan antara jumlah umbi kelas D dengan berat umbi bibit ... 37
10.Hubungan antara jumlah umbi kelas D dengan dosis pupuk KCl ... 37
DAFTAR LAMPIRAN
No Hal.
1. Data Pengamatan tinggi tanaman 4 MST ... 51
2. Daftar sidik ragam tinggi tanaman 4 MST... ... 51
3. Data Pengamatan tinggi tanaman 6 MST ... 52
4. Daftar sidik ragam tinggi tanaman 6 MST ... 52
5. Data pengamatan tinggi tanaman 8 MST... ... 53
6. Daftar sidik ragam tinggi tanaman 8 MST ... 53
7. Data pengamatan tinggi tanaman 10 MST ... 54
8. Daftar sidik ragam tinggi tanaman 10 MST... ... 54
9. Data Pengamatan jumlah batang utama 4 MST ... 55
10.Daftar sidik ragam jumlah batang utama 4 MST... ... 55
11. Data Pengamatan jumlah batang utama 6 MST ... 56
12.Daftar sidik ragam jumlah batang utama 6 MST ... 56
13.Data pengamatan jumlah batang utama 8 MST... 57
14.Daftar sidik ragam jumlah batang utama 8 MST ... 57
15.Data pengamatan berat umbi per sampel ... 58
16.Daftar sidik ragam berat umbi per sampel... ... 58
17.Data pengamatan berat umbi per plot... 59
18.Daftar sidik ragam berat umbi per plot... ... 59
19.Data pengamatan jumlah umbi per sampel ... 60
20.Daftar sidik ragam jumlah umbi per sampel... ... 60
21.Data jumlah umbi kelas A (70-200 g per umbi) ... 61
23.Data jumlah umbi kelas B (40-69 g per umbi) ... 62
24.Daftar sidik ragam jumlah umbi kelas B... 62
25.Data jumlah umbi kelas C (20-39 g per umbi) ... 63
26.Daftar sidik ragam jumlah umbi kelas C ... 63
27.Data jumlah umbi kelas D (< 20 g per umbi) ... 64
28.Daftar sidik ragam jumlah umbi kelas D ... 64
29.Data produksi per hektar... 65
30.Data sidik ragam produksi per hektar... 65
31.Rangkuman uji beda rataan... 66
32.Deskripsi tanaman kentang ... 67
33.Bagan tanaman per plot ... 68
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kentang (Solanum tuberosum L) berasal dari negara beriklim dingin
(Belanda, Jerman). Kentang sudah dikenal di Indonesia (Pengalengan Lembang
dan Karo) sejak sebelum perang dunia kedua yang disebut eigenheimer. Kentang
ini merupakan hasil seleksi di Negeri Belanda pada tahun 1890, kulit umbi
kekuning-kuningan, berdaging kuning dan rasanya enak. Kelemahan dari kentang
ini adalah peka terhadap penyakit busuk daun, virus Y, dan peka terhadap
penyakit layu (Soelarso, 1997).
Kentang merupakan tanaman pangan utama dunia setelah padi, gandum
dan jagung. di Indonesia, kentang masih dikonsumsi sebagai sayur dan makanan
ringan dan belum sebagai makanan pokok pengganti beras. Walaupun demikian,
di Indonesa mulai menjamur berbagai jenis makanan “fast food” artinya yang
utama. Melihat gaya hidup modern terutama di perkotaan maka fast food ini
makin lama makin populer dan kebutuhan akan kentang makin hari makin
meningkat. Permintaan kentang yang makin meningkat memberikan peluang emas
bagi peningkatan produksi kentang di Indonesia, baik oleh petani maupun oleh
perusahaan swasta (Anonimous, 2006).
Di Indonesia kentang di panen dari lahan dataran tinggi seluas 30.000
hektar pertahun dengan hasil yang masih rendah kurang dari 11,5 ton/Hektar.
Rendahnya hasil ini terutama disebabkan oleh penggunaan bibit yang kurang
bermutu dan kurang tepatnya cara pengendalian hama dan penyakit. Di kebun
menggunakan bibit impor dan pengelolaan tanaman yang intensif dapat
menghasilkan sampai 30 ton/ hektar (Hartus, 2001).
Untuk mencapai hasil yang lebih tinggi dan mutu yang baik banyak
bibit didatangkan dari luar negeri. Pada saat ini, Impor bibit diperlukan karena
untuk menghasilkan kentang berkualitas baik diperlukan bibit yang unggul. Selain
berkualitas, bibit tersebut juga tahan penyakit. Negara pengekspor bibit tersebut
kebanyakan dari Eropa, khususnya Jerman dan Belanda. Oleh karenanya, Balai
Pengembangan Hortikultura (BPH) Lembang membuat target, yaitu dalam tempo
2-3 tahun, Indonesia sudah dapat mengurangi impor kentang. Sedangkan target
akhirnya, setelah lima tahun impor kentang tidak diperlukan lagi, kecuali untuk
mengintroduksi jenis-jenis baru (Setiadi dan Surya Fitri, 2000).
Meskipun produksi kentang terus meningkat namun masih sangat rendah
dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda (36 – 60 ton/ha). Rendahnya
produktifitas ini adalah akibat pemakaian bibit yang kurang baik, varietas
berpotensi redah, teknik bercocock tanam yang kurang baik, keadaan lingkungan
yang berbeda serta faktor pemupukan (Asandhi, 1985).
Kelemahan para petani kentang di Indonesia adalah pemborosan biaya
produksi. Petani umumnya hanya menggunakan bibit yang di buat sendiri dari
hasil panen kentang yang sebelumnya dengan memilih umbi yang baik dan
selanjutnya akan di gunakan sebagai bibit. Teknis budidaya yang dilakukan petani
sudah baik, hanya saja mereka masih terlalu boros tentang penggunaan biaya,
terutama untuk biaya pembelian pestisida dan pupuk. Bahkan, biaya tersebut
Didaerah iklim sedang umbi digunakan untuk menghasilkan bibit. Hal ini
memerlukan jumlah umbi yang sangat besar, yang sebenarnya bisa dikonsumsi
umbi kecil yang tidak sesuai untuk dipasarkan kadang digunakan tanam langsung
di lapangan (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998)
Pemindahan tanaman dari satu tempat ketempat lain merupakan pola
paling penting untuk mengembangkan pertanian di seluruh dunia. Keperluan akan
varietas unggul mendorong kita untuk mendatangkan dari daerah lain. Untuk
mendatangkan suatu tanaman ke daerah baru pastinya menempuh jarak dan waktu
yang lama (Allard, 1960).
Pemupukan KCl diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan produksi
dan kualitas umbi kentang. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian pupuk KCl
tidak selalu meningkatkan kualitas kentang. Pertumbuhan dan produksi umbi
demikian pula kualitas umbi sangat tergantung pada jenis tanah, ketersediaan K
dalam tanah dan banyaknya K diadsorbsi, juga jumlah K dalam tanah yang dapat
dipertukarkan dan takaran K yang diberikan melalui pemupukan pada tanaman
(Nainggolan dan Tarigan, 1992).
Kalium bukan merupakan komponen dari bahan organik yang membentuk
tanaman. Ia khusus terdapat dalam cairan sel dalam bentu ion – ion K+. namun
kalium ini mempunyai fungsi yang mutlak harus ada dalam metabolisme tanaman.
Kalium mempunyai pengaruh positif terhadap hasil dan kualitas tanaman.
Kebutuhan tanaman akan unsur hara ini sangat tinggi, apabila Kalium tersedia
dalam jumlah terbatas maka gejala kekurangan unsur hara akan segera nampak
ditranslokasikan ke jaringan meristematik, bila mana jumlahnya terbatas bagi
tanaman (Nyakpa, Lubis, Pulung, Amrah, Munawar, Hong dan Hakim, 1988).
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian
tentang pengaruh berat umbi bibit dan dosis pupuk kalium terhadap pertumbuhan
dan produksi kentang (Solanum tuberosum L).
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat umbi bibit dan
dosis pupuk KCl yang tepat pada kentang.
Hipotesis Penelitian
1. Berat umbi bibit berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi
kentang.
2. Pupuk KCl berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi kentang.
3. Interaksi antara berat umbi bibit dan dosis pupuk kalium berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan produksi kentang.
Kegunaan Penelitian
1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan,
yaitu petani dan pengusaha yang bergerak dalam budidaya kentang.
2. Sebagai bahan untuk penulisan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas
TINJAUAN PUSTAKA
Botani Tanaman
Menurut Sharma (2002) dalam taksonomi tanaman, kentang (Solanum
tuberosum L) mempunyai sistematika sebagai berikut :
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledoneae
Ordo : Tubiflorae
Famili : Solanaceae
Genus : Solanum
Species : Solanum tuberosum L
Kentang termasuk jenis tanaman sayuran semusim, berumur pendek, dan
berbentuk perdu atau semak. Batang kentang berbentuk segi empat atau segi lima,
tergantung pada varietasnya. Batang tidak berkayu, namun agak keras apabila
dipijat. Batang kentang umumnya lemah sehingga mudah roboh bila kena angin
kencang. Warna batang umumnya hijau tua dengan pigmen ungu. Batang kentang
bercabang–cabang dan setiap cabang ditumbuhi oleh daun–daun yang rimbun.
Permukaan batang halus, pada ruas batang tempat tumbuhnya cabang mengalami
penebalan. Batang kentang berfungsi sebagai jalan zat–zat hara dari tanah ke daun
untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun kebagian tanaman yang lain
Kentang umumnya berdaun rimbun dan letak daun berselang-seling
mengelilingi batang tanaman. Daun berbentuk oval sampai oval agak bulat dengan
ujung meruncing dan tulang-tulang daun menyirip seperti duri ikan. Warna daun
hijau muda sampai hijau tua hingga kelabu. Ukuran daun yang sedang dengan
tangkai tidak panjang (Samadi, 1997).
Bunga kentang berwarna keputihan atau ungu, tumbuh ketiak daun teratas,
dan berjenis kelamin dua. Benang sarinya berwarna kekuning–kuningan dan
melingkari tangkai putik. Putik ini biasanya lebih cepat masak
(Setiadi dan Fitri, 2000).
Kedudukan benang sari tidak sama, ada yang lebih rendah dan ada pula
yang lebih tinggi atau sama dengan putiknya. Hal inilah yang memungkinkan
terjadinya persarian sendiri. Tiap benang sari mempunyai dua kantong sari atau
kepala sari berisi tepung sari yang kering hingga dapat tersebar oleh angin melalui
pori yang terdapat pada ujungnya. Bunga kentang tersusun dalam bentuk karangan
bunga (Inflorescence) yang tumbuh pada ujung batang. Satu karangan bunga
memiliki 1-30 bunga tetapi pada umumnya 7-15 bunga untuk tiap karangan
bunga. Susunan karangan bunga ada yang sederhana dan ada yang majemuk
(Soelarso, 1997).
Kentang memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang
dapat menembus tanah sampai kedalaman 45 cm, sedangkan akar kentang
umumnya tumbuh menyebar (menjalar) ke samping dan menembus tanah
dangkal. Akar kentang berwarna keputih-putihan dan halus berukuran sangat
Umbi kentang terbentuk dari cabang samping diantara akar-akar. Proses
pembentukan umbi ditandai dengan terhentinya pertumbuhan memanjang dari
stolon yang diikuti pembesaran sehingga stolon membengkak. Menurut Burton,
1966 pada umbi kentang terdapat mata tunas yang tersusun secara spiral dan
umumnya makin ke ujung umbi makin rapat mata tunasnya ( Soelarso, 1997 ).
Buah kentang mengandung 500 bakal biji yang dapat berkembang
menjadi biji hanyalah berkisar antara 10-300 biji. Buah kentang dapat dipanen
kira-kira 6-8 minggu setelah penyerbukan (Soelarso,1997).
Biji kentang berukuran kecil dengan garis tengah lebih kurang 0,5 mm,
berwarna krem dan memiliki masa dormansi lebih kurang 6 bulan tergantung jenis
varietas yang akan digunakan (Rukmana, 2002).
Syarat Tumbuh
Iklim
Kentang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik apabila ditanam pada
kondisi lingkungan yang sesuai dengan persyaratan tumbuhnya Di Indonesia,
kentang diusahakan di daerah yang memiliki ketinggian 500–3000 m di atas
permukaan laut, dan pada ketinggian optimum antara 1000–2000 m di atas
permukaan laut (Rukmana, 2002).
Suhu yang paling tepat bagi pertumbuhan kentang adalah 20oC-240C pada
siang hari dan 80C-120C pada malam hari .suhu yang cocok selama periode
pertumbuhan dari bertunas sampai stadium primordia bunga adalah 120C-160C.
sedangkan setelah stadium primordia bunga suhu yang cocok adalah 190C-210C.
melebihi 230C, daun biasanya akan menjadi kecil dan jarak antar ruas menjadi
panjang (Soelarso, 1997).
Kelembaban tanah yang cocok untuk kentang adalah 70% dan curah hujan
yang dikehendaki kentang antara 200–300 mm tiap bulan atau rata-rata 1000 mm
selama masa pertumbuhan (Setiadi dan Fitri, 2000).
Faktor cahaya yang paling penting untuk pertumbuhan kentang adalah
intensitas cahaya dan lama penyinaran. Untuk dapat berasimilasi dengan baik
kentang memerlukan intensitas cahaya yang besar. Menurut Harjadi (1979), laju
fotosintesis berbanding lurus dengan intensitas cahaya sampai kira – kira 1.200
foot candle. Maka semakin besar atau meningkat intensitas cahaya matahari yang
dapat diterima tanaman dapat mempercepat proses pembentukan umbi dan waktu
pembungaan. Lama penyinaran yang diperlukan tanaman untuk kegiatan
fotosintesis adalah 9 jam sampai 12 jam per hari (Samadi, 1997).
Tanah
Kentang menghendaki tanah yang subur dengan kandungan bahan organik
yang tinggi. Jenis tanah andisol merupakan pilihan yang paling tepat. Jenis tanah
ini umumnya ditemukan di dataran tinggi atau di lereng–lereng yang tinggi
(Hartus, 2001).
Keadaan sifat biologis tanah yang baik dicirikan dengan adanya aktifitas
organisme tanah. Kegiatan organisme tanah ini sangat dipengaruhi oleh sifat
kimia dan sifat fisika. Pengaruh sifat biologis tanah terhadap tingkat pertumbuhan
tanaman adalah dapat membantu tersedianya zat–zat hara yang diperlukan
petumbuhan organisme tanah yang merugikan (patogen), membantu proses
nitrifikasi tanah dan membantu melancarkan aerase atau peredaran udara dalam
tanah (Samadi, 1997).
Tanah yang gembur dengan dengan pH 5–5.5 paling optimal untuk
pertumbuhan dan perkembangan kentang. Pada pH kurang dari 5, kentang muda
terserang penyakit bintil–bintil pada umbi yang disebabkan oleh serangan
nematoda. Di samping itu, kentang akan mengalami defisiensi fospor(P) dan
magnesium (Mg) serta keracunan Mangan (Mn). Pada pH tinggi, tanaman
mengalami defisiensi kalium (Hartus,2001).
Pengaruh Berat Umbi Bibit
Pada dasarnya semua berat umbi bibit kentang dapat dipakai untuk dijadikan
sebagai bibit. Ukuran umbi untuk dijadikan bibit mempunyai berat per Umbi
30-60g. Namun demikian, dengan seleksi yang ketat maka ukuran umbi antara 20-30
g juga dapat dipakai sebagai bibit. Demikian pula umbi yang berukuran lebih
besar dari 60 gr juga dapat dipakai sebagai bibit untuk perbanyakan bibit juga
untuk pertanaman komersial (Sunarjono, 1978).
Apabila ukuran bibit yang digunakan kecil atau lebih kecil dari 30 g
pertumbuhan kentang tidak sempurna atau batang-batang utama tumbuhnya lebih
kecil. Hal ini disebabkan cadangan makanan sedikit dan mata tunas yang tumbuh
juga kecil-kecil sehingga produksi menjadi rendah, begitu juga bibit yang besar
atau lebih besar dari 60 g, pertumbuhan akan lebih rimbun. Hal ini disebabkan
cadangan makanan banyak dan mata tunas yang tumbuh juga banyak yang
pertumbuhan batang dan daun. Dan pembentukan umbi lebih sedikit
(Soelarso 1997 ).
Umbi yang dihasilkan umumnya tidak lagi berkuran seragam. Variasinya
sangat besar, mulai 20 g sampai 400 g. Penangkar biasanya memilih yang
berukuran kecil antara 20 – 50 g untuk dijual sebagai bibit. Umbi yang besarnya >
50 g dijual sebagai bahan untuk konsumsi (Hartus 2001).
Pemilihan bibit kentang bebas penyakit merupakan persyaratan utama
dalam budi daya kentang. Kentang yang sudah terkena penyakit virus tidak dapat
dikendalikan dengan penggunaan bahan kimia sehingga produktivitasnya di
bawah potensi varietas tersebut. Ukuran bibit yang baik adalah 30 g – 60 g tiap
umbi yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas I 30 – 45 g / umbi dan kelas II 45
– 60 g / umbi. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa menanam bibit yang
besar akan diperoleh umbi yang kecil dan demikian pula sebaliknya
(Soelarso 1997).
Pertumbuhan umbi karena pembelahan dan pembesaran sel yang terus
menerus karena karbohidrat kepangkal daun-daun muda disini terjadi
penghambatan meristem-meristem apical dan akar, umumnya bersama-sama
dengan penghentian pembelahan sel dan penggelembungan ke akar lateral
dipangkal daun-daun muda (Thomson and Kelly, 1957).
Kalium
Fungsi utama kalium (K) ialah membantu pembentukan protein dan
karbohidrat. Kalium juga berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun,
merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan
penyakit (Lingga dan Marsono, 2004).
Secara fisiologi K mempunyai fungsi mengatur pergerakan stomata dan
hal-hal yang berhubungan dengan cairan sel. Unsur K berperan dalam mengatur
membuka dan menutupnya stomata tanaman, sehingga mempengaruhi transpirasi.
Bila kandungan unsur K tinggi, maka sel-sel stomata tanaman menutup
(Novizan, 2002).
Kalium juga berperan sebagai aktivator metabolisme, aktivator enzim,
aktivator transportasi hasil metabolisme tanaman dan meningkatkan efisiensi
penggu naan air (Harjadi dan Sudirman, 1988).
Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Di dalam tanah, ion
tersebut bersifat sangat dinamis. Tak mengherankan jika mudah tercuci pada tanah
berpasir dan tanah dengan pH rendah. Dari ketiga unsur hara makro yang diserap
oleh tanaman (N, P, K), kaliumlah yang jumlahnya paling melimpah di
permukaan bumi (Novizan, 2002).
Pada dasarnya, kalium dalam tanah ditemukan dalam mineral-mineral
yang setelah terlapuk dapat melepaskan ion-ion kalium. Ion-ion diabsorbsi pada
kation tertukar dan cepat tersedia untuk diserap tanaman. Kalium tersedia
terkumpul di dalam tanah dengan regim kelembaban tanah ustic atau kering
dimana tidak ada pencucian (Foth, 1991).
Dalam pemupukan KCl, perlu diperhatikan jumlah kalium yang tersedia di
dalam tanah (hasil analisa tanah). Pada tanah ber-pH rendah ketersedian
maupun tanah basa (alkali) yang menunjukkan pencucian kalium dapat ditukat
terbatas. Ketersediaan Kalium diartikan sebagai Kalium yang dibebaskan dari
bentuk tidak dapat dipertukarkan kebentuk yang dapat dipertukarkan, sehingga
dapat diserap tanaman. Berbagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan Kalium
dalam tanah untuk tanaman adalah peristiwa pembekuan dan pencairan,
pembasahan dan pengeringan, pH tanah dan pelapukan. Kalium diserap dalam
bentuk kation K+ yang monovalen. Berbeda dengan Posfat dan Nitrogen, Kalium
tidak ikut menyusun bagian tanaman, (Gardner, Pearce dan Mitchell, 1991).
Akar-akar adventif berkembang pada tahap awal dari buku-buku dekat
penempelan daun pertama yang berkembang sempurna. Jumlah akar yang
terbentuk mencapai suatu maksimum pada 10-15 hari setelah pertanaman. Kondisi
lingkungan selama pertumbuhan awal mempengaruhi bagian akar yang terbentuk
dalam masing-masing golongan. Misalnya suhu dingin (220-240 C) dan persediaan
kalium yang cukup menyebabkan aktivitas yang cepat dalam pembentukan lingin
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanian di desa Ujung Sampun
Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dengan ketinggian ±1250 meter di atas
permukaan laut dengan jenis tanah andisol. Penelitian ini dilaksanakan mulai
bulan Agustus sampai bulan November 2007.
Bahan dan Alat Penelitian
Bahan – bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bibit kentang
varietas Granola G7, pupuk kandang lembu, pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk
KCl, pestisida Decis 2.5 EC, Kocide 77 WP, dan bahan – bahan lain yang
mendukung penelitian ini.
Alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, garu,
meteran, tali plastik, bambu, timbangan, gembor, hand prayer, papan nama, pacak
sampel, alat tulis dan peralatan lain yang mendukung dalam penelitian ini.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari 2 faktor perlakuan yaitu :
Faktor I : Perlakuan dari berat umbi bibit (B) yang terdiri dari 4 taraf yaitu :
B1 = 25-30 g
B2 = 35-40 g
B3 = 45-50 g
Faktor II : Dosis Pupuk KCl dengan 3 taraf yaitu :
K0 = 0 g KCl /tanaman
K1 = 166,6 kg KCl/Ha = 5,3 g KCl per tanaman
K2 = 333,3 kg KCl/Ha = 10,6 g KCl per tanaman
Dengan demikian penelitian ini terdiri dari 12 kombinasi perlakuan yaitu :
B1K0 B2K0 B3K0 B4K0
Jumlah seluruh tanaman = 720 tanaman
Jarak tanam = 80 cm x 40 cm
Jumlah kombinasi = 12
Luas lahan penanaman = 42,3 m x 7,6 m
Data yang diperoleh, dianalisis dengan sidik ragam linier sebagai berikut :
Yijk = µ + ρi + αj + βk + (αβ) jk + ijk
Yijk = hasil pengamatan blok ke-i dengan berat umbi bibit taraf ke- j dan
dosis pupuk KCl ke-k
αj = pengaruh perlakuan berat umbi bibit taraf ke-j βk = pengaruh dosis pupuk KCl ke-k
(αβ)jk = pengaruh interaksi perlakuan berat umbi bibit taraf ke-j dan dosis
pupuk KCl taraf ke-k
ijk = galat percobaan blok ke-i dengan berat umbi bibit ke-j dan dosis
pupuk KCl ke-k
Apabila pada daftar sidik ragam, perlakuan berpengaruh nyata terhadap
parameter maka dilanjutkan dengan Uji Duncan (Duncan Multiple Range Test)
dengan taraf 5 % (Bangun, 1991).
Pelaksanaan Penelitian
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakuan dalam pelaksanaan penelitian ini
adalah pengolaha tanah, pembuatan bedengan dan saluran drainase, penanaman,
aplikasi pupuk KCl, pemeliharaan, pengamatan parameter dan panen.
Pengolahan Tanah
Sebelum areal diolah, terlebih dahulu areal di bersihkan dari rerumputan,
sisa-sisa tanaman, dan batu-batuan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman
dengan menggunakan cangkul.
Pengolahan tanah di lakukan dengan mencangkul tanah sedalam + 30 cm
dengan cara membalikkan tanah. Pengolahan dilaksanakan dengan tujuan
menghancurkan dan menghaluskan tanah. Setelah pengolahan tanah selesai,
dilaksanakan penggaruan dan membersihkan areal pertanaman dari
Pembuatan Bedengan dan Saluran Drainase
Bedengan dibuat membujur searah Utara – Selatan, agar penyebaran
cahaya matahari dapat merata mengenai seluruh tanaman. Bedengan berukuran
lebar 80 cm, tinggi 30 cm, jarak antar bedengan 40 cm. Selanjutnya dibuat saluran
drainase pada pinggir lahan pada tempat yang paling rendah dengan lebar 50 cm
dengan dalam lebih rendah dari lahan.
Penanaman
Sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu dibuat lubang tanam
sedalam 5-10 cm dengan jarak tanam 80 cm x 40 cm. Penanaman dilakukan pada
lubang tanam dengan cara memasukkan umbi bibit ke lubang tanam yang telah di
tentukan. Masing-masing lubang dimasukkan satu umbi bibit dengan posisi tunas
menghadap keatas dan selanjutnya di tutup dengan tanah kira-kira setebal 5 cm.
Aplikasi Pupuk KCl
Pupuk KCl diaplikasikan pada saat tanaman berumur 1 bulan atau 4 MST
sesuai dengan dosis perlakuan yaitu 0 g KCl, 5,3 g KCl, 10,6 g KCL, per
tanaman dan dilakukan dengan sistem melingkar pada umbi kentang yang
ditanam.
Pemeliharaan
Pemeliharaan tanaman terdiri dari penyiraman, penyulaman, pemupukan,
a. Penyiraman
Penyiraman dilakukan setiap hari yaitu pagi atau sore hari serta tergantung
keadaan cuaca. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor dan
diusahakan agar tanahnya tidak terlalu basah.
b. Penyulaman
Penyulaman dilakukan bila terdapat tanaman yang mati atau tumbuh tidak
sehat. Penyulaman ini dilakukan hingga umur tanaman satu minggu setelah
tumbuh. Tujuan penyulaman untuk mengganti tanaman yang mati, layu, rusak
atau kurang baik tumbuhnya.
c. Pemupukan
Pupuk yang digunakan adalah pupuk anorganik Urea (200 kg), SP-36 (300
kg ), KCl (0 g KCl, 5,3 g KCl, 10,6 g KCl / tanaman) diberikan sesuai dengan
perlakuan yang telah dibuat. Pupuk buatan (anorganik) SP-36 diberikan langsung
pada waktu tanam dan dicampur dengan pupuk kandang lembu 20 ton/ha. Pupuk
KCl diberikan setelah tanaman berumur 4 MST, sedangkan pupuk urea diberikan
secara bertahap yaitu setengah bagian urea diberikan pada saat tanam dan sisanya
diberikan satu bulan setelah tanam bersamaan dengan pembumbunan pertama.
d. Penyiangan dan Pembumbunan
Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan gulma sekaligus
menggemburkan tanah. Tumbuhan pengganggu perlu dikendalikan agar tidak
menjadi saingan bagi tanaman utama dalam hal penyerapan unsur hara serta untuk
mencegah serangan hama dan penyakit. Penyiangan dilakukan secara manual
Pembumbunan dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama dilaksanakan setelah
tanaman berumur satu bulan (4 MST) bersamaan dengan pemberian pupuk
susulan. Pembumbunan kedua dilaksanakan pada saat tanaman berumur 60 HST.
e. Pengendalian Hama dan Penyakit
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara intensif dengan
pestisida. Pengendalian penyakit dilakukan dengan fungisida Kocide 77 WP,
dosis 2 g/l. Frekuensi penyemprotan dilakukan 1 minggu sekali dan apabila
terserang penyakit dilakukan 2 kali seminggu . Hama dicegah dengan insektisida
Decis 2.5 EC dengan dosis 0.5 ml/l. Interval penyemprotan dilakukan 1 minggu
sekali. Penyemprotan harus merata sampai belakang sisi daun.
Panen
Pemanenan dilakukan dengan kriteria daun-daun dan batangnya telah
menguning, umbinya sudah tidak mudah lecet (mengelupas) dan umur telah
mencapai 90 hari setelah tanam. Umbi kentang dipanen dengan cara mencabut
dan membongkarnya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan cacat pada umbi.
Pengamatan Parameter
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah
batang utama, berat umbi per sampel, berat umbi per plot, jumlah umbi per
a. Tinggi Tanaman (cm)
Tinggi tanaman diukur mulai dari permukaan tanah sampai ke titik tumbuh
tanaman dengan menggunakan meteran. Tanaman yang bercabang - cabang
diambil cabang yang paling tinggi. Untuk menentukan batas permukaan tanah
digunakan patokan standart. Pengukuran dilakukan mulai umur 4 MST dengan
interval dua minggu sampai tanaman berumur 60 HST.
b. Jumlah batang utama
Jumlah batang utama di hitung banyaknya jumlah batang yang muncul
diatas permukaan tanah. Waktunya bersamaan dengan pengukuran tinggi
tanaman.
c. Berat Umbi Per Sampel (kg)
Berat umbi ditimbang pada saat selesai panen dari tanaman sampel pada
setiap perlakuan.Umbi kentang terlebih dulu dibersihkan dari tanah yang
terangkat bersamaan dengan umbi lalu umbi ditimbang setiap sampel.
d. Berat Umbi Per Plot (kg)
Berat umbi dari setiap plot ditimbang pada saat selesai panen.Umbi yang
ditimbang adalah yang tidak terserang hama atau penyakit. Setelah diseleksi maka
ditimbang berat umbi seluruhnya.
e. Jumlah Umbi Per Sampel
Umbi dihitung seluruhnya pada setiap tanaman sample dengan cara
f. Jumlah Kelas Umbi
Mutu umbi diamati, setelah itu dimasukkan dalam kelas – kelasnya yaitu :
Kelas A = 70-200 g/umbi
Kelas B = 40-69 g/umbi
Kelas C = 20-39 g/umbi
Kelas D = >20 g/umbi
g. Produksi Per Hektar
Dari hasil yang telah diperoleh dihitung produksi per hektar tanaman kentang
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Setelah dilakukan pengamatan mulai dari 4 Minggu Setelah Tanam (MST)
hingga 13 MST, maka diperoleh hasil penelitian yang akan dijelaskan dibawah
ini.
Tinggi Tanaman (cm)
Hasil pengamatan tinggi tanaman dan daftar sidik ragam disajikan pada
lampiran 1 – 8 yang menunjukkan bahwa perlakuan berat umbi bibit dan pupuk
KCl serta interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata.
Data rataan tinggi tanaman pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Rataan tinggi tanaman pada umur 10 MST pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan
K0 K1 K2
B1 36.72 38.33 35.50 36.85
B2 39.67 36.67 39.33 38.56
B3 37.00 36.35 38.17 37.17
B4 39.33 36.83 39.00 38.39
Rataan 38.18 37.05 38.00
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa tinggi tanaman tertinggi pada
perlakuan berat umbi bibit yaitu pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) sebesar 38.39
cm dan yang terendah pada perlakuan berat umbi bibit 25-30 g (B1) sebesar 36.85
KCl 0 g (K0) sebesar 38.18 cm dan yang terendah pada pupuk KCl 5.3 g (K1)
sebesar 37.05 cm.
Jumlah Batang Utama Per Sampel (Batang)
Hasil pengamatan jumlah batang utama per sampel dan daftar sidik ragam
disajikan pada lampiran 9 – 14 yang menunjukkan bahwa perlakuan berat umbi
bibit dan pupuk KCl serta interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata pada
4 MST sedangkan 6 MST dan 8 MST pada perlakuan berat umbi bibit
berpengaruh nyata dan pada perlakuan dosis pupuk KCl serta interaksi kedua
perlakuan berpengaruh tidak nyata.
Data rataan jumlah batang utama per sampel pada perlakuan berat umbi
bibit dan dosis pupuk KCl dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Rataan jumlah batang utama per sampel pada umur 8 MST pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
berpengaruh nyata terhadap jumlah batang utama. Jumlah batang utama tertinggi
terdapat pada berat umbi bibit 45-50 g (B3) dengan rataan 3.14 dan terendah berat
umbi bibit 25-30 g (B1) dengan rataan 2.39. Perlakuan B3 berbeda nyata dengan
Kurva respon antara jumlah batang utama dengan berat umbi bibit pada 8
MST dapat dilihat pada gambar 1.
= -0.0022X2 + 0.2131X - 2.0285
Gambar 1. Hubungan antara Jumlah Batang Utama dengan Berat Umbi Bibit.
Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah batang utama pada
taraf perlakuan berat umbi bibit adalah kuadratik artinya berat umbi bibit 45-50 g
(B3) dapat meningkatkan jumlah batang utama tanaman kentang dan menurun
pada berat umbi bibit 55-60 g (B4).
Berat Umbi Per Sampel (kg)
Data pengamatan berat umbi per sampel tanaman kentang dapat dilihat
pada lampiran 15 sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 16.
Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa
perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap berat umbi per sampel
sedangkan dosis pupuk KCl dan interaksi kedua perlakuan tidak berpengaruh
Data rataan berat umbi per sampel pada perlakuan berat umbi bibit dan
dosis pupuk KCl dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Rataan berat umbin per sampel pada pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan
K0 K1 K2
B1 0.48 0.65 0.62 0.58 c
B2 0.82 0.76 0.72 0.77 ab
B3 0.79 0.85 0.84 0.82 a
B4 0.75 0.70 0.72 0.72 b
Rataan 0.71 0.74 0.72
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa berat umbi per sampel
berpengaruh nyata terhadap perlakuan berat umbi bibit. Berat umbi per sample
yang tertinggi pada berat umbi bibit 45-50 g (B3) dengan rataan 0.82 kg dan yang
terendah pada berat umbi bibit 25-30 g (B1) dengan rataan 0.58 kg. Perlakuan B3
berbeda nyata dengan B1dan B4, tetapi berbeda tidak nyata dengan B2. Perlakuan
Kurva respon antara berat umbi per sample dengan berat umbi bibit dapat
dilihat pada gambar 2.
= -0.0007X2 + 0.0696X - 0.8628
Gambar 2. Hubungan Antara Berat Umbi Per sampel dengan Berat Umbi Bibit
Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa hubungan berat umbi per sampel pada
taraf perlakuan berat umbi bibit adalah kuadratik dimana berat umbi per sampel
semakin meningkat sejalan dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) dan menurun
pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) tanaman kentang yang digunakan.
Berat Umbi Per Plot (kg)
Data pengamatan berat umbi per plot tanaman kentang dapat dilihat pada
lampiran 17 sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 18.
Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan
berat umbi bibit dan pupuk KCl juga interaksi antara perlakuan berpengaruh nyata
Data rataan Berat umbi per plot pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis
pupuk KCl serta interaksinya dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rataan berat umbi per plot pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot. Berat umbi per plot tertinggi
terdapat pada perlakuan berat umbi bibit 55-60 g (B4) sebesar 11.32 kg dan
terendah pada berat umbi bibit 25-30 g (B1) sebesar 9.02 kg. Dari tabel 4 dapat
dilihat juga bahwa dosis pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap berat umbi per
plot. Berat umbi per plot tertinggi pada perlakuan pupuk KCl 10.6 g (K2) dengan
rataan 12.67 kg dan terendah pupuk KCl 0 g (K0) sebesar 7.71 kg.
Selanjutnya juga dapat dilihat interaksi antara berat umbi bibit dengan
dosis kalium berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot, rataan tertinggi pada
perlakuan B4K2 sebesar 14.00 kg dan terendah pada B1K0 sebesar 4.73 kg.
Perlakuan B4K2 berbeda nyata dengan B1K0, B1K1, B1K2, B2K0, B2K1, B3K0,
B3K1, B3K2, B4K0, B4K1, tetapi berbeda tidak nyata dengan B2K2. Perlakuan
B1K2 berbeda nyata dengan B3K2, B3K1, B4K1, B2K1, B1K1, B3K0, B4K0,
nyata dengan B3K0, B4K0, B2K0, B1K0 tetapi berbeda tidak nyata pada B2K1,
B4K1, B3K1, B3K2 dan B1K2. Perlakuan B3K0 berbeda nyata dengan B4K0,
B2K0, B1K0 tetapi berbeda tidak nyata pada B1K1 dan B2K1. Perlakuan B4K0
berbeda nyata pada B2K0 dan B1K0 tetapi berbeda tidak nyata pada B3K0 dan
B1K1. Perlakuan B2K0 berbeda nyata dengan B1K0 tetapi berbeda tidak nyata
pada B4K0 dan B3K0.
Kurva respon interaksi antara perlakuan berat umbi per plot dengan dosis
pupuk KCl dapat dilihat pada gambar 3.
y = -0.07X2
Gambar 3. Hubungan Interaksi Antara Berat Umbi Per Plot dengan Pupuk KCl.
Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa hubungan berat umbi per plot pada
taraf perlakuan berat umbi bibit dengan dosis pupuk KCl adalah linier dimana
berat umbi per plot akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya dosis
pupuk KCl yang diberikan sebesar 10.6 g pertanaman dan berat umbi bibit 45-60
g (B3) yang akan digunakan pada tanaman kentang. Hubungan interaksi perlakuan
dapat dilihat dengan adanya perpotongan garis antara berat umbi bibit 35-40 g
sedangkan perpotongan berat umbi bibit 35-40 g (B2) dengan berat umbi bibit
45-50 g (B3) yaitu pada KCl sebesar 9.41 g dan perpotongan berat umbi bibit 45-45-50 g
(B3) dengan berat umbi bibit 55-60 g (B4) yaitu pada KCl sebesar 10.87 g.
Dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) dan pemberian dosis pupuk KCl sebesar
10.6 g pertanaman akan meningkatkan berat umbi per plot pada tanaman kentang.
Jumlah Umbi Per Sampel (Umbi)
Data pengamatan jumlah umbi per sampel tanaman kentang dapat dilihat
pada lampiran 19 sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 20.
Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan
berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi per sampel. Dan dosis
pupuk KCl tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi per sampel dan
interaksi antara kedua perlakuan.
Data rataan jumlah umbi per sampel tanaman kentang pada masing-masing
taraf perlakuan dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Rataan jumlah umbi per sampel pada perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah umbi per sample
berpengaruh nyata pada perlakuan berat umbi bibit. Jumlah umbi tertinggi pada
25-30 g (B1) sebesar 6.22. Perlakuan B3 berbeda nyata terhadap B1 dan B2, tetapi
berbeda tidak nyata terhadap B4. Perlakuan B2 berbeda nyata dengan B1.
Kurva respon antara jumlah umbi per sampel dengan berat umbi bibit
dapat dilihat pada gambar 4.
= -0.0006X3 + 0.0722X2 - 2.7953X + 39.952
Gambar 4. Hubungan antara Jumlah Umbi Per Sampel dengan Berat Umbi Bibit.
Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi per sampel
pada perlakuan berat umbi bibit adalah kubik, jumlah umbi per sampel akan
meningkat sejalan dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) dan menurun pada berat
umbi bibit 55-60 g (B4) yang akan digunakan.
Jumlah Umbi Menurut Kelasnya
a. Jumlah Umbi Kelas A (70-200 g per umbi)
Setelah dimasukkan kedalam kelas – kelasnya, maka data pengamatan
jumlah umbi kelas A dapat dilihat pada lampiran 21 sedangkan sidik ragamnya
dapat dilihat pada lampiran 22. Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam
dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap jumlah
Rataan jumlah umbi kelas A tanaman kentang pada masing-masing taraf
perlakuan dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Rataan jumlah umbi kelas A pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas A. Jumlah umbi kelas A tertinggi
pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) sebesar 2.25 dan terendah pada berat umbi
bibit 25-30 g (B1) sebesar 0.89. Perlakuan B4 berbeda nyata pada B3, B2 dan B1.
Perlakuan B3 berbeda nyata pada B2 dan B1.
Kurva respon antara jumlah umbi kelas A dengan berat umbi bibit dapat
dilihat pada gambar 5.
= 0.0455X - 0.59
Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi kelas A pada
perlakuan berat umbi bibit adalah linier yang artinya jumlah umbi kelas A akan
meningkat sejalan dengan semakin berat umbi bibit yang akan digunakan dengan
berat umbi bibit 55-60 g (B4).
b. Jumlah Umbi Kelas B (40-69 g per umbi)
Data pengamatan jumlah umbi kelas B dapat dilihat pada lampiran 23
sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 24. Berdasarkan data
pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas B. Juga dapat dilihat bahwa pupuk
KCl tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas B dan interaksi antara
kedua perlakuan.
Rataan jumlah umbi kelas B tanaman kentang pada masing-masing taraf
perlakuan dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Rataan jumlah umbi kelas B pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas B. Jumlah umbi kelas B tertinggi
bibit 25-30 g (B1) sebesar 2.86.B4 berbeda nyata dengan B3, B2 dan B1. B3
berbeda nyata dengan B2 dan B1.
Kurva respon antara jumlah umbi kelas B dengan berat umbi bibit dapat
dilihat pada gambar 6.
= 0.0479X + 1.317
Gambar 6. Hubungan antara Jumlah Umbi Kelas B dengan Berat Umbi Bibit.
Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi kelas B akan
semakin meningkat sejalan dengan semakin berat umbi bibit yang digunakan berat
umbi bibit 55-60 g (B4) dan grafik menunjukkan hubungan linier antara jumlah
umbi kelas B dengan berat umbi bibit.
c. Jumlah Umbi Kelas C (20-39 g per umbi)
Data pengamatan jumlah umbi kelas C dapat dilihat pada lampiran 25
sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 26. Berdasarkan data
pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
dan dosis pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas C.
Sedangkan interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah
Data rataan jumlah umbi kelas C tanaman kentang pada masing-masing
taraf perlakuan dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Rataan jumlah umbi kelas C pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan
K0 K1 K2
B1 0.67 1.08 2.08 1.28 c
B2 2.25 2.33 2.42 2.33 bc
B3 2.42 2.67 2.83 2.64 b
B4 2.92 2.75 3.33 3.00 a
Rataan 2.06 b 2.21 b 2.67 a
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas C. Jumlah umbi kelas C tertinggi
pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) dengan rataan 3.00 dan terendah pada berat
umbi bibit 25-30 g (B1) sebesar 1.28. B4 berbeda nyata dengan B3, B2 dan B1.
B3 berbeda nyata dengan B1, tetapi berbeda tidak nyata pada B2. Pada perlakuan
dosis pupuk KCl jumlah umbi kelas C tertinggi pada dosis pupuk 10.6 g (K2)
dengan rataan 2.67 dan terendah pada dosis pupuk 0 g (K0) dengan rataan 2.06.
Kurva respon antara jumlah umbi kelas C dengan berat umbi bibit dapat
dilihat pada gambar 7.
= 0.0547X - 0.149
Gambar 7. Hubungan antara Jumlah Umbi Kelas C dengan Berat Umbi Bibit.
Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi kelas C dengan
berat umbi bibit adalah linier yang artinya semakin berat umbi bibit yang
digunakan akan meningkatkan jumlah umbi kelas C.
Kurva respon antara jumlah umbi kelas C dengan dosis pupuk KCl dapat
dilihat pada gambar 8.
= 0.0575K + 2.0083
Dari gambar 8 dapat diketahui bahwa jumlah umbi kelas C semakin
meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pupuk KCl yang diberikan
dengan dosis 10.6 g per tanaman.
d. Jumlah Umbi Kelas D (<20 g per umbi)
Data pengamatan jumlah umbi kelas D dapat dilihat pada lampiran 27
sedangkan sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 28. Berdasarkan data
pengamatan daftar sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
dan dosis pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas D.
Sedangkan interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata.
Data rataan jumlah umbi kelas D tanaman kentang pada masing-masing
taraf perlakuan dapat dilihat pada tabel 9.
Tabel 9. Rataan jumlah umbi kelas D pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa perlakuan berat umbi bibit
berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas D. Jumlah umbi kelas D tertinggi
pada berat umbi bibit 55-60 g (B4) dengan rataan 2.14 dan terendah pada berat
umbi bibit 25-30 g (B1) sebesar 0.56. B4 berbeda nyata dengan B3, B2 dan B1.
B3 berbeda nyata dengan B2 dan B1, B2 berbeda nyata dengan B1. Pada
10.6 g (K2) dengan rataan 1.54 dan terendah pada dosis pupuk KCl 0 g (K0)
dengan rataan 1.29. K2 berbeda nyata dengan K0 tetapi berbeda tidak nyata
dengan K1. K1 berbeda nyata dengan K0.
Kurva respon antara jumlah umbi kelas D dengan berat umbi bibit dapat
dilihat pada gambar 9.
= 0.0552X - 1.044
Gambar 9. Hubungan antara Jumlah Umbi Kelas D dengan Berat Umbi Bibit.
Dari gambar 9 dapat dilihat bahwa hubungan jumlah umbi kelas D dengan
berat umbi bibit adalah linier yang artinya semakin berat umbi bibit yang
digunakan akan meningkatkan jumlah umbi kelas D.
Kurva respon antara jumlah umbi kelas D dengan dosis pupuk KCl dapat
dilihat pada gambar 10.
Dari gambar 10 dapat diketahui bahwa jumlah umbi kelas D semakin
meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pupuk KCl yang diberikan
dengan dosis 10.6 g per tanaman.
Produksi Per Hektar
Berdasarkan data pengamatan daftar sidik ragam pada lampiran 29-30
dapat dilihat bahwa perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap
produksi perhektar. Juga dapat dilihat bahwa pupuk KCl tidak berpengaruh nyata
terhadap produksi per hektar dan interaksi antara kedua perlakuan.
Data Produksi per hektar tanaman kentang pada masing-masing taraf
perlakuan dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10 .Rataan produksi per hektar pada berbagai perlakuan berat umbi bibit dan dosis pupuk KCl.
Berat Umbi Bibit (g) Kalium (g) Rataan
Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa berat umbi bibit berpengaruh
nyata terhadap produksi per hektar. Produksi tertinggi pada perlakuan berat umbi
bibit 45-50 g (B3) sebesar 25.59 ton dan terendah pada berat umbi bibit 25-30 g
(B1) sebesar 18.52 ton. Perlakuan B3 berbeda nyata pada B1 tetapi berbeda tidak
Kurva respon antara produksi per hektar dengan berat umbi bibit dapat
dilihat pada gambar 11.
= -0.0149X2 + 1.3749X - 6.693
Gambar 11. Hubungan antara Produksi Per Hektar dengan Berat Umbi Bibit.
Dari gambar 11 dapat diketahui bahwa produksi per hektar semakin
meningkat sejalan dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) yang digunakan.
kemudian menurun pada berat umbi bibit 55-60 g (B4). Hubungan produksi per
B. Pembahasan
Pengaruh Berat Umbi Bibit Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kentang.
Dari data pengamatan dan hasil analisis secara statistika maka diperoleh
bahwa perlakuan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap jumlah batang
utama (batang), berat umbi per sampel (kg), berat umbi per plot (kg), jumlah umbi
per sampel (umbi), jumlah kelas umbi A, B , C, D dan produksi umbi per hektar.
Serta berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman (cm).
Adanya pengaruh nyata terhadap jumlah batang utama disebabkan oleh
perbedaan berat umbi. Semakin besar berat umbi semakin besar ukuran umbi dan
jumlah mata tunas pada umbi akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan Samadi
(1997) yang menyatakan bibit kentang yang dianjurkan adalah 30 – 45 g atau 35 –
45 mm dan 40 – 60 g atau 45 – 55 mm, menurut penelitian umbi yang berukuran
besar akan menghasilkan jumlah tunas lebih banyak dibandingkan dengan yang
berukuran lebih kecil. Hal ini didukung oleh Setiadi (2000) yang menyatakan
umbi kentang untuk bibit dapat digunakan yang berukuran 30 – 45 g atau 50 – 60
g. Kalau besarnya diukur rata – rata antara 30 – 35 mm atau 45 – 50 mm dan
konon yang bagus 55 mm. Jumlah mata tunas sekitar 3-5. dan didukung juga oleh
Soelarso (1997) yang menyatakan mata umbi kentang sebenarnya adalah buku
dari batang. Jumlah mata umbi 2 – 14 buah tergantung pada ukuran umbi yang
digunakan.
Pengaruh nyata terhadap berat umbi persampel, berat umbi per plot dan
yang terbentuk semakin banyak, dengan meningkatnya jumlah stolon maka
produksi umbi akan semakin banyak. Hal ini sesuai Sutopo (1988) yang
menyatakan dengan semakin besar umbi bibit maka kandungan proteinnya makin
banyak pula. Besar benih berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan dan
produksi, karena berat bibit menentukan besarnya kecambah pada saat permulaan
dan berat tanaman pada saat dipanen.
Jumlah umbi per plot berpengaruh nyata disebabkan oleh semakin banyak
mata tunas, maka semakin banyak batang tanaman sehingga menghasilkan banyak
umbi. Selain itu kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah dapat di serap
oleh tanaman. Hal ini didukung oleh Setiadi (2000) yang menyatakan untuk
menentukan umbi untuk bibit tergantung dari diri sendiri, menurut petani umbi
yang baik untuk bibit adalah yang sehat, berukuran besar mempunyai mata tunas 3
– 5 dan bobotnya 80 – 100 g. Banyaknya mata tunas akan menentukan jumlah
batang tanaman semakin banyak batang akan semakin banyak menghasilkan
umbi. Namun, bila umbi yang digunakan terlalu besar ukurannya maka jumlah
umbi yang dihasilkan berjumlah banyak dengan ukuran umbi yang semakin kecil.
Pada jumlah kelas umbi A, B, C dan D berpengaruh nyata hal ini
disebabkan karena ukuran berat umbi yang digunakan menentukan banyaknya
tunas yang dihasilkan. Tunas yang berkembang menjadi batang utama
menghasilkan jumlah dan besar umbi. Semakin besar ukuran umbi maka jumlah
batang utama semakin banyak dan jumlah umbi yang di hasilkan akan semakin
banyak pula dengan ukuran yang semakin kecil. Hal ini didukung oleh
Soelarso (1997) yang menyatakan penggunaan umbi bibit ukuran besar (60 g)
menghasilkan ukuran umbi yang relatif kecil-kecil. Sedangkan tunas yang sedikit
akan menghasilkan ukuran umbi relatif besar.
Setiadi (2000) menyatakan bahwa salah satu faktor pembatas dalam
pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah penyerapan zat hara yang
penting (esensial). Dalam proses pertumbuhan tanaman menyerap unsur hara
sehingga terjadi proses metabolisme antara lain pertumbuhan sel dipenuhi,
disamping itu melalui berat umbi berarti ketersediaan makanan untuk
pertumbuhan semakin meningkat.
Perlakuan berat umbi bibit tidak nyata terhadap tinggi tanaman hal ini
diduga karena dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman. Walaupun umbi yang
digunakan berbeda beratnya tetapi sifat dari umbi sama, sehingga pada proses
pertumbuhan vegetatif tanaman tersebut tidak kelihatan perbedaanya.
Pengaruh Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kentang.
Berdasarkan data pengamatan tanaman kentang dapat diuraikan bahwa
pemberian pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot serta
berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah batang utama per
sampel, jumlah kelas umbi C,D dan produksi per hektar.
Salah satu faktor pembatas dalam pertumbuhan tanaman dan
perkembangan tanaman adalah suplai zat hara penting. Suplai zat hara dapat
ditingkatkan dengan melakukan tindakan yang optimum akan meningkatkan
potensi produksi tanaman. Sedangkan tingkat pemberian unsur hara yang terlalu
perkembangan tanaman. Unsur kalium diperlukan tanaman untuk pembentukan
karbohidrat didalam umbi, untuk kekuatan daun, ketebalan daun, dan pembesaran
daun. Tetapi pengaruhnya terhadap pertumbuhan vegetatif taanaman tidak begitu
nyata. Disamping itu unsur kalium berpengaruh terhadap penigkatan daya serap
air pada tanaman sehingga dapat mencegah tanaman menderita kelayuan,
menigkatkan ketahanan terhadap penyakit, memperbesar umbi dan meningkatkan
daya simpan umbi.
Pemberian pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap berat umbi per plot
pada tanaman kentang. Hal ini disebabkan karena pemberian pupuk KCl yang
cukup akan diserap tanaman yang berperan dalam proses pembentukan
karbohidrat sehingga menghasilkan umbi yang besar. Purohit (1986) menyatakan
bahwa kalium berperan dalam proses fotosintesis, respirasi, metabolisme dan
translokasi karbohidrat. Kalium juga berperan dalam pertumbuhan dan
perkembangan tanaman kentang setelah umbi terbentuk. Tanaman yang cukup
mendapat kalium akan mampu membentuk umbi yang besar juga disebabkan oleh
penyerapan air dan hara yang lebih baik dan translokasi yang lebih lancar.
Novizan (2002), menyatakan bahwa unsur kalium diperlukan tanaman dalam
sintesa protein dan karbohidrat serta translokasi karbohidrat lebih lancar.
Pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap jumlah umbi kelas C dan D. Hal
ini disebabkan karena unsur hara K berperan dalam pembentukan umbi. Novizan
(2002) menyatakan bahwa bila tanaman mengalami kakurangan atau defisiensi K
akan mengakibatkan pembentukan umbi terhambat atau tidak berumbi sama
sekali. Sutedjo (2002) menyatakan bahwa kalium berperan dalam pembentukan
Pemberian pupuk KCl berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman
kentang pada semua pengamatan. Hal ini diduga karena pemberian pupuk KCl
diperlukan tanaman untuk pembesaran daun, ketebalan daun dan untuk kekuatan
daun serta memacu meningkatnya jumlah klorofil daun sehingga tinggi tanaman
tidak terlalu tampak. Samadi (1997), menyatakan bahwa unsur kalium diperlukan
tanaman untuk pembentukan karbohidarat didalam umbi, untuk kekuatan daun,
ketebalan daun dan pembesaran daun tetapi pengaruhnya terhadap pertumbuhan
vegetatif tidak terlalu nyata.
Ada pengaruh tidak nyata terhadap jumlah batang utama diduga karena
peran kalium bukan untuk meningkatkan jumlah batang utama atau tunas, hal ini
sesuai dengan Novizan (2002) yang menyatakan kalium di dalam jaringan
tanaman tetap berbentuk K+ tidak ditemukan dalam bentuk senyawa organik.
Kalium bersifat mobil (mudah bergerak) sehingga siap dipindahkan dari satu
organ ke organ lain yang membutuhkan. Secara umum peran kalium berhubungan
dengan proses metabolisme, seperti fotosintesis dan respirasi.
Pemberian pupuk KCl berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah umbi per
sampel dan jumlah kelas umbi A dan B. Hal ini disebabkan karena pemberian
pupuk KCl banyak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor lingkungan yang
tidak cocok ataupun serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan
terganggunya tanaman sehinggga pertumbuhan tanaman terganggu, sehingga pada
waktu pembentukan umbi mengalami hambatan. Begitu juga dengan jumlah umbi
kelas A dan B dimana berasal dari banyaknya jumlah umbi. Sutedjo (2002)
menyatakan kebutuhan unsur hara untuk tiap fase pertumbuhan tanaman
Pemberian pupuk KCl berpengaruh tidak nyata terhadap berat umbi per
sampel dan produksi per hektar tanaman kentang. Hal ini diduga karena
pemberian pupuk KCl banyak dipengaruhi faktor seperti lingkungan yang tidak
cocok atau serangan hama dan penyakit, mengakibatkan kerusakan pada bagian
tanaman sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman.
Pengaruh Interaksi Antara Berat Umbi Bibit Dengan Dosis Pupuk KCl Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kentang.
Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa hasil interaksi antara
perlakuan berat umbi bibit dengan dosisi pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap
berat umbi per plot, hal ini disebabkan karena pembentukan akar pada tanaman
kentang didukung oleh unsur hara yang cukup pada tanaman, sehingga
pembentukan umbi semakin banyak jika pupuk KCl semakin tinggi dan berat
umbi bibit yang digunakan semakin besar. Hal ini sesuai dengan Sutopo (1988)
yang menyatakan dengan semakin besar umbi bibit maka kandungan proteinnya
makin banyak pula. Besar benih berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan
dan produksi, karena berat bibit menentukan besarnya kecambah pada saat
permulaan dan berat tanaman pada saat dipanen.
Marsono (2001) Kalium berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan
tanaman kentang setelah umbi terbentuk. Tanaman yang cukup mendapat kalium
akan mampu membentuk umbi yang besar juga disebabkan oleh penyerapan air
dan hara yang lebih baik.
Pemberian dosis kalium dan berat umbi bibit berpengaruh nyata terhadap
perpotongan pada kurva interaksi antara dosis kalium dengan berat umbi per plot
dan antara berat umbi bibit dengan berat umbi per plot. Adanya perpotongan garis
antara berat umbi bibit 35-40 g (B2) dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) yaitu
pada KCl sebesar 11.59 g sedangkan perpotongan berat umbi bibit 35-40 g (B2)
dengan berat umbi bibit 45-50 g (B3) yaitu pada pupuk KCl sebesar 9.41 g dan
perpotongan berat umbi bibit 45-50 g (B3) dengan berat umbi bibit 55-60 g (B4)
yaitu pada pupuk KCl sebesar 10.87 g. Berat umbi bibit 45-50 g (B3) berbeda
tidak nyata dengan berat umbi bibit 35-40 g (B2) dan berat umbi bibit 55-60 g
(B4). Pemberian dosis pupuk KCl sebesar 10.6 g (K2) per tanaman akan
meningkatkan berat umbi per plot pada tanaman kentang interaksi ini disebabkan
karena pemberian pupuk KCl yang cukup akan diserap tanaman yang berperan
dalam proses pembentukan karbohidrat sehingga ukuran umbi bibit yang besar
akan menghasilkan jumlah batang utama yang semakin banyak dan jumlah umbi
yang banyak Novizan (2002), menyatakan bahwa unsur kalium diperlukan
tanaman dalam sintesa protein dan karbohidrat serta translokasi karbohidrat lebih
lancar. Sedangakan penggunaan berat umbi bibit 25-30 g (B1) dan dosis pupuk
KCl 0 g (K0), 5.3 g (K1) per tanaman tidak dapat meningkatkan berat umbi per
plot interaksi ini nyata diduga karena umbi bibit yang digunakan dan pemberian
pupuk KCl hanya diperlukan tanaman untuk pembesaran daun, ketebalan daun
dan untuk kekuatan daun serta memacu meningkatnya jumlah klorofil daun.
Samadi (1997), menyatakan bahwa unsur kalium diperlukan tanaman untuk
pembentukan karbohidarat didalam umbi, untuk kekuatan daun, ketebalan daun
Tinggi tanaman, jumlah batang utama, berat umbi per sampel, jumlah
umbi per sampel, jumlah umbi kelas A, B, C dan D dan produksi per hektar
berpengaruh tidak nyata. Hal ini diduga karena antara perlakuan berat umbi bibit
dan dosis pupuk KCl saling mendukung dalam mempengaruhi pertumbuhan dan
produksi tanaman kentang secara bersamaan dimana dalam hal ini ada faktor
dominan menutupi faktor yang lain.
Poerwoidodo (1992) menyatakan bahwa bila salah satu faktor berpengaruh
lebih kuat daripada faktor lainnya, maka pengaruh faktor tersebut tertutupi dan
bila masing – masing faktor mempunyai sifat yang jauh berbeda pengaruh dan
sifat kerjanya maka akan menghasilkan hubungan yang berpengaruh tidak nyata
dalam mendukung suatu pertumbuhan tanaman.
Selanjutnya Hakim (1986), menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman
akan lebih baik bila faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seimbang dan
memberi keuntungan. Bila faktor ini tidak dapat dikendalikan maka pertumbuhan