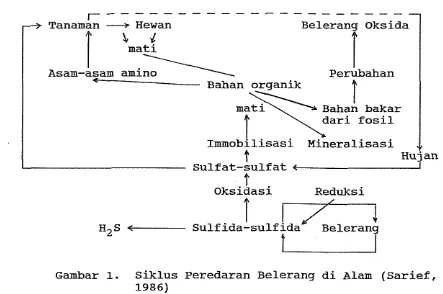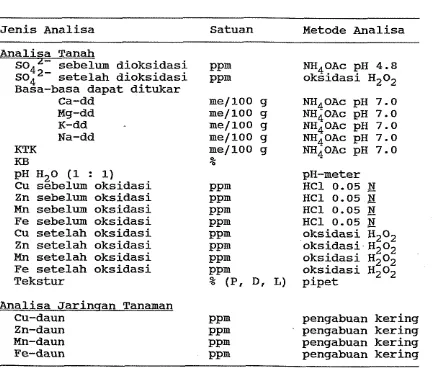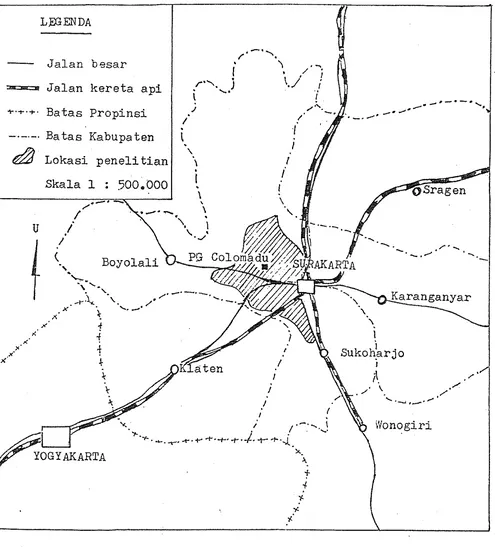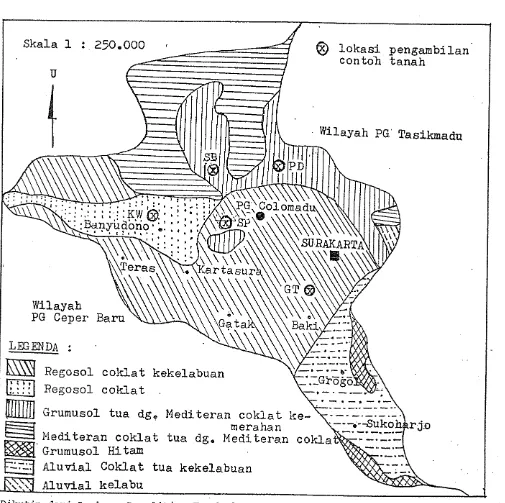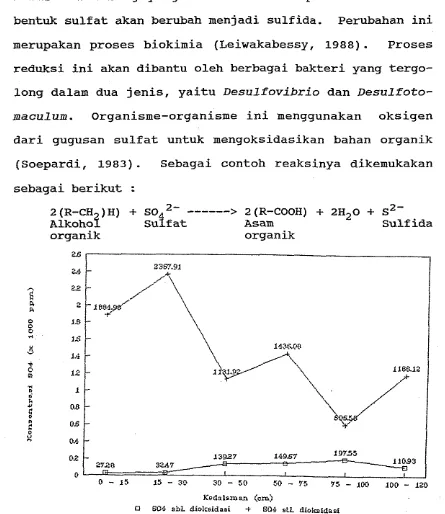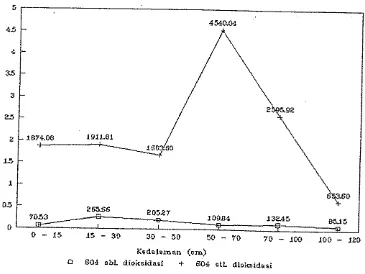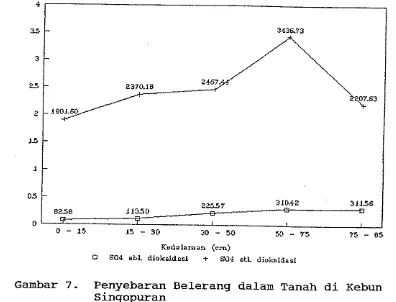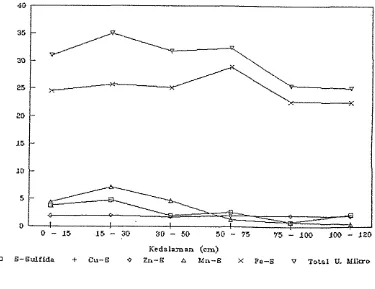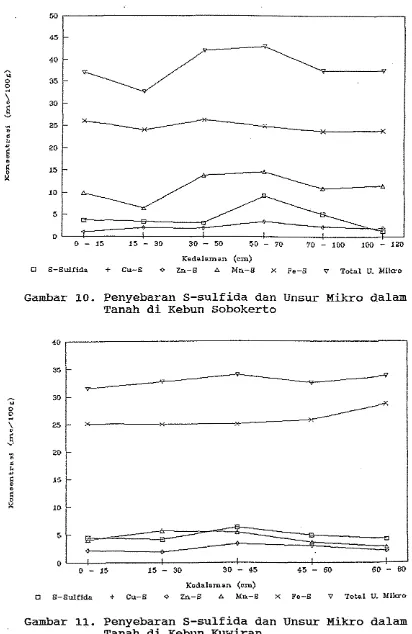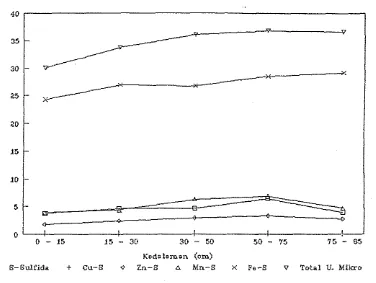Motto :
"
...
.Allah akan mening- gikan orang-orang yang ber- iman diantaramu dan orang- orang yanq diberi ilmu beberapa derajat (Q.S. A1 Mujadalah : 11)""...
Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang...
paling bertaqwa
(Q.S. AL Hujurat : 13)"
Kupersembahkan karyaku ini buat :
DAMPWK PENGGUNAWN ZA
SECAWA TEWUS
MENERUS
TERHADAP
STBUS
HARA
MlKWO
TANAH
PADA
BEBEWAPA
KEBUN
DI
PERKEBUMAN
TEBU
PG COLQMADU P T P
XY-XVl
SURWKAWTA
Oleh
MUHAMMAD SHOLEH
A 23.0677
JURUSAN TANAH
FAMULTAS BERTANIAN
INSTtTUT PERTANIAN BOGOR
SHOLEH. Dampak Penggunaan ZA Secara Terus Mene-
rus ~ e r h a d a ~ Status Hara Mikro Tanah pada Beberapa Kebun
di Perkebunan Tebu PG Colomadu, PTP XV-XVI Surakarta (Di
bawah bimbingan SUDARSONO).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak
penggunaan ZA (Ammonium Sulfat) secara terus menerus
terhadap status hara mikro tanah (Cu, Zn, Mn dan Fe) serta
hubungannya dengan produksi dan rendemen tebu pada bebera-
pa kebun di perkebunan tebu PG Colomadu, PTP XV-XVI Sura-
karta, Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil lokasi 6
blok kebun, yaitu kebun Pandeyan (PD 11), Sobokerto (SB
11) Kuwiran (KW), Singopuran (SP), Gentan (GT) serta
Klodran (KD). Keenam lokasi tersebut termasuk wilayah
kerja PG Colomadu. Pengambilan contoh tanah dan pengama-
tan lapang dilakukan dari tanggal 13 sampai 25 Agustus
1990, dan analisa contoh tanah dilakukan dari bulan Sep-
tember 1990 sampai Januari 1991. Analisa tanah dan tana-
man dilakukan di laboratorium Jurusan Tanah, Fakultas
Pertanian IPB dan laboratorium Balai Penelitian Tanaman
Pangan Bogor. Analisa Tanah meliputi sifat-sifat kimia
tanah berupa SO4 sebelum dan sesudah dioksidasi, unsur-
unsur mikro tanah (Cu, Zn, Mn dan Fe) baik sebelum maupun
sesudah dioksidasi, basa-basa dapat ditukar, KTK, KB, pH
jaringan tanaman didasarkan atas jaringan daun tebu umur
3-4 bulan pada daun ke-4 dari atas/pucuk. Data produksi
dan rendemen tebu serta pemupukan pada lokasi penelitian
digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.
Tanah yang diteliti merupakan wilayah perkebunantebu
yang telah diusahakan bertahun-tahun lamanya dengan sistem
q l e b a q a n . Pupuk ZA telah digunakan secara terus menerus
selama bertahun-tahun. Hasil analisa menunjukkan bahwa
pada tanah-tanah yang diteliti telah terjadi pencucian
sulfat, akibatnya terjadi akumulasi sulfat pada kedalaman
tertentu. Adanya perubahan penggunaan tanah secara ber-
gantian antara tebu dan padi menyebabkan perubahan reaksi
tanah pula. Transformasi sulfat menjadi sulfida terjadi
pada saat tanah digenangi (anaerobik). Akumulasi sulfida
akan terjadi pada kedalaman antara 15-30 cm (Kebun Pande-
yan)
,
50-70 cm (Kebun Sobokerto),
30-45 cm (Kebun Kuwirandan Gentan) dan 50-75 cm (Kebun Singopuran). Bentuk-
bentuk sulfida yang mengendap ini akan mengikat ion-ion
logam berat seperti cu2', zn2+, ~ n dan ~ e ~ + . ~ + Akibatnya
unsur-unsur mikro ini menjadi turut mengendap dan menjadi
kurang tersedia bagi tanaman.
Pengendapan S-sulfida berkorelasi sangat nyata terha-
dap pengendapan'~e-s dan tidak nyata terhadap Cu-S, Zn-S
dan Mn-S. Pengendapan Cu-S berkorelasi sangat nyata
terhadap pengendapan Fe-S dan berkorelasi tidak nyata
produksi cenderung menurun). Pengendapan Zn-S berkorelasi
nyata terhadap penurunan kadar Fe daun. Kadar Zn daun
berkorelasi nyata terhadap rendemen tebu. Sedangkan kadar
Fe daun berkorelasi nyata terhadap penurunan rendemen.
Kadar Zn daun berkorelasi sangat nyata dengan kadar Mn
d a m .
Hasil analisa jaringan tanaman menunjukkan adanya
defisiensi Cu pada kelima blok kebun yang diteliti (Kebun
Pandeyan, Sobokerto, Kuwiran, Singopuran, dan Gentan).
Secara m u m penggunaan ZA secara terus menerus pada
perkebunan tebu sawah akan menimbulkan dampak negatif
terhadap status hara mikro tanah, akibat lebih lanjut
adalah menurunkan produksi dan rendemen tebu. Hal ini
mengisyaratkan perlunya dipikirkan pengqunaan pupuk mikro
pada perkebunan tebu sawah ataupun perbaikan sistem pemu-
DAMPAK PENGGUNAAN ZA SECARA TERUS MENERUS
TERH?+DAP STATUS HARA MIKRO TANAH
PADA BEBERAPA KEBUN D I PERKEBUNAN TEBU
PG COLOMADU P T P XV-XVI
SW?AKARTA
S k r i p s i
Sebagai s a l a h s a t u s y a r a t
untuk m e m p e r o l e h gelar Sarjana P e r t a n i a n pada
F a k u l t a s P e r t a n i a n , I n s t i t u t P e r t a n i a n B o g o r
O l e h
SHOLEH
A 23.0677
JURUSAN TANAH
FAKULTAS PERTANIAN
I N S T I T U T PERTANIAN BOGOR
Judul
Nama Mahasiswa
Nomor Pokok
: Dampak Penggunaan ZA Secara Terus
Menerus Terhadap Status Hara Mikro
Tanah Pada Beberapa Kebun di
Perkebunan Tebu PG Colomadu, PTP
XV-XVI Surakarta
: Kuk-a Skoleh
: A 23.0677
Menyetujui, Dosen Pembimbing
A
Dr. Ir. Sudarsono, MSc. NIP 130 607 618
--
as Pertanian IPB
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Sragen, Jawa Tengah pada tang-
gal 10 Januari 1968 sebagai putra tunggal dari Bapak
Soegijo dan Ibu Siti 'Aisyah.
Pada tahun 1980 penulis menamatkan pendidikan Sekolah
Dasar Negeri 1 Girimargo di Sragen. Kemudian penulis
melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
A1 Islam 1 Surakarta (Solo) dan lulus pada tahun 1983.
Pendidikan Sekolah Menengah Atas dilalui di SMA A1 Islam 1
Surakarta hingga lulus pada tahun 1986. Pada tahun 1986
pula penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui
jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU).
Setahun kemudian, pada tahun 1987 penulis diterima menjadi
mahasiswa Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB.
Semasa menjadi mahasiswa penulis berperan aktif dalam
organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT) IPB dan
Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia
(FOKUSHIMITI) dan pernah diangkat menjadi asisten prakti-
kum pada mata ajaran Dasar-dasar Ilmu Tanah pada semester
ganjil tahun ajaran 1990/1991 dan 1991/1992, sekaligus
juga diangkat rnenjadi asisten praktikum pada mata ajaran
Dasar-dasar Interpretasi Foto Udara pada semester ganjil
tahun ajaran 1991/1992. Penulis juga pernah mewakili
Fakultas Pertanian IPB
dalam
Lomba Karya Inovatif Produk-tif (LKIP) Tingkat Nasional tahun 1990/1991 serta menjadi
delegasi IPB dalam Seminar Nasional Ilmu Tanah di Solo
DAFTAR IS1
Halarnan
DAFTAR IS1
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
KATA PENGANTAR
PENDAHULUAN
...
...
Latar Belakang
...
Tujuan
...
TINJAUAN PUSTAKA
Sifat Umum Tanah Grumusol
...
...
Sifat Umum Tanah Regosol
Sifat Umum Tanah Mediteran
...
Sifat Umum Tanah Aluvial
...
Botani dan Syarat Tumbuh Tanaman Tebu (Sac-
charum officinarum L.)
...
Pupuk ZA (Ammonium Sulfat) dan Pengaruhnya ter-
hadap Tanah
...
Perilaku Belerang dalarn Tanah
...
Unsur Mikro (Cu. Zn. Mn dan Fe) dalam Tanah
...
BAHAN DAN METODE
...
Waktu dan Tempat Penelitian
...
Bahan dan Alat
...
...
HASIL DAN PEXl3AHASAN
Keadaan Umum Lokasi Penelitian
...
Penyebaran Belerang dalam Tanah
...
...
Penyebaran Unsur Mikro dalam TanahHubungan Antara Pengendapan Sulfida Terhadap Unsur Mikro. Produksi dan Rendemen Rata- rata Serta Kadar Unsur Mikro dalam Jaringan Tanaman
...
KESIMPULAN DAN SARAN
...
...
KesimpulanSaran
...
11. Penyebaran S-Sulfida dan Unsur Mikro di Dalam
Tanah Yang Mengalami Pengendapan
...
5712. Hubungan Antara Ketersediaan Sulfida, Unsur
Mikro (Sampai Kedalaman 30 cm) dengan
Produksi dan Rendemen Rata-rata Serta Analisa Kadar Unsur Mikro dalam Jaringan
Tanaman
...
5813. Data Produksi dan Rendemen Tebu di 5 Lokasi
Kebun Selma 10 Tahun terakhir
...
5814. Rata-rata Produksi dan Rendemen Tebu Pada 5
Lokasi Penelitian Selama 10 Tahun Ter-
akhir
...
5915. Hasil Uji Jaringan tanaman Berdasarkan Anali-
sa Daun ke-4 Dari Atas Umur 3-4 Bulan dan
Titik Kritik Kecukupan Berdasarkan Anali-
Nomor Halaman
1. Siklus Peredaran Belerang di Alam
...
152. Peta Lokasi Daerah Penelitian Wilayah PG Coloma-
du
,
PTP XV-XVI...
303. Peta Tanah Perkebunan Tebu Wilayah kerja PG Co-
lomadu, PTP XV-XVI
...
3 14. Pola Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun
Pandeyan
...
345. Pola Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun
Sobokerto...
...
356. Pola Penyebaran Belerang -dalam Tanah di Kebun
Kuwiran
...
357. Pola Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun
singopuran
...
368. Pola Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun
Gentan
...
369. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam
Tanah di Kebun Pandeyan
...
3810. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam
Tanah di Kebun Sobokerto
...
3911. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam
Tanah di Kebun Kuwiran
...
3912. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam
Tanah di Kebun Singopuran
...:...
4013. Pola Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam
~ismillahirrohmanirrohim
Rssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pu j i syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subha-
nahu Wata'ala atas rahmah, hidayah serta inayah-Nya yang
telah dilimpahkan kepada penulis hingga selesainya skripsi
ini. Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertani-
an, Institut Pertanian Bogor.
skripsi ini membahas tentang dampak penggunaan ZA
secara terus menerus terhadap status hara mikro tanah di
perkebunan tebu PG Colomadu Surakarta. Selanjutnya diha-
rapkan dari penelitian ini diperoleh rekomendasi intensi-
fikasi tanaman tebu, terutama dalam ha1 pemupukan tanah
yang lebih baik. Dengan demikian produksi tebu dapat
ditingkatkan dan ketergantungan impor gula saat ini dapat
dikurangi.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Bapak Dr. Ir. Sudarsono, NSc. selaku pembimbing atas
kesediaannya membimbing penulis sampai selesainya
skripsi ini.
2. Bapak Abraham Moeljono, BSc. selaku Administratur dan
Bapak Ir. Suroto selaku Kepala Tanaman PG Colomadu
beserta staf dan karyawannya yang telah mengijinkan
3. Karyawan laboratorium dan rumah kaca Jurusan Tanah
IPB yang telah membantu lancarnya penelitian ini.
4. Ibu Ratna Setiati, BA dan lnbak Siti Rustini (Pegawai
Perpustakaan Jurusan Tanah IPB).
5. Rekan-rekan : Inay, Evi, Yanti, Ina, Haniek, Rika,
Endang, Wowon, Popi, Adhi, Neno, Santi, Wanny, Erlien,
Uci, Yoen, Linda, Deta, Ida, Bibin, Yenny, Kentus,
Banpol, Eko, Ali, A'iem, Birno, Bambang, Yayu', Budi,
Tuti dan The Soil Outsider atas dorongan serta ban-
tuannya sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Tanah lainnya serta
pihak-pihak lain yang telah banyak membantu lancarnya
penelitian ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi
ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan
kritik sangat kami harapkan untuk kesempurnaan skripsi
ini
.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang berke-
pentingan.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bogor, 3 Jumadilakhir 1412 H
9 Desember 1991 M
Latar Belakanq
Semula Indonesia merupakan negara penghasil dan
pengekspor gula terbesar di dunia setelah Kuba. Hal ini
terjadi sebelum perang dunia 11. Pada masa itu para
petani dipaksa untuk menyerahkan lahan-lahan kelas 1
kepada pengusaha perkebunan tebu yang pada umumnya adalab
kalangan pabrik gula. Jaman kolonial telah memaksa tanah-
tanah yang subur untuk disewa pemerintah guna ditanami
tebu. Pada masa kejayaannya produktivitas gula di Indone-
sia mencapai 17.67 ton hablur per hektar, ha1 itu merupa-
kan suatu prestasi yang belum dapat diungguli sampai saat
ini
.
Pada masa pendudukan Jepang, industri gula mulai
kehilangan arti. Posisinya sebagai komoditi strategis
telah luntur. Hal ini disebabkan kerusakan yang ditimbul-
kan perang dan revolusi yang mengakibatkan kemerosotan
produksi gula di Indonesia. Datangnya depresi ekonomi
dunia merupakan alamat buruk bagi perkebunan besar yang
sedang mekar. Dan kemerosotan produksi gula nasional
mencapai titik terendah pada tahun 1967, saat itu Indone-
sia mulai kehilangan peran sebagai eksportir. Produksi
gula dalam negeri tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan
penduduk yang berkembang begitu pesatnya. Fenomena ini
Berbagai usaha untuk mengembalikan sukses di bidang
produksi gula nasional telah dilakukan pemerintah. Adapun
usaha yang dilakukan di antaranya adalah : (I) perluasan
areal tebu ke luar Jawa (ekstensifikasi); (2) rehabilitasi
pabrik-pabrik gula yang ada; (3) pembangunan pabrik-pabrik
gula kecil di luar Jawa; dan ( 4 ) Intensifikasi penanaman
tebu rakyat, terutama di pulau Jawa.
Usaha-usaha tersebut selanjutnya disertai dengan
sebuah terobosan untuk mengatasi kelesuan industri gula,
yaitu dengan diberlakukannya Instruksi Presiden RI nomor 9
tahun 1975 tentang pelaksanaan program Tebu Rakyat Inten-
sifikasi (TRI). Akan tetapi dalam pelaksanaannya TRI
banyak menemui hambatan, terutama dalam menghadapi sikap
mental para petani. Secara kultural, petani di pulau Jawa
mempunyai keterikatan untuk memanfaatkan lahan yang dimi-
liki untuk tanaman pangan, terutama padi. Benturan peng-
gunaan lahan untuk tebu di satu pihak dan untuk padi sawah
dalam menunjang usaha mempertahankan swasembada beras
nasional telah mengisyaratkan perlunya usaha-usaha lain
untuk menyelaraskan kedua kepentingan tersebut.
Di samping itu kemerosotan produksi gula tebu juga
disebabkan menurunnya produktivitas lahan. Penggunaan
lahan yang terus menerus serta pemupukan yang berat dengan
pupuk-pupuk anorganik juga merupakan penyebab menurunnya
produktivitas lahan tersebut. Untuk itu usaha intensifi-
kasi pertanian dirasakan merupakan langkah yang tepat
Selain pemupukan yang tepat, tanaman tebu juga membu-
tuhkan pengolahan tanah yang tepat pula. Kondisi fisik
tanah yang baik perlu diusahakan untuk menunjang perturnbu-
han tanaman yang baik. Hal ini berhubungan erat dengan
struktur tanah. Sistem penggunaan tanah yang umum dilaku-
kan pada perkebunan tebu adalah sistem glebagan. Sistem
ini memungkinkan reduksi sulfat yang berasal dari pupuk ZA
menjadi sulfida pada tanah-tanah perkebunan tebu yang
disawahkan. Dalam suasana aerobik belerang umumnya dalam
bentuk sulfat, tetapi dalam keadaan anaerobik karena
penggenangan, maka bentuk ini akan segera direduksi menja-
di sulfida. Fenomena ini akan menyebabkan unsur-unsur
mikro bereaksi dengan sulfida dan menjadi tidak tersedia
bagi tanaman. Bilamana ha1 ini terjadi secara terus
menerus, tentu saja akan menyebabkan penurunan produksi
tanaman yang dalam ha1 ini adalah tanaman tebu.
Tuiuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak
penggunaan pupuk ZA (Ammonium Sulfat) secara terus menerus
terhadap status hara mikro tanah (Cu, Zn, Mn dan Fe) pada
beberapa kebun (Pandeyan, Sobokerto, Kuwiran, Singopuran,
dan Gentan) dan hubungannya dengan produksi tebu di per-
kebunan tebu PG Colomadu, PTP XV-XVI Surakarta, Jawa
TINJAUAN PUSTAKA
sifat Umum Tanah Grumusol
Jenis Tanah ini ditemukan di daerah dengan curah
hujan 1 000 sampai 2 500 mm tiap tahun dengan bulan kering
4 bulan dan iklimnya digolongkan dalam Am
-
As (Koppen)atau C, D, E, F (Schmidt dan Ferguson), dibentuk dari
bahan induk endapan batu kapur, batu liat, tufa volkan,
atau aluvium liat, terletak di atas medan miring, berombak
atau bergelombang, mempunyai relief mikro gilgai, umumnya
berada kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut
(Soepardi, 1983)
.
Proses pembentukan tanah ini adalah kalsifikasi,
pedoturbasi dan pencampuran sendiri. Solumnya agak dalam,
berhorizon A-B-C dan retakan mencapai kedalaman 0.5 m,
berwarna kelabu hingga hitam dengan chroma permanen,
tekstur liat dan makin dalam makin berat berstruktur me-
nyerupai bunga kubis di permukaan dan berblok di bagian
dalam, konsistensi teguh bila lembab, lekat bila basah,
keras bila kering, biasanya dijurnpai konkresi kapur dan
Mn, dan di bagian lebih dalam dijumpai bidang licin/
s l i c k e n s l i d e (Soepardi, 1983).
Reaksi tanah berkisar dari agak masam hingga alkalin,
berkadar bahan organik rendah, kejenuhan basa lebih dari
dari 35 %, umumnya jenuh Ca dan Mg dan KTK liat lebih dari
24 me/100 g, keadaan hara tergantung dari bahan induk
tetapi kaya bila berasal dari tufa volkan), P akan diikat
dalam suasana alkalin, mineral liat yang dominan adalah
tipe 2 : 1, permeabilitas lambat dan peka terhadap erosi
(Soepardi, 1983).
Selanjutnya Sarief (1986) mengatakan bahwa Grumusol
mempunyai pH antara 6.0
-
8.0, yaitu asam agak alkalis.Kandungan unsur hara banyak tergantung kepada bahan induk-
nya, yaitu bahan induk dari mergel atau napal, batu liat
dan tufa volkan. Yang berasal dari batu liat dan mergel
umumnya lebih miskin, sedangkan dari tufa volkan relatif
lebih kaya. Mineral liat pada tanah ini adalah dari
golongan montmorilonit. Daya menahan air cukup baik,
sedangkan permeabilitasnya cukup lambat dan sangat peka
terhadap erosi
.
Sifat
nmum
Tanah ReqosolJenis tanah ini ditemukan di daerah dengan iklim
beragam, berasal dari abu volkan, pasir pantai, atau bahan
sedimen yang telah bercerai-berai; berada di medan berge-
lombang, bergunung atau miring, vegetasinya beragam
(Soepardi, 1983)
.
Proses pembentukannya adalah tanpa alterasi atau
alterasi lemah. Solumnya berkisar dari dangkal sampai
dalam, berwarna kelabu hingga kuning, mempunyai horizon
(A)-C tetapi batasnya samar-samar, bertekstur pasir dan
debu, bertekstur tunggal, dan konsistensi gembur serta
Reaksi tanah beragam, kadar bahan organik rendah,
kejenuhan basa beragam dengan KTK rendah, kadar hara
beragam, permeabilitas cepat dan peka terhadap erosi
(Soepardi, 1983).
Menurut Sarief (1986), Regosol mempunyai sedikit atau
belum banyak perkembangan profilnya. Oleh sebab itu
umumnya tebal solum tanah tidak melebihi 25 cm. Tanah ini
berwarna kelabu, coklat atau coklat kekuning-kuningan
sampai keputih-putihan. Strukturnya lepas atau butir
tunggal, sedang teksturnya pasir sampai lempung berdebu,
konsistensi lepas atau teguh dan keras atau pejal bila
memadat. Bahan induknya adalah dari abu volkan, merge1
atau napal dan pasir pantai. Kandungan unsur haranya
banyak tergantung dari bahan induk tadi. Tanah ini mem-
punyai permeabilitas dan infiltrasi yang cepat sampai
sangat cepat, daya menahan air sangat rendah dan sangat
peka terhadap erosi.
S i f a t UIIIUBL Tanah Mediteran
Jenis Tanah ini dijumpai di daerah dengan curah hujan
800 hingga 2 500 mm setahun dengan bulan kering lebih dari
3 bulan dan iklimnya tergolong Aw atau Am (Koppen) atau C,
D dan E (Schmidt dan Ferguson); dibentuk dari bahan induk
batu kapur berkristal, batu endapan mengandung kapur, batu
atau tufa volkanik, bereaksi sedang hingga alkalin; ter-
bentuk di atas medan berombak hingga berbukit dari 0
sampai 700 m di atas permukaan laut; vegetasi utama
Proses pembentukan tanah ini adalah liksiviasi,
solumnya agak dalam, mempunyai horizon A-B2-C bila terben-
tuk dari tufa atau A-BZt-C bila terbentuk dari batu kapur;
berwarna kuning sampai merah, warnanya mantap atau ber-
khroma tinggi; bertekstur lempung hingga liat, di horizon
B2 terdapat kadar liat maksimum; struktur berblok hingga
prismatik clan konsistensi teguh (Soepardi, 1983).
Reaksi tanah berkisar dari agak masam hingga alkalin;
berkadar bahan organik rendah; kejenuhan basa lebih dari
35 %, jenuh Ca dan Mg dan KTK liat lebih dari 24 me/100 g
dengan permeabilitas baik; agak peka terhadap erosi;
mineral liat terdiri dari campuran tipe 1 : 1 dan 2 : 1
(Soepardi, 1983).
Sedangkan Sarief (1986) menyatakan bahwa tanah ini
mempunyai solum yang cukup tebal, yaitu antara 90 sampai
200 cm, tetapi batas antara horizon tidak begitu jelas.
Warna tanah coklat sampai merah. Teksturnya agak berva-
riasi dari lempung sampai liat, dengan struktur gumpal
sampai gumpal bersudut, sedangkan konsistensinya gembur
sampai teguh. Pada horizon A atau lapisan tanah atas
paling tinggi 3 % bahan organik. Reaksi tanah dicirikan
pH antara 6.0 sampai 7.5. Kadar unsur hara umumnya ting-
gi, tetapi banyak tergantung dari bahan induknya. Bahan
induknya adalah batu kapur, batuan endapan dan tuf volkan.
Sifat U m m Tanah Aluvial
Tanah aluvial ditemukan di daerah dengan iklim yang
beragam; terbentuk dari bahan induk aluvial atau koluvial;
terbentuk di atas medan datar sampai agak bergelombang di
dataran rendah, cekungan atau daerah banjir sungai; vege-
tasinya beragam (Soepardi, 1983).
Proses pembentukan tanah ini adalah tanpa alterasi
atau alterasi lemah. Tanah ini belum memperlihatkan
pembentukan horizon, umumnya berwarna kelabu hingga cok-
lat; bertekstur pasir dan debu; berstruktur qumpal atau
tanpa struktur; dan konsistensi teguh bila lembab, plastis
bila basah dan keras bila kering (Soepardi, 1983).
Reaksi tanah beragam, kadar bahan organik tergolong
rendah, kejenuhan basa sedang hingga tinggi dan KTK ting-
gi; kadar hara tergantung dari bahan induk; permeabilitas
lambat; dan peka terhadap erosi (Soepardi, 1983).
Sedangkan menurut Sarief (1986), Tanah aluvial ini
juga disebut sebagai tubuh tanah endapan atau recent
deposits yang belum memiliki perkembangan profil yang
baik. Tanah ini berwarna kekelabu-kelabuan sampai ke-
coklat-coklatan. Tekstur tanahnya adalah liat atau liat
berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 50 %. Struk-
turnya pejal atau tanpa struktur, sedangkan konsistensinya
keras bila kering dan teguh bila lembab. Kandungan unsur
haranya relatif kaya tergantunq kepada bahan induknya.
Reaksi tanahnya sangat bervariasi dari masam, netral
sampai basa. Permeabilitas umumnya lambat atau drainase-
nya rata-rata sedang dan cukup peka terhadap erosi.
Proses pembentukannya adalah alterasi lemah atau tanpa
pembentukan.
Botani dan Svarat Tumbuh Tebu (Saccharu~n offieinarum L.)
Tebu termasuk dalam tumbuhan kelas Monocotyledoneae,
ordo Glumaceae, Famili Gramineae, Sub famili Andropogo-
neae, dan Genus Saccharum. Terdapat lima species tebu
yang mempunyai arti penting dalam pemuliaan tebu untuk
tujuan komersial. Kelima species tersebut adalah : Sac-
charum officinarum, S. sinensis, S. barbei, S. spontaneum,
dan S. robusta (Sudiatso, 1983).
Batang tebu terdiri dari ruas-mas yang dibatasi oleh
buku-buku. Pada setiap buku terdapat mata tunas (bud) dan
bakal akar (Muljana, 1982; Sudiatso, 1983).
Selanjutnya Sudiatso (1983) juga mengatakan bahwa
tanaman tebu (S. officinarum L.) merupakan salah satu
tanaman penting sebagai penghasil gula. Sebagian besar
produksi gula dunia berasal dari tebu. Batangnya merupa-
kan bagian terpenting dalam memproduksi gula, karena
mengandung nira. Panjang batang terbagi atas beberapa
ruas, jarak antar ruas tanaman tebu dipengaruhi oleh
faktor luar, antara lain : iklim, kesuburan tanah, keadaan
air dan kesehatan tanaman. Batang tanaman yang sehat
atas ruas batang semakin panjang dan kemudian memendek di
bagian puncaknya.
Tanaman tebu membutuhkan iklim panas dan lengas.
Tanaman ini ditemukan antara 35O lintang utara dan 35O
lintang selatan, yaitu pada daerah tropis dan sub tropis
(Wirjodihardjo, 1953)
.
Selanjutnya Notojoewono (1964)menyatakan bahwa iklim sangat berpengaruh terhadap pertum-
buhan, hasil tebu, rendemen dan gula. Tanaman tebu tumbuh
baik di daerah tropik sampai sub tropik di sekitar khatu-
listiwa sampai dengan batas isotherm 20° C , yaitu 3g0
lintang utara sampai 35O lintang selatan. Di Indonesia
tanaman ini banyak diusahakan di dataran rendah. Suhu
optimum bagi pertumbuhan tebu berkisar antara 24O C sampai
30° C. hpabila kurang dari 24O C, aktivitas hormon tumbuh
berkurang dan pertumbuhannya terhambat, sedangkan pada
suhu di atas 30° C proses respirasi tanaman tebu berjalan
cepat sehingga akumulasi pembentukan gula tidak terbentuk
karena terbongkar lagi untuk respirasi. Curah hujan yang
baik adalah 1 500
-
3 000 mm per tahun dengan penyebaranyang sesuai untuk pertanaman tebu. Selanjutnya juga
dijelaskan bahwa dalam masa pertumbuhan tanaman tebu
banyak memerlukan air, sedangkan menjelang masa masak dan
siap dipanen dikehendaki suasana yang kering tidak ada
hujan, sampai pertumbuhan tanaman terhenti. Dengan demi-
kian tanaman tebu menghendaki adanya perbedaan yang nyata
man tebu di pulau Jawa umumnya memiliki musim kemarau dari
bulan Mei hingga Oktober dan musim hujan dari bulan Nopem-
ber hingga April. Oleh karena itu maka waktu tanam ter-
baik adalah bulan Mei, Juni dan Juli. Jika tidak ada
hujan dapat digantikan dengan pemberian air irigasi.
Pupuk %A (Ammonium Gulfat) dan Penuamhnva terhadap Tanah
Tebu termasuk golongan tanaman yang membutuhkan
banyak hara tanah, untuk itu tanaman tebu perlu dipupuk
meskipun pada umumnya tanaman tebu ditanam pada tanah yang
subur (Adisewojo, 1982). Pupuk yang banyak yang diqunakan
untuk pertanaman tebu adalah pupuk ZA. Hasil gula dari
tanaman tebu berkaitan erat dengan pemupukan ini (~irjodi-
hardjo, 1953)
.
Ammonium sulfat atau rumus kimianya (NH4)2S04 di
Indonesia dikenal juga dengan nama ZA (Zwavelzure
Amoniak). Pupuk ini dihasilkan dari reaksi sederhana :
2NH3
+
H2S04---
> (NH4)2S04Pupuk ini mengandung 21 % N dan memberikan efek residu
masam terhadap tanah, terutama apabila diberikan secara
terus menerus. Sisa ~ 0akan melarutkan A1 pada mineral ~ ~
-liat, sehingga penurunan produksi tanaman akan terjadi
dengan ta j
am.
Ammonium sulfat merupakan pupuk kristal yang berwarna
putih, mengandung f 23 % S sebagai hara esensial. Di
dalam tanah (NH4) 2S04 cepat larut, kemudian NH4' dibebas-
larut dalam larutan tanah dan dapat digunakan langsung
oleh tanaman (Leiwakabessy dan Sutandi, 1988).
Selanjutnya Soepardi (1983) menyatakan bahwa ammonium
sulfat dihasilkan secara sintetik. Ion NH*+ dalam keadaan
yang tepat dapat dinitrifikasikan, jadi membantu memper-
lancar penggunaan nitrogen. Di sawah, ion NH4+ tetap
berada dalam bentuk ini dan terhindar dari kemungkinan
tercuci, karena ia bereaksi dengan kompleks koloidal.
Karena pupuk ammonium sulfat bersifat masam, maka penggu-
naan di tanah ber-pH sedang hingga basa memberikan hasil
yang memuaskan.
Kadar nitrogen dalam pupuk ZA antara 20.5
-
21.0 %.pupuk ini dapat dikatakan tidak higroskopis, baru akan
menarik air dari udara pada kelembaban nisbi
+
80 % pada30° C. Oleh karena itu jika dipakai terus menerus pupuk
ini akan mengasamkan tanah, maka dikatakan bahwa pupuk ini
mempunyai reaksi fisiologis masam. Pengaruh mengasamkan
tanah ini dinyatakan dengan equivalent acidity-nya.
Equivalent acidity (EA) adalah jumlah CaCQ3 (kg) pupuk
yang diperlukan untuk meniadakan keasaman yang disebabkan
oleh 100 kg pupuk yang bersangkutan. Untuk ZA nilai
equivalent acidity-nya adalah 110 (Sarief, 1985).
Menurut Tisdale, Nelson dan Beaton (1985), ammonium
sulfat (ZA) mempunyai keuntungan karena bersifat tidak
tanaman, karena pupuk tersebut merupakan sumber N dan S
yang baik.
Pupuk ZA telah lama dipergunakan sebagai pupuk utama
di perkebunan tebu. Sampai tahun 1960 saja penggunaan ZA
di pabrik gula mencapai 30 600 ton. Pupuk ZA ini mudah
hancur dalam air, tetapi karena mudah diserap oleh butir-
butir tanah (Notojoewono, 1964).
Wirjodihardjo (1953), juga mengatakan bahwa penggu-
naan ZA yang terlalu banyak di perkebunan tebu akan menye-
babkan rendemen gula menurun. Bilamana karena pemupukan
dengan ZA, amoniak dinitrif ikasikan maka ion-ion
so4'-
yang ditinggalkan mengakibatkan naiknya kadar H+ dan ini
mengganggu keseimbangan antara ion-ion di dalam air tanah.
Air pengairan yang banyak mengandung elektrolit akan
mendesak ion-ion H+ yang ada di dalam kompleks tanah liat
ini dan menggantinya dengan kation-kation air pengairan.
Qleh sebab itu maka bahaya kemasaman karena pemupukan
dengan ZA tak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi bila air
pengairan mengandung hanya sedikit elektrolit-elektrolit
dan reaksi air pengairan masam, maka lambat laun pemupukan
ZA akan menimbulkan tanah yang masam.
P e r i l a h Beleranu dalam Tanah
Kadar belerang dalam kerak bumi diperkirakan sekitar
0.06
-
0.1 % dan merupakan unsur yang ke-13 terbanyak.Belerang juga banyak terdapat dalam air laut dalam bentuk
kadarnya rendah antara 0.5
-
50 ppm, kecuali yang berasaldari danau salin atau daerah endapan garam sulfat, kadar-
nya dapat mencapai 6 %. Belerang juga dapat dihasilkan
oleh industri dalam bentuk SO2 yang secara langsung dapat
diambil oleh tanaman. Kadar 0.5 ppm SO2 di udara tergo-
Long sangat tinggi, sehingga dapat meracuni tanaman yang
sensitif (Tisdale, Nelson dan Beaton, 1985).
Belerang di dalam tanah mengalami proses mineralisasi
dan immobilisasi (Buckman dan Brady, 1959). Bentuk orga-
nik harus dimineralisasi oleh jasad mikro sebelum dapat
diserap tanaman, ha1 ini diilustrasikan oleh Soepardi
(1983) sebagai berikut :
Belerang organik ----> Hasil pelapukan
----
> Sulfat(Protein dan kom- (H2S dan sulfida
binasi lainnya) lain)
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan perubahan terse-
but adalah kelembaban, suhu, dan kemasaman tanah (Waksman
dan Starkey, 1961).
Ada tiga sumber alam dimana tanaman dapat memperoleh
belerang, yaitu : (a) mineral tanah, (b) gas belerang
dalam atmosfir, dan (c) belerang yang terikat secara
organik. Ada beberapa mineral tanah yang mengandung
belerang dan belerang ini dibebaskan menjadi tersedia bagi
tanaman, contohnya sulfida besi, nikel dan tembaga (Soe-
pardi, 1983)
.
Kemudian Sarief (1986) menggambarkan siklus belerang
ana am an
--+ Hewan Belerang Oksidadari fosil
Immobilisasi Mineralisasi
t
I
sulfat-sulfat < H U ~ anr
Oksidasi Reduksi
7
rn
H2S
=+---
Sulfida-sulfida Belerang [image:30.556.48.491.71.365.2]t
I
Gambar 1. Siklus Peredaran Belerang di Alam (Sarief,
1986)
Selanjutnya Leiwakabessy (1988) mengatakan bahwa
belerang terdapat dalam bentuk sulfida besi dari berbagai
logam seperti pirit dan markasit (FeS2), sfalerit (ZnS),
chalcopirit (CuFeS2), cobaltit (CoAsS), galena (PbS),
pirkotit (Fellsl2), arsen pirit (FeS2.FeAs2), pentlondit
(Fe,Ni), S8. Dalam batuan, S sering berasosiasi dengan
unsur-unsur seperti Fe, Cu, Zn, Co, Au dan lain-lain.
Bentuk-bentuk belerang di dalam tanah merupakan bentuk
anorganik dan organik. Bentuk S anorganik meliputi sulfat
terlarut, SO4'- teradsorpsi, -SO4- diendapkan, dan
S-anorganik tereduksi. Sedangkan bentuk S-organik terdiri
dari S-mudah direduksi, S-diikat karbon dan S--organik yang
bentuk ~ 0tetapi dalam suasana anaerobik akan direduksi ~ ~
-menjadi sulfida.
Sulfat dapat tereduksi menjadi sulfida yang membentuk
senyawa-senyawa sukar larut dengan besi, mangan, seng dan
sebagainya (Engler dan Patrick, 1975). Dalam keadaan
tergenang sulfat akan berubah menjadi sulfida besi ( ~ e ~ + )
yang sukar larut (Ponnamperuma, 1972).
Keadaan reduksi akan lebih menonjol pada tanah-tanah
bertekstur berat dan di daerah sub soil. Menurut Van De
Venter (1915) dalam Notojoewono (1964) dikatakan bahwa
salah satu penyebab tidak suburnya tanah di perkebunan
tebu adalah adanya bahan yang tereduksi. Tanah yang
kekurangan udara (terendam air terlalu lama, becek) menim-
bulkan proses reduksi yang menghasilkan racun bagi tanaman
seperti sulfida besi yang berwarna hitam yang sangat
meracuni tanaman.
Selanjutnya De Datta (1981) mengemukakan bahwa trans-
formasi utama belerang pada tanah-tanah tergenang adalah
reduksi sulfat menjadi sulfida dan perubahan belerang
organik menjadi H2S ini bereaksi dengan ion-ion logam
berat dalam tanah (seperti ~ e ~ + , 2n2+, dan cu2+) yang
menjadikan sulfida tidak larut. Akibatnya unsur mikro
menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Hal ini juga dinya-
takan oleh Elkins dan Ersminger (1971) bahwa potensial
total untuk seluruh unsur belerang yang bersenyawa dengan
unsur logam serta H2S meningkat.
U n s w M i k r o tCu, Zn. Eln dan Fe) dalam Tanah
Unsur mikro adalah unsur hara esensial bagi tanaman
yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit (Soepardi, 1983;
Sarief, 1986; Tisdale, Nelson dan Beaton, 1985).
Perhatian terhadap unsur mikro di akhir dua dasawarsa
ini meningkat dengan pesat. Hal tersebut disebabkan : (a)
terangkutnya unsur mikro dalam tanaman menyebabkan ke-
tersediaan dalam tanah mencapai titik tidak dapat menun-
jang pertumbuhan normal; (b) penggunaan jenis unggul dan
pemakaian pupuk makro yang meningkat dosisnya mempertajam
menurunnya unsur mikro tanah; (c) pengqunaan kadar pupuk
berkadar unsur tinggi meniadakan peluang digunakannya
bahan-bahan kurang murni, sehingga kontaminasi unsur mikro
dalam pupuk berkurang, dan (d) kemampuan mengenal gejala
kekurangan unsur mikro telah demikian meningkatnya diban-
dingkan dengan masa lalu (Soepardi, 1983).
Menurut Leiwakabessy (1988), sumber unsur mikro
berasal dari batuan beku (sumber utama), batuan sedimen
dan batuan metamorfik. Selanjutnya V. M. ~oldschmidt
d a l a n Leiwakabessy (1988), rata-rata kandungan unsur mikro
Kandungan Cu dalam tanah sangat rendah, yaitu berki-
sar antara 10
-
80 ppm. Pada pH yang 'lebih rendah dari6.9 ion divalen cu2+ merupakan ion yang dominan, sedangkan
pada pH yang lebih tinggi lagi maka bentuk ell(OlQ2 paling
banyak ditemukan. Bentuk CUOH+ banyak ditemukan pada pH
sekitar netral (Tisdale, Nelson dan Beaton, 1985).
Lindsay (1972b) mengemukakan suatu reaksi kesetirnba-
ngan antara Cu dalam larutan tanah dengan Cu dalam kom-
pleks jerapan tanah, yaitu sebagai berikut :
cu2+
+
tanah-
Cu-tanah+
2H+[~u2+] = 10-3-2 CH+I
Kelarutan cu2+ sangat rendah dan tergantung pH.
Tisdale, Nelson dan Beaton (1985) menyatakan reaksi hidro-
lisis Cu sebagai berikut :
ell2+
+
H ~ O CUOH++
H+CUOH+
+
H20-
Cu (OH)+
H+Semakin tinggi konsentrasi ion Hf dalam larutan tanah maka
bentuk ion Cu yang dominan adalah cu2+.
Unsur Cu dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat
sedikit, tetapi mempunyai peranan yang cukup penting.
Anderseon dan Underwood dalam Lindsay (1972a) menyebutkan
bahwa Zn, Cu dan Mo merupdkan unsur-unsur hara mikro yang
sering ditemukan dalam keadaan kurang pada tanah-tanah
pertanian. Unsur-unsur ini merupakan bagian penting dari
Lebih lanjut Sabiham, Djokosudardjo dan Soepardi
(1982) mengemukakan bahwa tanah-tanah yang kekurangan Cu
biasanya dicirikan oleh bertekstur pasir, mengandung bahan
organik tinggi dan tanah yang mempunyai pH tinggi. Jumlah
Cu yang dikandung dalam tanah berkisar dari 2 sampai 100
P P ~
.
Gejala defisiensi pada berbagai tanaman ditunjukkan
oleh warna tanaman yang tidak normal, perkembangan yang
tidak normal, hasil dan buah yang rendah dan panenan yang
rendah pula (Darst and Reeves, 1968 serta Berger, 1965
dalam Morvedt, Giordano dan Lindsay, 1972). Selanjutnya
Soepardi (1983) menambahkan bahwa kekurangan Cu akan
mengganggu sintesis protein dan menyebabkan senyawa nitro-
gen larut meningkat. Kepekatan qula-reduksi pada tanaman
yang kekurangan Cu adalah rendah sedangkan kadar asam
organiknya tinggi.
Seng (Zn) merupakan penyusun dari berbagai enzim
logam meliputi dehidrogenase, di antaranya dehidrogenase
alkohol dan laktat. Di samping itu seng juga dapat ber-
fungsi sebagai kofaktor berbagai enzim tetapi tidak mem-
punyai kekhususan yang tinggi. Kekurangan seng menyebab-
kan pertumbuhan secara drastik terganggu, daun mengecil
dan ruas tanaman memendek membentuk suatu roset, yaitu
ruas-ruas gaga1 memanjang, sehingga daun dari beberapa
Sarief (1986) menyatakan juga bahwa kekurangan Zn
pada tanaman mempunyai beberapa macam gejala pokok yang
berbeda dan tergantung pada jenis-jenis tanaman. beberapa
gejala kekurangan Zn adalah : daun-daun kecil, daun men-
galami salah bentuk (kecil dan menyempit)
,
khlorosis padapuncak pertumbuhan baru dan membentuk pertumbuhan meling-
kar (roset) dan pengguguran daun terjadi mulai dari bawah
(base) menuju ke puncak.
Mangan (Mn) di dalam tanaman berfungsi sebagai akti-
vator dari berbagai enzim, di antaranya enzim pentransfer
fosfat dan enzim dalam Daur Krebs. Mangan juga merupakan
bagian penting dari khloroplas dan turut dalam reaksi yang
menghasilkan oksigen. Kekurangan unsur ini akan mempenga-
ruhi susunan khloroplas. Kepekatan mangan yang tinggi
dalam media dapat menimbulkan kekurangan besi dalam tana-
man (Soepardi, 1983).
Dalam keadaan reduksi Mn ditemukan dalam bentuk Mn2+
sedangkan dalam keadaan oksidasi sering dijumpai dalam
bentuk Mn02. Jumlah Total Mn dalam Tanah berkisar antara
20 sampai 3 00 ppm (Sabiham, Dj okosudard j o dan Soepardi,
1982).
Rinsema (1983) menambahkan bahwa persenyawaan Mn yang
larut dapat dioksidasi menjadi tidak larut. Dalam keadaan
yang kurang lebih anaerob, dapat berlangsung reduksi
kembali. Timbulnya kekurangan Mn pada tanah berpasir
menjadi sakit, sedangkan pada pH di bawah 5.4 tanaman
tetap sehat. Gejala kekurangan Mn ini juga diungkapkan
oleh Sarief (1986)
,
bahwa gejala kekurangan Mn menyerupaikekurangan unsur besi, tetapi pada kekurangan Mn tulang
daun yang paling kecilpun tetap berwarna hijau, bahkan
hijaunya seringkali masih terdapat di sisi tulang-tulang
daun
.
Jones (1972) mengemukakan bahwa gejala kekurangan Mn
akan terlihat jika konsentrasi dalam jaringan tanaman
kurang dari 20 ppm pada bahan kering. Akan tetapi banyak-
nya kadar kecukupan adalah pada konsentrasi antara 20
sampai 500 ppm Mn. Dan pada konsentrasi di atas 500 ppm
kemungkinan akan menyebabkan keracunan bagi beberapa
tanaman. Selanjutnya dikatakan oleh Gorsline et a l .
(1965) d a l a m Jones (1972) bahwa konsentrasi Mn dalam
jaringan ini akan bervariasi dari daun ke daun lainnya,
konsentrasinya akan meningkat dari daun di bagian bawah ke
atas. Hal ini juga dinyatakan oleh Leiwakabessy (1988),
bahwa kadar normal Mn dalam tanaman berkisar antara 20
-
500 ppm. Kekurangan Mn biasanya terjadi bila kadarnya
dalam bagian atas menjadi 15
-
25 ppm. Mn diabsorbsitanaman dalam bentuk ion mangano, Mn2+, dan juga dalam
bentuk molekul senyawa kompleks organik. Bentuk-bentuk
ini dapat diserap melalui daun.
Besi (Fe) merupakan bagian dari group prostetik
protein. Group prostetik yang mengandung besi ialah
porfirin besi, seperti sitokhrom, katalase, peroksidase
dan dehidrogenase. Besi juga dapat pula berperan sebagai
kofaktor dari berbagai enzim, tetapi jarang sekali mem-
punyai kekhususan tertentu. Sebagian besar dari besi di
dalam daun dijumpai sebagai bagian khloroplas dan besi
sangat esensial dalam pembentukan khloxofil (Soepardi,
1983).
Tisdale, Nelson dan Beaton (1985) serta Leiwakabessy
(1988) menyatakan bahwa tanaman terutama mengambil Fe
dalam bentuk ~ e dan Fe-kompleks yang larut, walaupun ~ +
~ e ~ + - ~ u n dapat diserap. Bentuk aktif dalam tanah adalah
~ e ~ + . Kadar Fe sebesar 50
-
250 ppm dalam tanah dinilaicukup. Besi diambil oleh tanaman dalam bentuk ion ataupun
dalam bentuk garam-garam kompleks organik (chelate) dan
dapat diabsorbsi oleh daun apabila besi sulfat ataupun
kompleks Fe-organik diberikan melalui daun. Kekurangan Fe
sering terjadi di tanah-tanah masam apabila dilakukan
pemupukan fosfat yang terlalu berat.
Neubert et al. (1969) dalam Jones (1972) menyatakan
bahwa pada umumnya kadar Fe 50 ppm atau kurang dalam bahan
kering akan menyebabkan ge jala def isiensi. Kadar kecuku-
pan Fe dalam tanaman berkisar antara 50 sampai 250 ppm.
Konsentrasi Fe dalam tanaman muda dapat sangat tinggi,
Menurut Leiwakabessy (1988), faktor-faktor yang
mempengaruhi ketersediaan dan pergerakan Fe di dalam tanah
adalah : (1) ketidakseimbangan ion : Fe/ (Cu
+
Mn),
dimanaCu dan atau Mn tinggi akan menyebabkan defisiensi Fe; (2)
-
pengaruh pH, HC03 dan C03 di daerah berkapur; (3) pengge-
nangan; (4) bahan organik; dan (5) interaksi dengan unsur
lain. Kelebihan unsur hara seperti Co, Cu, dan Zn juga
kadar P dan Mo yang tinggi dapat menyebabkan defisiensi
unsur Fe.
Fe, Mn dan Cu yang dioksidasikan umumnya kurang
larut pada pH yang biasa dijumpai dalam tanah dibandingkan
bentuk-bentuk yang direduksikan. Kelarutan Fe dalam tanah
ditentukan oleh konsentrasi oksidanya. Hidrolisis, pH,
khelat, reauksi dan oksidasi merupakan faktor yang penting
dalam ha1 ini. Fe-inorganik (111) di dalam larutan tanah
dapat dihidrolisis menjadi bentuk Fe2 (OH) 24i, ~ e ~ + ,
-
F ~ o H ~ + , F ~ ( O H ) 2i, F ~ ( O H ) 3° dan Fe(0H)
.
Empat bentukpertama tersebut terjadi pada pH di atas 7.0. Tanaman
dapat mengabsorbsi ion-ion tersebut tergantung pada kese-
timbangan dari masing-masing bentuk ion yang terjadi
B DAN ?SETODE
Waktu dan Tapat Penelitian
Pengambilan contoh tanah dilakukan pada beberapa blok
kebun (kebun Pandeyan, Sobokerto, Kuwiran, Singopuran,
Gentan dan Klodran) di lahan perkebunan tebu PG Colomadu,
PTP XV-XVI Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan Peta
Tanah dari lembaga Penelitian Tanah dan Pemupukan (1964),
jenis tanah yang terdapat di wilayah kerja PG Colomadu
tersebut adalah : Grumusol, Regosol, Hediteran dan Aluvi-
al. Pengambilan contoh tanah tersebut dilakukan dari
tanggal 13 sampai 25 Agustus 1990 pada lokasi yang di-
perkirakan terdapat pengendapan senyawa sulfida dan unsur
mikro
.
Pengambilan contoh tanaman dilakukan pada bulan
Desember 1990 terhadap daun ke-3
-
4 dari atas pada lokasipengambilan contoh tanah. Adapun contoh daun yang diambil
adalah umur 3
-
4 bulan.Analisa sifat kimia clan fisika tanah serta jaringan
dilakukan di laboratorium Jurusan Tanah, Fakultas Pertani-
an, Institut Pertanian Bogor dan Laboratorium Balai Pene-
litian Tanaman Pangan (Balittan) Cimanggu, Bogor. Analisa
tanah dan tanaman dilakukan dari bulan September 1990
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan untuk penelitian berupa sebidang
lahan di perkebunan tebu, daun tebu umur 3
-
4 bulan,bahan-bahan kimia untuk penetapan sifat-sifat fisik dan
kimia tanah dan jaringan tanaman serta air sebagai pelarut
berbagai bahan kimia yang digunakan dalam penelitian.
Adapun alat yang digunakan adalah : Bor belgi, cang-
kul, pisau lapang, meteran, plastik, Munsell Soil Color
Chart, kertas label, alat-alat tulis, serta alat-alat laboratorium untuk penetapan sifat-sifat fisik dan kimia
tanah serta jaringan tanaman di laboratorium.
Netode
Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil
survai dengan mengacu kepada perkiraan adanya timbunan
senyawa logam sulfida yang berwarna hitam (atau warna
gley) pada sub soil.
Analisa contoh tanah didasarkan pada pengamatan tiap
lapisan/horizon tanah dari suatu profil.
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah
berupa sifat-sifat kimia tanah berupa 5 0 ~ ~ - sebelum diok-
sidasi (yaitu analisa contoh tanah yang dikeringkan dari
lapang tanpa perlakuan tambahan) dan ~ 0 setelah diok- ~ ~
-sidasi (yaitu analisa contoh tanah yang telah diberi
perlakuan oksidasi dengan H202), unsur-unsur mikro (Cu,
Zn,
Mn,
Fe) sebelum dioksidasi (tanpa perlakuan H202) danKTK, KB, pH dan sifat fisik tanah berupa tekstur tanah.
Sedangkan analisa jaringan tanaman didasarkan atas jari-
ngan daun tebu umur 3
-
4 bulan pada daun ke 3-
4 dariatas/pucuk.
Adapun metode yang digunakan dalam penetapan sifat-
sifat kimia dan fisik tanah dan tanaman ini dapat dilihat
pada Tabel 2.
Data produksi tebu, rendemen serta pemupukan pada
lokasi penelitian digunakan sebagai data penunjang dalam
penelitian ini
.
Tabel 2. Bretode Penetapan Sifat-sifat Kimia dan Fisik
Tanah dan Tanaman dalam Penelitian
Jenis Analisa Satuan
Analisa Tanah
-
so4:-
sebelum dioksidasi ppmSO4 setelah dioksidasi ppm
Basa-basa dapat ditukar
Ca-dd me/lOO g
Brg-dd mejl0O g
K-dd me/100 g
Ha-dd me/100 g
KTK me/100 g
KB %
pH H20 ( 1 : 1)
Cu sebelum oksidasi PPm
Zn sebelum oksidasi PPm
Mn sebelum oksidasi PPm
Fe sebelum oksidasi PPm
Cu setelah oksidasi PPm
Zn setelah oksidasi PPm
Mn setelah oksidasi PPm
Fe setelah oksidasi PPm
Tekstur % ( P r Dt L)
-
Metode Analisa
NH,OAc pH 4.8
oksidasi H202
NH40Ac pH 7.0 NH40Ac pH 7.0 NH40Ac pH 7.0 NHdOAc pH 7.0 NHd OAc pH 7.0
pH-meter
HC1 0.05
N
KC1 0.05
N
HCl 0.05
N
HCl 0.05
N
oksidasi H202 oksidasi - H202
oksidasi
HZ02
oksidasi H202 pipet
Analisa Jarinqan Tanaman
Cu-daun PPm pengabuan kering
Zn-daun PPm pengabuan kering
Mn-daun PPm pengabuan kering
[image:42.556.64.501.350.718.2]ElAsIL DAN PKMB AN
Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Lokasi perkebunan tebu PG Colomadu PTP XV-XVI
Surakarta terletak pada ketinggian 110 meter di atas
permukaan laut, tipe iklim CZ-C3 (Oldeman, 1975) dan Awa
(Koppen), jenis tanahnya meliputi Grumusol, Regosol,
Aluvial dan Mediteran (Lembaga Penelitian Tanah dan Pemu-
pukan, 1964). Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa
blok kebun saja, yaitu kebun Pandeyan(PD 11), Sobokerto(SB
XI), Kuwiran (KW)
,
Singopuran (SP),
Gentan (GT) dan Klo-dran (KD). Beberapa informasi tentang lokasi penelitian
disa-jikan pada Tabel Lampiran 2, sedangkan produksi tebu
di lokasi penelitian disajikan pada Tabel Lampiran 3 , 4 ,
5, 6 dan 7. Kelima profil pertama setelah dianalisa akan
sulfatnya setelah dioksidasi menunjukkan gejala pencucian
di lapisan atas dan akumulasi sulfida pada kedalaman
tertentu, sedangkan pada profil di kebun Klodran tidak
menunjukkan adanya gejala akumulasi sulfida sehingga
analisa tanah ini tidak dilanjutkan (Tabel Lampiran 8).
Dugaan akumulasi sulfida ini juga ditunjukkan pada hasil
analisa warna tanah yang semakin gelap. Pada tanah di
kebun Pandeyan dan Sobokerto ditunjukkan dengan penurunan
tingkat value pada warna Munsell Soil Color Chart dan
diikuti dengan akumulasi liat (dari hasil analisa
tekstur). Sedangkan pada tanah di kebun Kuwiran, Singopu-
ran dan Gentan gejala berdasarkan sifat ini kurang tampak
Lokasi penelitian termasuk dalam DAS Bengawan Solo,
suhu rata-rata 29
-
31° C, kelembaban udara 45 - 56 %, dancurah hujan rata-rata 2378.4 mm per tahun. Jarak lokasi
penelitian ini adalah 5
-
12 kin dari PG Colomadu (Gambar 2dan 3).
Pengambilan contoh tanah dilakukan pada saat tanah
dalam keadaan oksidatif, kecuali pada tanah di kebun
Kuwiran dan Gentan yang baru saja ditanami padi dan baru
akan diolah untuk pertanaman tebu, kemungkinan pada tanah
ini keadaan tanah belum oksidatif sepenuhnya.
Secara umum lokasi penelitian merupakan wilayah
dengan fisiografi dataran, reaksi tanah agak masam sampai
agak basa. Hal ini dimungkinkan oleh bahan induk pada
lokasi tersebut berasal dari endapan pasir, abu
pasir/pasir, tuf volkan intermedier
-
basa dan tuf volkanalkali basis (Lembaga Penelitian Tanah dan Pernupukan,
1964). Tanah-tanah di seluruh kebun yang diteliti mem-
punyai kejenuhan basa yang sangat tinggi yaitu mencapai
100 %, ha1 ini terlihat nyata terutama dari kandungan
kalsium dapat ditukar yang sangat mendominasi basa-basa
yang dapat ditukar pada tanah-tanah tersebut (Tabel Lampi-
ran 10). Hal inilah yang menyebabkan tanah-tanah tersebut
J a l a n b e s a r
-
J a l a n k e r e t a a p i_,-.-.
*.+.+.
B a t a s P r o p i n s i [image:45.550.23.518.80.627.2]'*.+
.,.,,*.
r*.-t.*.J.,--l--,(
D i k u t i p d a r i Lembaga P e n e l i t i a n Tanah d a n Pemupukan, 1964
Lokasi penelitian merupakan wilayah perkebunan tebu
yang telah lama diusahakan berpuluh-puluh tahun lamanya,
bahkan sejak jaman kolonial Belanda. Sistem penggunaan
tanah yang umum digunakan dalam perkebunan tebu tersebut
adalah sistem qlebaqan, yaitu penanaman secara bergantian
antara tanaman tebu dan padi sawah. Sebagai usaha inten-
sifikasi pada tanah di perkebunan tebu digunakan pemupukan
ZA. Praktek penggunaan pupuk ZA tersebut telah lama digu-
nakan pada perkebunan tersebut. Semula hanya digunakan
pupuk ZA saja, akan tetapi dengan berkembangnya masalah
pemupukan, kemudian digunakan juga pupuk TSP dan KC1.
Penggunaan pupuk ini semakin lama semakin intensif, ha1
ini dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3, 4, 5, 6 dan 7.
Penvebaran Beleranu dalam Tanah
Kandungan belerang dalam bentuk sulfat sebelum diok-
sidasi pada tanah di kebun Pandeyan dan Sobokerto berkisar
- dari 27 -28 sampai 265.66 ppm SO4 yaitu dari hasil analisa
tanah pada kedalaman 0
-
120 cm. Sedangkan pada tanah dikebun Kuwiran, Singopuran dan Gentan berkisar dari 45.82
sampai 333.46 ppm SO4 yaitu hasil analisa tanah pada
kedalaman 0
-
85 cm. Penyebaran ketersediaan belerang inidapat dilihat pada Tabel Lampiran 10. Sedangkan kandungan
belerang setelah dioksidasi pada tanah di kebun Pandeyan
dan Sobokerto berkisar dari 606.58 sampai 4540.04 ppm SO4
dan pada tanah di kebun Kuwiran, Singopuran dan Gentan
berkisar dari 847.89 sampai 3436.73 ppm SO4 pada kedalaman
Pola penyebaran belerang di dalam tanah dapat dilihat
pada Gambar 4, 5, 6, 7 dan 8. Dari gambar-gambar tersebut
terlihat bahwa pola penyebaran belerang di dalam tanah
yang diteliti sebelum dioksidasi menunjukkan bahwa ke-
tersediaan pada lapisan atas lebih kecil dibandingkan
dengan lapisan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa belerang
tersebut telah tercuci ke lapisan yang di bawahnya. Adanya
pencucian sulfat dari lapisan atas ke lapisan bawah akan
disertai dengan peristiwa retensi sulfat. Sulfat yang
tercuci tersebut akan diretensi oleh tanah. Akibatnya
ketersediaan sulfat di lapisan bawah (sub soil) menjadi
lebih banyak dari pada lapisan atas. Hal ini sesuai
dengan pendapat Soepardi (1983) yang mengatakan bahwa
hampir semua tanah akan menahan sulfat, meskipun jumlah
yang diikat umumnya rendah dan daya retensinya rendah
dibandingkan dengan fosfat. Kapasitas retensi umumnya
lebih tinggi pada bagian bawah daripada lapisan atas.
Demikian juga pola penyebaran belerang dalam tanah
setelah dioksidasi ini menunjukkan adanya akumulasi bele-
rang dalam bentuk sulfida pada kedalaman tertentu. Ting-
ginya belerang yang terukur setelah dioksidasi ini juga
disebabkan oleh terlepasnya belerang dari ikatan mineral-
mineral liat. Selanjutnya oksidasi dengan H2O2 ini juga
akan mengakibatkan penurunan pH. Pada umumnya pola penye-
baran belerang setelah dioksidasi ini akan mengikuti pola
penelitian ini tidak demikian, terutama terlihat pada
tanah di kebun Pandeyan, Sobokerto, Kuwiran dan Gentan.
Hal ini disebabkan tingkat pencucian dan ketersediaan
belerang yang berbeda-beda pada tiap kedalaman tanah.
Sebaran belerang yang tercuci dari lapisan atas dalam
bentuk sulfat akan berubah menjadi sulfida. Perubahan ini
merupakan proses biokimia (Leiwakabessy, 1988). Proses
reduksi ini akan dibantu oleh berbagai bakteri yang tergo-
long dalam dua jenis, yaitu Desulfovibrio dan Desulfoto-
maculum. Organisme-organisme ini menggunakan oksigen
dari gugusan sulfat untuk mengoksidasikan bahan organik
(Soepardi, 1983). Sebagai contoh reaksinya dikemukakan
sebagai berikut :
2 (R-CH ) H)
+
SO'-
---
> 2 (R-COOH)+
2H20+
-5'~lkohoi sutfat Asam Sulf ida
organik organik
K a d s l a m a n (om)
[image:49.559.56.501.193.707.2]0 604 sbL diokeidnei + 604 s t 1 dioksidaai
Gambar 4 . Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun
Kedalaman (cm)
[image:50.550.108.473.59.333.2] [image:50.550.71.475.68.680.2]0 6 0 4 s b l dioksidnoi + 6 0 4 etL diolaridari
Gambar 5. Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun Sobokerto
Gambar 7. Penyebaran Belerang dalam Tanah di Kebun Singopuran
Kodslaman (cm)
0 504 sbL dioksidaei + 604 stL diokaidasi
Penvebaran Unsur Mikro dalam Tanah
Hasil analisa unsur mikro tanah disajikan pada Tabel
Lampiran 10 dan 11.
Adanya ion sulfida di dalam tanah akan segera bereak-
si dengan unsur-unsur mikro. Bentuk-bentuk ini akan
mengendap pada kedalaman tertentu. Pola penyebaran unsur
mikro dalam bentuk sulfida ini ternyata mengikuti pola
penyebaran S-sulfida. Hal ini dapat dilihat pada Tabel
Lampiran 11 dan Gambar 9, 10, 11, 12 dan 13.
Dari Tabel Lampiran 11 tersebut juga dapat diketahui
bahwa miliekivalen S-sulfida < miliekivalen total unsur
mikro dalam bentuk sulfida. Hal ini berarti ada bentuk-
bentuk lain unsur mikro bukan dalam bentuk sulfida. Unsur
mikro tersebut diduga adalah Fe dan sebagian Mn. Hal ini
bisa diduga dari besarnya nilai Mn dan Fe yang terukur
setelah dioksidasi (tidak tersedia). Unsur-unsur tersebut
diduga berasal dari kompleks batuan yang tidak larut atau
dari kompleks adsorbsi yang telah diduduki oleh basa-basa
dapat dipertukarkan (Ca, Mg, K dan Na). Bentuk-bentuk
lain unsur tersebut selain bentuk sulfida yang ikut teru-
kur, misalnya juga dalam bentuk khelat, hidroksida, karbo-
nat ataupun dalam bentuk lainnya yang tidak larut. Se-
dangkan unsur Cu dan Zn diikat dalam bentuk sulfida.
Pengendapan sulfida pada tanah di kebun Pandeyan
terjadi pada kedalaman antara 15
-
30 cm, di kebun Sobo-kebun Kuwiran dan Gentan terjadi pada kedalaman antara 30
-
4 5 cm dan pada kebun Singopuran terjadi pada kedalamanantara 50
-
75 cm.Secara umum dapat dilihat bahwa pengendapan unsur
mikro Cu < Zn < Mn < Fe. Fenomena ini tergantung dari
jumlah unsur-unsur tersebut sebelum dan sesudah dioksida-
si. Rendahnya unsur mikro sebelum dioksidasi pada tanah
yang diteliti selain disebabkan pengikatan oleh senyawa
sulfida juga disebabkan oleh tingginya pH tanah. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh Soepardi (1983) bahwa ke-
tersediaan unsur mikro akan semakin kecil pada pH yang
tinggi, kecuali unsur No dan B.
Kedalaman (cm)
[image:53.556.112.487.375.664.2]0 6-6ulfIda + Cu-6 0 Z ~ A - 6 A M i l - 6 X Ps-6 v T e t a l U . M i k r o
Gambar 9. Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam
Kedalaman (cm)
[image:54.556.81.493.57.691.2]O 6-6ulfida C Cu-S 0 Zn-6 4 Mn-6 X Fe-S v T o t a l U. Milaro
Gambar 10. Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam Tanah di Kebun Sobokerto
Gambar 11. Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam Tanah di Kebun Kuwiran
40
3!3
,-. Y 30
0
n *
\
256
.,
," 20
0
L
ir
;
152
6
1D5 -
0
-
-
-
7V
-
- X
-
-
I
-
E- d
4
0
-
-,
,
I I
0 - 15 1 5 - 30 30 - 45 45
-
60 6 0-
BDKodalsman (om)
K e d a l s m a n (cm)
0 6-Sulfida + Cu-S O Z n - S A Mn-S X Fe-S v Toial U. A(!liro
[image:55.559.119.495.69.352.2]Garnbar 12. Penyebaran S-sulfida dan Unsur Mikro dalam Tanah di Kebun Singopuran
Zn dan M n pada daun. Sebagian besar Fe yang mengendap ini
diduga bukan saja dalam bentuk sulfida, karena jumlah Fe
ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pengendapan
belerang sulfida yang terjadi. Diduga Fe yang terukur
ini selain dalam bentuk sulfida juga dapat terikat sebagai
khelat yang tidak larut. Proses pengkhelatan terjadi
karena pengikatan ion-ion mikro dengan bahan organik
dimana ion-ion tersebut sebagai penerima elektron dan
bahan organik sebagai pemberi elektron. Kekuatan ikatan
kompleks logam (khelat) adalah sebagai berikut (~eiwaka-
bessy, 1988) :
~ e > ~Cu2+ + > ~ i > ~co2+ + > zn2+ >
m2+
Demikian juga pengendapan Cu-S berkorelasi sangat
nyata terhadap pengendapan Fe-S dan cenderung menurunkan
produksi tebu
(r
= -0.715). Kadar Zn daun berkorelasinyata terhadap rendemen tebu. Sedangkan kadar Fe daun
berkorelasi nyata terhadap penurunan rendemen tebu.
Hubungan ini juga dapat dilihat bahwa pengendapan
Zn-S berkorelasi nyata terhadap kadar Fe daun. Demikian
juga kadar Zn daun berkorelasi sangat nyata terhadap pen-
ingkatan kadar Mn daun.
Dari hasil analisa jaringan tanaman (Tabel Lampiran
15) terlihat bahwa berdasarkan hasil analisa uji jaringan
tanaman pada seluruh blok kebun yang diteliti menunjukkan
gejala kekurangan unsur Cu, sedangkan unsur Zn, Mn dan Fe
Fenomena tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Pada saat tanah digenangi, maka reaksi tanah akan
berubah dari suasana oksidatif menjadi reduktif dimana
dalam suasana ini akan terjadi penurunan nilai potensial
redoks (Eh tanah). Dalam suasana tanah yang reduktif ini
maka akan terjadi transformasi sulfat menjadi sulfida dan
konversi senyawa organik menjadi hidrogen sulfida. Hidro-
gen yanq dihasilkan akan bereaksi dengan ion-ion logam
berat di dalam tanah, seperti Fez+, Zn2+ dan cu2+ untuk
menghasilkan senyawa sulfida yang tidak larut. Akibat-
nya ketersediaan belerang menjadi turun. Karena reduksi
Fe3+ menjadi Fez+ mendahului reduksi
so4'-,
maka biasanyaselalu ada ion-ion Fe2+ waktu terbentuk hidrogen sulfida,
sehinqga hidrogen sulfida ini dikonversi menjadi FeS yang
tidak larut. Demikian juga proses ini terjadi pada unsur
Cu dan Zn. Konsentrasi unsur mikro tersebut akan turun
setelah penggenanqan (Ismunadji dan Roechan, 1986).
Beberapa reaksi kimia yang terjadi pada saat proses
tersebut adalah seperti dikemukakan Corey dan Schulte
(1973) dalam Leiwakabessy (1988) :
~ 0
+
IOH+ ~ ~+
8e- --
H ~ S+
4H20Fe(0H)
+
3 ~ ++
e- - ~ e+
~3H20 +Mn02
+
4 ~ ++
2e- Mn2++
H20m 2 +
+
e-mf
Setelah tanah ditanami tebu suasana akan berubah
reduktif menjadi oksidatif yang berlawanan dengan keadaan
sebelumnya. Akan tetapi bentuk sulfida yang mengikat ion-
ion logam berat (unsur mikro) tersebut menjadi tidak
larut. Akibatnya akan terjadi akumulasi sulfida dan
unsur-unsur mikro pada kedalaman tertentu. Hal ini terja-
di karena akumulasi akan meningkatkan konsentrasi unsur
tersebut. Perubahan seperti ini terjadi secara terus
menerus di lahan perkebunan tebu sawah. Akibatnya pengen-
dapan sulfida yang diikuti dengan pengikatan unsur-unsur
mikro (Cu, Zn, Mn dan Fe) akan terakumulasi pada suatu
kedalaman tertentu dan mengakibatkan unsur mikro menjadi
tidak tersedia bagi tanaman. Hal ini selanjutnya akan
KESIMP DAN S
Penggunaan ZA secara terus menerus pada perkebunan
tebu sawah menimbulkan dampak pengendapan sulfida yang
disertai dengan pengendapan unsur hara mikro tanah (Cu,
Zn, Mn dan Fe), sehingga unsur-unsur tersebut tidak dapat
dimanfaatkan oleh tanaman.
Pengendapan sulfida ini berpengaruh nyata terhadap
pengendapan unsur Fe dan tidak nyata terhadap unsur Cu, Zn
dan Mn.
Pengendapan Cu berkorelasi sangat nyata terhadap
pengendapan Fe, tidak nyata terhadap Cu, Zn dan Mn. Akan
tetapi pengendapan Cu ini cenderung menurunkan produksi
tebu. Pengendapan Zn berkorelasi nyata terhadap penurunan
kadar Fe daun. Kadar Zn daun berkorelasi sangat nyata
terhadap kadar Mn daun dan nyata terhadap rendemen tebu.
Sedangkan kadar Fe daun berkorelasi nyata terhadap penuru-
nan rendemen tebu.
Pada seluruh blok kebun yang dit