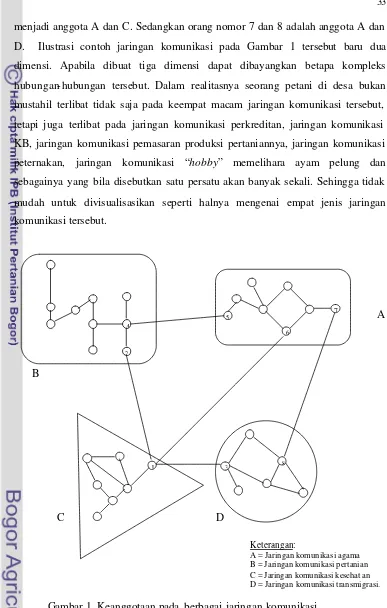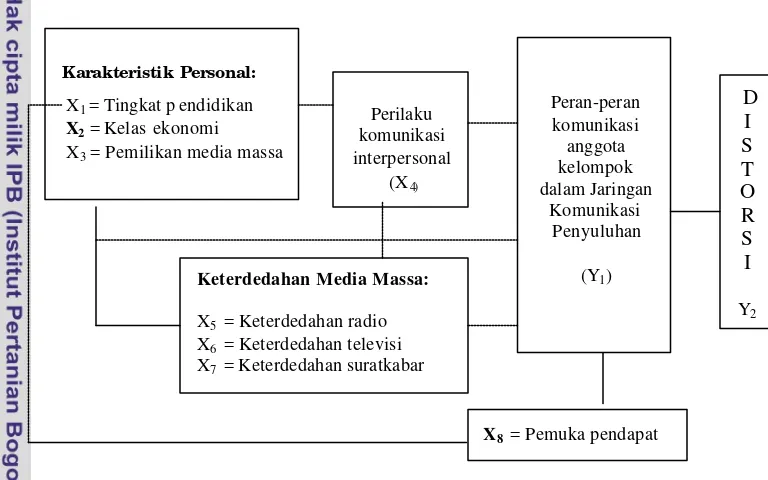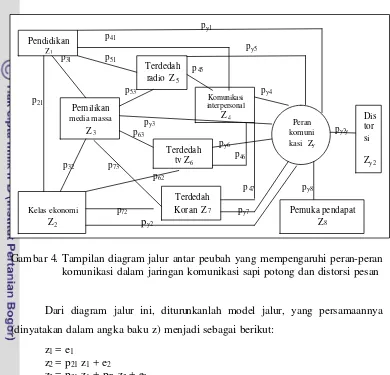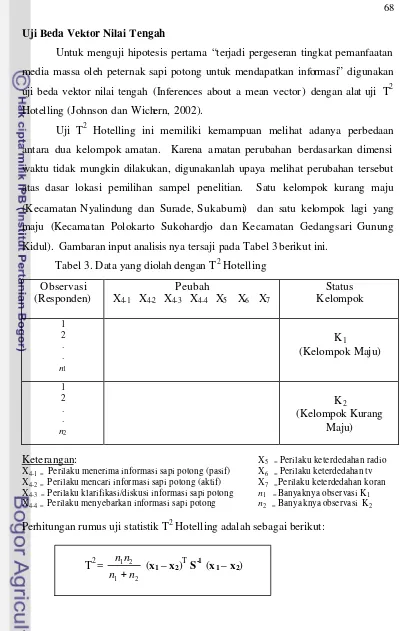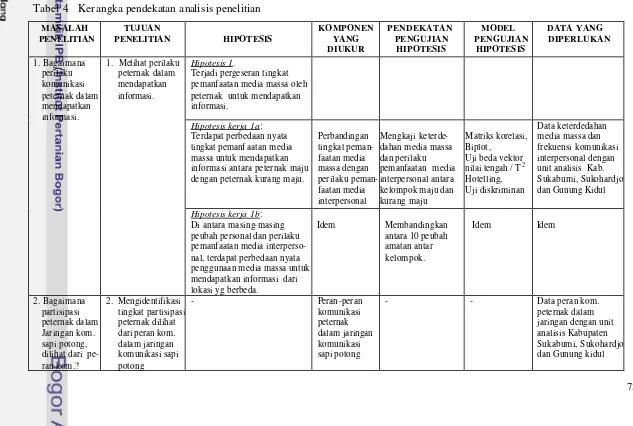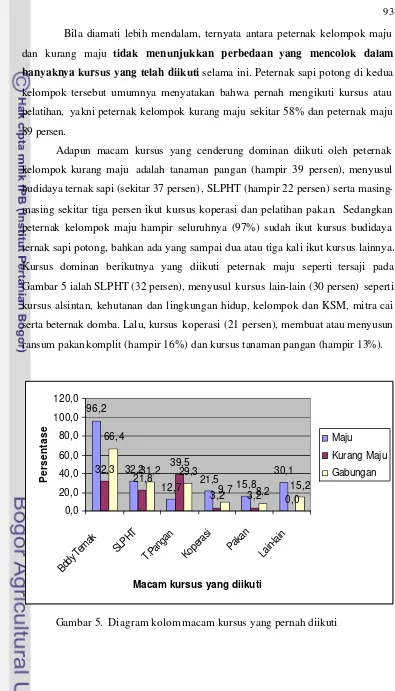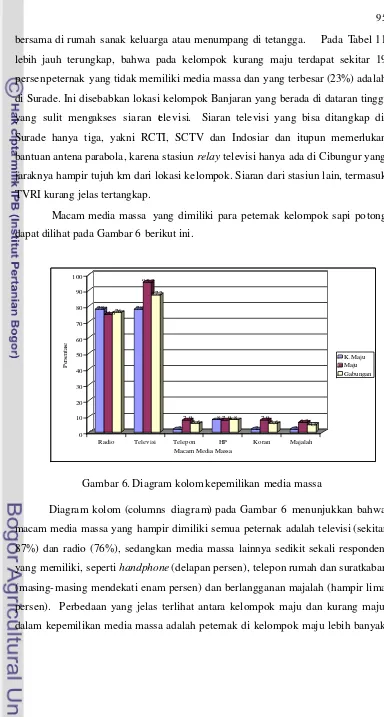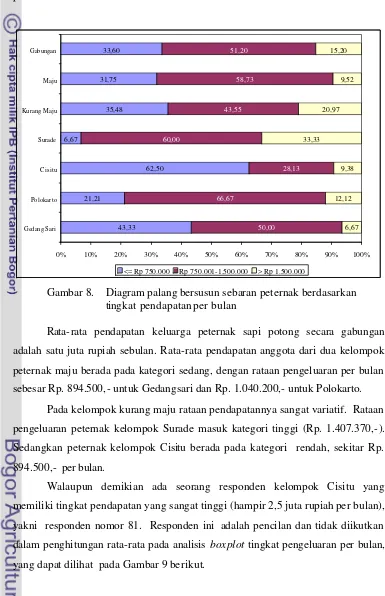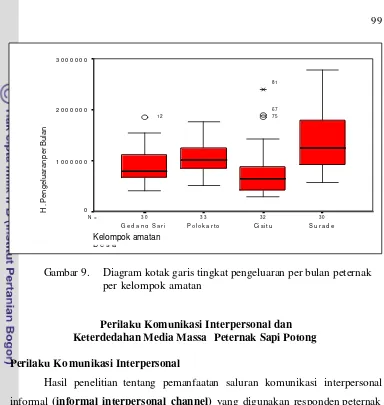TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA MASSA DAN PERAN KOMUNIKASI
ANGGOTA KELOMPOK PETERNAK DALAM JARINGAN KOMUNIKASI
PENYULUHAN
Oleh:
AMIRUDDIN SALEH
NRP. 965039
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:
“TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA MASSA DAN PERAN KOMUNIKASI
ANGGOTA KELOMPOK PETERNAK DALAM JARINGAN KOMUNIKASI
PENYULUHAN”
adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan
tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan
maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan
dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Bogor, Mei 2006
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS Al-Anfhal:27)
Dan tidaklah kami mengutus mu (Wahai Muhammad) melainkan agar menjadi kasih
sayang (Rahmat) bagi alam semesta (QS Al-Anbiya:107)
Berikut sebait sajak dari Khalifah Ali r.a. sebagai spirit dalam perjalanan menuju ilahi;
Ketika Ibumu melahirkanmu,
engkau menangis menjerit,
Sementara orang-orang di sekelilingmu,
tertawa bahagia ...
Maka berusahalah untuk dirimu,
ketika ajal menjemput,
Di saat orang-orang di sekelilingmu,
menangis sedih,
Ruhmu tersenyum gembira ...
Karya Kecil ini Kupersembahkan untuk:
ABSTRAK
AMIRUDDIN SALEH.
Tingkat Penggunaan Media Massa dan Peran Komunikasi
Anggota Kelompok Peternak dalam Jaringan Komunikasi Penyuluhan. Dibimbing oleh
BASITA GINTING SUGIHEN (Ketua), SEDIONO M.P. TJONDRONEGORO,
PRABOWO TJITROPRANOTO dan SISWADI (Anggota).
Tujuan dari penelitian ini (1) mengkaji adanya perubahan perilaku komunikasi,
dalam arti tingkat penggunaan media massa oleh para peternak dalam memanfaatkan pesan
penyuluhan sapi potong, (2) menganalisis tingkat partisipasi peternak dilihat dari
peran-peran komunikasi yang mereka lakukan dalam jaringan komunikasi sapi potong, (3)
mengungkapkan keeratan hubungan antara karakteristik personal, perilaku komunikasi
interpersonal dan keterdedahan media massa dengan peran komunikasi peternak dalam
jaringan komunikasi, dan (4) merumuskan strategi/model komunikasi penyuluhan.
Sampel terpilih sejumlah 125 responden peternak sapi potong diambil dari dua
kelompok peternak maju (Gedangsari Kabupaten Gunung kidul dan Polokarto Kabupaten
Sukohardjo) dan dua kelompok belum maju (Cisitu dan Surade, Kabupaten Sukabumi).
Penelitian yang didesain sebagai
survei deskriptif korelasional
dilaksanakan dari tanggal 14
Desember 2004 sampai 16 Februari 2005.
Hasil penelitian di antaranya : (1) ada perbedaan sangat nyata pada perilaku
komunikasi di kalangan peternak sapi potong kelompok maju dengan kelompok kurang
maju, yang mengindikasikan telah terjadi pergeseran tingkat pemanfaatan media massa
oleh peternak sapi potong untuk mendapatkan informasi. Dari mengutamakan komunikasi
interpersonal dalam menerima dan menyebarkan informasi ke perilaku komunikasi
bermedia, terutama televisi dan suratkabar. Peternak di kedua kelompok sapi potong
cenderung telah berubah perilaku komunikasi pemanfaatan media massanya yakni dominan
terdedah radio dan televisi. Akan tetapi, pemanfaatan media massa tersebut hanya untuk
hiburan dan berita, sedangkan untuk informasi teknis (peternakan) hanya mengandalkan
dari jaringan komunikasi; (2) tingkat peran komunikasi peternak dalam jaringan
komunikasi sapi potong terdiri atas
star
,
mutual pairs
dan
neglectee
, tidak ditemukan peran
komunikasi sebagai
isolate
. Peran komunikasi anggota kelompok peternak maju lebih
tersebar sebagai pemeran
neglectee
, sedangkan anggota kelompok peternak kurang maju
lebih tersebar pemeran
mutual pairs
. Peran
star
, lebih banyak di kelompok kurang maju
dibanding kelompok maju; (3) Terdapat hubungan nyata antara karakteristik pendidikan
formal dengan perilaku keterdedahan tv dan radio serta sangat nyata (p<0,01) dengan
perilaku keterdedahan suratkabar. Hubungan antara kelas ekonomi dengan perilaku
keterdedahan suratkabar sangat nyata, dan antara kepemilikan media massa dengan
perilaku keterdedahan televisi (p<0,01). Terdapat hubungan sangat nyata antara tingkat
pendidikan dan kepemilikan media massa dengan perilaku komunikasi interpersonal dalam
mencari informasi. Karakteristik personal peternak kelompok maju cenderung
berhubungan negatif dengan perilaku menyebarkan informasi. Tidak terdapat hubungan
nyata (p>0,05) antara karakteristik personal, perilaku komunikasi interpersonal dan
keterdedahan media massa dengan peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi.
Ciri peternak maju yang umumnya berpendidikan dan kelas ekonominya lebih tinggi, lebih
banyak dan variatif kepemilikan media massa, mampu memanfaatkan informasi sesuai
kebutuhan, bersifat petualang, berani menanggung risiko kerugian, kosmopolit, pola
komunikasi dan persahabatan bersifat umum, menyebabkannya tidak berperilaku
menyebarkan informasi; (4) Dari hasil penelitian ini diajukan faktor-faktor yang mendasari
penyusunan strategi komunikasi penyuluhan sapi potong adalah (i) ciri individual
peternak, (ii) distorsi pesan dan ketiadaan informasi (yang berkaitan dengan masalah
pemasaran, informasi harga, teknologi tepat guna yang sesuai kebutuhan, kapasitas
peternak dan akses permodalan), (iii) keterlibatan birokrasi (kelembagaan sosial maupun
penyuluhan, penyedia teknologi dan modal, (iv) pelibatan pemuka pendapat dan sumber
informasi relevan lainnya dalam menyampaikan informasi teknologi sapi potong melalui
saluran interpersonal, dan teknik komunikasi penyuluhan dengan cara: (i) menggencarkan
teknik kampanye, memanfaatkan media tradisional dan pembelajaran masyarakat melalui
media massa dengan siaran interaktif dan tidak satu arah, (ii) menggunakan teknik
komunikasi yang mampu meningkatkan kepadatan jaringan komunikasi kelompok melalui
penguatan kelembagaan peternak dan (iii) memantapkan partisipasi berdasarkan
pendekatan yang akseptabel sesuai dengan sosial budaya setempat.
ABSTRACT
AMIRUDDIN SALEH.
The Level of Mass Media Usage and The Role of
Commu-nication of Cattle Farmers Group Members in Extension CommuCommu-nication Network.
Supervised by: BASITA GINTING SUGIHEN (Chairperson), SEDIONO M.P.
TJONDRONEGORO, PRABOWO TJITROPRANOTO and SISWADI (Members).
The cattle agribusiness extension activities, similar with other types of extension are
supposed to undergo a communication structure change. The communication pattern is no
longer in the form of “oil droplets” extension having a top down outline, or relying on the
“LAKU (visiting and training)” extension system which has a dyadic pattern integrating the
top down and bottom up interest with an interpersonal or group communication approach.
However, turning to participation and exchange of knowledge and experiences through
“farmer as partner” communication pattern, (therefore) the advance technology and local
traditions are forming a synergy. It is suspected that the cattle farmer communication
pattern in cattle extension no longer relies on interpersonal.
The objectives of this research are (1) to show communication behavior of cattle
farmers in getting information, (2) analyze the level of participation of cattle farmers from
the standpoint of performing communication roles in a cattle communication network, (3)
devulge the closeness between personal characteristics relationship, interpersonal
communication behavior and the usage of mass media with cattle farmer communicatio n
role in communication network, (4) formulate the communication extension model.
Selected samples amount to 125 cattle farmer respondents, consisting of two highly
developed cattle farmers group s, and two lesser developed cattle farmers groups. The
research was designed as a correlated descriptive survey, and was conducted from
December 14, 2004 until February 16, 2005.
The results of research show: (1) there is a significant difference in the
communication behavior among the advanced cattle farmers group and the less advanced
group, indicating
(the circumstance) a level of mass media usage by cattle farmers in
getting information. From prioritised the interpersonal communication relationship in
receiving and diffusing information to the media communication behavior, particularly in
behavior impact of television broadcast and newspapers. The communication behavior of
two cattle farmers group members have changed from the usage of interpersonal
communication to impersonal communication (radio dan television). However, the use of
mass media dominantly for news and entertainment, and for technical matters they still rely
on communication network; (2) the level of cattle farmers communication role in a cattle
communication network comprising of star, mutual pairs and neglectee, did not indicate a
communication role as isolate. The advanced cattle farmers group members were more
distribution communication role as neglectee, while the less advanced group were more
distribution role of mutual pairs. The role of the star, was found more in the less advanced
group compared with the advanced group; (3) there is formal education characteristic
relationship significantly with tv and radio impact behavior, and the formal education
characteristic relationship significantly with newspaper impact behavior. The relationship
significantly between economic class with newspaper impact behavior, and between mass
media ownership with television impact behavior.
There is a significant relation between the education level and the mass media
ownership with the information search behavior. The characteristics of the advanced cattle
farmers group tend to show a negative correlation with the information distribution
behavior. There were no significant differences (p>0,05) between personal characteristics,
interpersonal communication behavior and the usage of mass media with cattle farmer
communication role in communication network. Some characteristics of advanced cattle
farmers were: well educated and of higher economic class, more owned a variety of mass
media, more capable to cons ume information according to their needs, behaving
adventurous ly, daring to bear risks, cosmopolites, having a communication pattern and
commonly friendships among cattle farmer group, it has caused does not act properly to
diffused information; (4) Research results offered several factors, becoming a basic for
developing a communication strategy in cattle farming extension, such as: (i) farmer
personality characteristics, (ii) messages distortion and unavailability of information
(including marketing, price, appropriate technology need, farmer capacity, and access to
capital), (iii) bureaucratic involved (such as: social institution as well as extension,
technology producer and capital accessibility), (iv) involving opinion leader and others
pertinent information source in delivering information.
And extension communication
techniques are (i) extension campaign continuously, (ii) utilizing traditional media and
social learning through mass media interactive and multi directions; employing
communication technique which is able to increase group communication network density
through enhancing cattle farmer institutions and (iii) securing participation based on
approaches acceptable to local social culture.
@
Hak Cipta milik Amiruddin Saleh, tahun 2006
Hak Cipta dilindungi
Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam
bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, microfilm, disket dan sebagainya
TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA MASSA DAN PERAN KOMUNIKASI
ANGGOTA KELOMPOK PETERNAK DALAM JARINGAN KOMUNIKASI
PENYULUHAN
AMIRUDDIN SALEH
Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Disertasi
:
Tingkat Penggunaan Media Massa dan Peran Komunikasi Anggota
Kelompok Peternak dalam Jaringan Komunikasi Penyuluhan
Nama Mahasiswa : Amiruddin Saleh
NIM
: 965039
Program Studi
: Ilmu Penyuluhan Pembangunan
Disetujui:
1. Komisi Pembimbing
Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, MA
Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro
Ketua
Anggota
Dr. H. Prabowo Tjitropranoto, MSc
Dr. Ir. H. Siswadi, MSc
Anggota Anggota
Diketahui:
2. Ketua Program Studi
3. Dekan Sekolah Pascasarjana
Ilmu Penyuluhan Pembangunan
Dr. Ir. Amri Jahi, MSc
Prof.Dr.Ir. Hj. Syafrida Manuwoto, MSc
Tanggal Ujian: 27 Februari 2006
Tanggal Lulus: Mei 2006
PRAKATA
Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah
SWT, karena atas kemurahan-Nya penulis dimampukan untuk merampungkan disertasi
berjudul “Tingkat Penggunaan Media Massa dan Peran Komunikasi Anggota Kelompok
Peternak dalam Jaringan Komunikasi Penyuluhan.” Terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, Prof.Dr.
Sediono M.P. Tjondronegoro, Dr. H. Prabowo Tjitropranoto, M.Sc dan Dr.Ir. H. Siswadi,
M.Sc selaku komisi pembimbing yang telah dengan sabar memberi bimbingan dan
dorongan serta saran dan arahan. Juga kepada Bapak Prof.Dr. H.R. Margono Slamet, M.Sc
dan Prof.Dr. H. Pang S. Asngari yang turut memberikan masukan dan arah disertasi ini.
Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada Bapak Dr.Ir Sumardjo selaku penguji luar
komisi yang telah memberikan koreksi dan saran untuk perbaikan disertasi ini. Pemberian
solusi dan perkenan Bapak Dr.Ir. Amri Jahi, M.Sc, selaku ketua program studi PPN yang
mengizinkan penulis merampungkan tugas akhir studi Doktor ini tak lupa pula penulis
mengucapkan terima kasih. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Soedijanto Padmowihardjo dan
Dr.Ir. Djuara P. Lubis yang telah berkenan menjadi penguji pada Ujian Sidang Terbuka
disertasi ini, saya pun mengucapkan banyak terima kasih.
Ungkapan terima kasih disampaikan kepada Ayahnda H. Saleh Muhammad
(almarhum) dan Ibunda Hj. Maryam (almarhumah), Bapak mertua H. Abdulah Marzuki
dan Ibu mertua Hj. Dahlia dan seluruh keluarga, istri tercinta Hj. Lailatus Syarifah,
anak-anak: Alyssa Nahla Amir, Ghifary Faisal Amir dan Muhammad Hafidz Syah Amir atas
segala do’a dan kasih sayangnya.
Sementara proses menuju ujian disertasi, sebagian hasil penelitian dari disertasi ini
telah disetujui untuk diterbitkan pada Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan
MEDIA PETERNAKAN Volume 29 No. 2 Tahun 2006, dan Jurnal Komunikasi dan
Pemberdayaan Komunitas edisi April 2006 yang diterbitkan oleh Departemen Komunikasi
dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB. Semoga disertasi
ini bermanfaat bagi pembaca dan penulisnya.
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Sungai Gerong-Palembang pada tanggal 13 Nopember 1961,
anak bungsu dari tujuh bersaudara pasangan Ibu Hj. Maryam (Almarhumah) dengan Bapak
H. Saleh Muhammad (Alm). Lulus SD Taman Siswa tahun 1973, SMP Bina Utama tahun
1976 dan tanggal 8 Mei 1980 menamatkan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Palembang.
Pada pertengahan tahun 1980 penulis mendapat kesempatan kuliah di IPB melalui
undangan pola seleksi Proyek Perintis II. Tahun 1981 diterima di Fakultas Peternakan dan
memperoleh beasiswa Yayasan Supersemar, lulus tahun 1984. Tahun 1986 melanjutkan ke
Program Magister Sains pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan
Perdesaan (Program Studi KMP) PPS-IPB dengan beasiswa pendidikan dari Yayasan
Ilmu-ilmu Sosial (YIIS), bantuan penelitian dari USAID dan Yayasan Toyota Astra, lulus 1988.
Kesempatan studi doktoral diperoleh tahun 1996 pada Program Studi Ilmu Penyuluhan
Pembangunan di institut yang sama, dengan beasiswa dari Tim Manajemen Program
Doktor (TMPD) Ditjen Dikti dan bantuan penelitian dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.
Pengalaman bekerja dimulai tahun 1983 dengan diangkatnya penulis menjadi
Asisten Muda Tidak Tetap mata kuliah “Perubahan Sosial” dan “Penyuluhan” pada
Fakultas Peternakan IPB dan saat ini sebagai Lektor Kepala (Gol. IV/a). Perjalanan karir
penulis di antaranya menjabat sebagai Kepala Humas IPB, Sekretaris Pusat Pendidikan dan
Pelayanan pada Masyarakat LPM-IPB, Sekretaris umum panitia pendirian masjid
Al-Hurriyyah IPB, Sekretaris Program Studi KMP PPS-IPB, dan pernah membantu (sebagai
konsultan/tim leader) kegiatan
community development
dan
capacity building
pada
pengembangan sapi potong di Jawa Barat dan proyek Pengembangan Usaha Tani Ternak di
Kawasan Timur Indonesia (Putkati). Tahun 2005-2006 menjadi konsultan akademik
entrepreneurship
bagi mahasiswa di Universitas Udayana Bali dan Politeknik Negeri
Samarinda Kalimantan timur, mendapat amanah menjadi sekretaris CENTRAS (
Center for
Tropical Animal Studies
: Pusat Studi Hewan Tropis) di Lembaga Penelitian dan
Pemberdayaan Masyarakat IPB. Dalam organisasi profesi penulis tercatat sebagai anggota
Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), Hanter (Himpunan Alumni Peternakan IPB),
Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembanguna n Indonesia (PAPPI), ketua I kepengurusan
Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI) periode 2003-2006.
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ………...
DAFTAR GAMBAR ………...
PENDAHULUAN
………...
Latar Belakang
………...
Masalah Penelitian
………...
Tujuan Penelitian
.………...
Kegunaan Penelitian ………...
DEFINISI ISTILAH ……….
TINJAUAN PUSTAKA
………...
Komunikasi dan Masyarakat ………...
Komunikasi Pembangunan dan Komunikasi dalam Masyarakat Desa ……
Komunikasi Pembangunan ………..
Komunikasi dalam Masyarakat Desa …………..……...
Jaringan Komunikasi .………...
Pengertian Jaringan Komunikasi ………..
Proses Pembentukan Jaringan Komunikasi …..…………...
Pengaruh Jaringan Komunikasi terhadap Psikologi dan Perilaku …
Pemuka Pendapat dan Jaringan Komunikasi ………
Analisis Jaringan Komunikasi ………...
Karakteristik Personal ..………...
Perilaku Komunikasi atau Keterdedahan Media Massa ………...
KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS ………..
Kerangka Berpikir
………...
Hipotesis Penelitian ………...
METODE PENELITIAN
………...
Populasi dan Sampel Penelitian ………...
Populasi ………...
Sampel ………...
Desain Penelitian ………...
Data dan Instrumentasi ………...
Data ………...
Instrumentasi ………...
Validitas dan Reliabilitas Instrumen ………..
Pengumpulan Data ………...
Analisis Data ………
Analisis Jalur ………..
Matriks Korelasi ………...
Analisis Biplot ……….
Uji Beda Vektor Nilai Tengah ………
Analisis Diskriminan ………..
Analisis Korespondensi ………
Kerangka Pendekatan Analisis Penelitian ………...
HASIL DAN PEMBAHASAN ..………
Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………
Kabupaten Sukabumi ………...
Kabupaten Gunung Kidul dan Sukohardjo ………...
Karakteristik Peternak Sapi Potong ………..
Perilaku Komunikasi Interpersonal dan Keterdedahan Media Massa
Peternak Sapi Potong …………...
Perilaku Komunikasi Interpersonal ...
Keterdedahan Media Massa ...
Peran-peran Komunikasi Anggota Kelompok dalam Jaringan Komunikasi
Penyuluhan Sapi Potong ...
Peranan Individu dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong di Cisitu
Peranan Individu dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong di Surade
Peranan Individu dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong di
Gedangsari ...
Peranan Individu dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong di
Polokarto ...
Distorsi Pesan ...
Pengujian Hipotesis ...
Hubungan Karakteristik Personal dengan Perilaku Keterdedahan
Media Massa ………
Analisis Jaringan Komunikasi Sapi Potong ……….
Hubungan Karakteristik Personal dengan Peran Komunikasi
Anggota Kelompok dalam Jaringan Komunikasi Sapi Potong …..
Hubungan Perilaku Komunikasi Interpersonal dan Peran
Komunika-si Anggota Kelompok dalam Jaringan KomunikaKomunika-si Sapi Potong …
Hubungan Perilaku Keterdedahan Media Massa dengan Peran
Komunikasi Anggota Kelompok dalam Jaringan Komunikasi
Sapi Potong ………...
Hubungan Peran Komunikasi Anggota Kelompok dalam Jaringan
Komunikasi Sapi Potong dengan Distorsi Pesan ………...
Pola Jaringan Komunikasi Antar Anggota Kelompok Peternak Sapi
Potong ………...
Pembahasan Hipotesis ………...
KESIMPULAN DAN SARAN ..………...
Kesimpula n ………...
Saran ………...
DAFTAR PUSTAKA ………...
168
173
173
175
177
DAFTAR TABEL
Halaman
01. Perbedaan komunikasi pembangunan dan komunikasi penunjang
pembangunan ………..………...
02. Perubahan lingkungan komunikasi ………...
03. Data yang diolah dengan T
2Hotelling ...………...
04. Kerangka pendekatan analisis penelitian ………….………..
05. Distribusi penduduk Desa Jagamukti menurut umur ………...
06. Macam pekerjaan pend uduk Desa Jagamukti per kepala keluarga …
07. Macam pekerjaan penduduk Desa Cisitu per kepala keluarga ……..
08. Macam pekerjaan penduduk Desa Ngalang per kepala keluarga …...
09. Distribusi penduduk Desa Mranggen menurut umur dan jenis
kela-min ………
10. Macam pekerjaan pendud uk Desa Mranggen per kepala keluarga …
11. Sebaran responden berdasarkan karakteristik personal di kelompok
kurang maju dan maju (dalam persen) ……….
12. Sebaran responden berdasarkan perilaku komunikasi interpersonal
di kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) ……….
13. Sebaran responden berdasarkan macam saluran komunikasi
interpersona l yang menerpa peternak kelompok kurang maju dan
maju (dalam persen) ………
14. Sebaran responden berdasarkan keterdedahan media massa di kelom-
pok kurang maju dan maju (dalam persen) ………...
15. Sebaran responden berdasarkan waktu mendengarkan radio di
kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) ………..
16. Sebaran responden berdasarkan preferensi program radio yang
didengar di kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) …..
17. Sebaran responden berdasarkan frekuensi membaca suratkabar di
kelompok kurang maju dan ma ju (dalam persen) ………...
xv
25
30
68
73
78
79
80
82
85
86
91
100
101
103
105
106
18. Sebaran responden berdasarkan peran komunikasi anggota kelompok
jaringan komunikasi sapi potong di kelompok kurang maju dan
maju (dalam persen) ……….
19. Sebaran responden berdasarkan distorsi pesan di kelompok peternak
kurang maju dan maju (dalam persen) ……….
20. Perbedaan tingkat pemanfaatan media massa, perilaku pemanfaatan
media interpersonal dan karakteristik personal antara peternak
kelompok kurang maju dan maju …………...
21. Matriks korelasi (Pearson) antar peubah karakteristik personal,
peri-laku pemanfaatan media interpersonal, pemanfaatan media massa,
peran komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong dan
distorsi pesan ……….
22. Sebaran responden berdasarkan kelas ekonomi pemeran
star
di
kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) ………..
23. Sebaran responden berdasarkan kelas ekonomi anggota jaringan
komunikasi sapi potong pemeran
star
monomorfik dan polimorfik di
kelompok kurang maju dan maju (dalam persen) ………..
125
126
131
134
161
165
DAFTAR GAMBAR
Halaman
01. Keanggotaan pada berbagai jaringan komunikasi .………..
02. Kerangka berpikir model hubungan berbagai peubah penelitian …..
03. Proses pembentukan jaringan komunikasi ………..………….
04. Tampilan diagram jalur antar peubah yang mempengaruhi peran-peran
komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong dan distorsi
pesan ………...
05. Diagram kolom macam kursus yang pernah diikuti ………..
06. Diagram kolom kepemilikan media massa ………...
07. Diagram kotak garis kelas ekonomi peternak per kelompok amatan
08. Diagram palang bersusun sebaran peternak berdasarkan tingkat
pendapatan per bulan ………...
09. Diagram kotak garis tingkat pengeluaran per bulan peternak per
kelompok amatan ………..
10. Diagram kolom kebiasaan menonton televisi ………...
11. Diagram kolom stasiun televisi yang paling sering ditonton peternak
12. Diagram kolom darimana suratkabar diperoleh ………
13a. Sosiogram jaringan komunikasi sapi potong pada kelompok peternak
Cisitu ………...
13b. Sosiogram jaringan komunikasi sapi potong pada kelompok peternak
Surade ………
13c. Sosiogram jaringan komunikasi sapi potong pada kelompok peternak
Gedangsari ………
13d. Sosiogram jaringan komunikasi sapi potong pada kelompok peternak
Polokarto ………...
14. Keragaan umum hasil analisis biplot keterkaitan peubah karakteristik
personal, perilaku komunikasi interpersonal dan keterdedahan media
massa peternak sapi potong ………..
xvii
33
52
53
64
93
95
96
98
99
108
108
111
115
117
120
122
15. Bagan model jalur antar peubah yang mempengaruhi peran
komuni-kasi anggota kelompok jaringan komunikomuni-kasi penyuluhan sapi potong
dan distorsi pesan ………..
16. Keragaan umum keterkaitan peubah perilaku komunikasi
interperso-nal dengan peran komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong
per desa amatan ………..
17. Keragaan umum keterkaitan peubah keterdedahan media massa
dengan peran komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong
per desa amatan ………...
18. Keragaan umum keterkaitan peubah perilaku komunikasi
interper-sonal dengan kelas ekonomi peternak anggota kelompok secara
gabungan ………
19. Keragaan hasil analisis korespondensi peubah perilaku
kepemim-pinan komunikasi dengan kelas ekonomi peternak anggota kelompok
secara gabungan ………
20. Keragaan hasil analisis korespondensi peubah perilaku
kepemim-pinan komunikasi dengan kelas ekonomi peternak berdasarkan
kelompok amatan ………..
xviii
141
151
157
160
164
1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penyuluhan ialah suatu istilah yang secara baku telah digunakan untuk
menunjukkan suatu kegiatan pendidikan non-formal yang semula hanya ditujukan
kepada petani ataupun peternak yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan di
sektor produksi pertanian. Maunder (1972) mengartikan penyuluhan (dari istilah
extension) sebagai suatu layanan atau sistem yang membantu petani, melalui
prosedur-prosedur pendidikan praktis, mengembangkan metode-metode dan
teknik-teknik baru pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan
pendapatan serta memperoleh tingkat hidup yang lebih tinggi bagi diri dan
keluarga mereka.
Penyuluhan sebagai pendidikan non-formal, setelah revolusi hijau kurang
menghasilkan kesejahteraan bagi petani kecil. Struktur komunikasi yang
dikembangkan cenderung diganti dari model-model yang mengikuti struktur
komunikasi “guru-murid”/top down, berkembang ke arah pola komunikasi dyadic
dan menjadi struktur komunikasi “petani sebagai partner.” Artinya, kegiatan
penyuluha n berkembang menjadi “saling belajar” dan karena itu fungsi penyuluh
lebih difokuskan pada fasilitator.
Dalam hal ini, penyuluh berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang
perlu mengalami proses belajar memperbaiki dirinya sendiri (Slamet, 1992).
Dengan pendidikan non-formal atau penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat di sini hendaknya
jangan dijadikan sebagai obyek pembangunan saja, melainkan harus dilibatkan
sebagai subyek pembangunan yang perlu mengalami suatu proses belajar untuk
mengetahui adanya kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya,
memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memanfaatkan kesempatan itu,
serta mau bertindak memanfaatkan kesempatan memperbaiki kehidupannya.
Asngari (2001) menyebutkan hal ini sebagai upaya empowerment, yakni
memberdayakan SDM-klien sebagai subyek penyuluhan yang aktif
2
mampu berprestasi prima. Untuk itu prakarsa da ri masyarakat petani harus
dirangsang, demikian juga pembangunan kelembagaannya harus diarahkan dan
diawasi cara mereka berkinerja dan melakukan fungsi-fungsinya dengan efektif
dan efisien (Tjondronegoro, 1998).
Malah, kini penyuluh di beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat
petani (community development) dan penyuluhan capacity building (penguatan
kapasitas kelembagaan) berubah fungsi sesuai dengan perkembangan SDM-klien.
Peran penyuluh dalam hal ini menjadi konsultan, dengan sasaran meningkatkan
kelem bagaan masyarakat petani maupun kapasitas SDM-klien, dimana petani
diharapkan aktif mencari, mendapatkan atau meminta advis atau layanan akan
informasi yang dibutuhkan dan aktif mendatangi penyuluh atau mengontak
sumber informasi.
Kegiatan pe nyuluhan sapi potong pun diduga mengalami perubahan
struktur komunikasi. Pola komunikasi bukan lagi berupa penyuluhan “tetesan
minyak”/ SSBM (swasembada bahan makanan) berpola “guru-murid”/top down
atau mengandalkan penyuluhan sistem LAKU (latihan dan kunjungan) yang
berpola dyadic memadukan kepentingan top down dan bottom up dengan
pendekatan komunikasi interpersonal maupun kelompok. Penyuluhan di sini harus
lebih menekankan pada capacity building kepada masyarakat.
Untuk mempercepat kesiapan masyarakat (petani/pe ternak) memasuki era
pasar bebas dan globalisasi di bidang ekonomi, maka pembangunan pertanian,
termasuk usahaternak sapi potong secara bertahap telah melakukan transformasi
rekayasa sistem agribisnis. Transformasi rekayasa sistem agribisnis di sini adalah
upaya membuat perubahan (bentuk, rupa, sifat dan sebagainya) rancangan
perlakuan sistem agribisnis ke arah ideal ditinjau secara ekonomis dan
sosial-budaya. Transformasi rekayasa sistem agribisnis tersebut bertujuan untuk
memicu percepatan kesiapan fisik maupun mental masyarakat petani-peternak
dalam menghadapi pasar bebas dan era globalisasi di bidang ekonomi. Banyak
ilmuwan sosial melihat istilah “rekayasa” terlalu mekanistik, sehingga lebih
melihatnya sebagai proses yang lebih lambat atau bertahap dis ebut “akulturasi”
3
Perubahan rancangan perlakuan pada sistem agribisnis, berarti proses
perubahan berencana dalam pembangunan peternakan sapi potong berwawasan
agribisnis. Di sini penyuluhan ikut memegang peranan penting. Untuk itu perlu
dipikirkan strategi penyuluhan pembangunan peternakan sapi potong yang
bagaimana, yang dapat dijadikan sebagai salah satu upaya menswadayakan
petani-peternak, sehingga lebih berdaya diri dan mampu berprestasi prima.
Dalam upaya ini, kegiatan aspek transformasi rekayasa tersebut lebih difokuskan
sebagai suatu strategi penyuluhan agribisnis sapi potong. Transformasi rekayasa
dalam pengertian tersebut meliputi upaya rekayasa sosial budaya, ekonomi, politik
dan teknologi. Hal ini perlu dipertimbangkan, karena ia merupakan langkah awal
pembenahan upaya pembangunan menuju masyarakat (petani/peternak)
berkualitas dan partisipatif.
Strategi sebagai desain operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk
mengimplementasikan kebijakan penyuluhan pertanian dan peternakan pada PJP I
(Pembangunan Jangka Panjang tahap Pertama), lebih kepada alasan kepentingan
percepatan pembangunan karena lebih banyak diorientasikan kepada strategi alih
teknologi (technology delivery strategy) daripada strategi pembangunan perdesaan
(rural development strategy), yang berorientasi penguatan kapasitas kelembagaan
dan pemandirian individu khalayak sasaran penyuluhan. Kenyataan, sampai
sekarang kebijakan penyuluhan masih bersifat “technology delivery system,”
hanya teknologinya yang diubah.
Sejak awal repelita VI, genderang pembangunan peternakan berorientasi
agribisnis sebenarnya telah dikumandangkan dan kini setelah lebih dari lima tahun
implementasi sistem agribisnis dalam pembangunan peternakan ini dilakukan,
diharapkan reorientasi strategi penyuluhan pun sudah dilaksanakan. Yakni dari
penyuluhan peternakan ke penyuluhan agribisnis yang paling tidak meliputi: (1)
penyuluhan teknik budidaya sudah berubah ke total agribisnis, (2) penyuluhan
teknologi ke arah bisnis, (3) penanganan sentralisasi ke desentralisasi dan (4)
sasaran penyuluhan hanya petani-peternak (aspek on -farm/di tingkat infrastruktur)
diperluas ke berbagai jenis sasaran strategis lainnya (aspek off-farm/di tingkat
4
Melihat sasaran strategis penyuluhan yang semakin variatif, maka media
penyuluhan seharusnya tidak hanya berorientasi pemanfaatan saluran komunikasi
interpersonal, tetapi juga mulai intensif menggunakan saluran media massa dan
memfungsikan forum-forum media (farm forum) yang ada di sistem petani (user).
Hal ini terjadi, karena tidak terlepas dari globalisasi informasi yang merupakan
tantangan dan peluang untuk lebih mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi
berbagai media penyuluhan (saluran komunikasi). Diharapkan masyarakat sudah
berubah pola komunikasinya. Dimana peternak sudah mampu menyerap dan
menerapkan informasi untuk meningkatkan usahaternaknya, sehingga mendapat
keuntungan yang lebih besar. Kemampuan komunikasi peternak atau masyarakat
perdesaan diharapkan sudah menjadi lebih baik, termasuk telah ada dialog antara
sesama mereka atau antara peternak dengan pemimpin mereka, dan dengan para
penyuluh/agen pembaruan atau dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini telah
terjadi peningkatan kebebasan atau terdedah informasi (selective exposure) dan
transparansi informasi.
Bukti empiris lain menunjukkan bahwa aksesibilitas sarana dan prasarana
komunikasi relatif tersedia di petani, seperti hampir setiap petani di hampir
seluruh wilayah perdesaan memiliki pesawat radio terutama transistor kecil (van
den Ban dan Hawkins, 1999); dan stasiun pemancar radio, terutama swasta dan
radio-radio lokal juga semakin banyak. Pemanfaatan radio bagi komunikasi
pertanian di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1969 hingga kini oleh RRI
(Radio Republik Indonesia) melalui “siaran pertanian/siaran perdesaan.” Setiap
desa/kelurahan di era orde baru pada tahun 80an difasilitas pesawat tele visi dan
dipancarkan siaran program perdesaan/pembangunan pertanian dua kali setiap
minggunya melalui TVRI. Kini Indonesia telah memiliki cakupan tv yang lebih
baik, sudah meningkat stasiun siaran dan jumlah stasiun penerima, termasuk
bermunculannya puluhan televisi swasta (nasional dan lokal) yang turut
menyemarakkan penyampaian pesan pembangunan dengan porsi beragam dan
minim. Di Indonesia proporsi penduduk desa yang menonton televisi sekitar 64,77
persen (BPS, 1994). Proporsi ini terus meningkat, karena kesejahteraan
5
samping program penyebaran tv ke perdesaan yang dilancarkan pemerintah (Jahi,
1993). Dengan kemajuan teknologi informasi dan adanya teknologi satelit
memungkinkan masyarakat menyaksikan siaran melintas antar stasiun tv
negara-negara di dunia (Rusadi, 1991), bahkan masyarakat perdesaan yang berbatasan
langsung dengan negara tetangga, malah terjadi intervensi (terdedah) siaran
tele visi asing dengan mudah (Harmoko, 1992 dan Rusadi, 1991). Aksesibilitas
radio dan tele visi tersebut, serta adanya kebijakan koran masuk desa (KMD)
tentunya memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh informasi sesuai
kebutuhan yang didasarkan pengalaman petani dan/atau hasil temuan penelitian.
Adanya globalisasi informasi, kebebasan dan transparansi informasi, serta
berkembangnya komunikasi antar pe tani dalam mengadopsi teknologi dan
informasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan, maka perlu pembenahan pola
komunikasi dalam penyuluhan agar partisipasi petani dapat semakin ditingkatkan.
Dengan kemampuan peternak menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam
mencari, mendapatkan atau menerima, mengolah dan memanfaatkan peluang
membangun, menyerap serta menerapkan informasi peternakan yang tepat dan
relevan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap tingkat produktivitas.
Berdasarkan hal di atas, masalah utama penelitian ini untuk melihat (1)
sejauhmana telah terjadi perubahan perilaku komunikasi peternak, baik dalam
penggunaan media massa (media exposure) maupun dalam pemanfaatan saluran
media interpersonal; (2) sebagai akibat dari keterbukaan informasi maka
partisipasi peternak dalam gerakan pembangunan juga diharapkan meningkat; dan
(3) aktivitas “self supporting” menggala ng kerja membangun dalam dirinya juga
meningkat melalui jaringan komunikasi sapi potong; dan (4) komunikasi sebagai
gejala sos ial dipengaruhi oleh dua faktor yang dominan, yakni faktor struktural
dan kultural. Salah satu faktor struktural ialah pelapisan sosial yang terbentuk atas
karakteristik personal turut mempengaruhi perilaku komunikasi, baik dalam hal
selective exposure atau keterdedahan (terpaan atau pajanan) terhadap media massa
maupun jaringan komunikasi yang terjadi. Kalaupun hambatan struktural dapat di
6
yang berakibat tidak mau menerima informasi yang terdedah terhadap dirinya.
Dengan demikian upaya mendiseminasikan informasi di kalangan masyarakat
tidak dapat dilakukan dengan mudah apabila kedua faktor tersebut tidak dapat di
atasi. Oleh karena itu, faktor-faktor personal peternak yang dilibatkan dalam
penelitian ini penting juga untuk dikaji.
Fenomena sudah terjadi perubahan penggunaan saluran komunikasi yang
variatif di kalangan peternak ini, perkuat pula oleh pendapat Slamet (1995) yang
menyebutkan bahwa masyarakat petani telah berubah secara nyata, yakni lebih
baik tingkat pendidikannya, lebih mengenal kemajuan, kebutuhan dan
keteram-pilannya telah jauh lebih baik, telah mampu berkomunikasi secara impersonal.
Di samping, telah terjadi perubahan karakteristik personal peternak sebagai akibat
pembangunan pertanian itu sendiri, dimana sudah terbentuk berbagai strata
ko-mersial pada diri petani (Jarmie, 1994; Slamet, 1999). Penelitian Sumardjo (1999)
malah menyebutkan bahwa beberapa petani telah mengarah pada terbentuknya
petani mandiri. Petani komersial dan mandiri ini membuat jejaring komunikasi
sendiri, mencari dan memanfaatkan informasi penyuluhan sesuai kebutuhan.
Masalah Penelitian
Sejak awal dilaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian periode
1945-1959 yang berupa kegiatan mendidik masyarakat desa dengan sistem penyuluhan
pertanian tetesan minyak. Kemudian, periode 1959-1963 menjadi gerakan massa
SSBM (swasembada bahan makanan). Sekitar tahun 1964 tetesan minyak diganti
dengan metode penyuluhan “tumpahan air,” yang ditandai dengan kampanye
besar-besaran di bawah Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM). Dampak
negatif penyuluhan sistem komando ini adalah para petani menjauhi penyuluh.
Periode 1963-1993 dikenal dengan gerakan swasembada beras karena penyuluhan
pertanian diintegrasikan dengan gerakan Bimas/Inmas untuk swasembada pangan
melalui sistem LAKU (latihan dan kunjungan) dan sukses swasembada berasnya
dicapai tahun 1984. Menyusul periode 1993-Sekarang, yang ditandai adanya
perubahan orientasi pendekatan komoditas ke pendekatan agribisnis dan otonomi
7
pemerintah daerah yang menyebabkan dinamika penyuluhan pertanian menurun
drastis. Di tahun 1998 diluncurkan program Gema Palagung 2001, Gema Protekan
2003 dan Gema Proteina 2003, ini pun menuai masalah. Memang, peningkatan
produksi berhasil tetapi meninggalkan masalah utang macet, dan prinsip
penyuluhan dirusak dengan pemberian insentif kepada penyuluh.
Terlihat bahwa penyuluhan hingga saat ini, intinya hanya untuk alih
teknologi dan mengejar peningkatan produksi. Sedangkan kegiatan penyuluhan
pertanian untuk meningkatkan kapasitas manusia (SDM)nya belum dilakukan.
Padahal, di kalangan petani telah banyak terjadi perubahan seperti tingkat
pengetahuan dan pendidikan yang semakin baik, tingkat pendapatan yang
meningkat, semakin tersedianya aksesibilitas sarana dan prasarana komunikasi,
sehingga petani mencari dari sumber lain akan kebutuhan yang mereka perlukan.
Fenomena ini dikuatkan oleh hasil penelitian Puspadi (2002) yang menyebutkan
bahwa telah terjadi perubahan pemenuhan kebutuhan informasi dan perilaku
usahatani yang semakin komersial, dimana akibat relatif tingginya tingkat
pendidikan para petani, perubahan cara belajar petani, makin tingginya kapasitas
inovasi dan informasi para petani, bangkitnya kesadaran petani atas hak-haknya,
perubahan referensi petani, munculnya gejala -gejala relativitas nilai di perdesaan,
makin tingginya otoritas petani dalam pengambilan keputusan, menuntut
perubahan peran, sistem dan paradigma penyuluhan pertanian.
Kalau penelitian Puspadi (2002) melihat pada perubahan pemenuhan
kebutuhan informasi, maka studi ini lebih melihat (pada) perubahan penggunaan
saluran komunikasi dan menentukan pola komunikasi yang paling efektif dalam
penyuluhan serta mengungkapkan distorsi informasi penyuluhan teknologi sapi
potong di sistem user.
Seperti telah disebutkan di atas, telaah komunikasi dalam penelitian ini
adalah telaah yang berkaitan dengan pembangunan. Komunikasi pembangunan
yang dilakukan di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang
sebenarnya bukan komunikasi pembangunan yang diungkapkan Schramm dan
Lerner (1976) dari studi penelitiannya di Desa Balgat, Turki, yakni komunikasi
8
diharapkan mampu mengubah sikap, pikiran serta kepribadian tradisional menjadi
modern. Selain itu, komunikasi bukan merupakan alat untuk diseminasi, tetapi
menjadi alat bagi peternak sendiri untuk menentukan saluran komunikas i yang
akan digunakannya dan informasi yang akan diambil. Sehingga, seperti halnya
program pengembangan sapi potong di desa-desa yang umumnya dilaksanakan
dalam situasi dan keadaan mikro berbentuk kampanye dan kaji tindak yang segera
akan diakhiri bila proyek pembangunan telah selesai dilaksanakan (Jayaweera,
1989), tak akan terjadi. Inilah yang mendasari perlunya komunikasi penunjang
pembangunan (KPP). Pendekatan ini bertentangan dengan kondisi pembangunan
selama ini. Melaksanakan KPP pada dasarnya tida k mengubah paradigma
pemba-ngunan itu sendiri. Kegagalan komunikasi dalam pembapemba-ngunan di Indonesia lebih
merupakan kegagalan paradigma pembangunan itu sendiri, yaitu paradigma
pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan fisik. Oleh karena
itu, kegagalan komunikasi dalam pembangunan di Indonesia merupakan
kegagalan komunikasi linear, maka studi-studi komunikasi hendaknya mengacu
pada model komunikasi konvergensi yang memandang proses komunikasi bukan
secara sepihak dari komunikator kepada penerima (user), melainkan suatu proses
berbagi informasi tanpa menunjukkan superioritas salah satu unsur yang terlibat
dalam proses komunikasi. Salah satu penelitian yang mengacu pada model
komunikasi konvergensi tersebut adalah studi mengenai jaringan komunikasi
interpersonal yang menggunakan metode analisis jaringan (Rogers, 1995).
Keuntungan menggunakan metode ini yang menggunakan
hubungan-hubungan interpersonal sebagai unit analisis dibandingkan dengan metode yang
menggunakan individu sebagai unit analisis (survei) ialah dapat dihimpitkannya
struktur sosial yang diambil dari pengkategorian karakteristik personal pada arus
komunikasi. Hal ini memungkinkan kita memahami hubungan antara struktur
sosial dengan arus pesan. Pemahaman ini sangat berguna sebagai masukan untuk
perumusan strategi komunikasi pembangunan, yang sering diabaikan oleh para
ekonom yang merancang pembangunan. Telaah komunikasi yang berkaitan
dengan pembangunan perlu dilakukan, terlebih pada usaha -usaha pemerataan
9
peningkatan pendapatan warga masyarakat, peternak yang hidup di perdesaan.
Untuk itu fokus penelitian ini adalah usaha pemahaman hubungan antara
karakteristik personal, terpaan atau keterdedahan arus informasi (selective
exposure), keterlibatan peran komunikasi peternak sapi potong dalam jaringan
komunikasi dan distorsi informasi. Konsep distorsi yang dimaksud di sini adalah
ketimpangan tingkat informasi antar anggota jaringan komunikasi.
Dari latar belakang dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan
penelitian utama, yakni “Apakah perilaku komunikasi peternak dalam
penyuluhan sudah tidak sepenuhnya mengandalkan komunikasi
interpersonal?” Dari pertanyaan utama tersebut dan melihat kondisi profil
peternak yang sudah lebih baik (terutama pendidikan dan strata komersial/ kelas
ekonomi), menimbulkan kecenderungan berperilaku komunikasi yang tidak hanya
interpersonal melainkan juga berkomunikasi impersonal sebagai alternatif
pola-pola terdahulu (tetesan minyak/SSBM, LAKU, US.Extension seperti sekolah
lapanga n atau kursus maupun pelatihan). Untuk itu, empat pertanyaan penelitian
yang lebih operasional berikut ini coba dirumuskan sebagai masalah penelitian,
yaitu:
1. Bagaimana perilaku komunikasi peternak dalam mendapatkan informasi?
2. Apa saja peran-peran komunikasi yang dilakukan peternak dalam jaringan
komunikasi sapi potong?
3. Sejauhmana hubungan karakteristik personal (tingkat pendidikan, kelas
ekonomi, kepemilikan media massa) dengan keterdedahan media massa dan
perilaku komunikasi interpersonal; keeratan hubungan karakteristik personal,
keterdedahan media massa dan perilaku komunikasi interpersonal dengan
peran-peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi sapi potong; dan
keterkaitan hubungan peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi
sapi potong dengan distorsi informasi?
4. Bagaimana pola jaringan komunikasi antar anggota kelompok peternak sapi
10
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bermaksud untuk menelusuri dan menganalisis perubahan
proses komunikasi penyampaian informasi penyuluhan pembangunan kepada
masyarakat, berupa program pengembangan sapi potong. Secara spesifik,
tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan studi ini adalah untuk:
1. Melihat perilaku komunikasi peternak dalam mendapatkan informasi.
2. Mengidentifikasi tingkat partisipasi peternak dilihat dari peran-peran
komunikasi dalam jaringan komunikasi sapi potong.
3. Menganalisis hubungan karakteristik personal dengan keterdedahan media
massa dan perilaku komunikasi interpersonal; hubungan karakteristik
personal, keterdedahan media massa dan perilaku komunikasi interpersonal
dengan peran-peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi sapi
potong; dan hubungan peran komunikasi peternak dalam jaringan komunikasi
sapi potong dengan distorsi pesan.
4. Mengetahui pola jaringan komunikasi antar anggota kelompok peternak sapi
potong.
5. Mendesain strategi/model komunikasi penyuluhan.
Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, hasil-hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna:
1. Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan komunikasi dan pembangunan
perdesaan, bagi praktisi bidang komunikasi, penyuluhan, penerangan dan
sebagainya, mengenai kemungkinan efektivitas jaringan komunikasi dapat
digunakan sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi
pembangunan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan
dalam memperbaiki kebijakan komunikasi penyuluhan yang sekarang masih
berlaku.
2. Bagi disiplin ilmu penyuluhan pembangunan, diharapkan hasil penelitian ini
11
masyarakat dan bidang komunikasi pembangunan pada umumnya dan ilmu
penyuluhan pembangunan pertanian bagi masyarakat perdesaan pada
khususnya, dengan memperhatikan beragam permasalahan yang terdapat di
perdesaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
bahan masukan bagi penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam
menelaah pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan bagi masyarakat
perdesaan.
3. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat menggugah kesadaran pihak-pihak
yang berkecimpung dalam bidang kegiatan sosial, seperti lembaga swadaya
masyarakat (LSM), akan pentingnya penelitian-penelitian komunikasi
12
DEFINISI ISTILAH
Karakteristik personal adalah suatu ciri atau sifat seseorang yang
bersumber dari unsur keturunan dan kemudian berkembang sesuai dengan
perkembangan lingkungan.
1. Karakteristik personal responden terpilih yang dikaji mencakup:
a. Pendidikan formal adalah pendidikan tertinggi yang telah dicapai atau
ditamatkan melalui jenjang sekolah oleh responden pada saat penelitian
dila kukan, diukur berdasarkan skala nominal, yang dikategorikan menjadi
Tidak Tamat/Tidak Lulus SD, Tamat SD dan Tamat Sekolah Lanjutan
(SMP/SMA).
b. Kelas ekonomi, adalah status/kedudukan seseorang di masyarakat dilihat
dari kekayaan materi yang dimilikinya, diukur dengan skala rasio
berdasarkan nilai rupiah kepemilikan barang atau hewan/ternak, seperti:
rumah, tanah, lampu teplok, petromak, mobil (pick up), sepeda motor,
sepeda, mesin jahit, kulkas, jam tangan, radio, tape recorder, tele visi,
telepon/Hp, sapi/kerbau dan kambing/domba , modal usaha, tabungan atau
deposito yang dimiliki saat penelitian dilakukan. Kemudian
dikelompok-kan menjadi tiga kategori, yakni rendah (< Rp. 55 juta), sedang (Rp.
55-110 juta) dan kategori tinggi (di atas Rp. 55-110 juta).
c. Kepemilikan media massa, adalah macam media massa (radio, tele visi,
suratkabar, majalah, bulletin, telepon, Hp, poster/pamlet, booklet, leaflet,
brosur, folders) yang dipunyai saat penelitian dilakukan, diukur dengan
skala nominal dan dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni sama
sekali tidak memiliki media massa, punya satu, punya dua dan punya lebih
dari dua media massa.
2 . Perilaku komunikasi interpersonal informal, ialah aktivitas komunikasi
interpersonal yang digunakan responden dalam berinteraksi dengan
orang-orang di dalam dan di luar sistem sosialnya, diukur dengan skala rasio
berdasarkan intensitas/frekuensi kontak atau komunikasi tatap muka
13
pejabat terkait lainnya, pedagang, pemodal dan pendamping, atau dengan
sesama peternak, maupun dengan kontak tani di luar pertemuan kelompok
atau kursus/pelatihan selama sebulan terakhir saat penelitian ini dilaksanakan.
Perilaku komunikasi interpersonal informal ini dilihat berdasarkan perilaku
responden peternak sapi potong dalam (a) menerima, (b) mencari, (c)
mengklarifikasi atau mendiskusikan dan (d) menyebarkan informasi.
3 . Keterdedahan media massa (mass media exposure ) yang dikaji mencakup :
a. Keterdedahan pada siaran radio, adalah aktivitas peternak mendengarkan
siaran radio dalam berbagai acara, yang diukur dengan skala rasio
berdasar kan frekuensi mendengarkan siaran radio dalam seminggu terakhir
saat penelitian dilakukan.
b. Keterdedahan pada tayangan televisi, adalah aktivitas peternak menonton
tayangan televisi dalam berbagai acara, yang diukur dengan skala rasio
berdasarkan frekuensi menont on tayangan televisi dalam seminggu
terakhir saat penelitian dilakukan. Juga diukur acara apa yang ditonton
berdasarkan skala nominal.
c. Keterdedahan pada suratkabar , ialah aktivitas peternak membaca berbagai
media suratkabar (lokal) baik tentang sapi potong maupun masalah umum,
yang diukur dengan skala rasio berdasarkan frekuensi membaca dalam
satu minggu terakhir saat penelitian dilakukan.
4 . Jaringan komunikasi responden yang dikaji dalam penelitian ini diukur
dengan mengajukan pertanyaan sosiometris (kepada siapa peternak tersebut
bertanya, dan dijadikan tempat bertanya oleh anggota kelompok atau peternak
lain tentang informasi sapi potong). Kemudian diukur peran komunikasi
anggota kelompok peternak dalam jaringan komunikasi sapi potong tersebut,
yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:
a. neglectee, adalah pemeran komunikasi yang pernah membicarakan pesan
penyuluhan sapi potong, tetapi tidak pernah diajak bicara atau dijadikan
14
b. mutual pairs, adalah pe meran komunikasi yang bersifat pilihan timbal
balik (dyadic ) dan hubungan mutual atau saling memilih sebagai tempat
bertanya informasi sapi potong.
c. star, adalah pemeran komunikasi yang menjadikan diri peternak tersebut
sebagai tempat be rtanya dan merupakan pemusatan jalur komunikasi dari
beberapa anggota jaringan dalam klik.
4 . Distorsi pesan ialah tingkat informasi yang dimiliki responden, dikumpulkan
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui salah benarnya
informasi yang dimiliki yang berhubungan dengan berusaha ternak sapi
potong, dengan menggunakan skala rasio. Data mengenai tingkat informasi
ini dikumpulkan melalui butir-butir pertanyaan yang telah diujicobakan
berdasarkan pemenuhan persyaratan koefisien reprodusibilitas dan koefisien
skalabilitas Guttman (Kerlinger, 1986; Nawawi dan Hadari, 1995; Siegel,
1997; Singarimbun dan Effendi, 1995). Secara garis besar butir-butir
pertanyaan yang diajukan meliputi pengertian dan cara berbisnis sapi potong
seperti aspek (a) bibit dan permodalan, (b) pakan konsentra t dan hijauan
makanan ternak, (c) perkandangan/peralatan peternakan, (d) pemeliharaan dan
manajemen, (e) kesehatan ternak dan obat-obatan, (f) reproduksi dan
perkembangbiakan: kawin alam atau IB, (g) pemasaran (h) pascausaha atau
pascapanen dan pemanfaatan limbah serta (i) kemitraan.
5 . Pemuka pendapat, adalah tokoh masyarakat tempat orang-orang bertanya
yang diambil dari kategori peran unisolate anggota kelompok peternak, dalam
hal ini berupa star atau memiliki struktur komunikasi integration dalam
jaringan komunikasi tersebut. Diukur berdasarkan skala nominal, dengan dua
kategori, yakni pemimpin polimorfik apabila pemuka pendapat tersebut
merupakan sumber informasi lebih dari satu jenis informasi dan pemimpin
monomorfik, bila sebagai tempat bertanya hanya satu jenis informasi.
6 . Pergeseran tingkat pemanfaatan media massa ialah perubahan yang
diindikasikan oleh perbedaan penggunaan media komunikasi massa (radio,
televisi dan suratkabar) oleh peternak maju dibandingkan dengan yang kurang
15
TINJAUAN PUSTAKA
Komunikasi dan Masyarakat
Komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pesan oleh
komunikator kepada komunikan (Berlo, 1960). Konsep komunikasi ini berasal
dari bahasa latin, yaitu communicare yang secara harfiah berarti berpartisipasi
atau memberitahukan; bisa juga berasal dari kata communis yang berarti milik
bersama (kebersamaan). Komunikasi dianggap sebagai suatu proses berbagi
informasi untuk mencapai saling pengertian atau kebersamaan (Rogers , 1986;
Kincaid dan Schramm, 1987). Hybels dan Weaver II (1998) menambahkan
bahwa komunikasi itu bukan saja proses orang-orang berbagi informasi,
melainkan juga ide (gagasan) dan perasaan. Se lanjutnya Rogers mengemukakan
bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana para partisipan saling
mengembangkan dan membagi informasi antara satu dengan lainnya untuk
mencapai suatu pemahaman bersama (Rogers, 1995). Di sini tersirat pengertian
bahwa antara satu partisipan dengan partisipan lainnya masing-masing menyadari
kekurangannya atas informa si-informasi yang lengkap mengenai suatu isu. Karena
itu penting untuk mengkomunikasikan pengetahuan-pengetahuan antara satu
dengan yang lain untuk membangun suatu pemahaman bersama yang sempurna.
Effendy (2001) menambahkan bahwa komunikasi di sini merupa kan proses
penyampaian pikiran atau perasaan seseorang (komunikator) kepada orang lain
(komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain sebagainya
yang muncul dari benaknya. Sedang perasaan bisa merupakan keyakinan,
kepastian, keragu-raguan dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.
Komunikasi mengacu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan
menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu
konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kese mpatan untuk
melakukan umpan balik (Devito, 1997).
Baik Miller (1986), Hovland (Effendy, 2000) maupun Mulyana dan
Rakhmat (2001) melih at komunikasi sebagai proses mengubah perilaku
16
pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu dengan efek
tertentu (Effendy, 2000; Laswell, 1976). Hal ini sejalan dengan pemikiran Slamet
(2003) yang melihat kegiatan komunikasi pembangunan (development
communication) sebagai aktivitas penyuluhan pertanian (agricultural extension
atau extension education), karena pada dasarnya tiga istilah itu semua mengacu
pada disiplin ilmu yang sama. Di sini beliau menyatakan bahwa tujuan
penyuluhan pertanian yang sebenarnya adalah perubahan perila ku kelompok
sasaran (Slamet, 1978). Mardikanto (1993) menegaskan melalui penyuluhan
pertanian ingin dicapai suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan luas,
memiliki sikap yang progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap
informasi baru, serta terampil dan mampu berswadaya untuk mewujudkan
keinginan dan harapan demi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dijelaskan bahwa proses komunikasi antara lain terdiri dari
model komunikasi lin ea r dan relational. Dalam model linear, informasi yang
berasal dari sumber disebut pesan dan yang berasal dari penerima disebut umpan
balik. Di sini penerima hanya memberikan umpan balik kepada sumber, tetapi
tidak menciptakan dan meneruskan pesan-pesannya. Model komunikasi seperti ini
biasanya terjadi secara vertikal. Dalam model komunikasi relational, setiap
partisipan komunikasi dapat saling meneruskan atau memberikan pesan baru
karena setiap pesan dapat dipakai sebagai perangsang untuk mendapat umpan
balik dari pesan-pesan sebelumnya. Proses komunikasi ini tidak terhenti sesudah
terdapat umpan balik, melainkan kembali ke peserta pertama kemudian peserta
tersebut menyusun pesan yang baru lagi (Kincaid dan Schramm, 1987). Dengan
demikian dalam model ini proses komunikasi berlangsung bolak-balik, yang
menur ut Effendy (2001) dikenal sebagai two -way traffic communication atau
komunikasi dua arah. Rahim (Depari dan MacAndrew s, 1998) menyebutkan
bahwa arah komunikasi dalam pembangunan desa biasanya mengalir dari atas
yang bersumber pada perencana pembangunan ata u pejabat daerah. Selain itu arus
17
Ruben dalam Muhammad (2000) mendefinisikan komunikasi manusia
adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok,
dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirim dan
menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain.
Sendjaja et al. (1994) sepakat melihat komunikasi sebagai sebuah tindakan untuk
berbagi informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi
yang terlibat di dalamnya guna mencapai kebersamaan makna. Tindakan
komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam beragam konteks. Konteks
komunikasi tersebut menurut Tubbs dan Moss (2000) terdiri dari komunikasi dua
orang, wawancara, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, komunikasi
organisasi, komunikasi massa dan komunikasi antarbudaya.
Komunikasi yang diartikan sebagai suatu proses dimana informasi terbagi,
lebih lanjut ditambahkan oleh Middleton (1980) bahwa proses ini sering disebut
juga sebagai jaring-jaring masyarakat (web of society) dimana individu, kelompok
dan pranata-pranata diatur bersama untuk membentuk suatu masyarakat.
Middleton pun menjelaskan bahwa sebagai suatu proses yang luas, komunikasi
melibatkan beberapa fungsi, seperti memberi dan menerima informasi,
mempengaruhi dan dipengaruhi, belajar dan mengajar, menghibur dan dihibur.
Pernyataan Middleton ini pernah disinggung oleh Rao (1966) yang pernah
menjadi anggota Departemen Komunikasi Massa UNESCO yang mengemukakan
bahwa komunikasi lebih mengacu pada proses sosial, yakni arus informasi,
peredaran pengetahuan dan gagasan-gagasan dalam masyarakat, pengembangan
dan internalisasi pikiran.
Fungsi komunikasi menurut Laswell adalah (1) pengamatan terhadap
lingkungan, (2) penghubung bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat agar
masyarakat dapat memberi respons terhadap lingkungan tersebut dan (3)
pemindahan warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya (Laswell,
1976). Konsep pengamatan terhadap lingkungan mengandung arti proses
mengumpulkan dan mendistribusikan “informasi” mengenai peristiwa-peristiwa
yang terjadi dalam suatu lingkungan, baik yang berasal dari dalam maupun dari
18
mengandung arti melakukan interpretasi terhadap informasi mengenai lingkungan,
dan selanjutnya memberitahukan cara -cara memberikan reaksi terhadap apa yang
terjadi. Sedangkan konsep pemindahan warisan sos ial dari satu generasi ke
generasi yang berikutnya berfokus pada mengkomunikasikan pengetahuan,
nilai-nilai dan norma-norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kegiatan
yang terakhir ini dikenal dengan sebutan pendidikan (Wright, 1986).
Ketiga fungsi komunikasi tersebut harus dijalankan seluruhnya. Bila salah
satu fungsi komunikasi itu terhambat, maka perkembangan masyarakat tidak akan
berjalan secara wajar, dan pada gilirannya akan menimbulkan
kekacauan-kekacauan yang merusak masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan ketiga
macam fungsi komunikasi tersebut, ada perbedaan antara cara yang digunakan
oleh masyarakat yang sederhana dan oleh masyarakat yang maju.
Komunikasi dalam masyarakat sederhana atau primitif cenderung
berlangsung secara tatap muka. Misalnya mereka merasa perlu berkomunikasi
antar sesamanya, baik waktu bermain maupun waktu beristirahat, berkumpul di
goa untuk melawan hawa dingin atau berlindung dari bahaya. Kelompok
masyarakat primitif ini juga menunjuk seorang penjaga yang bertugas mengawasi
keadaan sekeliling dan segera memberikan laporan bila musuh datang atau
memberi tahu bila ada binatang buruan yang dapat dijadikan bahan makanan
muncul. Informasi yang sampai pada masyarakat yang tinggal di goa ini, dipakai
untuk membuat keputusan mengenai hal yang harus dilakukan. Pemimpin atau
dewan pimpinan harus membuat keputusan setelah melakukan tukar-menukar
pendapat. Pimpinan kemudian menjelaskan situasi, mengeluarkan perintah dan
membagi tanggung jawab. Kebijakan yang diambil dalam masyarakat primitif
dapat juga didasarkan atas kepercayaan, kebiasaan atau hukum yang berlaku di
masyarakat tersebut. Jadi kewajiban penting yang harus dilakukan oleh
masyarakat ini adalah mengajarkan kepercayaan, kebiasaan, hukum dan
keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat yang masih
muda. Orang tua mengajari anak-anak mereka, orang yang lebih tua dan pemuka
agama mengajari orang-orang yang sudah dewasa. Peranan komunikasi yang
19
penjagaan (melakukan pengawasan terhadap alam sekeliling dan melaporkannya),
peranan kebijaksanaan (memutuskan kebijakan yang perlu diambil, memimpin
dan mengatur), dan peranan mengajar agar masyarakatnya mempunyai
keterampilan dan kepercayaan yang dipandang bernilai oleh masyarakat yang
bersa ngkutan. Di samping fungsi komunikasi formal tersebut, ada fungsi
komunikasi yang bersifat tidak formal, yaitu percakapan antar mereka sehari-hari.
Seperti mengungkapkan ekspresi cinta, persahabatan, menantang, berargumen dan
bertukar pikiran, barter dan perdagangan, menari, menyanyi, bercerita dan
melakukan komunikasi informal lainnya, memberi warna dan daya pengikat
masyarakat tersebut (Schramm, 1964).
Pada masyarakat maju atau masyarakat yang mempunyai peradaban tinggi
jangkauan komunikasi sangat luas. Aktivitas yang semula tidak formal dan santai
telah diformalkan. Sesuatu yang semula cukup ditangani oleh seorang atau
beberapa orang, sekarang diperlukan suatu lembaga sosial tersendiri untuk
menanganinya dengan memasukkan pula mesin-mesin ke dalam proses
komunikasi. Mesin-mesin digunakan untuk melihat, mendengar, berbicara dan
menulis dengan kemampuan jangkauan kerja yang sangat tinggi. Di lingkungan
mesin-mesin ini muncul pula institusi komunikasi yang sangat besar yang disebut
media massa. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa fungsi dasar komunikasi sendiri
tetap sama. Pekerjaan mengawasi lingkungan sekarang ditugaskan kepada media
massa. Pekerjaan yang membutuhkan konsensus, pembuatan kebijakan, dan
pengarahan tindakan-tindakan terutama menjadi tugas pemerintah. Organisasi
seperti partai politik dan media massa telah masuk jauh ke dalam proses
pembentukan opini dan tindakan. Tugas yang semula dilakukan oleh suatu
kelompok kecil dalam suatu percakapan singkat, sekarang menjadi diskusi
berbulan-bulan, yang melibatkan beratus-ratus ribu atau bahkan berjuta -juta
manusia dan mungkin memerlukan kampanye berskala nasional. Namun, esensi
kewajiban mereka tetap sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana,
yaitu memutuskan kebijakan dan memimpin. Kewajiban melakukan proses
sosialisasi terhadap anggota masyarakat dibebankan kepada sekolah dan media
20
ensiklopedi. Kebutuhan akan pengetahuan dan latihan tidak hanya tersedia
terbatas untuk anak-anak, melainkan juga untuk orang dewasa berupa lembaga
dan instruksi khusus, misalnya penyuluh pertanian, petugas peneliti dan
universitas , penyalur (dealer) penyediaan sarana, perbankan maupun lembaga
swadaya masyaraka t (LSM). Organisasi ini disebut “pelayanan informasi”
(Lionberger dan Gwin, 1982). Seluruhnya menjadi makin kompleks dan makin
canggih. Namun esensinya tetap sama, yaitu keperluan akan pelayanan informasi
(Schramm, 1964).
Di banyak desa di Indonesia, media komunikasi tradisional masih sering
dijumpai. Ketika sewaktu-waktu akan mengumpulkan warga masyarakat, cukup
dengan membunyikan kentongan yang dipukul dengan cara tertentu (kode) yang
berarti ada bahaya ataupun keadaan aman. Pertunjukan kesenian, se lain sebagai
alat hiburan juga merupakan sumber nilai-nilai atau petuah untuk menghadapi
berbagai masalah kehidupan yang mengarus melalui dialog ataupun perilaku yang
diperdengarkan dan dipertunjukan dalam kesenian seperti nyanyian rakyat, tarian
rakyat, musik instrumental rakyat dan drama rakyat. Menurut Jahi (1993) media
tradisional yang dekat dengan rakyat sangat efektif untuk menyampaikan pesan
pembangunan.