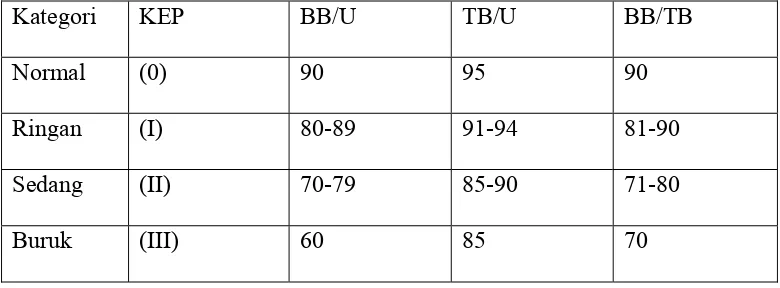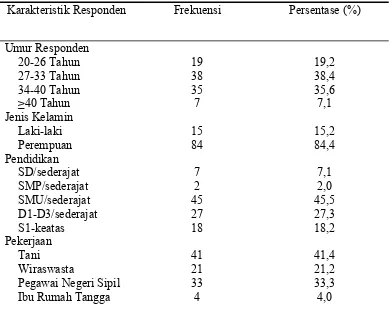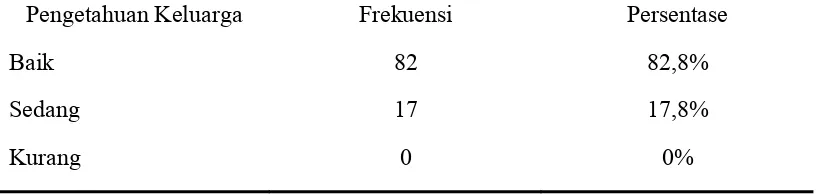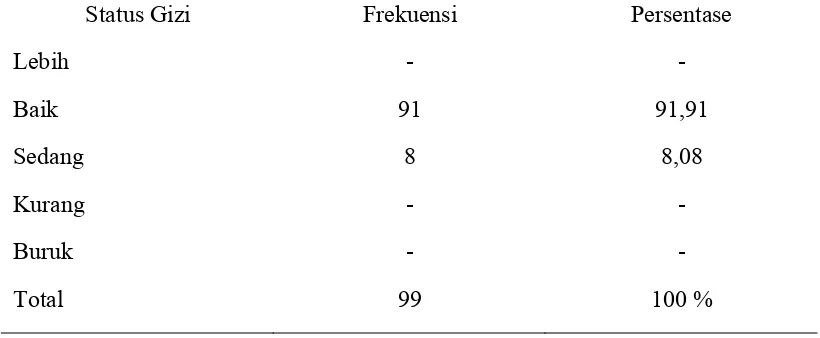PRAKATA
Segala puji kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang
telah dilimpahkan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu
dengan judul “Pengetahuan Keluarga Tentang Gizi dan Status Gizi BALITA di
Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli
Selatan”.
Di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bantuan dari
berbagai pihak, untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dedi Ardinata, M.Kes, selaku Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Sumatera Utara Medan
2. Ibu Siti Zahara Nasution, S.Kp. MNS, selaku Pembimbing I yang telah
banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis
3. Ibu Cholina Trisa S, S.Kep. M.Kep. Sp.KMB, selaku Pembimbing II yang
telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Ibu Farida Linda Siregar, S.Kep. Ns. M.Kep, selaku penguji dalam sidang
skripsi ini
5. Seluruh staff dan dosen yang mengajar di Fakultas Keperawatan
Universitas Sumatera Utara
6. Kedua orangtua dan abang saya Adi Amsyah Siregar, ST, yang telah
banyak memberikan dukungan moril dan materil dalam proses penyusunan
skripsi ini
7. Seluruh rekan yang ada di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam
hal penulisan maupun isi, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran
demi perbaikan skripsi ini.
Medan, 12 Januari 2011
DAFTAR ISI
Halaman Judul ... i
Halaman Pengesahan ... ii
Prakata ... iii
Daftar Isi…………. ... v
Daftar Tabel……… vii
Daftar Skema……… viii
Abstrak……… ix
Bab 4. Metodologi Penelitian ……….... 52
1. Desain Penelitian ... 52
2. Populasi dan Sampel ... 52
3. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 53
4. Pertimbangan Etik ... 53
5. Instrumen Penelitian ... 54
6. Validitas Instrumen Penelitian ... 54
7. Reliabilitas Instrumen Penelitian ... 55
8. Rencana Pengumpulan Data ... 55
9. Analisa Data ……… 56
Bab 5. Hasil dan Pembahasan………. 58
1. Hasil Penelitian……… 58
2. Pembahasan………...61
Bab 6. Kesimpulan dan Saran……… 65
Daftar Pustaka Lampiran-lampiran
1. Surat Persetujuan Menjadi Responden 2. Instrumen Penelitian
3. Format Penilaian Status Gizi 4. Daftar Riwayat Hidup 5. Surat Izin Penelitian
DAFTAR TABEL
DAFTAR SKEMA
Skema 3.1 Kerangka Konsep Gambaran Pengetahuan Keluarga
Judul : Pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi
BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
Nama Mahasiswa : Elisa Jaelina Siregar
NIM : 091121003
Fakultas : S1 Keperawatan
Tahun : 2010
Abstrak
WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memegang peranan besar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam fungsi keluarga, yaitu fungsi perawatan kesehatan, keluarga haruslah memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik mengenai gizi keluarga, khususnya gizi BALITA. Usia BALITA merupakan momentum penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pada masa ini terjadi pembentukan kepribadian dan kecerdasan, maka untuk mewujudkan BALITA yang sehat adalah dengan memenuhi kebutuhan gizinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2010 dan menggunakan kuesioner yang terdiri dari data demografi, pengetahuan keluarga tentang gizi, dan format penilaian status gizi BALITA berdasarkan standar WHO-NCHS, 1983. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga tentang gizi berada dalam kategori baik 82 responden (82,8%) dan kategori sedang 17 responden (17,8%). Penilaian berat badan BALITA menurut umur didapatkan bahwa sebanyak 91 BALITA (91,91%) memiliki status gizi baik, 8 BALITA (8,08%) memiliki status gizi sedang. Dengan pengetahuan yang baik khususnya mengenai kesehatan, keluarga akan lebih mudah memahami masalah kesehatan yang ada, baik yang potensial maupun yang beresiko mengancam kesehatan keluarga. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa selain faktor ekonomi yang baik, faktor lain yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kesehatan BALITA yang baik adalah adanya kesadaran dan penngetahuan orangtua tentang gizi keluarga.
Judul : Pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi
BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
Nama Mahasiswa : Elisa Jaelina Siregar
NIM : 091121003
Fakultas : S1 Keperawatan
Tahun : 2010
Abstrak
WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memegang peranan besar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam fungsi keluarga, yaitu fungsi perawatan kesehatan, keluarga haruslah memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik mengenai gizi keluarga, khususnya gizi BALITA. Usia BALITA merupakan momentum penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pada masa ini terjadi pembentukan kepribadian dan kecerdasan, maka untuk mewujudkan BALITA yang sehat adalah dengan memenuhi kebutuhan gizinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai BALITA di Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2010 dan menggunakan kuesioner yang terdiri dari data demografi, pengetahuan keluarga tentang gizi, dan format penilaian status gizi BALITA berdasarkan standar WHO-NCHS, 1983. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga tentang gizi berada dalam kategori baik 82 responden (82,8%) dan kategori sedang 17 responden (17,8%). Penilaian berat badan BALITA menurut umur didapatkan bahwa sebanyak 91 BALITA (91,91%) memiliki status gizi baik, 8 BALITA (8,08%) memiliki status gizi sedang. Dengan pengetahuan yang baik khususnya mengenai kesehatan, keluarga akan lebih mudah memahami masalah kesehatan yang ada, baik yang potensial maupun yang beresiko mengancam kesehatan keluarga. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa selain faktor ekonomi yang baik, faktor lain yang tidak kalah penting dalam mewujudkan kesehatan BALITA yang baik adalah adanya kesadaran dan penngetahuan orangtua tentang gizi keluarga.
BAB 1
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Tiap negara mempunyai kebudayaan masing-masing, termasuk kebudayaan
makan dengan ciri makanannya. Pola makan ini dipengaruhi oleh beberapa hal,
antara lain: kebiasaan kesenangan, budaya, agama, taraf ekonomi, lingkungan alam
dan sebagainya. Pola makan di suatu daerah dapat berubah-ubah sesuai dengan
perubahan faktor lingkungan ataupun kondisi setempat, yang dapat dibagi menjadi
tiga kelompok, yang pertama adalah faktor ketersediaan bahan pangan, yang kedua
faktor adat kebiasaan setempat, dan yang ketiga adalah bantuan atau subsidi
terhadap bahan pangan tertentu (Santoso dan Ranti, 2004).
Perubahan pola sosial di berbagai negara industri telah memberikan
pengaruh yang kuat, walau belum tentu memberikan manfaat nutrisi bagi
anak-anak. Tradisi untuk memasak di rumah atau menanam sayur sendiri telah bergeser
menjadi belanja di supermarket, makanan cepat saji dengan pelayanan yang
nyaman, dan makanan yang dapat dibawa pulang. Terdapat peningkatan dalam hal
kedua orangtua yang mencari pekerjaan di luar rumah, dan banyak keluarga yang
membeli makanan praktis yang cuma memerlukan penghangatan saja (Meadow &
Newell, 2005).
WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan
kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Sejak janin dalam kandungan, bayi,
gizi merupakan kebutuhan utama untuk bertahan hidup, pertumbuhan fisik,
perkembangan mental, prestasi kerja, kesehatan dan kesejahteraan (Soekirman,
2000).
Proses pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sejak dalam
kandungan. Pertumbuhan yang terjadi pada seseorang tidak hanya meliputi apa
yang terlihat seperti perubahan fisik, tetapi juga perkembangan dalam segi lain
seperti berfikir, berperasaan, dan bertingkah laku. Masa lima tahun merupakan
masa terbentuknya dasar-dasar kepribadian manusia, kemampuan penginderaan,
berfikir, keterampilan berbahasa dan berbicara, bertingkah laku sosial dan lain-lain
(Depkes RI, 2000).
Makanan bergizi sangat penting diberikan kepada bayi sejak masih dalam
kandungan. Selanjutnya, masa bayi dan BALITA merupakan momentum paling
penting dalam melahirkan generasi pintar dan sehat. Jika usia ini tidak dikelola
dengan baik, apalagi kondisi gizinya buruk, di kemudian hari akan sulit terjadi
perbaikan kualitas bangsa (Widjaja, 2002).
Masalah gizi menjadi masalah kesehatan utama di negara berkembang dan
salah satu penyebab kesakitan dan penyebab kematian paling sering pada anak di
seluruh dunia. Gizi buruk merupakan penyebab langsung dari 300.000 kematian
anak setiap tahunnya dan secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap
setengah dari seluruh kematian dari seluruh kematian anak. WHO ( World Health
Organization) memperkirakan bahwa 54% penyebab kematian bayi dan BALITA
Masalah gagalnya “penanganan bayi dan BALITA” bukan akibat
pembawaan, melainkan merupakan proses usaha yang kurang berhasil. Hal ini
dapat dilihat dari data yang menunjukkan perbandingan yang sangat berbeda antara
kondisi bayi yang lahir di negara berkembang dengan bayi yang lahir di negara
maju. Di Indonesia, misalnya masih banyak bayi yang lahir dengan berat badan di
bawah 2.500 gram. Artinya, di bawah berat badan normal. Sementara itu, di
beberapa negara maju berat badan bayi lahir rata-rata 3.800 gram. Hal ini
disebabkan kondisi ekonomi mereka yang telah maju, disamping adanya kesadaran
dan pengetahuan orangtua tentang gizi keluarga (Widjaja, 2002).
Sejak tahun 2004 sampai dengan 2006, pemerintah telah mengalokasikan
anggaran sebesar lebih dari Rp.528.379.595 untuk program perbaikan gizi
masyarakat. Departemen Kesehatan antara lain memanfaatkan anggaran tersebut
untuk membiayai berbagai program intervensi untuk mencegah dan
mananggulangi insiden gizi buruk dan gizi kurang. Data Depertemen Kesehatan
menyebutkan kasus gizi buruk dan gizi kurang pada BALITA tahun 2004
(Pemantauan Status Gizi 2004) masing-masing 8.00 % dan 20,47 % dari seluruh
populasi BALITA. Sementara tahun 2005 (Survei Sosial Ekonomi Nasional/
SUSENAS 2005) jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang berturut-turut 8,8 % dan
19,20 %. Tahun 2006, selama periode Januari-Oktober, jumlah total kasus gizi
buruk yang ditangani petugas kesehatan sebanyak 20.580 kasus dan 186
diantaranya menyebabkan kematian. Seminar Hari Gizi Nasional Tahun 2007,
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, menyebutkan bahwa sekitar 5.543.944
masalah gizi buruk dan gizi kurang (Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat, 2007)
Februari 2010, data yang diperoleh dari Puskesmas Pargarutan yang
mewakili untuk seluruh wilayah Kecamatan Angkola Timur, pada tahun 2008
terdapat 1621 BALITA yang terdaftar di pos penimbangan. Tahun 2009 terdapat
1423 BALITA di pos penimbangan. Februari 2010, terdapat 1060 BALITA di pos
penimbangan. Besarnya jumlah BALITA yang terdata diatas, menarik peneliti
untuk meneliti pengetahuan keluarga tentang gizi dan status gizi BALITA di
Kelurahan Lingkungan II Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Tujuan Penelitian
2.1 Tujuan Umum
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan
keluarga tentang gizi dan status gizi BALITA di Kelurahan Lingkungan II
Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
2.2 Tujuan Khusus
2.2.1 Melihat gambaran tingkat pengetahuan keluarga tentang gizi
3. Manfaat Penelitian
4.1 Bagi keluarga dan masyarakat
Hasil penelitian diharapkan dapat membawa manfaat bagi keluarga dan
masyarakat, yaitu di dalam pemasyarakatan pendidikan gizi untuk keluarga,
khususnya gizi BALITA, sehingga keluarga dapat lebih bijaksana dalam
menyikapi masalah-masalah keluarga yang berkaitan dengan gizi .
4.2 Praktek Keperawatan
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam praktek
keperawatan, khususnya bagi keperawatan keluarga mengenai pentingnya
memberikan pendidikan kesehatan mengenai gizi kepada keluarga, dan untuk
segenap profesi keperawatan dalam mengoptimalkan pemberian asuhan
keperawatan kepada masyarakat.
4.3Riset Keperawatan
Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam penyajian data awal
bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian selanjutnya dalam ruang
BAB 2
TINJAUAN TEORITIS
1. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi
melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, penciuman, pendengaran,
rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan
telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam
membentuk tindakan seseorang.
Hasil penelitian Rogers (1974) dalam Notoatmodjo (2007) mengungkapkan
bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri
orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni:
1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti
mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.
2. Interest, yakni orang mulai tertarik terhadap stimulus
3. Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi
dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru.
5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan,
kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.
Namun demikian, dari penelitian selanjutnya Rogers menyimpulkan bahwa
Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan.
1. Tahu (know)
Tahu diartikan sebagi mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat
kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau
rangsangan yang diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang
apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan,
menguraikan dan sebagainya.
2. Memahami (comprehension)
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara
benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut
secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat
menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya
terhadap objek yang dipelajari.
3. Aplikasi (aplication)
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang
telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang real (sebenarnya). Aplikasi disini
dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode,
prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
4. Analisis (analysis)
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu
objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur
dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat
bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.
5. Sintesis (synthesis)
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru
dari fomulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat
merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap
suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.
6. Evaluasi (evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau
penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada
suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang
telah ada. Misalnya, dapat membandingkan antara anak yang cukup gizi dengan
anak yang kekurangan gizi, dapat menganggapi terjadinya diare di suatu tempat,
dapat menafsirkan sebab-sebab mengapa ibu-ibu tidak mau ikut KB, dan
sebagainya (Notoatmodjo, 2007).
2. Keluarga
2.1 Defenisi Keluarga
Bailon dan Maglaya (1978) (dikutip dari Setyowati & Murwani, 2008)
mendefinisikan keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu
saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing
dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.
Spredley dan Allender (1996) (dikutip dari Setyowati & Murwani, 2008)
mendefinisikan keluarga adalah satu atau lebih individu yang tinggal bersama,
sehingga mempunyai ikatan emosional dan mengembangkan dalam interaksi
sosial, peran dan tugas.
Menurut BKKBN 1992 (Setyowati & Murwani, 2008) keluarga adalah unit
terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan
anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
2.2 Karakteristik Keluarga
1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan
perkawinan atau adopsi
2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap
memperhatikan satu sama lain
3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing
mempunyai peran sosial suami, istri, anak, kakak, adik.
4. Mempunyai tujuan; (a) menciptakan dan mempertahankan budaya, (b)
2.3 Fungsi Keluarga
Friedmann (1986) (Setyowati & Murwani, 2008) mengidentifikasi lima
fungsi dasar keluarga, sebagai berikut:
1. Fungsi afektif
a. Saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, saling menerima, saling
mendukung antar anggota keluarga. Hubungan intim di dalam keluarga
merupakan modal dasar dalam memberi hubungan dengan orang lain diluar
keluarga/ masyarakat.
b. Saling menghargai, bila anggota keluarga saling menghargai dan mengakui
keberadaan dan hak setiap anggota keluarga serta selalu mempertahankan
iklim yang positif, maka fungsi afektif akan tercapai.
c. Ikatan dan identifikasi ikatan keluarga dimulai sejak pasangan sepakat
memulai hidup baru. Ikatan antar anggota keluarga dikembangkan melalui
proses identifikasi dan penyesuaian pada berbagai aspek kehidupan anggota
keluarga.
2. Fungsi sosialisasi
Sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu,
yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan
sosial. Keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi.
Keberhasilan perkembangan individu dan keluarga dicapai melalui interaksi
3. Fungsi Reproduksi
Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber
daya manusia. Maka dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, selain untuk
memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan tujuan untuk membentuk
keluarga adalah untuk meneruskan keturunan.
4. Fungsi ekonomi
Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan
anggota keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
5. Fungsi perawatan kesehatan
Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan
kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan atau
merawat anggota keluarga yang sakit.
Tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut:
1. Mengenal masalah kesehatan
2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat
3. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit
4. Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat
5. Mempertahankan hubungan dengan (menggunakan) fasilitas kesehatan
3. Gizi
3.1 Defenisi Gizi
Kata gizi berasal dari bahasa Arab gidzha, yang berarti makanan. Zat gizi
(nutrients) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan
fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan
serta mengatur proses-proses kehidupan.
Gizi (nutrition) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan
yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorbsi, transportasi,
penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan,
untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari
organ-organ, serta menghasilkan energi (Rahmah, 2006).
WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang mempelajari “proses yang
terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengolah zat-zat padat dan
cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan,
berfungsinya organ-organ tubuh, dan menghasilkan energi” (Soekirman, 2000).
3.2Klasifikasi dan Fungsi Zat Gizi
WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan
kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Sejak janin dalam kandungan, bayi,
BALITA, anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, makanan yang memenuhi
syarat gizi merupakan kebutuhan utama untuk pertahanan hidup, pertumbuhan
fisik, perkembangan mental, prestasi kerja, kesehatan dan kesejahteraan
(Soekirman, 2000).
1. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan/ perkembangan serta
mengganti jaringan tubuh yang rusak.
2. Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari
3. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air dan
mineral dan cairan tubuh yang lain
4. Berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit.
1. Karbohidrat
Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembentuk berbagai
senyawa tubuh, bahan pembentuk asam amino esensial, metabolisme normal
lemak, menghemat protein, meningkatkan pertumbuhan bakteri usus,
mempertahankan gerak usus (terutama serat), meningkatkan konsumsi protein,
mineral dan vitamin B. Pangan sumber karbohidrat adalah beras, ubi jalar,
singkong, kentang, pisang, sagu dan gandum.
a) Karbohidrat digolongkan dalam polisakarida, disakarida dan monosakarida.
Monosakarida dan disakarida dikenal sebagai gula sederhana atau
karbohidrat sederhana. Monosakarida penting dalam pangan dan
metabolisme adalah glukosa, fruktosa, galaktosa dan mannosa, keempat
bahan tersebut merupakan unit pembentuk disakarida. Polisakarida dikenal
b) Jika dibakar dalam tubuh menghasilkan energi, CO2, dan air.
c) Beberapa karbohidrat dapat disintesa dalam tubuh dari lemak dan protein
yang tersimpan dalam tubuh.
d) Karbohidrat dapat disimpan sedikit dalam tubuh, yaitu di dalam hati dan
jaringan otot sebagai glikogen.
e) Jika sebagian besar karbohidrat yang diserap tubuh tidak segera digunakan
maka akan diubah menjadi lemak dan disimpan sebagai jaringan lemak
untuk memenuhi kebutuhan energi saat diperlukan nanti.
f) Biasanya bahan makanan yang kaya karbohidrat tampak berukuran besar
dan sedikit sekali mengandung zat gizi lainnya.
2. Gula
Gula yang diserap digunakan dalam satu dari enam cara berikut:
a) Sumber energi dan panas untuk mempertahankan suhu badan. Sistem saraf
pusat dan lensa mata hanya dapat menggunakan glukosa untuk energinya,
sedangkan jaringan lain dapat juga menggunakan lemak.
b) Disimpan sebagai glikogen dalam otot. Glikogen juga disimpan dalam hati
dan dibebaskan untuk mempertahankan gula darah jika dibutuhkan.
c) Dikonversi menjadi trigliserida dan disimpan sebagai lemak dalam jaringan
lemak.
d) Dikonversi menjadi karbohidrat lain seperti DNA, RNA, asam glukoronat,
e) Dikonversi menjadi asam amino esensial.
f) Dibuang bersama urin. Jika taraf glukosa darah melebihi 160 – 190 mg/dl
maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula dan gula tersebut
dibuang melalui urin. Kadar normal glukosa dalam urin sekitar 15 mg/dl.
3. Serat
Serat makanan adalah komponen makanan yang berasal dari tanaman yang
tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Serat makanan total terdiri
dari komponen serat makanan yang larut (misalnya pektin, gum) dan yang
tidak dapat larut dalam air (misalnya selulosa, hemiselulosa, lignin). Bahan
makanan yang banyak mengandung serat antara lain buah-buahan (apel,
mangga), sayuran terutama sayuran hijau (daun katuk, daun singkong, bayam,
kangkung), kacang-kacangan (kacang hijau), serealia (beras).
Serat bukanlah zat yang dapat diserap oleh usus. Namun, peranannya dalam
proses pencernaan sangat penting, bahkan pada penderita gizi lebih dapat
mencegah/mengurangi resiko penyakit degeneratif seperti jantung koroner,
diabetes dan kanker kolon. Serat larut lebih efektif dalam mereduksi plasma
kolesterol yaitu LDL (low density lipoprotein) dan meningkatkan kadar HDL
(high density lipoprotein). Serat larut sangat bermanfaat bagi penderita diabetes
karena mereduksi absorbsi glukosa dalam usus. Selain itu juga dapat membuat
kenyang sehingga mengontrol berat badan. Serat tak larut berperan dalam
pencegahan disfungsi alat pencernaan seperti konstipasi, ambeien, kanker usus
4. Protein
Setelah air, protein merupakan zat gizi yang paling banyak terdapat dapat
tubuh. Seperlima dari berat tubuh orang dewasa merupakan protein. Hampir
setengah jumlah protein terdapat di otot, seperlima terdapat di tulang atau
tulang rawan, sepersepuluh terdapat di kulit, sisanya terdapat di jaringan lain
dan cairan tubuh. Protein mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:
a) Membentuk jaringan baru dalam masa pertumbuhan dan perkembangan
tubuh.
b) Memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang
rusak, aus dan mati.
c) Menyediakan asam amino yang diperlukan dalam membentuk enzim
pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan.
d) Mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam tiga komponen yaitu
intraselular, intravaskular dan interstitial
e) Mempertahankan kenetralan (asam-basa) tubuh
Selama pencernaan, protein dipecah menjadi asam amino. Tubuh manusia
membutuhkan 8 – 10 asam amino yang berasal dari protein makanan dan mutlak
diperlukan pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Asam amino tersebut
disebut asam amino esensial karena tidak dapat dibentuk di dalam tubuh. Selain
itu, jika terdapat cukup gugusan amino dan vitamin B6, tubuh dapat membentuk
asam amino nonesensial melalui proses transaminasi
Jenis dan proporsi asam amino sangat menentukan mutu protein. Protein
memberikan pertumbuhan secara optimal disebut protein lengkap, dan umumnya
disusun oleh sepertiga asam amino esensial dan dua pertiga asam amino
nonesensial. Pola asam amino hewani merupakan sumber terbaik untuk memenuhi
kebutuhan manusia karena polanya menyerupai pola kebutuhan asam amino
manusia.
Pangan sumber protein hewani adalah daging ayam, sapi, ikan, telur, susu
dan produk olahannya. Pangan nabati yang banyak mengandung protein adalah
kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Sebagian kecil protein terdapat dalam sayur
dan buah-buahan.
5. Lemak (lipid)
Lemak dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sumbernya
didapat:
1. Lemak dalam tubuh, yaitu lipoprotein (mengandung trigliserida, fosfolipid,
dan kolesterol yang bergabung dengan protein; dihasilkan di hati dan
mukosa usus untuk mengangkut lemak yang tidak larut. Jenis yang terdapat
di dalam tubuh yaitu HDL (high density lipoprotein), LDL (low density
lipoprotein) dan VLDL (very low density lipoprotein) yang berperan dalam
penyakit jantung dan glikolipid.
2. Lemak yang terdapat dalam pangan yaitu trigliserida, asam lemak jenuh,
a. Trigliserida banyak ditemukan pada pangan hewani dan nabati, disebut
lemak netral, dengan struktur dasar meliputi satu molekul gliserol dan
tiga buah molekul asam lemak.
b. Asam lemak jenuh (saturated fatty acid-SAFA) yaitu lemak yang tidak
dapat mengikat hidrogen lagi, seperti asam palmitat, asam stearat yang
banyak ditemukan pada lemak hewani, keju, mentega, minyak kelapa
dan cokelat.
c. Asam lemak tidak jenuh, yang mempunyai satu titik terbuka untuk
mengikat hidrogen disebut asam lemak tak jenuh tunggal
(monosaturated fatty acid) seperti asam oleat yang dijumpai pada
minyak kacang tanah. Asam lemak tak jenuh ganda (polisaturated fatty
acid) seperti asam linoleat, linoleat, asam arachidonat. Asam linoleat
merupakan asam lemak esensial yang banyak terdapat dalam minyak
biji bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai. Asam lemak
omega-6 merupakan asam linoleat dan arachidonat yang banyak
terdapat pada minyak sayuran; asam lemak omega-3 banyak terdapat
dalam minyak ikan.
d. Fosfolipid, merupakan senyawa lipid yaitu gliserol dan asam lemak
bergabung dengan karbohidrat, fosfat dan atau nitrogen. Lemak ini
merupakan lemak tak kentara dalam pangan nabati maupun hewani dan
secara komersial digunakan sebagai aditif untuk membantu
e. Kolesterol, semacam lemak dengan struktur cincin yang kompleks yang
disebut sterol. Kolesterol hanya ditemukan dalam jaringan hewan
seperti telur, daging, lemak susu. Hati dan usus dapat mensintesis
semua kolesterol yang diperlukan tubuh tanpa mengkonsumsi kolesterol
dari luar.
Lemak yang terdapat dalam pangan berfungsi sebagai sumber energi yang
padat bagi tubuh yaitu 9 kkal/g, menghemat protein dan tiamin, memberi rasa
kenyang lebih lama, memberi cita rasa pada makanan.
6. Mineral
Kira-kira 6% tubuh manusia dewasa terbuat dari mineral. Mineral merupakan
bahan anorganik dan bersifat esensial. Fungsi mineral bagi tubuh sebagai
berikut:
a) Memelihara keseimbangan asam tubuh dengan jalan penggunaan mineral
pembentuk asam dan mineral pembentuk basa
b) Mengkatalisasi reaksi yang bertalian dengan pemecahan karbohidrat, lemak
dan protein serta pembentukan lemak dan protein tubuh
c) Sebagai hormon dan enzim tubuh
d) Membantu memelihara keseimbangan air tubuh
e) Menolong dalam pengiriman isyarat ke seluruh tubuh
f) Sebagai bagian cairan usus
g) Berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi dan jaringan
Mineral yang dibutuhkan manusia diklasifikasikan menjadi dua golongan,
yaitu mineral makro dan mineral mikro. Unsur-unsur dalam mineral makro adalah
kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium. Unsur-unsur mineral
mikro adalah besi, seng, selenium, mangan, tembaga, iodium, molibdenum, kobalt,
khromium, silikon, vanadium, nikel, arsen, dan fluor.
a) Kalsium dapat diperoleh dari pangan susu, lobak cina, kangkung, tiram,
udang, salem, dan kinjing.
b) Fosfor dapat diperoleh dari susu, keju, kuning telur, daging ikan, unggas,
dan kacang-kacangan
c) Kalium dapat diperoleh dari daging, ikan, unggas, tepung, buah-buahan dan
sayuran.
d) Natrium dapat diperoleh dari garam dapur, daging, ikan, unggas, susu dan
telur.
e) Khlor dapat diperoleh dari garam dapur, daging, susu dan telur.
f) Sulfur dapat diperoleh dari susu, telur, daging, keju dan kacang-kacangan.
g) Magnesium dapat diperoleh dari tepung gandum, kakao, kacang-kacangan,
daging, makanan laut dan susu.
h) Zat besi dapat diperoleh dari hati, daging dan kuning telur, sayuran berdaun
hijau tua, tiram, udang, salem, kinjing.
i) Mangan dapat diperoleh dari tepung gandum, kacang-kacangan, daging,
ikan, ayam, sayuran berdaun hijau.
j) Tembaga dapat diperoleh dari hati, tiram, daging, ikan, kacang-kacangan
k) Seng dapat diperoleh dari tiram, makanan laut, hati, lembaga gandum, ragi,
daging, telur, unggas dan ikan.
l) Iodium dapat diperoleh dari garam beriodium dan makanan laut.
m) Selenium dapat diperoleh dari ikan laut, kerang-kerangan.
n) Fluor dapat diperoleh dari air minum yang cukup kandungan fluornya.
7. Vitamin
Vitamin adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi
penting untuk fungsi metabolik dan harus didapat dari makanan. Vitamin
dibagi dalam dua kelas besar yaitu vitamin yang larut dalam air (vitamin C dan
vitamin B kompleks) dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E,
K).
a) Vitamin A berfungsi dalam proses penglihatan, pertumbuhan, reproduksi,
perkembangan tulang, kekebalan, mempertahankan jaringan epitel. Sumber
vitamin A adalah dari minyak ikan, hati, mentega, susu, keju, sayuran daun
hijau tua, sayuran dan buah berwarna kuning.
b) Vitamin D berfungsi menaikkan penyerapan Ca dan P dari usus,
mempengaruhi pemeliharaan P oleh ginjal, dan dapat diperoleh dari minyak
ikan, susu, sterol aktif, sedikit pada mentega, hati dan kuning telur.
c) Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi vitamin dalam
makanan, membantu dalam pernafasan jaringan. Vitamin E dapat diperoleh
biji kapas, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, susu, telur, daging dan
ikan.
d) Vitamin K berfungsi mengkatalisis reaksi karboksilasi atom karbon residu
asam glutamat pada protein tertentu dan untuk aktivitas anti pembekuan
darah. Sumber vitamin K adalah dari daun hijau seperti bayam, kubis, hati,
sintesis dalam usus oleh aktivitas mikroorganisme.
e) Vitamin C berfungsi dalam pembentukan kolagen, gigi, metabolisme
tirosin, sintesis neurotransmitter, utilisasi Fe, Ca, folat, mencegah kanker.
Vitamin C dapat diperoleh dari buah jeruk, tomat, arbei, kangkung,
kentang, cabai hijau, selada hijau, jambu biji.
f) Thiamin berfungsi sebagai unsur sistem enzim jaringan terutama dalam
hubungannya dengan karboksilasi, misal asam piruvat dan ketoglutarat.
Sumber thiamin adalah dari jantung, hati, ginjal, ragi, lembaga gandum,
kedelai, kacang tanah, kacang-kacangan dan susu.
g) Riboflavin berfungsi sebagai unsur sistem enzim pernafasan jaringan dan
beberapa enzim (flavoprotein) yang berperan dalam metabolisme asam
amino dan lipid. Didapat dari susu, hati, ginjal, jantung, daging, telur,
sayuran daun hijau, ragi kering.
h) Vitamin B6 (piridoksin) penting untuk transulfurasi dan dalam perubahan
triptopan menjadi niasin, juga sebagai koenzim dalam transaminasi.
Berperan dalam metabolisme asam lemak esensial. Penting dalam sintesis
porfirin. Sumber B6 adalah lembaga gandum, daging, hati, ginjal, tepung
i) Niasin berfungsi sebagai zat pemindah H dan elektron dalam pernafasan.
Triptofan dalam keadaan normal menambah suplai niasin. Niasin dapat
diperoleh dari hati, ginjal, daging, ikan, ayam, dan sayuran hijau, tomat,
kacang tanah, buah dan sayur sedikit mengandung niasin.
j) Asam pantotenat, merupakan unsur koenzim A yang berperan dalam
sintesis dan pemecahan asam lemak, sintesis kolesterol dan
hormon-hormon steroid. Pangan yang mengandung asam pantotenat adalah hati,
ginjal, daging sapi, kuning telur, kacang tanah, brokoli, kubis, dedak
tepung, susu skim dan buah.
k) Asam folat berperan dalam transfer dan pemakaian gugus satu karbon,
berperan dalam sintesis purin, tiamin, dan gugus metil. Mempunyai
peranan spesifik dalam metabolisme histidan dan peranan dalam
hemopoesis. Asam folat diperoleh dari hati, ginjal, ragi, sayuran daun hijau,
kembang kol, sistesis oleh aktivitas mikroorganisme usus.
l) Vitamin B12, berperan dalam metabolisme purin dan pirimidin, sintesis
asam nukleat (DNA), pematangan eritrosit, metabolisme metionin dan
transmetilasi. Pangan yang mengandung vitamin B12 adalah hati, ginjal,
daging, telur, susu, keju, sedikit pada tumbuh-tumbuhan. Sintesis dalam
4. Status Gizi
4.1 Defenisi Status Gizi
Status gizi merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan
antara kebutuhan dengan asupan zat gizi (Uripi, 2004).
Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk
variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu
(Supariasa, Bakri dan Fajar, 2001).
Keadaan kesehatan gizi masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi.
Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas hidangan. Kualitas
menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh dalam susunan
hidangan dan perbandingan yang satu terhadap yang lain. Kuantitas
menunjukkan kuantum masing-masing zat gizi terhadap kabutuhan tubuh.
Kalau susunan hidangan memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut kualitas
maupun kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan gizi yang
sebaik-baiknya (Santoso & Ranti, 2004).
4.2 Klasifikasi Status Gizi
Kebutuhan energi dan protein harus dicukupi dengan tepat. Jika
kekurangan menyebabkan keadaan yang disebut Kekurangan Energi dan
Protein (KEP). Jika berlebih, menimbulkan gizi yang lebih dikenal dengan
obesitas. Status gizi BALITA dapat dipantau dengan menimbang anak setiap
Tabel 2.1 Klasifikasi Status Gizi
INDEK Status Gizi Keterangan
Berat Badan Menurut Gizi Lebih 32 SD
Umur (BB/U) Gizi Baik -2 sampai +2 SD
Gizi Kurang <>
Gizi Buruk < -3 SD
Tinggi Badan Menurut Normal -2 sampai + 2 SD
Umur (TB/U) Pendek (Stunted) < -2 SD
Berat Badan Menurut Gemuk 32 SD
Tinggi Badan (BB/TB) Normal -2 sampai + 2 SD
Kurus (wasted) < -2 sampai -3 SD
Sangat Kurus < -3 SD
4.3 Penilaian Status Gizi
a. Penilaian Secara Langsung
Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi empat penilaian,
yaitu antropometri, klinis, biokimia, biofisik.
a.1 Antropometri
Secara umum bermakna ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut
pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam
pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur
dan tingkat gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat
ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini
terlihat dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti
lemak, otot dan jumlah air di dalam tubuh.
a.2 Klinis
Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang
dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Hal ini dapat dilihat pada
jaringan epitel (superficial epithelial tissues) seperti di kulit, mata, rambut
dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan
tubuh seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini umumnya untuk
survey klinis secara cepat (rapid clinical surveys). Survey ini dirancang
untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis kekurangan salah satu zat
gizi atau lebih. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat gizi
seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (sign) dan
a.3 Biokimia
Adalah suatu pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang
dilakukan dengan berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang
digunakan antara lain: urine, darah, feses, beberapa jaringan tubuh lain
seperti hati dan otot. Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa
kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi.
Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faali
dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang
spesifik.
a.4 Biofisik
Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status
gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat
perubahan struktur jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi
tertentu seperti kejadian buta senja epidemik (epidemic of night blindes).
Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap.
b. Penilaian Secara Tidak Langsung
Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi tiga yaitu:
survey konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi.
b.1 Survey Konsumsi Makanan
Adalah suatu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan
melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data
berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survei ini dapat
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.
b.2 Statistik Vital
Adalah dengan cara menganalisis data dari beberapa statistik kesehatan
seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian
akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.
Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak
langsung pengukuran status gizi masyarakat.
b.3 Faktor Ekologi
Berdasarkan ungkapan dari Bengoa dikatakan bahwa malnutrisi
merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik,
biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat
tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan lain-lain
(Supariasa, Bakri dan fajar, 2001).
5. BALITA
Secara harfiah, BALITA atau anak di bawah lima tahun adalah anak usia
kurang dari lima tahun sehingga bayi usia di bawah satu tahun juga termasuk
golongan ini. Namun, karena faal (kerja alat tubuh semestinya) bayi usia di bawah
satu tahun berbeda dengan anak usia di atas satu tahun, banyak ilmuwan yang
membedakannya. Utamanya, makanan bayi berbentuk cair, yaitu air susu ibu
(ASI), sedangkan umumnya anak usia lebih dari satu tahun mulai menerima
Anak usia 1-5 tahun dapat pula dikatakan mulai disapih atau selepas
menyusu sampai dengan prasekolah. Sesuai dengan pertumbuhan badan dan
kecerdasannya, faal tubuhnya juga mengalami perkembangan sehingga jenis
makanan dan cara pemberiannya pun harus disesuaikan dengan keadaannya.
Menurut Persagi (1992), berdasarkan karakteristiknya, BALITA usia 1-5 tahun
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak usia lebih dari satu tahun sampai tiga
tahun yang dikenal dengan BATITA, dan anak usia lebih dari tiga tahun sampai
lima tahun yang dikenal dengan usia prasekolah. BATITA sering disebut
konsumen pasif, sedangkan usia prasekolah lebih dikenal dengan konsumen aktif
(Uripi, 2004).
6. Gizi untuk BALITA
Kebutuhan gizi seseorang adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk
memelihara kesehatan pada umumnya. Secara garis besar, kebutuhan gizi
ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan dan tinggi badan. Antara
asupan gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status
gizi yang baik (Uripi, 2004).
6.1 Kebutuhan Energi
1. Karbohidrat sebanyak 60% - 70%
Karbohidrat dibutuhkan sebagai sumber energi utama, membuat
cadangan energi di dalam tubuh, dan memberikan rasa kenyang. Bahan
makanan yang mengandung karbohidrat adalah jenis padi-padian dan
masuk ke dalam tubuh disimpan sebagai glikogen di dalam hati atau
jaringan otot dan dipakai kembali saat tubuh memerlukan.
2. Lemak sebanyak 15% - 20%
Lemak merupakan sumber energi berkonsentrasi tinggi. Setiap 1
gram lemak menghasilkan 9 kalori. Selain itu, fungsi lemak adalah:
a. Sumber asam lemak esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan
kesehatan kulit
b. Zat pelarut vitamin A, D, E, K sehingga dapat diserap dalam usus halus
c. Menambah kelezatan makanan
d. Menurunkan volume makanan akibat kandungan energi yang tinggi
3. Protein sebanyak 10% - 20%
Protein juga dikenal sebagi zat putih telur karena ditemukan
pertama kali dalam putih telur. Selain dapat menyumbangkan tenaga, zat
ini lebih diharapkan berfungsi sebagai sumber zat pembangun. Dalam
keadaan asupan lemak dan karbohidrat kurang, protein dapat digunakan
sebagi zat tenaga. Namun hal ini dapat menyebabkan fungsi protein sebagai
6.2 Kebutuhan Zat Pembangun
Protein merupakan zat gizi yang multifungsi, berikut ini fungsi-fungsi
protein:
1. Zat pembangun, yaitu untuk pertumbuhan, pembentukan darah, enzim dan
hormon, serta mengganti sel-sel jaringan yang rusak akibat aus atau pun
penyakit
2. Zat pengatur, yaitu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh
3. Alat pertahanan tubuh saat diserang penyakit
4. Zat sumber tenaga jika cadangan energi dari karbohidrat dan lemak sudah
habis
Kebutuhan protein pada BALITA sehat dalam sehari sebagai berikut:
- BATITA (1-3 tahun) = 2,5 g per kg BB sehari
- Prasekolah (>3-5 tahun) = 2 g per kg BB sehari
6.3 Kebutuhan Zat Pengatur
1. Air
Air merupakan bahan utama cairan tubuh, terdiri atas 50% - 75% dari
total berat badan dan keberadaannya tergantung dari jumlah lemak di dalam
tubuh (Zeeman (1991)) dikutip dari Uripi (2004). Fungsi air di dalam tubuh
(Dudek (2001) dikutip dari Uripi (2004)).
a. Memelihara bentuk dan fungsi sel
b. Mengatur suhu tubuh
c. Membantu mencerna makanan dan absorbsi zat gizi
e. Melarutkan vitamin, mineral, glukosa, dan asam amino sehingga fungsi
berbagai alat tubuh dapat berjalan
f. Berpartisipasi dalam reaksi biokimia di dalam tubuh, misalnya dalam
pembentukan enzim dan hormon
g. Mengeluarkan zat racun dan zat tidak berguna bagi tubuh, baik melalui
air seni, keringat, pernafasan, maupun feses
Kebutuhan air pada BALITA (Persagi, 1992 dikutip dari Uripi (2004).
a. 1 tahun = 120 - 135 ml per kg BB sehari
b. 2-3 tahun = 115 - 125 ml per kg BB sehari
c. 4-5 tahun = 100 - 110 ml per kg BB sehari
2. Vitamin
a. Vitamin A atau vitamin anti infeksi
Menurut Aven-Hen, 1992 (dikutip dari Uripi, 2004) vitamin A
terutama berperan untuk kesehatan mata, kulit, dan selaput lendir, serta
paru-paru. Di dalam tubuh, vitamin A merupakan bahan utama
pembuatan rhodopsin. Vitamin A juga berperan dalam menjaga
keutuhan kulit dan selaput lendir termasuk selaput lendir mata agar
tetap lembab dan basah. Kekurangan vitamin A menyebabkan
gangguan mata, mulai dari buta senja sampai kebutaan. Selain itu dapat
menyebabkan kekeringan pada selaput lendir sehingga mudah terjangkit
penyakit infeksi. Selain itu kekurangan vitamin A juga dapat
Menurut Beck, 2000 (dikutip dari Uripi, 2004) biasanya kecukupan
vitamin A diukur dengan IU (International Unit) dan provitamin A
dengan mg (miligram). Satu mcg (mikrogram) ekuivalen vitamin A
sama dengan 3,33 IU vitamin A atau 6 mcg provitamin A. Berikut
kecukupan vitamin A yang dianjurkan:
- BATITA (1-3 tahun) = 1.500 IU vitamin A atau 2.700 mcg =
2,70 mg provitamin A
- Prasekolah (>3-5 tahun) = 1.88 IU vitamin A atau 3.240 mcg =
3,24 mg provitamin A
b. Vitamin D atau kalsiferol
Peran utama vitamin D, yaitu membantu metabolisme zat kapur
atau kalsium pembentuk tulang. Selain berperan dalam proses
kalsifikasi, vitamin ini mengatur keseimbangan mineral dalam tubuh
melalui pengaruhnya terhadap hormon paratiroid.
Aven-Hen, 1992 (dikutip dari Uripi, 2004) menyebut vitamin D
sebagai the sunshine vitamin. Hal ini sepenuhnya benar karena di dalam
tubuh tepatnya di kulit, vitamin ini dibentuk dari berbagai sterol yang
berasal dari bahan makanan nabati maupun hewani (provitamin D)
dengan bantuan sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet.
Menurut National Research Council, 1989 (dikutip dari Uripi,
2004) sangat sulit menentukan kebutuhan vitamin D pada setiap orang
Indonesia sebagai daerah tropis dengan matahari bersinar sepanjang
tahun, kekurangan vitamin D jarang ditemukan.
c. Vitamin E
Vitamin E merupakan salah satu vitamin yang bersifat antioksidan
selain vitamin A, C, dan mineral selenium. Menurut Aven-Hen, 1992
(dikutip dari Uripi, 2004) selain diperlukan dalam proses reproduksi,
vitamin E berperan dalam sirkulasi darah dan melindungi anak dari
gangguan jantung di kemudian hari. Vitamin ini juga berperan dalam
kesehatan kulit, mempercepat penyembuhan luka bakar, dan
mengurangi terjadinya jaringan parut.
Menurut National Research Council, 1989 (dikutip dari Uripi, 2004)
kebutuhan vitamin E pada anak meningkat sesuai dengan pertambahan
berat badan, tetapi tidak secepat pada tahun-tahun pertama kehidupan.
Berikut ini kecukupan vitamin E yang dianjurkan.
- 1-3 tahun dengan berat 13 kg = 6 mg per hari
- 7-10 tahun dengan berat 28 kg = 7 mg per hari
d. Vitamin K
Vitamin K dikenal sebagai vitamin anti perdarahan karena perannya
dalam pembekuan darah jika luka. Menurut National Research Council
(1989) (dikutip dari Uripi, 2004), vitamin ini berperan dalam
pembentukan berbagai zat yang berfungsi sebagai faktor-faktor dalam
pembekuan darah, misalnya protrombin. Dalam keadaan kekurangan
sehingga mudah terjadi perdarahan. Dalam keadaan sehat, saat saluran
cerna sudah berkembang, kebutuhan vitamin K dapat terpenuhi dari
produksi di dalam usus dan makanan. Kebutuhan ini akan meningkat
pada keadaan luka dan berbagai infeksi virus yang menyebabkan
perdarahan, misalnya demam berdarah.
e. Vitamin B Kompleks
Aven-Hen, 1992 (dikutip dari Uripi, 2004) menyebut vitamin B
kompleks dengan the nerve vitamin karena pada dasarnya vitamin yang
termasuk dalam kelompok ini berperan dalam kesehatan saraf walaupun
secara spesifik masing-masing mempunyai peran berbeda. Berikut ini
delapan vitamin yang masuk golongan vitamin B kompleks.
1. Thiamin (B1)
Utamanya, vitamin ini berperan dalam merangsang nafsu makan
selain memacu pertumbuhan dan kesehatan saraf.
2. Riboflavin (B2)
Utamanya, vitamin ini berperan dalam kesehatan kulit dan mata,
pembentukan sel darah merah dan antibodi, serta membantu
penyembuhan sariawan pada anak.
3. Niasin (B3)
Utamanya, vitamin ini berperan dalam fungsi otak dan peredaran
4. Asam Pantotenat (B5)
Vitamin ini berfungsi dalam pembentukan tenaga dan merangsang
pertumbuhan. Vitamin ini sangat diperlukan oleh anak yang
mendapat pengobatan dengan antibiotik dalam waktu lama. Vitamin
B5 mengurangi racun yang ditimbulkan oleh obat tersebut.
5. Piridoksin (B6)
Selain berperan dalam pencernaan makanan, vitamin B6 merupakan
zat esensial dalam pembentukan antibodi dan sel-sel darah merah.
Vitamin ini dapat mencegah mabuk perjalanan yang sering dialami
oleh anak-anak.
6. Asam folat
Vitamin ini melindungi anak dari serangan cacing atau parasit yang
terdapat dalam saluran pencernaan. Asam folat berperan dalam
pembentukan butir-butir darah merah dan pertumbuhan.
7. Siano-kobalamin (B12)
Bersama asam folat, vitamin B12 berperan dalam pembentukan
butir-butir darah merah dan memacu pertumbuhan. Vitamin ini juga
merangsang nafsu makan dan penting untuk kesehatan saraf.
8. Biotin
Biotin merupakan vitamin yang berperan dalam pertumbuhan.
Menurut, vitamin dapat mencegah penyakit eksem (bintik merah
Berikut ini kecukupan vitamin B yang dianjurkan dalam sehari pada
BALITA (National Research Council (1989) dikutip dari Uripi (2004)).
- Thiamin (B1) = 0,3 mg/1000 kkal (kilo kalori)
- Riboflavin (B2) = 0,6 mg/ 1000 kkal
- Niasin (B3) = 6,6 NE/ 1000 kkal (8 mg)
- Asam pantotenat (B5) = 3-4 mg
- Piridoksin (B6) = 0,02 mg/ mg protein
- Asam folat = sekitar 3 mcg per kg BB
- Siano-kobalamin (B12) = 0,05 mcg/ kg BB maksimum 2 mcg
- Biotin = 15-30 mcg
f. Vitamin C atau asam askorbat
Vitamin C juga merupakan salah satu vitamin yang berperan
sebagai antioksidan, yaitu melindungi anak-anak dari berbagai
pencemaran lingkungan. Vitamin ini berperan sebagai antibiotik dan
dalam proses penyembuhan luka.
Beck, 2000 (dikutip dari Uripi, 2004) berpendapat, fungsi vitamin C
adalah membentuk jaringan ikat yang memegang peranan utama dalam
penyembuhan luka. Selain itu vitamin ini juga berperan dalam
kesehatan gigi, gusi dan tulang. Kecukupan vitamin C yang dianjurkan
3. Mineral
Mineral yaitu zat kimia anorganik yang terdapat di alam. Mineral
berguna agar organ dan jaringan tubuh berfungsi efisien. Mineral yang
penting bagi pertumbuhan anak, antara lain kalsium, besi, iodium, fluor,
dan fosfor.
1. Kalsium (zat kapur)
Utamanya, mineral ini berperan dalam pertumbuhan dan kesehatan tulang
serta gigi. Di samping itu, kalsium berperan dalam proses pembekuan darah
jika luka dan pengaturan denyut jantung. Menurut Widya Karya Pangan
dan Gizi, 1983 (dikutip dari Uripi, 2004) kecukupan kalsium yang
dianjurkan untuk BALITA adalah 0,5 mg sehari.
2. Fosfor
Fosfor merupakan mineral yang berfungsi dalam pertumbuhan tulang dan
gigi bersama dengan kalsium dan vitamin D. Mineral ini juga berperan
dalam pertumbuhan dan perbaikan sel-sel jaringan tubuh serta aktivitas otot
dan saraf. Fosfor memegang peranan penting dalam pembentukan energi
dan karbohidrat. Kebutuhan fosfor secara tepat belum dapat dipastikan,
tetapi National Research Council, 1989 (dikutip dari Uripi, 2004)
menetapkan kecukupan fosfor anak usia 1-10 tahun adalah 800 mg sehari.
3. Zat besi (ferum)
Zat besi merupakan zat yang esensial untuk pembentukan hemoglobin yang
Gizi, 1983 (dikutip dari Uripi, 2004) kecukupan zat besi yang dianjurkan
untuk anak BALITA adalah 10 mg sehari.
4. Iodium
Iodium merupakan mineral utama untuk pembentukan hormon tiroksin,
yaitu hormon yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh serta unsur
penting bagi perkembangan fisik dan mental.
5. Fluor
Utamanya, mineral ini berperan dalam pembentukan gigi, pencegahan
karies (lubang gigi) (Uripi, 2004).
7. Masalah Gizi Pada BALITA
Masalah gizi adalah gangguan dari beberapa segi kesejahteraan perorangan
atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan zat gizi
yang diperoleh dari makanan (Uripi, 2004).
Penyakit-penyakit gizi di Indonesia terutama tergolong ke dalam kelompok
penyakit defisiensi. Penyakit gizi lebih (over nutrition) dan keracunan pangan
(food intoxication) belum dianggap telah mencapai tingkat bahaya nasional. Empat
penyakit defisiensi gizi yang dianggap sudah mencapai kegawatan nasional karena
kerugian yang ditimbulkannya terhadap pembangunan manusia secara nasional
adalah: 1) penyakit kekurangan kalori protein (KKP), 2) penyakit defisiensi
vitamin A, 3) penyakit defisiensi iodium dan 4) penyakit anemia defisiensi zat besi
1) Penyakit Defisiensi Kalori dan Protein (KKP)
a. Penggolongan KKP
Salah satu gejala dari penderita KKP ialah hepatomegali yang terlihat oleh
ibu-ibu sebagai pembuncitan perut. Ada berbagai variasi bentuk KKP yaitu
penyakit kwashiorkor, marasmus, dan marasmikkwashiorkor. Kwashiorkor
adalah penyakit KKP dengan kekurangan protein sebagai penyebab dominan.
Marasmus merupakan gambaran KKP dengan defisiensi energi yang ekstrem.
Marasmikkwashiorkor merupakan kombinasi defisiensi kalori dan protein pada
berbagai variasi.
Penyebab secara langsung dari KKP (KKP primer) adalah konsumsi kurang
dan sebab tak langsungnya (KKP sekunder) adalah hambatan absorbsi dan
hambatan utilisasi (penggunaan) zat gizi karena berbagai hal, misalnya karena
penyakit.
Penggunaan kombinasi berat badan dan tinggi badan terhadap umur
diusulkan oleh Waterlow:
Tabel 2.2 Klasifikasi KEP menurut BB dan TB
Kategori KEP BB/U TB/U BB/TB
Normal (0) 90 95 90
Ringan (I) 80-89 91-94 81-90
Sedang (II) 70-79 85-90 71-80
b. Upaya penanganan kurang energi protein
Pada dasarnya, perawatan penderita kurang energi protein ditujukan dalam
dua hal. Pertama, adalah untuk memulihkan keadaan gizinya dengan cara
mengobati penyakit penyerta dan memenuhi kebutuhan gizinya. Kedua, adalah
mencegah kekambuhan. Untuk pemulihan taraf gizi diperlukan makanan yang
mengandung energi lebih tinggi dari yang dikonsumsi setiap hari. Setelah
mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan, maka usaha berikutnya adalah
mencegah kekambuhan, mempertahankan taraf gizi yang sudah dicapai dan
bila mungkin ditingkatkan.
2) Penyakit Defisiensi Vitamin A
a. Penggolongan defisiensi vitamin A
Gambaran defisiensi vitamin A yang menyangkut kondisi mata, disebut
Xerophthalmia. Konsumsi vitamin A yang kurang adalah karena kebiasaan
makan yang salah, tidak suka sayur dan buah, atau karena daya beli yang
rendah, tidak sanggup membeli bahan makanan hewani maupun nabati yang
kaya akan vitamin A dan karoten tersebut. Sebagian besar kasus defisiensi
vitamin A di Indonesia menyangkut anak BALITA, karena konsumsi kurang
dan hambatan absorbsi.
b. Usaha penanggulangan kekurangan vitamin A
Upaya yang paling tepat untuk meningkatkan taraf gizi vitamin A suatu
masyarakat adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan secara
keseluruhan sehingga diperoleh vitamin A dan zat gizi lain yang diperlukan.
yaitu melalui pemberian makan berupa sumber-sumber vitamin A dan karoten
dari hewani maupun nabati.
3) Penyakit Defisiensi Iodium
Salah satu manifestasi gambaran penyakit kekurangan zat gizi iodium yang
menonjol adalah pembesaran kelenjar gondok (struma simplex). Sudah menjadi
konsensus di antara para ahli bahwa manifestasi defisiensi iodium terjadi karena
kekurangan hormon Thyroxin, yang dihasilkan oleh kelenjar thyroid.
a. Hubungan defisiensi iodium dengan gondok endemik
Iodium merupakan komponen struktural dari hormon Thyroxin yang
dihasilkan oleh kelenjar gondok. Pada defisiensi iodium pembentukan hormon
Thyroxin terhambat, sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Maka kelenjar thyroid
berusaha mengadakan kompensasi dengan menambah jaringan kelenjar, sehingga
terjadi hipertrofi kelenjar gondok yang disebut struma simplex, dan karena terjadi
di daerah tertentu secara endemik, disebut juga gondok endemik.
b. Pengaruh hormon thyroxin
Thyroxin berpengaruh kepada banyak fungsi tubuh, dan merupakan hormon
pertumbuhan. Defisiensi Iodium juga mengakibatkan gambaran klinik lain selain
goiter endemik, yang disebut juga Iodeine Deficiency Diseases (IDD).
c. Upaya penanggulangan dan pencegahan gondok endemik
Cara yang telah dilakukan di Indonesia adalah dengan penyuntikan lipiodol
sebagai usaha jangka pendek. Usaha jangka panjang adalah melalui distribusi
4) Anemia Defisiensi Zat Besi (Fe)
a. Pengaruh defisiensi Fe, terutama melalui kondisi gangguan fungsi
hemoglobin. Merupakan alat transportasi yang diperlukan pada banyak
reaksi metabolik tubuh. Defisiensi Fe dapat didiagnosis berdasarkan data
klinik dan data laboratorik yang ditunjang oleh konsumsi pangan.
Gambaran klinik memperlihatkan kondisi anemia.
b. Upaya penanggulangan anemia Fe
Upaya dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama adalah pemberian
suplementasi tablet zat besi. Kedua adalah melalui fortifikasi bahan
makanan dengan zat besi seperti garam dapur, tepung terigu, dan penyedap
masakan. Berikutnya adalah membatasi pembuangan zat besi dari tubuh
yang bersifat patologis. Beberapa jenis penyakit, termasuk penyakit cacing
akan memperbesar pengeluaran zat besi dari tubuh atau menghambat
penyerapan zat besi. Mengatasi penyakit tersebut untuk mencegah
timbulnya anemia (Santoso & Ranti, 2004).
8. Pedoman Umum Gizi Seimbang untuk Keluarga dan Masyarakat
Di dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang, penempatan kelompok bahan
makanan adalah berdasarkan jumlah yang digunakan dalam menu sehari-hari.
Kelompok makanan sebagai sumber energi ditempatkan pada dasar karena paling
banyak dikonsumsi., kelompok bahan makanan sumber zat pengatur di tengah,
sedangkan kelompok bahan makanan sumber protein ditempatkan pada bagian
Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) adalah pedoman dasar tentang
gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di
masyarakat yang baik dan benar. PUGS digambarkan dalam logo berbentuk
kerucut. Dalam logo tersebut, bahan makanan dikelompokkan berdasarkan tiga
fungsi utama zat gizi yaitu:
1) Sumber energi atau tenaga, yaitu padi-padian atau serealia seperti beras,
jagung, dan gandum; sagu; umbi-umbian seperti singkong dan talas; serta
hasil olahannya seperti tepung, mie, roti, makaroni, havermut, dan bihun.
2) Sumber protein, yaitu sumber protein hewani, seperti daging ayam, telur,
susu dan keju; serta sumber nabati saperti kacang-kacangan berupa kacang
kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tolo; serta
hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom.
3) Sumber zat pengatur berupa sayur dan buah. Sayuran diutamakan yang
berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, daun
katuk, kangkung, wortel, dan tomat; serta sayur kacang-kacangan; seperti
kacang panjang, buncis dan kecipir. Buah-buahan diutamakan yang
berwarna kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam, seperti pepaya,
mangga, nenas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk.
Selain bahan makanan yang dikemukakan diatas, menu sehari-hari juga
menggunakan sumber lemak murni, seperti minyak goreng, margarin, mentega,
PUGS menganjurkan agar 60-75% kebutuhan energi diperoleh dari
karbohidrat (terutama karbohidrat kompleks), 10-15% dari protein, dan 10-25%
dari lemak (Almatsier, 2005).
WHO (1990) dan FAO/WHO (1992) dalam Soekirman (2000) mendorong
negara-negara anggotanya untuk mempromosikan pola makan dan pola hidup yang
sehat dengan pedoman gizi seimbang. Kemudian pada tahun 1995 diterbitkan buku
panduan “13 Pesan Dasar Gizi Seimbang”. Adapun ke-13 pesan tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Makanlah makanan yang beraneka ragam setiap hari. Beberapa jenis
makanan kaya akan zat gizi tertentu, sedang jenis makanan yang lain kaya
akan zat gizi yang lainnya. Dengan makan yang beraneka ragam berarti
kekurangan gizi dari suatu makanan dapat diisi oleh zat gizi dari makanan
lain.
2. Makanlah makanan yang mengandung cukup energi. Energi dibutuhkan
pertama-tama untuk memelihara fungsi dasar tubuh yang disebut
metabolisme basal sebesar 60-70% dari kebutuhan energi total. Selain itu
energi juga diperlukan untuk fungsi tubuh lain seperti mencerna, mengolah
dan menyerap makanan dalam alat pencernaan, serta untuk bergerak,
berjalan, bekerja dan beraktivitas lainnya.
Setiap harinya tubuh memerlukan makanan yang memberikan cukup energi
yang sesuai dengan kebutuhan badan. Untuk menjaga kesehatan diperlukan
adanya keseimbangan antara makanan sumber energi yang kita makan
beraktivitas. Apabila masukan energi lebih kecil dari energi yang keluar,
akan terjadi defisit energi dan berat badan menurun, sebaliknya masukan
energi yang lebih besar dari pengeluaran energi, terjadi surplus energi yang
disimpan dalam bentuk lemak, akibatnya berat badan naik.
3. Untuk sumber energi, upayakan agar separuhnya berasal dari makanan
yang mengandung zat karbohidrat komplek. Disarankan agar setidaknya
separuh dari makanan sumber energi mengandung karbohidrat komplek
karena alasan berikut, makanan sumber karbohidrat komplek mengandung
serat yang penting untuk kelancaran proses pembuangan kotoran dari usus
dan mencegah terjadinya penyakit kanker. Selain itu sumber karbohidrat
komplek terutama yang berasal dari sereal juga mengandung protein,
vitamin B dan Vitamin E.
4. Upayakan agar sumber energi dari minyak dan lemak tidak lebih dari
seperempat dari energi total yang anda butuhkan. Selain dari karbohidrat,
energi juga dihasilkan oleh zat lemak. Tetapi zat lemak tidak hanya penting
untuk menghasilkan energi. Ada beberapa fungsi penting lain dari zat
lemak, antara lain memberi rasa dan aroma, memberikan rasa kenyang,
melindungi organ-organ penting, melindungi tubuh dari suhu yang tidak
normal, pembawa vitamin dan zat gizi lain, merupakan bahan baku dinding
sel, dan sebagainya.
Dari susunan kimianya dikenal lemak yang baik dan lemak tidak baik.
Lemak baik terdiri dari asam lemak tidak jenuh, sedang yang tidak baik
tidak lebih dari 25 persen energi total, penting juga memperhatikan jenis
lemak.
5. Gunakan hanya garam beryodium untuk memasak sehari-hari. Kekurangan
yodium mengakibatkan gangguan yang disebut dengan gangguan akibat
kurang yodium atau GAKY. Pada tingkat kekurangan yodium ringan,
GAKY dapat menghambat perkembangan kecerdasan anak. Cara yang
paling sederhana dan murah mencegah kekurangan zat yodium adalah
dengan menggunakan garam beryodium.
6. Makanlah banyak makanan yang kaya akan zat besi. Zat besi terdapat
dalam banyak makanan yang berasal dari hewan seperti daging, hati,
jeroan, kuning telur, ikan, kacang-kacangan dan beberapa jenis sayuran
mengandung banyak zat besi, tetapi pada umumnya kurang dapat diserap
oleh usus. Sumber zat besi dari hewani lebih mudah diserap dan
dimanfaatkan oleh darah.
7. Berikan hanya air susu ibu untuk bayi sampai usia 4 bulan. ASI adalah
satu-satunya makanan yang lengkap mengandung zat gizi yang dibutuhkan
oleh bayi, khususnya sampai usia 4 bulan. Selain mengandung semua zat
yang dibutuhkan pertumbuhan dan perkembangan bayi, ASI juga
mengandung zat kekebalan atau antibodi yang melindungi anak dari infeksi
terutama diare dan ISPA.
8. Biasakan makan pagi setiap hari. Penelitian gizi anak SD di Bogor dan
Jakarta tahun 1998, 90 persen anak SD menjawab “ya” atas pertanyaan