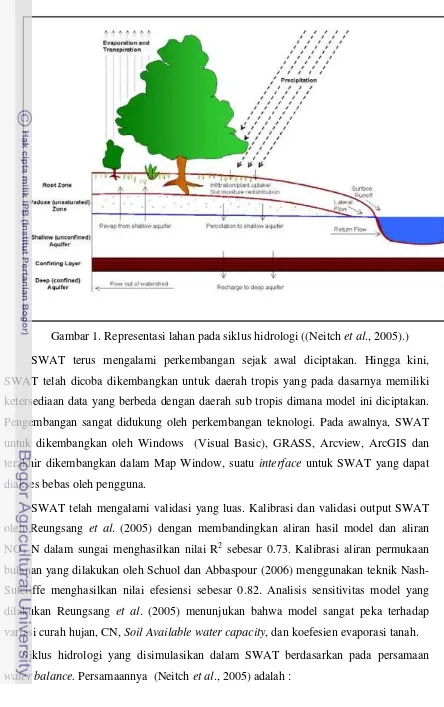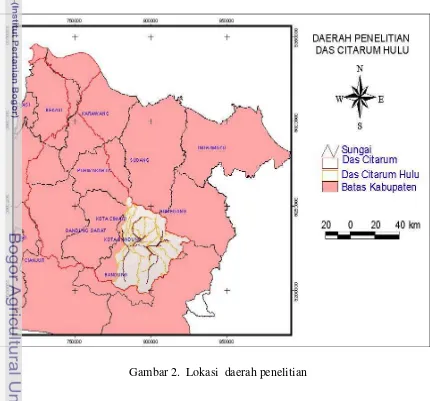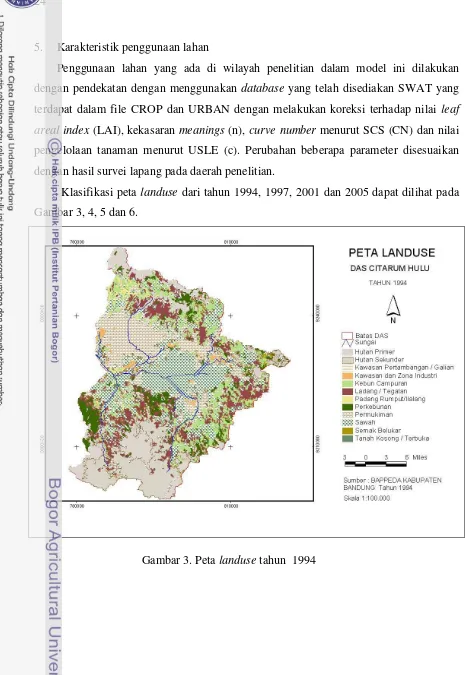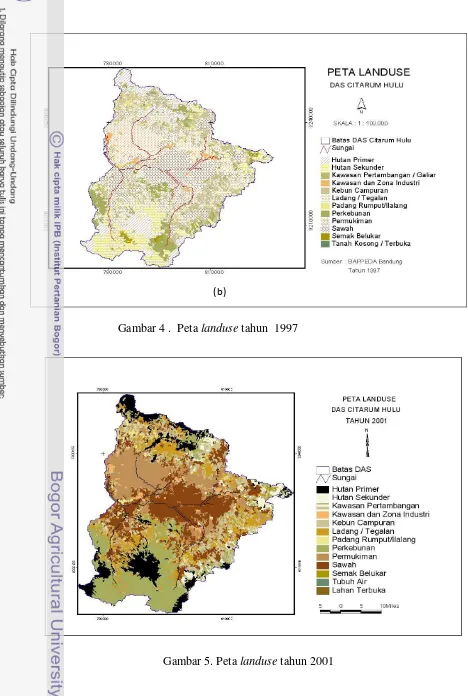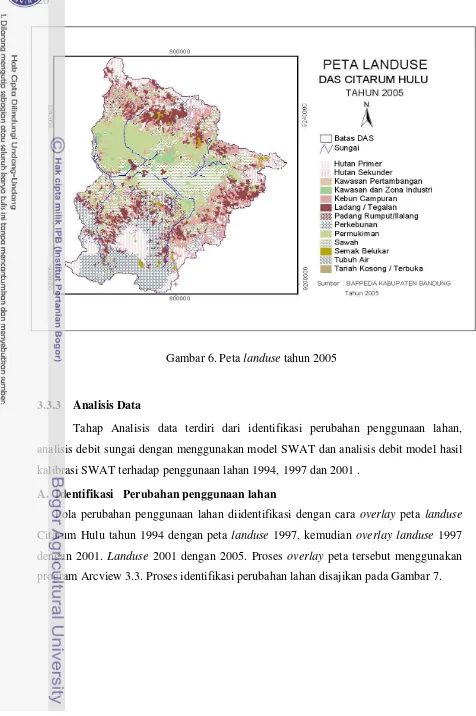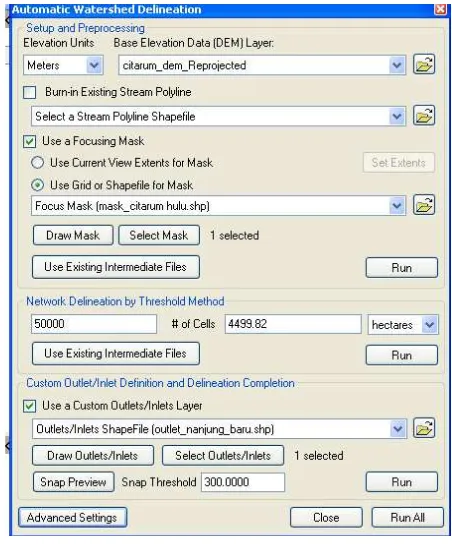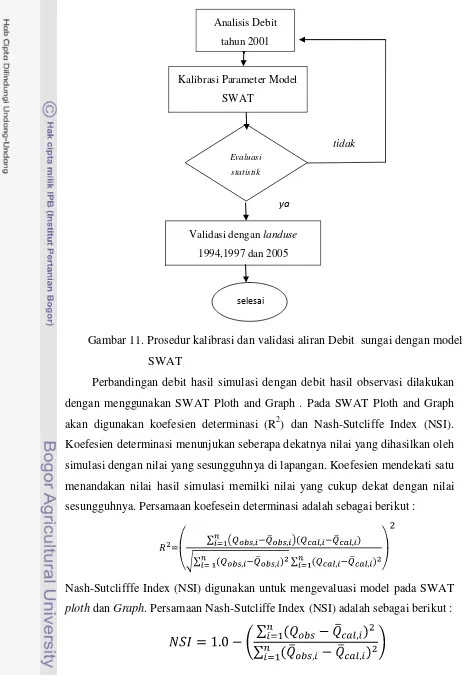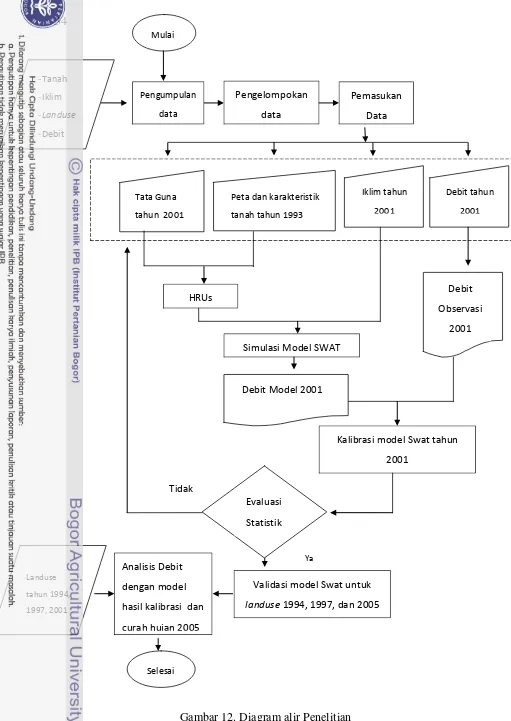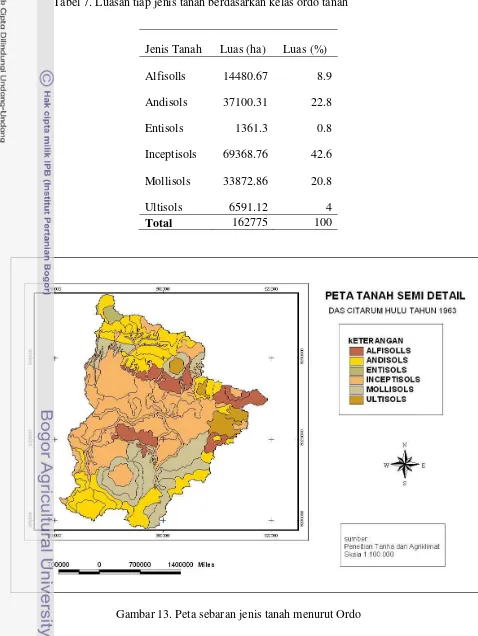PADA BERBAGAI PENGGUNAAN LAHAN
DI DAS CITARUM HULU JAWA BARAT
ADRIONITA
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Analisis Debit Sungai dengan Model MWSWAT pada berbagai penggunaan lahan di DAS Citarum Hulu Jawa Barat” adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Juli 2011
Adrionita NRP. F451090091
Landuse at Upper Citarum Watershed, West Java. Supervised by Nora H. Pandjaitan and Machmud A. Raymadoya.
Observation was conducted at Upper Citarum Watershed, West Java Province in area of 12.000 km2
The highest of landuse change was 1994 to 2005, where the forest had been change to other landuse. The result of calibrated SWAT model showed that the model was quite accurate to predict surface flow at Upper Citarum Watershed with Nash-Sutcliffe efficiency value of 0.714 and R
. The purpose of this study were (1) to identify rate of landuse changes at Upper Citarum Watershed (2) to analyze river discharge by SWAT Model (3) to calibrate SWAT model with landuse 2001 (4) to validate parameters model with landuse of 1994, 1997 and 2005 (5) to analyze river discharge of calibrated SWAT model with land use of 1994, 1997 and 2001.
2
The analysis by calibrated SWAT model was done based on rainfall data in 2005 for landuse 1994, 1997 and 2001. The analysis result on landuse 1994 showed that surface flow was 112.5 mm and discharge rate was 76.7 m
= 0.715. The calibration process was done by adjusting thirteen very sensitive parameters : Surlag ,MSK_Col1, MSK_Col2, MSK_X (.BSN), alpha BF, Shallst, GWQMIN, REVAPMN, GW DELAY (QW File), CHK2 (RTE File), CHNI (SUB File), EPCO (HRU File) and CN2 (.MGT File) .
3
/s.The highest surface flow of 126.6 mm with discharge rate of 77.4 m3/s were obtained from analysis by calibrated SWAT model, landuse 1997 and rainfall in 2005. From analysis by calibrated SWAT model , landuse 2001 and rainfall in 2005 were obtained surface flow of 107.5 mm and discharge rate of 76.8 m3/s
Penggunaan Lahan di DAS Citarum Hulu Jawa Barat. Dibimbing oleh Nora H. Pandjaitan dan Machmud A. Raymadoya.
Peningkatan kebutuhan manusia akan lahan menyebabkan semakin meningkatnya perubahan lahan saat ini. Perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang lebih tinggi, yang sering tidak mengikuti konsep pengelolaan/penggunaan lahan berdasarkan konservasi tanah dan air. Perubahan penggunaan lahan khususnya daerah terbangun mengalami peningkatan yang pesat sehingga beberapa kegiatan akan bergeser ke daerah pinggiran.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi laju perubahan penggunaan lahan pada DAS Citarum Hulu (2) menganalisis debit Sungai Citarum Hulu dengan menggunakan model MWSWAT (3) melakukan kalibrasi model SWAT berdasarkan landuse 2001 (4) melakukan validasi model SWAT hasil kalibrasi untuk landuse 1994, 1997 dan 2005 (5) menganalisis debit sungai model SWAT hasil kalibrasi berdasarkan curah hujan tahun 2005
Penelitian ini dilaksanakan di DAS Citarum hulu dengan luas DAS sebesar 12.000 km2
Pada peta penggunaan lahan yang paling dominan pada tahun 1994 adalah hutan dengan persentase luas hutan terhadap luas DAS sebesar 26.7 % sedangkan penggunaan lahan yang paling dominan pada tahun 1997, 2001 dan 2005 adalah sawah dengan persentase luasan sebesar 23.5 %, 21% dan 19.3%. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada DAS Citarum Hulu selama periode tahun 1994 sampai 2005 didominasi oleh peningkatan lahan perkebunan 51.2% dan
. Peta penggunaan lahan yang digunakan adalah tahun 1994, 1997, 2001 dan 2005 yang diperoleh dari BAPPEDA Bandung. Identifikasi Perubahan penggunaan lahan diketahui dengan cara overlay peta penggunaan lahan DAS Citarum tahun 1994 dengan tahun 1997 kemudian tahun 1997 dengan tahun 2001 serta tahun 2001 dengan tahun 2005, sehingga diperoleh informasi perubahan penggunaan lahan secara spasial dan temporal. Analisis debit aliran menggunakan MWSWAT. Prosedur analisis debit aliran terdiri dari : tahap (1) deliniasi daerah penelitian. Metode yang digunakan adalah metode treshold dan besar kecilnya
treshold menentukan jumlah anak sungai yang terbentuk dan kemudian jaringan sungai tersebut akan menentukan banyaknya Sub DAS yang terbentuk dalam DAS. Tahap (2) adalah pembentukan HRU. Metode yang digunakan adalah
Nilai total debit sungai per tahun yang diperoleh dari prediksi model SWAT pada tahun 1994 sebesar 792.18 m3/dtk, pada tahun 1997, nilai debit model SWAT sebesar 452.97 m3/dtk, tahun 2001 sebesar 884.78 m3/dtk dan tahun 2005 sebesar 668.63 m3
Hasil kalibrasi model SWAT untuk debit bulanan dilakukan pada outlet Nanjung pada tahun 2001 telah memberikan nilai NSI mencapai 0.714 dan R
/dtk .
2
sebesar 0.715 serta diperoleh 13 parameter yang paling sensitif. Validasi dilakukan untuk landuse 1994 menghasilkan nilai NSI sebesar 0.734 dengan nilai R2 sebesar 0.847. Pada landuse 1997 menghasilkan nilai NSI sebesar 0.718 dengan nilai R2 sebesar 0.901 dan pada landuse 2005 diperoleh nilai NSI sebesar 0.678 dengan nilai R2
Berdasarkan model SWAT hasil kalibrasi dan curah hujan tahun 2005 pada landuse tahun 1994 diduga ketebalan aliran permukaan sebesar 112.5 mm sedangkan dengan landuse 1997 dan 2001 diperoleh ketebalan aliran permukaan berturut-turut sebesar 126.6 mm dan 107.5 mm. Laju debit sungai rata-rata per tahun berdasarkan model SWAT dan landuse 1994 diduga sebesar 76.7 m
sebesar 0.712. Hasil Kalibrasi dan validasi nilai NSI menunjukan hasil yang memuaskan.
3
@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2011
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
- pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah
- pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB
PADA BERBAGAI PENGGUNAAN LAHAN
DI DAS CITARUM HULU JAWA BARAT
ADRIONITA
Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nama : Adrionita
NRP : F451090091
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA
Ketua Anggota
Ir. Machmud A. Raimadoya
Mengetahui
Ketua Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr
Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Analisis Debit Sungai dengan Model MWSWAT pada Berbagai Penggunaan Lahan di DAS Citarum Hulu Jawa Barat” dapat diselesaikan.
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA dan Ir. Machmud A. Raimadoya, M.Sc selaku komisi pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat dan motivasi mulai dari awal penelitian hingga selesainya karya tulis ini. Terima kasih juga disampakan kepada Prof. Asep Safei, MS selaku penguji luar komisi yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua dan adikku tercinta atas doa dan kasih sayang yang telah diberikan. Tak lupa diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
Disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan nantinya dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bogor, Agustus 2011
Penulis dilahirkan di Teluk Betung Bandar Lampung pada tanggal 26 Februari 1983 dari Ayah yang bernama Muh.Isa dan Ibu bernama Ellida Ma’ruf. Penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara.
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Karakteristik saluran terbuka untuk menentukan nilai kekasaran Manning
berdasarkan Chow (1959) ... 20
Tabel 2. Konduktivitas hidrolik efektif tanah pada saluran terbuka berdasarkan Lane (1983) ... 20
Tabel 3. File-file input dan fungsinya pada Model SWAT ... 21
Tabel 4. Hydrograph Soil Groups (HSG) ... 23
Tabel 5. Karakteristik tanah untuk input SWAT ... 23
Tabel 6. Jenis, luas, dan persentase lerengan di DAS Citarum Hulu... 35
Tabel 7. Luasan tiap jenis tanah berdasarkan kelas ordo tanah ... 37
Tabel 8. Luas pengunaan lahan DAS Citarum Hulu tahun 1994, 1997, 2001 dan 2005 ... 42
Tabel 9. Perubahan penggunaan lahan dari tahun 1994 sampai 2005 ... 43
Tabel 10. Matrik perubahan landuse tahun 1994-1997 ... 46
Tabel 11. Tabel distribusi perubahan lahan 1997-2001 ... 47
Tabel 12. Matrik perubahan tataguna lahan tahun 2001-2005 ... 49
Tabel 13. Matrik perubahan tataguna lahan tahun 1994-2005 ... 51
Tabel 14. Luas Sub DAS pada DAS Citarum Hulu hasil deliniasi Model ... 52
Tabel 15. Penyesuaian jenis landuse Lokal dengan landuse global (Database SWAT) .. 55
Tabel 16. Jumlah curah hujan tahun 1994, 1997. 2001 dan 2005 pada DAS Citarum Hulu ... 57
Tabel 17. Parameter input yang sensitif pada tahap kalibrasi ... 62
Tabel 18. Perbandingan debit model SWAT dan debit observasi pada tahap validasi (tahun 2001) ... 63
Tabel 19. Perbandingan debit model SWAT dan debit observasi pada tahap validasi (tahun 1994) ... 65
Tabel 20. Perbandingan debit model SWAT dan debit observasi pada tahap validasi (tahun 1997) ... 66
Tabel 21. Perbandingan debit model SWAT dan debit observasi pada tahap validasi (tahun 2005) ... 68
Halaman
Gambar 1. Representasi lahan pada siklus hidrologi ... 14
Gambar 2. Lokasi daerah penelitian ... 17
Gambar 3. Peta landuse tahun 1994 ... 24
Gambar 4 .Peta landuse tahun 1997 ... 25
Gambar 5. Peta landuse tahun 2001 ... 25
Gambar 6. Peta landuse tahun 2005 ... 26
Gambar 7. Proses identifikasi perubahan lahan ... 27
Gambar 8. Kotak dialog watershed delineation ... 28
Gambar 9. Kotak dialog pembentukan HRUs ... 29
Gambar 10. Kotak dialog penggabungan HRUs dan iklim ... 29
Gambar 11. Prosedur kalibrasi dan validasi aliran Debit sungai ... 32
Gambar 12. Diagram alir Penelitian ... 34
Gambar 13. Peta sebaran Jenis tanah menurut Ordo ... 37
Gambar 14 .Rata-rata Curah hujan bulan dari tahun 2004-2008 ... 38
Gambar 15. Sebaran stasiun penakar hujan DAS Citarum Hulu ... 39
Gambar 16 .Debit aliran sungai rata-rata bulanan (2004-2008) ... 40
Gambar 17. Komposisi kelas Penggunaan Lahan pada DAS Citarum Hulu ... 42
Gambar 18. Perubahan Penggunaan Lahan tahun 1994-1997 ... 44
Gambar 19. Perubahan Penggunaan Lahan tahun 1997-2001 ... 45
Gambar 20. Perubahan tataguna lahan 2001-2005 ... 48
Gambar 21. Perubahan tataguna lahan 1994-2005 ... 50
Gambar 22 .Hasil deliniasi DAS Citarum Hulu dengan model MW SWAT ... 53
Gambar 23. Hasil output simulasi SWAT 2001 ... 56
Gambar 24. Debit model dan debit observasi bulanan sebelum dikalibrasi di outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 58
Gambar 25. Debit model dan debit observasi bulanan sebelum dikalibrasi di outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 58
Gambar 26. Debit model dan debit observasi bulanan sebelum dikalibrasi di outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 59
Gambar 28. Perbandingan antara curah hujan dengan debit model SWAT
dan debit observasi Pada Outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 64 Gambar 29. Perbandingan antara curah hujan dengan debit model SWAT
dan debit observasi Pada Outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 65 Gambar 30. Perbandingan antara curah hujan dengan debit model SWAT
dan debit observasi Pada Outlet Nanjung (Sub DAS 23) ... 67 Gambar 31. Perbandingan antara curah hujan dengan debit model SWAT
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. File Input Daftar Stasiun Iklim ... 77 Lampiran 2. File Input weather generator... 78 Lampiran 3. Hasil analisis aliran dengan model SWAT
untuk penggunaan lahan tahun 1994 ... 79 Lampiran 4. Hasil analisis aliran dengan model SWAT
untuk penggunaan lahan tahun 1997 ... 80 Lampiran 5. Hasil analisis aliran dengan model SWAT
untuk penggunaan lahan tahun 2001 ... 81 Lampiran 6. Karakteristik fisik tanah untuk DAS Citarum Hulu ... 82 Lampiran 7. Jenis tanah pada DAS Citarum Hulu berdasarkan klasifikasi USDA
Lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting dalam kehidupan
manusia karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (vink 1975).
Penggunaan lahan oleh manusia berhubungan dengan kegiatan konsumsi (perumahan
dan rekreasi) dan kegiatan produksi (pertanian). Kebutuhan manusia akan terus
meningkat karena jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun
(Hardjowigeno & Widiatmaka 2007; Sitorus 2004a).
Peningkatan kebutuhan manusia akan lahan menyebabkan semakin terbatasnya
ketersediaan lahan saat ini (Hardjowigeno & Widiatmaka 2007). Keterbatasan tersebut
menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang lebih
tinggi, yang sering tidak mengikuti konsep pengelolaan/penggunaan lahan berdasarkan
konservasi tanah dan air. Perubahan penggunaan lahan khususnya daerah terbangun
mengalami peningkatan yang pesat sehingga beberapa kegiatan akan bergeser ke daerah
pinggiran (Rosnila 2005). Dengan demikian maka terjadilah pergeseran fungsi kawasan
pinggiran, yang tadinya kawasan hutan merupakan daerah resapan air dan pertanian
berubah fungsi menjadi kawasan perumahan, industri dan kegiatan non pertanian
lainnya yang mempengaruhi kondisi tata air.
Hutan di DAS Citarum tinggal 9% dari luas wilayah DAS (Puslitbang dan Jasa
Tirta II 2003) sehingga menyebabkan aliran permukaan, sedimentasi dan pencucian
hara sangat tinggi. Dengan semakin berkurangnya daerah resapan air dapat
menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bencana banjir terjadi hampir setiap
tahun. Pada tahun 2008, 2009, dan 2011 bencana banjir terjadi di beberapa kecamatan di
Kabupaten Bandung (Baleendah, Cieanteung dan Andir) dengan ketinggian muka air
mencapai 3 m.
Alih fungsi lahan yang terjadi di DAS Citarum telah menyebabkan perubahan
karakteristik hidrologi dan apabila tidak dilakukan perbaikan maka akan mengakibatkan
hilangnya sumber air yang pontensial di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu
adanya suatu pengelolaan DAS yang baik yang dapat menjamin terjaganya distribusi air
Pengelolaan DAS yang baik adalah pengelolaan yang memperhatikan berbagai
aspek yang terkait di dalamnya baik aspek sosial, ekonomi maupun fisik. Dari aspek
fisik, perlu adanya pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan sehingga dapat
mengontrol perubahan aliran air dan meminimalkan kerusakan tanah (Pawitan, 2006).
Model hidrologi dapat digunakan untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan
terhadap karakteristik hidrologi. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model
SWAT (Soil and Water Assesment Tools). SWAT merupakan dasar kelanjutan dari
model hidrologi dikembangkan untuk memprediksi pengaruh manajemen lahan pada
air, sedimen, dan lahan kimia pertanian yang masuk ke sungai atau badan air pada suatu
DAS yang kompleks dengan tanah, penggunaan tanah dan pengelolaannya
bermacam-macam sepanjang waktu yang lama (Neitsch et al. 2005).
1.2 Perumusan Masalah
Daerah aliran Sungai Citarum wilayah Jawa Barat membentang dari wilayah hulu
Gunung Wayan, Kabupaten Bandung hingga Laut Jawa di Kabupaten Karawang. DAS
Citarum terbagi menjadi tiga bagian yaitu hulu, tengah, dan hilir. Di DAS ini terdapat
tiga waduk besar yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. Tiga
waduk ini mempunyai peran vital yaitu menyuplai air untuk kebutuhan air minum,
perikanan, pertanian dan pembangkit listrik dimana kualitas air yang disuplai tergantung
dari bagian hulu dan tengah DAS.
Kondisi DAS Citarum secara umum mengalami kerusakan cukup parah. Selain
pencemaran yang diakibatkan aktivitas warga dan pabrik-pabrik di sekitar DAS,
kerusakan juga disebabkan rusaknya hutan di sekitar DAS yang menjadi tangkapan air
sehingga menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau yang
pada akhirnya akan mempengaruhi kelestarian sungai citarum.
Adanya perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi daerah pertanian, atau
daerah resapan air bersih beralih fungsi menjadi pemukiman, akan mempengaruhi aliran
pemukaan, sedimentasi dan hara yang terbawa bersama aliran permukaan. Limpasan
permukaan di wilayah DAS Citarum bagian Hulu ini tergolong tinggi yaitu sekitar
58.3% dari nilai curah hujan yang terjadi. Selain itu, terdapat sekitar 61.7 % wilayah
yang mepunyai limpasan permukaan hampir sama dengan nilai curah hujannya. Hal ini
hanya mampu menginfiltrasikan air hujan sebesar 11.3%. Limpasan permukaan yang
tinggi tersebut lebih banyak disebabkan oleh pemanfaatan lahan sebagai lahan
terbangun, sawah dan tegal sayur.
Pengurangan daerah resapan air sebagai dampak perubahan fungsi lahan yang
pada daerah hulu DAS Citarum dapat menimbulkan dampak pada bagian DAS Citarum
lainnya baik bagian tengah maupun bagian hilir. Semakin berkurangnya lahan hijau
sebagai daerah resapan air maka akan meningkatkan jumlah air yang tidak terserap
tanah dan mengalir dipermukaan. Dampak pengurangan jumlah air yang terserap tanah
ini salah satunya dapat terlihat dengan jelas adanya perubahan debit aliran sungai
(runoff).
Berkaitan dengan masalah-masalah diatas, maka diharapkan pendugaan debit
sungai dengan menggunakan model MWSWT ini dapat dijadikan dasar dalam
perencanaan pengelolaan DAS Citarum Hulu.
1.3 Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi laju perubahan penggunaan lahan pada DAS Citarum Hulu
2. Menganalisis debit Sungai Citarum Hulu dengan menggunakan model
MWSWAT
3. Melakukan kalibrasi model SWAT berdasarkan landuse 2001
4. Melakukan validasi model SWAT hasil kalibrasi untuk landuse 1994, 1997 dan
2005
5. Menganalisis debit sungai model SWAT hasil kalibrasi berdasarkan curah hujan
2.1 Daerah Aliran Sungai
Sebagai suatu sistem, DAS dapat dipandang dari dua arah yakni satu sistem
hidrologi dan satu ekosistem alami. Sebagai satu sistem hidrologi, DAS merupakan
suatu kawasan yang dialiri oleh sebuah sistem sungai yang saling berhubungan sehingga
aliran-aliran yang berasal dari kawasan tersebut keluar melalui satu aliran tunggal.
Secara operasional, DAS didefinisikan sebagai wilayah yang terletak diatas suatu titik
pada suatu sungai yang dibatasi oleh batas topografi mengalirkan air yang jatuh
diatasnya ke dalam sungai yang sama melalui titik yang sama pada sungai tersebut
(Arsyad, 1985).
Daerah hulu sungai merupakan bagian penting karena memiliki fungsi
perlindungan terhadap seluruh DAS (Asdak, 2004). Adanya fungsi perlindungan
tersebut menunjukan adanya keterkaitan antara hulu dan hilir suatu DAS yang berarti
bahwa kegiatan yang dilakukan di hulu selain memberikan dampak terhadap keadaaan
di hilir (Sudadi et al. 1991). Aktivitas perubahan lanskap termasuk perubahan tata guna
lahan atau pembuatan bangunan konservasi di daerah hulu akan menimbulkan dampak
di daerah hilir berupa perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta material
terlarut dalam sistem aliran air lainnya (Asdak, 2004). Selain itu kegiatan pertanian/
bercocok tanaman yang tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi pun dapat
meningkatkan erosi yang pada akhirnya akan menurunkan kaidah produktivitas lahan
pertanian (Arsyad, 2006).
Daerah Aliran Sungai merupakan sistem hidrologi yang terdiri dari masukan
(input), proses, dan keluaran (output) (Asdak, 2004). DAS merespon curah hujan yang
jatuh di atasnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya
evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, aliran permukaan, kandungan air tanah dan aliran
sungai. Setiap masukan DAS dapat dievaluasi proses yang telah dan sedang terjadi
dengan cara melihat atau mengetahui keluaran dari sistem tersebut. Curah hujan sebagai
input akan berinteraksi dengan komponen-komponen DAS sehingga akan menghasilkan
keluaran berupa debit, muatan sedimen dan material lainnya yang terangkut oleh aliran
sungai.
Pengaruh daerah aliran sungai terhadap aliran permukaan dapat dilihat melalui
elevasi/kemiringan dan susunan anak-anak sungai/kerapatan drainase (Asdak 2004).
Semakin besar ukuran DAS, semakin besar aliran permukaan. Tetapi laju maupun
volume aliran permukaan per satuan wilayah dalam DAS menurun apabila luas daerah
tangkapan bertambah besar. Semakin besar kemiringan lereng suatu DAS, semakin
cepat laju aliran permukaan, dengan demikian mempercepat respon DAS tersebut oleh
adanya curah hujan. Bentuk DAS yang memanjang dan sempit cenderung menurunkan
laju aliran permukaan dari pada DAS berbentuk melebar walaupun luas keseluruhan
dari dua DAS tersebut sama. Kerapatan drainase merupakan jumlah dari semua saluran
sungai (km) dibagi luas DAS (km2
Sistem hidrologi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dapat dipengaruhi
oleh manusia maupun yang tidak dapat dipengaruhi oleh manusia. Diantara faktor yang
dapat dipengaruhi oleh manusia yaitu tata guna lahan dan panjang lereng (pembuatan
teras). Oleh karena itu, dalam perencanaan pengelolaan DAS diperlukan kegiatan yang
salah satu fokusnya ditujukan pada perubahan tata guna lahan serta pengaturan panjang
lereng (Asdak 2004).
). Semakin tinggi kerapatan daerah aliran, semakin
besar kecepatan aliran permukaan untuk curah hujan yang sama.
Pengelolaan DAS merupakan usaha untuk menggunakan semua sumberdaya
(tanah, vegetasi, air dan sebagainya) pada DAS tersebut secara rasional untuk
mendapatkan penggunaan lahan yang berkelanjutan demi tercapainya produksi
maksimum atau optimum dalam waktu yang tidak terbatas dan untuk menekan bahaya
kerusakan seminim mungkin sehingga didapat hasil air dalam jumlah, kualitas dan
distribusi yang baik (Sinukaban, 2007a). Pengelolaan suatu DAS dikatakan berhasil
apabila terpenuhi beberapa hal berikut yaitu : (1) tercapainya kondisi hidrologis yang
optimal, (2) meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan
kesejahteraan masyarakat, (3) terbentuknya kelembagaan masyarakat yang muncul dari
bawah sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat dan (4) terwujudnya
2.2. Daur Hidrologi
Perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah
dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti, air tersebut akan tertahan
(sementara) di sungai, danau/waduk dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh
manusia atau mahluk hidup lainnya.
Energi panas matahari dari faktor-faktor iklim lainnya menyebabkan terjadinya
proses evaporasi pada permukaan vegetasi dan tanah, di laut atau badan-badan air
lainnya. Uap air sebagai hasil proses evaporasi akan terbawa oleh angin melintasi
daratan yang bergunung maupun datar, dan apabila keadaan atmosfer memungkinkan
sebagian dari uap air tersebut akan terkondensasi dan turun sebagai air hujan. Air hujan
mencapai permukaan tanah sebagian masuk ke dalam tanah (infiltration). Sedangkan air
yang tidak terserap ke dalam tanah akan tertampung sementara dalam
cekungan-cekungan permukaan tanah (suface detention) untuk kemudian mengalir di atas
permukaan tanah ke tempat yang lebih rendah (runoff), untuk selanjutnya masuk ke
sungai. Air infiltrasi dan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya
akan membentuk kelembaban tanah. Apabila tingkat kelembaban air tanah telah cukup
jenuh maka air hujan yang baru masuk ke dalam tanah akan bergerak secara lateral
(horizontal) untuk selanjutnya pada tempat tertentu akan keluar ke permukaan tanah
(subsurface flow) dan akhirnya mengalir ke sungai (Asdak, 2004)
Aliran permukaan terdiri dari dua jenis yaitu stream flow untuk aliran air yang
berada dalam sungai atau saluran dan surface run off (overland flow) untuk aliran yang
mengalir diatas permukaan tanah (Arsyad, 2006).
Akibat panas matahari air di permukaan bumi akan berubah wujudnya menjadi
gas/uap dalam bentuk evaporasi dan bila melalui tanaman disebut transpirasi. Proses
pengambilan air oleh akar tanaman kemudian terjadinya penguapan dari dalam tanah
disebut sebagai evapotranspirasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya runoff antara lain :
1. Besar presipitasi.
2. Besar evapotranspirasi.
a. Ukuran dan bentuk DAS.
Daerah aliran sungai (DAS) adalah wilayah yang dibatasi oleh punggung
bukit atau percabangan saluran yang mengalirkan air dari beberapa titik di wilayah
bagian atas DAS (upstream) menuju titik outlet (Cech, 2005). DAS sering disebut
juga watershed, catchment area, atau river basin (Sinukaban, 2007). Semakin besar luas DAS, akan semakin besar nilai runoff. Bentuk DAS yang cendrung bulat akan
menghasilkan aliran runoff yang tinggi karena runoff dari berbagai titik tersebut akan
mencapai outlet pada waktu yang hampir sama. Sedangkan pada DAS yang berbentuk lebih memanjang, runoff pada bagian downstream akan keluar dari outlet
terlebih dahulu yang kemudian disusul runoff dari upstream.
b. Topografi.
Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang
datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Kemiringan lahan
sangat erat hubungannya dengan besarnya erosi. Semakin besar kemiringan lereng,
peresapan air hujan ke dalam tanah menjadi lebih kecil sehingga limpasan
permukaan dan erosi menjadi lebih besar. Kecuraman suatu lereng dapat
dikelompokan juga sebagai berikut :
1. A = 0 sampai < 3% (datar)
2. B=> 3% sampai 8% (landai atau berombak)
3. C => 8 % sampai 15% (agak miring atau bergelombang)
4. D=>15% sampai 30%
5. E=> 30% sampai 45% (Agak curam atau bergunung)
6. F => 45% sampai 65% (curam)
7. G=> 65% (sangat curam) (Arsyad, 2006)
c. Jenis tanah dan penggunaan lahan.
Tanah merupakan bahan hasil pelapukan batuan. Karakteristik tanah dan sebaran
jenisnya dalam DAS sangat menentukan besarnya infiltrasi limpasan permukaan
(overland flow) dan aliran bawah permukaan (sub surface flow). Karakteristik tanah
yang penting untuk diketahui antara lain berat isi, tekstur, kedalaman dan pelapisan
tanah (horison) (Subekti, 2009). Vegetasi penutup lahan memegang peranan penting
dalam proses intersepsi hujan yang jatuh dan transpirasi air yang terabsorpsi oleh
kinetis hujan sehingga memperkecil terjadinya erosi percik (splash erosion),
memperkecil koefisien aliran sehingga mempertinggi penyerapan air hujan
khususnya pada lahan dengan solum tebal (sponge effect) (Subekti, 2009).
Daerah hulu dari suatu DAS berperan sebagai lingkungan pengendali
(conditioning environtment). Sedangkan daerah hilir merupakan daerah penerima
(acceptor) bahan dan energi, atau lingkungan konsumsi atau lingkungan yang
dikendalikan (commanded environtment ). Perubahan yang terjadi pada suatu DAS
dari segi hidrologi mempengaruhi bagian lain dalam DAS tersebut. Penanganan
suatu DAS harus meliputi penanganan sebagai suatu kesatuan sistem bagian DAS
lainnya sehingga perbaikan DAS dapat berjalan efektif (Sinukaban, 2007).
2.3. Perubahan Penggunaan Lahan
Lahan memiliki berbagai fungsi seperti pertumbuhan tanaman pangan dan
pohon-pohonan, perumahan, transportasi, lapangan, bermain, industri dan penggunaan lainnya
yang menunjukan kompleksitas kehidupan modern. Lahan merupakan bagian dari
bentang lahan (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim,
topografi, hidrologi termasuk vegetasi alami yang semuanya akan berpengaruh terhadap
penggunaan lahan (Sitorus, 2004b). Hal tersebut digunakan untuk menentukan tipe
penggunaan lahan yang akan dikembangkan atau diusahakan di suatu wilayah, dilihat
dari kualitas dan karakteristik lahan.
Penggunaan lahan merupakan setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia
baik permanen maupun berupa sebuah siklus dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya baik material maupun spritual dari alam kompleks maupun sumberdaya
buatan secara bersama-sama disebut lahan (Vink, 1975). Penggunaan lahan dapat
digolongkan atas dua golongan yaitu (1) penggunaan lahan pedesaan dalam artian luas
mencakup pertanian, kehutanan, cagar alam/suaka marga dan daerah rekreasi, (2)
penggunaan lahan perkotaan industri yang mencakup kota, perkampungan, kompleks
industri, jalan raya dan daerah pertambangan. Penggolongan yang lain adalah
penggunaan untuk kawasan lindungan, budidaya dan daerah pertambangan
(Hardjowigeno & Widiatmaka, 2007). Pengetahuan akan penggunaan lahan penting
Penggunaan lahan dibatasi oleh beberapa faktor, baik yang dapat dipengaruhi oleh
manusia maupun yang tidak dipengaruhi oleh manusia. Faktor yang tidak dapat
dipengaruhi oleh manusia adalah iklim dan relief. Dua faktor ini yang cenderung stabil
dan tidak responsif terhadap intervensi manusia. Faktor lainnya seperti vegetasi, air dan
tanah merupakan faktor yang responsif terhadap intervensi manusia bahkan terkadang
dapat menyebabkan terjadinya degradasi (Vink, 1975).
Pada awalnya, pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilakukan melalui perluasan
areal yang belum diusahakan. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk terus
meningkat sedangkan lahan tidak meningkat jumlahnya. Oleh karena itu terjadilah
keterbatasan lahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Meningkatnya jumlah
penduduk disertai oleh tuntutan akan peningkatan penyediaan kebutuhan pangan dan
kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan terjadinya kompetisi antara berbagai
kemungkinan penggunaan lahan (Sitorus, 2004a). Untuk mengatasi hal tersebut, maka
diperlukan evaluasi sumberdaya lahan yang dapat menyajikan seperangkat data objektif
yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang perencanaan
sehingga lahan dapat digunakan secara efisien. Dengan demikian, kemungkinan
pengalih lahan pertanian ke lahan non pertanian dapat diusahakan agar masih sesuai
dengan konsep penggunaan lahan yaitu sesuai dengan kemampuan dan daya dukungnya
serta mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah.
Perubahan penggunaan lahan merupakan perubahan penggunaan dari satu sisi
penggunaan ke penggunaan lainnya yang diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan
lahan dari suatu waktu ke waktu berikutnya (Vink, 1975). Perubahan penggunaan lahan
tidak mungkin dihindari karena pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat
menyebabkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan lahan pertanian tidak
seimbang (Asdak, 2004). Dengan demikian menyebabkan pemilikan lahan pertanian
menjadi semakin sempit sehingga mulai merambah hutan dan lahan tidak produktif
lainnya sebagai lahan pertanian.
Menurut Vink (1975), perubahan atau perkembangan penggunaan lahan yang
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami
diantaranya yaitu iklim, relief, tanah atau adanya bencana alam seperti gempa dan
banjir. Faktor manusia mempunyai pengaruh yang dominan dibanding faktor alami
dalam memenuhi kebutuhannya pada sebidang lahan yang spesifik seperti konversi
hutan menjadi areal perkebunan atau konversi lahan sawah menjadi tempat pemukiman.
Perubahan penggunaan lahan akan mengubah karakteristik aliran sungai, jumlah aliran
permukaan, kualitas air dan sifat hidrologi daerah yang bersangkutan (Leopold &
Dunne di dalam Sudadi et al., 1991).
2.4. Pengaruh Perubahan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi
Perubahan penggunaan lahan, dilihat dari aspek hidrologi, berpengaruh langsung
terhadap karakteristik penutupan lahan sehingga akan mempengaruhi sistem tata air
DAS. Fenomena ini ditunjukan oleh karakteristik hidrologi DAS yang dapat dikenali
melalui produksi air, erosi dan sedimen (Seyhan, 1999).
Perubahan penggunaan lahan, dari lahan kawasan hutan yang memiliki penutup
tanah (mulsa) menjadi lahan pertanian maupun pemukiman menyebabkan hilangnya
vegetasi permukaan dan berkurangnya daerah yang dapat meresapkan air. Dengan
demikian, peresapan air ke dalam tanah (infiltrasi) menjadi rendah sehingga simpanan
air bawah tanah berkurang yang dapat menyebabkan terjadinya kekeringan di musim
kemarau (Sinukaban, 2007b).
Disisi lain, hal tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan air di permukaan pada
musim hujan. Harto (2000) juga menyatakan pengaruh perubahan penggunaan lahan
paling besar terjadi distribusi hujan menjadi aliran permukaan yang selanjutnya akan
mengubah aliran sungai.
Menurut Asdak (2004), perubahan sifat aliran sungai adalah peningkatan
koefisien aliran permukaan yaitu terjadinya peningkatan jumlah air hujan yang menjadi
aliran permukaan sehingga meningkatkan debit sungai. Peningkatan debit puncak akan
merubah pula bentuk hidrograf secara drastis dalam waktu yang relatif singkat.
Puslitbangtanak dan Jasa Tirta (2002) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh
perubahan penggunaan lahan terhadap debit puncak aliran permukaan. Perubahan
penggunaan lahan dari tahun 1994 sampai 1997 memberikan dampak terhadap
peningkatan debit puncak aliran permukaan yaitu sebesar 3,188 m3/detik hingga 8,03
m3
Perubahan respon hidrologi akibat perubahan penggunaan lahan juga dapat
dilihat dari rasio antara debit maksimum dan debit minimum suatu sungai (Prastowo,
kerusakan atau tidak. Apabila fluktuasi debit maksimum dan minimum tinggi, berarti
pada musim hujan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi sehingga menyebabkan
meningkatnya aliran permukaan dan musim kemarau hujan turun dengan intensitas yang
rendah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa DAS mengalami kerusakan fungsi
hidrologi dan telah terjadinya degradasi kualitas DAS. Hal ini dikarenakan tingginya
aliran permukaan juga akan meningkatkan jumlah erosi dan sedimen yang terangkut
bersama aliran permukaan (Asdak, 2004).
2.5. Model Hidrologi DAS
Model hidrologi merupakan model yang menggambarkan secara abstrak
keadaan hidrologi yang mempunyai kesamaan dengan keadaan hidrologi sebenarnya di
lapangan (Pawitan, 2006). Hal yang sama dinyatakan Harto (1993), bahwa model
hidrologi adalah sebuah sajian sederhana dari sebuah sistem hidrologi yang kompleks.
Adapun tujuan penggunaan suatu model dalam pengkajian hidrologi adalah untuk 1)
peramalan (forecasting) termasuk sistem peringatan dan manajemen, peramalan disini
menunjukan baik besaran maupun waktu kejadian yang dianalisis berdasarkan
probabilistik, 2) perkiraan (prediction) termasuk besaran kejadian dan hipotetik, 3) alat
deteksi dalam masalah pengendalian, dengan sistem ynag telah pasti dan keluaran yang
diketahui maka masukan dapat dikontrol dan diatur, 4) alat pengenal (identification
tool) dalam masalah perencanaan misalnya untuk melihat pengaruh urbanisasi, pengelolaan tanah dengan membandingkan masukan dan keluaran sistem tertentu, 5)
ekstrapolasi data/informasi, 6) perkiraan lingkungan akibat tingkat perilaku manusia
yang berubah/meningkat dan 7) penelitian dasar dalam proses hidrologi.
2.6. Soil and Water Assessment Tool (SWAT)
Analisis hidrologi dapat dilakukan dengan menggunakan software SWAT yang
pertama kali dikembangkan oleh DR. Jeff Arnold pada awal tahun 1990-an untuk
Agricultural Research Service (ARS) dari USDA. Menurut Neitsche et al (2005), SWAT merupakan hasil gabungan dari beberapa model yaitu Simulator for Water
Agricultural Management System (GREAMS); dan Erosion Productivity Impact Calculator (EPIC).
Software SWAT pertama kali digunakan di Amerika Serikat yang kemudian meluas ke Eropa, Afrika, dan Asia. Software SWAT dikembangkan untuk mengetahui
pengaruh dari manajemen lahan terhadap siklus hidrologi, sedimen yang ditimbulkan
dan daur ulang bahan kimia pertanian yang diperoleh berdasarkan data pada jangka
waktu tertentu. Software SWAT akan diaplikasikan sebagai tools tambahan pada menu
bar plug-in Map Window-46SR. Map Window 46SR adalah open source software
berbasis GIS yang memungkinkan para penggunanya untuk menambahkan sendiri
program atau tool baru. Dengan demikian, SWAT dapat diintegrasikan dengan
MapWindow (MapWindow SWAT/MWSWAT) tanpa perlu membeli sistem berbasis
GIS lainnya secara lengkap.
SWAT merupakan model hidrologi berbasis fisika (physically based) yang membutuhkan informasi spesifik tentang iklim, sifat-sifat tanah, topografi , vegetasi dan
praktek pengelolaan lahan yang terjadi di dalam DAS. SWAT dapat dimodelkan secara
langsung proses-proses fisika yang terkait dengan pergerakan air, sedimen,
pertumbuhan tanaman, siklus unsur hara dan lain sebagainya (Neitch et al., 2005).
Proses-proses tersebut didasarkan pada konsep neraca air. Untuk pemodelan, suatu
DAS dibagi menjadi menjadi beberapa Sub DAS atau Sub Basin yang didasarkan pada
kesamaan penggunaan tanah dan kesamaan penggunaan tanah atau sifat lain yang
berpengaruh terhadap hidrologi.
Simulasi hidrologi suatu DAS dengan model SWAT dipisahkan ke dalam dua
bagian utama yaitu fase lahan pada siklus hidrologi (Gambar 1) dan fase air pada siklus
hidrologi. Fase lahan mengendalikan jumlah air, sedimen, unsur hara dan pestisida
yang masuk ke dalam saluran utama pada setiap Sub DAS. Fase air atau penelusuran
Gambar 1. Representasi lahan pada siklus hidrologi ((Neitch et al., 2005).)
SWAT terus mengalami perkembangan sejak awal diciptakan. Hingga kini,
SWAT telah dicoba dikembangkan untuk daerah tropis yang pada dasarnya memiliki
ketersediaan data yang berbeda dengan daerah sub tropis dimana model ini diciptakan.
Pengembangan sangat didukung oleh perkembangan teknologi. Pada awalnya, SWAT
untuk dikembangkan oleh Windows (Visual Basic), GRASS, Arcview, ArcGIS dan
terakhir dikembangkan dalam Map Window, suatu interface untuk SWAT yang dapat
diakses bebas oleh pengguna.
SWAT telah mengalami validasi yang luas. Kalibrasi dan validasi output SWAT
oleh Reungsang et al. (2005) dengan membandingkan aliran hasil model dan aliran NO3-N dalam sungai menghasilkan nilai R2
Siklus hidrologi yang disimulasikan dalam SWAT berdasarkan pada persamaan
water balance. Persamaannya (Neitch et al., 2005) adalah :
sebesar 0.73. Kalibrasi aliran permukaan
bulanan yang dilakukan oleh Schuoldan Abbaspour (2006) menggunakan teknik
Nash-Sutcliffe menghasilkan nilai efesiensi sebesar 0.82. Analisis sensitivitas model yang
dilakukan Reungsang et al. (2005) menunjukan bahwa model sangat peka terhadap
Keterangan
SWt = kandungan akhir air tanah (mmH
:
2
SW
O)
0 = kandungan air tanah awal pada hari ke-i (mmH2
R
O)
day = Jumlah presipitasi pada hari ke-i (mmH2
Q
O)
Surf = Jumlah surface runoff pada hari ke-i (mmH2
Ea = Jumlah evapotranspirasi pada hari ke-i (mmH O)
2
Wseep = Jumlah air yang memasuki vadose zone pada profil tanah pada hari O)
ke- I (mmH2
Qgw = Jumlah air yang kembali pada hari ke-i (mmH O)
2
Data masukan model untuk setiap HRU Sub DAS dikelompokan ke dalam
beberapa kategori yaitu iklim, unit respon hidrologi (Hydrologic Respon Unit/HRU),
genangan/daerah basah, air bawah tanah dan saluran utama yang mendrainase Sub
DAS. HRU merupakan kelompok lahan dalam Sub DAS yang memiliki kombinasi
tanaman penutup, tanah dan pengolahan yang unik. Data yang dibutuhkan dalam model
ini merupakan data harian.
O)
Data iklim menyediakan masukan air dan energi yang berpengaruh terhadap
keseimbangan air. Input energi berupa iklim penting dalam melakukan simulasi dalam
SWAT untuk menghasilkan perhitungan water balance yang akurat (Neitsch et al., 2005). Paramater iklim yang digunakan dalam SWAT berupa hujan harian, temperatur
udara maksimum dan minimum, radiasi matahari, kecepatan angin, serta kelembaban
nisbi. Keunggulan dari SWAT adalah data iklim yang sulit untuk disediakan secara
harian dapat dibangkitkan dengan menggunakan input file weather generator (.wgn).
Output SWAT terangkum dalam file-file yang terdiri dari file HRU, SUB dan RCH. File HRU berisikan output dari masing-masing HRUs, sedangkan SUB berisikan
output dari masing-masing sub DAS dan RCH merupakan output dari masing-masing sungai utama pada setiap sub DAS. Informasi output pada file SUB dan file HRU
adalah luas area (AREA km2), jumlah curah hujan (PRECIP mm), evapotranspirasi
actual (ET mm H2O), kandungan air (SW), aliran permukaan (SURQ mm), aliran
lateral (LATQ), aliran dasar (GWQ), hasil sedimen (SED ton/ha). Sedangkan informasi
curah hujan (PRECP mm), evapotranspirasi aktual (ET mm), kandungan air tanah (SW
mm), air perkolasi (PERC mm), aliran permukaan (SURQ mm), aliran ground water
(GW_Q mm), hasil air (WYLD mm).
2.7. Penelitian Terdahulu
Opensource MWSWAT telah digunakan dalam analisis dan validasi debit pada DAS Cisadane hulu dengan letak outlet sungai di daerah Batubeulah. Simulasi debit
dari MW SWAT menghasilkan debit rata-rata sebesar 77.08 m3/detik. Nilai ini tidak
terlalu jauh dengan debit rata-rata bulanan hasil observasi. Dari perbandingan secara
statistik, diperoleh nilai R2
Model SWAT juga telah dilakukan analisis terhadap penggunaan lahan di daerah
DAS Cirasea pada tahun 1998, 2004, dan 2007 menunjukan bahwa menunjukan bahwa
terjadi perubahan penggunaan lahan di DAS Cirasea selama kurun waktu tersebut.
Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di DAS Cirasea mengakibatkan terjadinya
perubahan respon hidrologi khususnya aliran permukaan dan aliran dasar. Aliran
permukaan yang terbesar dihasilkan oleh penggunaan lahan sesuai dengan RTRW yaitu
sebesar 279,51 mm (Srimalahayati, 2010).
sebesar 0.712 dan nilai NSI sebesar 0.696. Hal ini
menunjukan simulasi SWAT yang dijalankan dapat dikategorikan memuaskan.
Penelitian ini masih menggunakan beberapa parameter dan data global misalnya untuk
karakteristik tanah, karakteristik tanaman dan wilayah urban (pemukiman) (Faradina,
3.1. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan di DAS Citarum hulu dengan luas DAS sebesar 12.000 km2. Sungai Citarum yang berhulu di gunung Wayang, Kabupaten Bandung
(1700 m dpl) melewati dasar cekungan dan mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara
di pantai Utara Jawa. Wilayah cekungan bandung ini berada pada koordinat 107° BT
and 6° 32’ LS dimana outlet dari sungai citarum ini adalah outlet nanjung yang berada pada koordinat 6°57' LS 107°32' BT. Penelitian akan dilaksanakan bulan Januari
sampai Juni 2011.
3.2. Alat dan Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : peta tanah DAS
Citarum Hulu skala 1: 100.000, peta landuse 1994-2005 (sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung) skala 1:100.000, DEM (Digital Elevation Model) dengan
Resolusi 30 m x 30 m untuk wilayah Citarum dan data karakteristik tanah.
Peralatan yang digunakan adalah seperangkat komputer dengan perangkat lunak
MapWindow46SR, MWSWAT versi 1.9, Arc View version 3.3 with extension : Spatial
Analysis 2.0 dan Image Analysis, Global Mapper dan Miscrosoft Office.
3.3. Metode Pelaksanaan 3.3.1 Pengumpulan data
Pada tahap kegiatan pengumpulan data terdiri dari beberapa kegiatan:
1. Persiapan
Persiapan merupakan rangkaian awal suatu kegiatan penelitian. Hal-hal yang
perlu dipersiapkan :
a) Peta-peta dasar
Peta-peta yang perlu dipersiapkan adalah :
1)Peta DEM yang berasal dari DEM (Digital Elevation Model) dengan resolusi
30mx30m untuk wilayah Citarum, berasal dari
2)Peta landuse seri 1994, 1997, 2001, dan 2005 berasal dari BAPPEDA Kabupaten Bandung skala 1: 100.000.
3)Peta jenis tanah DAS Citarum skala 1 :100.000 berasal dari Balai Besar
Penelitian Tanah dan Agroklimat tahun 1993.
b) Jenis data sekunder yang diperlukan
Jenis data sekunder yang diperlukan merupakan data biofisik lahan yang
disesuaikan dengan masukan data (input) yang diperlukan model SWAT. Data
sekunder yang dibutuhkan adalah data debit aliran sungai bulanan dan harian
dari tahun 1994-2005, data curah hujan (1994-2005) dan data karakteristik
tanah. Semua data sekunder bersumber dari Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Air, Balai Pendayagunaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung serta Pusat Penelitian Tanah dan
Agroklimat-Bogor.
2. Pengelompokan data
Data-data hasil inventarisasi disusun berdasarkan masukan model pada model
SWAT berupa :
a) Data iklim
Data iklim yang dibutuhkan berupa data harian yang terbentuk time series yang
terdiri dari data curah hujan (mm), temperatur maksimum dan minimum, radiasi
matahari (MJ/m2
Pada penelitian ini data curah hujan berasal dari 5 stasiun penakar hujan (tahun
1994-2005) disajikan pada Gambar 15 dan metode perhitungan evapotranspirasi
pontensial menggunakan perhitungan Penman-Monteith.
/hari) serta kecepatan angin (m/dt). Stasiun lokasi penakar hujan
telah diketahui koordinat dan elevasinya. Penyiapan data iklim harus disesuaikan
dengan metode prediksi evapotranspirasi pontensial yang digunakan pada model.
Model SWAT sendiri menyediakan tiga model prediksi yaitu metode
Penman-Monteith, Priestley-Taylor dan Hargreaves.
b) Karakteristik tanah
Karaktersitik tanah diperlukan adalah sifat fisika tanah untuk masing-masing
horizon meliputi kedalaman efektif (mm) dan infiltrasi tanah, ketebalan horizon
(mm), tekstur tanah, bulk density (g/cm3), kapasitas menahan air (mm H2
c) Karakteristik sungai
O/mm
tanah), Saturated hydraulic conductivity, kandungan fraksi batuan (%), nilai erodibilitas tanah dan kandungan bahan organic (%).
Karakteristik sungai yang diamati adalah karakteristik saluran sungai yang ada
di wilayah penelitian. Pengamatan karakteristik sungai ini menentukan kekasaran
manning saluran pada Tabel 1, konduktivitas hidroulik efektif tanah pada saluran
Tabel 1. Karakteristik saluran terbuka untuk menentukan nilai kekasaran manning
berdasarkan Chow (1959).
No Karakteristik Saluran Nilai Kekasaran Manning Rata-rata Range 1. Sudah dikeruk atau digali
a) Terpelihara, lurus dan seragam
0.025 0.016-0.023
b)Terpelihara, berkelok dan tidak seragam
0.035 0.023-0.05
c) Tidak terpelihara dan banyak tanaman liar
0.075 0.04-0.14
2.
a) Sedikit tanaman dan berbatu
0.05 0.025-0.065
b)Banyak pohon dan berbatu 0.1 0.05-0.15
Sumber : Neitsch et al, 2005
Tabel 2. Konduktivitas hidrolik efektif tanah pada saluran terbuka berdasarkan
Lane (1983)
No Material Dasar Karakteristik Material Dasar
Konduktivitas Hidrolik (mm/jam) 1 Kecepatan kehilangan
sangat cepat
Tidak ada kerikil dan pasir dengan ukuran besar
127
2 Kecepatan kehilangan cepat
Sedikit mengandung krikil dan pasir
51-127
3 Kecepatan kehilangan rendah
Campuran krikil dan pasir dengan kandungan liat-debu sedang
6-25
4 Kecepatan kehilangan rendah
Campuran krikil dan pasir dengan kandungan liat-debu tinggi
0.025-2.5
Sumber : Neitsch et al, 2005
3.3.2 Pemasukan data
Data Input yang disiapkan pada tahap pengumpulan data dimasukan ke dalam
file-file data input (SWAT Input File). Terdapat 17 file data input yang terkait dengan analisis hidrologi seperti disajikan pada Tabel 3. File PCP, TMP, SLR, HMD dan SOL
Sedangkan file FIG, CIO, COD, BSN, SUB, HRU, MGT, GW, dan RTE terbentuk setelah prosedur pengolahan data dijalankan.
Tabel 3. File-file input dan fungsinya pada Model SWAT
Nama File Fungsi
FIG Mendefinisikan jaringan hidrologi DAS CIO Mengontrol file parameter DAS
COD Menentukan waktu simulasi BSN Mengontrol parameter input PCP File data curah hujan
TMP File data temperatur maksimum dan minimum harian
SLR File data radiasi matahari harian HMD File data kelembaban udara harian CROP File parameter penutup
lahan/pertumbuhan tanaman URBAN File data lahan terbangun
SUB Mengontrol parameter input ditingkat Sub DAS
WGN File input generator iklim
RTE File input saluran utama : mengontrol parameter pergerakan air dan sedimen di tingkat Sub DAS
HRU Mengontrol parameter ditingkat HRU MGT File input pengelolaan : skenario
pengelolaan dan penutupan lahan SOL File karakteristik tanah
GW File air bawah tanah Sumber : Neitsch et al (2005)
Prosedur input data untuk file-file pada level DAS sebagai berikut:
1. File-file PCP dan TMP disusun dalam format miscrosoft Access. File-file ini disusun menggunakan format yang telah ditentukan oleh model SWAT dimana
setiap file terdiri dari 2 bentuk yaitu :
a) File berisi lokasi stasiun
b) File berisi besarnya data masing-masing stasiun
Pada file ini terdiri dari judul, tanggal dan besarnya data (PCP dan TMP). Sedangkan data hujan, temperatur maksimum-minimum, radiasi matahari dan
kecepatan angin untuk membangun file yang disetting dalam data SWAT. Data
yang diperlukan untuk generator iklim:
a. Rata-rata temperatur udara maksimum harian setiap bulan (˚C)
b. Rata-rata temperatur udara minimum harian setiap bulan (˚C)
c. Standar deviasi temperatur udara maksimum harian setiap bulan (˚C)
d. Standar deviasi temperatur udara minimum harian setiap bulan (˚C)
e. Rata-rata curah hujan bulanan (mm)
f. Standar deviasi curah hujan bulanan (mm)
g. Koefesien skewnes curah hujan bulanan
h. Probabilitas hari basah mengikuti hari kering tiap bulan
i. Probabilitas hari kering mengikuti hari basah tiap bulan
j. Rata-rata jumlah hari hujan tiap bulan
k. Rata-rata curah hujan yang jatuh lebih dari 30 menit tiap bulan
l. Rata-rata radiasi sinar matahri harian tiap bulan (MJ/m2
m.Rata-rata temperatur titik embun harian tiap bulan (˚C) /hari)
n. Rata-rata kecepatan bulanan tiap bulan (m/detik)
2. Karakteristik tanah dan Hydrology Soil Group (HSG)
Tipe dan karakteristik tanah di daerah penelitian berdasarkan hasil penelitian tanah
(Puslittanak) pada tahun 1993 untuk tanah skala semi detail. HSG sebagai dasar
analisis untuk tektur tanah dan kemampuan infiltrasi dan sangat berpengaruh pada
aliran permukaan untuk tiap tipe jenis penggunaan lahan yang berbeda. Tipe dan
Tabel 4. Hydrograph Soil Groups (HSG)
Tabel 5. Karakteristik tanah untuk input SWAT
KODE SWAT Keterangan NLAYERS Jumlah horizon
HYDGRP Group hidrologi tanah (berdasarkan penamaan kriteria dari SCS (Soil Conservation Service))
SOL_ZMX (mm) Kedalaman maksimum perakaran tanaman pada profil tanah (mm)
TEXTURE Tekstur tanah pada semua lapisan pada profil tanah. Data ini tidak diproses dalam model
SOL_Z Ketebalan setiap horizon pada profil tanah dari permukaan tanah (mm)
SOL_BD Bulk density (Mg/m3 atau gr/cm3 SOL_AWC
)
Kapasitas menahan air pada setiap lapisan (mm H2
SOL_CBN
O/mm tanah)
Kandungan bahan organik tanah (% berat tanah)
CLAY Kandungan liat tanah (% berat tanah
SILT Kandungan debut tanah (%berat tanah)
ROCK Kandungan fraksi batuan (% berat tanah)
K_USLE Nilai erodibilitas tanah menurut USLE (m3
-ton cm) Hydrology Soil
Groups (HSG)
Keterangan Laju infiltrasi (cm/hour)
A Dalam pasir, debu beragregat 0.76-1.14
B Dangkal, pasir berlempung 0.38-0.76 C Liat berlempung, pasir
berlempung dangkal
0.13-0.38
D Tanah yang megembang pada waktu basah, liat sangat tinggi >60%, tanah yang dipengaruhi oleh garam
5. Karakteristik penggunaan lahan
Penggunaan lahan yang ada di wilayah penelitian dalam model ini dilakukan
dengan pendekatan dengan menggunakan database yang telah disediakan SWAT yang
terdapat dalam file CROP dan URBAN dengan melakukan koreksi terhadap nilai leaf
areal index (LAI), kekasaran meanings (n), curve number menurut SCS (CN) dan nilai pengelolaan tanaman menurut USLE (c). Perubahan beberapa parameter disesuaikan
dengan hasil survei lapang pada daerah penelitian.
Klasifikasi peta landuse dari tahun 1994, 1997, 2001 dan 2005 dapat dilihat pada
Gambar 3, 4, 5 dan 6.
Gambar 5. Peta landuse tahun 2001
(b)
3.3.3 Analisis Data
Tahap Analisis data terdiri dari identifikasi perubahan penggunaan lahan,
analisis debit sungai dengan menggunakan model SWAT dan analisis debit model hasil
kalibrasi SWAT terhadap penggunaan lahan 1994, 1997 dan 2001 .
A. Identifikasi Perubahan penggunaan lahan
Pola perubahan penggunaan lahan diidentifikasi dengan cara overlay peta landuse Citarum Hulu tahun 1994 dengan peta landuse 1997, kemudian overlay landuse 1997 dengan 2001. Landuse 2001 dengan 2005. Proses overlay peta tersebut menggunakan
Gambar 7. Proses identifikasi perubahan lahan
B. Analisis Debit Sungai menggunakan model MWSWAT
Pada tahap ini, telah dilakukan pengolahan analisis debit aliran dengan
menggunakan data lokal daerah penelitian. Analisis debit aliran yang akan di
simulasikan adalah debit aliran permukaan runoff, aliran lateral dan aliran dasar.
Prosedur analisis debit aliran adalah sebagai berikut :
a) Deliniasi Daerah penelitian
Deliniasi daerah penelitian dilakukan menggunakan DEM STRM 30 x 30 m
dengan bantuan program Map Window. Daerah penelitian akan dideliniasi dari
DEM secara otomatis berdasarkan topografi alaminya, begitu pula dengan jaringan
hidrologinya. SWAT membagi DAS menjadi beberapa Sub DAS dimana setiap Sub
DAS mempunyai jaringan utama. Metode yang digunakan dalam proses deliniasi
DAS adalah metode treshold. Besar kecilnya treshold yang digunakan akan menentukan jumlah jaringan sungai yang terbentuk kemudian, jaringan sungai
tersebut akan menentukan banyaknya Sub DAS yang terbentuk dalam DAS.
Deliniasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Kotak dialog watershed delineation
b) Pembentukan HRU
HRU merupakan unit analisis hidrologi yang dibentuk berdasarkan
karakteristik tanah dan penggunaan lahan yang spesifik. HRU diperoleh melalui
overlay peta tanah dan penggunaan lahan. Satu sub DAS terdiri dari beberapa HRU. Proses pembentukannya dapat diihat pada Gambar 9.
Pembuatan HRU ( Create Hidrology Response Unit)
- Interval slope menurut Arsyad (2006)
- Peta raster landuse dan peta raster tanah format sistem koordinat proyeksi
UTM.
Gambar 9. Kotak dialog pembentukan HRUs
c) Penggabungan HRUs dengan data iklim
Tahap penggabungan HRUs dengan data iklim dilakukan setelah satuan analisis
terbentuk. Pada tahap ini harus ditentukan periode simulasi terlebih dahulu
kemudian memasukan data iklim.
d) Simulasi
Proses simulasi dijalankan setelah proses penggabungan HRU dengan data iklim
selesai dilakukan. Kemudian simulasi hidrologi tersebut dijalankan berdasarkan
periode harian. Persamaan yang digunakan di dalam SWAT untuk memprediksi
aliran permukaan adalah metode SCS Curve Number.
Dimana Qsurf adalah jumlah aliran permukaan pada hari I (mm). Rday
Dimana CN curve number (bilangan kurva), Curve Number (CN) diturunkan dari
analisis spasial dimana peta tanah dikonversi menjadi Hydrology Soil Group dan
dioverlay dengan peta penutupan lahan masing–masing tahun. CN digunakan
untuk memprediksi nilai runoff atau infiltrasi dan Ia adalah 0.2 S (berdasarkkan
hasil penelitian), sehingga persamaan perhitungan aliran menjadi :
adalah
jumlah curah hujan pada hari ke I (mm). Ia adalah kehilangan akibat resapan
permukaan, intersepsi dan infiltrasi (mm) dan S adalah parameter retensi (mm).
Paramater retensi dihitung berdasarkan persamaan berikut :
Qsurf =
Persamaan untuk menghitung aliran lateral adalah :
Dimana Qlat adalah jumlah air lateral yang masuk ke sungai utama pada hari ke
I (mm), SW iy,excess adalah kelebihan air pada lapisan tanah (mm), Ksat adalah
saturated hydraulic conductivity (mm/jam), slp adalah lereng (m/m), Ød adalah porositas tanah (mm/mm) dan Lhill
SW
adalah panjang lereng (m). Kelebihan air
pada lapisan tanah dihitung dengan persamaan :
iy,excess = SWly - FCly jika SWly > FC
ly adalah kandungan air tanah(mm) dan FCly
Aliran bawah tanah atau base flow (Q
adalah kapasitas
lapang (mm).
Dimana Ksat
e) Output SWAT
adalah hydraulic conductivity (mm/hari), = adalah jarak antar sub DAS ke saluran utama (m) dan adalah tinggi muka air tanah (m).
Hasil debit model SWAT yang menggunakan peta landuse pada tahun
2001 dan curah hujan tahun 2001 dapat divisualiasi dalam gradasi warna. Output
yang dipilih berupa debit rata-rata bulanan pada tahun 2001.
Output SWAT tersimpan dalam file-file output (SWAT Output File) yang terdiri dari file BSB, SBS dan RCH. File BSB berisi informasi sub DAS, file
SBS berisi informasi masing-masing HRU dan RCH berisi informasi pada
masing-masing sungai utama dalam sub DAS. Informasi yang terdapat pada
masing-masing sub DAS dan HRU dihasilkan selama periode simulasi dan
terdiri dari area (km2
f) Kalibrasi dan Validasi Model SWAT
), jumlah curah hujan (mm), kandungan air tanah (mm),
perkolasi (mm), aliran permukaan (mm), aliran lateral (mm) dan aliran dasar
(mm).
Kalibrasi dan pengujian model bertujuan agar output model yang
digunakan hasilnya mendekati dengan output dari DAS yang diuji. Kalibrasi
dilakukan terhadap nilai debit dengan cara membandingkan antara hasil prediksi
dengan hasil observasi (hasil pengukuran stasiun pengamat arus sungai (SPAS
di lapangan) dimana perbandingan tersebut menggunakan kriteria stastistik. Data
hasil observasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari SPAS Nanjung
dari tahun 1994-2005.
Model SWAT telah menyediakan 500 parameter untuk simulasi, tapi tidak
semua parameter digunakan untuk daerah Citarum Hulu sesuai dengan waktu
dan ketersediaan data. Pemilihan dan penyesuaian parameter ini dilakukan
dengan proses kalibrasi manual. Setelah dilakukan kalibrasi terhadap parameter
model, dilakukan pengujian model (validasi). Validasi dilakukan terhadap
Perbandingan debit hasil simulasi dengan debit hasil observasi dilakukan
dengan menggunakan SWAT Ploth and Graph . Pada SWAT Ploth and Graph
akan digunakan koefesien determinasi (R2
Nash-Sutclifffe Index (NSI) digunakan untuk mengevaluasi model pada SWAT
ploth dan Graph. Persamaan Nash-Sutcliffe Index (NSI) adalah sebagai berikut : ) dan Nash-Sutcliffe Index (NSI).
Koefesien determinasi menunjukan seberapa dekatnya nilai yang dihasilkan oleh
simulasi dengan nilai yang sesungguhnya di lapangan. Koefesien mendekati satu
menandakan nilai hasil simulasi memilki nilai yang cukup dekat dengan nilai
sesungguhnya. Persamaan koefesein determinasi adalah sebagai berikut :
Gambar 11. Prosedur kalibrasi dan validasi aliran Debit sungai dengan model
SWAT
Analisis Debit tahun 2001
Evaluasi
statistik
tidak
ya Kalibrasi Parameter Model
SWAT
selesai
Keterangan :
Qobs = debit observasi (m3
Q
/det)
cal,i = debit hasil simulasi (m3
= debit Simulasi rata-rata (m /det)
3
= debit observasi rata-rata (m /det)
3
Range nilai NSI adalah antara ∞ sampai dengan 1. Kategori simulasi
berdasarkan nilai NSI (Van Liew et al, 2005 dalam Stehr, 2009) adalah sebagai
berikut :
/det)
Layak jika ≥ 0.75
Memuaskan jika 0.36 ≤ NSI < 0.75
Kurang Memuaskan jika < 0.36
C. Analisis Debit Sungai dengan Model SWAT Hasil Kalibrasi terhadap Penggunaan Lahan 1994, 1997 dan 2001
Analisis debit terhadap penggunaan lahan tahun 1994, 1997 dan 2001
dilakukan dengan menggunakan model SWAT hasil kalibrasi. Analisis
dilakukan dengan menggunakan curah hujan tahun 2005 sebagai input tetap.
Pada análisis ini diasumsikan bahwa :
1. Parameter penggunaan lahan (sebagai parameter input ) nilainya berubah
BAB IV
Gambar 12. Diagram alir Penelitian
Pengelompokan
Kalibrasi model Swat tahun 2001
Tidak
Validasi model Swat untuk
landuse 1994, 1997, dan 2005
Ya Analisis Debit
4.1 Topografi dan Tata Sungai
DAS Citarum Hulu merupakan suatu cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan
Tangkuban Perahu di daerah utara dengan puncaknya antara lain Gunung Burarang
(2.076 m), Gunung Tangkuban Perahu (2.064 m), Gunung Manglayang (1800 m), dan
Gunung Jarian (1282 m). Dibagian Timur dilingkupi oleh Gunung Malang (1256 m)
dan Gunung Tanjak Nangsi (1514 m). Di bagian Barat cekungan muncul sederetan
instrusi yang membentuk punggung-punggung tak teratur yaitu Pegunungan Krenceng
(1736 m) dan Gunung Mandalawangi (1676 m) yang membatasi cekungan ini di daerah
timurnya.
DAS Citarum Hulu terdiri dari dataran tinggi (60%) dan daerah perbukitan
bergelombang (40%). Lereng dalam DAS Citarum Hulu sangat bervariasi dengan
jumlah keseluruhan 1.771 100.000 ha (pada Tabel 6).
Tabel 6. Jenis, luas, dan persentase lerengan di DAS Citarum Hulu
No Jenis Lerengan Luas (ha) %
Daerah resapan pada DAS Citarum Hulu berdasarkan kondisi hidrologi geologi
dan topografi resapan utama terdiri atas daerah dengan endapan alluvial dan Volkanik
Muda. Daerah endapan aluvial mempunyai karakteristik topografi landai dan gradien air
bumi dangkal. Karakteristik resapan diasumsikan sebanding dengan endapan dataran
pantai berlumpur yang diestimasikan koefesien resapannya adalah 8 %. Fluktuasi muka
air bumi dangkal pada cekungan Bandung (bagian depan aluvial) umumnya sama. Total
area ini adalah sebesar 336.8 km2
Daerah endapan vulkanik Muda mempunyai total area zone sebesar 1.285.7 km .
2
.
Daerah endapan ini dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan topografi, lereng dan
a) Lereng vulkanik bagian atas dan tengah. Lereng antara 20-30% dan bagian tengah
dapat mencapai 30%. Resapan baik karena bagian atas ditutupi oleh endapan
vulkanik yang porous. Jika lava mineral berarti resapan dapat dianggap tidak ada.
Pada zone ini sering muncul mata air bila muka air bumi terpotong oleh tebing.
Rata-rata koefesien resapan berdasarkan pengukuran aliran dasar bagian atas DAS
adalah sebesar 15-25%.
b) Lereng vulkanik bagian bawah dan kaki bukit elevasi di bawah 800 m dari
permukaan laut (dpl) lerengan antara 5% dan 10%. Karakteristik resapan baik.
Koefesien resapan didasarkan pada fluktuasi muka air bumi ditetapkan sebesar 25%.
Slope dan panjang slope adalah dua factor yang menentukan topografi dari suatu
DAS,dimana dua faktorini dapat menentukan kecepatan dan volume run off. (Asdak,
2004).
4.2 Karakteristik Tanah
Jenis tanah di daerah penelitian diperoleh dari peta Tanah Semi Detail DAS
Citarum Hulu sekala 1:100.000 tahun 1993. Berdasarkan peta tersebut terdapat 55 SPT
di DAS Citarum Hulu yang terbagi ke dalam 6 ordo yaitu Inceptisol, Alfisolls,
Andisolls, Mollisols, Entisols dan Ultisolls. Klasifikasi tanah berdasarkan ordo untuk
daerah penelitian data dilihat pada Gambar 13.
Inceptisols terdiri dari Sub Group Aquic Eutropepts, Typic Tropaquepts, Aeric
Tropaquepts, Oxic Humitropepts , Vertic Tropaquepts, Andic Dystropepts. Andisols
terdiri dari Typic Hapludands, Eutric Hapludans, Thaptic Hapludans, Entisols terdiri
dari Troporthents. Mollisols terdiri dari : Oxic Argiudolls, Typic Hapludolls, Aquic
Hapludolls, Cumulic Hapludolls, Andic Hapludolls. Ultisols terdiri dari sub group :
Typic Rhodudullts.
Jenis tanah yang paling dominan pada DAS Citarum Hulu adalah Tanah Inceptisol
dengan persentase luas 42.6% (69368,76 ha). Luasan tiap jenis tanah berdasarkan kelas
Tabel 7. Luasan tiap jenis tanah berdasarkan kelas ordo tanah
Jenis Tanah Luas (ha) Luas (%)
Alfisolls 14480.67 8.9
Andisols 37100.31 22.8
Entisols 1361.3 0.8
Inceptisols 69368.76 42.6
Mollisols 33872.86 20.8
Ultisols 6591.12 4
Total 162775 100
4.3 Kondisi Iklim
Keadaan iklim tergolong tropis yang dicirikan oleh adanya dua musim yang
berbeda, yaitu musim penghujan dan musim kemarau dengan rata-rata suhu 27.15°C
pada daerah rendahnya dan 19.67°C pada daerah tingginya. Kelembaban berkisar
70-83%.
Di dalam DAS terdapat 59 stasiun curah hujan yang terdiri atas tipe biasa
(ordinary type), 15 buah tipe otomatis (outamatic type) dan 9 buah tipe otomatis yang
dilengkapi dengan sistem telemetri. Rata-rata tahunan curah hujan berkisar antara 1800
m dan 3500 mm. DAS Citarum Hulu memiliki curah hujan rata-rata tahunan berkisar
antara 1800 mm hingga 2800 mm.
Daerah Penelitian temasuk tipe iklim D berdasarkan klasifikasi Oldeman.
Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kebasahan suatu wilayah, yaitu dari banyaknya
bulan basah (curah hujan bulanan >200 mm) dan bulan kering (curah hujan<100 mm).
Berdasarkan klasifikasi tersebut daerah penelitian mempunyai bulan basah 3-4 bulan
basah dan bulan kering 4 bulan. Curah hujan rata-rata bulanan dari tahun 2004-2008
pada stasiun Bandung dapat dilihat pada Gambar 14. Pada Gambar 14 curah hujan
rata-rata bulanan < 100 mm (bulan kering) terjadi pada bulan Juli, Agustus, September dan
Oktober sedangkan curah hujan >200 mm (bulan basah) terdapat 8 bulan yaitu Januari
sampai Juni dan Noverber sampai Desember. Stasiun penakar hujan yang terdekat untuk
DAS Citarum berjumlah lima stasiun, dimana lokasi titik stasiun penakar hujan dapat
dilihat pada Gambar 15.
Gambar 14 . Rata-rata curah hujan bulan dari tahun 2004-2008
0
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
Gambar 15. Sebaran stasiun penakar hujan DAS Citarum Hulu
4.4 Kondisi Hidrologi
Debit observasi yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari pos duga Air
Nanjung. Pemilihan pos duga air Nanjung karena ketersediaan data debit sungai untuk
yang tersedia lengkap adalah data debit bulanan dan harian. Gambar 16 menunjukan
rata-rata debit bulanan dari tahun 2004-2008.
Gambar 16 . Debit aliran sungai rata-rata bulanan (2004-2008)
Rata-rata debit minimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 9.29 m3/s dan
rata-rata debit maksimu terjadi pada bulan pada bulan Maret sebesar 128.95 m3/s.
0 20 40 60 80 100 120 140
jan feb mar apr mei jun jul Agus Sept Agust Okt Nov Des
Q
(m
3/