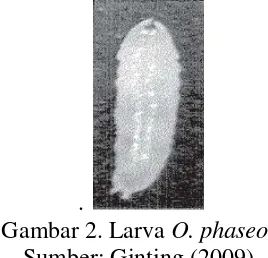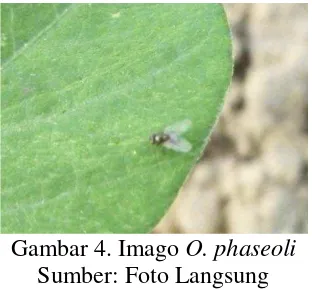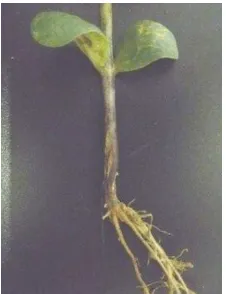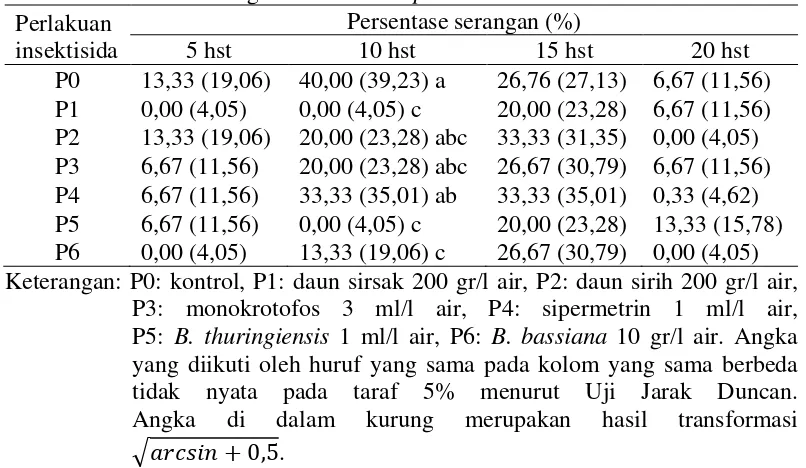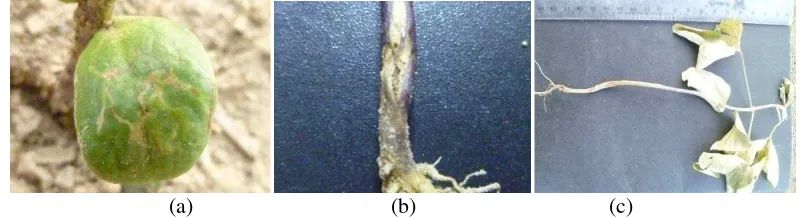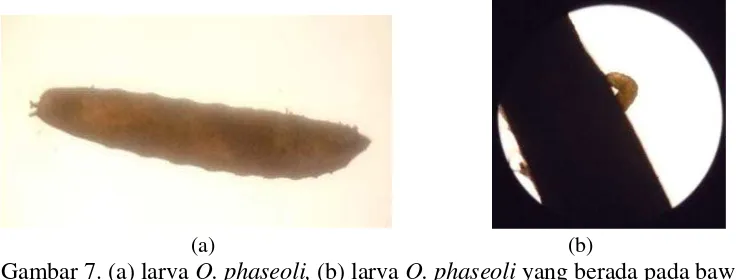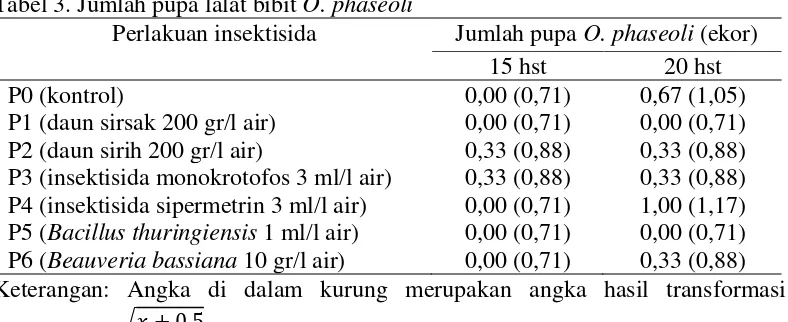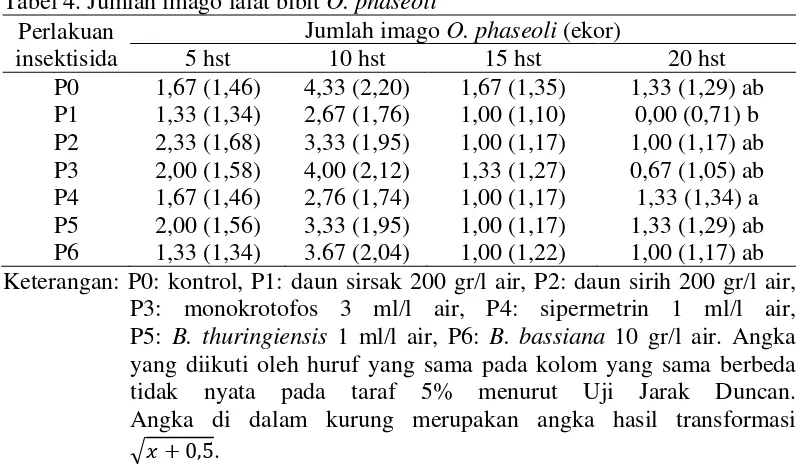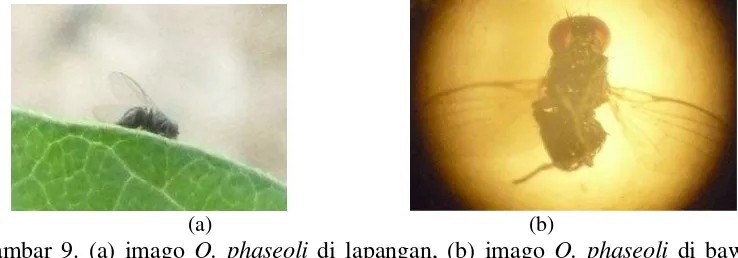PENGARUH JENIS INSEKTISIDA TERHADAP LALAT BIBIT (Ophiomyia phaseoliTry.) PADA TANAMAN
KEDELAI (Glycine maxL.)
SKRIPSI OLEH :
YUAN CYNTHIA Br. SIMANJUNTAK 090301198/ AGROEKOTEKNOLOGI
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
PENGARUH JENIS INSEKTISIDA TERHADAP LALAT BIBIT (Ophiomyia phaseoliTry.) PADA TANAMAN
KEDELAI (Glycine maxL.)
SKRIPSI
OLEH :
YUAN CYNTHIA Br. SIMANJUNTAK 090301198/ AGROEKOTEKNOLOGI
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
Judul Skripsi :Pengaruh Jenis Insektisida Terhadap Lalat Bibit (Ophiomyia phaseoli Try.) Pada Tanaman Kedelai (Glycine max L.)
Nama : Yuan Cynthia Br. Simanjuntak
NIM : 090301198
Program Studi : Agroekoteknologi
Minat Studi : Hama dan Penyakit Tumbuhan
Disetujui Oleh Komisi Pembimbing
Ir. Yuswani Pangestiningsih, MS. Dr. Lisnawita, SP., M.Si.
Ketua Anggota
Mengetahui,
Ir. T. Sabrina, M.Agr, Sc, Ph.D Ketua Program Studi Agroekoteknologi
ABSTRAK
Yuan Cynthia Br. Simanjuntak. 2013. Pengaruh jenis insektisida terhadap lalat bibit (Ophiomyia phaseoli Try.) pada tanaman kedelai (Glycine max L.), dibimbing oleh Yuswani Pangestiningsih dan Lisnawita.
Penggunaan insektisida kimia secara tidak bijaksana untuk mengendalikan lalat bibit dapat menyebabkan resistensi hama. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan insektisida biologi, nabati, dan kimia yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari pestisida tersebut. Penelitian dilaksanakan di kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai dari Juni sampai Juli 2013 dengan menggunakan rancangan acak kelompok non faktorial. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan daun sirsak 200 gr/l air (P1) efektif mengendalikan populasi lalat bibit dengan persentase serangan (0,00%), jumlah larva (0,00 ekor), dan jumlah imago (0,00 ekor) lebih rendah dibandingkan perlakuan P0 (kontrol), P2 (daun sirih 200 gr/l air), P3 (monokrotofos 3 ml/l air), P4 (sipermetrin 1 ml/l air), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air), dan P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air). Waktu munculnya gejala pada penggunaan daun sirsak 200 gr/l air (P1) juga lebih lama yaitu 6 hari setelah tanam (hst) dibanding dengan perlakuan lainnya.
ABSTRACT
Yuan Cynthia Br. Simanjuntak. 2013. Effect of insecticides to control bean fly
(Ophiomyia phaseoli Try.) on soybean (Glycine max L.). Supervised by Yuswani Pangestiningsih and Lisnawita.
Using chemical insecticide to control bean fly unwisely caused pest resistance. For that purpose in this research used biology, botany, and chemical insecticide to determine their effectiveness. This research was conducted at Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai from June to July 2013 using factorial randomized block design. The result showed used soursop leaf 200 gr/l of water (P1) was more effective to control population of bean fly with percentage of attack (0.00%), number of larvae (0.00 larvae), number of bean fly (0.00 bean fly) lower than P0 (control), P2 (betel leaf 200 gr/l of water), P3 (monokrotofos 3 ml/l of water), P4 (sipermetrin 1 ml.l of water), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l of water), and P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l of water). Time symtomp in P1 (soursop leaf 200 gram/l of water) also lower than the other treatments was six days after planted.
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 1992 dari ayah
V.J.J Simanjuntak dan ibu Erwin Tri Ratna Wati. Penulis merupakan putri
pertama dari tiga bersaudara.
Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 1, Binjai dan pada tahun yang
sama masuk ke Fakultas Pertanian USU melalui jalur Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis memilih minat Hama dan Penyakit
Tumbuhan, program studi Agroekoteknologi.
Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif sebagai anggota Himpunan
Mahasiswa Agroekoteknologi (Himagrotek).
Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di PT. Paya Pinang
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul ”Pengaruh jenis insektisida terhadap hama lalat bibit
(Ophiomyia phaseoli Try.) pada tanaman kedelai (Glycine max L.)”
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada
Komisi Pembimbing Ir. Yuswani Pagestiningsih, MS. selaku ketua dan
Dr. Lisnawita, SP, M.Si selaku anggota yang telah memberikan saran dan
arahannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis
mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan
dukungan finansial dan spiritual. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada
seluruh staf pengajar, pegawai serta kerabat di lingkungan Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara yang telah berkontribusi dalam kelancaran studi dan
penyelesaian skripsi ini.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini
bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.
Medan, Desember 2013
DAFTAR ISI
ABSTRAK ... i
ABSTRACT ... ii
RIWAYAT HIDUP ... iii
KATA PENGANTAR ... iv
DAFTAR TABEL ... vii
DAFTAR GAMBAR ... viii
DAFTAR LAMPIRAN ... ix
PENDAHULUAN Latar belakang ... 1
Tujuan penelitian ... 3
Hipotesis penelitian ... 3
Kegunaan penelitian ... 3
TINJAUAN PUSTAKA Hama lalat bibit pada tanaman kedelai ... 4
Ophiomyia phaseoli Try. ... 4
Taksonomi ... 4
Biologi ... 5
Gejala serangan ... 6
Insektisida monokrotofos ... 8
Insektisida sipermetrin ... 8
Insektisida nabati ... 9
Daun sirih (Peper bettle L.) ... 10
Daun sirsak (Annona muricata Linn) ... 10
Bacillus thuringiensis ... 11
Beauveria bassiana ... 12
BAHAN DAN METODE Tempat dan waktu penelitian ... 13
Bahan dan alat ... 13
Metode penelitian ... 13
Pelaksanaan penelitian ... 15
Persiapan lahan ... 15
Penanaman ... 15
Pemeliharaan tanaman ... 15
Penyiraman ... 15
Penyulaman ... 16
Penjarangan ... 16
Penyiangan ... 16
Persiapan insektisida ... 16
Larutan sirih ... 16
Larutan sirsak ... 16
Insektisida kimia ... 17
Insektisida biologi ... 17
Aplikasi insektisida ... 17
Pengambilan sampel ... 18
Peubah amatan ... 18
Persentase serangan ... 18
Jumlah larva lalat bibit ... 18
Jumlah pupa lalat bibit ... 19
Jumlah imago lalat bibit ... 19
Waktu munculnya gejala ... 19
HASIL DAN PEMBAHASAN Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli (%) ... 20
Jumlah larva lalat bibit O. phaseoli (ekor) ... 23
Jumlah pupa lalat bibit O. phaseoli (ekor) ... 25
Jumlah imago lalat bibit O. phaseoli (ekor) ... 28
Waktu munculnya gejala (hst) ... 30
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 31
Saran ... 31
DAFTAR TABEL
No. Halaman
1. Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli ... 20
2. Jumlah larva lalat bibit O. phaseoli ... 23
3. Jumlah pupa lalat bibit O. phaseoli ... 26
4. Jumlah imago lalat bibit O. phaseoli ... 28
DAFTAR GAMBAR
No. Halaman
1. Telur Ophiomyia phaseoli Try. ... 5
2. Larva O. phaseoli ... 5
3. Pupa O. phaseoli ... 6
4. Imago O. phaseoli ... 6
5. Gejala serangan O. phaseoli ... 7
6. Gejala Serangan O. phaseoli (a) bekas gerekan larva pada kotiledon, (b) luka pada kulit pangkal batang dekat leher akar, (c) tanaman (15 hst) yang mati akibat serangan hama lalat bibit. ... 22
7. (a) larva O. phaseoli (b) larva O. phaseoli yang berada pada bawah permukaan kulit batang ... 24
8. (a) pupa O. phaseoli dibawah mikroskop perbesaran 4 x 10, (b) kulit batang tanaman kedelai yang sudah dikelupas dan terdapat larva O. phaseoli ... 28
9. (a) imago O. phaseoli di lapangan, (b) imago O. phaseoli di bawah mikroskop perbesaran 4 x 10 ... 29
DAFTAR LAMPIRAN
No. Halaman
1. Bagan plot penelitian. ... 35
2. Bagan penanaman pada plot ... 36
3. Data persentase serangan O. phaseoli 5 hst ... 37
4. Data persentase serangan O. phaseoli 10 hst ... 38
5. Data persentase serangan O. phaseoli 15 hst ... 39
6. Data persentase serangan O. phaseoli 20 hst ... 40
7. Data jumlah larva O. phaseoli 5 hst ... 41
8. Data jumlah larva O. phaseoli 10 hst ... 42
9. Data jumlah larva O. phaseoli 15 hst ... 43
10. Data jumlah larva O. phaseoli 20 hst. ... 44
11. Data jumlah pupa O. phaseoli 15 hst ... 45
12. Data jumlah pupa O. phaseoli 20 hst ... 46
13. Data jumlah imago O. phaseoli 5 hst ... 47
14. Data jumlah imago O. phaseoli 10 hst ... 48
15. Data jumlah imago O. phaseoli 15 hst ... 49
16. Data jumlah imago O. phaseoli 20 hst ... 50
17. Lampiran gambar ... 51
ABSTRAK
Yuan Cynthia Br. Simanjuntak. 2013. Pengaruh jenis insektisida terhadap lalat bibit (Ophiomyia phaseoli Try.) pada tanaman kedelai (Glycine max L.), dibimbing oleh Yuswani Pangestiningsih dan Lisnawita.
Penggunaan insektisida kimia secara tidak bijaksana untuk mengendalikan lalat bibit dapat menyebabkan resistensi hama. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan insektisida biologi, nabati, dan kimia yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari pestisida tersebut. Penelitian dilaksanakan di kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai dari Juni sampai Juli 2013 dengan menggunakan rancangan acak kelompok non faktorial. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan daun sirsak 200 gr/l air (P1) efektif mengendalikan populasi lalat bibit dengan persentase serangan (0,00%), jumlah larva (0,00 ekor), dan jumlah imago (0,00 ekor) lebih rendah dibandingkan perlakuan P0 (kontrol), P2 (daun sirih 200 gr/l air), P3 (monokrotofos 3 ml/l air), P4 (sipermetrin 1 ml/l air), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air), dan P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air). Waktu munculnya gejala pada penggunaan daun sirsak 200 gr/l air (P1) juga lebih lama yaitu 6 hari setelah tanam (hst) dibanding dengan perlakuan lainnya.
ABSTRACT
Yuan Cynthia Br. Simanjuntak. 2013. Effect of insecticides to control bean fly
(Ophiomyia phaseoli Try.) on soybean (Glycine max L.). Supervised by Yuswani Pangestiningsih and Lisnawita.
Using chemical insecticide to control bean fly unwisely caused pest resistance. For that purpose in this research used biology, botany, and chemical insecticide to determine their effectiveness. This research was conducted at Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai from June to July 2013 using factorial randomized block design. The result showed used soursop leaf 200 gr/l of water (P1) was more effective to control population of bean fly with percentage of attack (0.00%), number of larvae (0.00 larvae), number of bean fly (0.00 bean fly) lower than P0 (control), P2 (betel leaf 200 gr/l of water), P3 (monokrotofos 3 ml/l of water), P4 (sipermetrin 1 ml.l of water), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l of water), and P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l of water). Time symtomp in P1 (soursop leaf 200 gram/l of water) also lower than the other treatments was six days after planted.
PENDAHULUAN Latar belakang
Kedelai (Glycine max L. Merr.) berasal dari daerah Manshukuon (Cina Utara). Di Indonesia kedelai mulai dibudidayakan pada abad ke-17 sebagai
tanaman makanan dan pupuk hijau. Saat ini kedelai banyak ditanam di dataran
rendah yang tidak banyak mengandung air, seperti di pesisir Utara Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara (Gorontalo), Lampung, Sumatera
Selatan dan Bali (Prihatman, 2000). Meirina et al. (2008) menyatakan kebutuhan terhadap kedelai semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk dan
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makanan berprotein nabati.
Produksi kedelai tahun 2011 di Indonesia sebesar 851,29 ribu ton biji
kering, menurun sebanyak 55,74 ribu ton (6,15%) dibandingkan tahun 2010.
Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa sebesar 59,09 ribu ton, tetapi di luar
Jawa mengalami peningkatan sebesar 3,35 ribu ton. BPS (2012) juga
memperkirakan akan terjadi penurunan produksi kedelai pada tahun 2012 yang
relatif besar terdapat di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat,
Sumatera Utara, dan Lampung.
Penurunan produksi biji kering kedelai dipengaruhi oleh berbagai faktor
biotik maupun abiotik. Salah satu faktor biotik terpenting adalah serangan
organisme pengganggu tanaman, salah satunya serangan hama lalat bibit
Menurut Djuwarso et al. (1992) serangan berat oleh O. phaseoli pada stadia awal pertumbuhan tanaman kedelai dapat menurunkan hasil lebih dari 50%
bahkan kematian tanaman. Sedangkan menurut hasil penelitian Ginting (2009)
menunjukkan bahwa pada umur 10 hari setelah tanam (hst) tingkat serangan lalat
bibit mencapai 29,29% dan meningkat menjadi 65,00% pada umur 13 hst.
Salah satu teknik pengendalian hama lalat bibit yang dapat dilakukan
adalah pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi adalah penggunaan
insektisida kimia untuk mengendalikan hama. Penggunaan insektisida tepat dosis
dan tepat waktu aplikasi berdasarkan pemantapan ambang kendali dapat
mengurangi intensitas kerusakan akibat serangan hama dan mempertahankan hasil
tetap tinggi (Marwoto, 1997). Namun kenyataannya banyak petani yang
menggunakan insektisida kimia tidak bijaksana. Deptan (2011b) menyatakan
penggunaan insektisida secara tidak bijaksana dapat menyebabkan timbulnya
resistensi (kekebalan), sehingga untuk mengatasi organisme pengganggu yang
resisten perlu dosis yang lebih tinggi dan membahayakan.
Pengendalian hama dengan insektisida kimia telah menimbulkan banyak
masalah lingkungan oleh karena itu diperlukan alternatif pengendalian yang aman
dan efisien. Salah satu alternatif pengendalian yang cukup potensial adalah
penggunaan patogen serangga seperti Beauveria bassiana dan Bacillus thuringiensis (Soetopo dan Indrayani, 2007).
Insektisida biologi adalah insektisida yang mengandung mikroba (jamur,
bakteri, virus dan nematoda) yang diformulasikan oleh manusia. Menurut Untung
(2000) insektisida biologis termasuk jenis insektisida yang yang memiliki
Pestisida nabati adalah pestida yang bahan dasarnya berasal dari tanaman.
Penggunaan pestisida nabati mulai banyak diminati oleh petani karena mahalnya
pertisida kimiawi (Rachmawati dan Korlina, 2009). Deptan (2011a) menyatakan
pestisida nabati dapat mengendalikan serangga hama dan penyakit melalui cara
kerja yang spesifik yaitu merusak perkembangan telur, larva, dan pupa, penolak
makan, dan menghambat reproduksi serangga betina.
Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk membandingkan
efektifitas antara insektisida kimia, nabati, dan biologi terhadap lalat bibit.
Tujuan penelitian
Untuk mengetahui jenis insektisida yang efektif terhadap lalat bibit
(O. phaseoli) pada tanaman kedelai (Glycine max L.).
Hipotesis penelitian
1. Insektisida biologi, nabati dan kimia dapat menekan serangan hama lalat bibit (O. phaseoli) pada tanaman kedelai
2. Insektisida kimia lebih efektif menekan serangan hama lalat bibit (O. phaseoli) dari pada insektisida biologi dan nabati.
Kegunaan penelitian
- Untuk memperoleh data penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. - Untuk memperoleh jenis insektisida yang efektif untuk mengendalikan lalat bibit pada
kedelai.
TINJAUAN PUSTAKA Hama lalat bibit pada tanaman kedelai
Sejak tumbuh ke permukaan tanah hingga tanaman tua, tanaman kedelai
tidak luput dari serangan hama. Hama yang menyerang tanaman kedelai sebanyak
111 jenis salah satunya adalah lalat bibit. Terdapat 3 jenis lalat bibit yang menjadi
hama utama pada kedelai, antara lain Ophiomyia phaseoli Try., Melanagromyza sojae Zehn., dan Melanagromyza dolichostigma de meij (Marwoto, 1997).
Kalshoven (1981) mengatakan bahwa Ophiomyia phaseoli Try. merupakan hama pada pembibitan pada kacang-kacangan yang paling merusak di
Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini hanya diteliti tingkat kerusakan
O. phaseoli. Menurut Djuwarso (1998) cara termudah untuk membedakan spesies lalat adalah dengan mengidentifikasi letak larva dan pupanya, yaitu dengan jalan
membelah tanaman. Apabila letak larva dan pupa ada di bawah kulit batang
biasanya O. phaseoli Ophiomyia phaseoli Try. Taksonomi
Adapun klasifikasi dari lalat bibit Ophiomyia phaseoli Try. menurut Kalshoven (1981) antara lain sebagai berikut:
Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Ordo : Diptera
Famili : Agromizidae
Genus : Ophiomyia
Biologi
Telur O. phaseoli berwarna putih susu seperti mutiara, berbentuk lonjong dan tembus cahaya (Gambar 1). Panjang telur 0,13 mm dan lebarnya 0,13 mm,
lama stadium telur berkisar antara 2-4 hari. dilapangan telur mulai ditemukan
pada tanaman berumur 5-7 hari. Puncak populasi telur pada keping biji terjadi
pada tanaman berumur enam hari (Djuwarso, 1988). Menurut Kartasapoetra
[image:19.595.219.401.276.401.2](1990) daya produksi telurnya dapat mencapai rata-rata 95 butir per lalat.
Gambar 1. Telur Ophiomyia phaseoli Try. Sumber: Deptan (2008)
Larva yang baru ditetaskan dari telur berwarna bening, tetapi instar
terakhir berwarna putih kekuningan. Bentuk larva memanjang dan ramping
(Gambar 2). Stadia rata-rata larva adalah 10 hari (Goot, 1984). Menurut
Kalshoven (1981) larva dan pupa O. phaseoli terletak pada jaringan kulit batang tanaman muda. Yang memiliki sepasang tanduk dibagian apikal dan ujung
posteriornya (proses dari pembentukan tanduk pada toraks dan spirakel pada
abdomen) pupanya memiliki dua tanduk yang terpisah.
.
Gambar 2. Larva O. phaseoli
[image:19.595.241.375.605.734.2]Pupa terbentuk di bawah epidermis kulit pada pangkal batang atau pangkal
akar. Pupa yang terbentuk berwarna kuning kecoklatan (Gambar 3), berukuran
panjang 3 mm dengan stadia pupa berkisar antara 7-13 hari. stadia pupa berkisar
antara 13-20 hari (Rusamsi, 1982).
Gambar 3. Pupa O. phaseoli
Sumber: Foto langsung.
Deptan (2008) melaporkan bahwa imago betina O. phaseoli meletakkan telur sejak tanaman kedelai muncul di atas tanah sampai sekitar dua minggu
setelah tanam (mst). Dari hasil penelitian Ginting (2009) imago O. phaseoli mulai ditemukan pada pertanaman kedelai mulai umur tanaman 6 hari setelah tanam
[image:20.595.235.391.502.647.2](hst). Imago O. phaseoli berukuran 1,9-2,2 mm, lalat kacang dewasa berwarna hitam (Gambar 4).
Gambar 4. Imago O. phaseoli
Sumber: Foto Langsung
Gejala serangan
Tanaman terserang lalat kacang ditunjukkan dari adanya bintik-bintik
putih pada keping biji atau daun pertama. Bintik-bintik tersebut merupakan luka
alur-alur coklat pada keping biji dan kulit batang yang merupakan bekas gerekan
larva. Tanaman yang tidak tahan dengan serangan larva keping biji akan cepat
gugur, tanaman layu dan akhirnya mati (Djuwarso et al. 1992).
Gerekan larva menyebabkan tanaman menjadi layu, mati dan kering
karena akar tidak dapat berfungsi normal untuk menghisap air dan unsur hara.
Tanda serangan awal berupa bintik-bintik putih pada kotiledon, daun pertama atau
daun kedua, yaitu bekas tusukan alat peletak telur lalat. Serangan larva sebelum
umur 13 hari dapat menyebabkan kematian tanaman. Ambang kendali hama lalat
bibit yaitu 1 imago per 5 m baris atau 1 imago per 50 rumpun (Deptan, 2008).
Penelitian Ginting (2009) menunjukkan gejala serangan larva pada
kotiledon mulai tampak pada umur tanaman 10 hst (Gambar 5). Pada umur 13 hst
kotiledon yang terserang larva sudah mulai menguning dan larva sudah masuk ke
dalam jaringan kulit batang. Berdasarkan hasil pengamatan gejala serangan pada
kotiledon menunjukkan pada umur kedelai 10 hst tingkat serangan mencapai
29,9% dan menjadi 65,00% pada umur 13 hst. Pada umur 17 hst kotiledon sudah
gugur dan larva sudah masuk ke dalam jaringan kulit batang sehingga gejala
serangan tidak nampak dari luar, namun pertumbuhan kedelai tampak terhambat
[image:21.595.256.369.580.727.2]atau lebih kerdil dibandingkan tanaman yang tidak terserang.
Gambar 5. Gejala serangan O. phaseoli
Insektisida monokrotofos
Organofosfat (OP) merupakan insektisida dengan unsur P sebagai inti
yang aktif. Organofosfat merupakan insektisida yang sangat beracun bagi
serangga dan bersifat baik sebagai racun kontak, racun perut, maupun fumigan.
Berbeda dengan organoklorin. Daya racun OP mampu menurunkan populasi
serangga dengan cepat. Insektisida OP menghambat bekerjanya enzim
asetilkolinestrase yang berakibat terjadi penumpukan asetilkolin dan kekacauan
pada sistem penghantaran implus ke sel-sel otot. Keadaan ini menyebabkan otot
kejang dan akhirnya terjadi kelumpuhan (paralisis) dan kematian (Untung, 2000).
Organofospat (contoh: malation, monokrotofos, paration, fosfamidon,
bromofos, diazinon, dimetoat, diklorofos, fenitrotion, fention, dan puluhan
lainnya) bekerja sebagai insektisida kontak atau sistemik. Kebanyakan
diantaranya memiliki aktivitas residu dalam waktu pendek, karena itu perlu
diaplikasikan berulang-ulang (Oka, 1999).
Monokrotofos merupakan insektisida yang termasuk dalam golongan
fosfat organik. Senyawa dari golongan pestisida ini berkerja menghambat
aktivitas enzim kolinestrase yang dapat berakit fatal pada tubuh dengan gejala
antara lain sakit kepala, pusing-pusing, lemah, pupil mengecil, gangguan
penglihatan dan sesak nafas, mual, muntah, kejang pada perut dan diare, sesak
pada dada dan detak jantung menurun (Saenong, 2012).
Insektisida sipermetrin
Sipermertin merupakan insektisida golongan Organoklorin yang
digunakan untuk mengendalikan hama pada kapas dan sayuran seperti cabai,
Sipermetrin merupakan insektisida piretroid sintesis yang telah
diformulasikan dengan berbagai merek. Insektisida ini mempunyai aktivitas yang
rendah terhadap manusia, mamalia dan burung tetapi cukup toksik terhadap ikan
atau organisme air. Sipermetrin stabil terhadap cahaya dan oksigen tetapi mudah
terdegradasi dalam tanah dan tidak dapat dilacak pengaruhnya terhadap
mikrofauna dan mikroflora (Loekman et al. 2005). Sama halnya dengan insektisida golongan organoklorin dan organofosfat, senyawa ini memiliki
dampak negatif apabila digunakan secara tidak bijaksana (Sari et al. 2012).
Organoklorin atau sering disebut Hidrokarbon Klor merupakan kelompok
insektisida sintetik yang merupakan racun kontak dan racun perut, efektif untuk
mengendlikan larva, nimfa dan imago kadang-kadang untuk pupa dan telur.
Secara umum dapat dikatakan bahwa keracunan serangga oleh organoklorin
ditandai dengan terjadinya gangguan pada sistem syaraf pusat yang
mengakibatkan terjadinya hiperaktivitas, gemetaran, kejang-kejang dan akhirnya
terjadi kerusakan syaraf dan otot serta kematian (Untung, 2000).
Insektisida nabati
Insektisida nabati adalah insektisida yang bahan dasarnya berasal dari
tanaman dan sudah lama digunakan oleh petani. Insektisida nabati dapat dibuat
dengan teknologi yang sederhana dapat berupa larutan hasil perasan, rendaman,
ekstrak rebusan dari bagian tanaman berupa akar, umbi, batang , daun, biji, dan
buah. Apabila dibandingkan dengan insektisida kimia penggunaan insektisida
nabati relatif murah dan aman. Beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan
sebagai insektisida nabati yang dapat dibuat melalui teknologi sederhana adalah:
(Swiatenia mahagoni), sirih (Peper bettle L.), dan sirsak (Annona muricata Linn) (Deptan, 2011a).
Daun sirih (Peper bettle L.)
Daun sirih mengandung minyak atsiri yang di dalamnya terdapat senyawa
fenol sebanyak 55%. Senyawa ini mempresipitasikan protein secara aktif sehingga
susunan protein berubah menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan sel, serta
merusak membran sel, dan menyebabkan terjadinya osmosis sehingga sel
mengalami lisis. Hal ini menyebabkan metabolisme di dalam sel menjadi
terganggu (Rachmawati danKorlina, 2009).
Kandungan kimia daun sirih adalah minyak atsiri 0,8 - 1,8 % (terdiri atas
chavikol, chavibetol (betel phenol), allylprocatechol (hydroxychavikol), allypyrocatechol-mono dan diacetate, karvakrol, eugenol, phenol cymene, cineole,
caryophyllene, cadinene, esragol, terpenena, seskuiterpena, fenil propane, tannin,
diastase, karoten, tiamin, riboflavin, asam nikotinat, vitamin C, gula, pati dan
asam amino. Chavikol yang menyebabkan sirih berbau khas dan memiliki khasiat
antibakteri (daya bunuh bakteri lima kali lebih kuat daripada fenol biasa)
(Arsensi, 2012).
Daun sirsak (Annona muricata Linn)
Buah mentah, biji, daun, dan akar sirsak mengandung senyawa kimia
annonain yang dapat berperan sebagai insektisida, larvasida, penolak serangga
(repellent), dan anti-feedant dengan cara kerja sebagai racun kontak dan racun
perut. Selain itu daun sirsak juga mengandung senyawa acetogenin antara lain
Riyanto (2009) melaporkan ekstrak daun sirsak terbukti efektif untuk
dijadikan bahan repelen (penolak). Sifat repelen disebabkan karena adanya bau
yang sangat tajam. Dari hasil penelitiannya didapati dalam waktu 96 jam fumigasi
dengan ekstrak sirsak lebih toksik dibandingkan fumigasi ekstrak lengkuas dan
beluntas terutama pada konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%. Pada konsentrasi ini sifat
toksik fumigasi ekstrak sirsak sama dengan sifat toksik karbofuran dengan waktu
fumigasi 48 jam dengan konsentrasi 0,25%.
Bacillus thuringiensis
Berdasarkan hasil penelitian Salaki dan Sembiring (2006) dari ciri-ciri
morfologi sel dan koloni diperoleh 32 isolat bakteri B. thuringiensis. Ke 32 isolat tersebut pada media biakan menunjukkan morfologi koloni berbentuk ireguler,
permukaan koloni kasar, datar dan agak mengkilap, warna koloni putih
kekuningan. Sel vegetatif berbentuk batang dengan spora sub terminal.
Bersamaan dengan terbentuknya spora dibentuk pula benda berupa kristal yang
berada dekat spora yang dikenal dengan nama kristal protein yang merupakan
bahan toksik terhadap serangga.
Gama et al. (2010) melaporkan ada tanda-tanda kerusakan epitel dan saluran pencernaan yang timbul akibat aktivitas kristal protein (toksin) yang
dihasilkan oleh B. thuringiensis isolat Madura. Pada jaringan usus tampak berlubang dan pada tepi lubang-lubang tersebut tampak warna gelap (hitam) yang
mengelilingi jaringan tersebut. Hal ini disebabkan karena aktivitas kristal protein
Beauveria bassiana
Jamur entomopatogen B. bassiana memproduksi beauvericin yang mengakibatkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga inang.
Seperti umumnya jamur, B. bassiana menginfeksi serangga inang melalui kontak fisik, yaitu dengan menempelkan konidia pada integumen. Perkecambahan
konidia terjadi dalam 1-2 hari kemudian dan menumbuhkan miselianya di dalam
tubuh inang. Serangga yang terinfeksi biasanya akan berhenti makan sehingga
menyebabkan imunitasnya menurun, 3- 5 hari kemudian mati dengan ditandai
adanya pertumbuhan konidia pada integumen (Decianto danIndriyani, 2009).
Selanjutnya Soetopo dan Indriyani (2007) melaporkan konidia B. bassiana
dapat diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada kanopi tanaman, ditaburkan
pada permukaan tanah, atau dicampur dengan tanah atau kompos. Temperatur dan
kelembaban adalah faktor abiotik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
konidia B. bassiana, cahaya melalui panjang gelombang sinar ultraviolet juga berpotensi merusak konidia sehingga aplikasi pada pagi (di bawah pukul 08.00)
atau sore hari (di atas pukul 15.00) dapat menghindari kerusakan B. bassiana
BAHAN DAN METODE Tempat dan waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota,
Kotamadya Binjai dengan ketinggian tempat + 25 m dpl. Penelitian dilaksanakan
pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2013.
Bahan dan alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih tanaman kedelai
varietas Grobogan (Balai Benih Biogen, Bogor), pupuk urea, pupuk TSP, pupuk
KCL, daun sirih, daun sirsak, insektisida monokrotofos (Azodrin 15 WSC),
insektisida sipermetrin (Cypermax 100 EC), insektisida biologi B. thuringiensis
(Bite FC), insektisida biologi B. bassiana (Beauverin P).
Alat yang digunakan adalah cangkul, gembor, meteran, blender,
timbangan, kain saring, handsprayer, gelas ukur, kamera digital, lup, mikroskop,
pisau lipat, alat tulis dan alat-alat lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
percobaan.
Metode penelitian
Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)
non-faktorial dengan 7 perlakuan dan 3 ulangan.
Mencari ulangan (r) :
(t-1)(r-1) > 15
(7-1)(r-1) > 15
6(r-1) > 15
6r – 6 > 15
Adapun perlakuan yang digunakan adalah :
P0 : Kontrol
P1 : Daun sirsak 200 gram/liter air (Konsentrasi larutan 20%)
P2 : Daun sirih 200 gram/liter air (Konsentrasi larutan 20%)
P3 : Insektisida berbahan aktif Monokrotofos 3 ml/liter air
P4 : Insektisida berbahan aktif Sipermetrin 1 ml/liter air
P5 : Bacillus thuringiensis 1 ml/liter air (109) P6 : Beauveria bassiana 10 gram/liter air (107)
Jumlah Perlakuan : 7
Jumlah Ulangan : 3
Jarak Tanam : 20 cm x 25 cm
Jumlah Plot Lahan : 21 Plot
Luas Tiap Plot Lahan : 2 m x 2 m
Luas Lahan Seluruhnya : 160 m2
Jarak Antar Plot : 50 cm
Lebar Parit Keliling : 75 cm
Jumlah Tanaman Tiap Plot : 63 Tanaman
Jumlah Tanaman Sampel Tiap Plot : 5 Sampel
Jumlah Tanaman Seluruhnya : 1323 Tanaman
Jumlah Tanaman Sampel yang diambil Seluruhnya : 105 Tanaman
Data dianalisis dengan sidik ragam menggunakan model linear:
Yij= µ + τi+ βj + ∑ij
Yij = respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
τi = pengaruh perlakuan ke-i
βj = Pengaruh blok ke-j
∑ij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
Pelaksanan penelitian Persiapan lahan
Persiapan lahan diawali dengan membabat gulma dan mencangkul lahan
untuk memperoleh tekstur tanah yang lebih gembur. Plot percobaan berukuran
2 m x 2 m dengan jarak antar plot 0,5 m dan lebar parit tepi 0,75 m.
Penanaman
Kedelai yang ditanam adalah varietas Grobogan. Benih ditanam dengan
sistem tugal. Lubang dibuat sedalam 5 cm dengan jarak tanam 20 x 25 cm. Pada
satu lubang diberi 2 benih kedelai untuk menghindari resiko benih gagal
berkecambah.
Pemeliharaan tanaman Pemupukan
Pemupukan dasar dilakukan pada saat sebelum bibit ditanam. Pemupukan
dilakukan dengan cara ditabur. Kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum
penanaman, agar pada saat penanaman hara sudah tersedia bagi benih kedelai
yang akan berkecambah. Pemupukan dengan pupuk dasar urea 100 kg/ha, TSP
200 kg/Ha dan KCl diberikan dengan dosis 150 kg/ha (Sinaga, 2009).
Penyiraman
Penyiraman dilakukan setiap hari, banyaknya air yang diberikan sesuai
kebutuhan agar tanah tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Penyiraman
Penyulaman
Penyulaman dilakukan dengan menggantikan tanaman yang tidak tumbuh
dengan tanaman baru yang berumur sama. Penyulaman dilakukan pada saat
tanaman berumur satu minggu.
Penjarangan
Penjarangan dilakukan untuk mengurangi tanaman yang pada satu lubang
tanam ditumbuhi dua kecambah atau lebih. Penjarangan dilakukan dengan
menggunting salah satu tanaman yang pertumbuhannya lebih terhambat.
Penyiangan
Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh pada lahan
budidaya, penyiangan dilakukan setiap ada gulma yang tumbuh.
Persiapan insektisida Larutan sirih
Diambil daun tanaman sirih sebanyak 200 gram kemudian dicuci,
dihaluskan menggunakan blender dengan 1 liter air. Pemberian air ke dalam
blender dapat dilakukan sedikit demi sedikit, lalu sisa air dapat ditambahkan pada
larutan sirih yang telah selesai di blender. Kemudian larutan disaring
menggunakan kain saring lalu dimasukkan ke dalam botol dan didiamkan selama
satu malam untuk mengendapkan ampas dari daun sirih. Setelah 24 jam larutan
daun sirih di pindahkan ke botol lain secara perlahan agar endapan tidak
tercampur kembali (Deptan, 2011a).
Larutan sirsak
Diambil daun tanaman sirsak sebanyak 200 gram kemudian dicuci,
blender dapat dilakukan sedikit demi sedikit, lalu sisa air dapat ditambahkan pada
larutan sirsak yang telah selesai di blender. Kemudian larutan disaring
menggunakan kain saring lalu dimasukkan ke dalam botol dan didiamkan selama
satu malam untuk mengendapkan ampas dari daun sirih. Setelah 24 jam larutan
daun sirih di pindahkan ke botol lain secara perlahan agar endapan tidak
tercampur kembali (Deptan, 2011a).
Insektisida kimia
Insektisida kimia yang digunakan dalam penelitian ini berbahan aktif
monokrotofos (Azodrin 15 WSC) dengan dosis anjuran 3 ml/liter air dan
insektisida kimia yang berbahan aktif sipermetrin (Cypermax 100 EC) dengan
dosis anjuran 1 ml/liter air.
Insektisida biologi
Insektisida biologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
B. thuringiensis (Bite FC) dan B. bassiana (Beauverin P). Dosis yang digunakan
adalah 1 ml/liter air untuk B. thuringiensis (109) dan 10 gr/liter air untuk
B. bassiana (107). Aplikasi insektisida
Pengaplikasian insektisida dilakukan sebanyak dua kali. Aplikasi pertama
pada saat tanaman berumur 4 hari dan aplikasi kedua pada saat tanaman berumur
10 hari. Aplikasi insektisida sesuai dengan perlakuan masing-masing.
Pengaplikasian insektisida dilakukan pada sore hari. Penyemprotan dilakukan
sampai membasahi seluruh bagian tanaman dengan volume semprot 2 ml/tanaman
Pengambilan sampel
Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan sampel random
sederhana. Tiap populasi diberi nomor kemudian sampel yang diinginkan ditarik
secara random dengan menggunakan undian biasa (Nazir, 2009).
Peubah amatan
Persentase serangan
Pengamatan persentase serangan pada tanaman kedelai dimulai setelah
satu hari setelah aplikasi (hsa), yaitu pada saat tanaman berumur 5 hari setelah
tanam (hst), dan dilakukan dengan interval lima hari sekali yaitu pada 5 hst,
10 hst, 15 hst dan 20 hst. Persentase serangan dihitung dengan menggunakan
rumus :
PS =A
B x 100%
Dimana :
PS = Persentase Serangan
A = Jumlah tanaman sampel yang terserang
B = Jumlah keseluruhan tanaman sampel
(Ginting, 2009).
Jumlah larva lalat bibit
Perhitungan larva dilakukan pada saat tanaman berumur 10 hst, 15 hst, dan
20 hst, dilakukan dengan cara membelah batang tanaman kedelai dan kulit batang
kedelai lalu diamati di bawah mikroskop. Perhitungan larva dilakukan dengan
Jumlah pupa lalat bibit
Perhitungan pupa dilakukan pada saat tanaman berumur 15 hst, dan 20 hst,
dilakukan dengan cara membelah batang tanaman kedelai dan kulit batang kedelai
lalu diamati di bawah mikroskop. Perhitungan pupa dilakukan dengan mengambil
5 sampel tanaman.
Jumlah imago lalat bibit
Perhitungan hama dilakukan dengan mengamati 1 plot tanaman.
Pengamatan dilakukan pada pukul 07.00 pagi dan diambil pada 5 hst, 10 hst,
15 hst dan 20 hst.
Waktu munculnya gejala
Pengamatan waktu munculnya gejala dilakukan dengan mengamati waktu
munculnya gejala pertama kali pada sampel tanaman kedelai untuk setiap
perlakuan di lapangan. Pengamatan dilakukan mulai dari tanaman berusia 3 hst
HASIL DAN PEMBAHASAN Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli (%)
Berdasarkan data pengamatan dan tabel sidik ragam (lampiran 3-6)
diketahui bahwa perlakuan pemberian beberapa jenis insektisida pada tanaman
kedelai berpengaruh sangat nyata terhadap persentase serangan pada 10 hst.
[image:34.595.111.514.262.496.2]Persentase serangan 5-20 hst dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli
Perlakuan insektisida
Persentase serangan (%)
5 hst 10 hst 15 hst 20 hst
P0 13,33 (19,06) 40,00 (39,23) a 26,76 (27,13) 6,67 (11,56) P1 0,00 (4,05) 0,00 (4,05) c 20,00 (23,28) 6,67 (11,56) P2 13,33 (19,06) 20,00 (23,28) abc 33,33 (31,35) 0,00 (4,05) P3 6,67 (11,56) 20,00 (23,28) abc 26,67 (30,79) 6,67 (11,56) P4 6,67 (11,56) 33,33 (35,01) ab 33,33 (35,01) 0,33 (4,62) P5 6,67 (11,56) 0,00 (4,05) c 20,00 (23,28) 13,33 (15,78) P6 0,00 (4,05) 13,33 (19,06) c 26,67 (30,79) 0,00 (4,05) Keterangan: P0: kontrol, P1: daun sirsak 200 gr/l air, P2: daun sirih 200 gr/l air,
P3: monokrotofos 3 ml/l air, P4: sipermetrin 1 ml/l air, P5: B. thuringiensis 1 ml/l air, P6: B. bassiana 10 gr/l air. Angka
yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% menurut Uji Jarak Duncan. Angka di dalam kurung merupakan hasil transformasi �������+ 0,5.
Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli diamati dengan memperhatikan gejala yang timbul pada tanaman kedelai. Pada penelitian ini persentase serangan
lalat bibit pada 5, 15 dan 20 hst tidak berbeda nyata untuk semua perlakuan.
Sedangkan pada 10 hst persentase serangan tertinggi (40,00%) terdapat pada
perlakuan P0 (kontrol) tidak berbeda nyata dengan P2 (daun sirih 200 gr/l air), P3
(monokrotofos 3 ml/l air), dan P4 (sipermetrin 1 ml/l air) tetapi berbeda sangat
mengendalikan O. phaseoli dibanding perlakuan lainnya. Kemampuan daun sirsak dalam mengendalikan O. phaseoli disebabkan oleh bau yang sangat tajam dari daun sirsak, yang berfungsi sebagai bahan repelent (penolak) serangga. Hal ini sesuai dengan literatur Riyanto (2009) yang menyatakan bahwa ekstrak daun
sirsak terbukti efektif untuk dijadikan bahan repelent (penolak) serangga. Hal yang sama juga terjadi pada B. thuringiensis dan B. bassiana yang mampu menekan persentase serangan lalat bibit, hal ini dikarenakan B. thuringiensis
menghasilkan kristal protein yang bersifat toksik terhadap serangga.
Salaki dan Sembiring (2006) yang menyatakan B. thuringiensis menghasilkan kristal protein yang bersifat toksik terhadap serangga yang berada didekat spora
yang merupakan sel vegetatif. Sedangkan B. bassiana memproduksi beauvericin yang mengakibatkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga
inang, Decianto dan Indriyanto (2009) yang menyatakan jamur entomopatogen
B. bassiana memproduksi beauvericin yang mengakibatkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga inang dan menginfeksi serangga inang melalui
kontak fisik.
Dari Tabel 1 terlihat persentase serangan hama lalat bibit O. phaseoli pada perlakuan P0 (kontrol) tidak berbeda dengan perlakuan P4 (Sipermetrin 1 ml/l air)
yaitu 33,33%. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya kekebalan hama terhadap
insektisida kimia atau sering juga disebut sebagai resistensi hama. Resistensi
hama ini terjadi akibat pemakaian insektisida kimia dengan tidak bijaksana dan
terus menerus. Bahagiawati (2001) menyatakan kasus hama berkembang menjadi
resisten juga telah terjadi di Indonesia pada awal tahun 1970 pada tanaman padi.
spesies serangga berkembang menjadi resisten. Selanjutnya Deptan (2011)
menyatakan penggunaan insektisida kimia secara tidak bijaksana dapat
menyebabkan timbulnya resistensi (kekebalan), sehingga untuk mengatasi
organisme pengganggu yang resisten perlu dosis yang lebih tinggi.
Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui gejala serangan O. phaseoli
berupa adanya lubang tusukan pada kotiledon yang merupakan bekas tusukan
ovipositor lalat bibit betina pada saat meletakkan telur. Selain itu terdapat gerekan
pada kotiledon yang merupakan aktivitas jalur makan larva yang baru menetas
pada kotiledon (Gambar 6 a.) sebelum akhirnya turun ke batang dan berdiam di
pangkal batang dekat leher akar sampai menjadi pupa, yang dapat menyebabkan
terbelahnya kulit batang di dekat leher akar (Gambar 6 b). Pada serangan berat
dapat menyebabkan kematian tanaman yang biasanya diikuti dengan pangkal
batang yang patah dan tanaman mengering (Gambar 6 c). Djuwarso et al. (1992) menyatakan bahwa tanaman terserang lalat bibit ditunjukkan dari adanya
bintik-bintik yang merupakan luka bekas tusukan ovipositor lalat bibit, selain itu gejala
serangan ditunjukkan dari alur-alur coklat pada keping biji dan kulit batang yang
merupakan bekas gerekan larva, tanaman yang tidak tahan dengan serangan larva
keping biji akan cepat gugur, tanaman layu dan akhirnya mati.
[image:36.595.111.513.583.692.2](a) (b) (c)
Jumlah larva lalat bibitO. phaseoli (ekor)
Berdasarkan data pengamatan dan hasil sidik ragam (lampiran 7-10)
diketahui bahwa perlakuan pemberian beberapa jenis insektisida berpengaruh
sangat nyata terhadap jumlah larva O. phaseoli pada 10 hst. Dimana rataan tertinggi terdapat pada perlakuan P4 (Sipermetrin 1 ml/l air) yaitu 1,00 larva.
Sedangkan rataan terendah (0,00 ekor) terdapat pada perlakuan P1 (daun sirsak
200 gr/l air) dan P5 (B. thuringiensis 1 ml/l air). Rataan jumlah larva lalat bibit
O. phaseoli dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Jumlah larva lalat bibit O. phaseoli
Perlakuan Rataan jumlah larva O. phaseoli (ekor)
insektisida 5 hst 10 hst 15 hst 20 hst
P0 0,00 (0,71) 0,67 (1,00) ab 0,67 (1,05) 0,00 (0,71) P1 0,00 (0,71) 0,00 (0,71) b 0,00 (0,71) 0,33 (0,88) P2 0,00 (0,71) 0,33 (0,88) ab 1,33 (1,27) 0,00 (0,71) P3 0,00 (0,71) 0,33 (0,88) ab 0,67 (1,00) 0,00 (0,71) P4 0,00 (0,71) 1,00 (1,17) a 1,33 (1,29) 0,00 (0,71) P5 0,00 (0,71) 0,00 (0,71) b 0,33 (0,88) 0,33 (0,88) P6 0,00 (0,71) 0,67 (1,05) ab 0,67 (1,00) 0,00 (0,71) Keterangan: P0: kontrol, P1: daun sirsak 200 gr/l air, P2: daun sirih 200 gr/l air,
P3: monokrotofos 3 ml/l air, P4: sipermetrin 1 ml/l air, P5: B. thuringiensis 1 ml/l air, P6: B. bassiana 10 gr/l air. Angka
yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% menurut Uji Jarak Duncan. Angka di dalam kurung merupakan angka hasil transformasi ��+ 0,5.
Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah larva pada 5,
15, dan 20 hst tidak berbeda nyata pada semua perlakuan, sedangkan pada
pengamatan 10 hst jumlah larva tertinggi (1,00 ekor) terdapat pada perlakuan P4
(Insektisida Sipermetrin 1 ml/liter air) tidak berbeda nyata dengan perlakuan P0
(kontrol), P2 (daun sirih 200 gr/l air), P3 (B. thuringiensis 1 ml/l air), dan P6 (B. bassiana 10 gr/l air), tetapi berbeda sangat nyata dengan P1 (daun sirsak 200
sipermetrin yang digunakan dalam penelitian ini termasuk insektisida racun
kontak dan perut, sedangkan larva O. phaseoli terdapat di dalam kotiledon dan di bawah permukaan kulit batang, jadi tidak memungkinkan untuk mengenai larva
secara langsung (kontak langsung) oleh karena itu efektifitasnya menjadi kurang
maksimal. Untung (2000) menyatakan insektisida kontak memasuki tubuh
serangga apabila serangga mengadakan kontak langsung dengan insektisida atau
serangga berjalan di atas permukaan tanaman yang telah mengandung insektisida.
Berdasarkan hasil pengamatan di bawah mikroskop dengan perbesaran
10 x 40 diketahui bahwa larva yang diperoleh pada 5 hst, 10 hst, 15 hst, dan 20 hst
adalah larva O. phaseoli (Gambar 7). Larva ini terletak di bawah epidermis batang. Dari Gambar 7 (a) ini dapat dilihat bahwa larva memiliki sepasang tanduk
pada bagian anterior dan ujung posteriornya. Ukuran rata-rata larva yaitu panjang
3 mm dan lebarnya 0,95 mm. Kalshoven (1981) menyatakan larva dan pupa
O. phaseoli terletak pada jaringan kulit batang tanaman muda, memiliki sepasang tanduk di bagian apikal dan ujung posteriornya (proses dari pembentukan tanduk
pada toraks dan spirakel pada abdomen).
(a) (b)
Gambar 7. (a) larva O. phaseoli, (b) larva O. phaseoli yang berada pada bawah permukaan kulit batang
Dari data penelitian yang didapat rataan jumlah keseluruhan larva tertinggi
[image:38.595.122.490.521.661.2]meletakkan telur pada saat tanaman muncul di atas permukaan tanah
(rata-rata 5 hst), menetas 2-4 hari kemudian, menggerek kotiledon dan akhirnya
turun ke dalam batang, dan mengerek batang, berdiam di sekitar leher akar selama
kurang lebih 10 hari dan akhirnya menjadi pupa. Djuwarso (1988) menyatakan di
lapangan telur mulai ditemukan pada tanaman berumur 5-7 hari, puncaknya pada
umur 6 hari, lama stadium telur berkisar antara 2-4 hari. Menurut Goot (1984)
stadia rata-rata larva adalah 10 hari.
Dari hasil pengamatan diketahui pada saat tanaman berumur 5 hst tidak
ada larva yang ditemukan (Tabel 2). Hal ini dikarenakan pada saat tanaman
berumur 5 hst tanaman kedelai baru mulai tumbuh dan membuka kotiledonnya.
Lalat O. phaseoli baru mulai meletakkan telurnya pada saat kotiledon telah membuka. Deptan (2008) menyatakan imago betina O. phaseoli meletakkan telur sejak tanaman muncul di atas tanah sampai dua minggu setelah tanam (mst).
Sedangkan Ginting (2009) menyatakan imago O. phaseoli mulai ditemukan pada pertanaman kedelai sejak 6 hari setelah tanam (hst).
Jumlah pupa lalat bibit O. phaseoli (ekor)
Berdasarkan data pengamatan dan hasil sidik ragam (lampiran 11-12)
diketahui bahwa perlakuan pemberian beberapa jenis insektisida berpengaruh
tidak nyata terhadap jumlah larva O. phaseoli pada 15 dan 20 hst. Dimana rataan tertinggi terdapat pada perlakuan P4 (Sipermetrin 1 ml/l air) yaitu 1,00 pupa.
Sedangkan rataan terendah (0,00 ekor) terdapat pada perlakuan P1 (daun sirsak
200 gr/l air) dan P5 (B. thuringiensis 1 ml/l air). Rataan jumlah pupa lalat bibit
Tabel 3. Jumlah pupa lalat bibit O. phaseoli
Perlakuan insektisida Jumlah pupa O. phaseoli (ekor) 15 hst 20 hst
P0 (kontrol) 0,00 (0,71) 0,67 (1,05)
P1 (daun sirsak 200 gr/l air) 0,00 (0,71) 0,00 (0,71) P2 (daun sirih 200 gr/l air) 0,33 (0,88) 0,33 (0,88) P3 (insektisida monokrotofos 3 ml/l air) 0,33 (0,88) 0,33 (0,88) P4 (insektisida sipermetrin 3 ml/l air) 0,00 (0,71) 1,00 (1,17) P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air) 0,00 (0,71) 0,00 (0,71) P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air) 0,00 (0,71) 0,33 (0,88) Keterangan: Angka di dalam kurung merupakan angka hasil transformasi
��+ 0,5.
Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pupa pada 15
dan 20 hst tidak berbeda nyata pada semua perlakuan. Pada perlakuan
P0 (kontrol), P1 (daun sirsak 200 gr/l air), P4 (insektisida sipermetrin 3 ml/l air),
P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air), dan P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air) pada 15 hari tidak terdapat pupa, padahal pada pengamatan jumlah larva sebelumnya
terdapat larva. Tidak terdapatnya pupa dapat disebabkan oleh beberapa hal,
diantaranya larva belum berubah menjadi pupa karena siklus hidup dari telur
sampai menjadi pupa berlangsung antara 11-14 hari. Sedangkan lalat bibit
meletakkan telur pada saat tanaman berumur 4-5 hari. Selain itu faktor lingkungan
dan cuaca juga mempengaruhi siklus hidup lalat bibit. Pada saat tanaman berumur
7 hari, curah hujan mulai tinggi sehingga keberhasilan pertumbuhan larva menjadi
pupa menjadi rendah. Djuwarso (1988) menyatakan lama stadium telur O. phaseoli berkisar antara 2-4 hari, dan stadia larva pada dataran rendah rata-rata 10 hari dan di daerah yang temperaturnya lebih rendah, stadia larva berlangsung
lebih lama antara 17-22 hari. Kelembaban dan curah hujan merupakan faktor
cuaca yang berperan dalam kelimpahan imago, telur dan pupa lalat bibit. Semakin
rendah kelembaban, populasi imago dan telur semakin meningkat, dan semakin
Dari hasil penelitian diketahui jumlah larva tertinggi terdapat pada
perlakuan P4 (Sipermetrin 1 ml/l air) yaitu 1,00 pupa. Sedangkan rataan terendah
(0,00 pupa) terdapat pada perlakuan P1 (daun sirsak 200 gr/l air) dan P5 (B. thuringiensis 1 ml/l air). Hal ini disebabkan oleh insektisida sipermetrin yang digunakan termasuk dalam golongan racun kontak, sedangkan pupa O. phaseoli
terdapat di dalam pangkal batang tanaman kedelai sehingga insektisida
sipermetrin tidak dapat mengenai larva secara langsung. Sedangkan daun sirsak
merupakan golongan racun perut yang berperan sebagai larvasida yang dapat
mematikan larva sebelum berubah menjadi pupa. Ruliansyah et al. (2009) menyatakan bahwa buah mentah, biji, daun dan akar sirsak mengandung senyawa
anonain yang dapat berperan sebagai insektisida, larvasida, penolak makan, dan
penolak serangga sebagai racun kontak dan racun perut. Hal yang sama juga
terjadi pada B. thuringiensis termasuk golongan racun perut yang dapat menghasilkan kristal protein yang toksik pada serangga. Gama et al. (2010) menyatakan B. thuringiensis menghasilkan kristal protein yang toksik terhadap serangga dan menyebabkan kerusakan epitel dan saluran pencernaan serangga.
Dari hasil pengamatan di bawah mikroskop dengan perbecaran 4 x 10
terbukti bahwa pupa yang terletak di bawah permukaan kulit tanaman kedelai di
dekat leher akar (Gambar 8 b) adalah pupa O. phaseoli. Dengan ciri pupa
berwarna kuning kecoklatan, ukuran rata-rata panjang 3 mm dan lebar 0,9 mm
(Gambar 8 a). Pupa memiliki kulit yang keras dan sepasang tanduk yang terpisah.
Rusamsi (1982) menyatakan pupa terbentuk di bawah epidermis kulit pada
pangkal batang atau pangkal akar. Pupa yang terbentuk berwarna kuning
[image:42.595.121.525.93.282.2]
(a) (b)
Gambar 8. (a) Pupa O. phaseoli dibawah mikroskop perbesaran 4 x 10, (b) kulit
batang tanaman kedelai yang sudah dikelupas dan terdapat pupa
O. phaseoli
Jumlah imago lalat bibitO. phaseoli (ekor)
Dari data pengamatan yang diperoleh dan hasil sidik ragam (lampiran
11-14) diketahui bahwa perlakuan pemberian beberapa jenis insektisida
berpengaruh nyata terhadap jumlah imago lalat bibit O. phaseoli pada 20 hst. Rataan jumlah imago lalat bibit O. phaseoli dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Jumlah imago lalat bibit O. phaseoli
Perlakuan insektisida
Jumlah imago O. phaseoli (ekor)
5 hst 10 hst 15 hst 20 hst
P0 1,67 (1,46) 4,33 (2,20) 1,67 (1,35) 1,33 (1,29) ab P1 1,33 (1,34) 2,67 (1,76) 1,00 (1,10) 0,00 (0,71) b P2 2,33 (1,68) 3,33 (1,95) 1,00 (1,17) 1,00 (1,17) ab P3 2,00 (1,58) 4,00 (2,12) 1,33 (1,27) 0,67 (1,05) ab P4 1,67 (1,46) 2,76 (1,74) 1,00 (1,17) 1,33 (1,34) a P5 2,00 (1,56) 3,33 (1,95) 1,00 (1,17) 1,33 (1,29) ab P6 1,33 (1,34) 3.67 (2,04) 1,00 (1,22) 1,00 (1,17) ab Keterangan: P0: kontrol, P1: daun sirsak 200 gr/l air, P2: daun sirih 200 gr/l air,
P3: monokrotofos 3 ml/l air, P4: sipermetrin 1 ml/l air, P5: B. thuringiensis 1 ml/l air, P6: B. bassiana 10 gr/l air. Angka
yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% menurut Uji Jarak Duncan. Angka di dalam kurung merupakan angka hasil transformasi ��+ 0,5.
Dari hasil sidik ragam diketahui bahwa pada jumlah imago 5, 10, dan
15 hst tidak berbeda nyata pada semua perlakuan. Sedangkan pada 20 hst
[image:42.595.112.516.439.676.2]dengan P1 (daun sirsak 200 gr/l air, jumlah imago 0,00 ekor). Hal ini
menunjukkan daun sirsak efektif untuk mengusir hama lalat bibit O. phaseoli
karena daun sirsak memiliki kandungan senyawa kimia annonain yang dapat
berperan sebagai insektisida, larvasida dan anti-feedant dengan cara kerja sebagai racun kontak dan racun perut. Tohir (2010) menyatakan daun sirsak mengandung
senyawa kimia annonain yang dapat berperan sebagai insektisida, larvasida,
penolak serangga dan bekerja sebagai racun kontak dan racun perut. Selain itu
acetogenin antara lain, asimisin, bulatacin, dan squamosin.
Mendukung hasil pengamatan dan identifikasi pada larva sebelumnya, dari
hasil pengamatan dan identifikasi terdapat lalat bibit yang menyerang tanaman
kedelai di penelitian ini adalah spesies O. phaseoli (Gambar 9 a dan b). Hal ini ditandai dengan ukuran rata-rata panjang tubuh lalat bibit yang diperoleh yaitu 1,9
mm dan lebarnya 0,7 mm. Dari hasil pengamatan rata-rata panjang tubuh lalat
apabila sayap dikembangkan adalah 3,2 mm dan lalat ini berwarna hitam
(Gambar 9 a). Ginting (2009) menyatakan imago O. phaseoli berukuran 1,9-2,2 mm, lalat dewasa berwarna hitam.
(a) (b)
[image:43.595.126.495.527.656.2]Waktu munculnya gejala (hst)
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan gejala awal yang diperoleh
[image:44.595.118.510.227.351.2]pada tanaman kedelai akibat serangan lalat bibit O. phaseoli adalah adanya lubang bekas tusukan ovipositor oleh O. phaseoli betina. Waktu munculnya gejala pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Waktu munculnya gejala serangan lalat bibit O. phaseoli
Perlakuan Waktu muncul gejala (hst)
P0 (kontrol) 5
P1 (daun sirsak 200 gr/l air) 6
P2 (daun sirih 200 gr/l air) 5
P3 (insektisida monokrotofos 3 ml/l air) 5 P4 (insektisida sipermetrin 3 ml/l air) 5 P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l air) 5 P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air) 6
Gejala serangan mulai nampak pada 5-6 hst (Gambar 10 a). Gejala awal
yang terlihat adalah adanya bekas tusukan ovipositor hama lalat bibit betina yang
akan meletakkan telurnya pada kotiledon tanaman kedelai yang sudah membuka
pada umur 5 hst (Gambar 10 b). Hal ini sesuai dengan Djuwarso (1988) yang
menyatakan di lapangan telur mulai ditemukan pada tanaman berumur 5-7 hari.
Puncak populasi telur pada keping biji terjadi pada tanaman berumur enam hari.
(a) (b)
[image:44.595.128.504.537.684.2]KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Persentase serangan lalat bibit O. phaseoli mencapai puncaknya pada saat tanaman kedelai berumur 15 hari setelah tanam (hst), sedangkan jumlah lalat
bibit O. phaseoli mencapai puncaknya pada saat tanaman berumur 10 hst. 2. Perlakuan P1 (daunsirsak 200 gr/l air, 0,00%), P5 (Bacillus thuringiensis 1 ml/l
air, 0,00%) dan P6 (Beauveria bassiana 10 gr/l air, 13,33%) efektif dalam menekan persentase serangan lalat bibit.
3. Perlakuan P1 (daunsirsak 200 gr/l air, 0,00 ekor) dan P5 (Bacillus thuringiensis
1 ml/l air, 0,00 ekor) efektif dalam menekan jumlah larva lalat bibit
4. Perlakuan P1 (daunsirsak 200 gr/l air, 0,00 ekor) efektif dalam menekan
jumlah imago lalat bibit.
5. Waktu munculnya gejala serangan antara 5-6 hst.
Saran
Dari 7 perlakuan yang diuji, perlakuan yang disarankan untuk
DAFTAR PUSTAKA
Arsensi I. 2012. Pengaruh Pemberian ekstrak Daun sirih Terhadap Penyebab Penyakit Bulai Pada Tanaman Jagung Manis (Zea mays L.
Sacaracharata). Ziraa’ah 33(1):17-21.
Bahagiawati. 2001. Manajemen Resistensi Serangga Hama pada Pertanaman Tanaman Transgenik Bt. Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan, Bogor. Diunduh dari
[BPS] Badan Resmi Statistik. 2012. Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai. 15(7):1-10. Diunduh dari
Decianto S & I G A A Indriyani. 2009. Jamur Entomopatogen Beauveria bassiana: Potensi dan Prospeknya dalam Pengendalian Hama Tungau.
Perspektif 8(2):65-73.
[Deptan] Departemen Pertanian. 2011a. Pengendalian Hama dan Penyakit dengan Pestisida Nabati. Diunduh dari tanggal 25 Maret 2013.
______. 2011b. Pedoman Pembinaan penggunaan Pestisida. Diunduh dari http://ppvt.setjen.deptan.go.id pada tanggal 26 Juli 2013
______. 2008. Lebih Dekat Mengenal Lalat Kacang (Agromyza phaseoli) Hama Pada Tanaman Kedelai. Diunduh dari tanggal 25 Maret 2013.
Djuwarso T. 1988. Bioekologi, Serangan, dan Pengendalian Lalat Kacang. Balai
Penelitian Tanaman Pangan, Bogor.
Djuwarso T; D M Arsyad; & I B G Suryawan. 1992. Uji Lapangan Varietas Kedelai Terhadap Hama Lalat Kacang Ophiomyia phaseoli (Tryon) (Diptera: Agromyzidae) Balai Penelitian Tanaman Pangan, Bogor.
Gama Z P; B Yanuwiadi; & T H Kurniati. 2010. Strategi Pemberantasan Nyamuk Aman Lingkungan: Potensi Bacillus thuringiensis Isolat Madura Sebagai Musuh Alami Nyamuk Aedes aegypti. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari 1(1):1-10.
Ginting Y F. 2009. Perkembangan Lalat Bibit Ophiomyia phaseoli Try. (Diptera: Agromyzidae) Pada Tanaman Kedelai. Skripsi Institut Pertanian Bogor, Bogor. Halaman 6-17.
Kalshoven L G E. 1981. The Pest of Crops in Indonesia. Revised by van der Laan. PT Ichtiar Baru-Van Hoeeve. Jakarta.
Kartasapoetra A G. 1990. Hama tanaman Pangan dan Perkebunan. Bumi Aksara. Jakarta.
Loekman U; H Suyani; E Munaf; & R Zein. 2005. Penentuan Sipermetrin dan Permetrin Sebagai Residu Pestisida Dalam Kubis Secara HPLC. Jurnal Kimia Andalas. 11(1):21-24.
Marwoto. 1997. Rakitan Teknologi PHT pada Tanaman Kedelai. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-Umbian, Malang.
Meirina T; S Darmanti; & S Haryanti. 2008. Produktivitas Kedelai (Glycine max (L.) Merril var. Lokon) Yang Diperlakukan Dengan Pupuk
Organik Cair Lengkap Pada Dosis Dan Waktu Pemupukan Yang Berbeda.
Nazir M. 2009. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor.
Oka I N. 1999. Pengendalian Hama Terpadu dan Implementasinya di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Prihatman K. 2000. Kedelai (Glycine max L.). Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Diunduh dari
Rachmawati D & E Korlina. 2009. Pemanfaatan Pestisda Nabati Untuk Mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jawa Timur. Diunduh dari
Riyanto. 2009. Potensi Lengkuas (Languas galangal L.), Beluntas (Pluchea indica L.), dan Sirsak (Annona muricata L.) sebagai Insektisida
Nabati Kumbang Kacang Hijau Callosobruchus chinensis L. (Coleoptera : Bruchidae). 6(2):58-66.
Ruliansyah A; W Ridwan & A J Kusnandar. 2009. Efikasi Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Sirsak (Anona muricata) Terhadap Jentik Nyamuk Culex quinquefasciatus. Aspirator 1(1):46-50
Rusamsi E K. 1982. Sebaran dan Penarikan Contoh Telur dan Larva Agromyza phaseoli Coq. Pada Kedelai. Tesis Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Salaki C L & L Sembiring. 2006. Eksplorasi Bakteri Bacillus thuringiensis Dari Berbagai Habitat Alami yang Berpotensi Sebagai Agensia Pengendalian Hayati Nyamuk Aedes aegypti Linn.
Sinaga S W. 2009. Pengaruh Pemberian Insektisida Nabati Terhadap serangan Hama Polong Pada Tanaman Kedelai (Glycine max L. Merill) di Lapangan. Skripsi Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Soetopo D & I G A A Indriyani. 2007. Status Teknologi dan Prospek Beauveria bassiana Untuk Pengendalian Serangga Hama Tanaman Perkebunan yang Ramah Lingkungan. Perspektif 6(1):29-46.
Tohir A M. 2010. Teknik Ekstraksi dan Aplikasi Beberapa Pestisida Nabati untuk Menurunkan Palatabilitas Ulat Grayak (Spodoptera litura Fabr.) di
Laboratorium. Buletin Teknik Pertanian 15(1):37-40.
Lampiran 1. Bagan Plot Penelitian
BLOK II BLOK III BLOK I
50 cm 50 cm
P0 P0 P0
P1
P4 P1
P4 P2
P5
P3
P4 P6
P6 P6
P2
P3 P3
P5 P1 P2
Lampiran 2. Bagan Penanaman Pada Plot
200 cm
Keterangan :
A = 25 cm
B = 20 cm
200 cm B
A A
Lampiran 3. Data Persentase Serangan O. phaseoli 5 hst
Data Transformasi Arcsin√X
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 26,57 26,57 4,05 57,18 19,06
P1 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05
P2 26,57 4,05 26,57 57,18 19,06 P3 4,05 4,05 26,57 34,67 11,56 P4 4,05 4,05 26,57 34,67 11,56 P5 4,05 4,05 26,57 34,67 11,56
P6 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05
Total 73,40 50,89 118,42 242,72
Rataan 10,49 7,27 16,92 11,56
Daftar Sidik Ragam
SK db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket
Blok 2 337,81 168,90 1,50 3,88 6,93 tn
P 6 675,61 112,60 1,00 3,00 4,28 tn
galat 12 1351,23 112,60 total 20 2364,65
FK 2805,44 KK 0,92
Keterangan : tn = Tidak Nyata
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 20,00 20,00 0,00 40,00 13,33
P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P2 20,00 0,00 20,00 40,00 13,33 P3 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67 P4 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67 P5 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67
P6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 40,00 20,00 80,00 140,00
Lampiran 4. Data Persentase Serangan O. phaseoli 10 hst
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 40,00 40,00 20,00 100,00 33,33
P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P2 0,00 40,00 20,00 60,00 20,00 P3 40,00 20,00 0,00 60,00 20,00 P4 20,00 40,00 40,00 100,00 33,33
P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P6 0,00 20,00 20,00 40,00 13,33 Total 100,00 160,00 100,00 360,00
Rataan 14,29 22,86 14,29 17,14
Data Transformasi Arcsin√X
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 39,23 39,23 26,57 105,03 35,01
P1 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05
P2 4,05 39,23 26,57 69,85 23,28 P3 39,23 26,57 4,05 69,85 23,28 P4 26,57 39,23 39,23 105,03 35,01
P5 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05
P6 4,05 26,57 26,57 57,18 19,06 Total 121,25 178,93 131,09 431,27
Rataan 17,32 25,56 18,73 20,54
Daftar Sidik Ragam
SK Db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket
Blok 2 241,52 120,76 0,98 3,88 6,93 tn
P 6 3350,94 558,49 4,55 3,00 4,28 **
galat 12 1472,95 122,75 total 20 5065,41
FK 9384,86 KK 0,53
Keterangan : ** = Sangat Nyata tn = Tidak Nyata
Uji Jarak Duncan
SY 6,40 -16,42 -17,31 -2,75 1,08 0,89 12,49 16,71
I 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
SSR 0.05 3,20 3,34 3,41 3,47 3,50 3,52 3,52 LSR 0.05 20,47 21,36 21,81 22,20 22,39 22,52 22,52
Perlakuan P1 P5 P2 P3 P0 P6 P4
Rataan 4,05 4,05 19,06 23,28 23,28 35,01 39,23
b
c
Lampiran 5. Data Persentase Serangan O. phaseoli 15 hst
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 20,00 60,00 0,00 80,00 26,67 P1 0,00 20,00 40,00 60,00 20,00 P2 40,00 60,00 0,00 100,00 33,33 P3 20,00 20,00 40,00 80,00 26,67 P4 20,00 40,00 40,00 100,00 33,33 P5 0,00 40,00 20,00 60,00 20,00 P6 20,00 20,00 40,00 80,00 26,67 Total 120,00 260,00 180,00 560,00
Rataan 17,14 37,14 25,71 26,67
Data Transformasi Arcsin√X
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 26,57 50,77 4,05 81,39 27,13 P1 4,05 26,57 39,23 69,85 23,28 P2 39,23 50,77 4,05 94,05 31,35 P3 26,57 26,57 39,23 92,36 30,79 P4 26,57 39,23 39,23 105,03 35,01 P5 4,05 39,23 26,57 69,85 23,28 P6 26,57 26,57 39,23 92,36 30,79 Total 153,60 259,70 191,60 604,90
Rataan 21,94 37,10 27,37 28,80
Daftar Sidik Ragam
SK db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket
Blok 2 825,56 412,78 1,63 3,88 6,93 tn
P 6 349,84 58,31 0,23 3,00 4,28 tn
galat 12 3040,81 253,40 total 20 4216,20
FK 17423,84 KK 0,55
Lampiran 6. Data Persentase Serangan O. phaseoli 20 hst
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 0,00 0,00 20,00 20,00 6,67
P1 0,00 20,00 0,00 20,00 6,67
P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P3 0,00 20,00 0,00 20,00 6,67
P4 0,00 0,00 1,00 1,00 0,33
P5 0,00 40,00 0,00 40,00 13,33
P6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 80,00 21,00 101,00
Rataan 0,00 11,43 3,00 4,81
Data Transformasi Arcsin√X
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 4,05 4,05 26,57 34,67 11,56 P1 4,05 26,57 4,05 34,67 11,56
P2 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05
P3 4,05 26,57 4,05 34,67 11,56
P4 4,05 4,05 5,47 13,85 4,62
P5 4,05 39,23 4,05 47,34 15,78
P6 4,05 4,05 4,05 12,16 4,05
Total 28,38 108,58 52,58 189,54
Rataan 4,05 15,51 7,51 9,03
Daftar Sidik Ragam
SK Db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket
Blok 2 483,49 241,74 2,14 3,88 6,93 tn
P 6 401,19 66,86 0,59 3,00 4,28 tn
galat 12 1356,76 113,06
total 20 2241,44
FK 1710,78
KK 1,18
Lampiran 7. Data Jumlah Larva O. phaseoli 5 hst
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
Rataan 0,00 0,00 0,00 0,00
Data Transformasi √X + 0,5
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71
P1 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71
P2 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71
P3 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71
P4 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71
P5 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71
P6 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71
Total 4,95 4,95 4,95 14,85
Rataan 0,71 0,71 0,71 0,71
Daftar Sidik Ragam
SK db JK KT F.hit F.tab Ket
Blok 2 0,00 0,00 0,00 4,26 tn
P 6 0,00 0,00 0,00 3,37 tn
galat 9 0,00 0,00 0,00 total 17 0,00
FK 10,50 KK 0,00
Lampiran 8. Data Jumlah Larva O. phaseoli 10 hst
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 0,00 2,00 0,00 2,00 0,67 P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P2 0,00 1,00 0,00 1,00 0,33 P3 0,00 1,00 0,00 1,00 0,33 P4 0,00 2,00 1,00 3,00 1,00 P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P6 0,00 1,00 1,00 2,00 0,67 Total 0,00 7,00 2,00 9,00
Rataan 0,00 1,00 0,29 0,43
Data Transformasi √X + 0,5
Perlakuan Blok Total Rataan
1 2 3
P0 0,71 1,58 0,71 3,00 1,00 P1 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71 P2 0,71 1,22 0,71 2,64 0,88 P3 0,71 1,22 0,71 2,64 0,88 P4 0,71 1,58 1,22 3,51 1,17 P5 0,71 0,71 0,71 2,12 0,71 P6 0,71 1,22 1,22 3,16 1,05 Total 4,95 8,25 5,99 19,19
Rataan 0,71 1,18 0,86 0,91
Daftar Sidik Ragam
SK Db JK KT F.hit F 0,05 F 0,01 ket
Blok 2 0,81 0,41 7,92 3,88 6,93 **
P 6 0,54 0,09 1,75 3,00 4,28 tn
galat 12 0,62 0,05
total 20 1,97 FK 17,53
KK 0,25
Keterangan : ** = Sangat Nyata tn = Tidak Nyata
Uji Jarak Duncan
SY 0,13 0,31 0,28 0,44