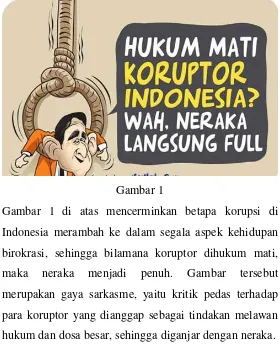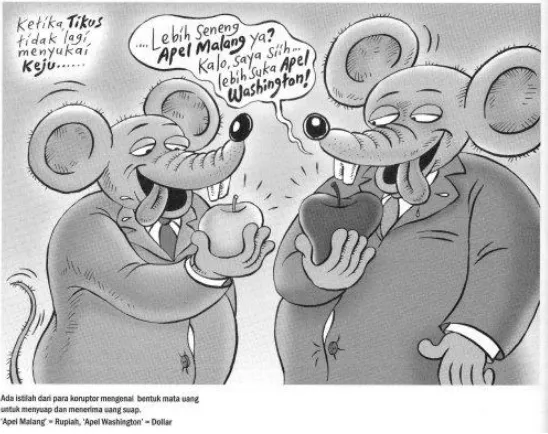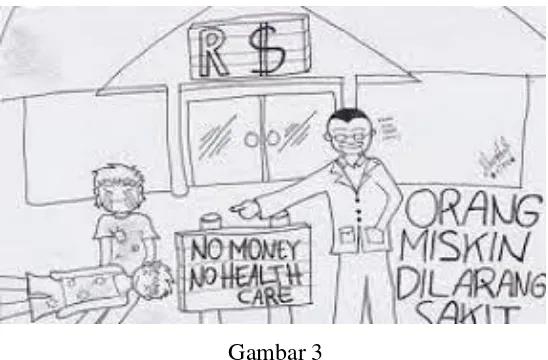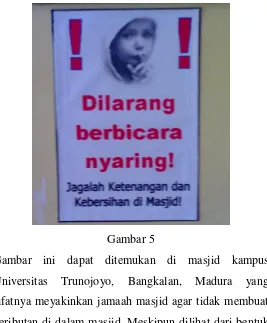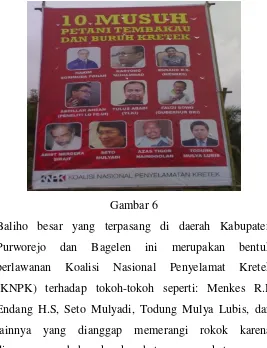BAB I
SEJARAH FILSAFAT BAHASA DAN SEMIOTIKA
A. Pengertian Filsafat Analitis
Filsafat analitis (Analytical Philosophy) adalah satu mainstream dalam bidang filsafat yang muncul sebagai reaksi atas pemikiran neohegelianisme yang masuk ke Inggris pada pertengahan abad kesembilanbelas. Para filsuf Inggeris yang dapat dikategorikan sebagai filsuf analitis awal seperti: G.E.Moore dan Bertrand Russell menganggap bahwa ungkapan filsafat neohegelianisme itu selain sulit dimengerti, tetapi juga telah menyimpang dari logika akal sehat. Charlesworth, salah seorang pemerhati Filsafat analitis mengomentari bahwa filsafat di Inggris setelah melewati kurun waktu lima puluh tahun mulai bangkit dalam suatu bentuk revolusi menentang pengaruh pemikiran neohegelianisme (Charlesworth, 1959 : 1).
kecenderungan filsafat yang bercorak logosentrisme. Logosentrisme artinya terkait dengan bahasa, teks, isi pemikiran, kata, dan pembicaraan. Tujuan analisis bahasa adalah menghasilkan pengetahuan yang benar tentang dunia, karena unsur-unsur terkecil bidang pikiran (mind), yaitu unsur terkecil dari bahasa (logical atomism) merupakan gambaran dari unsur paling kecil bidang matter, yaitu atomic facts. Hamersma menyitir pemikiran Russell yang menekankan analisis bahasa sebagai jalan aman untuk menghindari spekulasi metafisis sebagaimana yang dilakukan penganut neoidealisme (Hamersma, 1983: 135-141).
bagi Leibniz berarti benar dalam semua dunia yang mungkin (Quine, 1997: 197). Hamersma membedakan tiga macam pengetahuan dalam pemikiran Kant, yaitu pengetahuan analitis - a priori, sintetis - a posteriori, dan sintetis - a priori (Hamersma, 1983: 29).
Pertama, pengetahuan analitis adalah jenis pengetahuan yang predikat sudah termuat dalam subjek, predikat dapat diketahui melalui analisis subjek. Contoh: Lingkaran ini bulat; jumlah sebuah sudut segitiga adalah 180 derajat. Solomon menjelaskan tentang analitis dalam pemikiran Kant sebagai berikut:
―Analytic (of) a sentence or truth) demonstrably true (and necessasarily true) by virtue of the logical form or the meanings of the components words. The concept was introduced by Kant, who defined it in terms of a sentence (he called it a judgment) in which the predicate was contained in the subject and added nothing to it‖ (Solomon, 1992: 329).
Kedua, pengetahuan sintetis-a posteriori adalah jenis pengetahuan yang predikatnya dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman inderawi. Solomon menegaskan bahwa apa yang dimaksudkan dengan a posteriori adalah bentuk pengetahuan yang diperoleh setelah dialami, after experience or empirical . Contoh: ―hari ini cuaca panas sekali‖, ini merupakan hasil pengamatan inderawi (Solomon, 1992: 330).
Ketiga, pengetahuan sintetis - a priori yaitu jenis pengetahuan yang menempatkan akal budi dan pengalaman inderawi secara serentak. Contoh: 10 x 100 =1000. Ilmu pengetahuan alam juga bersifat sintetis - a priori, sehingga untuk penjelasannya diperlukan sebuah analisis struktur seluruh proses pengetahuan (Hamersma, 1983: 29). A priori menurut Solomon bebas dari semua pengalaman. Ia menegaskan:
‖A priori knowledge is always necessary, for there can be no imaginable instances that would refute it and no intelligible doubting of it. Knowledge is a priori if it can be proven independently of experience‖ (Solomon, 1992: 330).
semua keputusan dimana relasi subjek pada predikat dipikirkan (Kant menyebutnya keputusan afirmatif), maka relasi tersebut hanya dapat dibedakan dalam dua cara. Relasi pertama, predikat B termasuk ke dalam subjek A. Relasi kedua, predikat B terletak di luar konsepsi A. Relasi pertama dinamakan Kant dengan istilah keputusan analitis, sedangkan relasi kedua dinamakannya keputusan sintetis. Keputusan analitis yang bersifat afirmatif menunjukkan bahwa hubungan antara predikat dengan subjek diketahui melalui identitas, sedangkan dalam keputusan sintetis hubungan antara predikat dengan subjek diketahui tanpa identitas. Kant menegaskan hal tersebut dalam pernyataan sebagai berikut:
judgements (affirmative) are therefore those in which the connection of the predicate with the subject is cogitated through identity; those in which this connection is cogitated without identity, are called synthetical judgements‖ (Kant, 2009: 25).
dari pernyataan itu sendiri dan terbebas dari fakta (Quine, 1994: 197).
Kant sendiri menjelaskan tentang pengetahuan a priori dan a posteriori bahwasanya yang dimaksud dengan istilah pengetahuan a priori, yaitu kita akan meletakkannya dalam pengertian akibat yang ditimbulkannya, bukan sebagai seperti pengetahuan yang tergantung pada pengalaman, melainkan pengetahuan yang sama sekali terlepas dari pengalaman. Pengetahuan a priori ini berbeda dengan pengetahuan empiris, ia bersifat murni, karena di dalamnya tidak ada unsur empiris. Kant mencontohkan pengetahuan a priori dalam proposisi ―setiap perubahan ada penyebabnya‖, alasan Kant perubahan merupakan suatu konsepsi yang dapat dijabarkan dari pengalaman (Kant, 2009:29).
dibedakan dari intuisi atau sensasi indera semata (Cassirer, 1968: 152).
Philosophical Investigations dan J.L.Austin (Ordinary Language Philosophy); tahap penerapan filsafat analitis ke dalam berbagai kajian ilmiah seperti yang dilakukan J.F.Lyotard. Kelima tahap tersebut memainkan peranan penting sekaligus memperlihatkan corak pemikiran yang cukup berbeda, meskipun tentu saja ada kemiripan yang dapat ditemukan dalam setiap tahapan.
filsafat analitis lainnya yang tidak kalah penting, yaitu memberikan klarifikasi terhadap pernyataan-pernyataan filsafat itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atas gagasan yang diungkapkan para filsuf. Wittgenstein menegaskan tugas filsafat itu dalam pernyataan berikut:
―The object of philosophy is the logical clarification of thoughts. Philosophy is not a theory but an activity. A philosophical work consist essentially of elucidations. The result of philosophy is not a number of philosophical propositions, but to make propositions clear‖ (Wittgenstein, 1995: 77).
(―Objek filsafat adalah klarifikasi logis dari pemikiran-pemikiran. Filsafat bukanlah sebuah teori namun suatu aktivitas. Sebuah karya filosofis dasarnya terdiri dari penjelasan-penjelasan. Hasil dari filsafat bukanlah sejumlah proposisi filosofis, tetapi untuk membuat proposisi menjadi jelas‖).
sekaligus menjelaskan permasalahan dan menghilangkan kekaburan dalam pernyataan filosofis. Filsafat itu pada hakikatnya hanya membicarakan bahasa, sehingga apabila seorang filsuf telah memutuskan bahwa suatu pernyataan itu bermakna, dan memberitahukan tentang alam dan tidak hanya tentang caranya mempergunakan perkataan, maka tibalah giliran para ahli sains untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut (Titus, dkk, 1984:367-368).
dari bahasa Yunani analusis yang artinya membubarkan (dissolving) dan melepaskan (loosening up). Istilah tersebut juga dihubungkan dengan konsep analysandum yaitu sesuatu yang akan dianalisis, dan analysans, kegiatan menganalisis (Glock, 2008: 21).
Martinich dalam karyanya yang lain, A Companion To Analytic Philosophy menegaskan bahwa istilah umum filsafat analitis secara praktis digunakan pada paruh pertama abad keduapuluh di negara-negara berbahasa Inggris dan Jerman, kemudian berkembang pula di Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru. Analisis konsep bertujuan untuk memecah konsep-konsep yang kompleks ke dalam bentuk komponen-komponen yang lebih sederhana. Rancangan konseptual inilah yang membedakan aktivitas filosofis dari berbagai analisis yang yang diterapkan terhadap objek-objek nir-konseptual (Martinich and Sosa, 2001: 1).
sosial. Quine dalam kata pengantar bukunya Word and Object menegaskan bahwa bahasa adalah seni sosial, karena dalam mendapatkan bahasa seseorang sangat tergantung pada isyarat hubungan antara subjek tentang apa yang dikatakan dan kapan itu dikatakan (Quine, 1994: ix). Dengan demikian analisis konsep mutlak diperlukan untuk mendapatkan kejelasan makna dan menghindarkan pemaknaan subjektif yang berlebihan dalam memahami suatu objek. Dalam hal ini problem arti atau makna merupakan salah satu fokus pembicaraan para filsuf analitis
B. Kajian Filsafat Bahasa
dianggap paling bertanggungjawab atas penggunaan bahasa yang bernuansa ambiguitas (ambiguity), ketidaktersuratan (inexplicitness), kekaburan (vagueness), sehingga diperlukan klarifikasi dan penjernihan atas bahasa filsafat.
Filsafat bahasa lahir sebagai sikap skeptis atas ungkapan metafisika yang mengaburkan makna suatu ungkapan dengan realitas yang sesungguhnya. Filsafat bahasa menurut Honderich dalam The Oxford Companion to Philosophy (1995: 937) mengkaji tentang presupposition of language dan nature of language. Kajian tentang presupposition of language membicarakan masalah bahasa privat, ide bawaan, dan intensionalitas bahasa. Kajian tentang nature of language membahas masalah gramatika bahasa, relasi antara bahasa dengan sistem simbol lain, serta relasi bahasa dengan interpretasi, penerjemahan, dan analisis.
cabang-cabang filsafat lainnya, hanya fokus pembahasannya meletakkan bahasa sebagai objek material filsafat, sehingga membahas hakikat bahasa itu sendiri.
Toety Herati meletakkan perbincangan filsafat bahasa ini sebagai bentuk meta-language yang menekankan pada metode analisis sebagai pendekatan khas filsafat analitis. Lantaran menganalisis bahasa filsafat maka dinamai filsafat bahasa (Toety Herati, 1984: 73).
C. Pengertian Semiotika
menyebutnya dengan istilah yang mirip, namun sedikit berbeda. Peirce menamakan studi tentang tanda dengan istilah semeiotic, sedangkan Saussure menyebutnya dengan istilah semiology.
Kedua tokoh ini dianggap sebagai pemicu kelahiran semiotika dalam dunia ilmiah, meskipun keduanya memiliki pemikiran yang khas dan melahirkan dua mainstream dalam dunia semiotika. Sepintas terlihat bahwa kedua mainstream itu menimbulkan cara pandang yang berbeda, namun sesungguhnya keduanya saling melengkapi, lantaran baik wilayah kebahasaan maupun komunikasi pada hakikatnya merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Di satu pihak bahasa merupakan sarana bagi komunikasi, sedangkan di pihak lain komunikasi membutuhkan bahasa untuk mengungkapkan gagasan pemikiran.
gagasan. Bahasa sebagai sarana komunikasi merupakan kajian yang banyak dibicarakan dalam semiotika, karena kajian tentang tanda termasuk hal yang menjadi perhatian para tokoh semiotika.
BAB II
PERSOALAN MAKNA DALAM STATEMEN FILSAFAT
A. Problem Makna Dalam Filsafat Bahasa
Problem makna ungkapan di kalangan para filsuf bahasa melahirkan beberapa teori seperti: Teori ideasi, teori tingkah laku, dan teori acuan, namun teori arti yang paling banyak menarik perhatian para ahli filsafat bahasa adalah teori acuan (Referential theory), meskipun kedua teori lainnya juga tidak kalah pentingnya dalam kajian filsafat tanda. Oleh karena itu untuk memperjelas perbedaan dan menunjukkan karakteristik masing-masing teori arti itu berikut akan dipaparkan ketiga jenis teori arti tersebut.
1. Teori Ideasi (Ideasional Theory)
2004: 251). Locke menyatakan bahwa kata-kata atau ungkapan bahasa itu sesungguhnya merupakan tanda-tanda yang dapat diinderai dari gagasan penggunanya. Seseorang yang menggunakan tanda bahasa itu merekam gagasan tentang tanda itu ke dalam pikirannya. Ketika seseorang mengungkapkan kata-kata kepada orang lain sesungguhnya orang tersebut bermaksud menyampaikan gagasan yang ada dalam pikirannya atau yang diketahuinya kepada pihak lain. Locke menegaskan hal itu dalam pernyataan sebagai berikut:
―Words, in their immediate signification, are the sensible signs of his ideas who uses them. The use men have of these marks being either to record their own thoughts, for the assistance of their own memory or, as it were, to bring out their ideas, and lay them before the view of others: words, in their primary or immediate signification, stand for nothing but the ideas in the mind of him that uses them, how imperfectly soever or carelessly those ideas are collected from the things which they are supposed to represent. When a man speaks to another, it is that he may be understood: and the end of speech is, that those sounds, as marks, may make known his ideas to the hearer‖ (Locke, 2004: 251).
yang yang menggunakannya. Mereka yang menggunakannya memiliki tanda ini, baik untuk mencatat pemikiran mereka sendiri, untuk membantu memori mereka sendiri atau untuk menunjukkan ide-ide mereka, dan meletakkan pandangan mereka sebelum pandangan orang lain: kata-kata, pada dasarnya atau pemaknaan langsung, bukanlah untuk menggantikan sesuatu tetapi gagasan ada dalam pikiran orang yang menggunakannya, betapapun tidak sempurnanya, namun ide-ide tersebut dihimpun dari hal-hal yang mereka anggap mewakili. Ketika seorang berbicara kepada yang lain, itu berarti bahwa dia dapat dimengerti: dan akhir wicara bahasa adalah, bahwa suara-suara, sebagai tanda, menjadikan gagasannya dikenal pendengarnya").
mendapatkan ciri-ciri penggunaan bahasa, maka hal itu memberikan unit-unit linguistik makna yang mereka miliki (Alton, 1964: 19).
Judowibowo menegaskan bahwa menurut teori ideasi ini, apa yang memberi arti atau makna dari suatu kata atau ungkapan bahasa adalah kenyataan bahwa kata atau ungkapan bahasa ini secara teratur digunakan dalam komunikasi sebagai suatu tanda (mark) untuk menyatakan suatu ide kepada pihak lain. Jika suatu kata atau ungkapan bahasa itu digunakan menurut teori ideasi, maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
‖1) harus ada ide dalam pikiran si pembicara, 2) si pembicara harus mengeluarkan kata atau ungkapan bahasa agar orang lain mendengar bahwa ide yang dimaksud itu ada dalam pikiran si pembicara pada waktu itu, 3) apabila komunikasi itu berhasil, maka ungkapan bahasa tadi harus menimbulkan ide yang sama dalam pikiran si pendengar‖ (Judowibowo, TT: 19).
2. Teori Tingkah laku (Behavioral Theory)
Teori ini menemukenali (mengidentifikasi) arti ungkapan bahasa dengan situasi pengucapan dan tanggapan atau reaksi yang dilakukan lantaran adanya ucapan tersebut. Bentuk paling sederhana dari teori tingkah laku ini terletak pada arti suatu ungkapan bahasa yang menempatkan situasi pengungkapan bahasa dari si pembicara dan tanggapan (response) yang ditimbulkannya pada pendengar (Judowibowo, TT: 18). Teori tingkah laku ini menanggapi bahasa sebagai semacam kelakuan dan mengembalikannya kepada stimulus dan response. Makna menurut teori tingkah laku adalah rangsangan untuk menimbulkan perilaku tertentu sebagai tanggapan atas rangsangan itu tadi (Toeti Heraty, 1984: 76).
menyadari akan kerumitan yang terdapat di dalamnya. Bloomfield mengatakan bahwa makna suatu bentuk linguistik adalah situasi yang ada dalam diri si pembicara dan tanggapan yang timbul dari si pendengar (Alston, 1964: 26).
Inti pemikiran teori tingkah laku ini terletak pada situasi pengucapan yang dilakukan si pembicara sehingga menimbulkan tanggapan dari si pendengar. Beberapa contoh yang diucapkan si pembicara yang diharapkan menimbulkan tanggapan (baik langsung maupun tidak) kepada pendengar antara lain:
a.―Tolong ambilkan saya kunci di atas meja itu!‖ b.―Dapatkah anda mengecilkan suara musik itu,
karena suaranya sangat mengganggu konsentrasi belajar saya?‖
c.―Silahkan keluar dari raungan ini, jika anda tidak setuju dengan keputusan saya!‖
karena orang yang mendengar tidak ingin bertemu dengan si penyapa.
Teori tingkah laku didasarkan atas asumsi bahwa setiap ungkapan yang dilontarkan dalam situasi umum akan menghasilkan tanggapan yang sama.
3. Teori Acuan (Referential Theory)
Teori acuan didasarkan pada suatu asumsi bahwa setiap ungkapan bahasa yang dipergunakan itu membicarakan atau mengacu pada sesuatu. Teori acuan merupakan jawaban pertama atas pertanyaan tentang makna kata atau ungkapan. Makna kata atau ungkapan menurut teori acuan, dianggap identik dengan objek yang menjadi acuan kata atau ungkapan tersebut. Contoh yang paling banyak dijumpai ialah nama diri (proper names) yang langsung menunjuk satua ekstralinguistik yang sekaligus menjadi makna nama tersebut.Teori acuan dalam perkembangan selanjutnya beranggapan bahwa makna suatu kata atau ungkapan identik dengan relasi antara kata dan acuannya (Toeti Heraty, 1984: 76).
dalam teori acuan, yang pertama menyatakan bahwa arti sebuah kata atau ungkapan adalah sesuatu yang diacunya. Versi kedua teori acuan menyatakan bahwa arti sebuah kata atau ungkapan dan acuan adalah hubungan antara acuan dengan ungkapan atau kata (Judowibowo, TT: 15). Teori acuan versi kedua lebih luas pengertiannya daripada versi pertama yang hanya menempatkan arti pada sesuatu yang diacu, karena relasi atau hubungan antara acuan dengan ungkapan mengandaikan lingkup yang lebih luas.
sejauh mereka dinamakan atau ditandakan sesuatu, namun pemberian nama itu sendiri bersifat arbitrer. Frege menegaskan bahwa tanda dan nama dipahami sebagai bentuk penunjukkan nama diri (proper names). Pengertian dari sebuah nama diri dimunculkan setiap orang yang sudah cukup akrab dengan bahasa yang dipergunakannya. Acuan sebuah nama diri adalah objek itu sendiri yang ditunjuk melalui artinya, gagasan yang dimiliki dalam hal ini cenderung bersifat subjektif. Misalnya seseorang mengamati bulan menggunakan teleskop, ia membandingkan bulan itu sendiri pada acuannya, maka bulan itu adalah objek yang diamati, yang diperantarai oleh objek kaca pembesar yang merupakan alat kelengkapan teleskop, dan melalui retina mata si pengamat. Citra optik dalam teleskop terletak di satu sisi dan tergantung pada sudut pengamatan. Apabila pengamatan itu dilakukan oleh beberapa pengamat, maka hal itu akan menjadi lebih objektif (Frege, 2008: 113-115).
berbahasa satu acuan dapat disebutkan dengan kata atau ungkapan yang berbeda-beda. Misalnya: ―isteri abang saya‖ dan ―kakak ipar saya‖. Demikian pula halnya dengan kata-kata deiktik seperti: ―aku‖, ―kini‖, ―tadi‖, ―nanti‖, ―di sini‖ adalah kata yang dalam struktur bahasa menunjuk pada tempat dan situasi tuturan. Kata-kata deiktik itu menurut Toety Herati menunjukkan koordinat ruang dan waktu (spasiotemporal), yakni saat dan tempat kata-kata itu diucapkan (Toety Herati,1984: 75-76).
Ullmann mengemukakan konsep teori acuan (Referensial) berdasarkan model segitiga dasar yang diajukan Ogden dan Richards bahwa ada relasi anatara pikiran sebagai referensi dengan lambang dan acuan itu sendiri (Ullmann, 2009: 66).
bidang-bidang studi lainnya pada umumnya, kiranya perlu dilakukan.
B. Makna dalam Semiotika
(http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/english/semiotic.htm: h.1).
Ada pula yang mendefinisikan semiotika sebagai bentuk penerapan metode linguistik atas objek selain bahasa alami, artinya semiotika terkait dengan bahasa dalam pengertian artifisial. Dengan demikian semiotika adalah suatu cara pandang atas segala sesuatu sebagaimana hal tersebut dibentuk dan berfungsi sesuai dengan bahasa. Semiotika mencakup segala hal yang dapat digambarkan sebagai bahasa seperti: sistem kekeluargaan, permainan kartu, bahasa isyarat, ekspresi wajah, seni memasak, ritual agama, dan lain-lain. (http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/english/semiotic.htm: h.2).
Tanda selalu melibatkan aktivitas mental dan pikiran manusia, sehingga pemikiran manusia mengalami pengembangan yang pesat tergantung pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri dalam memahami dan
memaknai tanda. (Chandler,
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem02.ht
m1, page 1).
Tanda itu sendiri dapat mengambil berbagai bentuk dalam kata, suara, bau, rasa, tindakan, atau objek. Namun bukan berarti setiap tanda mengandung makna secara intrinsik, ia mengandung makna manakala kita menanamkan itu ke dalamnya. Segala sesuatu dapat menjadi sebuah tanda sepanjang seseorang menafsirkan itu sebagai bermakna, mengacu atau menggantikan sesuatu yang lain. Manusia hanya berpikir dalam tanda, ujar Peirce dalam Elements of Logic (1998: 169). Namun penafsiran makna suatu tanda terkait dengan sistem konvensi yang dikenal luas, hal ini dikenal dengan istilah simbol..
yang luas. Semiotika dalam pengertian yang sederhana adalah studi penggunaan dan proses tanda (Zoest, 1991: 54). Semiotika dalam pengertian yang lebih luas adalah studi tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda; cara berfungsi tanda, hubungannya dengan tanda-tanda yang lain, pengiriman dan penerimaan oleh mereka yang menggunakan tanda (van Zoest, 1992: 5).
tanda (sign) yang terus menerus hadir dalam pikiran seseorang untuk mewakili objek yang sama (Locke, 1910: 12).
Eugene Gorny dalam artikelnya yang berjudul
What is Semiotics?
menyatakan bahwa semiotika adalah sebuah transfer dari bahasa metafor ke dalam fenomena yang non-linguistik. Ketiga; semiotika sebagai suatu ilmu yang dilembagakan oleh para semiotikawan. Tanda orientasi semiotika sebagai karya yang diterima adalah penggunaan terminologi semiotika konvensional (seperti: sign, code, signification, semiosis, etc) bersama dengan acuan pada karya semiotika lainnya. Dengan demikian definisi semiotika yang ketiga ini adalah semiotika sebagaimana yang dimaksudkan oleh para semiotikawan.
rambut uban, sikap diam membisu, gagap, bicara cepat, berjalan sempoyongan, menatap, api, putih, bentuk bersudut tajam, kecepatan, kesabaran, kegilaan, kekhawatiran, kelengahan semuanya itu dianggap sebagai tanda (Zoest, 1993:18).
mengevaluasi sistem dalam praktik kebudayaan, seseorang harus memiliki latar belakang ketertarikan. Kelima; Semiotika merupakan sebuah kerangka mitis, artinya manusia tidak memersepsikan dunianya secara langsung, namun melihatnya lewat saringan berupa mode semiotik atau kerangka mitis. Keenam; semiotika merupakan sebuah barometer kebudayaan yang menandakan adanya pergerakan dinamis dari sejarah sosial (Solomon, 1988: 10).
objek. Interpretan itu boleh jadi sebuah pemikiran atau notasi yang menghadirkan kembali suatu objek, tetapi interpretan bukan merupakan objek itu sendiri. Lebih lanjut Deborah menegaskan pemikiran salah seorang tokoh semiotika, yakni Peirce tentang tanda dalam pengalaman manusia di dunia ini selalu diperantarai melalui tanda, sehingga seseorang tidak pernah mengetahui objek secara penuh dan langsung. Seseorang hanya dapat mengetahui objek secara parsial, hanya melalui penafsiran atas tanda-tanda dari objek yang memberikan kepadanya pandangan sekilas pada beberapa hal atau kapasitas objek (Deborah, 2005: 225-226).
apabila seorang zoologis membicarakan tentang ‖mamalia‘, maka kemampuan ahli zoologi tersebut untuk melakukan klasifikasi kategori atas ‖mamalia‖ menjadi sangat penting. Misalnya: penelusuran tentang asal mula seekor anjing mulai dari species, family hingga genus. (Eco, 1984: 54-55). Semiotika juga dapat dipergunakan untuk menginterpretasi dan mengklasifikasi perihal budaya, termasuk wayang. Misalnya interpretasi atas tokoh-tokoh film sebagai simbol kebaikan dan kejahatan; simbol kejujuran dan kelicikan; simbol keteguhan prinsip dan keraguan, dan seterusnya.
sudah siap untuk diketahui, bukan dari sesuatu yang tidak diketahui. Konsekuensinya, sebuah penalaran dianggap baik manakala menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar dari premis-premis yang benar pula. Dengan demikian persoalan validitas murni bertitik tolak dari fakta, bukan pemikiran, dan fakta itu dibentuk dan disusun dalam premis (Buchler, 1955:7-9). Relasi timbal balik antara logika dan tanda identik dengan relasi antara premis atau pernyataan dengan fakta, karena premis atau pernyataan merepresentasikan logika, sedangkan fakta merepresentasikan tanda.
BAB III
POKOK-POKOK PEMIKIRAN PARA FILSUF ANALITIS
Sebagaimana yang diungkapkan di atas bahwasanya pemikiran dalam filsafat analitis dapat dibagi ke dalam lima tahap perkembangan dengan corak yang khas, yaitu tahap perintis dengan tokoh utama Moore; tahap Atomisme Logis dengan tokoh utama Russell dan Wittgenstein periode Tractatus; tahap Positivisme Logis dengan tokoh utama A.J.Ayer; tahap Filsafat Bahasa Biasa dengan tokoh utama Wittgenstein periode Philosophical Investigations, dan tahap aplikatif dengan tokoh utama J.F.Lyotard. Pengkajian atas pemikiran dalam filsafat analitis akan difokuskan pada pemikiran para filsuf tersebut di atas.
A. G.E. Moore (1873 – 1958)
keduapuluh. Kebanyakan pernyataan pengikut neohegelianisme itu menurut Moore, sulit bahkan tidak terpahami dengan common sense atau akal sehat manusia. Oleh karena itu salah satu cara untuk menentang pemikiran mereka itu, maka diperlukan standar yang bisa diterima oleh kebanyakan pemikiran manusia, dalam hal ini common sense merupakan tolok ukur yang dianggap Moore paling memadai. Karya Moore yang menganalisis alur pemikiran idealisme berjudul Philosophical Studies, kemudian karyanya yang mengkaji tentang common sense adalah Some Main Problems of Philosophy; sedangkan Principia Ethica merupakan kajian tentang meta-etika atau filsafat analitis yang diarahkan ke dalam bidang etika.
1. Penolakan atas Idealisme
apa yang menampak, dan kedua bahwa alam semesta itu memiliki sejumlah besar sifat-sifat yang tidak tertangkap oleh indera manusia. Moore mencontohkan kursi, meja, gunung terlihat sangat berbeda dari manusia, demikian pula halnya dengan keseluruhan alam semesta yang dinyatakan penganut idealisme sebagai sesuatu yang spiritual. Hal itu menurut Moore sama halnya dengan menganggap alam semesta itu jauh lebih luas maknanya daripada apa yang bisa dipikirkan oleh seseorang (Moore, 1951 : 1).
gagasan yang ada dalam pikiran seseorang harus membedakan dua unsur, yaitu objek dan kesadaran. Di saat sebuah gagasan itu muncul, maka seseorang harus memilih beberapa hal, yakni hanya objek, atau kesadaran semata, ataukah keduanya sekaligus. Sesuatu objek hanya eksis karena didukung oleh fakta mental, dengan demikian objek dan kesadaran itu sama-sama eksis, hal ini dinamakannya objek pada kesadaran dalam berbagai gagasan. Objek dalam hal ini semata-mata adalah isi dari gagasan. Moore menegaskan bahwa dalam setiap peristiwa dapat dibedakan dua unsur, yaitu pertama, fakta tentang adanya perasaan atau pengalaman; kedua, apa yang dialami, sensasi atau gagasan itu yang dikatakan sebagai bentuk keseluruhan yang harus dibedakan dua aspek yang tidak terpisah (inseparable aspects) yakni isi (contents) dan keberadaan (existence) (Moore, 1951: 20-21).
sehari-hari. Penggunaan istilah-istilah seperti: ―real‖, ―exists‖ dalam bidang filsafat berbeda dengan apa yang dipahami dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Para filsuf idealisme menurut Moore memahami makna istilah real itu secara ambigu, bermakna ganda. Hal ini diungkapkan Moore dalam pernyataan berikut:
―What is the meaning of the word ‗real‘? What I want to do is to raise certain questions about the nature of this notion, which is called up by the word ‗real‘, not merely to call it up. And, therefore, I think it perhaps unfortunate of me to describe this question of mine as a question as to the meaning of the word ‗real‘. The fact that the very same words: What is the meaning of the word ‗real‘? may be used to express these two entirely different questions, may, I think, give rise to misunderstandings as to the precise nature and bearings of the one which I do want to raise. And I want now, by the help of this distinction, to try to point out more clearly exactly what the chief question I do want to raise is, and what its bearings are‖ (Moore, 1953: 218-219).
'nyata'. Kenyataan bahwa kata-kata yang sama: Apa arti dari kata 'nyata'? dapat digunakan untuk mengekspresikan dua pertanyaan yang sama sekali berbeda, mungkin, saya pikir, menimbulkan kesalahpahaman sebagai sifat yang tepat dan mendukung dari satu yang saya ingin munculkan. Dan yang saya inginkan sekarang, dengan bantuan dari perbedaan ini, untuk mencoba menunjukkan lebih jelas apa pertanyaan utama yang saya ingin munculkan, dan sesuatu yang mendukungnya‖).
diidentikkan dengan keseluruhan dari bagian. Ketiga, kata real adalah sifat yang mengandung tingkatan, sehingga dapat bersifat kurang real´atau lebih real (Moore, 1953: 231).
Pandangan metafisika Moore menegaskan bahwa objek harus dipisahkan dari kesadaran. Objek tidak menyatu dengan subjek dalam kesadaran sebagaimana yang dianut oleh kaum idealis (Abbas Hamami, 2005: 47). Disinilah pentingnya peran common sense dalam memahami realitas menurut pandangan Moore.
2. Common sense
tumbuh-tumbuhan, benda-benda tak bernyawa (gunung, batu-batuan). Semua unsur alam semesta itu dipercayai oleh manusia lantaran common sense mempercayai adanya itu semua. Namun di samping objek material yang bersifat fisik, manusia dengan common sense-nya juga percaya bahwa ada fenomena yang sangat berbeda seperti pikiran (minds), tindakan mental atau kesadaran (consciousness) (Moore, 1953: 2-4).
Moore menyebutkan tiga karakteristik paling penting dari objek material sebagai berikut. Pertama, objek material merupakan sesuatu yang berbeda dari tindakan kesadaran. Kedua, semua objek material itu terletak dalam dimensi ruang dan waktu. Ketiga, objek material memiliki sifat yang khas, yakni selalu eksis meskipun manusia tidak menyadarinya (Moore, 1953: 9).
data inderawi yang pasti. Ketiga, apa yang terjadi dalam persepsi inderawi sesungguhnya adalah ketika seseorang mencoba untuk menemukan sesuatu atau peristiwa melalui pengamatan atas pikirannya sendiri (Moore, 1953: 52).
3. Analitika Bahasa Dalam Meta Etika
―duty‖, ―right‖, ―Ought‖, ―good‖, ―bad‖. Di saat itulah menurut Moore manusia sedang membuat putusan dan pertimbangan etis. Pada saat seseorang mengatakan bahwa ―orang itu baik‖, maka secara umum dimaksudkan bahwa orang itu melakukan tindakan yang benar. Demikian pula ketika seseorang mengatakan bahwa ―pemabuk itu merupakan tindakan yang buruk‖, maka yang dimaksudkan secara umum adalah tindakan minum alkohol itu salah atau tindakan yang buruk (Moore, 1954: 1-2). Keunikan etika menurut Moore, bukan terletak pada penyelidikan tentang tindakan manusia, melainkan penjelasan tentang sifat sesuatu yang ditunjuk oleh istilah ―baik‖ atau sebaliknya sifat yang ditunjuk oleh istilah ―buruk‖ (Moore, 1954 :36).
pandangan Moore termasuk ke dalam bagian kebaikan yang paling pokok (ultimate good). Moore menunjukkan dua prosedur yang perlu diperhatikan ketika seseorang bermaksud melakukan pertimbangan moral secara umum. Pertama, keputusan intuitif yang dilakukan seseorang setelah ada pertimbangan atas pertanyaan manakala putusan moral ditempatkan sebelumnya. Ada relasi antara subjek yang sadar dengan objek moral bilamana muncul kesadaran yang mengiringinya dan diakibatkan dari putusan itu bukan merupakan hal yang pokok dan keinginan yang bersifat intrinsik Moore berpendapat bahwa ada objek yang lebih daripada sekadar sesuatu yang bersifat material, ketika dipertimbangkan terpisah dari relasi kesadaran manusia. Kedua, perbandingan menyeluruh atas pertimbangan kemanusiaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari
(Moore, 1954: 86).
B. Bertrand Russell (1872 – 1970)
Atomisme Logis ini adalah suatu faham atau ajaran yang berpandangan bahwa bahasa itu dapat dipecah menjadi proposisi atomis atau proposisi-proposisi elementer, melalui teknik analisis logis atau analisis bahasa. Setiap proposisi atomis atau proposisi elementer itu tadi mengacu pada atau mengungkapkan keberadaan suatu fakta atomis, yaitu bagian terkecil dari realitas. Pandangan kaum Atomisme Logis ini bermaksud menunjukkan adanya hubungan yang mutlak antara bahasa dengan realitas.
filsafat ilmiah pada hakikatnya ialah epistemologi kaum empiris dan teori pengetahuan yang didasarkan pada logika matematik (Stroll, 2000: 45). Sumber kepustakaan kedua adalah karya Russell yang berjudul An Inquiry into Meaning and Truth yang membahas tentang proper names dan basic propositions. Sebenarnya masih ada sumber kepustakaan lainnya, yaitu kata pengantar yang dibuat Russell untuk karya Wittgenstein yang berjudul Tractatus Logico- Philosophicus, namun secara umum orang menganggap keseluruhannya sebagai karya Wittgenstein, padahal itu merupakan pemikiran Russell sendiri sebagai bentuk komentar atas pemikiran Wittgenstein dalam karya tersebut..
1. Konsep Atomisme Logis Bertrand Russell
Moore menurut Russell, tidaklah tepat. Russell tidak sekedar bermaksud mengarahkan teknik analisis yang diajukan oleh Moore itu untuk menentang ungkapan kosong dari kaum Hegelian, akan tetapi Russell juga mencoba untuk membentuk filsafat yang bercorak ilmiah dengan cara menerapkan metode ilmiah pada filsafat (Charlesworth,1959 : 49). Russell menegaskan bahwa dalam percobaan yang dilakukan secara serius, tidaklah selayaknya seorang filsuf menggunakan bahasa biasa, sebab susunan bahasa biasa itu selain buruk (abominable), juga merupakan penghalang besar bagi kemajuan filsafat (Charlesworth,1959 : 51-52). Berbagai bentuk kalimat menurut Russell mengungkapkan pertanyaan (interogative), mengungkapkan harapan (optative), kalimat seru (exclamatory), dan menunjukkan perintah (imperative) mengandung maksud-maksud tertentu, bersifat indikatif, sehingga masing-masing mengandung logika tersendiri (Russell,1980: 30).
dan struktur realitas. Persoalan logis menjadi sangat penting bagi Russell, karena hal itu merupakan kondisi terbentuknya simbolisme yang akurat, artinya setiap kalimat mengandung arti yang terbatas dan pasti, meski dalam kenyataannya, bahasa biasanya kabur, sehingga apa yang disampaikan tidak pernah benar-benar tepat. Salah satu hal yang penting menurut Russell adalah kondisi simbolisme terhadap keunikan makna atau acuan dalam simbol atau kombinasi simbol. Sebuah bahasa logis yang sempurna harus mengandung aturan sintaksis yang dapat mencegah bahasa yang tidak bermakna, dan salah satu langkah yang tepat adalah dengan meletakkan simbol tunggal yang memiliki makna unik dan terbatas (Russell, 1995: 8).
merupakan bagian dari tugas filsafat, namun Russell tidak percaya bahwa hal itu merupakan bagian yang paling penting. Bagian terpenting menurut Russell justru terkandung dalam kritik dan penjelasan terhadap pernyataan yang mungkin untuk dijawab sebagai dasar dan pengakuan yang tidak dapat diganggu gugat (Charlesworth,1959 : 49).
empiris murni tidak dapat mempertanggungjawabkan hal seperti itu (Charlesworth,1959: 50). Russell menganjurkan untuk mencari teori ilmiah yang lain, lebih daripada sekadar empiris murni. Pandangan yang demikian inilah yang agaknya membuat Russell lebih mencurahkan pemikirannya untuk membentuk suatu bahasa ideal bagi filsafat dengan didasarkan pada bahasa logika. Bahasa ideal yang dimaksud ialah bahasa yang mengandung makna yang unik, terbatas, tidak bermakna ganda.
kesepadanan, sehingga pengetahuan itu merupakan sejumlah pernyataan yang tersusun membentuk suatu sistem yang mengacu pada unsur pada realitas. Kesepadanan atau prinsip isomorfi merupakan kesesuaian struktur antara bahasa logis dengan realitas (Toety Herati, 1984: 85-86).
2. Corak Logis (Logical Types)
bahasanya sama, namun memiliki struktur logis yang berbeda (Charlesworth, 1959 : 52). Penjelasan Russell mengenai suatu pengertian atau istilah yang memiliki corak logis yang sama diungkapkan melalui contoh berikut: ―A dan B hanya dapat dikatakan memiliki corak logis yang sama, jika unsur A mengandung kesesuaian dengan unsur B, sehingga akibat yang berlaku atau unsur lawan bagi B dapat digantikan pada A. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: Socrates dan Plato dianggap memiliki corak yang sama, sebab ―Socrates adalah seorang filsuf‖ dan ―Plato seorang filsuf‖, keduanya mengandung fakta yang sama, yakni sama-sama berperan sebagai filsuf‖ (Charlesworth,1959: 53).
penafsiran yang mungkin dikenakan bagi istilah itu, tetapi yang lebih banyak ditonjolkan di sini adalah aspek logis yang didukung oleh fakta tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis pula bagi istilah yang diperbandingkan. Jadi kalau dikatakan ―Socrates‖ dan ―Plato‖ adalah dua nama yang memiliki corak logis yang sama, kesimpulan itu didasarkan pada kenyataan bahwa keduanya termasuk atau digolongkan ke dalam kelas atau kategori sebagai filsuf. Pemahaman corak logis yang terkandung dalam ungkapan menurut Russell akan dapat membedakan antara bentuk tatabahasa berupa penampakan bentuk logis dengan bentuk sintaksis berupa bentuk logis yang nyata dari sebuah kalimat.
3. Prinsip Isomorfi
dengan hanya menggunakan definisi dan prinsip logika (Bertens, 1976 : 28). Russell berkeyakinan, dengan memadukan prinsip matematik ke dalam prinsip logika, maka akan mampu memecahkan persoalan filsafat. Kecenderungannya untuk menerapkan metode ilmiah – dengan bertitik tolak pada prinsip logika itu— pada bidang filsafat inilah yang merupakan inti pemikiran dari Atomisme Logis. Upaya untuk mengungkapkan pengetahuan yang benar ke dalam bentuk pernyataan yang benar –atas dasar prinsip logika— telah membawa Russell memasuki wilayah analisis bahasa.
acuan itu Russell menganggap telah ‖mengisi‖ setiap pernyataan dengan fakta.
Gambaran yang jelas tentang pemberian dasar acuan (reference) bagi kata atau istilah sebagai unsur-unsur bahasa itu dapat dilihat pengelompokan sebagai berikut.
Uraian mengenai pemberian dasar acuan terhadap kata atau istilah ini merupakan salah satu upaya Russell untuk membuktikan adanya kesepadanan atau kesesuaian antara unsur bahasa dengan unsur realitas. Logika pada umumnya membagi kata-kata ke dalam beberapa kategori seperti: nama-nama, predikat, relasi diadik, relasi triadis, dan seterusnya. Kendatipun demikian hal ini belum mencakup keseluruhan kata, sebab ada kata-kata yang tidak termasuk ke dalam kategori logis, sehingga diragukan apakah kata itu meliputi kata-kata untuk sikap proposisional seperti: percaya, hasrat, kesangsian, dan lain-lain. Demikian pula halnya kesulitan atas bentuk partikular egosentris seperti: aku, disini, sekarang. Kata-kata sifat proposisional dan partikular egosentris menurut Russell harus dipertimbangkan sebagai nama diri logis (Russell, 1980: 94; Toety Herati, 1984: 86).
1981 : 31, Wittgenstein,1995: 31). Inilah sesungguhnya tujuan utama yang terkandung dalam prinsip isomorfi itu. Metafisika yang terdapat dalam teori Russell ini merupakan suatu ―Pluralisme radikal‖ (Bertens, 1981 : 31), sebab realitas atau dunia fakta itu dipecah menjadi fakta atomis. Corak pandangan metafisis yang didasarkan atas analisis bahasa itu merupakan ciri khas yang menandai kaum Atomisme Logis yang diteruskan dan diperkuat dalam pemikiran Wittgenstein.
4. Fungsi Kebenaran
contoh: ‖Saya kira hari akan hujan‖, kalimat ini mengandung kalimat subordinat yaitu ‖hari akan hujan‖. Sebuah kalimat merupakan bentuk atomis jika ia mengandung satu relasi kata dan sejumlah kata lain yang terkecil (Russell, 1980: 95).
5. Proposisi Atomis dan Proposisi Majemuk
logis, sehingga diperoleh proposisi yang paling sederhana yang mengacu pada fakta yang paling sederhana pula –fakta atomis— yaitu proposisi atomis. Setiap proposisi itu pada hakikatnya mengacu pada dua hal yaitu data inderawi (particularia) yang merupakan hasil persepsi konkret individual, dan sifat atau hubungan (universalia) dari data inderawi itu tadi (Toeti Heraty, 1984 : 86).
―Socrates was a wise Athenian, consists of two facts, ‗Socrates was a wise‘ and ‗Socrates was an Athenian‘. A fact which has no parts that are facts is called by Mr Wittgenstein a Sachverhalt. This is the same thing that calls an atomic fact. An atomic fact, although it contains no parts that are facts, nevertheless does contain parts‖ (Russell, 1995: 12).
(―Kalimat ‗Socrates adalah warga Athena yang bijaksana‘, terdiri dari dua fakta, yaitu ‗Socrates adalah orang yang bijaksana‘ 'dan' Socrates adalah warga Athena‘. Menurut Mr. Wittgenstein, sebuah fakta yang tidak memiliki bagian-bagian yang berupa fakta disebut Sachverhalt. Hal ini sama dengan ‗fakta atomik‘. Sebuah ‗fakta atomik‘, meskipun tidak berisi bagian-bagian yang merupakan fakta, namun tetap mengandung bagian-bagian‖).
tidak ada fakta molekuler atau fakta majemuk, yang ada hanyalah fakta atomis (Russell, 1995: 13-17).
Suatu proposisi atomis menurut Russell dalam kata pengantar Tractatus Logico-Philosophicus, mempunyai arti tertentu karena mengacu pada fakta atomis. Fakta atomis itu sendiri tidak dapat dikatakan benar atau salahnya, sebab ia tidak dapat mengungkapkan dirinya sendiri. Hanya bahasa –proposisi atomis— yang merupakan sarana untuk mengungkapkan perihal fakta atomis itulah yang dapat dinilai benar atau salahnya; sedangkan unsur yang terdapat dalam proposisi atomis seperti; Socrates, bijaksana, dan lain-lain disebut objek (Russell, 1995: 12).
Konsep Atomisme Logis Russell inilah yang akan dilanjutkan dan dikembangkan oleh Wittgenstein dalam Tractatus Logico-Philosophicus.
C. Ludwig Wittgenstein I (1889 – 1951)
pada analisis bahasa melalui teknik analitika, bukan membahas tentang fakta atau realitasnya sendiri.
1. Konsep Atomisme Logis Wittgenstein Periode I Filsafat Wittgenstein dibagi menjadi dua periode, periode pertama filsafatnya (Wittgenstein I), dikenal melalui karyanya Tractatus Logico-Philosophicus, sedangkan periode kedua filsafatnya (Wittgenstein II), termuat dalam karyanya Philosophical Investigations. Khusus pembahasan mengenai konsep Atomisme Logis ini dapat ditemukan dalam periode pertama filsafatnya, sekaligus Wittgenstein I ditempatkan sebagai tokoh utama Atomisme Logis. Pembahasan mengenai konsep Atomisme Logis dari Wittgenstein ini dikaitkan langsung dengan karya besarnya, Tractatus Logico-Philosophicus.
oleh dalil di belakangnya yang ditandai dengan pecahan desimal (1.1, 1.11, 1.12, dan seterusnya). Kurang lebih ada lima ratus dua puluh lima (525) dalil yang termuat dalam 189 halaman minus index dalam buku versi bahasa Inggris dan bahasa Jerman tersebut.
Kendatipun Tractatus bukanlah sebuah karya filosofis yang panjang, namun isinya memuat dasar-dasar pemikiran luas dari Wittgenstein, sehingga pengaruh yang ditimbulkannya begitu besar dalam bidang filsafat, khususnya bagi gerakan baru yang dikenal dengan nama filsafat analitis. Sejak dipublikasikannya buku ini untuk pertama kali (1921), hampir dapat dipastikan, metode analisis bahasa telah mendapatkan tempat yang cukup terhormat di gelanggang filsafat, terutama di Inggris. Nama besar Wittgenstein mulai dikenal peminat filsafat sebagai seorang tokoh utama Atomisme Logis disamping Russell yang telah lebih dahulu dikenal sebagai seorang filsuf.
2. Dalil Utama Tractatus Logico-Philosophicus
1. The world is everything that is the case (Wittgenstein, 1995: 31).
(―Dunia adalah segala sesuatu yang sedemikian‖).
2. What is the case, the fact, is the existence of atomic facts ((Wittgenstein, 1995: 31).
(―Apakah yang sedemikian itu, fakta, yaitu keberadaan fakta-fakta atomis‖).
3. The logical picture of the facts is the thought ( Wittgenstein, 1995: 43).
(―Gambaran logis fakta adalah pikiran‖). 4. The thought is the significant proposition
(Wittgenstein, 1995: 61).
(―Pikiran adalah proposisi yang bermakna‖). 5. Proposition is a truth-functions of elementary
propositions.
(―Proposisi adalah suatu fungsi kebenaran proposisi-proposisi elementer‖).
(An elementary proposition is a truth-function of itself) Wittgenstein, 1995: 103).
6. The general form of truth-function is proposition (Wittgenstein, 1995: 153).
(―Bentuk umum fungsi kebenaran adalah proposisi‖).
7. Whereof one cannot speak, thereof one must be silent (Wittgenstein, 1995: 189).
(―Sesuatu yang tidak dapat dibicarakan atau dipikirkan sebaiknya dibiarkan dalam keheningan‖).
merupakan sikap dan pandangan metafisis yang pluralistis.
Dalil ketiga, ―The logical picture of the facts is the thought‖ menegaskan bahwa gambaran logis fakta itu adalah pikiran, atau bisa dikatakan bahwa pikiran itu mencerminkan gambaran logis fakta. Dalil ketiga ini pula yang kemudian dikembangkan menjadi teori gambar (The Picture Theory). Teori gambar adalah sebuah pandangan yang menegaskan adanya paralelitas antara dunia dengan bahasa. Pikiran merupakan cerminan gambaran logis fakta, sedangkan bentuk pikiran diungkapkan ke dalam bahasa. Wittgenstein menggambarkan tentang gambaran fakta dalam pikiran untuk kemudian diungkapkan ke dalam bahasa sebagai berikut:
("Kita membuat penggambaran fakta-fakta bagi diri kita sendiri. Untuk objek sesuai dengan unsur-unsur gambar. Unsur-unsur-unsur gambar berdiri, dalam gambar, untuk objek. Gambar terdiri dalam kenyataan bahwa unsur-unsur itu dikombinasikan satu sama lain dalam cara yang pasti. Pada gambar dan foto, harus ada sesuatu yang identik agar salah satu dapat menjadi gambar dari lain secara keseluruhan").
Dalil-dalil inilah yang kemudian dikenal sebagai teori gambar atau teori cermin (The Picture Theory).
menyembunyikan pikiran seseorang, sehingga dari bentuk penampilan eksternal seseorang melalui bahasa tidak dapat disimpulkan begitu saja apa yang sedang ia pikirkan (Wittgenstein, 1995: 63).
mengacu pada fakta atomis, sehingga kebenarannya dapat diterima secara logis. Oleh karena itu analisis logis berfungsi untuk melacak keberadaan proposisi elementer.
berlebih yang tidak diperlukan. Misalnya: pria duda, wanita janda. Proposisi logika tidak dapat diuji secara empirik, karena itu para logikus menjadikannya sebagai postulat (Wittgenstein, 1995: 163).
benda (Titus, Smith, and Nolan, 1984 60). Perbincangan tentang subjek itu termasuk ke dalam wilayah metafisika. Kematian juga merupakan tema yang sering dibicarakan dalam metafisika atau wilayah agama menurut Wittgenstein bukanlah sebuah peristiwa kehidupan, karena kematian tidak dialami dalam kehidupan. Death is not an event of life. Death is not lived through (Wittgenstein, 1995: 6.4311).
3. Konsep Tanda Dalam Tractatus
Ada beberapa butir pemikiran Wittgenstein dalam Tractatus yang membicarakan tentang masalah tanda. Pertama; dalil 3.327 yang berbunyi:‖The sign determines a logical form only together with its logical syntactic application‖ (Wittgenstein, 1995: 57). Tanda menentukan sebuah bentuk logis hanya bersama dengan aplikasi sintaksis logis, artinya sebuah tanda dalam pemikiran Wittgenstein I merupakan sesuatu yang mengandung struktur logis, sehingga dalam penerapannya dapat dipahami manusia secara logis pula. Pandangan ini sama halnya dengan mengatakan bahwa bahasa sebagai tanda dalam kehidupan manusia mengandung struktur logis, sehingga membuka peluang bagi orang lain untuk memahami apa yang ingin disampaikan.
Ketiga; dalil 3.3442 yang berbunyi:‖The sign of the complex is not arbitrarily resolved in the analysis, in such a way that its resolution would be different in every propositional structure‖ (Wittgenstein, 1995: 61). (―Tanda kompleks tidak serta-merta diselesaikan dalam analisis, sedemikian rupa sehingga resolusinya akan berbeda dalam setiap struktur proposional"). Tanda yang kompleks dalam hal ini mengacu pada proposisi majemuk yang dapat dipecah ke dalam proposisi yang lebih kecil, yakni proposisi elementer melalui teknik analisis. Contoh: ―Megawati ketua Umum PDIP yang mantan Presiden RI ke-5 berpidato pada peringatan Hari Lahirnya Pancasila‖ terdiri atas dua proposisi elementer, yaitu (1) Megawati sebagai ketua umum PDIP berpidato pada peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2011, (2). Megawati sebagai mantan presiden RI ke-5 berpidato pada peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2011.
4. Bahasa Logika
kalimat yang mengandung pengertian, adalah menggambarkan berbagai bentuk peristiwa. Jika bentuk peristiwa digambarkan melalui suatu proposisi, maka hasilnya ada dua kemungkinan, yaitu proposisi itu benar atau sebaliknya proposisi itu salah (Hacker, 2001: 72). Peran proposisi untuk menggambarkan bentuk-bentuk peristiwa (state of affairs) inilah yang merupakan sentral pemikiran Wittgenstein dalam Tractatus. Tugas utama filsafat adalah menggambarkan realitas sebagaimana adanya melalui ungkapan yang tepat dan logis, karena itu pemikiran filsafat terdahulu perlu diklarifikasi dan dianalisis secara kritis.
orang itu berpikir tidak logis pula (Wittgenstein, Ludwig, 1995: 43).
Penggunaan bahasa logika yang sempurna berarti pemakaian alat-alat bahasa –kata dan kalimat— secara tepat, sehingga setiap kata hanya mempunyai suatu fungsi tertentu saja, dan setiap kalimat hanya ―mewakili‖ suatu keadaan faktual saja. Suatu bahasa logika yang sempurna mengandung aturan sintaksis sehingga mencegah ungkapan tidak bermakna, dan mempunyai simbol tunggal yang selalu bermakna unik dan terbatas. salah Satu fungsi filsafat menurut Wittgenstein, adalah menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dikatakan (atau dipikirkan) dengan menghadirkan secara jelas sesuatu yang dapat dikatakan (Edwards, Paul, 1967 : 331). Suatu karya filsafat bagi Wittgenstein seharusnya mengandung penjelasan. Apa yang dihasilkan dari suatu karya filsafat bukan melulu sederetan ungkapan filsafati, melainkan membuat ungkapan itu menjadi jelas. Wittgenstein menegaskan pandangannya sebagai berikut:
is not a number of ‗philosophical propositions‘, but to make propositions clear‖ (Wittgenstein, Ludwig, 1995: 77).
(―Objek filsafat adalah klarifikasi logis pikiran. Filsafat bukanlah teori melainkan suatu aktivitas. Suatu karya filsafat pada hakikatnya berisikan penjelasan-penjelasan. Hasil filsafat bukan lah sejumlah proposisi filsafati, melainkan membuat proposisi-proposisi tersebut menjadi jelas‖).
Upaya yang ditempuh Wittgenstein untuk membuat jelas ungkapan atau bahasa dalam filsafat ini serupa pula halnya dengan Russell, yaitu menentukan kesesuaian antara struktur bahasa dengan struktur realitas. Pandangan ini lebih dikenal dengan nama teori gambar (the picture theory).
5. Teori Gambar (The Picture Theory)
titik perbedaan di antara keduanya. Namun pada prinsipnya keduanya sependapat bahwa ada paralel mutlak antara bahasa dengan realitas.
Unsur mutlak yang diperlukan untuk mendukung sebuah ungkapan yang bermakna –dengan sendirinya merupakan proposisi— adalah suatu bentuk peristiwa ataupun suatu keadaan faktual (states of affairs). Wittgenstein menegaskan bahwa proposisi adalah gambaran realitas, jika seseorang memahami proposisi itu berarti ia mengetahui bentuk peristiwa atau keadaan faktual yang dihadirkan melalui proposisi tersebut. Seseorang dengan mudah dapat memahami proposisi itu tanpa perlu diberitahu lagi pengertian yang terkandung di dalamnya (Wittgenstein, 1995: 67).
diajukan oleh Aristoteles dalam prinsip logika. Selama ini kebanyakan filsuf telah menyalahgunakan pemakaian proposisi untuk mengungkapkan sesuatu yang tak terkatakan, sehingga sulit bagi seseorang untuk dapat mengatakan ‖ya‖ atau ‖tidak‖ terhadap kemungkinan realitas yang dikandungnya. Oleh karena itu ungkapan dalam filsafat terdahulu itu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu proposisi, karena tidak mencerminkan realitas apa pun. Dalam pandangan Wittgenstein, pengertian sebuah proposisi terletak pada situasi yang digambarkan atau dihadirkan di dalamnya (Pitcher, 1964 : 45).
struktur proposisi menggambarkan kemungkinan bagi kombinasi unsur-unsur dalam realitas, yaitu suatu kemungkinan mengenai keadaan faktual atau bentuk suatu peristiwa (Pitcher, 1964 : 78).
Unsur-unsur gambar adalah alat-alat dalam bahasa, seperti kata dalam kalimat, sedangkan unsur realitas adalah suatu keadaan faktual yang merupakan objek perbincangan dalam bahasa. Dengan demikian ada dua faktor utama yang mendukung teori gambar ini, yaitu proposisi yang menggunakan alat dalam bahasa filsafat dan fakta yang ada dalam realitas. Jenis proposisi yang paling sederhana dinamakan proposisi elementer yang merupakan penjelasan keberadaan suatu bentuk peristiwa. Keseluruhan proposisi elementer itu tadi merupakan bayangan seperangkat benda atau hubungan antar-benda di dunia, dan bayang-bayang itu kemudian menggiring benda atau hubungan antar-benda itu menjadi suatu gambar timbul (Sokolowski, 1964 : 179).
Wittgenstein berkeyakinan bahwa ia mempunyai alasan baik untuk menentukan adanya proposisi elementer biarpun contohnya tidak mungkin diberikan (Bertens, 1981 : 44). Proposisi elementer tidak dapat diajukan contohnya, maka keberadaan suatu bentuk peristiwa yang dungkapkan melalui proposisi elementer itu pun tidak diberikan contohnya oleh Wittgenstein. Proposisi elementer hanya mengatakan suatu bentuk peristiwa merupakan suatu gabungan objek atau sesuatu yang konkret (Wittgenstein, 1995: 31). Bentuk peristiwa itu merupakan bagian terkecil (elementer atau atomis) yang sesuai dengan proposisi elementer (Pitcher, 1964: 46). Wittgenstein sendiri mengatakan bahwa jenis proposisi yang paling sederhana –suatu proposisi elementer— menjelaskan keberadaan suatu bentuk peristiwa (Wittgenstein,1995: 89).
atau salah, sehingga sebuah proposisi mempunyai dua kutub dalam arti ia mengandung kebenaran jika bersesuaian dengan suatu peristiwa dan mengandung kesalahan jika tidak bersesuaian dengan suatu peristiwa.
Pengertian situasi atomis dianggap sebagai suatu bentuk peristiwa, karena Wittgenstein sendiri tidak menjelaskan secara lebih rinci tentang apa yang dimaksudkannya dengan situasi atomis tersebut. Sokolowski menafsirkan tentang situasi atomis bahwa istilah ‘atom‘ dipergunakan Wittgenstein serupa halnya dengan istilah ‘Archai‘ yang dipakai para filsuf Yunani, yaitu suatu keharusan prinsip filsafat. Alasan Wittgenstein, sesuai dengan apa yang disimpulkannya bahwa seseorang mengalami realitas material sebagai bentuk keluasan, oleh karena itu harus ada beberapa bagian benda yang sifatnya terbatas, yakni atom, yang dapat memperluas dirinya sendiri dan sebagai komponen dasar bagi pembentukan benda dalam lingkup yang luas (Sokolowski, 1964: 179).
dasar realitas, berarti kedua filsuf tersebut telah menunjukkan asal dunia dari fakta atomis. Bahkan dalil pertama dan kedua yang termuat dalam Tractatus pun sesungguhnya merupakan titik-tolak pemikiran Wittgenstein untuk menyusun pandangan metafisis. ‖The world is everything that is the case. The world is the totality of facts, not of things. What is the case, the fact, is the existence of atomic facts‖ (Wittgenstein, 1995: 31). (‖Dunia adalah segala sesuatu yang sedemikian. Dunia adalah keseluruhan fakta, bukan benda-benda. Apa yang sedemikian itu, fakta, yaitu keberadaan fakta atomis‖).
ke arah metafisika merupakan sesuatu yang tak terbantahkan.
D. Alfred Jules Ayer (1910-1989)
ini, menimbulkan perbedaan yang hakiki di antara kedua aliran ini.
Kendati demikian menurut komentar Charlesworth, sejarah filsafat mencatat tradisi analisis bahasa yang sesungguhnya terdapat dalam pemikiran Moore-Russell-Wittgenstein. Positivisme Logis hanya dianggap sebagai suatu penyelangan dari tradisi analisis yang sesungguhnya dari ketiga tokoh Analitika bahasa tersebut. Corak positif yang diterapkan dalam teknik analisis bahasa oleh kaum Positivisme Logis begitu ketat dan kaku, sehingga ada kecenderungan untuk menilai bahwa kaum Positivisme Logis ini telah membekukan metode filsafat Moore dan Wittgenstein itu menjadi suatu dogma (Charlesworth, 1959: 127). Salah satu jasa kaum Positivisme Logis adalah menjadikan filsafat analitis lebih dikenal di kalangan filsafat di luar Inggris.
1. Prinsip Verifikasi (Verification Principle)
yang demikian itu membawa perubahan yang cukup besar terhadap teknik analisis bahasa yang telah diajukan oleh Russell dan Wittgenstein, terutama mengenai tolok ukur untuk menentukan bermakna atau tidaknya suatu pernyataan. Sesuatu yang tidak dapat diukur bagi Positivisme Logis berarti tidak mempunyai makna. Makna sebuah proposisi tergantung apakah seseorang dapat melakukan verifikasi terhadap proposisi yang bersangkutan (Charlesworth, 1959: 138).
semacam itu terlihat dalam kalimat protokol dan inilah yang menjadi permulaan bagi ilmu (Beerling, 1966: 107). Penafsiran Schlick mengenai prinsip verifikasi ini menimbulkan perdebatan di kalangan kaum Positivisme Logis itu sendiri, terutama penganut Positivisme Logis yang muncul kemudian. Upaya untuk meletakkan prinsip verifikasi hanya pada peristiwa yang dapat dialami secara langsung, sama halnya telah menafikan bidang sejarah sebagai produk masa lampau dan prediksi (ramalan) ilmiah sebagai produk bagi masa yang akan datang.
Ayer, salah seorang penganut Positivisme Logis yang muncul kemudian, atau dapat dikatakan sebagai generasi penerus tradisi Positivisme Logis, menyadari pula kelemahan yang terkandung dalam prinsip verifikasi yang diajukan Schlick itu Ayer memperluas prinsip verifikasi itu dalam pengertian berikut:
―A further distinction which we must make is the distinction between ‗strong‘ and the ‗weak‘ sense of the term ‗verifiable‘. A proposition is said to be verifiable, in the strong sense of the term, if and only if, its truth could be conclusively established in experience. But it is verifiable, in the weak sense, if it is possible for experience to render it probable (Ayer, 1952 : 37).
(―Pembedaan lebih lanjut yang harus dibuat adalah pembedaan antara yang dapat diverifikasi secara ‗ketat' dan 'longgar'.'. Sebuah proposisi dikatakan telah terverifikasi dalam arti yang ketat, jika dan hanya jika, kebenarannya dapat ditegakkan secara meyakinkan dalam sebuah pengalaman. Namun hal tersebut akan terverifikasi dalam arti yang longgar, jika hal tersebut memungkinkan bagi sebuah pengalaman").
Ayer melalui kedua macam pengertian verifiable ini, terutama verifiable dalam arti longgar (weak sense) telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah masa lampau dan juga prediksi ilmiah atau perkiraan atas peristiwa masa depan, sebagai pernyataan yang mengandung makna.
2. Proposisi Analitis
―Planet Uranus memiliki duapuluh bulan‖, maka pernyataan ini merupakan proposisi empiris, karena pernyataan tersebut mengandung kemungkinan untuk diverifikasi. Misalnya; pengiriman satelit Voyager II oleh Badan Ruang Angkasa Amerika sebagai upaya untuk membuktikan apakah pernyataan tersebut dapat dibenarkan atau ditolak. Apabila dalam pembuktian nanti ditemukan ada duapuluh lima ataupun tigapuluh buah bulan yang mengitari planet Uranus, berarti pernyataan di atas ditolak, namun pernyataan itu tetap mengandung makna, karena ada cara untuk membuktikannya.
didasarkan pada penggunaan istilah yang pasti, jadi maknanya terletak pada bahasa atau ungkapan verbal (Charlesworth,1959: 132).
Suatu proposisi analitis yang semata-mata benar berdasarkan susunan simbolnya dapat dijumpai dalam matematik. Jadi kalau dikatakan ―10 x 10 = 100‖, maka kebenaran proposisi itu semata-mata tergantung pada fakta bahwa ungkapan simbol ―10 x 10‖ adalah sinonim dengan ―100‖.
Kebenaran proposisi analitis yang didasarkan pada a priori artinya, penjelasan yang sama merupakan pegangan untuk setiap kebenaran a priori lainnya. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan refleksi logis (a priori) menurut Ayer, seperti halnya contoh pengertian bahwa setiap spesialis mata (occulist) adalah seorang dokter mata, didasarkan atas fakta bahwa simbol ‖dokter mata‖ itu secara logis sama artinya dengan spesialis mata (Ayer, 1952: 85).
karena ―bulat‖ itu merupakan sifat yang sudah semestinya ada pada setiap lingkaran.
Proposisi analitis yang semata-mata didasarkan penggunaan istilah yang pasti maksudnya, proposisi analitis itu termasuk proposisi yang tidak mempunyai kandungan faktual, dan itu berarti, tidak ada pengalaman yang dapat membuktikan ketidakbenarannya (Ayer, 1952: 79). Contoh: Beberapa jenis serangga termasuk parasit atau kalau tidak, maka tak ada satu pun serangga yang parasit. Seseorang hanya perlu menganalisis istilah, bukan melakukan pengamatan untuk mendapatkan ada atau tidaknya serangga yang dikategorikan sebagai parasit.
3. Eliminasi Metafisika
pada kerangka bahasa logika. Kendatipun tampak kecenderungan yang lebih kuat dalam pemikiran Ayer itu untuk menerapkan teknik-teknik analisis bahasa dari Atomisme Logis, namun analisis bahasa sehari-hari seperti dalam pandangan Moore digunakan dengan maksud untuk mencegah atau menilai sejumlah pandangan metafisis (Charlesworth,1959: 135).