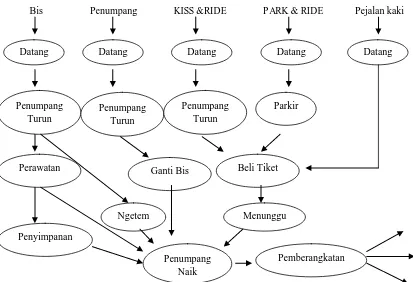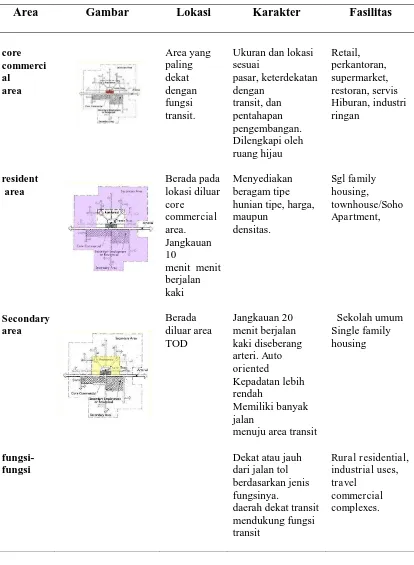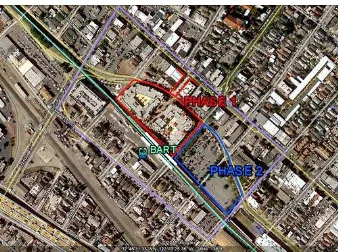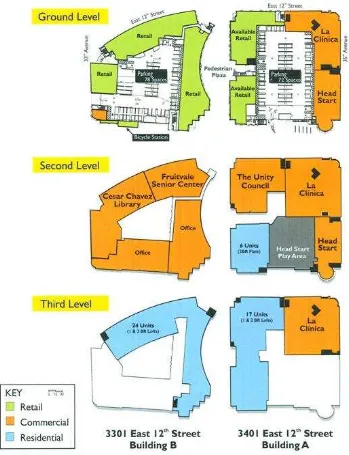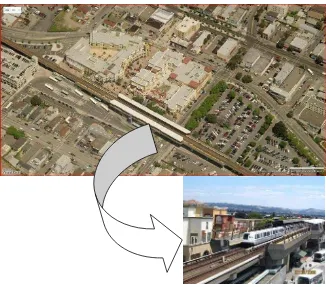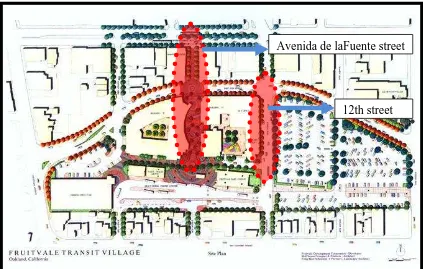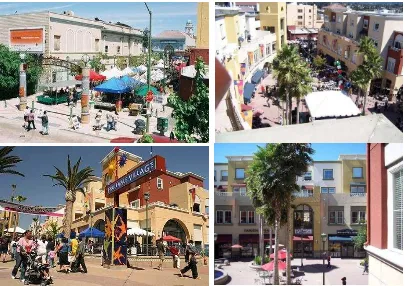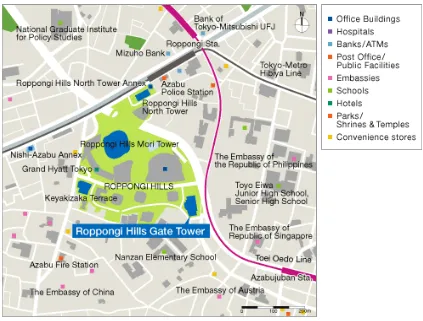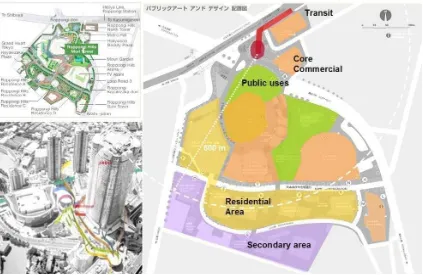BAB II
KAJIAN TEORITIS
2.1 Pengertian Terminal
Terminal merupakan salah satu fasilitas yang menunjang pergerakan manusia
dan barang dari satu tempat ketempat lain. Sebagai fasilitas umum, terminal harus
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda
transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Fungsi
terminal menurut Ditjen Perhubungan Darat, 1995 dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur
yaitu: penumpang, pemerintah, dan operator bus. Fungsi terminal bagi penumpang
adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau
kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya
fasilitas-fasilitas dan informasi (peralatan, teluk, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko,
loket, dll), serta fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi. Fungsi terminal bagi
pemerintah antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk
menata lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi
dan sebagai pengendali arus kendaraan umum. Fungsi terminal bagi operator bus
adalah untuk pengaturan pelayanan operator bus, penyediaan fasilitas istirahat,
informasi arah bus, dan fasilitas pangkalan.
umum mengambil dan menurunkan penumpang dari satu moda ke moda transportasi
lainnya, juga merupakan prasarana angkutan penumpang dan menjadi unsur ruang
yang mempunyai peran penting bagi efisiensi kehidupan wilayah. Keputusan Menteri
Perhubungan No. 31 Tahun 1995 tentang Prasarana Lalulintas Jalan mengatakan
bahwa terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra/atau antar-moda
transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan penumpang umum.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Perhubungan No.
31 Tahun 1995 menyatakan bahwa penentuan lokasi terminal penumpang dan barang
dilakukan dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan lokasi simpul yang
merupakan bagian dari rencana umum tata ruang, kepadatan lalu lintas dan kapasitas
jalan di sekitar terminal, keterpaduan moda transportasi baik intra maupun
antar-moda, kondisi topografi lokasi terminal, dan kelestarian lingkungan (Oktara, Tetriana
Vivi. 2008).
Tujuan diadakannya tempat perhentian sesuai dengan peraturan Dirjen
Perhubungan darat adalah untuk:
1. Menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
2. Menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum;
3. Kepastian keselamatan untuk menaikkan danlatau menurunkan
penumpang; dan
4. Kemudahan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan
Secara umum pemberhentian angkutan umum dapat dikelompokkan menjadi
3 (tiga) kategori, yaitu:
1. Perhentian di ujung rute (terminal)
Terminal adalah tempat dimana angkutan umum harus memulai atau
memutar untuk mengakhiri perjalannya. Pada lokasi perhentian ini
penumpang harus mengakhiri perjalanannya atau sebaliknya penumpang
memulai perjalanannya.
2. Perhentian terletak di sepanjang rute
Perhentian harus disediakan dengan jarak dan jumlah yang memadai, agar
penumpang diberi kemudahan untuk akses dan juga agar kecepatan
angkutan umum dapat dijaga pada batas yang wajar.
3. Perhentian pada titik dimana dua atau lebih lintasan bertemu
Pada perhentian ini, penumpang dapat bertukar angkutan dengan lintasan
rute lainnya. Pergantian angkutan umum pada titik tersebut dapat disebut
transfer (Aprianto, totok, 2006).
Adapun persyaratan umum yang harus dimiliki oleh tempat perhentian adalah
sebagai berikut:
a. Berada di sepanjang rute angkutan umum/bus;
b. Terletak pada jalur pejalan kaki dan dekat pada fasilitas pejalan kaki;
c. Diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau pemukiman;
2.1.1 Tipe dan fungsi terminal
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 31/1995, Terminal
penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya dibagi menjadi:
1. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk
angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan
pedesaan.
2. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk
angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan
pedesaan.
3. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk
angkutan pedesaan.
2.1.2 Pendekatan terminal bus
Terminal Bus adalah tempat sekumpulan bus mengakhiri dan mengawali
lintasan operasionalnya. Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka pada
bangunan terminal penumpang dapat mengakhiri perjalanannya, atau memulai
perjalananya atau juga dapat menyambung perjalanannya dengan mengganti lintasan
bus lainnya. Di lain pihak, bagi pengemudi bus, maka bangunan terminal adalah
tempat untuk memulai perjalanannya, mengakhiri perjalannya dan juga sebagai
tempat bagi kendaraan beristirahat sejenak, yang selanjutnya dapat digunakan juga
Jika kita amati suatu sistem terminal bus, maka kita akan melihat pada sistem tersebut
terdapat sekumpulan komponen yang saling berinteraksi satu dengan lainnya
(Ardiansyah, Ferry Wisnu, 2005).Komponen-komponen yang dimaksud meliputi:
1. Bus
Dari lintasan rutenya, bus datang di terminal, kemudian menurunkan
penumpang penumpangnya. Setelah menunggu beberapa lama (tergantung
pada jadwal), selanjutnya bus menaikkan penumpangnya kemudian pergi
kembali menelusuri lintasan rutenya. Terkadang, dengan alasan tertentu,
bus terpaksa harus diperbaiki atau dilakukan perawalan kecil, seperti
mengganti ban, mengganti busi ataupun penyetelan mesin. Untuk bus-bus
yang harus berangkat dari terminal di pagi hari, maka bus harus menginap
di tempat penyimpanan khusus.
2. Penumpang
Untuk penumpang, kegiatan di terminal dimulai dengan datangnya
penumpang, baik datang dengan bus ataupun datang dengan sarana
lainnya. Sesampainya diterminal, maka penumpang turun dari bus. Jika
ingin meneruskan perjalannya maka penumpang tersebut harus berganti
bus dengan lintasan rute yang sesuai dengan arah perjalanannya.
Sedangkan jika penumpang ingin mengakhiri perjalanannya dengan
berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan lain, maka dia keluar
Setelah itu, ketika bus yang dinanti datang, dia naik ke dalam bus dan
akhimya bus meninggalkan terminal.
3. Kiss & Ride
Bagi calon penumpang yang diantar dengan kendaraan oleh orang lain,
maka ketika sampai di terminal, dia segera turun untuk segera membeli
tiket sesuai dengan lintasan, rute dan arah yang dituju. Selanjutnya dia
menuju ke platform di mana bus yang dimaksud berada, dan menunggu
beberapa saat sampai bus dimaksud datang Selanjutnya dia naik ke bus
dan bersama bus pergi dari terminal.
4. Park & Ride
Bagi calon penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi ke terminal,
maka pada saat di terminal dia memarkir kendaraannya dan masuk ke
terminal untuk membeli tiket, sesuai dengan lintasan rute dan tujuannya.
Selanjutnya dia menuju ke platform di mana bus yang dimaksud berada,
dan menunggu beberapa saat sampai bus dimaksud datang. Kemudian dia
naik ke bus dan bersama bus pergi dari terminal.
5. Pejalan Kaki
Bagi seorang pejalan kaki yang ingin menggunakan bus untuk
perjalannnya, dia harus datang ke terminal dengan berjalan kaki.
Sesampainya di terminal dia membeli tiket, sesuai dengan lintasan rute
dimaksud berada, dan menunggu beberapa saat sampai bus dimaksud
datang. Kemudian dia naik ke bus dan bersama bus pergi dari terminal.
Jika kesemua komponen di atas memang diakomodasi dalam sebuah terminal maka
mekanisme yang ada secara keseluruhan (Gambar 2.1). Tapi perlu diingat bahwa
suatu terminal tidak selamanya berfungsi untuk mengantisipasi kelima komponen di
atas. Pada beberapa kasus, hanya dua atau tiga komponen saja yang dilayani,
misalnya pada terminal kecil di mana hanya menampung komponen bus, penumpang
dan kiss & ride.
Gambar 2.1 Mekanisme yang terjadi diTerminal bus (http://kamiharibasuki.blogspot.com/)
Bis Penumpang KISS &RIDE PARK & RIDE Pejalan kaki
Datang
Penumpang Turun
Perawatan
Penyimpanan
Penumpang Turun
Penumpang Turun
Parkir
Ganti Bis Beli Tiket
Ngetem Menunggu
Penumpang Naik
Pemberangkatan
Tempat berhenti di perlukan keberadaannya disepanjang rute angkutan umum
agar gangguan terhadap lalu lintas dapat diminimalkan, oleh sebab itu tempat
pemberhentian angkutan umum harus diatur tempatannya sesuai dengan kebutuhan.
Pemberhentian memiliki 2 karakter, yakni pemberhentian permanen dan
pemberhentian sejenak. Kegiatan berhenti secara permanen mengambarkan lokasi
pemberhentian sebagai sebuah destinasi. Sedangkan kegiatan berhenti sejenak
menggambarkan lokasi perhentian sebagai sebuah peralihan atau perlintasan (transit).
Ketika pergerakan tengah berlangsung, maka timbul simpul perpindahan dibeberapa
tempat.
2.2 Transit Orientasi Development (TOD)
Transit Oriented Development merupakan restruktur konsep pembangunan
yang berpusat pada fasilitas transit, yang sebenarnya telah dikenal sejak awal abad
ke-20 berupa konsep pengembangan terpadu pada stasiun kereta api dan Bus Rapid
Transit sebagai fasilitas publik transportasi massal. Yang kemudian coba di
rekonstruksi menjadi sebuah teori oleh Calthrope.
Konsep Transit Oriented Development (TOD) pada akhir 1980-an, dan
sementara yang lain telah mempromosikan konsep serupa dan berkontribusi pada
konsep desain, TOD menjadi bagian dari perencanaan modern ketika buku "The Next
American Metropolis" diterbitkan oleh Peter Calthrope pada tahun 1993. TOD telah
didefinisikan secara umum sebagai "komunitas mixed use yang mendorong orang
mengemudi." Calthorpe melihatnya sebagai neo-panduan tradisional desain
masyarakat yang berkelanjutan. Diluar definisi bentuk yang dibangun, itu juga teori
desain sebuah komunitas yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai masalah sosial.
Konsep TOD mengintegrasikan jaringan transportasi dengan pusat-pusat
aktivitas masyarakat perkotaan sehingga lebih mudah terjangkau dan mengurangi
penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Percampuran fungsi ini dikombinasikan
dengan keseluruhan ruang-ruang publik seperti plaza, berbentuk seperti sebuah
kompleks kawasan yang compact, dimana warganya dapat hidup, bekerja, dan
bersantai pada ruang-ruang pedestrian dan menawarkan variasi pilihan aktivitas
dengan akses yang nyaman.
Konsep TOD berfokus pada percampuran fungsi pada lahan, seperti hunian,
perkantoran, perdagangan, fasilitas publik dan hiburan dengan jarak-jarak yang
nyaman untuk berjalan (tidak lebih dari 600 meter atau 5-10 menit berjalan) yang
terintegrasi dengan titik transit, misalnya stasiun kereta api atau stasiun bus,
(Calthrope, 1993) (Gambar 2.2).
Pada beberapa lokasi, jarak berjalan yang nyaman ini dipengaruhi sekali oleh
topografi, iklim, dan kondisikondisi fisik alam lainnya. Untuk itu, ukuran kawasan
TOD ini menjadi sangat relatif, busa lebih besar ataupun lebih kecil tergantung
kondisi di lingkungan sekitarnya. Konsep TOD dapat diterapkan pada wilayah
metropolitan kota yang sudah berkembang maupun daerah pinggiran kota, khususnya
daerah yang belum dikembangkan undeveloped, maupun daerah yang potensial untuk
dikembangkan kembali redevelopment. Pemilihan dan penempatan fungsi-fungsinya
harus memperhatikan kesesuaian dengan lingkungan di sekitar kawasan.
2.2.1 Prinsip transitoriented development
Sebagai strategi untuk mencapai tujuan dari konsep TOD yakni member
alternatif bagi pertumbuhan pembangunan kota, sub urban dan lingkungan ekologis
disekitarnya maka dirumuskan 7 prinsip urban desain dalam transit oriented
development, yaitu:
a. Mengorganisasi pertumbuhan pada level regional menjadi lebih kompak
dan mendukung fungsi transit.
b. Menempatkan fungsi komersial, pemukiman, pekerjaan dan fungsi umum
dalam jangkauan berjalan kaki dari fungsi transit.
c. Menciptakan jaringan jalan yang ramah terhadap pejalan kaki yang secara
langsung menghubungkan destinasi.
d. Menyediakan campuran jenis, segmen dan tipe pemukiman.
f. Menjadikan ruang publik sebagai fokus dari orientasi bangunan.
g. Mendorong adanya pembangunan yang bersifat mengisi infill dan
pembangunan kembali redevelopment pada area transit.
2.2.2 Struktur transitoriented development
Prinsip-prinsip yang telah dijabarkan sebelumnya akan berimplikasi pada
desain struktur TOD. Lebih detail struktur TOD dan daerah sekitarnya terbagi
menjadi area-area sebagai berikut:
1) Fungsi publik public uses. Area fungsi publik dibutuhkan untuk
memberikan pelayanan bagi lingkungan kerja dan pemukiman didalam
TOD dan kawasan disekitarnya. Lokasinya berada pada jarak yang
terdekat dengan titik transit pada jangkauan 5 menit berjalan kaki.
2) Pusat area komersial core commercial area. Adanya pusat area
komersial sangat penting dalam TOD. Area ini berada pada lokasi
jangkauan 5 menit berjalan kaki. Ukuran dan lokasi sesuai dengan kondisi
pasar, kedekatan dengan titik transit dan pentahapan pengembangan.
Fasilitas yang ada umumnya berupa retail, perkantoran,supermarket,
restoran servis dan hiburan.
3) Area pemukiman residential area. Area pemukiman termasuk pemukiman
yang berada pada jarak perjalanan pejalan kaki dari area pusat komersial
tipe pemukiman, termasuk single-family housing, townhouse,
condominium dan apartement.
4) Area sekunder. Setiap TOD memiliki area yang berdekatan dengannya,
termasuk area diseberang kawasan yang dipisahkan oleh jalan arteri.
Area ini berjarak lebih dari 1 (satu) mil dari pusat area komersial.
Jaringan area sekunder harus menyediakan beberapa jalan/akses langsung
dan jalur sepeda menuju titik transit dan area komersial dengan
seminimal mungkin terbelah oleh jalan arteri. Area ini memiliki
densitas yang lebih rendah dengan fungsi single-family housing,
sekolah umum, taman dengan komunitas yang besar, fungsi pembangkit
perkantoran dengan intensitas rendah dan area parkir.
5) Fungsi-fungsi lainnya, yakni fungsi-fungsi yang secara ekstensif
bergantung pada kendaraan bermotor, truk atau intensitas perkantoran
yang rendah yang berada diluar kawasan TOD dan area sekunder (Tabel
2.1).
Tabel 2.1 Karakter setiap area dalam transit oriented development
Area Gambar Lokasi Karakter Fasilitas
Area Gambar Lokasi Karakter Fasilitas
menuju area transit
Sekolah umum
2.2.3 Tipologi transitoriented development
Tipologi TOD berbeda-beda berdasarkan lokasi penerapan dan jenis
pengembangannya. Berdasarkan konteks lokasinya TOD dapat dikembangkan baik
pada daerah metropolitan maupun pada daerah yang belum berkembang dan sedang
mengalami urbanisasi selama lokasi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan
kembali redevelopment, re-use and renewal. Sehingga terdapat dua model
pengembangan dalam TOD, yaitu:
1) Neighborhood TOD, merupakan TOD yang berlokasi pada jalur bus
feeder dengan jarak jangkauan 10 menit berjalan (tidak lebih dari 3 mil)
dari titik transit. Neighborhood TOD harus berada pada lingkungan
hunian dengan densitas menengah, fasilitas umum, servis, retail dan
rekreasi. Hunian dan pertokoan lokal harus disesuaikan dengan konteks
lingkungan dan tingkat pelayanan transit. Konsep ini juga membantu
pengembangan hunian bagi masyarakat menengah kebawah, dengan
dimungkinkannya pencampuran variasi hunian.
2) Urban TOD, merupakan TOD dengan skala pelayanan kota berada pada
jalur sirkulasi utama kota seperti halte bus antar kota dan stasiun kereta
api baik light rail maupun heavy rail. Urban TOD harus dikembangan
bersama fungsi komersial yang memiliki intensitas tinggi, blok
perkantoran dan hunian dengan densitas menengah tinggi. Setiap TOD
pada kota, memiliki karakter tersendiri sesuai dengan karakter
kawasan perkantoran, hunian, komersial yang memiliki densitas tinggi
karena memungkinkan akses langsung ketitik transit tanpa harus
melakukan pergantian dengan moda lain. Satu urban TOD dengan yang
lainnya berada dalam radius ½ sampai 1 mil untuk memenuhi kriteria
persyaratan area transit (Gambar 2.3).
Perbedaan fungsi Neighborhood TOD dan Urban TOD, terdiri atas fungsi publik,
pusat perkantoran dan permukiman (Tabel 2.2).
Tabel 2.2 Perbedaan fungsi Neighborhood TOD dan Urban TOD
Fungsi Neighborhood TOD Urban TOD
Publik 10% - 15% 5% - 15%
Pusat Perkantoran 10% - 40% 30% - 70%
Permukiman 30% - 80% 20% - 60%
Pada perjalanannya, tipologi TOD, baik urban maupun neighborhood TOD
berkembang seiring bertambahnya pelajaran yang dapat diambil pada kasus-kasus
penerapannya. Berdasarkan peruntukan lahan, fungsi dan perannya yang berbeda Gambar 2.3 Urban TOD (kiri) dan Neighborhood TOD (kanan)
dalam sistem regional, tipologi urban TOD menjadi urban downtown dan Urban
neighborhood. Urban downtown muncul sebagai pusat pemerintahan dan pusat
budaya dibanding sekedar persinggahan aktivitas bekerja. Sedangkan urban
neighborhood merupakan lingkungan historis yang umumnya mengelilingi pusat kota
downtown dan menyokong kehidupannya.
Karena itu keduanya memiliki densitas, ukuran dan jenis pelayanan transit
yang berbeda. Dalam mengaplikasikan jenis tipologi tersebut harus dipahami bahwa
pada dasarnya TOD adalah tentang menciptakan sinergi antara komunitas dan
kawasan regional, antara pekerjaan dan pemukiman, antara tingkat kepadatan dan
tingkat pelayanan transit, antara manusia dan kualitas komunitas yang aktif dan
dalam tingkat umur, tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda. Berkaitan dengan
tipologi yang diatas, mengaitkan fungsi transit dikawasan urban dan pengembangan
disekitarnya dengan mengkategorikan area pengembangan berbasis transit area
development berdasarkan karakter, land use, jenis fasilitas transit dan pendekatan
pengembangan yang dikehendaki. Maka tipologi urban downtown yang
dikategorikan dibagi kembali menjadi urban mixed use, dan speciality urban. Urban
mixed use diidentifikasi dengan adanya campuran land use dan berganda dengan
dominasi lingkungan struktur dan memiliki ketinggian lebih dari 3 lantai dan dilayani
beragam mode transportasi dalam sebuah jaringan. Speciality urban diidentifikasi
dengan adanya land use tematik, bercampur dan berganda. Kedua tipologi ini
Tabel 2.3 Karakter Urban Downtown dan Urban Neighborhood
Tipologi Densitas Fungsi Jenis Transit
Urban downtown
Minimal 60 unit/acre
Terspesialisasi sebagai sebuah distrik dengan fungsi dan kegunaan yang berbeda
Dilayani oleh beberapa pada jalur utama Sekolah dan taman
terintegrasi dengan area permukiman Jalan didesain dengan beragam fungsi
Perpanjangan dari grid jalan dari pusat kota. Dilayani oleh street car ataupun kereta. Berada pada jarak 5-10 menit berjalan kaki
2.2.4 Keuntungan TransitOriented Development
Beberapa pihak masih meragukan keuntungan dari diterapkannya TOD dalam
pemecahan permasalahan sprawl dan kemacetan (Hajar Suwantoro, 2009). Hal ini
dikarenakan pelaksanaan TOD masih belum dapat diaplikasikan secara menyeluruh
dalam sebuah skala regional. Dengan demikian manfaat yang dapat dirasakan dari
TOD adalah manfaat-manfaat yang bersifat jangka pendek seperti perbaikan
lingkungan dan komunitas. Perbaikan berupa berkurangnya pola sprawl dan
kemacetan dinilai belum dapat dirasakan. Namun, jika TOD dilihat sebagai sebuah
langkah awal dalam sebuah upaya jangka panjang yang bersifat menyeluruh dalam
skala regional, maka berbagai studi telah membuktikan manfaat dari prinsip-prinsip
TOD bagi kota. Diantara manfaat yang dibuktikan melalui studi-studi tersebut
1) Penurunan penggunaan mobil dan mengurangi pengeluaran keluarga
untuk akses. Penelitian untuk memprediksikan hubungan penggunaan
mobil serta densitas pengeluaran rumah tangga untuk transportasi telah
diadakan oleh tim gabungan dari Center of Neighborhood Technology,the
Natural Resources Defense Concil dan the Surface Transportation Policy
Project. Penelitian tersebut membuktikan bahwa perbedaan pada tingkat
densitas dan transit dapat menjelaskan perbedaaan tingkat penggunaan
kendaraan per rumah tangga yang signifikan yakni variasi 3:1 pada tingkat
pendapatan yang sama dan jumlah anggota rumah tangga yang sama.
2) Peningkatan pejalan kaki dan pengguna transit. Sebuah penelitian telah
dilakukan Dittmar dan Poticha terhadap data perjalanan menuju lokasi
kerja di kawasan-kawasan TOD yakni empat suburban center di
Arlington County, dua urban station di San Francisco, dan tiga urban
stations di Chicago. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat
pejalanan kaki dan penggunaan transit pada setiap area stasiun dengan
kawasan TOD jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pejalan kaki pada
kawasan-kawasan lain di kota-kota tersebut secara keseluruhan.
3) Menghidupkan kembali kawasan pusat kota dan meningkatkan instensitas
serta densitas pembangunan disekitar area transit. Sebagai contoh adalah
keberhasilan pemerintah Arlington County dalam meningkatkan densitas
Rosslyn-Ballston yang secara terus menerus mulai ditinggalkan 36.4%
penduduknya tersebut.
4) Meningkatkan penjualan properti di sekitar transit. Pada kasus yang sama,
tingkat penjualan properti pada proyek ini pada Februari 2003 mencapai
US$ 166 juta, yakni rekor nilai tertinggi di Amerika selama beberapa
tahun.
5) Meningkatkan kesempatan bagi berbagai kegiatan dan fungsi di sekitar
transit. Beberapa variasi fungsi muncul dengan aktifnya kegitan transit
contohnya penitipan anak di Tamien Station di San Jose, rental dan parkir
sepeda di Long Beach, Car Sharing Program and Rental di berbagai kota
di Eropa dan Amerika seperti Chicago, Seattle, dan San Francisco.
2.3 Studi Banding Tema Sejenis
Studi banding tematik yang diambil mengenai kawasan-kawasan yang
dikembangkan berdasar konsep TOD, yaitu kawasan Fruitvale, Oakland, California
dan Roppongi Hills, Tokyo, Jepang.
2.3.1 Fruitvale Village, Oakland, California
Fruitvale Village berada di Oakland, California. Proyek Fruitvale Transit
Village adalah hasil dari kemitraan berbasis luas di antara organisasi publik, swasta,
Pembangunan berorientasi transit adalah konsep perencanaan yang berusaha
untuk menggunakan stasiun angkutan massal sebagai blok bangunan untuk
revitalisasi ekonomi dan perbaikan lingkungan. Pembangunan mixed-use berdekatan
dengan Fruitvale Bay Area Rapid Transit District station (BART) di Oakland,
California. Fruitvale, salah satu dari tujuh distrik masyarakat Oakland, adalah
masyarakat berpenghasilan rendah. Studi kasus ini berfokus pada penggabungan
prinsip-prinsip keadilan lingkungan ke dalam perencanaan dan desain Fruitvale
Transit Village (Gambar 2.5).
Kawasan Fruitvale adalah sebuah kawasan yang dikenal memiliki
karakteristik khusus karena penghuninya didominasi oleh etnis latin (amerika
selatan). Fruitvale Transit Village adalah pusat dari kawasan ini, yang dirancang
sebagai area komersial dan perkantoran yang melayani penduduk Fruitvale dengan
menciptakan lingkungan yang pedestrian-friendly (Gambar 2.6).
Gambar 2.5 Kawasan Fruitvale Village yang sudah direvitalisai (merah) dan kawasan rencana pembangunan tahap 2 (biru)
Pembangunan mencakup 47 unit apartemen dan 257.000 ft2 (±23.800 m2)
ruang komersial. Fasilitas-fasilitas lain yang tersedia antara lain perpustakaan, klinik
kesehatan, child development facility, community resource center, pusat lansia,
pedestrian plaza yang total luasnya 114.000 ft, retail seluas 40.000 ft,
perkantoran seluas 24.000 ft, community service seluas 40.000 ft2 dan fasilitas
parkir sebanyak 150 unit, (Gambar 2.7).
Gambar 2.6 Kawasan Fruitvale Village yang sudah direvitalisasi
Rencana Tahap 2 (diuraikan dalam warna biru pada Gambar 2.6) sedang
dilakukan. Sementara ini difokuskan sebagai area parkir kendaraan. Tujuannya adalah Gambar 2.7 Zoning fungsi perlantai
untuk memperluas pada apa yang saat ini ada sambil terus membangun yang sudah
ada,selanjutnya menyatukan komponen perumahan dengan sektor ritel dan komersial.
Kawasan TOD Fruitvale adalah kawasan mixed-use yang berfokus pada
stasiun BART dan area komersial yang terkonsentrasi di International blvd.
International blvd adalah koridor komersial yang terdiri dari dua hingga empat lantai
bangunan retail yang melayani kawasan ini. Fruitvale Transit Village
menghubungkan stasiun BART dengan koridor komersial yang sudah ada
sebelumnya yaitu retail di sepanjang jalan International blvd. Letak stasiun BART
pada kawasan Fruitvale (Gambar 2.8).
Beberapa lahan parkir menghadap 12th street di perbatasan distrik, yang
menghasilkan lalu lintas pedestrian dari lahan parkir ini menuju stasiun BART
melalui Fruitvale Village. Alur pedestrian dalam kawasan ini dimulai dari stasiun
BART melalui plaza pedestrian Fruitvale Village dan jalan Avenida de laFuente
(dimana jalan-jalan tersebut tidak dilalui mobil) kemudian terbagi ke arah berlawanan
di International blvd pada Gambar 2.9.
Kawasan ini memiliki struktur yang jelas antara stasiun transit, area komersial
mixed-use dan kawasan existing. Pengorientasian dalam kawasan ini juga mudah
karena sekuens dari transit menuju area existing sangat sederhana berupa jalan lurus Gambar 2.9 Avenida de laFuente street (area bebas kendaraan)
(http://libweb.lib.buffalo.edu)
Avenida de laFuente street
jelas dengan karakteristik yang identik pada masing-masing distrik. Selain itu
Fruitvale Transit Village berperan sebagai simpul node utama di kawasan ini.
Selain itu terdapat sejumlah besar lalu lintas pedestrian sepanjang 12th street
dari/ke stasiun BART dari lahan parkir atau area residensial. Berikut ini suasana area
bebas kendaran pada Gambar 2.10.
Berdasarkan analisa pada contoh kasus TOD Fruitvale Transit Village, dapat
disimpulkan, sebagai berikut:
1. Area pengembangan kawasan TOD pada Fruitvale Transit Village
dilakukan pada lahan redevelopable. Area pengembangan TOD pada Gambar 2.10 Suasana areal bebas kendaraaan khusus pedestrian,Fruitvale Village
Fruitvale Transit Village relatif kecil. Berdasar teori TOD dapat
dikembangkan dalam jarak radius ¼ mile dari stasiun transit.
2. Berdasar perhitungan, kawasan TOD dapat mencakup area seluas 124
acre. Kawasan Fruitvale Transit Village memiliki luas pembangunan 16
acre, jauh lebih kecil dari pada luas yang dimungkinkan. Hal ini dapat
dipahami karena program pengembangan TOD di kawasan ini berjalan di
atas daerah eksisting yang sebelumnya sudah memiliki kepadatan
pemukiman dan fungsi-fungsi lainnya.
3. Pembangunan berorientasi transit pada kawasan ini disebabkan karena
kawasan Fruitvale dilalui oleh BART yang memiliki 44 stasiun di empat
kabupaten San Fransisco dan salah satu stasiun terletak pada Kawasan
Fruitvale Transit Village.
4. Berdasarkan analisa zona-zona yang terletak pada kawasan dibagi 3
bagian, yaitu: Stasiun BART, area pembangunan tahap 1 dan
pembangunan tahap 2 yang sedang berlangsung. Pada kawasan dapat
terlihat jelas antara stasiun transit, area komersial mixed-use dan kawasan
existing, dan Fruitvale Transit Village berperan sebagai simpul node
utama di kawasan ini.
5. Beberapa jalan utama pada kawasan ini bebas kendaraan sehingga
2.3.2 Roppongi Hills, Tokyo, Jepang
Kondisi perkotaan Tokyo yang dipenuhi dengan jalan-jalan kecil, hunian
berkepadatan rendah yang berbentuk sprawl, serta sedikit sekali taman atau ruang
terbuka publik tidak menyediakan kualitas urban yang baik bagi warganya. Apalagi,
orientasi cityscape yang mengarah ke horizontal tidak mencerminkan sebuah kota
yang memiliki reputasi internasional (Gambar 2.11).
Gambar 2.11 Tata guna lahan Roppongi Hills di Tokyo, Jepang
Terletak di barat daya Roppongi Station di jalur kereta bawah tanah Hibiya,
Roppongi Hills adalah proyek pembangunan kembali sektor swasta terbesar di
Jepang. Dengan luas sekitar 11,6 hektar dan total luas lantai sekitar 760.000 m2,
berdasarkan konsep "pusat peradaban Tokyo" (Gambar 2.12).
Roppongi Hills mengintegrasikan fungsi-fungsi dalam berbagai kebutuhan,
mulai dari perkantoran, museum berkelas internasional, menara hunian, hotel
berbintang, pusat sinema, pusat pertokoan, sebuah stasiun subway, dan restoran,
yang semuanya terhubung melalui jalur pedestrian yang nyaman. Kawasan ini Gambar 2.12 Jenis-jenis fungsi kawasan Roppongi Hills di Tokyo, Jepang
menyatukan fungsi publik, komersial dan aktifitas dalam berbagai level bangunan
(Gambar 2.13).
Kawasan ini sangat baik dalam merumuskan visinya yakni sebagai Art And
Intelligent City. Penerapan mixed use dapat dilihat dari beragamnya jenis komersial,
publik, dan hunian. Kawasan ini menyatukan fungsi publik, komersial, dan
aktifitas dalam berbagai level bangunan. Penggunaan hasil karya seni dalam
rancangan bangunan dan lansekap pun menghasilkan pengalaman yang menarik
di seluruh kawasan. Usaha penciptaan sense of place pada kawasan ini diawali dari
perumusan visinya sebagai art and intelligent city (Gambar 2.14).
Roppongi Hills mudah diakses melalui angkutan umum dengan jalur kereta Hibiya
dan Oedo lines berhenti di stasiun Roppongi dan keluar melalui Metro Hat pada
Gambar 2.15.
Kawasan ini berorientasi pedestrian melalui penyediaan koneksi antar Gambar 2.14 Posisi subway pada kawasan Roppongi Hills
(http://academyhills.com/)
serta penyediaan ruang terbuka yang sangat optimal. Beberapa suasana kawasan
Roppongi Hills pada Gambar 2.16.
Pada kawasan Roppongi Hills terdapat sculpture berbentuk laba-laba dengan
tinggi 10 meter dan berada tepat di depan mori tower seperti yang terlihat pada
Gambar 2.17.
Gambar 2.16 Suasana Kawasan Roppongi Hills (http://www.jerde.com)
Tabel proporsi fungsi pada Ropppongi Hills dibandingkan dengan proporsi
fungsi pada urban TOD (Tabel 2.4).
Tabel 2.4 Proporsi fungsi pada Ropppongi Hills dibandingkan dengan proporsi fungsi pada urban TOD
No Fungsi Fasilitas Luas lantai (m2)
Proporsi dari luas bangunan total
(%)
Proporsi pada TOD (%)
1 Komesrsial Retail 30.000 68.00 30-70
Office 380.000
Restaurants 15.000
2 Residensial Residential 140.000 31.00 20-60
Hotels 53.000
3 Publik Cultural space 6.300 1.00 5-15
Total luas lantai bangunan 624300 100.00 100
Berdasarkan analisa pada contoh kasus TOD Ropppongi Hills dapat
disimpulkan, sebagai berikut:
1. Area pengembangan kawasan TOD pada Ropppongi Hills dilakukan pada
lahan redevelopable. Area yang menjadi daerah pengembangan seluas 11,6
hektar dan total luas lantai sekitar 760.000 m2.
2. Area pengembangan kawasan TOD pada Ropppongi Hills menitik beratkan
pada konsep vertikal building dengan fungsi utama sebagai pusat kebudayaan
berkelas internasional, menara hunian, hotel berbintang, pusat sinema, pusat
pertokoan, sebuah stasiun subway, dan restoran.
3. Keberadaan stasiun subway yang menjadi lokasi transit bagi para penduduk
berada pada kawasan Roppongi Hills, dimana penggunaan kendaraan massal
masuk melalui stasiun roppongi dan keluar melalui bangunan Metro Hat.
4. Kawasan ini mengutamakan pejalan kaki pada seluruh kawasan, sehingga
antar bangunan dengan berbagai fungsi di akses menggunakan jalur pedestrian
yang menarik, lebar dan nyaman, serta penyediaan ruang terbuka yang sangat
optimal.
2.3.3 D-Cube City, Seoul, Korea
D-Cube City berlokasi dekat distrik Yeouido, tepat di sebelah selatan Sungai
Hangang didominasi zona industri, digunakan untuk menjadi rumah bagi pabrik
pengolahan batubara besar yang dimiliki oleh Daesung.
Client : Daesung Industrial Co, Ltd
Arsitek Lokal, Menara Apartemen : SAMOO Architects & Engineers
Arsitek Lanskap : Oikos
Desainer Water Fiture :Fluidity
D-Cube City adalah mega-kompleks yang mencakup, department store, ruang
kantor, tempat parkir pusat seni, garasi parkir, teater, hotel, restoran, taman hiburan,
Berbatasan langsung dan terhubung ke Stasiun Shindorim, proyek ini menjadi
contoh global pembangunan berkelanjutan, berorientasi transit mengakibatkan
regenerasi perkotaan dan kemajuan sosial. Posisi stasiun transit pada kawasan
D-Cube city (Gambar 2.18).
Transformasi inovatif kawasan menjadi mixed-use distrik publik mewakili
keberhasilan besar dari pengembangan lahan di Korea dan diharapkan menjadi katalis
untuk pertumbuhan berkelanjutan dan evolusi kawasan menjadi area perkotaan yang
hidup (Gambar 2.19).
Dimaksudkan untuk merumuskan ko-eksistensi alam dan budaya dalam
lingkungan perkotaan yang sangat padat, desain vertikal berseni D-Cube City
menggabungkan elemen mengingatkan lukisan lanskap tradisional Korea yakni
pegunungan dan sungai yang tak berujung. Di antara proyek desain yang penting
adalah membangun bentuk organik di Korea yang berbentuk seperti lentera Asia yang
membuat kesan hangat, cahaya bersinar tersaring melalui cladding eksterior pada
malam hari untuk menarik pengunjung ke dalam proyek. Ada juga jalur luar mendaki
melalui bangunan lentera menuju puncak kompleks ritel yang memiliki karakter
seperti sebuah kota bukit Italia dan dieksekusi dalam arsitektur modern kontemporer Gambar 2.19 Zoning Landscape D-Cube City
Keunikan untuk Seoul, desain D-Cube City menjalin ekspresi alami untuk
menciptakan sebuah oase perkotaan yang mengubah masa lalu industri kabupaten.
D-Cube City menggunakan hiburan, komponen lanskap budaya untuk mendorong
aktivitas pejalan kaki, sambil terus meningkatkan pola sirkulasi sekitarnya. Sebagai
ikon landmark baru untuk distrik, kantor bertingkat tinggi dan menara hotel ini
dirancang untuk melambangkan energi tumbuh ke arah langit dan kebangkitan daerah
sebagai pusat utama dari Seoul, dan mengeksrepsikan cerobong asap tambang
batubara yang dulu berada di kawasan tersebut (Gambar 2.20).
Daesung D-Cube City, yang terletak di ibukota padat Seoul, Korea,
menetapkan standar baru dalam mixed-use transit oriented development terhubung ke
jalur metro kota tersibuk. Kebudayaan baru dan tujuan komersial adalah salah satu
perkembangan kota terintegrasi penuh dari jenisnya, terdiri dari lebih dari 300.000
meter persegi kantor highrise dan hotel, ritel komersial multi-level, hiburan dan Gambar 2.20 D Cube City site map
D-Cube City muncul sebagai kehidupan utama kota Seoul , bekerja, bermain,
dan tujuan untuk menetap ,distrik yang berorientasi pejalan kaki yang otentik dan
bersemangat dengan enam tingkat 80.000 m2 kompleks ritel dan gedung pertunjukan
besar di atapnya sebagai pusat. 42 lantai landmark office dan menara hotel muncul
dari distrik komersial, sedangkan sebuah taman publik baru menghubungkan proyek
menuju ke Stasiun Shindorim. Dua menara apartemen yang berdekatan berlantai 50
melengkapi kompleks perkotaan yang baru (Gambar 2.21).
Gambar 2.21 D-Cube Guide (http://www.dcubecity.com) Location : 360-51 Sindorim-dong, Guro-gu, Seoul
Contruction Overview
a. Site Area : 16.853 m b. Gross floor area : 229.922m c. Parking space : 2.556 vehicles
Kota D-Cube menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya, sehingga menjadi
salah satu tujuan paling banyak dikunjungi di Seoul. Suasana kawasan D-Cube city
pada Gambar 2.22.
Sampai saat ini, Jerde telah memimpin desain pada lebih dari 25 proyek di
seluruh wilayah, termasuk Kota dan D3 Star City (2008) di Seoul, Changwon City 7
(2008); Color Square Stadium Mall di Daegu (2011); Habjung di Seoul, dijadwalkan
selesai pada tahun 2012, dan Eunpyung Kota Baru, dijadwalkan selesai pada 2014
(Gambar 2.23).
Tabel proporsi fungsi pada D-Cube City dibandingkan dengan proporsi fungsi
pada urban TOD (Tabel 2.5).
Tabel 2.5 Proporsi fungsi pada D-Cube City dibandingkan dengan proporsi fungsi pada urban TOD
No Fungsi Fasilitas Luas
lantai (m2)
Proporsi dari luas bangunan total
(%)
Proporsi pada TOD (%) 1 Komersial Retail/Entertaiment 74.507 40.69 30-70
Office 27.801
2 Residensial Residential 89.735 47.58 20-60
No Fungsi Fasilitas Luas
Civic space 23.831
Total luas lantai bangunan 251390 100.00 100
2.4 Temuan Studi Banding Kasus dan Literatur
Melalui kajian studi banding kasus yang diuraikan berdasarkan prinsip
perancangan TOD didapat beberapa hal yang dapat dipelajari sehingga menjadi
pertimbangan dalam pengembangan dan perancangan sebuah kawasan TOD, yaitu:
1. Hubungan antara area transit dan kawasan mixed-use:
Hubungan area transit dan kawasan mixed-use pada Fruitvale village,
dihubung kan oleh fruitvale bay area rapid transit distrik station (BART).
Kawasan TOD fruitvale merupakan kawasan mixed-use yang berfokus
pada stasiun BART dan International blvd/ koridor komersial, sehingga
pada kawasan dapat terlihat jelas antara stasiun transit, area komersial
mixed-use dan kawasan eksisting. Fruitvale village sendiri adalah pusat
kawasan di Oakland, California. Sedangkan pada studi kasus roppongi
hills, keberadaan stasiun subway yang menjadi lokasi transit bagi para
penduduk berada pada kawasan itu sendiri, hanya saja penggunaan
bangunan pada yang kawasan yang disebut metro hat. Sama hal nya
dengan kawasan roppongi hills, D-Cube City memiliki konsep yang
sebagian besar mirip hanya saja posisi stasiun transit berada di luar
kawasan mixed-use. Berikut penjelasan secara lebih jelas dalam Table 2.6.
Tabel 2.6 Hubungan antara area transit dan kawasan mixed-use
No Studi Kasus Hubungan antara area transit dan kawasan mixed-use 1 Fruitvale Village Area komersial dan kawasan eksisting di hubungkan oleh
stasiun BART
2 Roppongi Hills Jalur kendaraan dan jalur pedestrian terpisah, dihubung kan oleh suatu bangunan yang disebut Metro hat
3 D-Cube City Jalur kendaraan dan jalur pedestrian terpisah, pusat transit berada di luar kawasan di bagian jalan arteri.
2. Percampuran Fungsi:
Percampuran fungsi pada ketiga studi kasus telah terakomodasi dengan
baik. Namun proporsi masing-masing fungsi pada tiap studi kasus
berbeda-beda, Pada studi kasus Fruitvale Village proporsi fungsi terbesar
terdapat pada resendesial, karena kawasan tersebut berada pada kawasan
tingkat ekonomi menengah kebawah (Tabel 2.7).
Tabel 2.7 Proporsi Percampuran Fungsi pada Studi Kasus
No Studi Kasus Komersial Resendesial Publik
2 Roppongi Hills 68.00 % 31.00% 1.00%
3. Percampuran Hunian:
Percampuran kepadatan hunian pada masing-masing studi kasus
diterapkan berbeda-beda. Pada studi kasus Fruitvale Village kepadatan
hunian terletak pada fungsi apartemen, publik dan komersil. Sedangkan
pada Roppongi Hills terdapat tipologi hunian hotel dan service
apartments. Berbeda dengan kawasan D-Cube City sebagai ikon landmark
baru bagi warga Seoul, kantor bertingkat tinggi dan menara hotel ini
dirancang untuk melambangkan energi tumbuh ke arah langit dan
kebangkitan daerah sebagai pusat utama dari Seoul.
4. Jalan dan Sistem Sirkulasi:
Pada ketiga studi kasus, jaringan jalan sudah terakomodasi dengan baik,
akses menuju pusat transit, area pusat komersial, hunian, dan
fungsi-fungsi publik juga mudah dan jelas. Selain itu, seluruh jaringan jalan pada
studi kasus juga ramah terhadap pejalan kaki pedestrian friendly, ditandai
dengan adanya peneduh pada trotoar, jalur masuk menuju bangunan dan
parkir (Gambar 2.24).
5. Jalur Pejalan Kaki.
Jalur pejalan kaki pada ketiga studi kasus sudah terakomodasi dengan
baik, dari ketiga studi kasus kawasan TOD dirancang khusu bagi pejalan
kaki, sehingga tidak ada jalur kendaraan bermotor yang masuk dalam
kawasan mixed-use. Berikut suasan pedestrian bagi pejalan kaki pada
studi kasus Fruitvale village dan Roppongi Hills pada Gambar 2.25.
Berdasarkan studi literatur dan beberapa contoh studi kasus yang di bahas,
maka dapat disimpulkan kriteria-kriteria perencanaan TOD terhadap teori Kevin
Lynch. 1981 dan Shirvani Hamid 1985 (Tabel 2.8).
Tabel 2.8 Kriteria perencanaan TOD berdasarkan kajian teori dan studi kasus
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori 1 Land Use Densitas Densitas urban TOD antara land
use komersial :hunian : public maksimal = 70 :20:10
Kepadatan hunian pada Urban TOD sebaiknya minimal 12 unit/acre (30 unit/ha) dan rata-rata 15 unit/acre (37,5 unit/ha). Dan pada urban downtown rata-rata 60 unit/acre. yang harus dihubungkan dengan peraturan setempat
Calthorpe, 1993
Jenis Land Use Mempromosikan aktivitas pagi hingga malam hari dan meningkatkan keamanan
Mixed use pada setiap area pengembangan dengan jenis fungsi berdasarkan analisis pasar dan analisis tapak
Calthorpe, 1993
Lokasi a.Menempatkan fungsi
komersial, permukiman, pekerjaan, dan fungsi umum dalam jangkauan berjalan kaki dari fungsi transit
b.Melibatkan orientasi kegiatan berjalan kaki pada daerah komersial, area sekunder, dan area publik lainnya pada jarak 10 menit berjalan kaki
a.Core area berada pada jangkauan 5 menit berjalan kaki (380 m)
b.Area publik berada pada jangkauan 5 menit berjalan kaki (380 m)
c.Pemukiman area berada pada jangkauan 10 menit berjalan kaki (760 m)
d.Area sekunder berada pada jangkauan lebih dari 10 menit berjalan kaki
e.bangunan institusional dan bangunan komunitas lingkungan harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat berdekatan dengan perhentian transit.
Calthorpe, 1993
Konfigurasi Mengintegrasikan peruntukan secara mutual berkesesuaian dan mendukung satu sama lain
konfigurasi land use sesuai dengan kompetensi kawasan yang ditentukan dan potensi yang telah ada berdasarkan analisis
Calthorpe, 1993
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori pasar, tapak dan taksonomi intermodal
Luasan Luas masing - masing peruntukan mendukung fungsi transit
Ukuran area transit sebagai pusat area komersial paling sedikit 10 % dari total daerah perancangan modul TOD yang ada.
Calthorpe,
Mendekatkan bangunan ke jalur pejalan kaki / jalan pada batas garis sempadan bangunan (GSB). Jarak GSB bangunan dari jalan merefleksikan karakter tertentu kawasan dan menciptakan lingkungan berskala akrab.
Skala ruang tinggi banding lebar minimal 1:1. GSB pada area komersial umumnya adalah 0 disesuaikan dengan kebutuhan pejalan kaki. Dapat disiasati melalui penggunaan arcade.
Griffin, 2004
Intensitas a. Intensitas mendukung fungsi transit
b.Intensitas retail dan perkantoran diterapkan dengan tepat untuk mendapatkan lahan optimal
Jumlah lantai di area komersial boleh melewati KLB/FAR standar akibat penambahan intensitas, dengan penambahan lantai untuk fungsi rumah susun. Intensitas fungsi hunian dapat menggunakan TDR (Transfer of Development Right) . Disesuaikan aturan KLB rata-rata ditambah penambahan intensitas
Griffin, 2004
Bangunan parkir
Disarankan parkir on street, parkir dalam bangunan parkir atau basement
Menempatkan basement pada area yang jauh dari aliran air
Griffin, 2004
Fasade Muka bangunan menciptakan Fasade bervariasi. Jendela dan pintu masuk Griffin, Tabel 2.8 (Lanjutan)
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori lingkungan yang akrab bangunan komersial berskala pejalan kaki
fasade tidak terputus oleh jalur parkir mobil.
2004
Tipologi Menyediakan berbagai tipe densitas hunian
Menyediakan berbagai tipe densitas Sesuai analisa pasar
Griffin, 2004 Orientasi Pintu masuk bangunan komersial
harus berorientasi ke plaza, taman atau jalur pejalan kaki. Orientasi jangan menuju ruang dalam blok bangunan atau lot parkir.
Akses masuk, bukaan, teras, beranda atau
Menempatkan fungsi yang mengaktifkan interaksi dalam pergerakan
fungsi retail di lantai dasar, perkantoran, komersial lain, dan hunian di lantai atas
Griffin, 2004
Lokasi Transit Lokasi jalur transit harus ditentukan secara terintegrasi dengan kepadatan lokasi dan kualitas pengembangan suatu kawasan
Lokasi titik transit menjadi pusat dari area komersial dekat dengan ruang terbuka publik
Calthorpe, 1993
3 Sirkulasi dan Parkir
Tipe moda Menyediakan, menyambungkan titik transit dan memisahkan jalur dari moda-moda transportasi yang berbeda. Meminimalkan adanya konflik pada area crossing
a.Pemisahan jalur dengan yang memanfaatkan level underground dan upperground
b.Penggabungan titik transit dengan bangunan dan jalur pejalan kaki
c.Jalur kendaraan berupa drop off bangunan
Calthorpe, 1993 Tabel 2.8 (Lanjutan)
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori parkir dan basement
d.Jalur sepeda, adanya jalur sepeda yang terpadu dengan keseluruhan desain TOD
Akses masuk Akses masuk jelas dan didesain secara efisien yang memudahkan akses bagi publik, dan tidak ada yang memotong modul inti lingkungan TOD
Calthorpe, 1993
Parkir a. Memudahkan pencapaian b. Mendukung fungsi transit
a. Penempatan garasi dan tempat parkir diintegrasikan dalam bentuk Parkir di sisi jalan (sejajar) sekitar 7–8 feet (2,1 – 2,4 m) dan diterapkan di berbagai tipe jalan, kecuali jalan arteri, bangunan/ parkir, ataupun penggunaan bangunan parkir. b.Penyediaan parkir bagi sepeda
c. Mengurangi kebutuhan parkir kendaraan dari standar
Dibutuhkan akses langsung yang menghu-bungkan komunitas setempat dan kawasan disekitarnya bagi kendaran dan pejalan kaki dalam jarak tercepat
Adanya pemisahan jalur tiap moda transportasi dengan elemen penghubung yang tercepat dan termudah. Trotoar berisian dengan jalur kendaraan. Adanya pemisahan jalur tiap moda transportasi dengan elemen
Dittmar& Ohland, 2004 Tabel 2.8 (Lanjutan)
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori dan termudah. Konfigurasi jalur
kendaraan dan pejalan kaki pada area komersial pusat seimbang
penghubung yang tercepat dan termudah
Orientasi Adanya pemisahan jalur tiap moda transportasi dengan elemen penghubung yang tercepat dan termudah
Adanya orientasi jelas ke arah titik-titik transit melalui vista dan sistem wayfinding
Dittmar& Ohland, 2004
Tingkat pelayanan
Adanya distribusi pergerakan yang baik tidak menimbulkan kemacetan
LOS jalan maksimal sesuai dengan hirarki jalan dan bangkitan fungsi.
Calthorpe, 1993
Kecepatan Kecepatan lalu lintas menciptakan skala pejalan kaki yang nyaman
Batas kecepatan jalan-jalan bagian dalam kawasan rencana diperlambat yakni 15 miles/hour (24 km/jam)
Calthorpe, 1993
Ukuran skala pejalan kaki yang nyaman. Ukuran, bentuk, dan lebar menciptakan skala pejalan kaki yang nyaman
Lebar harus dikurangi menjadi lebar lintasan bersih 8-10 feet (2,42 - 3,03 m) dan lebar jalan 7,27 – 7,88 m sesuai hirarki jalan
Calthorpe, 1993
Visual Visual Adanya kualitas visual yang baik
Pembentukan arah jalan terhadap alam dan bangunan yang membentuk vista yang baik, khususnya pada area stasiun.
Fruin, 1971
Penerangan Perlunya penerangan tidak hanya pada jalur kendaraan namun juga gang dan jalur pejalan kaki
Perlunya penerangan yang cukup berada pada jarak 10- 15 meter
Fruin, 1971 Tabel 2.8 (Lanjutan)
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori Tipe
penggunan
Memperhitungkan berbagai skenario pergerakan bagi berbagai pengguna dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan
Jalur pejalan kaki/trotoar harus menyediakan jalur sepeda dan difabel sesuai standar pada lokasi-lokasi yang sesuai
Calthorpe, 1993
4 Pedestrian Keterhubungan Jalur-jalur pejalan kaki menerus dan saling berhubungan dengan jarak tercepat dan termudah. Ada akses penghubung antar bangunan atau jalan setapak / gang. ini dibutuhkan terutama antar bangunan hunian dan area komersial.
a. Penggunaan zebracross, jenis perkerasan yang berbeda, jembatan, skybridge /skywalk untuk menandakan jalur pejalan kaki yang menghubungkan titik transit. b. Desain persimpangan harus
mengakomodasi integrasi antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan c. Daerah drop off dari moda transportasi
tidak mengganggu pejalan kaki
Fruin ,1971
Orientasi Adanya orientasi jelas Adanya pembentukan vista dan sistem wayfinding. Pola sirkulasi dapat terbaca, berhirarki, dan sesuai kebutuhan fungsi yang dikaitkannya
Fruin ,1971
Penerangan Menciptakan skala pejalan kaki yang nyaman. Semua ini tanpa mengurangi aspek keamanan pejalan kaki, parkir sisi jalan ( on-street parking) dan jalur sepeda.
Adanya penerangan pada setiap jarak 10-15
Adanya distribusi pergerakan yang Baik. Menekankan
Konfigurasinya seimbang antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan. Tingkat
Fruin ,1971 Tabel 2.8 (Lanjutan)
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori kenyamanan berjalan kaki dengan
daya dukung yang sesuai area transit
pelayanan jalur pejalan kaki pada area transit 10-12 pfm (LOS C), publik dan komersial (LOS D) serta hunian (maksimal LOS jalur pejalan kaki C)
Kecepatan Memudahkan aksesibilitas transit- fungsi dan transit - transit dalam jarak ternyaman, termudah & tercepat
Jalur pejalan kaki penghubung titik transit dalam jangkauan 5 menit menggunakan kombinasi taksonomi vertikal dan horizontal. Penggunaan escalator, ramp, skywalk/ pedestrian bridge, dan underground tunnel secara proporsional
Fruin ,1971
Lebar Lebar jalur pejalan kaki nyaman, mudah dilihat dan dicapai
Jalur pejalan kaki didesain sepanjang sisi jalan menerus (tanpa terputus), dengan lebar 5 feet (1,5 m). lebar ini akan bertambah pada daerah komersial
Fruin ,1971
Peneduh Jalur pejalan kaki terlindung dari sengatan sinar matahari
Penggunaan pohon peneduh ataupun shelter Calthorpe, 1993
Jenis jalur pejalan kaki
Pejalan kaki terlindung dari kecelakaan kendaraan bermotor
Menyediakan dan memisahkan jalur pejalan kaki,sepeda, dan moda-moda kendaraan yang berbeda.Meminimalkan adanya konflik pada area crossingdengan jembatan penyeberangan. Penggunaan bollard
Calthorpe, 1993
visual Adanya akses visual yang baik Pembentukan vista terhadap alam dan bangunan yang menarik khususnya pada area
Calthorpe, 1993 Tabel 2.8 (Lanjutan)
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori stasiun
penerangan Penerangan jalur pejalan kaki menjamin keamanan
Adanya penerangan tidak hanya pada jalur kendaraan namun juga gang dan jalur pejalan kaki dalam jarak 10 - 15 m
Calthorpe, 1993
aktivitas Adanya aktivitas yang menjamin keamanan pejalan kaki selama 24 jam
Memberikan wadah interaksi sosial dan kegiatan 24 jam khusunya pada area transit melalui penempatan fungsi komersial 24 jam di level ground atau perencanaan kegiatan 24 jam
Fruin ,1971
Akses visual Pejalan kaki mudah dilihat dari jalan
Berdampingan dengan jalan mobil, sehingga terlihat langsung dari jalan raya
Fruin
a. Pepohonan ditanam dengan jarak maksimal 30 feet (9 m), sekaligus menjadi pengarah bagi pejalan kaki. b. Perhentian transit dilengkapi dengan
area tunggu dan nyaman dan terlindung dari cuaca.
Fruin ,1971
Luas Taman tersebar pada bebearapa lokasi di lingkungan TOD dan area sekunder secara merata
a. 1 – 4 acre (0,4 – 1,6 ha) village park diletakkan di antara 2 blok permukiman
b. 5 – 10 acre (2 – 4 ha) neighborhood park diletakkan pada perbatasan TOD atau bersebelahan dengan sekolah
Calthorpe, 1993 Tabel 2.8 (Lanjutan)
N o
Komponen Penataan
Variabel Prinsip Indikator Sumber
Teori c. 10 – 30 acre (4 – 12 ha) community
park sepanjang ruang terbuka berskala regional atau jalur sepeda d. Taman Pusat TOD dan plaza transit
sebagai pengarah pandangan ke area pusat komersial dengan luas 1 – 3 acre (0,4 – 1,2 Ha) sedangkan plaza transit umumnya lebih kecil
Bentuk dan Konfigurasi
Bentuk taman secara integral menyatu dengan lingkungan sekitar dan memiliki ciri khusus
a. Bukan merupakan lahan sisa. b. Berfungsi sebagai elemen tambahan,
sambungan, dan tembusan
Calthorpe, 1993 Tabel 2.8 (Lanjutan)