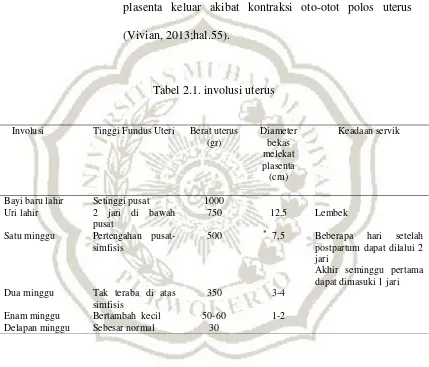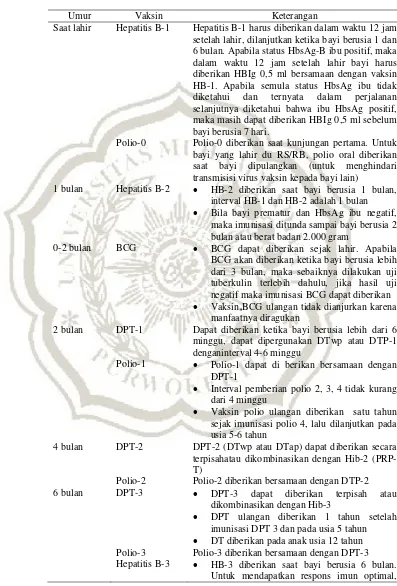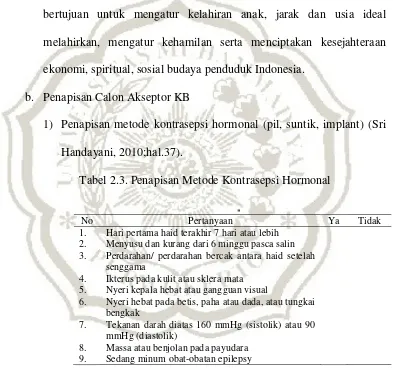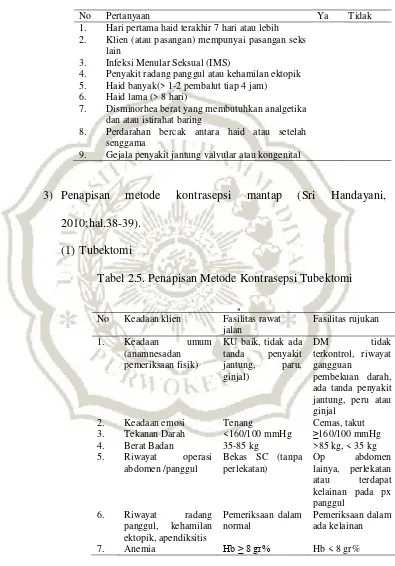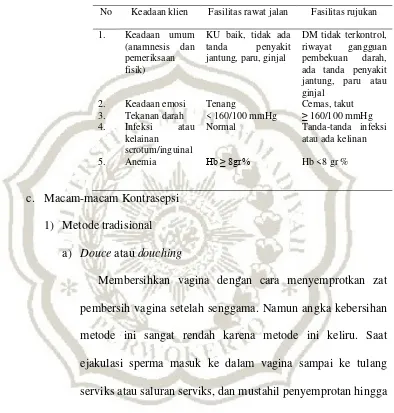BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Medis 1. Kehamilan
a. Definisi Kehamilan
Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan
ovum kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila
dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnnya bayi, kehamilan normal
akan berlangsung selama 40 minggu atau 10 bulan. Kehamilan terbagi
menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung dalam 12
minggu. Trimester kedua 15 minggu (dari minggu ke 13 hingga 27)
dan trimester ketiga 13 minggu (dari minggu ke 28 hingga ke 40)
(Prawirodardjo, 2014; h.213).
Proses kehamilan merupakan matarantai yang berkesinambungan
dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan
pertumbuhan zigot, nidasi pada uterus, pembentukan plasenta, dan
tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba,
2010;hal.75).
Dari beberapa pengertian kehamilan diatas, dapat disimpulkan
kehamilan adalah proses bertemunya spermatozoa dan ovum yang
b. Tanda – Tanda Kehamilan
Untuk memastikan diagnose suatu kehamilan, dibawah ini penilaian
terhadap beberapa tanda dan gejala kehamilan :
1) Tanda dugaan kehamilan
a) Amenorea (terlambat datang bulan)
Kontrasepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi
pembentukan folikel de graaf dan ovulasi. Dengan
mengetahui hari pertama haid terakhir dengan perhitungan
rumus neagle, dapat ditentukan perkiraan persalinan
(Manuaba, 2010;h.107).
b) Mual dan muntah (emesis)
Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan
pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Mual dan
muntah terutama pada pagi hari tersebut morning sickness.
Dalam batas yang fisiologis, keadaan ini dapat diatasi. Akibat
mual dan muntah, nafsu makan berkurang (Manuaba,
2010;hal.107).
c) Ngidam
Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu,
keinginan yang demikian disebut ngidam (Manuaba,
d) Sinkope atau pingsan
Terjadinya gangguan sirkulasi kedaerah kepala (sentral)
menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan
sinkop atau pingsan. Keadaan ini menghilang setelah usia
kehamilan 16 minggu (Manuaba, 2010;hal. 107).
e) Payudara tegang
Pengaruh Estrogen-progeteron dan somamamotrofin,
menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara.
Payudara membesar dan tegang. Ujung saraf tertekan
menyebabkan rasa sakit terutama pada hamil pertama
(Manuaba, 2010;hal. 107).
f) Sering miksi
Desakan rahim kedalam menyebabkan kandung kemih
cepat penuh dan sering miksi. Pada triwulan kedua gejala ini
sudah menghilang (Manuaba, 2017;hal. 107).
g) Konstipasi atau obstipasi
Pengaruh progesteron dapat menghambat peristatik usus,
menyebabkan kesuliatan untuk buang air besar (Manuaba,
2010;hal. 107).
h) Pigmentasi kulit
Keluarnya melanophore stimulating hormone hipofisis
dinding perut, dan sekitar payudara (Manuaba, 2010;hal.
108).
i) Varises atau penampakan pembuluh darah vena karena
pengaruh dari estrogen dan progesterone terjadi penampakan
pembuluh darah vena. Terutama bagi mereka yang
mempunyai bakat, penampakan pembuluh darah itu terjadi
sekitar genetalia eksterna, kaki, betis, dan payudara.
Penampakan pembluh darah ini dapat menghilang setelah
persalinan (Manuaba, 2010;hal. 108).
2) Tanda tidak pasti kehamilan
Tanda tidak pasti kehamilan dapat ditentuka oleh :
a) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya hamil.
b) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai tanda Hegar, tanda
Chadwicks, tanda Piscaseck, kontraksi Braxton Hick, dan
teraba ballottement.
c) Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif. Tetapi sebagian
kemungkinan positif palsu (Manuaba, 2010;hal. 108).
3) Tanda pasti kehamilan
Tanda pasti kehamilan dapat ditentukan meliputi :
a) Gerakan janin dalam rahim.
b) Terlihat/teraba gerakan janindan teraba bagian-bagian janin.
d) Didengar dengan stetoskop laenek, alat kardiotokografi, alat
doppler. Dilihat dengan ultrasonografi. Pemeriksaan dengan
alat canggih, yaitu rontgen untuk melihat kerangka janin,
ultrasono grafi (Manuaba, 2010;hal.109).
c. Ketidaknyamanan kehamilan tiap trimester dan cara penanganannya
1) Trimester 1
a) Kelelahan dan fatique
Salah satu dugaan wanita bahwa keletihan diakibatkan oleh
penurunan drastis laju metabolisme dasar awal kehamilan,
tetapi hal tersebut masih belum jelas, dugaan lain yaitu bahwa
peningkatan progesterone memiliki efek samping sehingga
menyebabkan tidur. Metode untuk meredakannya adalah
meyakinkan kembali wanita tersebut bahwa keletihan adalah
hal yang normal dan bahwa keletihan akan hilang secara
spontan pada trimester kedua. Pengetahuan ini akan membantu
wanita untuk sering beristirahat selama siang hari jika
memungkinkan hingga kelelahannya menghilang. Latihan
ringan dan nutrisi yang baik juga dapat membantu mengatasi
keletihan (Varney, 2007;hal.537-538).
Cara penanganannya yaitu: yakinlah bahwa hal ini normal
terjadi dalam kehamilan, dorong ibu untuk sering beristirahat,
b) Keputihan
Cara penanganannya: meningkatkan kebersihan dengan
mandi setiap hari, memakai pakaian dalam yang terbuat dari
katun bukan nilon, menghindari pencucian vagina dengan
sabun dari arah belakang ke depan (Kusmiyati, 2009;hal.123).
c) Ngidam
Cara penanganannya: tidak seharusnya menimbulkan
kekhawatiran asalkan cukup bergizi dan makanan yang
diinginkan makanan yang sehat, menjelaskan tentang bahaya
makanan yang tidak baik, mendiskusikan makanan yang dapat
diterima yaitu makanan yang bergizi dan memuaskan ngidam
atau kesukaan tradisional (Kusmiyati, 2009;hal.123).
d) Sering buang air kencing/nocturia
Cara penangananya: penjelasan mengenai sebab terjadinya,
kosongkan saat tersa dorongan untuk kencing, perbanyak
minum pada siang hari, jangan kurangi minum dimalam hari
untuk mengurangi nocturia (kecuali nocturia mengganggu tidur
dan menyebabkan keletihan), batasi minum bahan diuretika
alamiah (kopi, teh, cola, caffein) (Kusmiyati, 2009;hal.124).
e) Mual dan muntah
Dengan atau tanpa disertai muntah-muntah. Nausea lebih
kerap terjadi dipagi hari. Penyebab morning sickness masih
belum diketahui pasti, tetapi sejumlah ide telah dikembangkan .
Ide ini mencakup perubahan hormone selama kehamilan. Kadar
gula darah yang rendah disebabkan oleh tidak makan sehingga
mengakibatkan siklus yang tidak berujung pangkal. Lambung
yang terlalu penuh peristaltic yang lambat dan factor emosi
lainnya. Saran yang diberikan untuk meredakan morning
sickness yairu (Varney, 2007; hal. 536-537) :
(1) Makan porsi kecil, sering, bahkan setiap dua jam karena hal
ini lebih mudah dipertahankan dibanding makan porsi besar
tiga kali sehari.
(2) Jangan menyikat gigi anda segera setelah makan untuk
menghindari stimulus reflek gag.
(3) Hindari makanan beraroma kuat atau menyengat.
(4) Istirahat
2) Trimester II
a) Keputihan
Cara penanganannya: meningkatkan kebersihan dengan
mandi setiap hari, memakai pakaian dalam yang terbuat dari
katun bukan nilon, menghindari pencucian vagina dengan
sabun dari arah belakang ke depan (Kusmiyati,
b) Cloasma
Cara penanganannya: hindari sinar matahari berlebihan
selama masa kehamilan, gunakan bahan pelindung non
alergis (Kusmiyati, 2009;hal.126).
c) Striae gravidarum
Cara penanganannya: gunakan emollient topikal tau
antipruritik jika ada indikasinya, kenakan pakaian yang
menompang payudara dan abdomen (Kusmiyati,
2009;hal.126).
d) Hemorhoid
Cara penanganannya: hindari konstipasi, makan makanan
berserat, gunakan kompres es, kompres hangat, dengan
perlahan masukan kembali kedalam rektum jika perlu,
hindari BAB sambil jongkok (Kusmiyati, 2009;hal.127).
e) Konstipasi
Konstipasi diduga terjadi akibat penurunan paristaltik
yang disebabkan relaksasi otot polos pada usus besar ketika
terjadi peningkatan jumlah progesterone. Cara
penanganannya (Varney, 2007;hal.539) :
(1) Asupan cairan yang adekuat, yakni minum air minimal 8
(2) Istirahat cukup. Hal ini memerlukan periode istirahat
pada siang hari.
(3) Makan makanna yang berserat, dan mengandung serat
alami (misalnya : selada, daun seledri, kulit padi).
(4) Minum air hangat (misalnya : air putih, teh) saat bangkit
daro tempat tidur untuk menstimulasi peristaltik.
f) Sesak nafas
Cara penanganannya: dorong secara sengaja mengatur laju
dan dalamnya pernafasan pada kecepatan normal ketika
terjadi hiperventilasi, secara periodik berdiri dan
merentangkan lengan diatas kepala serta manarik nafas
panjang, mendorong postur tubuh yang baik melakukan
pernafasan intercostal, latihan nafas melalui senam hamil,
tidur dengan bantal ditinggikan, makan tidak terlalu banyak,
bagi yang merokok (berhenti), kosul ke dokter jika ada asma
(Kusmiyati, 2009;hal.129).
g) Nyeri ligamentum rotondum
Cara penangananya: tekuk lutut kearah abdomen, mandi
air hangat, gunakan bantalan pemanas pada area yang terasa
sakit hanya jika diagnosa lain tidak melarang, topang uterus
dengan bantal dibawahnya dan sebuah bantal diantara lutut
h) Pusing
Cara penanganannya: bangun secara perlahan dari posisi
istirahat, hindari berdiri terlalu lama dalam lingkungan yang
hangat atau sesak, hindari berbaring dalam posisi terlentang,
konsultasi/periksa untuk rasa sakit yang terus menerus
(Kusmiayati, 2009;hal.131).
i) Varises pada vagina dan vulva
Varises vena yang lebih mudah muncul ada wanita yang
memiliki kecenderungan tersebut dalam keluarga atau juga
memiliki factor predisposisi congenital. Varises dapat
diakibatkan oleh gangguan sirkulasi vena dan peningkatan
tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. Perubahan ini
diakibatkan penekanan penekanan uterus yang membesar
pada vena panggul saat wanita tersebut duduk atau berdiri
dan penekanan pada vena kava inferior saat ia berbaring.
Pakaian yang ketat menghambat aliran vena balik dari
ekstremitas bagian bawah, atau posisi berdiri yang lama
memperberat masalah tersebut. Penanganan untuk mengatasi
varises (Varney, 2007;hal.540)
(1) Hindari mengenakan pakaian ketat
(3) Sediakan waktu istirahat, dengan kaki dielevasi secara
periodik setiap hari.
(4) Berbaring dengan mengambil posisi sudut kanan
beberapa kali sehari.
(5) Ambil posisi inklisi beberapa kali sehari (untuk varises
vulva).
(6) Lakukan latihan ringan dan berjalan secara teratur untuk
memfasilitasi penigkatan sirkulasi.
(7) Lakukan latihan kegel untuk mengurangi varises vulva
atau hemoroid untuk meningkatkan sirkulasi.
j) Ginggivitis dan epulis
Cara penanganannya: menghindari trauma, kebersihan
gigi yang bersih, penggunaan sikat yang lunak dan
perlahan-lahan, menghindari infeksi (Kusmiyati, 2009;hal.132).
3) Trimester III
a) Keputihan
Cara penanganannya: meningkatkan kebersihan dengan
mandi setiap hari, memakai pakaian dalam yang terbuat dari
katun bukan nilon, menghindari pencucian vagina dengan
b) Sering buang air kecil
Cara penangananya: penjelasan mengenai sebab terjadinya,
kosongkan saat terasa dorongan untuk kencing, perbanyak
minum pada siang hari, jangan kurangi minum dimalam hari
untuk mengurangi nocturia (kecuali nocturia mengganggu tidur
dan menyebabkan keletihan), batasi minum bahan diuretika
alamiah (kopi, teh, cola, caffein) (Kusmiyati, 2009;hal.124).
c) Hemorhoid
Cara penanganannya: hindari konstipasi, makan makanan
berserat, gunakan kompres es, kompres hangat, dengan
perlahan masukan kembali kedalam rektum jika perlu, hindari
BAB sambil jongkok (Kusmiyati, 2009;hal.127).
d) Konstipasi
Cara penanganannya: tingkatkan intake cairan, serat
didalam diit, buah prem atau jus prem, minum cairan
dingin/panas jika perut kosong, istirahat yang cukup, senam,
membiasakan buang air secara teratur, BAB segera setelah ada
dorongan (Kusmiyati, 2009;hal.128).
e) Sesak nafas
Cara penanganannya: dorong secara sengaja mengatur laju
dan dalamnya pernafasan pada kecepatan normal ketika terjadi
diatas kepala serta manarik nafas panjang, mendorong postur
tubuh yang baik melakukan pernafasan intercostal, latihan
nafas melalui senam hamil, tidur dengan bantal ditinggikan,
makan tidak terlalu banyak, bagi yang merokok (berhenti),
kosul ke dokter jika ada asma (Kusmiyati, 2009;hal.129).
f) Nyeri ligamentum rotondum
Cara penangananya: tekuk lutut kearah abdomen, mandi air
hangat, gunakan bantalan pemanas pada area yang terasa sakit
hanya jika diagnosa lain tidak melarang, topang uterus dengan
bantal dibawahnya dan sebuah bantal diantara lutut pada waktu
berbaring miring (Kusmiyati, 2009;hal.130).
g) Pusing
Cara penanganannya: bangun secara perlahan dari posisi
istirahat, hindari berdiri terlalu lama dalam lingkungan yang
hangat atau sesak, hindari berbaring dalam posisi terlentang,
konsultasi/periksa untuk rasa sakit yang terus menerus
(Kusmiayati, 2009;hal.131).
h) Virises pada kaki/vulva
Varises vena yang lebih mudah muncul ada wanita yang
memiliki kecenderungan tersebut dalam keluarga atau juga
memiliki faktor predisposisi kongenital. Varises dapat
tekanan vena pada ekstremitas bagian bawah. Perubahan ini
diakibatkan penekanan penekanan uterus yang membesar pada
vena panggul saat wanita tersebut duduk atau berdiri dan
penekanan pada vena kava inferior saat ia berbaring. Pakaian
yang ketat menghambat aliran vena balik dari ekstremitas
bagian bawah, atau posisi berdiri yang lama memperberat
masalah tersebut. Penanganan untuk mengatasi varises
(Varney, 2007;hal.540) :
(1) Hindari mengenakan pakaian ketat
(2) Hindari berdiri lama
(3) Sediakan waktu istirahat, dengan kaki dielevasi secara
periodik setiap hari.
(4) Berbaring dengan mengambil posisi sudut kanan beberapa
kali sehari.
(5) Ambil posisi inklisi beberapa kali sehari (untuk varises
vulva).
(6) Lakukan latihan ringan dan berjalan secara teratur untuk
memfasilitasi penigkatan sirkulasi.
(7) Lakukan latihan kegel untuk mengurangi varises vulva
d. Patologis pada kehamilan
1) Trimester I dan trimester II
a) Anemia Kehamilan
b) Anemia kehamilan adalah suatu keadaan adanya penurunan
hemoglobin, hematocrit dan jumlah eritrosit dibawah nilai
normal (Rukiayah, 2010;hal.114).
c) Hyperemesis gravidarum
Hyperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan
pada ibu hamil
d) Abortus
Abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum mampu
hidup di luar kandungan dengan berat badan yang kurang dari
1000 gr atau umur kehamilan kurang dari 28 minggu
(Rukiayah, 2010;hal.136).
e) Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) adalah kehmilan yang
terjadi bila sel telur dibuahi berimplantasi dan tumbuh di luar
endometrium kavum uteri (Rukiayah, 2010;hal.163).
2) Trimester III
a) Kehamilan dengan hiperteni
Kehamilan dengan hipertensi adalah tekanan darah yang
kehamilan itu sendiri, memiliki potensi yang menyebabkan
gangguan yang serius pada kehamilan (Rukiyah, 2010;hal.167).
b) Pre eklamsia
Pre eklamsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi,
proteinuria dan edema yang timbul karen kehamilan (Rukiyah,
2010;hal.172)
c) Eklamsia
Eklamsia adalah kelainan akut pada wanita hamil,
dalam persalinan, atau masa nifas yang ditandai dengan
timbulnya kejang dan koma dimana sebelumnya sudah
menunjukan gejala-gejala pre eklampsia (Rukiyah,
2010;hal.186).
d) Perdarahan antepartum
(1) Solusio antepartum
Solusio antepartum adalah terlepasnya plasenta yang
letaknya normal pada korpus uteri yang terlepas dari
perlekatanya sebelum janin lahir (Rukiyah, 2010;hal.199).
(2) Plasenta previa
Plasenta prefia dalah plasenta ada didepan jalan lahir.
(3) Insertio Velamentosa
Insertion velamentosa adalah tali pusat yang tidak
sehingga pembuluh darah umbilikus berjalan diantara
amnion dan karion menuju plasenta (Rukiyah,
2010;hal.211).
(4) Ruptura sinus marginalis
Saolusio plasenta ringan disebut juga ruptura sinus
marginalis, dimana tempat pelepasan sebagian kecil
plasenta yang tidak berdarah banyak (Rukiyah,
2010;hal.212).
e. Perubahan Fisiologis Pada Kehamilan
Dengan terjadinya kehamilan maka seluruh system genetalia wanita
mengalami perubahanyang mendasar sehingga dapat menunjang
perkembangan dan pertumbuhan janin dan rahim. Plasenta dalam
perkembanganya mengeluarkan hormon somatomamotropin, estrogen,
dan progesterone yang menyebabkan perubahan pada bagian-bagian
tubuh dibawah ini :
1) Uterus
Rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau
beratnya 30 gram akan mengalami hipertrofi dan hyperplasia,
sehingga menjadi seberat 1000 gram saat akhir kehamilan. Otot
rahim mengalami hyperplasia dan hipertrofi menjadi lebih besar,
lunak, dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena pertumbuhan
Perubahan isthmus uteri (rahim) menyebabkan isthmus menjadi
lebih panjang dan lunak sehingga pada pemeriksaan dalam
seola-olah kedua jari dapat saling sentuh. Perlunakan isthmus disebut
tanda hegar. Hubungan antara besarnya rahim dan usia kehamilan
penting untuk diketahui karena kemungkinan penyimpangan
kehamilan seperti hamil kembar, hamil molahidatidosa, hamil
dengan hidramnionyang akan teraba lebih besar. Sebagai gambaran
dapat ditemukan sebagai berikut:
a) Pada usia kehamilan 16 minggu, kavum uteri seluruhnya diisi
oleh amnion, dimana desidua kapsularis dan desidua perientalis
telah menjadi satu. Tinggi rahim adalah setengah dari jarak
simfisis dan pusat. Plasenta telah terbentuk seluruhnya.
b) Pada usia kehamilan 10 minggu, fundus rahim terletak dua jari
dibawah pusat sedangkan pada usia 24 minggu tepat ditepi atas
pusat.
c) Pada usia kehamilan 28 minggu, tinggi fundus uteri sekitar 3
jari diatas pusat atau sepetiga jarak antara pusat dan peosesus
xifoideus.
d) Pada usia kehamilan 32 minggu, tinggi fundus uteri adalah
setengah jarak prosesus xifoideus dan pusat (Manuaba,
e) Pada usia kehamilan 36 minggu tinggi fundus uteri sekitar satu
jari dibawah prosesus xifoideus, dan kepala bayi belum masuk
pintu atas panggul (Manuaba, 2010;hal.87).
f) Pada usia kehamilan 40 minggu fundus uteri turun setinggi tiga
jari dibawah prosesus xifoideus, oleh karena saat ini kepala
janin telah masuk pintu panggul (Manuaba, 2010;hal. 88).
2) Vagina
Selama kehamilan, terjadi peningkatan vaskularitas dan
hyperemia dikulit dan otot perineum dan vulva, disertai perlunakan
jaringan ikat di bawahnya. Meningkatnya vaskularitas sangat
memenuhi vagina dan menyebabkan warna menjadi keunguan
(tanda Chadwick) (Williams, 2013;hal. 116).
3) Kulit
Pada kulit perut akan terjadi perubahan warna menjadi
kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga mengenai daerah
payudara dan paha dikenal dengan nama striae gravidarum. Kulit
digaris pertengahan perutnya (linea alba) akan berubah menjadi
hitam kecoklatan yang disebut dengan linea nigra. Kadang-kadang
akan muncul dalam ukuran bervariasi pada wajah dan leher yang
disebut Cloasma gravidarum. Selain itu, pada areola dan daerah
genetalia juga terlihat pigmentasi berlebihan (Prawirohardjo,
4) Ovarium
Pada ovarium ovulasi terhenti, masih terdapat korpus luteum
graviditas sampai terbentuknya uri yang mengambil alih
pengeluaran estrogen dan progesterone (Rustam Mochtar,
2012;hal. 30).
5) Payudara
Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai
persiapan memberi ASI pada saat laktasi. Perkembangan payudara
tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hormone saat kehamilan,
yaitu estrogen, progesterone, da somatomamotrofin (Manuaba,
2010;hal. 92).
6) Perubahan Metabolik
Sebagian besar penambahan berat badan selama kehamilan
berasal dari uterus dan isinya. Kemudian payudara, volume darah,
dan cairan ekstraseluler. Diperkirakan selama kehamilan berat
badan akan bertambah 12,5 kg. Peningkatan jumlah cairan selama
kehamilan dalah suatu hal yang fisiologis. Hal ini disebabkan oleh
turunya osmolaritas dari 10 mOsm/kg yang diinduksi oleh makin
rendahnya ambang rasa haus dan sekresi vasopressin. Pada saat
aterm ±3,5 l cairan berasal dari janin, plasenta, dan cairan amnion,
sedangkan 3 l lainnya berasal dari akumulasi peningkatan volume
cairan selama kehamilan adalah 6,5 l (Prawirohardjo, 2014;hal.
180).
7) Sistem Kardiovaskuler
Sejak pertengahan kehamilan pembesaran uterus akan menekan
vena kava inferior dan aorta bawah ketika berada dalam posisi
terlentang. Penekanan vena kava inferior ini akan mengurangi
darah balik ke vena jantung. Akibatnya, terjadinya penurunan
preload dan cardiac output sehingga akan menyebabkan terjadinya
hipotensi arterial yang dikenal dengan sindrom hipotensi supine
dan pada keadaan yang cukup berantakan mengakibatkan ibu
kehilangan kesadaran. Penekanan pada aorta ini juga akan
mengurangi aliran darah uteroplasenta ke ginjal. Selama trimester
terakhir posisi terlentang akan membuat fungsi ginjal menurun jika
dibandingkn posisi miring (Prawirohardjo, 2014;h. 183).
f. Perubahan Psikologis Dalam Masa Kehamilan
1) Pada trimester 1
Trimester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuian
terhadap kenyataan bahwa ia sedang mengandung.pada trimester
ini, wanita merasa sedih, mengalami kekecewaan, penolakan,
2) Pada trimester II
Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan baik,
yakni ketika ibu merasa sehat, ibu sudah menerima kehamilanya,
merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran, dan
persiapan untuk peran baru (Varney, 2007;hal.502).
3) Pada trimester III
Sering disebut periode penantian dengan penuh kewaspadaan.
Wanita akan merasakan kembali ketidaknyamanan fisik yang
semakin kuat menjelang akhir kehamilan. Ibu akan merasa
canggung, jelek, berantakan, memerlukan dukungan yang sangat
besar dan konsisten dari pasangan masing-masing (Varney,
2007;hal.504).
g. Standar kunjungan Ante-natal Care (ANC)
1) Kunjungan Ante-natal Care (ANC) minimal :
a) Satu kali pada trimester I (usia kehamilan 0 – 13 minggu).
Informasi yang diberikan ketika memberikan asuhan kebidanan
yaitu:
(1) Menjalin hubungan saling percaya
(2) Deteksi masalah
(3) Mencegah masalah (TT dan anemia)
(4) Persiapan persalinan dan komplikasi
b) Satu kali pada trimester II (usia kehamilan 14 – 27 minggu).
Pada trimester II, bidan memberikan informasi yang
berkaitan dengan pre-eklamsi ringan. Bidan mengajak pasien
dan keluarga untuk aktif dalam memantau kemungkinan
gejala-gejala pre-eklamsi ringan dalam kehamilanya sehingga timbul
tanggung jawab bagi pasien dan keluarga untuk
mempertahankan kesehatanya secara mandiri.
c) Dua kali pada trimester III (usia kehamilan 28 – 40 minggu)
Informasi yang perlu disampaikan adalah:
(1) Gemeli (28-36 minggu)
(2) Letak janin (>36 minggu)
(Sulistyawati,2009; h.4-7).
2) Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan. Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan harus
memenuhi elemen pelayanan (10T) meliputi:
a) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
b) Pengukuran tekanan darah
c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)
d) Pengukuran tinggi puncak rahin (fundus uteri)
e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi
f) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama
kehamilan.
g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
h) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi
interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana)
i) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes
hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan
pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan
sebelumnya)
j) Tatalaksana kasus (Profil kesehatan Indonesia,
2016;hal.103-104).
h. Standar Asuhan Kehamilan
1) Standar 3: Identifikasi Ibu Hamil
Melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat
secara berkala untuk penyuluhan dan motivasi untuk pemeriksaan
dini dan teratur (Kusmiyati, 2009;hal.4).
2) Stanndar 4: Pemeriksaan dan pemantauan antenatal
Sedikitnya 4 kali pelayanan kehamilan. Pemeriksaan meliputi:
anamnesis dan pemantauan ibu dan janin, mengenal kehamilan
resiko tinggi, imunisasi, nasehat dan penyuluhan, mencata data
yang tepat, tindakan tepat untuk dirujuk
4) Standar 6: pengelolaan anemia pada kehamilan
5) Standar 7: pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan
6) Standar 8: persiapan persalinan (Kusmiyati, 2009;hal.4).
i. Tujuan Asuhan Kehamilan
1) Memantau kemajuan kehamilan, memastikan kesejateraan ibu dan
tumbuh kembang janin.
2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, serta
sosial ibu dan bayi.
3) Menemukan secara dini adanya masalah/gangguan dan
kemungkinan komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan.
4) Mempersiapkan kehamilan dan persalinan dengan selamat, baik
ibu maupun bayi, dengan trauma seminimal mungkin.
5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas dan pemberian ASI ekslusif
berjalan normal.
6) Mempersiapkan ibu dan keluarga dapat berperan dengan baik
dalam memelihara bayi agar dapat tumbuh dan berkembang secara
normal (Sulistyawati,2009; h.4).
j. Tanda bahaya dalam kehamilan
1) Perdarahan.
2) Nyeri hebat di daerah abdominopelvikum.
3) Sakit kepala yang hebat.
5) Bengkak pada muka dan tangan.
6) Bayi kurang bergerak seperti biasa
(Asrinah ,2010;hal.114-115).
k. Tata Cara Rujukan
1) Pasal 7
a) Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal
b) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda
tingkatan.
c) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu
tingkatan
d) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke
tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya
(Permenkes RI, 2012).
2) Pasal 8
Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan
fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara
3) Pasal 9
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke
tingkatan pelayanan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan apabila:
a) Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub
spesialistik
b) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas,
peralatan dan/atau ketenagaan (Permenkes RI, 2012).
4) Pasal 10
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke
tingkatan pelayanan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan apabila: a. permasalahan
kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan
kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan
kewenangannya; b. kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat
pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani
oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk
alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang;
sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana,
prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan (Permenkes RI, 2012).
5) Pasal 11
a) Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk
pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan
memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat
persetujuan pasien atau keluarganya.
b) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber
daya, atau geografis.
6) Pasal 12
a) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau
keluarganya.
b) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan
dari tenaga kesehatan yang berwenang.
c) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya meliputi: a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan
medis yang diperlukan; b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan; d.
transportasi rujukan; dan e. risiko atau penyulit yang dapat
7) Pasal 13
Perujuk sebelum melakukan rujukan harus: a. melakukan
pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien
sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan
keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan; b. melakukan
komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa
penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien
gawat darurat; dan c. membuat surat pengantar rujukan untuk
disampaikan kepada penerima rujukan.
8) Pasal 14
Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b, penerima rujukan berkewajiban: a. menginformasikan
mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan
ketersediaan tenaga kesehatan; dan b. memberikan pertimbangan
medis atas kondisi pasien (Permenkes RI, 2012).
9) Pasal 15
Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf c sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pasien; b. hasil
pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang) yang telah dilakukan; c. diagnosis kerja; d. terapi
10)Pasal 16
a) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi
pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
b) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus
dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga
kesehatan yang kompeten.
c) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan
kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain
yang layak.
11)Pasal 17
a) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima
oleh penerima rujukan.
b) Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan
pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
c) Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk
mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai
memberikan pelayanan (Permenkes RI, 2012).
l. Kekurangan Energi Kronis
1) Pengertian
KEK merupakan salah satu keadaan malnutrisi, malnutrisi
secara relative atau absolut satu atau lebih zat gizi (Supriasa,
2002:h 82).
KEK adalah keadaan dimana seseorang mengalami
kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau
menahun. Dengan ditandai berat badan kurang dari 40 kg atau
tampak kurus dan dengan LILA-nya kurang dari 23,5 cm
(Depkes, 1999:h 5).
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi
Dari penelitian Surasih (2005), faktor-faktor yang
mempengaruhi KEK antara lain: jumlah asupan energy, umur,
beban kerja ibu hamil, penyakit, pengetahuan ibu tentang gizi
dan pendapatan keluarga. Adapun penjelasanya:
a) Jumlah asupan makanan
Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak dari
pada kebutuhan wanita yang tidak hamil. Upaya
mencapai gizi masyarakat yang baik atau optimal
dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup.
Penyediaan pangan dalam negeri yaitu: upaya pertanian
dalam menghasilkan bahan makanan pokok, lauk pauk,
sayuran dan buah-buahan. Pengukuran konsumsi
makanan sangat penting untuk mengetahui kenyataan
untuk mengukur gizi dan menemukan faktor diet yang
menyebabkan malnutrisi.
b) Umur
Semakin muda dan semakin tua umur seseorang ibu
yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap
kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur yang muda perlu
tambahan gizi yang banyak karena selain digunakan
pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri, juga
harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung.
Sedangkan untuk umur tua perlu energy yang besar juga
karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan
untuk bekerja maksimal, maka memerlukan tambahan
energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang
sedang berlangsung. Sehingga usia yang paling baik
adalah lebih dari 20 tahun dan kurang dari 35 tahun,
dengan diharapkan gizi ibu hamil akan lebih baik.
c) Beban kerja
Aktifitas dan gerakan seseorang berbeda-beda, seorang
dengan gerak yang otomatis memerlukan energi yang
lebih besar dari pada mereka yang hanya duduk diam
saja. Setiap aktifitas memerlukan energi, maka apabila
dibutuhkan juga semakin banyak. Namun pada seorang
ibu hamil kebutuhan zat gizi berbeda karena zat gizi
yang dikonsumsi selain untuk aktifitas, zat gizi juga
digunakan untuk perkembangan janin yang ada
dikandungan ibu hamil tersebut. Kebutuhan energi
rata-rata pada saat hamil dapat ditentukan sebesar 203 sampai
263 kkal/hari, yang mengasumsikan pertambahan berat
badan 10-12 kg tidak ada perubahan tingkat kegiatan.
d) Penyakit
Malnutrisi dapat mempermudah tubuh terkena penyakit
infeksi dan juga infeksi akan mempermudah status gizi
dan mempercepat malnutrisi.
e) Pengetahuan ibu tentang gizi
Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipegaruhi oleh
pengetahuan, sikap terhadap makanan dan
praktik/perilaku pengetahuan tentang nutrisi melandasi
pemilihan makanan. Pendidikan formal dari ibu rumah
tangga sering kali mempunyai asosiasi yang positif
dengan pengembangan pola-pola konsumsi makanan
dalam keluarga. Beberapa studi menunjukan bahwa jika
tingkat pendidikan dari ibu meningkat maka
Usaha-usaha untuk memilih makanan yang bernilai
nutrisi semakin meningkat, ibu-ibu rumah tangga yang
mempunyai pengetahuan nutrisi akan memilih makanan
yang lebih bergizi dari pada yang kurang bergizi.
f) Pendapatan keluarga
Pendapatan keluarga merupakan faktor yang
menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Pada
rumah tangga berpendapatan rendah, sebanyak 60%
hingga 80% dari pendapatan riilnya dibelanjakan untuk
membeli makanan. Artinya pendapatan tersebut
70%-80% energy dipengaruhi oleh sumber energy lainya
seperti lemak dan protein. Pendapatan yang meningkat
akan menyebabkan semakin besarnya total pengeluaran
termasuk besarnya pengeluaran untuk pangan.
3) Patogenesis
Proses terjadinya KEK merupakan akibat dari faktor lingkungan
dan faktor manusia yang didukung oleh kekurangan asupan
zat-zat gizi, maka simpanan zat-zat gizi pada tubuh memenuhi
kebutuhan. Apabila keadaan ini berlangsung lama maka
simpanan zat gizi akan habis dan akhirnya terjadi kemerosotan
4) Tanda dan Gejala
Tanda dan gejala adalah berat badan kurang dari 40 kg atau
tampak kurus dan LILA kurang dari 23,5 cm (Supriasa, 2002:h
48).
a) Pengertian Ukuran Lingkar Lengan Atas
Kategori KEK adalah apabila LILA kurang dari 23,5 cm
atau di bagian merah pita LILA (Supriasa, 2002:H 49).
Menurut Depkes RI (1994) didalam buku Supriasa
(2002,h 48) pengukuran LILA pada kelompok wanita
usia subur (WUS) adalah salah satu deteksi dini yang
mudah dan dapat dilaksanakan masyarakat awam, untuk
mengetahui kelompok beresiko KEK. Wanita usia subur
adalah wanita usia 15-45 tahun. LILA adalah salah satu
cara untuk mengetahui resiko KEK.
b) Tujuan
Tujuan pengukuran LILA adalah mencakup masalah
WUS baik pada ibu hamil maupun calon ibu, masyarakat
umum dan peran petugas lintas sektoral.
c) Ambang batas
Ambang batas LILA pada WUS dengan resiko KEK di
Indonesia adalah 23,5 cm, apabila ukuran LILA kurang
wanita tersebut merupakan resiko KEK, dan
diperkirakan akan melahirkan berat badan bayi rendah
(BBLR). BBLR mempunyai resiko kematian, kurang
gizi, gangguan pertumbuhan dan gangguan
perkembangan anak (Supriasa, 2002:h 49).
d) Cara mengukur LILA
Pengukuran LILA dilakukan melalui urut-urutan yang
telah ditetapkan. Ada 7 urutan pengukuran LILA
(Supriasa, 2002:h 49) yaitu:
(1) Tetapkan posisi duduk
(2) Siku kiri ditekuk
(3) Letakan pita anatara bahu dan siku
(4) Tentukan titik tengah lengan
(5) Lingkarkan pita LILA pada tengah lengan
(6) Pita jangan telalu dekat
(7) Pita jangan terlalu longgar
e) Cara pembacaan skala yang benar
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran
LILA adalah pengukuran dilakukan dibagian tengah
antara bahu dan siku lengan kiri (kecuali orang kidal).
dalam keadaan tidak tegang atau kencang dan alat ukur
dalam keadaan baik.
5) Pengaruh KEK
Kurang energy kronik pada saat kehamilan dapat berakibat pada
ibu maupun pada janin yang dikandungnya (Waryono, 210:h
46).
a) Terhadap ibu
Dapat menyebabkan resiko dan komplikasi antara lain:
anemia, perdarahan, berat badan tidak bertambah secara
normal, dan terkena penyakit infeksi.
b) Tehadap persalinan
Dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan
sebelum waktunya (premature), perdarahan.
c) Terhadap janin
Dapat menimbulkan keguguran/abortus, bayi lahir mati,
kematian neonatal, cacat bawaan, aemia pada bayi, bayi
2. Persalinan
a. Definisi
Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin
dan uri) yang dapat hidup kedunia luar, dari rahim melalui jalan lahir
atau dengan jalan lain (Rustam Mochtar, 2012;hal.69).
Proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah
cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau
melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan
sendiri) (Manuaba, 2010;hal.164).
Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan
pengeluaran hasil konsepsi ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi
persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif pada servik,
da diakhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 2008;hal.672).
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa
persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi dimulai dari kala
1 pembukaan, hingga kala 3 yaitu kala pengeluaran plasenta.
b. Teori penyebab timbulnya persalinan
Teori yang dikemukakan diantaranya faktor hormonal, stuktur
rahim, sirkulasi rahim, pengaruh tekanan pada saraf dan nutrisi yaitu :
1) Teori penurunan hormone
Pada waktu 1-2 minggu sebelum partus, mulai terjadi
2) Teori plasenta menjadi tua
Penuaan plasenta akan menyebabkan turunya kadar estrogen
dan progesterone sehingga terjadi kekejangan pembuluh darah.
Hal tersebut akan menimbulkan kontraksi rahim (Rustam
Mochtar, 2012;hal.70).
3) Teori distensi rahim
Harim yang menjadi besar dan meregang menyebabkan iskemia
otot-otot rahim sehingga mengganggu sirkulasi uteroplasenta.
4) Teori iritasi mekanik
Dibelakang servik, terdapat ganglion servikale. Apabila
ganglion tersebut digeser dan ditekan, oleh kepala bayi maka akan
timbul kontraksi uterus.
5) Induksi partus.
Partus dapat ditimbulkan dengan :
a) Gagang luminaria, beberapa luminaria dimasukan dalam
kanalis servisis dengan tujuan merangsang pleksus
frsnkenhauser
b) Aminiotomi (pemecahan ketuban)
c) Tetesan oksitosin (pemberian oksitosin melalui tetesan perinfus
c. Mekanisme persalinan
Mekanisme persalinan merupakan gerakan posisi yang dilakukan
janin untuk menyesuaikan diri terhadap pelvis ibu. Gerakan ini
diperlukan karena diameter terbesar janin harus sejajar dengan
diameter terbesar pelvis ibu agar janincukup bulan dapat melewati
pelvis dan kemudian bayi dapat dilahirkan (Varney, 2008;hal. 753).
Mekanisme persalinan meliputi :
1) Engagement
Meknisme ketika diameter biparietal diameter transversal
terbesar pada presentasi oksiput melewati apertura pelvissuperior
disebut angagement. Kepala janin dapat mengalami engage selama
beberapa minggu terakhir kehamilan atau tidak mengalami engage
hingga setelah permulaaan persalinan (Williams, 2013;hal.396).
2) Asinklitismus
Defleksi lateral kearah posisi anterior atau posterior pelvis
disebut asinklitisme. Asinklitismus derajat sedang merupakan
persaratan persalinan normal (Williams, 2013;hal.397).
3) Desensus
Pada nulipara, angagement dapat berlangsung sebelum awitan
persalinan, dan proses desensus selanjutnya dapat tidak terjadi
hingga awitan kala dua. Pada perempuanmultipara, desensus
Desensus ditimbulkan oleh satu atau beberapa dari empat
kekuatan, yaitu :
a) Tekanan cairan amnion
b) Tekanan langsung fundus pada bokong saat kontraksi
c) Tekanan ke bawah otot-otot abdomen maternal
d) Ekstensi dan pelurusan tubuh janin (Williams, 2013;hal.398).
4) Fleksi
Pada gerakan ini, dagu mengalami kontak lebih dekat dengan
dada janin dan diameter sub oksipito bregmatikum yang lebih
pendek menggantikan diameter oksipitofrontalis yang lebih
panjang (Williams, 2013;hal.398).
5) Rotasi internal
Gerakan putaran kepala sedemikian rupa sehingga oksiput
secara bertahap bergerak kearah simfisis pubis dibagian anterior
dari posisi awal atau yang lebih jarang, kearah posterior menuju
lengkung sacrum. Rotasi internal penting untuk penuntasan
persalinan, kecuali bila ukuran janin abnormal kecil (Williams,
2013;hal.398).
6) Ekstensi
Dengan distensi progresif perineum dan pembukaan vagina,
urutan oksiput, bregma, dahi, hidung, mulut, da akhirnya dagu
melewati tepi anterior perineum (Williams, 2013;hal.398).
7) Rotasi eksternal
Resusitasi kepala ke posisi oblik diikuti dengan penyelesaian
rotasi eksternal ke posisi transversal. Gerakan ini sesuai rotasi
tubuh janin dan membuat diameter bisakrominal berkorelasi
dengan diameter anteroposterior aperture pelvis inferior. Sehingga,
salah satu bahu terletak anterior belakang simfisis pubis,
sedangkan bahu lainya terletak di posterior. Gerakan ini tampaknya
ditimbulkan oleh faktor pelvis yang sama dengan terjadinya rotasi
internal kepala (Williams, 2013;hal.398).
8) Ekspulsi
Hampir segera setelah rotasi eksternal, bahu anterior terlihat
dibawah simfisis pubis, dan perineum segera terdistensi oleh bahu
posterior. Setelah pelahiran bahu, bagian tubuh lainya lahir dengan
cepat (Williams, 2013;hal.398).
d. Tanda dan gejala menjelang persalinan
1) Perasaan distensi abdomen berkurang (Lightening)
2) Perubahan serviks
3) Persalinan palsu
4) Ketuban pecah dini
6) Lonjakan energy
7) Gangguan saluran cerna (Varney, 2008;hal.672).
e. Ada 3 Jenis Persalinan yaitu :
1) Persalinan spontan. Jika persalinan seluruhnya berlangsung dengan
kekuata ibu sendiri.
2) Persalinan buatan. Jika proses persalinan dengan bantuan tenaga
dari luar.
3) Persalinan anjuran (partus presipitatus) (Manuaba, 2010;hal.164).
f. Tahapan persalinan
Tahapan dari persalinan terdiri atas kala 1(kala pembukaan), kala II
(kala pengeluaran), kala III (pelepasan plasenta), dan kala IV (kala
pengawasan atau observasi atau kala pemulihan).
1) Kala 1
Kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol
sampai pembukaan lengkap. Pada pembukaan his, kala pembukaan
berlangsung tidak begitu kuat sehingga parturient masih dapat
berjalan-jalan. Lamanya kala 1 untuk primigravida berlangsung 12
jam sedangkan multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurva
friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida 1 cm/jam dan
pembukaan multigravida 2 cm/jam (Manuaba, 2010;hal.173).
Menurut Sulistyawati dan Nugraheny (2010;hal.75) asuhan-
asuhan kebidanan kala I yaitu:
a) Pemantauan terus-menerus kemajuan persalinan menggunakan
patograf
b) Pemantauan terus-menerus terhadap tanda vital
c) Pemantauan terus menerus terhadap keadaan bayi
d) Pemberian hidrasi bagi pasien
e) Menganjurkan dan membantu pasien dalam upaya perubahan
posisi dan ambulasi
f) Mengupayakan tindakan yang membuat pasien nyaman
g) Memfasilitasi dukungan keluarga
2) Kala II
Ketika dilatasi serviks lengkap dan berakhir dengan pelahiran
janin. Durasi median sekitar 50 menit untuk nulipara dan sekitar 20
menit untuk multipara, tetapi sangat bervariasi. Pada perempuan
paritas tinggi dengan riwayat dilatasi vagina dan perineum
sebelumnya, dua atau tiga usaha ekspulsif setelah dilatasi serviks
lengkap mungkin cukup untuk menyelesaikan proses pelahiran.
Sebaliknya, pada perempuan dengan kontraktur pelvis, janin besar,
gangguan usaha ekspulsif akibat analgesia regional atau sedasi,
kala dua dapat memanjang secara abnormal (Williams,
Menurut Sulistyawati dan Nugraheny (2010;hal.115-118)
asuhan-asuhan kebidanan kala II yaitu:
a) Pemantauan ibu
(1) Kontraksi
His atau kontraksi harus selalu dipantau selama kala 2
persalinan karena selain dorongan meneran pasien,
kontraksi uterus merupakan kunci dari proses persalinan.
(2) Tanda-tanda kala II (merasa ingin meneran, perineum
menonjol, merasa seperti ingin buang air besar, lubang
vagina dan sfingter ani membuka, jumlah air ketuban
meningkat)
(3) Tanda vital
Tekanan darah diperiksa setiap setiap 15 menit dengan
waktu pemeriksaan diantara dua kontraksi. Suhu, nadi, dan
pernafasan diperiksa setiap dua jam
(4) Kandung kemih
(5) Hidrasi
Kondisi kekurangan cairan akibat berkeringat semakin
meningkat, sehingga pasien perlu mendapatkan suplai
energy berupa minuman yang manis (Sulistyawati,
2010;hal.116).
(7) Integritas perineum
Mengidetifikasi elastisitas perineum beserta kondisi pasien
serta taksiran berat janin untuk membuat keputusan
dilakukanya episiotomi.
(8) Kebutuhan dan jenis episiotomi
(Sulistyawati, 2010;hal.117).
b) Pemantauan bayi
(1) Saat bayi belum lahir
(a) Frekuensi denyut jantung janin
(b) Bagian terendah janin
(c) Penurunan bagian terendah janin
(2) Saat bayi sudah lahir
(a) Penilaian sekilas sesaat setelah bayi lahir
(b) Menit pertama kelahiran (Sulistyawati, 2010;hal.118).
3) Kala III adalah kala pengeluaran uri.
Bayi lahir, kontraksi rahim beristirahat sebentar. Uterus teraba
keras dengan fundus uteri setinggi pusat, dan berisi plasenta yang
menjadi dua kali lebih tebal dari sebelumnya. Dalam waktu 5-10
menit, seluruh plasenta terlepas, terdorong kedalam vagina dan
akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan kedalam vagina,
dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas
setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai dengan
pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc (Rustam Mochtar,
2012;hal.73).
Menurut Sulistyawati dan Nugraheny (2010;hal.165)
asuhan-asuhan kebidanan kala III yaitu:
a) Dukungan mental dari bidan dan keluarga atau pendamping
b) Penghargaan terhadap proses kelahiran janin yang telah dilalui
c) Informasi yang jelas mengenai keadaan pasien sekarang dan
tindakan apa yang akan dilakukan
d) Penjelasan mengenai apa yang harus ia lakukan untuk
membantu mempercepat kelahiran plasenta, yaitu kapan saat
meneran dan posisi apa yang mendukung untuk pelepasan dan
kelahiran plasenta
e) Bebas dari kasa risih akibat bagian bawah yang basah oleh
darah dan ketuban
f) Hidrasi (Sulistyawati, 2010;hal.165).
4) Kala IV (observasi)
Bertujuan untuk melakukan observasi karena perdarahan
postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi
yang dilakukan meliputi tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan
tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi dan pernafasan,
masih normal bila jumlahnya tidak melibihi 400-500 cc (Manuaba,
2010;hal.174).
Asuhan-asuhan kebidanan kala IV yaitu:
a) Pemeriksaan fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan
setiap 30 menit jam ke 2, jika kontraksi uterus tidak kuat,
masase uterus sampai menjadi keras
b) Periksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, dan perdarahan
setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam ke 2
c) Anjurkan ibu untuk minum untuk mencegah dehidrasi
d) Bersihkan perineum dan kenakan pakaian yang bersi dan
kering
e) Biarkan ibu untuk beristirahat karena telah bekerja keras
melahirkan bayinya, bantu ibu posisi yang nyaman
f) Biarkan bayi didekat ibu untuk meningkatkan hubungan ibu
dan bayi
g) Bayi sangat bersiap segera setelah melahirkan. Hal ini sangat
tepat untuk memberikan ASI
h) Pastikan ibu sudah buang air kecil tiga jam pascapersalinan
i) Anjurkan ibu dan keluarga mengenai bagaimana memeriksa
fundus dan menimbulkan kontraksi serta tanda-tanda bahaya
g. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persalinan
1) Passanger (janin dan plasenta)
2) Passage (jalan lahir)
3) Power (tenaga ibu/his/kontraksi)
4) Penolong
5) Psikologi
(Rustam Mochtar, 2012;hal.58).
h. Perubahan Fisiologis pada persalinan
Sejumlah perubahan fisiologis yang normal akan terjadi selama
persalinan, hal ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan
yang dapat dipastikan secara klinis sehingga dapat menginterpretasi
dengan akurat tanda, gejala, dan temuan fisik serta laboratorium
tertentu, dan normal tidaknya temuan tersebut selama kala satu
persalinan (Varney, 2008;hal.686).
1) Tekanan darah
Tekanan darah meningkat selama kontraksi disertai
peningkatan sistolik rata 15 (10-20) mmHg dan diastolic
rata-rata 5-10 mmHg. Pada waktu diantara kontraksi, tekanan darah
kembai ketingkat sebelum persalinan. Dengan mengubah posisi
tubuh dari terlentang ke posisi miring, perubahan tekanan darah
kekhawatiran dapat semakin meningkatkan tekanan darah (Varney,
2008;hal.686).
2) Perubahan Metabolisme
Selama persalinan, metabolisme karbohidrat baik aerob maupun
anaerob meningkat dengan kecepatan tetap. Peningkatan ini
terutama disebabkan oleh ansietas dan aktivitas otot rangka.
Peningkatan aktivitas metabolic terlihat dari peningkatan suhu
tubuh, denyut nadi, pernafasan, curah jantung, cairan yang hilang
(Varney, 2008;hal.686).
3) Perubahan suhu
Suhu sedikit meningkat selama persalinan, tertinggi selama dan
segera setelah melahirkan. Dianggap normal bila peningkatan suhu
yang tidak lebih dari 0,5 sampai 1°C, yang mencerminkan
peningkatan metabolisme selama persalinan (Varney,
2008;hal.687).
4) Perubahan denyut nadi (frekuensi jantung)
Perubahan yang mencolok selama kontraksi disertai
peningkatan selama fase peningkatan, penurunan selama titik
puncak sampai frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi
diantara kontraksi, dan peningkatan selama fase penurunan hingga
mencapai frekuensi lazim diantara kontraksi (Varney,
5) Pernafasan
Sedikit peningkatan frekuensi pernafasan masih normal selama
persalinan dan mencerminkan peningkatan metabolisme yang
terjadi. Hiperventilasi yang memanjang adalah temuan abnormal
dan dapat menyebabkan alkalosis (Varney, 2008;hal.687).
6) Perubahan pada ginjal
Poiuria sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat
diakibatkan peningkatan lebih lanjut curah jantung selama
persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus
dan aliran plasma ginjal. Poliuria menjadi kurang jelas pada posisi
terlentang karena posisi ini membuat aliran urin berkurang selama
kehamilan (Varney, 2008;hal.687).
7) Perubahan pada saluran cerna
Mortilitas dan absorpsi lambung terhadap makanan padat jauh
berkurang. Apabila kondisi ini diperburuk oleh penurunan lebih
lanjut sekresi asam lambung selama persalinan, maka saluran cerna
bekerja dengan lambat sehingga waktu pengosongan lambung
menjadi lebih lama. Cairan tidak dipengaruhi dan waktu yang
dibutuhkan untuk pencernaan dilambung tetap seperti biasa.
Makanan yang diingesti selama periode menjelang persalinan atau
berada didalam lambung selama persalinan (Varney,
2008;hal.687).
8) Perubahan hematologi
Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 gm/100 Ml salama
persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari
pertama pascapartum jika tidak ada kehilangan darah yang
abnormal (Varney, 2008;hal.688).
i. Aspek Dasar persalianan
Ada lima aspek dasar, atau lima benang merah yang penting dan
saling berkaitan dalam asuhan persalinan yang bersih dan aman.
Berbagai aspek tersebut melekat pada setiap persalinan, baik normal,
maupun patologis yaitu :
1) Membuat keputusan klinik
2) Asuhan sayang ibu dan sayang bayi
3) Pencegahan infeksi
4) Pencatatan (rekam medik) asuhan persalinan
5) Rujukan (APN, 2014;hal.7).
j. Asuhan Persalinan normal 60 langkah persalinan menurut
Prawirohardjo (2014) yaitu :
1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II
b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum
dan/vaginanya.
c) Perenium menonjol.
d) Vulva vagina dan sfingter anal membuka
2) Memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial siap di
gunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan
tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set.
3) Mengenakan baju penutup atau clemek plastik yang bersih.
4) Melepaskan semua perhiasan yang di pakai di bawah siku, mencuci
kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan
mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai / pribadi yang
bersih.
5) Memakai sarung tangan DTT atau steril untuk semua pemeriksaan
dalam.
6) Menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan
memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi/steril) dan
meletakkan kembali ke partus set wadah disinfeksi tingkat tinggi
atau steril tanpa mengontaminasi tabung suntik.
7) Membersihkan vulva dan perenium, menekannya dengan hati-hati
dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kassa
yang sudah di basahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut
membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari
depan ke belakang. Membuang kapas atau kassa yang
terkontaminasi dalam wadah yang benar. Mengganti sarung tangan
jika terkontaminasi (meletakan kedua sarung tangan tersebut
dengan benar di dalam larutan dekontaminasi)
8) Dengan menggunakan teknik aseptic, melakukan pemeriksaan
dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah
lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan
sudah lengkap, lakukan amniotomi
9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan
yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin
0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta
merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
Mencuci kedua tangan.
10)Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir
untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (100-180
kali/menit)
11)Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin
baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai
dengan keinginannya.
a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran.
janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan
mendokumentasikan temuan.
b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat
mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai
meneran
12)Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk
meneran. (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk
dan pastikan ia merasa nyaman)
13)Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang
kuat untuk meneran:
a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai
keinginan untuk meneran.
b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk
meneran
c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan
pilihannya (tidak meminta ibu berbaring terlentang).
d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi.
e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi
semangat pada ibu.
f) Menganjurkan asupan cairan peroral.
h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi
segera waktu 120 menit (2 jam) meneran untuk ibu primipara
atau 60 menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera. Jika
ibu tidak mempunyai keinginan unutuk meneran.
i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil
posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 60
menit, anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak
kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat di antara
kontraksi.
j) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi
segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera
14)Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm,
letakan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi.
15)Meletakan kain yang bersih di lipat 1/3 bagian, di bawah bokong
ibu.
16)Membuka partus set.
17)Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan
18)Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi
perenium dengan sarung tangan yang di lapisi kain tadi, letakkan
tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut
keluar lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran
perlahan-lahan atau bernafas cepat saat kepala lahir
19)Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan
kain atau kassa yang bersih.
20)Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai
jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses
kelahiran bayi:
a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan
lewat bagian atas kepala bayi.
b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di
dua tempat dan memotongnya
21)Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara
spontan Lahir bahu.
22)Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua
tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk
meneran saat berkontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya
kearah bawah dan kea rah luar hingga bahu anterior muncul di
bawah akus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah
atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior.
23)Setelah kedua bahu di lahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala
bayi yang berada di bagian bawah kea rah perenium, membiarkan
kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum, gunakan
lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat di
lahirkan.menggunakan tangan anterior (bagian atas) untuk
mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir.
24)Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di
atas (anterior) dari punggung kea rah kaki bayi untuk
menyangganya saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata
kaki bayi dengan hati-hati membantu kalahiran kaki
25)Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian meletakan
bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih
rendah dari tubuhnya (bilatali pusat terlalu pendek, meletakan bayi
di tempat yang memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksia,
lakukan resusitasi.
26)Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan
biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan oksitosin/i.m.
27)Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat
bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem kea rah ibu
dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (ke arah ibu)
28)Memegang tali pusat dengan sarung tangan, melindungi bayi dari
gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut.
29)Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan
menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi
mengalami kesulitan bernapas, ambil tindakan yang sesuai.
30)Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk
memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu
menghendakinya
31)Meletakan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi
abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua.
32)Membritahu kepada ibu bahwa ia akan di suntik
33)Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan
oksitosin 10 unit I.M. di gluteus 1/3 atas paha kanan ibu bagian
luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu.
34)Memindahkan klem pada tali pusat.
35)Meletakan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di
atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan
palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Memegang tali pusat
dan klem dengan tangan yang lain.
36)Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan
penegangan kea rah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan
tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan
cara menekan uterus kea rah atas dan belakang (dorso kranial)
dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversion
penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut
mulai.
Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota
keluarga untuk melakukan rangsangan putting susu.
37)Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil
menarik tali pusat kea rah bawah dan kemudian kea rah atas,
mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawan
arah pada uterus.
a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga
berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva.
b) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali
pusat selama 15 menit:
(1) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit I.M.
(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi kandung
kemih dengan menggunakan teknik aseptic jika perlu.
(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan.
(4) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit
berikutnya.
(5) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit
sejak kelahiran bayi.
38)Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran
hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan
melahirkan selaput ketuban tersebut.
Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan disinfeksi
tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu
dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau klem atau
forceps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan
bagian selaput yang tertinggal.
39)Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase
uterus, meletakan telapak tangan di fundus dan melakukan masase
dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus
berkontraksi (fundus menjadi keras)
40)Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun
janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa plasenta di
dalam kantung plastic atau tempat khusus.
41)Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan
segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif.
42)Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan
baik.
43)Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam
larutan klorin 0,5 %, membilas kedua tangan yang masih bersarung
tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan
44)Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril
atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati
kelilin tali pusat sekitar 1 cm dari pusat.
45)Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan
dengan simpul mati yang pertama.
46)Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan
klorin 0,5 %.
47)Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya.
Mmemastikan handuk atau kainnya bersih atau kering.
48)Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI.
49)Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan
pervaginam:
a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pacapersalinan.
b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pascapersalinan.
c) Setiap 20 – 30 menit pada jam kedua pascapersalinan.
d) Jika uterus tidak kontraksi dengan baik laksanakan perawatan
yang sesuai untuk menatalaksanaan tonia uteri.
e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan
penjahitan dengan anestesi local dan menggunakan teknik yang
sesuai.
50)Mengajarkan pada ibu/keluarga bahgaimana melakukan massase
51)Mengevaluasi kehilangan darah.
52)Memeriksa tekanan darah, nadi dan kandung kemih setiap 15 menit
selama satu jam perttama pascapersalinan dan setiap 30 menit jam
kedua setelah pascapersalinan.
a) Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam kedua jam
pertama pascapersalinan
b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak
normal.
53)Menempatkan semua pralatan di dalam larutan klorin 0,5 % untuk
dekontaminasi (10 menit ). Mencuci dan membilas peralatan
setelah dekontaminasi.
54)Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat
sampah yang sesuai.
55)Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tinggat
tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lender, dan darah.
Membantu ibu memakaikan pakaian yang bersih dan kering.
56)Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI.
Menganjurkan keluarga untuk memberikan minuman dan makanan
yang diinginkan.
57)Mendekontaminasi daerah yang digunakan utuk melahirkan