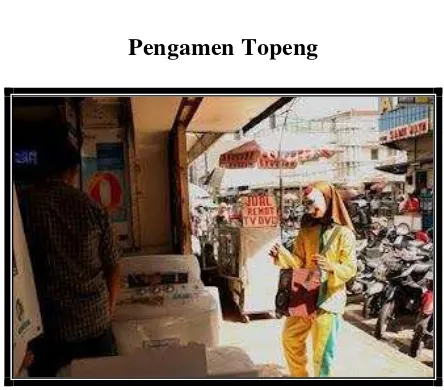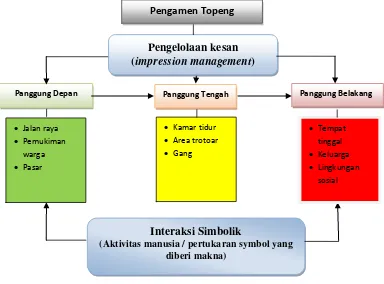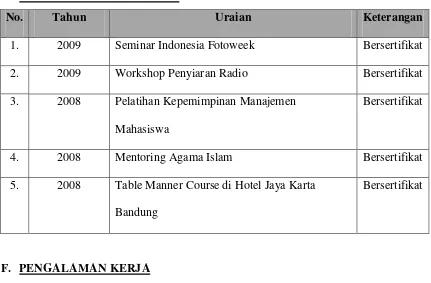SKRIPSI
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas
Oleh, AAN MULYADI
NIM.41808141
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG
iv
Kesan Pengamen Topeng Dalam Menjalani Kehidupannya Di Kota Bandung)
Oleh:
Nama :Aan Mulyadi NIM: 41808141
Penelitian ini di bawah Pembimbing :
Yadi Supriadi., S.Sos., M.Phil
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Kesan Pengamen Topeng Di Kota Bandung (Studi Dramaturgi Mengenai Pengelolaan Kesan Pengamen Topeng Dalam Menjalani Kehidupannya Di Kota Bandung). Untuk menjawab masalah diatas, maka diangkat sub fokus-sub fokus penelitian berikut ini: Panggung depan, Panggung tengah dan Panggung belakang. Sub fokus tersebut bertujuan untuk mengukur fokus penelitian, yaitu: Pengelolaan Kesan Pengamen Topeng Di Kota Bandung.
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan Metode studi dramaturgi, Subjek penelitiannya adalah pengamen topeng. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, untuk informan penelitian berjumlah 3 (tiga) orang pengamen topeng, dan untuk memperjelas serta memperkuat data adanya informan pendukung serta informan kunci. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, studi pustaka dan penelusuran data online. Adapun teknik analisis data dengan mereduksi data, mengumpulkan data, menyajikan data, menarik kesimpulan, dan evaluasi. Untuk uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan membercheck.
Hasil penelitian menunjukan bahwa panggung depan (front stage) pengamen topeng semuanya mencoba untuk memaikan perannya dengan baik, peran yang dihasilkan dari wujud peniruan individu terhadap aktifitas individu lain yang dipersepsikan sebagai tokoh penghibur. Pada panggung tengah (middle stage) pengamen topeng dan juga merupakan area yang dipakai dimana pengamen topeng melakukan brief mental yang kuat saat berada dipanggung depan. Pada panggung belakang (back stage), pengamen topeng benar-benar memainkan sebuah peran yang utuh, mereka tidak seperti pada saat berada di panggung depan (front stage) yang menutupi keadaan mereka.
Saran Penelitian: Bagi pengamen topeng untuk memberikan suguhan pertunjukan seni yang lebih dapat diterima oleh masyarakat sehingga pekerjaan sebagai pengamen topeng ini bisa memiliki nilai sebagai salah satu bentuk hiburan. Bagi masyarakat untuk tidak selalu memandang sebelah mata pada pengamen topeng, karena memiliki harapan agar ada yang bisa memberikan perhatian lebih terhadap mereka.
v
Studies Regarding singers dramaturgy Mask In Living His life in the city of Bandung)
by:
Name: Aan Mulyadi
NIM: 41808141
This research under the Supervisor:
Yadi Supriadi., S.Sos., M.Phil
This research was meant to find out How to Manage Impressions singers Mask In the city of Bandung (Dramaturgy Studies Regarding An impression management Dancer Mask In Living His life in Bandung). To answer the above problems, the appointed every element focus on the following this research is : the next stage, middle stage and back stage. Sub focus is to measure the focus of research, namely is: Impression Management singers Mask In the city of Bandung.
This is a qualitative research approach with the method of dramaturgical studies, research subjects are dancer mask. Informants selected by purposive sampling techniques, to research informants amounted to 3 (three) mask singers, and to clarify and strengthen the data supporting the existence of informants and key informants. The research data obtained through in-depth interviews, observation, documentation, library research and online data retrieval. To test the validity of the data using the technique of data triangulation. The data analysis techniques to reduce data, collect data, present data, draw conclusions, and evaluation.
The results showed that the next stage (front stage) singers try to mask it all played a role well, the role of a form of imitation produced the individual against another individual activities are perceived as a figure entertainer. In the middle stage (middle stage) singers and also a mask worn area where singers perform mask brief strong mentally while in front of the stage. On the back of the stage (back stage), singers mask really play an integral role, they do not like being on stage at the front (front stage) that cover their situation.
Advice research: For the mask to give up singers performing art that is more acceptable to the community so that the work as busker this mask can have value as a form of entertainment. For people to not always looked at the eyes on the mask, because it has the singer hopes that anyone could give more attention to them.
vi Assalamu’alaikum. Wr. Wb
Alhamdulillahirabbil, alamin, Segala puji dan syukur seraya peneliti
panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia – Nya yang telah
meridhoi segala jalan dan upaya peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi
ini tepat pada waktu yang telah ditentukan pada akhirnya Penulis dapat membuat
dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan lancar, serta dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.
Dalam melakukan penelitian skripsi ini tidak sedikit peneliti menghadapi
kesulitan serta hambatan baik tekhnis maupun non tekhnis. Namun atas izin Allah
SWT, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang
peneliti terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak,
akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih
kepada keluarga tercinta di Lampung yang sudah memberikan doa dan dukungan
baik Materil ataupun Inmateril. Terimakasih untuk ayah tercinta Fhadiel dan Ibunda tercinta Siti Aminah , selaku orang tua penulis yang sudah banyak memberikan supportnya, doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan
vii
Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin
menyampaikan rasa hormat, terimakasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya
kepada Yang Terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia,
yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi.
2. Bapak Drs. Manap Solihat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer
Indonesia.
3. Ibu Desayu Eka Surya, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Kemahasiswaan
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia, serta sebagai Wali dosen Peneliti dari
awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini.
4. Bapak Yadi Supriadi, S.Sos, M.Phil, selaku Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer
Indonesia. Sekaligus dosen pembimbing yang telah sabar dalam
memberikan bimbingan, nasehat, semangat dalam penyusunan penelitian
skripsi ini.
5. Yth. Ibu dan Bapak Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi & Public Relations, serta seluruh dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya
selama ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih
yang tiada tara untuk segala jasanya serta dukungan yang telah diberikan
vii
6. Ibu Ratna W., A.Md., selaku sekretariat Dekan FISIP, Ibu Astri Ikawati., A.Md,.Kom., dan Ibu Rr. Sri Intan Fajarini, S.I.Kom Selaku Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNIKOM, yang telah
membantu kelancaran proses administrasi skripsi penulis dari pra hingga
pasca skripsi.
7. Buat Kakak-kakak serta adik tercinta, Terimakasih atas doa dan segala dukungannya.
8. Keluarga Bapak Karsum (Pengamen topeng) yang sudah mengajarkan
peneliti tentang arti kehidupan, Terimakasih yang sebesar-besarnya.
9. Rekan-rekan Ilmu Komunikasi Angkatan 2008 tanpa terkecuali. Sukses
selalu untuk kita semua.
10.Para sahabat, teman dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya, Terimakasih yang sebesar-besarnya.
Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah
membantu Penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Akhir kata Peneliti
berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Peneliti khususnya
dan pembaca sekalian umumnya.
Bandung, 2012
Peneliti
ix
LEMBAR PENGESAHAN………...…….i
LEMBAR PERNYATAAN………...……ii
LEMBAR PERSEMBAHAN………...…..iii
ABSTRAK………...……….iv
ABSTRACT………....……...v
KATA PENGANTAR………...vi
DAFTAR ISI………...ix
DAFTAR TABEL……….….….xii
DAFTAR GAMBAR………..…...viii
DAFTAR LAMPIRAN………..….….ix
BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Masalah……….………..1
1.2Rumusan Masalah……….………8
1.2.1Pertanyaan Macro………8
1.2.2 Pertanyaan Micro……….…..……..9
1.3Maksud dan Tujuan Penelitian……….…………9
1.3.1Maksud Penenlitian………...9
1.3.2 Tujuan Penelitian………...…..9
1.4Kegunaan Penelitian………….………..10
1.4.1Kegunaan Teoritis………..10
x
2.1.2 Tinjauan Tentang Dramaturgi………...18
2.1.2.1 Interaksi Simbolik Sebagai Induk dari Teori Dramaturgis..18
2.1.2.2 Kajian Dramaturgis………...24
2.1.2.3 Panggung Pertunjukan………...27
2.1.3 Presentasi Diri dan pengelolaan Kesan (impression management)..30
2.1.4 Tinjauan Tentang Pengamen………...33
2.1.4.1 Pengertian Pengamen………....33
2.1.4.2 Faktor- Faktor Penyebab Munculnya Pengamen…………..34
2.1.5 Tinjauan Tentang Tari Topeng………..35
2.2 Kerangka Pemikiran………...40
2.2.1 Kerangka Teoritis………..40
2.2.2 Kerangka Konseptual………42
BAB III SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Subjek Penelitian………..…..45
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian……….62 3.3.1 Lokasi Penelitian………62
xi
4.1.2 Identitas Informan Kunci / Pendukung…..………..74
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian………..76
4.2.1 Panggung Depan Pengamen Topeng………… ………...76
4.2.2 Panggung Tengah Pengamen Topeng………..………….92
4.2.3 Panggung Belakang Pengamen Topeng………..100
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian………105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan……….…………..110
5.2 Saran……….111
DAFTAR PUSTAKA………....113
x
Tabel 3.1 Tempat pengamen di Kota Bandung………..47
Tabel 3.2 Jumlah pengamen………..………..48
Tabel 3.3 Daftar informan penelitian………...…..….58
Tabel 3.4 Daftar informan kunci…….………....59
Tabel 3.5 Waktu penelitian………...………...…63
Tabel 4.1 Jadwal Wawancara Informan………..65
xi
Gambar 2.1 Konseptual panggung pengamen topeng………...…...43
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisa Data Model Kualitatif ……….60
Gambar 4.1 Informan Penelitian...68
Gambar 4.2 Informan Penelitian...70
Gambar 4.3 Informan Penelitian...72
Gambar 4.4 Informan Kunci...74
x
Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian...………...116
Lampiran 2 : Surat Pemeberitahuan Survey/Penelitian/Praktek Kerja.………….117
Lampiran 3 : Surat Research………..………...118
Lampiran 4 : Lembar Revisi Usulan Penelitian…………...119
Lampiran 5 : Berita Acara Bimbingan………...120
Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Pembimbing………..121
Lampiran 7 : Lembar Pengajuan Pendaftaran Ujian Sidang Sarjana……….122
Lampiran 8 : Lembar Identitas Informan Dan Key Informan………123
Lampiran 9 : Transkrip Pedoman Wawancara………...128
Lampiran 10 : Dokumentasi……….179
1 1.1Latar Belakang Masalah
Pengamen sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi ketika
berada di kota-kota besar. Keberadaan pengamen adalah bukti nyata akan
dampak yang ditimbulkan dari akibat kondisi ekonomi dan menjadi
permasalahan sosial yang menggejala secara simultan di kota-kota besar di
Indonesia. Begitu juga di Kota Bandung.
Pengamen kerap kali dianggap pekerjaan yang tak ubahnya
pengemis oleh sebagian besar orang. Pekerjaan ini dipandang sebagai
aktifitas meminta-minta dengan cara memaksa meski mengandalkan
sebuah keiklasan dari masyarakat, karena pengamen ini merupakan hal
yang tidak diharapkan kehadirannya. Selain itu berbagai opini juga sudah
santer terdengar dari investigasi yang dilakukan dari berbagai media bahwa
pengemis adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan karena
pendapatannya yang ternilai sangat besar. Seperti kehidupan seorang
pengemis yang dikenal sukses di kampung halamannya dengan memiliki
harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pendapatan mengemis yang ia
lakukan ketika berada di kota.1 Hal ini sudah menjadi penyebab timbulnya
1
keraguan dari banyak orang untuk memberikan respon terhadap
keberadaan pengemis.
Melihat kehidupan sosial masyarakat yang ada dikalangan
menengah kebawah di Kota Bandung yang majemuk, terdapat suatu
fenomena tentang perilaku manusia yang dalam kehidupannya bekerja
dengan cara melakukan perubahan peran secara sengaja, dan dari
perubahan tersebut tampak jelas berbeda dengan pribadi yang dimilikinya.
Peran yang bersifat dramatic karena berdasar pada ide khayali. Cara demikian sudah dianggap lazim karena mengingat segala keterbatasan serta
kebutuhan yang bersifat fundamental yang dimiliki, sehingga menuntut
mereka untuk dapat mempertahankan hidup.
Pengamen Topeng merupakan pekerjaan yang dijalani oleh
seseorang dengan mencoba menampilkan diri nya pada sebuah pertunjukan
dua unsur seni, yakni seni Tari dan Musik. Dalam aktivitas ini terdapat
atribut-atribut yang digunakan seperti pakaian khusus, topeng serta kotak
musik (music box) yang merupakan pelengkap dalam pertunjukan
pengamen topeng ini.
Unsur seni yang terdapat pada pertunjukan Pengamen Topeng ini
merupakan konsep yang membantu berjalannya suatu interaksi dengan
masyarakat, dan melalui interaksi tersebut seorang individu mencoba
menampilkan diri-nya yang melalui peran yang dramatik. Dalam situasi
yang bersifat Teatrikal. Aktivitas ini dilakukan atas dasar harapan akan
terpenuhinya suatu kebutuhan dari individu, dan merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam aktivitas ini pula seorang individu
mencoba memberikan isyarat melalui komunikasi non verbal yang
dilakukan untuk membangun sebuah persepsi dari individu lain, dan hal ini
sangat bersinggungan dengan sebuah Interaksi Sosial.
‘Nopeng’ istilah yang biasa dipakai untuk menyebutkan pekerjaan
ini, merupakan jenis pekerjaan yang tidak umum karena hanya sedikit
orang yang tahu tentang pekerjaan ini. Dalam pertunjukan pengamen
topeng ini, kita dapat melihat perilaku dari seseorang yang menampilkan
sifat monodualismenya sebagai manusia. Dengan kata lain manusia akan
menampilkan sosok lain pada dirinya atau bahkan sosok yang sering ia
tampilkan dihadapan orang lain.
Gambar 1.1 Pengamen Topeng
Pada situasi dan untuk maksud tertentu manusia akan bertindak
sesesuai dengan apa yang diinginkannya, termasuk menunjukan suatu aksi
yang merupakan hasil dari daya khayal-nya. Begitupun dengan seorang
pengamen topeng, seseorang yang mempertontonkan diri nya dihadapan
orang lain dengan peran yang didasari daya khayal dan yang menjadi
tujuan utamanya adalah ekspektasi dari orang lain yang menjadi mitra pada
interaksi yang terjadi pada situasi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh
seorang pengamen topeng merupakan sebuah perwujudan penyajian diri
dan dalam interaksinya tersebut seseorang akan melakukan suatu
pengelolan kesan.
Pengelolaan kesan (Impression Management) di temukan dan
dikembangkan oleh Erving Goffman pada tahun 1959, dan telah
dipaparkan dalam bukunya yang berjudul “The Presentation of Self in
Everyday Life”. Pengelolaan kesan juga secara umum dapat didefinisikan
sebagai sebuah teknik presentasi diri yang didasarkan pada tindakan
mengontrol persepsi orang lain dengan cepat dengan mengungkapkan
aspek yang dapat menguntungkan diri sendiri atau tim.
Presentasi Diri ini dilakukan ketika seseorang berinteraksi dengan
orang lain dan mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain
terhadapnya, melalui sebuah pertunjukan diri yang mengalami setting di
hadapan khalayak. Dalam sebuah pertunjukan ini kebanyakan menggunakan
menyebut pertunjukan (performance) merupkan aktivitas untuk
mempengaruhi orang lain. Sebuah pertunjukan yang ditampilkan seseorang
berdasarkan atas perhitungan untuk memperoleh respon dari orang lain.
Penampilan serta perilaku seseorang dalam sebuah interaksi merupakan suatu
proses interpretif, yang dimana tujuannya agar terbentuknya sebuah persepsi
yang merupakan hasil dari suatu interpretasi yang dilakukan orang lain
(Mulyana, 2008: 113).Goffman memandang ini dengan perspektif Dramaturgi.
Berdasarkan hasrat dasar manusia, secara ilmiah manusia memiliki
kekuatan yang dapat menguasai sikap dan tindakannya. Manusia mempunyai
kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya. Untuk itu dia menempuh
jalan bertemu dengan orang lain yang melakukan pertunjukan dan
memproyeksikan diri dengan peranan-peranan yang melakonkan hidup dan
kehidupan di atas pentas secara khayali (Harymawan, 1986: 194).
Menurut Moulton (dalam Harymawan, 1986: 1) menyebutkan
bahwa presentasi (presented) diartikan sebagai sebuah drama, yaitu “hidup
yang dilukiskan dengan gerak”. Maksud dari presented disini adalah suatu
kehidupan yang bukan hanya bersifat fantasi manusia, namun kehidupan
yang bersifat fantasi tersebut diekspresikan secara langsung (live) atau
nyata.
Bertolak pada pengertian dramaturgi menurut RMA. Harymawan
yang mempelajari tentang hukum dan konvensi drama. Hukum-hukum drama
tersebut mencakup tema, alur (plot), karakter (penokohan), dan latar (setting).
Dramaturgi yang diperkenalkan oleh Goffman adalah perspektif yang
didalami berdasar dari segi sosiologi, dan menyatakan :
“Perspektif yang digunakan dalam laporan ini adalah
perspektif pertunjukan teater; prinsip-prinsipnya bersifat dramaturgis. Saya akan membahas cara individu menampilkan dirinya sendiri dan aktivitasnya kepada orang lain, cara ia memandu dan mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadapnya, dan segala hal yang mungkin atau tidak mungkin ia
lakukan untuk menopang pertunjukan di hadapan orang lain.”
(Mulyana,2008: 107)
Pada pernyataan Goffman tersebut mengartikan bahwa kehidupan
manusia diibaratkan seperti teater, interaksi sosial yang mirip dengan
pertunjukan di atas panggung yang dimana seseorang akan seperti seorang
aktor yang memainkan peran-peran tertentu saat berhadapan dengan orang
lain. Dalam perspektif dramaturgi, Goffman membagi kehidupan sosial
menjadi dua bagian yaitu “wilayah depan” (front region) dan “wilarah belakang” (back region). Saat individu menampilkan diri-nya dengan peran
tertentu di hadapan penonton atau khalayak, maka individu tersebut
dianggap seperti sedang berada di depan panggung (front stage), dan saat
individu sedang tidak bermain peran atau sedang mempersiapkan diri-nya
untuk menjalani peran, maka di wilayah ini adalah panggung belakang
(back stage), serta panggung tengah (middle stage) yang dimana daerah ini
merupakan wilayah seorang individu melakukan persiapan untuk ke
Pelaku dramaturgi disini adalah sekelompok kecil orang yang telah
lama menjalani pekerjaan sebagai pengamen topeng dan merupakan
individu-individu yang secara subyektif diamati oleh peneliti. Kelompok
ini merupakan warga pendatang yang berasal dari luar daerah, yang secara
kesehariannya bertumpu pada penghasilan dari pekejaannya dijalanan atau
disejumlah tempat keramaian di Kota Bandung. Para pengamen topeng
yang menjadi subyek penelitian ini juga adalah seorang kepala keluarga
yang bertempat tinggal disalah satu kawasan padat penduduk di Kota
Bandung.
Aspek fundamental yang dimiliki oleh sekelompok pengamen
topeng ini menjadi faktor timbulnya perilaku aktif namun bersifat
sementara dari sekelompok pengamen topeng. Dan disini peneliti mencoba
memahami proses dari perilaku tersebut. Dengan dilatar belakangi oleh
kebutuhan ekonomi, sekelompok pengamen topeng ini sudah
mempersepsikan pekerjaannya sebagai bagian dari diri mereka.
Pekerjaan ini sudah dianggap sebagai suatu aktifitas yang rutin
dilakukan, menurut penuturan dari salah satu pengamen topeng yaitu
Bapak Karsum atau biasa disapa “abah” mengungkapkan :
anggap bukan apa-apa, karena pekerjaan ini bukan tindakan mencuri. Dan saya bisa mecari makan dengan cara yang halal.”
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
keberadaan pengamen topeng adalah fenomena yang terjadi dalam
kehidupan sosial, yaitu suatu gambaran tentang tindakan yang dilakukan
individu yang terdorong oleh kondisi hidup yang menuntut dirinya untuk
dapat berpikir kreatif. Dengan kata lain fenomena pengamen topeng ini
adalah aktifitas dari kelompok kecil masyarakat dalam menjalani
kehidupan sosialnya. Hal ini juga merupakan suatu gejala sosial yang layak
untuk dipahami. Untuk itu disini peneltiti mencoba untuk mendeskripsikan
tentang bagai mana proses yang terjadi dari tindakan yang ada pada gejala
sosial tersebut.
1.2Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti
mengidentifikasi yang akan menjadi pokok masalah yang akan di teliti
yaitu sebagai berikut:
1.2.1Pertanyaan Macro
“Bagaimanakah Pengelolaan Kesan Pengamen Topeng Di Kota
1.2.2 Pertanyaan Micro
1. Bagaimana front stage(panggung depan) Pengamen Topeng Di
Kota Bandung ?
2. Bagaimana middle stage (panggung tengah) Pengamen Topeng Di
Kota Bandung ?
3. Bagaimana back stage (panggung belakang) Pengamen Topeng Di Kota Bandung ?
1.3Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1Maksud Penenlitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk analisis, mendeskripsikan,
menjelaskan tentang bagaimana Presentasi Diri Pengamen Topeng Dalam
Menjalani kehidupannya di Kota Bandung
1.3.2 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana front stage (panggung depan)
Pengamen Topeng Di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana middle stage (panggung tengah)
Pengamen Topeng Di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaiman backt stage (panggung belakang)
1.4Kegunaan Penelitian
Secara teoritis Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil
yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.
1.4.1 Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu
Komunikasi secara umum, khusunya kajian mengenai Presentasi diri yang
dilakukan seseorang dalam menjalani kehidupan sosialnya, terlebih lagi
mengenai peran yang di mainkan oleh seseorang sebagai perilaku dalam
sebuah interaksi sosial.
1.4.2 Kegunaan praktis a. Kegunaan Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan
mengenai Presentasi-diri, hal ini adalah salah satu macam perilaku
sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini juga memberikan
kesempatan yang baik bagi peneliti untuk mempraktekan berbagai teori
komunikasi dalam bentuk nyata terhadap fenomena yang ada di
masyarakat.
b. Kegunaan Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Program Studi Ilmu
satu sumber pengetahuan baru mengenai masalah yang diteliti. Terutama
bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan
tema yang sama.
c. Kegunaan Bagi Masyarakat
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
yang ingin mendapatkan informasi mengenai pengamen topeng di kota
Bandung, sehingga diharapkan pula dapat memberikan pengaruh terhadap
12
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Tinjauan Tentang Komunikasi
Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan menjadi
kebutuhan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan. Sebagai makhluk sosial,
manusia tidak mampu untuk hidup sendiri, untuk itu manusia membutuhkan
interaksi dengan individu lainnya. Dalam interaksi itulah terjadi sebuah
komunikasi yang disadari ataupun tidak bahkan terjadi dihampir setiap waktu
ketika kita bersinggungan dengan lingkungan sekitar. Komunikasi tersebut
dapat berupa komunikasi verbal maupun non verbal. Sebagaimana dikatakan,
manusia tidak dapat bertahan hidup jika tidak menjalin komunikasi dengan
individu lainnya.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang Ilmu Komunikasi, berikut ini
adalah pengertian dan asal kata dari para ahli.
1. Pengertian Komunikasi
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal
dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti
sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang
komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna
mengenai apa yang dipercakapan.
Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mendevinisikan komunikasi
sebagai: “transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya,
dengan menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, gambar, figure, grafik,
penampilan dan sebagainya”. Definisi yang mensyaratkan kesengajaan dari
komunikasi dikemukakan oleh Gerald R Miller, yang menyatakan bahwa
komunikasi sebagai “situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber
mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari
untuk mempengaruhi perilaku penerima” (Mulyana, 2008: 68).
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Shanon dan Weaver yang
menyatakan bahwa komunikasi adalah : “Bentuk interaksi manusia yang
saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak
terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka,
lukisan, seni dan teknologi” (Wiryanto, 2004 :7).
Dari beberapa definisi yang disampaikan para ahli dapat
disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang
(komunikator) menyatakan pesan yang dapat berupa gagasan untuk
memperoleh “commones” dengan orang lain (komunikate) mengenai objek
tertentu di mana komunikate merubah tingkah lakunya sesuai dengan yang
terdapat persamaan pengertian, artinya tidak ada perbedaan terhadap
pengertian tentang sesuatu, maka terjadilah situasi yang disebut
kesepemahaman.
2. Sifat Komunikasi
Sifat komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy ( dalam Dicky,
2010) ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
1. Tatap muka (face-to-face)
2. Bermedia (mediated)
3. Verbal (verbal)
Lisan (oral)
Tulisan (written/priated)
4. Nonverbal
Gerakan /isyarat badaniah (gestural)
Bergambar (pictorial).
Komunikator dituntut untuk memiliki kemampuan dan sarana agar
mendapatkan umpan balik (feedback) dari komunikan, sehingga maksud dari
pesan yang tersampaikan dapat berjalan dengan efektif. Komunikasi dengan
tatap muka (face-to-face) dilakukan antara komunikator dengan komunikan
secara langsung, tanpa menggunakan media apapun kecuali bahasa sebagai
lambang atau simbol komunikasi bermedia dilakukan oleh komunikator
kepada komunikan dengan menggunakan media sebagai alat bantu dalam
Komunikator dapat menyampaikan pesannya secara verbal dan
nonverbal. Verbal dibagi kedalam dua macam yaitu lisan (oral) dan tulisan
(written/printed). Sementara nonverbal dapat menggunakan gerakan atau
isyarat badaniah (gestural) seperti melambaikan tangan, mengedipkan mata
dan sebagainya, serta menggunakan gambar untuk mengemukakan idea tau
gagasannya.
3. Tujuan Komunikasi
Kegiatan atau upaya komunikasi yang dilakukan tentunya mempunyai
tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud disini menunjuk pada suatu hasil atau
akibat yang diinginkan oleh pelaku komunikasi.
Secara umum, Wilbur Schramm menyatakan bahwa tujuan
komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif kepentingan yakni: kepentingan
sumber atau pengirim atau komunikator dan kepentingan penerima atau
komunikan. Dengan demikian maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai
dapat digambarkan sebagai berikut:
1 Tujuan Komunikasi dari sudut kepentingan sumber
Memberikan Informasi
Mendidik
Menyenangkan atau menghibur
2 Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima
Memahami Informasi
Mempelajari
Menikmati
Menerima atau menolak anjuran (Sendjaja, 2004:2)
Menurut Onong Uchjana Effendy, tujuan dari komunikasi adalah:
1. Perubahan sikap (attitude change)
2. Perubahan pendapat (opinion change)
3. Perubahan perilaku (behavior change)
4. Perubahan sosial (social change). (Effendy, 2003: 8)
Sedangkan tujuan komunikasi pada umumnya menurut H. A. W.
Widjaja adalah sebagai berikut:
a. Supaya yang disampaikan dapat dimengerti. Sebagai komunikator
harus dapat menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan
sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang
dimaksud oleh pembicara atau penyampai pesan (komunikator).
b. Memahami orang Sebagai komunikator harus mengetahui benar
aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya. Jangan hanya
berkomunikasi dengan kemauan sendiri.
c. Supaya gagasan dapat diterima oleh orang lain Komunikator harus
menggunakan pendekatan yang persuasif bukan dengan memaksakan
kehendak.
d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu Menggerakkan
sesuatu itu dapat berupa kegiatan yang lebih banyak mendorong
seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki (Widjaja,
2000: 66).
Jadi, secara keseluruhan dapat dipahamai bahwa tujuan dari komunikasi
tidak terlepas dari bagaimana manusia mengisi hidupnya dalam pola
interaksi sosial yang tercipta antara satu dengan lainnya. Baik untuk
aktualisasi diri, interaksi, eksistensi, ekspresi, apresiasi maupun menciptakan
esensi dalam hidupnya.
4. Fungsi Komunikasi
Fungsi komunikasi Menurut Widjaja dalam karyanya “Ilmu Komunikasi
: pengantar studi” apabila dipandang dari arti yang lebih luas adalah sebagai
berikut :
1. Informasi.
2. Sosialisasi.
3. Motivasi.
4. Perdebatan dan diskusi.
5. Pendidikan.
6. Memajukan kehidupan.
7. Hiburan.
Komunikasi merupakan ajang pertukaran informasi bagi masyarakat
dimana masyarakat merupakan manusia yang memerlukan sosialisasi
didalam kehidupannya. Dengan komunikasi juga dapat mendorong kegiatan
individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
2.1.2 Tinjauan Tentang Dramaturgi
2.1.2.1 Interaksi Simbolik Sebagai Induk dari Teori Dramaturgis “An actor performs on a setting which is constructed of a stage and a backstage; the props at either setting direct his action; he is being watched by an audience, but at the same time he is an audience for his viewers' play”. (The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman, 1959)
Interaksi simbolik merupakan pembahasan penting karena tidak bisa
dilepaskan dari dramaturgi. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas
yang merupakan ciri khas manusia. Maka, jika menyinggung mengenai
masalah dramaturgi tidak lepas dari konteks interaksi simbolik. Interaksi
simbolik dapat dikatakan berupa pertukaran simbol yang diberi makna
(Mulyana, 2008: 68). Hal ini berhubungan dengan permainan peran oleh
individu tertentu.
Munculnya suatu studi tentang interaksi simbolik dipengaruhi oleh
teori evolusi milik Charles Darwin. Darwin menekankan pandangan bahwa
semua perilaku organisme, termasuk perilaku manusia, bukanlah perilaku
yang acak, melainkan dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan
organisme dan lingkungannya serasi dalam suatu hubungan dialektik.
Artinya, cara lingkungan berpengaruh terhadap organisme antara lain
dibentuk oleh alam, pengalaman lalu, dan aktifitas yang dilakukan organisme
saat itu.
Beberapa ilmuwan mempunyai andil sebagai perintis dari
interaksionisme simbolik, yaitu James Mark Baldwin, William James,
Charles Horton Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George
Herbert Mead. Mead adalah sebagai peletak dasar teori tersebut. Pada masa
Herbert Blumer, istilah interaksi simbolik dipopulerkan pada tahun 1937.
Dalam interaksi simbolik, Blumer melihat individu sebagai agen yang aktif,
reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit serta
sulit diramalkan dan memberi tekanan pada sebuah mekanisme yang disebut
interaksi diri yang dianggap membentuk dan mengarahkan tindakan individu.
Interaksi diri memberikan pemahaman bahwa pemberian makna merupakan
hasil pengelolaan dan perencanaan dari aspek kognitif dalam diri individu.
Ketika individu itu melakukan suatu proses olah pikir sebelum makna itu
disampaikan melalui simbol-simbol tertentu, interpretasi makna bisa
dipastikan akan berjalan dengan yang diharapkannya.
Interaksi simbolik menurut Blumer, merujuk pada karakter interaksi
khusus yang berlangsung antarmanusia. Aktor tidak semata-mata beraksi
terhadap tindakan yang lain, tetapi juga menafsirkan dan mendefenisikan
langsung, selalu didasarkan atas makna penilaian tersebut. Maka dari itu,
interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran
atau dengan menemukan makna tindakan oran lain. Dalam konteks itu,
menurut Blumer, aktor akan memilih, memeriksa, berpikir,
mengelompokkan, dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan
situasi di mana dan ke arah mana tindakannya.
Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri
khas, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana,
2008: 68). Perspektif ini berusaha memahami perilaku manusia dari sudut
pandang subjek. Perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang
memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan
mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi
mereka
Dalam bukunya yang berjudul “Symbolic Interactionism; Perspective
and Method”, Blumer (dalam Puspa, 2011) menekankan tiga asumsi yang mendasari tindakan manusia, yaitu:
1. Human being act toward things on the basic of the meaning that the things have for them (manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimilikinya).
2. The meaning of the things arises out of the social interactions one with one’s fellow (makna tersebut muncul atau berasal dari interaksi individu
3. The meaning of things are handled in and modified through an interpretative process used by the person in dealing with the thing he encounters (makna diberlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang
dijumpainya).
Dari pendapat Blumer di atas maka dapat disimpulkan bahwa makna
tidak melekat pada benda, melainkan terletak pada persepsi masing-masing
terhadap benda tersebut.
Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya
adalah “interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol”. Mereka
tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang
merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi
dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas
simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi
sosial. Penganut interaksionisme simbolik berpandangan, perilaku manusia
pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling
mereka, jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan
(Mulyana, 2008).
Tindakan individu mengenai bagaimana tampilan dirinya yang ingin
orang lain ketahui memang akan ditampilkan se-ideal mungkin. Perilakunya
dalam interaksi sosial akan selalu melakukan permainan informasi agar
menginginkan identitas lain yang ingin ditonjolkan dari identitas yang
sebenarnya, di sinilah terdapat pemeranan karakter seorang individu dalam
memunculkan simbol-simbol relevan yang diyakini dapat memperkuat
identitas pantulan yang ingin ia ciptakan dari identitas yang sesungguhnya
(lebih jauh perkembangan ini melahirkan studi dramaturgi).
Pada perkembangannya, selain dari aspek kognitif, interaksi simbolik
juga mendapatkan kritik berkaitan dengan pengklarifikasian dari konteks di
mana proses komunikasi itu berlangsung. Penggunaan interaksi simbolik yang
hanya dalam suatu presentasi diri dan dalam konteks tatap muka, seolah-olah
menganggap keberhasilan suatu makna ditentukan oleh pengelolaan simbol yang
sudah terencana. Jadi makna tersebut dapat diciptakan dan disampaikan oleh
individu pengirim pesan saat proses interaksi berlangsung.
Erving Goffman, salah seorang yang mencoba memperjelas dari
pengklarifikasian dari proses interaksi simbolik. Pandangan Blumer bahwa
individu-lah yang secara aktif mengontrol tindakan dan perilakunya, bukan
lingkungan, dirasa kurang tajam pada masanya. Interaksi simbolik hanya
sebatas pada “individu memberi makna”, Goffman memperluas
pemahamannya bahwa ketika individu menciptakan simbol, disadari atau
tidak, individu tersebut bukan lagi dirinya.
Menurut Goffman, ketika simbol-simbol tertentu sebelum
dipergunakan oleh individu sebagai sebuah tindakan yang disadari (dalam
karena ketika individu tersebut mencoba symbol-simbol yang tepat untuk
mendukung identitas yang akan ditonjolkannya, ada simbol-simbol lain yang
disembunyikan atau “dibuang”. Ketika individu tersebut telah memanipulasi
cerminan dirinya menjadi orang lain, berarti ia telah memainkan suatu pola
teateris, peng-aktor-an yang berarti dia merasa bahwa ada suatu panggung
dimana ia harus mementaskan suatu tuntutan peran yang sebagaimana
mestinya telah ditentukan dalam skenario, bukan lagi pada tuntutan interaksi
dirinya, simbol-simbol yang diyakini dirinya mampu memberikan makna,
akan terbentur pada makna audiens. Artinya bukan dirinya lagi yang
memaknai identitasnya, tetapi bergantung pada orang lain. Pengelolaan
simbol-simbol pada bagian dari tuntutan lingkungan (skenario).dirinya
sebagai
Maka berangkat dari sinilah yang memicu Erving Goffman untuk
mengoreksi dan mengembangkan Teori Interaksionisme Simbolik secara
lebih jauh dengan mengklarifikasikan konteks dari berlangsungnya interaksi
tersebut. Bertindak dalam cara yang berbeda dan dalam pengaturan yang
berbeda, yaitu secara teateris.
Melalui pandangannya terhadap interaksi sosial, dijelaskan bahwa
pertukaran makna di antara individu-individu tersebut disebabkan pada
tuntutan pada apa yang orang harapkan dari kita untuk kita lakukan. Lalu,
(performance) di hadapan khalayak, bukan lagi individu lain. Memainkan
simbol dari peran tertentu di suatu panggung pementasan.
2.1.2.2 Kajian Dramaturgis
Kenneth Duva Burke (1945) seorang teoritis literatur Amerika dan
filosof memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode yang bersifat
analogis dan teoretis untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama
sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan sosial. Dengan kata lain model
dramatis menempatkan individu dan perilaku sosial dalam analogi dramatis
yang menandai aktor sosial pada “panggung” kehidupan yang sebenarnya.
Burke memandang perilaku sosial sebagai interaksi atau rasio antara lima
unsur daramatis (yakni, lakon, adegan, agent, agency, tujuan) atau penggunaan strategi simbolis dalam memanipulasikan bahasa (Rahmat, 1986
: 327-328).
Menurut pandangan Burke, cara yang paling baik untuk meneropong
kehidupan sosial manusia adalah melalui pendekatan drama (Mulyana, 2008:
158). Tujuan Dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk
memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa
yang mereka lakukan. Dramatisme memperlihatkan bahasa sebagai model
tindakan simbolik ketimbang model pengetahuan. Pandangan Burke adalah
Dramaturgi adalah suatu pendekatan yang lahir dari pengembangan
Teori Interaksionisme Simbolik. Dramaturgi diartikan sebagai suatu model
untuk mempelajari tingkah laku manusia. Teori dramaturgi menjelaskan
bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas
tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas
manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain.
Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut.
Dalam dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan
teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan
karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan
dramanya sendiri”. Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep
dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang
mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, seorang
aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan.
Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunakan
kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuan untuk
meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan
mencapai tujuan. Oleh Goffman, tindakan diatas disebut dalam istilah
“impression management”.
Erving Goffman (1959), salah seorang sosiolog yang paling
berpengaruh pada abad 20 telah memperkenalkan dramaturgi dalam bukunya
Goffman ini lebih bersifat penampilan teateris. Yakni memusatkan perhatian
atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip
dengan pertunjukan drama di panggung. Ada aktor dan penonton. Tugas
aktor hanya mempersiapkan dirinya dengan berbagai atribut pendukung dari
peran yang ia mainkan, sedangkan bagaimana makna itu tercipta,
masyarakatlah (penonton) yang memberi interpretasi. Individu tidak lagi
bebas dalam menentukan makna tetapi konteks yang lebih luas menentukan
makna (dalam hal ini adalah penonton dari sang aktor). Karyanya
melukiskan bahwa manusia sebagai manipulator simbol yang hidup di dunia
simbol.
Inti dari drmaturgi adalah menghubungkan tindakan dengan
maknanya, dan dalam pandangan dramaturgis tentang kehidupan sosial,
makna bukanlah warisan budaya, sosialisasi, atau tatanan kelembagaan, atau
perwujudan dari potensi psikologis dan biologis, melainkan pencapaian
problematik interaksi manusia dan penuh dengan perubahan, kebaruan, dan
kebingungan. Namun yang lebih penting lagi, makna bersifat behavioral,
secara sosial terus berubah, abitrer, dan merupakan ramuan interaksi
manusia. Maka atas suatu simbol penampilan atau perilaku sepenuhnya
bersifat serba mungkin, sementara atau situasional. Dapat dikatakan juga
pendekatan dramaturgi Goffman khususnya berintikan pandangan bahwa
ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan
pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang orang lakukan, apa yang
ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan
bagaimana mereka melakukannya (Mulyana, 2008: 107).
2.1.2.3 Panggung Pertunjukan
Melalui perspektif dramaturgis, kehidupan ini ibarat teater, perilaku
manusia dalam sebuah interaksi sosial mirip dengan sebuah pertunjukan di
atas panggung dengan menampilkan berbagai peran yang dimainkan oleh
sang aktor.
Menurut Goffman, kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi
“wilayah depan” (front region) dan “wilayah belakang” (back region).
Wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan (front stage) yang
ditonton khalayak penonton, sedangkan wilayah belakang ibarat panggung
sandiwara bagian belakang (back stage) ataw kamar rias tempat pemain
sandiwara bersantai, mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan
perannya di panggung depan (Mulyana, 2008: 114).
Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat
aktor berada di atas panggung (“front stage”) dan di belakang panggung (“back stage”) drama kehidupan. Kondisi akting di front stage adalah
adanya penonton (yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian
pertunjukan. Saat itu kita berusaha untuk memainkan peran kita
dibatasi oleh oleh konsep-konsep drama yang bertujuan untuk membuat
drama yang berhasil (lihat unsur-unsur tersebut pada impression management
diatas). Sedangkan back stage adalah keadaan dimana kita berada di belakang panggung, dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Sehingga
kita dapat berperilaku bebas tanpa mempedulikan plot perilaku bagaimana
yang harus kita bawakan.1
Lebih jelas akan dibahas tiga panggung pertunjukan dalam studi
dramaturgi:
1. Front Stage (Panggung Depan)
Merupakan suatu panggung yang terdiri dari bagian pertunjukkan
(appearance) atas penampilan dan gaya (manner). Di panggung inilah aktor
akan membangun dan menunjukkan sosok ideal dari identitas yang akan
ditonjolkan dalam interaksi sosialnya. Pengelolaan kesan yang ditampilkan
merupakan gambaran aktor mengenai konsep ideal dirinya yang sekiranya
bisa diterima penonton. Aktor akan menyembunyikanhal-hal tertentu dalam
pertunjukkan mereka.
Melalui aspek front stage, back stage, dan aspek middle stage yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian yang mengkaji tentang presentasi
diri yangdikemukakan oleh Goffman, peneliti dapat menganalisa presentasi
diri dari pengamen topeng dalamperspektif dramaturgi.
1
2. Middle Stage (Panggung Tengah)
Middle Stage merupakan sebuah panggung lain di luar panggung resmi saat sang aktor mengkomunikasikan pesan-pesannya, yaknipanggung depan
(front stage) saat mereka beraksi di depan khalayak tetapi juga di luar
panggung belakang (back stage) saat mereka mempersiapkan segala atribut
atau perlengkapan untuk ditampilkan di panggung depan (Mulyana, 2008:
58).
Di panggung inilah segala persiapan aktor disesuaikan dengan apa yang
akan dihadapi di atas panggung, untuk menutupiidentitas aslinya. panggung
ini disebut juga panggung pribadi, yang tidak boleh diketahui oleh orang
lain. panggung ini juga yang menjadi tempat bagi aktor untuk
mempersiapkan segala sesuatu atribut pendukung pertunjukannya. Baik itu
tata rias, peran, pakaian, sikap, perilaku, bahasa tubuh, mimik wajah, isi
pesan, cara bertutur dangaya bahasa.
3. Back Stage (Panggung Belakang)
Panggung belakang merupakan wilayah yang berbatasan dengan
panggung depan, tetapi tersembunyi dari pandangan khalayak. Ini
dimaksudkan untuk melindungi rahasia pertunjukan, dan oleh karena itu
khalayak biasanya tidak diizinkan memasuki panggung belakang, kecuali
dalam keaadaan darurat. Di panggung inilah individu akan tampil
2.1.3 Presentasi Diri dan pengelolaan Kesan (impressionmanagement) Presentasi diri dapat diartikan sebagai cara individu dalam
menampilkan dirinya sendiri dan aktifitasnya kepada orang lain, cara ia
memandu dan mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadapnya,
dan segala hal yang memungkinkan atau tidak mungkin ia lakukan untuk
menopang pertunjukannya di hadapan orang lain (Mulyana, 2008: 107).
Bertolak pada gagasan diri menurut Cooley yang menyatakan bahwa
diri terdiri dari tiga komponen yakni yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita tampil bagi orang lain. Kedua, kita membayangkan bagaimana penilaian mereka atas penampilan kita. Ketiga, kita mengembangkan sejenis perasaan diri, seperti kebanggaan atau malu, sebagai
akibat membayangkan penilaian orang lain tersebut. Berdasarkan gagasan
tersebut Goffman mencoba mengembangan dan mengartikan bahwa diri
adalah suatu hasil kerja sama (collaborative manufacture) yang harus
diproduksi baru dalam peristiwa interaksi sosial.
Menurut Goffman, presentasi diri merupakan suatu kegiatan yang
dilakukan oleh individu tertentu untuk memproduksi definisi situasi dan
identitas sosial bagi para aktor dan definisi situasi tersebut mempengaruhi
ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi
yang ada (Mulyana, 2008: 110).
Dalam presentasi diri ini Goffman mengasumsikan bahwa ketika
akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai “pengelolaan kesan”
(impression management), yaitu teknik-teknik yang digunakan aktor untuk
memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi-situasi tertentu untuk mencapai
tujuan tertentu (Mulyana, 2008: 112). Lebih jauh pengelolaan kesan ini
merupakan upaya individu untuk menumbuhkan kesan tertentu di depan
orang lain dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas
dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dalam proses produksi identitas
tersebut, ada suatu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan mengenai
atribut simbol yang hendak digunakan sesuai dan mampu mendukung
identitas yang ditampilkan secara menyeluruh.
Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam buku “Psikologi Komunikasi”
menyatakan bahwa impression management atau pengelolaan kesan
merupakan suatu usaha untuk menimbulkan kesan tertentu terhadap seorang
individu.
Menurut Goffman, kebanyakan atribut, milik atau aktivitas manusia
digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang kita kenakan, tempat
kita tinggal, rumah yang kita huni berikut cara kita melengkapinya (furnitur
dan perabotan rumah), cara kita berjalan dan berbicara, pekerjaaan yang kita
lakukan dan cara kita menghabiskan waktu luang kita. Lebih jauh lagi,
dengan mengelola informasi yang kita berikan kepada orang lain, maka kita
akan mengendalikan pemaknaan orang lain terhadap diri kita. Hal itu
itu, Goffman menyebut aktivitas untuk mempengaruhi orang lain itu sebagai
pertunjukkan (performance), yakni presentasi diri yang dilakukan individu
pada ungkapan-ungkapan yang tersirat, suatu ungkapan yang lebih bersifat
teateris, kontekstual, non-verbal dan tidak bersifat intensional (Mulyana,
2008: 112-113).
Seseorang akan berusaha memahami makna untuk mendapatkan
kesan dari berbagai tindakan orang lain, baik yang dipancarkan dari mimik
wajah, isyarat dan kualitas tindakan. Menurut Goffman, perilaku orang
dalam interaksi sosial selalu melakukan permainan informasi agar orang lain
mempunyai kesan yang lebih baik. Kesan non-verbal inilah yang menurut
Goffman harus dicek keasliannya (Puspa, 2011: 81).
Goffman menyatakan bahwa hidup adalah teater, individunya
sebagai aktor dan masyarakat adalah penontonnya. Dalam pelaksanaannya,
selain panggung di mana ia melakukan pementasan peran, ia juga
memerlukan ruang ganti yang berfungsi untuk mempersiapkan segala
sesuatunya. Ketika individu dihadapkan pada panggung, ia akan
menggunakan simbol-simbol yang relevan untuk memperkuat identitas
karakternya, namun ketika individu tersebut telah habis masa
pementasannya, maka di belakang panggung akan terlihat tampilan
2.1.4 Tinjauan Tentang Pengamen 2.1.4.1 Pengertian Pengamen
‘Ngamen’ sebenarnya dapat diartikan sebagai menjual ‘keahlian’,
khususnya dalam bidang musik yang berpindah-pindah tempat atau
berkeliling dari stau tempat ke tempat yang lain, sedangkan pengamen adalah
orang yang melakukan kegiatan ngamen tersebut.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia ngamen terdiri dari dua pengertian,
pertama sebagai kegiatan keliling bermain musik dengan mengharapkan
bayaran, kedua sebagai kegiatan pergi melaut mencari ikan. Demikian juga
pengertian yang sama dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Dalam
kamus online pengamen ditulis sebagai “beg while singing playing musical
instruments or reciting prayers, atau be persistent (memaksa).” Pengertian-pengertian yang diberikan dalam beberapa kamus Pengertian-pengertiannya hampir
sama. Kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain dengan
mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang mereka suguhkan.
Namun karya yang mereka suguhkan berbeda-beda, baik dari segi bentuk
dan kualitas maupun performanya.
Definisi Pengamen itu sendiri, awalnya berasal dari kata ’amen’ atau
’mengamen’ (menyanyi, main musik, dsb) untuk mencari uang.
Amen/pengamen (penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak bertempat
umum). Jadi pengamen itu mempetunjukkan keahliannya di bidang seni.
Seorang pengamen tidak bisa dibilang pengemis, karena perbedaannya cukup
mendasar.2
2.1.4.2 Faktor- Faktor Penyebab Munculnya Pengamen
Menurut hasil penelitian Artidjo Alkastar dalam (Kristiana, 2009)
tentang kehidupan seseorang yang bekerja sebagai pengamen menyatakan
bahwa yang menyebabkan menuju kearah kehidupan jalanan dipengaruhi
oleh faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :
a. Faktor Intern meliputi : kemalasan, tidak mau bekerja keras, tidak kuat
mental, cacat fisik dan psikis, adanya kemandirian hidup untuk tidak
bergantung kepada orang lain.
b. Faktor Ekstern meliputi :
1. Faktor ekonomi : pengamen dihadapkan kepada kemiskinan keluarga
dan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada.
2. Faktor geografis : kondisi tanah tandus dan bencana alam yang tak
terduga.
3. Faktor sosial : akibat arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota
tanpa disertai partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan
sosial.
2
4. Faktor pendidikan : rendahnya tingkat pendidikan dan tidak memiliki
keterampilan kerja.
5. Faktor psikologis : adanya keretakan keluarga yang menyebabakan
anak tidak terurus.
6. Faktor kultural : lebih bertendensi pasrah kepada nasib dan hukum
adat yang membelenggu.
7. Faktor lingkungan : anak dari keluarga pengamen telah mendidik
anak menjadi pengamen pula.
8. Faktor agama : kurangnya pemahaman agama, tipisnya iman dan
kurang tabah dalam menghadapi cobaan hidup.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang
menyebabkan munculnya pengamen adalah adanya dua faktor, yaitu intern
dan ekstern dimana faktor intern antara lain kemalasan,dan bahkan
kemandirian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung
dengan orang lain, dan faktor ekstern yaitu meliputi kondisi ekonomi.
2.1.5 Tinjauan Tentang Tari Topeng
Tari topeng adalah salah satu tarian tradisional yang ada di Cirebon.
Tari ini dinamakan tari topeng karena ketika beraksi sang penari memakai
topeng. Kesenian tari topeng Cirebon menjalankan sisi dakwah keagamaan
mempunyai empat tingkatan yang biasa disebut : Sareat, Tarekat, Hakekat
dan Ma’ripat.
Mengulas kesenian Tari Topeng Cirebon maka tidak bisa lepas dari
perjalanan sejarah berdirinya Penguasa Islam di daerah ini. Pada saat
berkuasanya Sunan Gunung Jati sebagai Pimpinan Islam di Cirebon, maka
datanglah percobaan untuk meruntuhkan kekuasaan Cirebon di Jawa Barat.
Tokoh pelakunya adalah Pangeran Welang dari daerah Karawang. Tokoh ini
ternyata sangat sakti dan memiliki pusaka sebuah pedang bernama Curug
Sewu. Penguasa Cirebon beserta para pendukungnya tidak ada yang bisa
menandingi kesaktian Pangeran Welang. dalam keadaan kritis maka
diputuskan bahwa utnuk menghadapi musuh yang demikian saktinya harus
dihadapi dengan diplomasi kesenian. Setelah disepakati bersama antara
Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Kalijaga maka
terbentuklah team kesenian dengan penari yang sangat cantik yaitu Nyi Mas
Gandasari dengan syarat penarinya memakai kedok/topeng.
Mulailah team kesenian ini mengadakan pertunjukan ke setiap tempat
seperti lazimnya sekarang disebut ngamen. dalam waktu singkat team
kesenian ini menjadi terkenal sehinga Pangeran Walang pun penasaran dan
tertarik untuk menontonnya. Setelah pangeran Walang menyaksikan sendiri
kebolehan sang penari, seketika itu pula dia jatuh cinta, Nyi Mas Gandasari
pun berpura – pura menyambut cintanya dan pada Saat Pangeran Walang
Sewu. Pangeran Walang tanpa pikir panjang menyerahkan pedang pusaka
tersebut bersamaan dengan itu maka hilang semua kesaktian Pangeran
Walang.
Dalam keadaan lemah lunglai tidak berdaya Pangeran Walang
menyerah total kepada sang penari Nyi Mas gandasari dan memohon ampun
kepada Sunan Gunung Jati agar tidak dibunuh. Sunan Gunung Jati memberi
ampun dengan syarat harus memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama
Islam Pangeran Walang dijadikan petugas pemungut cukai dan dia berganti
nama menjadi Pangeran Graksan. Sedangkan para pengikut Pangeran
Walang yang tidak mau memeluk agama Islam tetapi ingin tinggal di
Cirebon, oleh Sunan Gunung Jati diperintahkan untuk menjaga keraton –
keraton Cirebon dan sekitarnya.
Melihat keberhasilan misi kesenian topeng bisa dijadikan penangkal
serangan dari kekuatan – kekuatan jahat maka pihak penguasa Cirebon
menerapkan kesenian topeng ini untuk meruat suati daerah yang dianggap
angker. Dan kelanjutannya kesenian topeng ini masih digunakan di desa –
desa untuk upacara ngunjung, nadran, sedekah bumi dan lain – lainnya.
Setelah masyarakat menerima tradisi meruat itu, di samping harus ada
pagelaran wayang kulit juga harus menampilkan tari topeng, maka tumbuh
suburlah penari – penari topeng di Cirebon. Namun yang mula – mula
sebelum pentas wayang, pada siang hari sang dalang harus menari topeng
terlebih dahulu. Oleh karenanya para dalang wayang kulit yang lahir sebelum
tahun 1930 diwajubkan untuk mendalami tari topeng terlebih dahulu sebelum
menjadi dalang wayang kulit. Dalam hubungannya pihak keraton selalu
melibatkan kesenian untuk media dakwah dalam penyebaran agama Islam,
dan pihak keraton memberikan nama Ki Ngabei untuk seniman yang juga
berdakwah.3
Dalam tarian ini, terdapat beraneka macam warna topeng dan dari
masing-masing warna topeng yang dikenakan mewakili karakter tokoh yang
dimainkan, sebut saja misalnya warna putih. Warna ini melambangkan tokoh
yang punya karakter lembut dan alim. Sedangkan topeng warna biru, warna
itu menggambarkan karakter sang ratu yang lincah dan anggun. Kemudian
yang terakhir, warna merah menggambarkan karakter yang berangasan
(tempramental) dan tidak sabaran. Dan busana yang dikenakan penari sendiri
adalah biasanya selalu memiliki unsur warna kuning, hijau dan merah yang
terdiri dari toka-toka, apok, kebaya, sinjang, dan ampreng.4
Tari Topeng ini sesungguhnya secara filsafat menggambarkan
perwatakan kehidupan manusia.
3
http://blesak.wordpress.com/2009/01/27/sejarah-topeng-cirebon/ diakses pada 11/05/12 pukul 23:55WIB
4
1. Tari Panji : menggambarkan manusia yang suci layaknya seorang prabu, pemimpin yang arif, adil dan bijaksana dan selalu mengerjakan perbuatan
yang baik.
2. Tari Samba : menggambarkan gemerlapnya keduniawian, harta benda,
wanita, bermewah - mewah, glamour. Oleh karena itu tarian ini kelihatan
lincah dan kaya akan gerak dan irama.
3. Tari Tumenggung : adalah gambaran dari sikap kehidupan prajurit dan
kepahlawanan yang gagah berani. penuh dedikasi, loyalitas dan tanggung
jawab yang tinggi.
4. Tari Kelana / Rahwana : menggambarkan angkara murka, watak manusia yang serakah dan menghalalkan segala cara demi mewujudkan
ambisi pribadinya. Namun dia juga adalah pemimpin yang kaya raya,
memiliki keduniawian yang tangguh.
Melihat tradisi seni tari topeng, pengamatan kita tidak bisa lepas dengan
perlengkapan yang dipakai seperti tersebut di bawah ini :
1. Kedok / Topeng yang terbuat dari kayu dan cara memakainya dengan
menggigit bantalan karet pada bagian dalam nya.
2. Sobra sebagai penutup kepala yang dilengkapi dengan jamangan dan dua
buah sumping.
3. Baju yang berlengan.
4. Dasi yang di lengkapi dengan peniti ukon (mata uang jaman dulu )
6. Ikat pinggang stagen yang dilengkapi badong.
7. Celana sebatas bawah lutut.
8. Sampur / selendang
9. Gelang tangan
10.Keris
11.Kaos kaki putih sampai lutut
12.Kain batik
13.Kadang - kadang dilengkapi dengan boro (epek)5
2.2 Kerangka Pemikiran 2.2.1 Kerangka Teoritis
Menurut RMA. Harymawan mengenai dalam bukunya yang berjudul Dramaturgi:
”Dramaturgi adalah ajaran tentang masalah hukum, dan konvensi atau persetujuan drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu
dramoai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi dan
sebagainya: dan “drama” berarti : perbuatan, tindakan.” (RMA.
Harymawan, 1986 : 1).
Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris dramaturgy yang berarti seni atau
teknik penulisan drama dan penyajiannya dalam bentuk teater. Berdasar
pengertian ini, maka dramaturgi membahas proses penciptaan teater mulai dari
penulisan naskah hingga pementasannya.
5
Perspektif drmaturgi dari Goffman merupakan pendekatan yang lahir
dari pengembangan Teori Interaksi Simbolik. Dramaturgi sendiri diartikan
sebagai suatu model untuk mempelajari tingkah laku manusia, tentang
bagaimana manusia itu menetapkan arti kepada hidup mereka. Dan
pendekatan dramaturgis Goffman khususnya berintikan pandangan bahwa
ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan
yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya (Mulyana, 2008: 107).
Deddy Mulyana dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi
menjelaskan bahwa tidak hanya ada dua panggung saja tetapi ada panggung lain
di luar daripada back stage dan front stage yaitu middle stage (Mulyana, 2008:
58). Berikut gambaran tentang tiga panggung yang dilalui oleh seorang aktor
yaitu:
1. Panggung Belakang (Back Stage)
Panggung belakang adalah wilayah dimana seorang aktor dapat
menampilkan wajah aslinya. Di panggung ini juga seorang aktor menunjukan
kepribadian aslinya pada masyarakat sekitar (Mulyana, 2008: 58).
2. Panggung Tengah (Middle Stage)
Merupakan sebuah panggung lain di luar panggung resmi saat sang actor
mengkomunikasikan pesan-pesannya, yakni panggung depan (front stage) saat
mereka beraksi di depan khalayak tetapi juga di luar panggung belakang (back